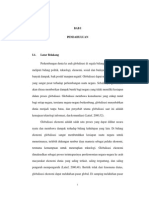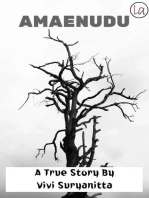Komunitas Petungkriyono - Potret Komunitas Desa Yang Rasional
Diunggah oleh
Ali Murtadha Alaydrus0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan5 halamanJudul Asli
Komunitas Petungkriyono_ Potret Komunitas Desa yang Rasional
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan5 halamanKomunitas Petungkriyono - Potret Komunitas Desa Yang Rasional
Diunggah oleh
Ali Murtadha AlaydrusHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Komunitas Petungkriyono: Potret Komunitas Desa yang Rasional
Petungkriyono merupakan bagian dari Kabupaten Pekalongan. Wilayah ini terbagi
menjadi sembilan desa. Sembilan desa tersebut adalah Tlagapakis, Kayupuring, Kasimpar,
Yosorejo, Songgodadi, Curugmuncar, Simego, Gumelem, dan Tlagahendro. Keseluruhan
kawasan ini merupakan hamparan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 500-1.634
m di atas permukaan laut. Seluruh kecamatan ini merupakan daerah dengan kelembaban
udara yang relatif tinggi. Sebuah laporan penelitian telah menuliskan bahwa suhu rata-rata di
Petungkriyono berkisar antara 12-18 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 5000-6000
mm/tahun. Dengan iklim yang relatif basah inilah tak heran jika hampir 70 % wilayah
Petungkriyono merupakan hutan yang terus dijaga hingga sekarang .
Dengan iklim basah ini sebagian besar masyarakat sekitar hutan di Petungkriyono
bekerja sebagai petani kecil. Populasi terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi lahan mereka
tidak bertambah menyebabkan akses petani Petungkriyono terhadap lahan semakin kecil. Di
Tlagapakis misalnya, pada tahun 1990 hanya terdapat 315 KK yang tinggal di kawasan ini.
Di tahun 1997 jumlah tersebut meningkat menjadi 346 KK, dan pada tahun 2007 ini 448 KK
telah tinggal di Tlagapakis. Dengan peningkatan populasi tersebut lahan pertanian tiap
keluarga di Petungkriyono pun tidaklah lebih dari 0,4 ha Dengan lahan yang sempit tersebut
selain menanam padi, ketela, ubi dan jagung sebagai sumber makanan sehari-hari, mereka
juga menanam bermacam tanaman komoditas seperti bawang daun, kopi, cabai, tomat,
ataupun wortel. Dari lahan tegalan, pohon aren yang sering tumbuh terutama di daerah yang
tak terlalu tinggi seperti
Kasimpar dan Kayupuring pun dimanfaatkan masyarakat dengan mengolahnya
menjadi gula aren. Sementara di daerah yang relatif tinggi seperti Gumelem dan Simego
tanaman teh dan tembakau banyak ditanam sebagai penyokong perekonomian masyarakat.
Pemeliharaan sapi turut berperan penting pula dalam perekonomian orang Petungkriyono1.
Selain memelihara sapi peranakan Ongole yang telah ada di Jawa dan Sumatra sejak awal
tahun 1900-an, kini orang Petung juga banyak memelihara sapi peranakan Kobis , Charolais,
Simmental, dan Brahman. Sapi-sapi ini dikandangkan di sekitaran rumah, sedang tidak semua
sapi yang dipelihara oleh sebuah keluarga di Petunkriyono merupakan milik keluarga yang
bersangkutan. Seringkali satu keluarga di Petung hanya memeliharakan sapi orang lain.
Dengan sistem ini baik pemilik ataupun pemelihara sapi akan memperoleh 50% dari laba
penjualan jika sapi tersebut dijual. Orang Petung biasa menyebutnya dengan maro bathi.
pakannya diperoleh dari merumput di lahan tegalan ataupun hutan pinusan. Di
Petungkriyono, usaha pemeliharaan sapi hanya diupayakan untuk pembesaran sapi. Sapi yang
masih kecil diberi makan terus hingga besar, dan setelah besar ditukar dengan dua ekor pedet
demikian berulang seterusnya.
Sementara itu, gerbang penelusuran sejarah masyarakat Petungkriyono dapat dimulai
dari lingga-yoni Nagapertala, sebuah peninggalan arkeologis yang berada di sebelah timur
laut pusat perkampungan Desa Tlagapakis, Petungkriyono. Lingga-yoni yang diperkirakan
dibuat sejak masa Mataram Hindu pada abad ke 9 masehi ini menunjukkan bahwa
Petungkriyono telah berkembang menjadi pemukiman besar dan komplek baik dari segi
sosial maupun keagamaannya sejak masa prakolonial . Analisis Semedi akan keberadaan
peninggalan arkeologis di wilayah petungkriyono ini bahkan menunjukkan bahwa selain
sebagai tempat pemujaan agama Hindu, kawasan
Di samping peranan pentingnya dalam konstelasi politik Mataram Hindu, masyarakat
di kawasan Petungkriyono masa itu telah berkembang menjadi masyarakat petani. Mereka
membuka lahan di tempat yang relatif datar dan dekat sumber air untuk menanam padi, ubi,
talas, dan sayur-sayuran dengan teknik rotasi tanam . Beberapa kebutuhan lain yang tidak
dapat dihasilkan di lahan pertanian mereka dapatkan dari hutan di sekitar pemukiman.
Sayangnya, tidak banyak informasi yang mampu didapatkan dari peninggalan-peninggalan
arkeologis di kawasan Tlagapakis ini. Sumber informasi mengenai kawasan ini yang lain
diperoleh dari data tertulis yang baru berasal dari era 1860-an , masa ketika kebijakan tanam
paksa hampir berakhir. Mengenai tanam paksa sendiri, diperkirakan kebijakan pemerintah
kolonial Belanda ini turut membawa perubahan besar di Petungkriyono. Deskripsi Hüsken
yang memaparkan adanya migrasi penduduk yang besar di pedesaan Jepara yang terkena
kebijakan tanam paksa tampaknya terjadi juga di kawasan Pekalongan dan sekitarnya. Untuk
kasus di Pekalongan, migrasi ini terjadi dalam dua arah: sebagian dari mereka lari ke pesisir
dan hidup sebagai nelayan , sedang sebagian yang lain lari ke pegunungan seperti
Petungkriyono untuk terlepas dari jerat tanam paksa. Dengan datangnya para pendatang dari
utara ini maka penduduk di Petungkriyono mengalami peningkatan pesat.
Perubahan penting kedua di masa ini adalah mulai dikenalnya budidaya tanaman kopi
di kawasan Petungkriyono . Perubahan ini sangatlah penting karena di kemudian hari biji
kopi ini menjadi satu dari tiga komoditas utama yang mendukung perekonomian masyarakat
Petungkriyono. Dua komoditas lain adalah daun bawang yang oleh masyarakat disebut
dengan selong dan aren yang diolah menjadi gula.
Benih permasalahan kelangkaan lahan mulai muncul di Indonesia atas tanah-tanah
yang ditempatinya, sehingga memungkinkan penjulan dan penyewaan tanah .
Padahal, ketika kebijakan ini diberlakukan kemungkinan besar masyarakat Petungkriyono
masih melakukan aktivitas pertanian perladangan. Dengan sistem perladangan ini, tentu
terdapat lahanlahan yang dibiarkan menganggur untuk memperoleh kesuburannya kembali.
Berdasar kebijakan liberasi ekonomi, tanahtanah bero ini dianggap pemerintah sebagai tanah
tak bertuan dan kemudian dianggap menjadi milik pemerintah untuk dijadikan hutan.
Pembukaan hutan untuk pemukiman, serta penebangan hutan untuk perkebunan yang intensif
di awal abad ke-20 juga menghadirkan masalah baru. Setiap tahun daerah Pekalongan dilanda
banjir kiriman dari dataran tinggi Petungkriyono. Bertolak dari masalah ekologi ini kebijakan
baru pun diterapkan bagi wilayah Petungkriyono. Pada tahun 1930-an pemerintah kolonial
menyusun satu kebijakan perbaikan hutan dengan menutup sebagian lahan pertanian dan
pemukiman milik penduduk untuk dijadikan lahan reboisasi 2.
Tahun 1942 hingga 1945, ketika pemerintah pendudukan Jepang berkuasa, kondisi
ekonomi masyarakat Petungkriyono tidaklah lebih baik. Beberapa orang di Tlogopakis masih
ingat begitu sulitnya hidup di jaman pendudukan Jepang. Setiap 10 pocong hasil panen padi
masyarakat masa itu dua pocong di antaranya harus diserahkan ke pemerintah. Pakaian
mereka terbuat dari goni, sehingga kalau kehujanan tangan mereka harus tetap memegang
celananya agar tak lepas. Untuk mendapatkan dua buah sarung, mereka harus menjual seekor
kambing jawa 3 Dinamika sosial, ekonomi di Petungkriyono terus bergerak. Agustus 1945
Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka. Paparan orang-orang tua di
Tlogopakis menyebutkan bahwa areal lahan yang kini di pakai sebagai hutan pinus
PERHUTANI dahulu merupakan tanah milik. Tlogopakis tidak kuat membayar seluruh
tanggungan pajak tanah. Orang-orang yang tidak mampu membayar seluruh tanggungan
pajak ini akan mendapat dluwang srip atas tanah yang tidak terpajaki. Tanah-tanah sitaan
inilah yang kini dipakai PERHUTANI sebagai lahan hutan pinus.
Paparan seorang informan menyebutkan pula bahwa sebuah sarung di zaman
pendudukan Jepang ini harus dibeli dengan harga 50 perak. Padahal, harga beras kala itu
hanya 5 sen/kg. Masa-masa sulit terus terjadi di Petungkriyono hingga dekade
Kartosuwirjo. Hampir tiada beda, kedua kekuatan militer «lokal» ini justru seringkali
menjarah harta rakyat. Mereka menjarah apa saja, «ada padi diangkat padi, ada jagung
diangkat jagung, ada kambing siangkat kambing, bahkan ada sisa nasi dalam periuk juga
diangkat bersama periuknya», demikian deskripsi Semedi untuk melukiskan kondisi
Petungkriyono masa itu. Pertengahan 1960 geger gerakan 30 September terjadi di negeri ini.
Walau dalam skala yang tidak besar, beberapa ketegangan sempat terjadi di wilayah
Petungkriyono. Dimulai sebelum tahun 1965, PKI telah berusaha menggalang masa di daerah
ini. «Orang-orang yang ikut PKI dijanjikan boleh membuka hutan tanpa biaya sedikit pun,»
demikian cerita mbah Tawirja.
Rahmat dari Kayupuring adalah mereka yang masuk PKI. Menuju tahun 1966 tiga
nama pertama pun diciduk dalam sebuah operasi pembersihan anggota PKI. Mereka dibawa
ke Pekalongan dan tak pernah kembali hingga saat ini . Sementara nama terakhir, Rahmat,
bernasib lebih baik. Dia hanya diwajibkan lapor di koramil
Petungkriyono. Akhir 1965, keadaan mulai relatif lebih tenang. Era pembangunan pun
dimulai. Melalui strategi pembangunan lima tahunnya, pemerintah Orde Baru melakukan
proyek «perubahan wajah» di Jawa. Daerah-daerah terpencil seperti Petungkriyono pun
merasakan imbasnya. Tahun 1971, dibuka sebuah jalan tembus yang menghubungkan
Petungkriyono dan Lebakbarang Prodjodirdjo, 1973 Keadaan peternakan di Petungkriyono
baru mulai membaik ketika PERHUTANI membuka peluang masyarakat untuk menanam
rumput gajah di lahan hutan pinus pada tahun 1986 .
Untuk meningkatkan produksi pertanian pemerintah juga membangun sebuah saluran
irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 325,290 ha. Di Mudal, bak-bak penampungan air
juga dibangun untuk memudahkan kebutuhan MCK masyarakat. Seiring berbagai perubahan
fisik tersebut, perubahan besar dalam sistem pertanian pun terjadi. Untuk pertanian padi,
masyarakat mulai mengenal bibit padi kucir . Dengan masa panen yang hanya 4-5 bulan
masyarakat mampu panen dua kali setahun yaitu dengan tetap menanam varietas padi Jawi
dalam masa tanam pertama dan menanam padi kucir di masa tanam kedua. Akibatnya,
kebutuhan tenaga kerja pun semakin besar. Apalagi jika masa tanam dan masa panen tiba.
Untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja ini masyarakat membangun sebuah mekanisme
kerja bersama bernama sambatan. Melalui sambatan seseorang yang hendak menggarap
lahannya dapat minta bantuan kerabat dan tetangganya untuk turut dalam kerja di lahan
pertaniannya. Konsekuensinya, ia pun harus bersedia membantu menggarap lahan kerabat
dan tetangganya. Tak ada upah dalam sistem sambatan.
Sambatan untuk menggarap lahan di Petungkriyono tidaklah menyentuh pada
tanaman komoditas. Sambatan untuk menggarap tanaman komoditas dianggap ora ilok .
Selong ke pasar Doro hingga dua kali sebulan. Di samping itu, setiap hari orang Petung
masih dapat mengambil 10-20 lingget selong di ladang untuk ditukar dengan kebutuhan
sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi dari lahan sendiri. Intensifnya masa panen selong ini
dimungkinkan karena hingga tahun 1980-an tak ada sistem musim dalam penanaman selong.
Setiap ingin memanen seseorang hanya akan memetik anakan dari serumpun selong. Induk
rumpun yang masih hidup akan tumbuh terus hingga tiap bulan seseorang dapat memetik
selong secara reguler. Sebagai tanaman komoditas, peran selong dalam perekonomian
masyarakat Petung sangatlah tinggi.
Anda mungkin juga menyukai
- Bab 3 Dan 4Dokumen12 halamanBab 3 Dan 4Eni KiryaniBelum ada peringkat
- Sejarah Pertanian Dunia Dan IndonesiaDokumen17 halamanSejarah Pertanian Dunia Dan IndonesiamuthiaBelum ada peringkat
- Sejarah PertanianDokumen8 halamanSejarah PertanianHayu Setyatma Erryna PutriBelum ada peringkat
- BAB I TAS 09.07.003 Nur DDokumen28 halamanBAB I TAS 09.07.003 Nur DMuhammad Rizky SimamoraBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Usahatani Di IndonesiaDokumen4 halamanSejarah Perkembangan Usahatani Di IndonesiaWulan Widjaya Ningrum100% (3)
- Sosio Kelompok SangarDokumen14 halamanSosio Kelompok SangardavidBelum ada peringkat
- Dai Tugas 1 Pengatar Ilmu PertanianDokumen10 halamanDai Tugas 1 Pengatar Ilmu PertanianDa'i ParakkasiBelum ada peringkat
- Sejarah Usaha TaniDokumen8 halamanSejarah Usaha TaniRifki A. FuadyBelum ada peringkat
- Bandit Pedesaan JawaDokumen7 halamanBandit Pedesaan JawaTok Tik0% (1)
- Resistensi Dan Gaya Hidup para Petani DiengDokumen14 halamanResistensi Dan Gaya Hidup para Petani DiengHery Santoso100% (1)
- 111 299 1 SMDokumen24 halaman111 299 1 SMAnisa Rizki NurainiBelum ada peringkat
- Land Reform Kolonial Belanda Di IndonesiaDokumen4 halamanLand Reform Kolonial Belanda Di IndonesiaEgo Vinda A. PBelum ada peringkat
- Paper Sejarah UsahataniDokumen16 halamanPaper Sejarah UsahataniIrma NovianaBelum ada peringkat
- Farhan Rizka Ananda-1907155233-Budaya Melayu-Teknik Sipil S1Dokumen6 halamanFarhan Rizka Ananda-1907155233-Budaya Melayu-Teknik Sipil S1Farhan Rizka AnAndaBelum ada peringkat
- 1505 2919 1 PBDokumen9 halaman1505 2919 1 PBDevan FirmansyahBelum ada peringkat
- As Jati Milik Di BloraDokumen6 halamanAs Jati Milik Di BloraAgus SumindarBelum ada peringkat
- Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Comal Kabupaten Pemalang Tahun 1830-1930Dokumen12 halamanTingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Comal Kabupaten Pemalang Tahun 1830-1930Romanti SilvaBelum ada peringkat
- Geografi Desa Kota Pertemuan 6Dokumen6 halamanGeografi Desa Kota Pertemuan 6Adek Eka PutriBelum ada peringkat
- Dian Octaviani - 463158 - UTS Sejarah Indonesia Abad 19-20Dokumen5 halamanDian Octaviani - 463158 - UTS Sejarah Indonesia Abad 19-20Dian OctavianiBelum ada peringkat
- Sejarah Usahatani Di IndonesiaDokumen5 halamanSejarah Usahatani Di IndonesiaHabi SusiloBelum ada peringkat
- 53 - Anandio Rendy Pamungkas - 13040220130123 - Antrop Pembangunan ADokumen3 halaman53 - Anandio Rendy Pamungkas - 13040220130123 - Antrop Pembangunan ADio BobothBelum ada peringkat
- Luthfiona Fitri R.S. (190110301062) Tugas 1 Sejarah Indo 19-20Dokumen7 halamanLuthfiona Fitri R.S. (190110301062) Tugas 1 Sejarah Indo 19-20Fiona RamadhaniBelum ada peringkat
- Mendaki MimpiDokumen42 halamanMendaki MimpiSudi ArtoBelum ada peringkat
- Ebijakan Pangan Dan Pembangunan Pertannian Di Indonesia Pada Masa Kemerdekaan (Orba / OrlaDokumen15 halamanEbijakan Pangan Dan Pembangunan Pertannian Di Indonesia Pada Masa Kemerdekaan (Orba / OrlaPutri Ari PrabandariBelum ada peringkat
- Presepektif Tekno Ekonomi Dalam Cerita Rakyat Gunung Bromo Bahasa IndoDokumen3 halamanPresepektif Tekno Ekonomi Dalam Cerita Rakyat Gunung Bromo Bahasa Indowarda ajaBelum ada peringkat
- Review Buku Dari Industri Hingga Batik PekalonganDokumen12 halamanReview Buku Dari Industri Hingga Batik PekalonganlenimarpelinaBelum ada peringkat
- 7.1 Kuli KontrakDokumen4 halaman7.1 Kuli KontrakMufti Ar RafiBelum ada peringkat
- Alma Dayini Selgi - 135200057 - RESUME MANAJEMEN USAHATANIDokumen8 halamanAlma Dayini Selgi - 135200057 - RESUME MANAJEMEN USAHATANIAlma Dayini SelgiBelum ada peringkat
- Bedah Ekonomi Nagari Dan Profil Ekonomi NagariDokumen23 halamanBedah Ekonomi Nagari Dan Profil Ekonomi NagariFakhrul RoziBelum ada peringkat
- Makalah Resensi Buku MaduraDokumen26 halamanMakalah Resensi Buku MaduraMuhammad Taufik Nurwansyah100% (1)
- Pertemuan. 2 ILMU USAHATANIDokumen19 halamanPertemuan. 2 ILMU USAHATANINyomanDarsanaBelum ada peringkat
- B. Pranata Politik Dan KepemimpinanDokumen4 halamanB. Pranata Politik Dan KepemimpinanDhiyat UddinBelum ada peringkat
- Aliefya Arinda Nurvita - V4120009 - Tugas Review FilmDokumen4 halamanAliefya Arinda Nurvita - V4120009 - Tugas Review FilmAliefya Arinda NurvitaBelum ada peringkat
- Perlawanan Rakyat IndramayuDokumen7 halamanPerlawanan Rakyat IndramayuSalsaBelum ada peringkat
- Pip GabunganDokumen180 halamanPip GabunganEka SaputraBelum ada peringkat
- BAB I - OkDokumen40 halamanBAB I - OkDaeng IpiiBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen18 halamanBab Iiahmad mun'imBelum ada peringkat
- Sejarah Penanaman Sawah Padi TradisionalDokumen30 halamanSejarah Penanaman Sawah Padi TradisionalCalvinMau100% (1)
- Peranan Rakyat BesukiDokumen8 halamanPeranan Rakyat BesukiAnonymous mRdcatBelum ada peringkat
- Hasil Peenlitian EtnografiDokumen8 halamanHasil Peenlitian Etnografi2020ANATASYA MAY FaneshaBelum ada peringkat
- Hegemoni Tengkulak Terhadap Petani Cengkeh Di Desa Bengkel, Kecamatan Busung Biu, BulelengDokumen55 halamanHegemoni Tengkulak Terhadap Petani Cengkeh Di Desa Bengkel, Kecamatan Busung Biu, Bulelengtenanki100% (1)
- Laporan Live - in KKN 72 UAJYDokumen20 halamanLaporan Live - in KKN 72 UAJYFelix YossyBelum ada peringkat
- Profil Dusun Dadapan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota BatuDokumen8 halamanProfil Dusun Dadapan Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota BatuDyah SeptianasariBelum ada peringkat
- Wa0002.Dokumen19 halamanWa0002.LANCARBARUBelum ada peringkat
- Upload Scribd 4Dokumen4 halamanUpload Scribd 4lilaalya4Belum ada peringkat
- Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Comal Kabupaten Pemalang Tahun 1830-1930Dokumen13 halamanTingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Comal Kabupaten Pemalang Tahun 1830-1930Romanti SilvaBelum ada peringkat
- Ipi287382 PDFDokumen12 halamanIpi287382 PDFxxxxudunxnuckerBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen22 halamanBab 1Fakhrul AnamBelum ada peringkat
- Konten Download Desa Wisata - Sembalun LawangDokumen8 halamanKonten Download Desa Wisata - Sembalun LawangAgie AditamaBelum ada peringkat
- Bina Desa, Laporan Pertanian Alami Desa Salassae (12 Feb 2019)Dokumen74 halamanBina Desa, Laporan Pertanian Alami Desa Salassae (12 Feb 2019)kristina tahukahBelum ada peringkat
- Tugas Paper Sejarah Pertanian (Pip)Dokumen8 halamanTugas Paper Sejarah Pertanian (Pip)Luthfi HalimBelum ada peringkat
- Perkembangan PertanianDokumen9 halamanPerkembangan PertanianAvril Rizqullah Syabas GhozaliBelum ada peringkat
- Sosiologi Kehutanan Dan LingkunganDokumen7 halamanSosiologi Kehutanan Dan LingkunganAlfi SofyanBelum ada peringkat
- Review Buku Dari Industri Hingga Batik PekalonganDokumen13 halamanReview Buku Dari Industri Hingga Batik PekalonganlenimarpelinaBelum ada peringkat
- Sejarah DesaDokumen8 halamanSejarah DesaMuhammad AkshaBelum ada peringkat
- Ciri Ekonomi TradisionalDokumen11 halamanCiri Ekonomi TradisionalHidayah Rosly50% (2)
- Makalah Sejarah Perkebunan IndonesiaDokumen20 halamanMakalah Sejarah Perkebunan IndonesiaRahmat Phoenix100% (3)
- AgrariaDokumen18 halamanAgrariapurple youBelum ada peringkat
- Perubahan Sosial Masyarakat PertanianDokumen2 halamanPerubahan Sosial Masyarakat PertanianAkmal AmalBelum ada peringkat