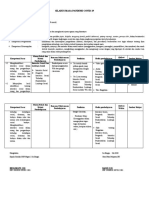BAB I Sejarah Sastra
Diunggah oleh
Liska SeptianaDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
BAB I Sejarah Sastra
Diunggah oleh
Liska SeptianaHak Cipta:
Format Tersedia
BAB I SEJARAH SASTRA INDONESIA
1.1 PENGERTIAN SEJARAH Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sastra Indonesia ialah sastra berbahasa Indonesia, sedangkan hasilnya adalah sekian banyak puisi, cerita pendek, novel, roman, dan naskah drama berbahasa Indonesia. Akan tetapi, defenisi yang singkat dan sederhana itu dapat didebat dengan pendapat yang mengatakan bahwa sastra Indonesia adalah kesseluruhan sastra yang berkembang di Indonesia selama ini. Pada kenyataannya telah berkembang sastra-sastra daerah, seperi: Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Bugis, Toraja, Lombok, dan sebagainya. Dalam konteks wilayah pertumbuhan dan perkembangannya secara nasional, berbagai sastra daerah itu dapat disebut juga sastra Indonesia dengan pengertian sastra milik bangsa Indonesia. Apabila dihubungkan dengan usaha mewujudkan kebudayaan nasional, jelaslah bahwa sastra daerah itu merupakan unsur kebudayaan nasional. Hal ini telah dibahas dalam seminar pengembangan sastra daerah di jakarta, 13-17 Oktober 1975. Ilmu sastra sudah merupakan ilmu yang cukup tua usianya. Ilmu ini sudah berawal pada Abad ke-3 Sebelum Masehi, yaitu pada saat Aristoteles (384-322 SM) menulis bukunya yang berjudul Poetica yang memuat tentang teori drama tragedi. Istilah Poetica sebagai teori ilmu sastra, lambat laun digunakan dengan beberapa istilah lain oleh para teoretikus sastra seperti The Study Of Literatur, oleh W. H. Hudson, Theory Of Literatur, oleh Rene Wellek dan Austin Warren, Literary Scholarship, oleh Andre Lafavere, serta Literary Knowledge (ilmu sastra) oleh A. Teeuw. Sementara itu, Teeuw menyatakan ada kerugian untuk membagi-bagi sastra Indonesia menurut bahasanya tanpa memerhatikan keseluruhan dan kesatuan sastra Indonesia. Sebaiknya sastra Indonesia diteliti sebagai satu bidang dengan memerhatikan beberapa hal, seperti sejarah dan perbandingan sastra, tipologi, metode dan manfaatnya dalam konteks semboyan Bhineka Tunggal Ika. Pendapat Teeuw mengisyaratkan pemakaian istilah sastra Indonesia dengan pengertian yang luas, bahkan sejarahnya terbilang sudah sangat tua. Akan tetapi, ilmuh sejarah di indonesia terbilang tidak populer. Usianya juga relatif masih muda kalau dihitung dari pertumbuhannya pada akhir tahun 1950-an. Padahal manfaatnya sering dikatakan penting oleh para ahli dan penguasa. Misalnya, sering terdengar slogan jangan melupakan sejarahdalam pidato politik. Maksudnya agar masyarakat mau belajar dari pengalaman
~1~
masa lampau dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya, menurut Kuntowijoyo (1994:17) sejarah masih merupakan barang mewah yang sedikit peminatnya. Apabila dilihat secara individual, setiap orang dewasa pastih telah memiliki sejarah atau riwayat hidupnya sendiri. Seorang remaja yang mulai memasuki dunia perguruan tinggi dapat membuka catatan harian atau ingatan dan kenangan pribadinya tentang banyak hal yang sudah terjadi di masa lampau. Misalnya, mengingat kembali kampus sekolahnya, kawan-kawannya, gurugurunya, dan berbagai peristiwa yang penuh kenangan. Tentu saja tidak mungkin seluruh pengalaman masa lampau itu teringat kembali karena keterbatasan daya ingat manusia. Biasanya pengalaman yang teringat terbatas pada hal-hal yang luar biasa, hebat, berkesan, dan terikat juga oleh rentang waktu kehidupannya. Semakin jauh jarak pengalaman dengan keinginan seseorang maka terjadilah kekaburan atau kelupaan, kecuali terdukung oleh bukti-bukti sejarah atau riwayat pribadi, seperti foto-foto, dokumen, buku harian, dan pengakuan orang lain. Ketika seseorang mengingat-ingat atau mengenang kembalipengalaman masa lampau sebenarnya sedang merekonstruksi sejarah sesuai dengan tafsiran atau kepentingannya sendiri. Apa yang dianggap penting bagi dirinya belum tentu tampak penting juga di mata orang lain. Secara umum objek penulisan sejarah adalah masa lampau umat manusia dengan segala kegiatannya yang tampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan secara khusus objek penulisan sejarah adalah bidang-bidang tertentu, seperti politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, kesenian, dan sastra. Setiap bidang masih dapat dibatasi lagi pada proyek yang spesifik. Dengan demikian, sangat terbuka kemungkinan berkembang penulisan sejarah politik, sejarah perekonomian, sejarah sosial, sejarah kota, sejarah desa, sejarah kebudayaan, sejarah kesenian, sejarah sastra, dan lain-lain (lihat juga Sejarah Dewasa ini oleh Yuliet Gardiner, 1996). Masih sangat banyak masalah sejarah yang pantas diketahui siapa pun yang meminatinya, tetapi untuk sementara baiklah dibatasi sampai di sini dengan alasan sekedar pengetahuan elementer bagi mahasiswa atau calon sarjana sastra. Tentu saja pendalaman dan pengembangannya menjadi tanggung jawab profesi di masa depan. Akan tetapi, pantas dicatat bahwa sarjana sastra tidak harus menjadi sejarawan lebih dahulu untuk menulis sejarah sastra. Analog dengan hal itu, sarjana sastra tidak harus menjadi sosiolog lebih dahulu untuk meneliti aspek sosial karya sastra. Sarjana sastra pun tidak harus menjadi psikolog untuk mengkaji aspek psikologis tokoh-tokoh cerpen, novel atau roman. Akan tetapi, sarjana sastra harus memahami prinsip-prinsip sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, sejarah, dan lain-lain yang merupakan ilmu bantu pengkajian sastra.
~2~
1.2 SEJARAH SASTRA Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sejarah sastra merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Dengan pengertian dasar itu, tampaklah bahwa objek sejarah sastra adalah segala peristiwa yang terjadi pada rentang masa pertumbuhan dan perkembangan sastra suatu bangsa. Dalam Pengantar Ilmu sastra (Luxemburg, 1982: 200-212) dijelaskan bahwa dalam sejarah sastra dibahas periode-periode kesusatraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan juga reaksi pembaca. Semua itu dapat dihubungkan dengan perkembangan di luar bidang sastra, seperti: sosial dan filsafat. Jadi, sejarah sastra meliputi penulisan perkembangan sastra dalam arus sejarah dan di dalam konteksnya. Perhatian parah ahli sastra di Eropa terhadap sejarah muncul pada abad ke-19, berawal dari perhatian ilmuwan pada zaman Romantik yang menghubungkan segala sesuatu dengan masa lampau suatu bangsa. Adapun dasarnya adlah filsafat positivisme yang bertolak pada prinsip kausalitas, yaitu segala sesuatu dapat diterangkan bila sebabnya dapat dilacak kembali. Dalam hal sastra, sebuah karya sastra dapat diterangkan atau telah secara tuntas apabila diketahui asal usulnya yang bersumber pada riwayat hidup pengarang dan zaman yang melingkunginya. Ahli sejarah sastra Jerman, Wilhelm Scherer (1841-1886) mempergunakan tiga faktor penentu, yaitu: das Ererbte (warisan), das Erlebte (pengalaman), dan das Erlernte (hasil proses belajar). Penerapannya menuntut kerja sama yang erat antara ahli fisiologi, psikologi, linguistik, dan sejarah kebudayaan. Dia menegaskan bahwa seorang penulis sejarah sastra harus mampu menyelami seluruh kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, dalam kebertautan yang kausal. Positivisme telah berjasa terhadap penulisan sejarah sastra yang menghubungkan perkembangan sastra dengan kejadian-kejadian didalam bidang sejarah, politik, dan sosial dengan kecenderungan terhadap data pengarang dan karya mereka disertai komentar evaluatif si penulis. Pada perkembangan kemudian (awal abadke-20) tampaklah munculnya teori formalisme, strukturalisme, dan sejarah resepsi yang pantas di kaji dalam penulisan sejarah sastra. Sementara itu, Joeri Tynjanov memandang karya sastra sebagai suatu sistem dan menekankan pada fungsi berbagai unsur di dalam sistem itu. Unsur tertentu dapat berfungsi dominan pada suatu masa dan digeser oleh unsur lain pada masa yang lain karena pengaruh tradisi. Untuk menentukan unsur mana yang berfungsi paling tepat dalam sistem sastra maka harus dilakukan penyelidikan sejauh mana unsur itu telah berakar pada tradisi.
~3~
1.3 SEJARAH SASTRA INDONESIA Perhatian masyarakat Sastra Indonesia terhadap masalah sejarah kebudayaan, termasuk sastra, telah tampak sejak awal pertumbuhan Sastra Indonesia di tahun 1930-an sebagaimana terbaca dalam Polemik Kebudayaan suntingan K. Mihardja (1977). Polimik yang berkembang antara tokoh-tokoh S. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, poerbatjaraka, m. Amir, Ki hadjar Dewantara, Adinegoro, dan lain-lain memang tidak secara khusus memperdebatkan konsep kesusastraan Indonesia, tetapimemperlihatkan kesadaran mereka terhadap sejarah kebudayaan Indonesia. Takdir Alisjahbana berpendapat bahwa sebutan Indonesia telah dipergunakan secara luas dan kabur, sehingga tidak secara tegas menunjuk pada semangat keindonesiaan yang baru sebagai awal pembangunan kebudayaan Indonesia Raya. Menurut Takdir, semangat keindonesiaan yang baru seharusnya berkiblat kebarat dengan menyerap semangat atau jiwa intelektualnya agar wajahnya berbeda dengan masyarakat kebudayaan pra-Indonesia. Namun, pendapat yang teoritis itu di kritik oleh Sanusi Pane yang berpendapat bahwa keindonesiaan itu sudah ada sejak sekian abad yang silam dalam adat dan seni. Sanusi Pane berpendapat, kebudayaan Barat yang mengutamakan intelektualitas untuk kehidupan jasmani tidak dengan sendirinya istimewa karena terbentuk oleh tantangan alam yang keras sehingga orang harus berpikir dan bekerja keras. Sementara itu, kebudayaan Timur pun memiliki keungulan, yaitu: mengutamakan kehidupan rohani karena kehidupan jasmani telah dimanjakan oleh alam yang serba memberikan kemudahan. Oleh karena itu, kebudayaan indonesia baru dapat dibentuk dengan mempertemukan semangat intelektualitas Barat dengan semangat kerohanian Timur. Poerbatjaraka berpendapat bahwa sambungan kesejarahan itu sudah ada dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, deperlukan penyelidikan tentang jalannya sejarah sehingga orang dapat menengok ke belakang sebagai landasan melihat keadaan zaman yang bersangkutan dan selanjutnya mengatur hari-hari yang akan datang. Lintasan pendapat itu mengisaratkan kesadaran para tokoh intelektual Indonesia tahun 1930-an terhadap sejarah kebudayaan. Adapun kesadaran terhadap sejarah sastra Indonesia makin tampak pada tahun 1940-an ketika S. Takdir Alisjahbana Menulis Puisi Baru (1946) dan H. B. Jassin menyusun antologi Gemah Tanah Air (1948) dan Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang (1948). Menurut Takdir, perkenalan masyarakat bangsa Indonesia denga bangsa Eropa selama berabad-abad telah menimbulkan perubahan besar dalam gaya hidup dan pemikiran sehingga pada abad ke-19 boleh dikatakan bangsa Indonesia telah memasuki zaman modern.
~4~
BAB II Masa Pertumbuhan Sastra Indonesia
2.1 Sekolah dan Pers Gambaran umum kehidupan sastra Indonesia tahun 1900-1945 sudah ditulis oleh, Bakri Siregar (1964), Zuber Usman (1964), Teeuw (1952; 1979;1980), Ajip Rosidi (1969), danJakob Sumardjo (1992) dengan pandangan masing-masing. Apapun yang sudah mereka tulis itu perlu dibaca setiap peminat sejarah sastra Indonesia dengan wawasan atau penafsiran baru. Akan tetapi, ada kemungkinan buku-buku mereka itu tidak tersedia di setiap perpustakaan dan tokoh buku sehingga sulit di jangkau peminat. Buku Bakri Siregar misalnya, sangat mungkin sulit diperoleh di mana-mana karena termasuk buku yang dibekukan atau dilarang pada tahun 1966 terkait dengan kedudukan penulisnya sebagai tokoh Lekra. Jadi, wajarlah apabila kemudian hilang di celah khazanah pustaka masyarakat. Buku Teeuw yang terbit tahun 1952 itu pun tampaknya sudah sulit diperoleh di berbagai perpustakaan. Demikian juga nasib buku Ajip Rosidi dan Jakob Sumardjo. Buku-buku terbitan tahun yang silam akan terbaca kembali oleh generasi kemudian apabila di cetak ulang dan diterbitkan kembali. Padahal masalah itu tidak sederhana karena terkait dengan sejumlah alasan dan kepentingan, seperti pembelajaran sastra di sekolah dan kepentingan penerbit yang perlu memperhitungkan keuntungan. Buku yang di pandang penting oleh suatu pihak belum tentu dipandang penting juga oleh penerbit dengan alasan aktualitas, pangsa pasar, dan lain-lain. Dengan demikian, kelangkaan buku-buku tertentu harus dipahami dengan kesadaran bahwa penerbitan buku apa pun terbilang rumit. Tentu saja masalah itu bukan hambatan para peneliti sebab masih terbuka kemungkinan memperolehnya di perpustakaan terkemuka, koleksi pribadi, atau Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin di jalan Cikini Raya 73, Jakarta. Di kantor ini tersimp[an buku, majalah, koran, dan kliping sastra sejak puluhan tahun yang silam dapat di simak dan dibaca langsung di tempat atau difotokopi untuk kepentingan penelitian. Peneliti yang berdomisili di luar Jakarta pun dapat memanfaatkan jasa pelayanannya dengan permintaan data secara tertulis disertai biaya pengganti fotokopi dan pengiriman. Apabila datanya sudah tersedia, permintaan siapapun pasti dilayani sebagaimana mestinya. Sementara itu, lembaga lain yang dapat diharapkan dukungannya terhadap penelitian sastra Indonesia adalah Pusat Bahasa di jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta. Peranan lembaga ini pun semakin penting dengan banyaknya penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan Daerah.
~5~
2.2 Balai Pustaka Nama Penerbit Balai Pustaka sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terpelajar Indonesia, karena sekarang Balai Pustaka merupakan salah satu penerbit besar yang banyak memproduksi berbagai jenis buku. Nama tersebut telah bertahan selama lebih dari 90 tahun, kalau dihitung dari berdirinya pada tahun 1917 yang merupakan pengukuhan komisi untuk Sekolah Bumiputra dan Bacaan Rakyat (Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 14 September 1908. Jelas bahwa badan penerbit itu merupakan organ pemerintah kolonial yang semangatnya boleh dikatakan berseberangan dengan penerbitpenerbit swasta, baik yang semata-mata bervisi komersial maupun bervisi kebangsaan. Akn tetapi, mengingat sejarahnya yang panjang itu maka sepantasnya menjadi bagian khusus dalam pengkajian atau telaah sejarah sastra Indonesia. Secara teoretis dapat dikatakan banyak masalah yang dapat diungkapkan dari Balai Pustaka selama ini, antara lain visi dan misi status, program kerja, para tokoh, kebijakan redaksi, pengarang, produksi, dan distribusi. Telaah semacam itu dapat dijadikan pengkajian sejarah mikro yang pasti relevan dengan sejarah makro sastraIndonesia. Ditambah dengan pengkajian berbagai gejala yang berkembang di sekitarnya pastilah memperluas wawasan pengetahuan masyrakat. Mungkin saja kemudian berkembang pendapat bahwa Balai Pustaka ternyata bukan satu-satunya penerbit yang pada tahun 1920-an membuka tradisi sastra modern, atau justru dilupakan saja karena berjejak kolonial. Apa pun kemungkinan itu jelas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh para pakar dan peneliti sejarah sastra Indonesia. Yang jelas ada beberapa masalah esensial Balai Pustaka yang secara historis tidak terbantahkan. Kapan pun harus ditulis bahwa Balai Pustaka didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan keputusan gubernemen pada 14 September 1908 dan pada tahun 1917 dikukuhkan menjadi Balai Pustaka kapan pun harus dicatat bahwa Balai Pustaka telah menerbitkan sejumlah roman, seperti Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar, Siti Nurbaya karangan Marah Rusli, dan Salah Asuhan karangan Abdul Muis, yang kemudian terbaca banyak orang. Kalaupun pandangan orang terhadapnya berubah dan berkembang, bahkan berbeda antara yang satu dengan yang lain, harus dipahami kontekstual. Maksudnya, dipahami dalam kaitannya dengan siapa yang berpendapat, apa latar belakangnya, kapan dan di mana berpendapat, apa datanya, dan sebagainya. Dengan demikian, berkembanglah pandangan yang komprehensif.
~6~
Pada tahun 1930-an Balai Pustaka dapat menjadi penerbit besar karena di dukung oleh kekuasaan pemerintahan sehingga mampu menyebarluaskan produksinya ke seluruh pelosok Nusantara. Sementara itu, di luar Balai Pustaka berkembang penerbit-penerbit swasta, baik yang semata usaha dagang maupun organ parai politik dan organisasi daerah. Dalam penelitian Tasai (2002: 11-17) tercatat sejumlah surat kabar atau majalah yang terbit pada tahun 1920-an, antara lain Penghidupan, Penghibur, Warna Warta, Bintang Hindia, Han Sing, Sin Po, Cerita Melayu, Zaman Baru, Azyraq, Panorama, Mustika, Deliana, Keng Po, Dunia Istri, Caya Timur; pada tahun 1930-an tercatat antara lain Pedoman Masyrakat, Panji Islam, Pedoman Islam, Pewarta Deli, Pelita Andalas, Penyedar, Pujangga Baru, Asia Masa, dan Bahtera Masa. Tokoh-tokoh yang pernah memimpin Balai Pustaka tercatat Dr. D. A. Rinkes, Dr. G. W. J. Drewes, Dr. K. A. Hidding, sedangkan sastrawan Indonesia yang pernah bekerja di sana tercatat Adinegoro, S. Takdir Alisjabana, Armijin Pane, Nur Sutan Iskandar, dan H. B. Jassin. Pada zaman itu Balai Pustaka menghasilkan bermacam buku, majalah, dan almanak. Bukubuku populer yang terbit meliputi; kesehatan, pertanian, peternakan, budi pekerti, sejarah, adat, dan lain-lain. Majalah yang di terbitkan Balai Pustaka adalah Sri Pustaka yang kemudian bernama Panji Pustaka berbahasa Melayu (1923), Kejawen berbahasa Jawa (1926), dan Parahiangan berbahasa Sunda (1929). Tiras penerbitan Panji Pustaka pernah mencapai 7.000 eksemplar, Kejawen mencapai 5.000 eksemplar, Parahiangan 2.500 eksemplar, Almanak yang diterbitkan Balai Pustaka adalah Volksalmanak, Almanak Tani, dan Almanak Guru.
~7~
2.3 Pujangga Baru Seperti halnya Balai Pustaka, Pujangga Baru pun merupakan sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia. Kata itu dapat diartikan sebagai majalah aslinya tertulis Poedjangga Baroe, dan dapat juga diartikan gerakan kebudayaan Pujangga Baru tahun 1930-an yang tidak terpisahkan dari tokoh-tokoh pemuda terpelajar Muhammad Yamin, Rustam Effendi, S. Takdir Akisjahbana, Armijn Pane, Sanusi Pane, J. E. Tatengkeng, dan Amir Hamzah. Majalah Pujangga Baru terbit pertama kali pada Mei 1933 dengan tujuan menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah karena sebelumnya boleh dikatakan cerai berai dengan menulis berbagai majalah. Sebenarnya usaha menerbitkan suatu majalah kesusastraan sudah muncul pada tahun 1921, 1925, dan 1929, tetapi selalu gagal. Baru pada tahun 1933 atas usaha S. Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Arijn Pane dapat diterbitkan majalah bernama Pujangga Baru, Tujuannya tampak pada keterangan resmi yang berbunyi, majalah kesusastraan dan bahasa dan bahasa serta kebudayaan umum kemudian berubah menjadi pembawa semangat baru dalam kesusastraan, seni, kebudayaan dan soal masyarakat umum dan berganti lagi menjadi pembimbing semangat baru yang dinamis untuk membentuk kebudayaan persatuan Indonesia (Rosidi, 1969: 35). Majalah Pujangga Baru mendapat sambutan hangat dari sejumlah terpelajar, seperti: Adinegoro, Ali Hasjmy, Amir Sjarifuddin, Aoh K. Hadimadja, H. B. Jassin, I Gusti Nyoman Panji Tisna, J. E. Tatengkeng, Karim Halim, L. K. Bohang, Muhammad Dimjati, Poerbatjaraka, Selasih, Sumanang, Sultan Sjahrir, dan W. J. S. Poerwadarminta. Namun, di sisi lain, majalah itu tidak ditanggapi oleh kaum bangsawan melayu, dan bahkan dikritik keras oleh para guru yang setia kepada pemerintah kolonial Belanda. Kata mereka, majalah tersebut merusak bahasa Melayu karena memasukkan bahasa daerah dan bahasa asing. Majalah itu bertahan terbit hingga tahun 1942, kemudian dilarang oleh penguasa militer jepang karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Akan tetapi, setelah Indonesia merdeka dapat diterbitkan lagi tahun 1949-1953 di bawah kendali S. Takdir Alisjahbana dengan dukungan tenaga-tenaga baru, seperti: Achdiat K.mihardja, Asrul Sani, Chairil Anwar, Dodong Djiwapradja, Harijadi S. Hartowardojo, dan Rivai Apin. Tentu saja semangatnya sudah berbedah dengan semangat tahun 1930-an karena kondisi sosial politik pun sudah berubah.
~8~
Sumbangan Pujangga Baru terhadap perkembangan pemikiran kebudayaan Indonesia pantas dihargai tinggi karena memberikan kesempatan para sastrawan dan budayawan untuk menyalurkan pendapat-pendapatnya sehingga berkembang Polemik yang semarak sebagaimana tampak pada buku Polemik Kebudayaan susunan Achdiat K. Mihardja (1977). Tokoh-tokoh yang terlibat dalam polemik itu antara lain S. Takdir Alisjahbana, Sanusi Pane, R. M. Ng. Poerbatjaraka, Dr. Sutomo, Adinegoro, Dr. M. Amir, dan Ki Hajar Dewantara. Identitas mereka itu dapat dibaca pada bagian akhir Polemik Kebudayaan. Tokoh-tokoh Angkatan Pujangga Baru adalah S. Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, Armijn Pane, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Rustam Efendi, J. E. Tatengkeng, Asmara Hadi, dan lain-lain. Masa jaya majalah Pujangga Baru surut karena datangnya bala tentara Jepang pada Maret 1942. Janganlah di bayangkan kejayaan majalah tersebut seperti majalah sastra Horison yang dewasa ini tercetak bagus dan tersebar luas. Menurut pengakuan H. B. Jassin sebagaimana disampaikan dalam wawancara Wahyu Wibowo dan Kasijanto yang termuat di Basis Juli 1983 (halaman 263-270), majalah Pujangga Baru tidak terdukung modal keuangan dan sedikit saja peminatnya. Pada zaman itu tercetak paling banyak 400 eksemplar dengan persebaran terbatas ke kalangan guru dan mereka yang dianggap memiliki perhatian terhadap masalah kebudayaan dan kesusastraan. Majalah Pujangga Baru ternyata tidak menyediakan honorarium untuk para penyumbang, bahkan tidak juga mengkaji redaksinya, termasuk H. B. Jassin yang pada tahun 1940-1942 menjadi Sekretaris Redaksi. Namun, pengaruhnya terhadap semangat para penulis dan pengarang pantas dibanggakan, terbukti banyak tulisan yang mengalir ke Redaksi Pujangga Baru. Kebanyakan tergugah oleh tulisan-tulisan Takdir Alisjahbana yang pada waktu itu selalu bersemangat menawarkan gagasan-gagasan menuju Indonesia baru. Di mata Jassin, majalah yang profilnya sederhana itu ibarat perambah jalan atau pelopor. Kesederhanaan majalah Pujangga Baru masih dapat dinikmati atau disaksikan di Pusat Dokumentasi Sastra H. B. Jassin di Jakarta.
~9~
Bab IV Penutup Pengetahuan sastra Indonesia, baik secara garis besar (makro) maupun secara terperinci (mikro) merupakan modal kerja yang penting bagi siapa pun yang meminati pengkajian sastra Indonesia dengan tujuan akhir lebih memahami makna sastra Indonesia bagi kehidupan bebangsa yang berbudaya, mengingat teks sastra Indonesia (dan daerah) merupakan rekaman gagasan para pengarang yang dipercaya mencerminkan identitas bangsa di bidang kebudayaan. Pengetahuan itu pun dapat berkembang menjadi ilmu atau disiplin tersendiri di tangan para pakar, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, kritikus, esais, penyair, pengarang, pustakawan, dan guru sastra yang sepantasnya berada di wilayah pengkajian tersebut. Pengetahuan itu akan memperluas wawasan berpikir dan membantu seseorang mengetahui posisinya di tengah dinamika kehidupan sastra Indonesia. Pengetahuan secara garis besar akan mencakup pertumbuhan dan pekembangan sastra Indonesia dari masa ke masa, sedangkan perinciannya akan tampak pada dinamika sastra Indonesia pada setiap masa. Tentu saja pengetahuan itu tidak cukup diperoleh hanya dengan sekali baca, tetapi harus dengan membaca dan membaca lagi; sebab perkembangan dan dinamika sastra Indonesia sudah terbilang pesat, sehingga sulitlah diikuti jejaknya secara sambil lalu. Dengan kata lain, pengkajian atau telaah sejarah sastra Indonesia pun sebenarnya tidak cukup disajikan hanya dalam sebuah buku. Kalaupun hal itu dilaksanakan dalam buku ini, alasan yang utama adalah kehendak memenuhi kepentingan praktis dalam pengajaran sejarah sastra Indonesia yang seharusnya mengungkap sejumlah masalah dari masa awal pertumbuhan hingga masa perkembangan muktakhir. Awal sejarah sastra Indonesia dapat dirunut sekurang-kurangnya pada pembentukan Komisi Bacaan Rakyat tahun 1908 yang kemudian diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917, tetapi dapat juga di perjauh sampai pertengahan abad ke -19, suatu masa yang telah melahirkan tradisi sastra Melayu rendah sebagai embrio sastra Indonesia. Masa pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia yang relatif cukup sudah panjang,terhitung seratus tahun dari 1900 sampai dengan 2007, dapat dibagi-bagi menjadi beberapa masa atau periode berdasarkan konsep atau pendekatan tertentu. Tujuannya adalah memudahkan deskripsi dinamika kehidupan sastra Indonesia dari masa ke masa sehingga terbentuk gambaran teoretis mengenai keseluruhannya. Gambaran umum itu dapat dijadikan acuan untuk pengkajian mikro atau telaah yang khusus dan terbatas.
~ 10 ~
DAFTAR PUSTAKA
Fananie, Zainuddin. (2000). Telaah Sastra. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Faulkner, Peter. (1991). Modernismse Seri Konsep Sastra. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasan, Fuad. (1992). Perkenalan dengan Eksistensialisme. Jakarta: Pustaka Jaya. Hardja, Andre. (1991). Kritik Sastra Sebuah Pengantar. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. Pringgodo, A. G. (1977). Ensiklopedi Umum. Jakarta: Kanisius. Abdullah, Taufik. (1998). Pusat Bahasa: Kenangan Dan Harapan dalam Dendy Sugono (Ed). Setengah Abad Kiprah Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia 1947-1997. Jakarta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Anonim, 1992 Rumusan Hasil Kongres Kebudayaan 1991 dalam Kebudayaan, No. 2 Th.I, 1991/1992. Anwar, Rosihan. 1973. Sekelumit Kenang-kenangan Kegiatan Sastrawan di Zaman Jepang 1943-1945. Budaya Jaya, No. 65 Th. VI, Oktober. Adilla, Ivan. 2003. A. A. Navis: Karya dan Dunianya. Jakarta: Grasindo. Adiwimarta, Sri Sukesi. 1983. Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
~ 11 ~
Anda mungkin juga menyukai
- Puisi Chairil Anwar Dan Amir HamzahDokumen15 halamanPuisi Chairil Anwar Dan Amir HamzahVeni Zakiatun NabilahBelum ada peringkat
- Kesusateraan Kebudayaan MelayuDokumen35 halamanKesusateraan Kebudayaan MelayuBritney SoniaBelum ada peringkat
- Teori Transformasi GeneratifDokumen23 halamanTeori Transformasi GeneratifKasim DekBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Sastra Indonesia - 2017Dokumen2 halamanSejarah Perkembangan Sastra Indonesia - 2017Tanti Hartanti RivaiBelum ada peringkat
- Puisi ModenDokumen6 halamanPuisi ModenGabriel WongBelum ada peringkat
- TataBahasa GeneratifDokumen3 halamanTataBahasa GeneratifXiah MunirahBelum ada peringkat
- Sejarah Sastra IndonesiaDokumen13 halamanSejarah Sastra IndonesiaihsanBelum ada peringkat
- HBML4203 - 720211115031 - Kesusasteraan MelayuDokumen14 halamanHBML4203 - 720211115031 - Kesusasteraan MelayuawieinaBelum ada peringkat
- Analisis PuisiDokumen5 halamanAnalisis PuisiVhe Vena S100% (1)
- Sejarah Puisi Di IndonesiaDokumen5 halamanSejarah Puisi Di IndonesiaNurul AzuraBelum ada peringkat
- Definisi PuisiDokumen7 halamanDefinisi PuisiMimbar KataBelum ada peringkat
- Teori Dialogisme BakhtinDokumen7 halamanTeori Dialogisme BakhtinRindiyani Sri BarokahBelum ada peringkat
- Asimen Linguistik 2Dokumen12 halamanAsimen Linguistik 2fazilaziz100% (1)
- Teori Strukturalisme Dan SemiotikaDokumen12 halamanTeori Strukturalisme Dan SemiotikaAdi Ginanjar Gunaf0% (1)
- Assigment DR - Rasid (Pantun)Dokumen18 halamanAssigment DR - Rasid (Pantun)supian72Belum ada peringkat
- Konsep SosiologiDokumen2 halamanKonsep SosiologiAnonymous JFhBUNBfLBelum ada peringkat
- Asgmt Okonkwo Usm Tahun 3Dokumen16 halamanAsgmt Okonkwo Usm Tahun 3FatinayuSkpsIIBelum ada peringkat
- Karya Agung Tugasan KeduaDokumen15 halamanKarya Agung Tugasan KeduaKhoirulnizam NizamBelum ada peringkat
- Sari27 (2) 2009Dokumen31 halamanSari27 (2) 2009HananiIepinBelum ada peringkat
- Tugasan PantunDokumen29 halamanTugasan PantunAnne SudkiBelum ada peringkat
- Teori RasaDokumen5 halamanTeori RasaAzaha IbrahimBelum ada peringkat
- Ayat Majmuk CampuranDokumen5 halamanAyat Majmuk CampuranRazif Ismaiel SoulflyBelum ada peringkat
- A Samad Said - Nilai Murni DLM SasDokumen8 halamanA Samad Said - Nilai Murni DLM SasJasmine Eng67% (3)
- Sastera RakyatDokumen19 halamanSastera RakyatNur Ain Mohd Amin100% (6)
- Esemen SasteraDokumen20 halamanEsemen SasteraAnis Suraya100% (1)
- Penghayatan SasteraDokumen5 halamanPenghayatan SasteraCikgu Osman bin ZainiBelum ada peringkat
- Kesantunan MelayuDokumen12 halamanKesantunan MelayuSafiatikhah AhmedBelum ada peringkat
- Rejab FDokumen29 halamanRejab FKu Rushidi Ku AhmadBelum ada peringkat
- Penghayatan Karya Agung MelayuDokumen15 halamanPenghayatan Karya Agung MelayuermazlieBelum ada peringkat
- Tips Menulis PuisiDokumen2 halamanTips Menulis PuisidillaBelum ada peringkat
- PUISI Amir Hamzah 'Padamu Jua'Dokumen1 halamanPUISI Amir Hamzah 'Padamu Jua'AntonPutraBelum ada peringkat
- EKM322 - Kesusasteraan MelayuDokumen4 halamanEKM322 - Kesusasteraan MelayuXi ZhenBelum ada peringkat
- Kritikan SasteraDokumen5 halamanKritikan SasteraqasehsafinahBelum ada peringkat
- Melayu KlasikDokumen8 halamanMelayu Klasikwww_sharudindamit93Belum ada peringkat
- Teori Sastra (Materi)Dokumen60 halamanTeori Sastra (Materi)Rany FebrianiBelum ada peringkat
- Penggunaan Bahasa Melayu Dalam Hikayat AbdullahDokumen23 halamanPenggunaan Bahasa Melayu Dalam Hikayat AbdullahFadhilah Atikah100% (2)
- TUGASAN 2 From Folklore To Urban FolkloreDokumen1 halamanTUGASAN 2 From Folklore To Urban FolkloreFadhli Hariz Fayahet100% (1)
- JPMM 2009 Awang Azman Awang PawiDokumen16 halamanJPMM 2009 Awang Azman Awang PawiFazliani OsmanBelum ada peringkat
- Isu SosiolinguistikDokumen2 halamanIsu SosiolinguistikKhairullah AffaroukBelum ada peringkat
- RETORIKDokumen16 halamanRETORIKFawwaz SulhiBelum ada peringkat
- Perubahan Makna Dalam Bahasa MelayuDokumen3 halamanPerubahan Makna Dalam Bahasa MelayuAMYLIA ANNABelum ada peringkat
- Definisi Sosiolinguistik Dan Sosiologi BahasaDokumen1 halamanDefinisi Sosiolinguistik Dan Sosiologi BahasaAlmon BantinBelum ada peringkat
- Definisi Genre SasteraDokumen5 halamanDefinisi Genre SasteraNaziha SanusiBelum ada peringkat
- Karya Saduran Dan Karya AsliDokumen10 halamanKarya Saduran Dan Karya AsliTora ToraBelum ada peringkat
- Analogi Dan QiyasDokumen3 halamanAnalogi Dan QiyasAliBinMuhammadAljufriBelum ada peringkat
- Berbahasa Berpikir Dan BerbudayaDokumen7 halamanBerbahasa Berpikir Dan BerbudayaRutzendBelum ada peringkat
- Usman AwangDokumen19 halamanUsman Awangmyuri5100% (2)
- ISIDokumen16 halamanISIDemimawati LaiaBelum ada peringkat
- Ciri-Ciri GurindamDokumen6 halamanCiri-Ciri GurindamNengahBelum ada peringkat
- PANTUNDokumen35 halamanPANTUNNur Syafiqah Noraslin100% (1)
- Assig SasteraDokumen28 halamanAssig SasteraazuraBelum ada peringkat
- Pantun BruneiDokumen9 halamanPantun BruneiMohd FaizanBelum ada peringkat
- AsigmentDokumen10 halamanAsigmentNor FaDyllaBelum ada peringkat
- Ukm 2005 4 (1-24)Dokumen25 halamanUkm 2005 4 (1-24)Ag Nordin AjamainBelum ada peringkat
- Metafora KonseptualDokumen2 halamanMetafora KonseptualRelina ElizabethBelum ada peringkat
- Makalah Sastra IndoesiaDokumen11 halamanMakalah Sastra IndoesiaDonny SittohangBelum ada peringkat
- Resume Buku Pengantar Teori Sastra (Tomi Hardiyanto)Dokumen46 halamanResume Buku Pengantar Teori Sastra (Tomi Hardiyanto)tomi hardiyanto100% (1)
- SEJARAH SASTRA INDONESIA DAN PERIODISASINYA Oleh FAJAR FITRIANTODokumen28 halamanSEJARAH SASTRA INDONESIA DAN PERIODISASINYA Oleh FAJAR FITRIANTOAsrBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah SastraDokumen12 halamanMakalah Sejarah SastraBatula SE100% (1)
- Makalah Sejarah SastraDokumen12 halamanMakalah Sejarah SastraPutra BangsawanBelum ada peringkat
- Benua Fix Kelas 9313Dokumen4 halamanBenua Fix Kelas 9313Liska SeptianaBelum ada peringkat
- RPP Daring Ipa KLS Vii RKDokumen1 halamanRPP Daring Ipa KLS Vii RKLiska SeptianaBelum ada peringkat
- Latihan Abk Modul 1Dokumen6 halamanLatihan Abk Modul 1Liska SeptianaBelum ada peringkat
- Silabus Daring Bahasa Inggris Kelas ViiDokumen5 halamanSilabus Daring Bahasa Inggris Kelas ViiLiska Septiana50% (2)
- Silabus Daring Ips Kelas 7.2Dokumen2 halamanSilabus Daring Ips Kelas 7.2Liska SeptianaBelum ada peringkat
- Tugas Formatif 3 Dan 4Dokumen2 halamanTugas Formatif 3 Dan 4Liska SeptianaBelum ada peringkat
- Silabus Daring Ips Kelas 7.1Dokumen3 halamanSilabus Daring Ips Kelas 7.1Liska SeptianaBelum ada peringkat
- Penerapan Model Pembelajaran ScrambleDokumen11 halamanPenerapan Model Pembelajaran ScrambleLiska SeptianaBelum ada peringkat