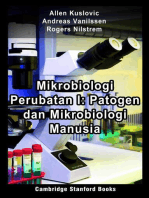Gontar
Gontar
Diunggah oleh
edi khoirumanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Gontar
Gontar
Diunggah oleh
edi khoirumanHak Cipta:
Format Tersedia
Universa Medicina
Vol.24 No.1
Penatalaksanaan non bedah dari karsinoma hati
Gontar A. Siregar
Divisi Gastrohepatologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK
Karsinoma hepatoseluler (KHS) atau hepatoma adalah kanker hati primer yang paling sering
dijumpai dan frekuensinya menunjukkan peningkatan di seluruh dunia. Sebab dari kenaikan insidens
KHS ini adalah karena penyebaran infeksi virus hepatitis di masyarakat. Dua jenis virus penyebab
tunmor ini adalah virus hepatitis B (HBV) dan virus hepatitis C (HCV). Distribusi global dari KHS
berkaitan dengan prevalensi geografis dari karier kronik HBV. Tingkat yang paling tinggi dijumpai
di Asia Tenggara dan sub-Sahara Afrika. Infeksi persisten dari HCV juga penting untuk terjadinya
KHS. Prognosis tumor ini buruk, survival rates-nya hanya di bawah 5 persen saja. Bila dapat
diidentifikasi pada saat dini, tumor ini mungkin masih dapat diobati dengan terapi radikal seperti
reseksi, transplantasi hati, atau ablasi lokal. Tindakan non-bedah yang meliputi di antaranya
kemoembolisasi, injeksi perkutan dan lain-lain teknik dapat diberikan kepada penderita-penderita
sementara menunggu agar tidak terjadi pembesaran tumor. Tindakan non-bedah juga terbukti sedikit
meningkatkan derajat survival.
Kata kunci : Karsinoma hepatoseluler, non-bedah, tatalaksana
Management of non surgical hepatocellular carcinoma
ABSTRACT
Hepatocellular carcinoma (HCC) or hepatoma is one of the most common primary cancer of
the liver and is occuring with increasing frequency in the world. The likely reason for the rising
incidence is the spread of hepatitis virus infection in the population. Two viruses cause this tumor
are hepatitis virus B (HBV) and hepatitis C virus (HCV). The global distribution of hepatocellular
carcinoma correlates with geographic prevalence of chronic carrier of HBV. The highest rates are
in Southeast Asia and sub-Sahara Africa. Persistent infection with HCV is also important for HCC.
Hepatocellular carcinoma has a poor prognosis with five-year survival rates less than 5 percent.When
identified at early stages of the disease, the tumor maybe curable by radical treatments such as
re s e c t i o n , l i v e r t r a n s p l a n t a t i o n , o r l o c a l a b l a t i o n . N o n s u rg i c a l t re a t m e n t s w h i c h i n c l u d e
chemoembolization, percutaneous injections, and other techniques may be applied to patients on
the waiting list to prevent tumor progression. These procedures has also shown to improve the survival
rates slightly.
Keywords: Hepatocellular carcinoma, nonsurgical, management
35
Siregar
PENDAHULUAN
Karsinoma hepatoseluler (KHS) adalah
salah satu jenis keganasan hati primer yang
paling sering ditemukan dan banyak
menyebabkan kematian. Dari seluruh
keganasan hati, 80-90% adalah KHS. (1) Dua
jenis virus yang dapat dikatakan menjadi
penyebab dari tumor ini adalah virus hepatitis
B (HBV) dan virus hepatitis C (HCV).
Distribusi global dari KHS berkaitan erat
dengan prevalensi geografis dari karier kronik
virus hepatitis B dan hepatitis C yang
mencapai 400 juta di seluruh dunia. (2) KHS
banyak ditemukan di Sub-Sahara Afrika,
Cina, Asia Tenggara, dan Jepang. Laki-laki
lebih banyak daripada wanita dengan
perbandingan 2-3 kali. Di antara mereka yang
mengalami infeksi HBV pada saat lahir, lakilaki diperkirakan memiliki risiko sebesar 50%
terhadap KHS sepanjang hidupnya, sedangkan
untuk wanita sebesar 20%. (2) Di negara-negara
tersebut di atas, derajat infeksi HBV berkisar
antara 10-25% dan menetap melalui transmisi
vertikal dari virus tersebut oleh ibu ke bayinya
atau oleh infeksi dari anak-anak di bawah 10
tahun melalui transmisi horisontal di dalam
keluarga. Dalam keadaan infeksi HBV yang
persisten ini, risiko terjadinya karsinoma
hepatoseluler meningkat 100 kali. (3) Infeksi
persisten dengan hepatitis C juga merupakan
faktor risiko untuk terjadinya KHS. Ada
sekitar 4 juta orang di Amerika Serikat yang
menderita infeksi HCV kronik. Virus ini
seringkali disebarkan secara parenteral pada
orang dewasa dan infeksi kronik terjadi pada
sekitar 80% orang-orang yang terpapar virus
tersebut. ( 4 ) Rute parenteral ini dijumpai
misalnya pada transfusi dan penyalah-gunaan
obat.
Di Amerika Serikat, insidens KHS
meningkat tajam dan hampir mencapai dua
kali dalam waktu 20 tahun terakhir ini. (3)
Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh
36
Non bedah karsinoma hati
karena adanya epidemi dari virus hepatitis C
yang dapat mengakibatkan sirosis dan KHS.
Sirosis karena virus hepatitis C merupakan
70% dari penyebab kasus-kasus KHS di
Jepang dan 30-50% di Amerika Serikat. (2)
Namun demikian, di Amerika Utara kasuskasus KHS terdapat pada sekitar 40%
penderita-penderita nonsirosis hati.
Karsinoma hati primer dibedakan atas
karsinoma yang berasal dari sel-sel hati
(KHS), karsinoma dari sel-sel saluran empedu
(karsinoma kolangioseluler), dan campuran
dari keduanya. Karsinoma juga dapat berasal
dari jaringan ikat hati seperti misalnya
fibrosarkoma hati. Secara makroskopis
karsinoma hati dapat dijumpai dalam bentuk
(i) masif yang biasanya di lobus kanan,
berbatas tegas, dapat disertai nodul-nodul
kecil di sekitar masa tumor dan bisa dengan
atau tanpa sirosis; (ii) noduler, dengan nodul
di seluruh hati, (iii) difus, seluruh hati terisi
sel tumor. Secara mikroskopis, sel-sel tumor
biasanya lebih kecil dari sel hati yang normal,
berbentuk poligonal dengan sitoplasma
granuler. Sering ditemukan sel raksasa yang
atipik. Dalam kaitan dengan tumor ganas ini,
optimisasi penanganan KHS merupakan suatu
tantangan besar bagi dokter karena frekuensi
KHS yang meningkat tajam pada tahun-tahun
terakhir ini.
PATOGENSIS DAN GAMBARAN KLINIS
Beberapa faktor patogenesis karsinoma
hepatoseluler telah didefinisikan baru-baru
ini. Hampir semua tumor di hati berada dalam
konteks kejadian cedera kronik (chronic
injury) dari sel hati, peradangan dan
meningkatnya kecepatan perubahan hepatosit.
Respons regeneratif yang terjadi dan adanya
fibrosis menyebabkan timbulnya sirosis, yang
kemudian diikuti oleh mutasi pada hepatosit
dan berkembang menjadi karsinoma
hepatoseluler. HBV atau HCV mungkin ikut
Universa Medicina
terlibat di dalam berbagai tahapan proses
onkogenik ini. Misalnya, infeksi persisten
dengan virus menimbulkan inflamasi,
meningkatkan
perubahan
sel,
dan
menyebabkan sirosis. Sirosis selalu didahului
oleh beberapa perubahan patologis yang
reversibel, termasuk steatosis dan inflamasi;
baru kemudian timbul suatu fibrosis yang
ireversibel dan regenerasi nodul. Lesi noduler
diklasifikasikan sebagai regeneratif dan
displastik atau neoplastik. (5) Nodul regeneratif
merupakan parenkim hepatik yang membesar
sebagai respons terhadap nekrosis dan
dikelilingi oleh septa fibrosis.
Selain proses di atas, pada waktu periode
panjang yang tipikal dari infeksi (10-40
tahun), genom virus hepatitis dapat
berintegrasi ke dalam kromosom hepatosit.
Peristiwa ini menyebabkan ketidakseimbangan (instability) genomik sebagai
akibat dari mutasi, delisi, translokasi, dan
penyusunan kembali (rearrangements) pada
berbagai tempat di mana genom virus secara
acak masuk ke dalam DNA hepatosit. Salah
satu produk gen, protein x HBV (Hbx),
mengaktifkan transkripsi, dan pada periode
infeksi kronik, produk ini meningkatkan
ekspresi gen pengatur pertumbuhan (growthregulating genes) yang ikut terlibat di dalam
transformasi malignan dari hepatosit. (6)
Gambaran klinis berupa rasa nyeri
tumpul umumnya dirasakan oleh penderita dan
mengenai perut bagian kanan atas, di
epigastrium atau pada kedua tempat
epigastrium dan hipokondrium kanan. Rasa
nyeri tersebut tidak berkurang dengan
pengobatan apapun juga. Nyeri yang terjadi
terus menerus sering menjadi lebih hebat bila
b e rg e r a k . N y e r i t e r j a d i s e b a g a i a k i b a t
pembesaran hati, peregangan glison dan
rangsangan peritoneum. Terdapat benjolan di
daerah perut bagian kanan atas atau di
epigastrium. Perut membesar karena adanya
asites yang disebabkan oleh sirosis atau
Vol.24 No.1
karena adanya penyebaran karsinoma hati ke
peritoneum.
Umumnya terdapat keluhan mual dan
muntah, perut terasa penuh, nafsu makan
berkurang dan berat badan menurun dengan
cepat. Yang paling penting dari manifestasi
klinis sirosis adalah gejala-gejala yang
berkaitan dengan terjadinya hipertensi portal
yang meliputi asites, perdarahan karena
varises esofagus, dan ensefalopati. (7)
DIAGNOSIS
Untuk menegakkan diagnosis karsinoma
hati diperlukan beberapa pemeriksaan seperti
misalnya
pemeriksaan
radiologi,
ultrasonografi, computerized tomography
(CT) scan, peritoneoskopi dan pemeriksaan
laboratorium. Deteksi lesi noduler hati dengan
imaging tergantung pada perbedaan yang
kontras antara parenkim hati normal dan lesi
noduler. Adanya fibrosis dapat mempengaruhi
sensitivitas dari modalitas imaging sehingga
dapat mengganggu deteksi dan karakterisasi
tumor hati. (8)
Ultrasonografi
Dengan ultrasonografi, gambaran khas
dari KHS adalah pola mosaik, sonolusensi
perifer, bayangan lateral yang disebabkan
pseudokapsul fibrotik, dan peningkatan
akustik posterior. (5) KHS yang masih berupa
nodul kecil cenderung bersifat homogen dan
hipoekoik, sedangkan nodul yang besar
biasanya
heterogen.
Penggunaan
ultrasonografi sebagai sarana screening untuk
mendeteksi tumor hati pada penderita dengan
sirosis yang lanjut memberikan hasil bahwa
34 dari 80 penderita yang diperiksa
menunjukkan tanda-tanda tumor ganas dan 28
di antaranya adalah KHS. (5) Ultrasonografi
memberikan sensitivitas sebesar 45% dan
spesifisitas 98%.( 5) Oleh karena sensitivitas
tes ini maka setiap massa yang terdeteksi oleh
37
Siregar
ultrasonografi harus dianggap sebagai
k e g a n a s a n . (5) K a r s i n o m a h a t i s e k u n d e r
memberikan gambaran berupa nodul yang
diameternya kecil mempunyai densitas tinggi
dan dikelilingi oleh gema berdensitas rendah.
Gambaran ini berbentuk seperti mata sapi.
CT-scan dan angiografi
KHS dapat bermanifestasi sebagai massa
yang soliter, massa yang dominan dengan lesi
satelit di sekelilingnya, massa multifokal, atau
suatu infltrasi neoplasma yang sifatnya difus.
C T -s c a n t e l a h b a n y a k d i g u n a k a n u n t u k
melakukan karakterisasi lebih lanjut dari
tumor hati yang dideteksi melalui
ultrasonografi. CT-scan dan angiografi dapat
mendeteksi tumor hati yang berdiameter 2 cm.
Walaupun ultrasonografi lebih sensitif dari
angiografi dalam mendeteksi karsinoma hati,
tetapi angiografi dapat lebih memberikan
kepastian diagnostik oleh karena adanya
hipervaskularisasi tumor yang tampak pada
angiografi. Dengan media kontras lipoidol
yang disuntikkan ke dalam arteria hepatika,
zat kontras ini dapat masuk ke dalam nodul
tumor hati. Dengan melakukan arteriografi
yang dilanjutkan dengan CT-scan, ketepatan
diagnostik tumor akan menjadi lebih tinggi.
MR imaging
M a g n e t i c re s o n a n c e ( M R ) i m a g i n g
umum digunakan secara rutin untuk screening
penderita-penderita dengan sirosis. Pada studi
yang dilakukan oleh Krinsky dkk (8) menguji
sensitivitas dan spesifisitas dari sarana tes ini
untuk KHS dan nodul displastik pada sirosis
hati. Hasil studi menunjukkan sensitivitas
untuk diagnosis KHS dilaporkan hanya
sebesar 53% saja. Hal ini disebabkan karena
lesi-lesi yang tidak terdeteksi tersebut
kebanyakan mempunyai diameter kecil yaitu
rata-rata 1,3 cm. Sebaliknya, nodul displastik
38
Non bedah karsinoma hati
derajat tinggi meskipun dapat dideteksi namun
terdiagnosis sebagai KHS karena adanya
arterial phase enhancement. Dengan
demikian, diperlukan kriteria lain selain
arterial phase enhancement untuk
membedakan nodul displastik dari KHS yang
kecil.
Biopsi
Untuk pemastian diagnosis karsinoma
hati, diperlukan biopsi dan pemeriksaan
histopatologi. Biopasi dilakukan terhadap
massa yang terlihat pada ultrasonografi, CTscan atau melalui angiografi. Biopsi aspirasi
jarum halus dapat dilakukan secara buta
(blind). Ada kalanya dibutuhkan tindakan
laparoskopi atau laparatomi untuk melakukan
biopsi.
Uji faal hati
Karsinoma hati dapat menyebabkan
terjadinya obstruksi saluran empedu atau
merusak sel-sel hati oleh karena penekanan
massa tumor atau karena invasi sel tumor
hingga terjadi gangguan hati yang tampak
pada kelainan SGOT, SGPT, alkali fosfatase,
laktat dehidrogenase. Gangguan faal hati ini
tidak spesifik sebagai petanda tumor. Alfafetoprotein (AFP) adalah suatu glikoprotein
dengan berat molekul sebesar 70,000. AFP
disintesis oleh hati, usus dan yolk sac janin.
Pada manusia, AFP mulai terdeteksi pada
fetus umur 6-7 minggu kehamilan dan
mencapai puncaknya pada minggu ke-13. Pada
bayi yang baru lahir, kadarnya adalah sebesar
10,000 - 100,000 ng/ml, kemudian menurun
dan pada usia 250-300 hari kelahiran
kadarnya sama dengan kadar pada orang
dewasa. Adanya peningkatan kadar AFP
diduga karena sel-sel hati mengalami
diferensiasi menyerupai sel hati pada janin.
AFP merupakan petanda karsinoma hati.
Universa Medicina
PENATALAKSANAAN
Banyak faktor memegang peranan dalam
penanganan KHS. Pertama, adanya sirosis
hati dalam berbagai tingkatan yang mengikuti
KHS sedikit banyak mempengaruhi pilihanpilihan pengobatan. ( 1 0 ) F u n g s i h a t i p a d a
penderita-penderita KHS dapat sangat
bervariasi dari normal sampai dekompensasi.
Sirosis dapat dijumpai pada sekitar 90% dari
s e m u a k a s u s K H S . ( 11 ) K e d u a , K H S
menunjukkan perangai biologis yang sangat
bervariasi dari satu daerah dan daerah yang
lain. Misalnya, di daerah pedesaan Afrika
Selatan, KHS mengenai penderita-penderita
dalam usia yang lebih muda dan sering baru
terdiagnosis setelah tahap lanjut dan
mempunyai durasi gejala-gejala yang lebih
singkat dibanding kasus-kasus di Amerika
Utara. (10) Manifestasi klinis pada penderitapenderita ini didominasi oleh gejala-gejala
yang disebabkan oleh tumornya sedangkan di
Amerika Utara gejala-gejala sirosis tampil
secara dominan dalam waktu yang lama. Oleh
karena itu, protokol pengobatan yang
dikembangkan di suatu daerah atau negara
mungkin tidak sesuai dan tidak optimal untuk
daerah lainnya.
Secara umum, tatalaksana bedah
(surgical management) seperti reseksi dan
transplantasi dianggap pengobatan yang ideal
untuk KHS. Kemajuan teknik bedah dan
perawatan perioperatif telah mampu untuk
menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat
operasi, bahkan pada penderita-penderita
sirosis. Dengan seleksi yang baik terhadap
penderita-penderita, 5-year survival rate
pasca-reseksi dilaporkan dapat mencapai
sedikitnya 35%. (12) Namun demikian, 70% dari
penderita-penderita ini mengalami rekurensi
setelah reseksi kuratif ini, biasanya antara
18-24 bulan. (12)
Vol.24 No.1
Meskipun
penanganan
terhadap
karsinoma hepatoseluler secara operatif
dianggap ideal, tetapi banyak kesulitan
dijumpai karena penderita-penderita umumnya
datang pada stadium yang sudah lanjut
sehingga tidak dapat dilakukan reseksi dan
transplantasi. Selain itu, biaya operasi yang
mahal, pemberian imunosupresi sepanjang
hidup serta sulitnya mendapatkan donor
transplantasi merupakan suatu kendala yang
besar terutama di negara-negara berkembang.
Oleh karena itu, yang paling baik adalah
melakukan usaha-usaha pencegahan, terutama
pencegahan terhadap penularan virus hepatitis
dan bila telah terjadi infeksi, mencegah
kemungkinan terjadinya sirosis postnecrotic
sehingga dapat dicegah terjadinya karsinoma
hati.
Pengobatan non-bedah
Meskipun pendekatan multidispliner
terhadap KHS dapat meningkatkan hasil
reseksi dan orthotopic liver transplantation,
tetapi kebanyakan penderita tidak memenuhi
persyaratan untuk terapi operasi karena
stadium tumor yang telah lanjut, derajat
sirosis yang berat, atau keduanya. Oleh karena
itu, terapi non-bedah merupakan pilihan untuk
pengobatan penyakit ini. Beberapa alternatif
pengobatan non-bedah karsinoma hati
meliputi:
a.
Percutaneous ethanol injection (PEI)
PEI pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1986. (11) Teknik terapi PEI dilaporkan
memberikan hasil sebaik reseksi untuk KHS
yang kecil. Kerugian dari cara ini adalah
tingkat rekurensi lokal yang tinggi dan
kebutuhan akan sesi terapi berulang kali
(multipel) agar didapatkan ablasi lengkap dari
l e s i . (10) P E I d i l a k u k a n d e n g a n c a r a
menyuntikkan per kutan etanol murni (95%)
39
Siregar
ke dalam tumor dengan panduan radiologis
untuk mendapatkan efek nekrosis dari tumor.
Tindakan ini efektif untuk tumor berukuran
kecil (<3 cm). Untuk penderita-penderita
dengan asites, koagulopati sedang atau berat
dan lesi permukaan, PEI tidak dianjurkan.
Efek PEI adalah demam, sakit di daerah
suntikan, perdarahan intrahepatik dan
perdarahan peritoneal.
b.
Chemoembolism
Transcatheter arterial chemoembolism
dapat digunakan sebagai terapi lokal (targeted
chemoembolism) atau regional (segmental,
l o b a r c h e m o e m b o l i s m ) t e rg a n t u n g d a r i
ukuran, jumlah dan distribusi lesi.
Kemoembolisme dianggap terapi baku untuk
KHS yang tidak dapat dilakukan reseksi.
Lipoidol diberikan dengan obat kemoterapi
yang kemudian akan terkonsentrasi di dalam
sel tumor tetapi secara aktif dibersihkan dari
sel-sel yang non-maligna. Pada cara ini,
terjadi devaskularisasi terhadap tumor
sehingga menghentikan suplai nutrisi dan
oksigen ke jaringan tumor dan mengakibatkan
terjadinya
nekrosis
tumor
akibat
vasokonstriksi arteri hepatika. Dengan teknik
ini didapatkan respon yang lebih baik
dibandingkan kemoterapi arterial atau
sistemik. Selain lipoidol dapat juga digunakan
gelfoam dan kolagen. Efek samping yang
sering terjadi antara lain adalah demam,
nausea, vomitus, sakit di daerah abdominal.
Kemoembolisasi pada penderita-penderita
dengan karsinoma hepatoseluler yang tidak
dapat direseksi dilaporkan menunjukkan
reduksi dari pertumbuhan tumor tetapi tidak
memberikan peningkatan survival. Efikasi
yang terbatas dari kemoembolisasi pada
penderita KHS dengan tumor yang besar dan
tidak dapat direseksi dapat dijelaskan oleh
adanya sel-sel tumor yang tetap hidup setelah
terapi, terutama dengan adanya invasi
40
Non bedah karsinoma hati
vaskuler, adanya anak nodul kecil-kecil, dan
adanya trombi tumor. Kemoembolisasi efektif
untuk tumor kecil tunggal dengan
hipervaskularisasi. Respons yang lebih besar
dan derajat survival yang lebih tinggi
diperoleh bilamana kemoembolism diikuti
dengan PEI. (11)
c.
Kemoterapi sistemik
Pemberian terapi dengan anti-tumor
ternyata dapat memperpanjang hidup
penderita. Sitostatika yang sering dipakai
sampai saat ini adalah 5-fluoro uracil (5-FU).
Zat ini dapat diberikan secara sistematik atau
secara lokal (intra-arteri). Sitostatika lain
yang sering digunakan adalah adriamisin
(doxorubicin HCl) atau adriblastina. Dosis
yang diberikan adalah 60-70 mg/m 2 luas badan
yang diberikan secara intra-vena setiap 3
minggu sekali atau dapat juga diberikan
dengan dosis 20-25 mg/m 2 luas badan selama
3 hari berturut-turut dan diberikan setiap 3
minggu sekali. Adriamisin sebagai obat
tunggal sangat efektif dengan peningkatan
survival rate sebesar 25% dibandingkan bila
tidak diberi terapi. Penggunaan kombinasi
sisplatin, IFN-2B, adriamisin dan 5-FU yang
diberikan secara sistematik pada penderita
KHS memberikan rerspon yang sangat baik
untuk tumor hati dan ekstrahepatik. Dengan
rejimen seperti ini ternyata 18% penderita
yang awalnya tidak dapat dieseksi dapat
direseksi dan 50% menunjukkan remisi
histologis yang sempurna. Namun demikian,
kombinasi di atas tidak dapat ditoleransi
penderita-penderita sirosis lanjut.
d.
Kemoterapi intra-arterial
(transcatheter arterial chemotherapy)
Pengobatan karsinoma hati dengan
sitostatika ternyata kurang memberikan
manfaat yang diharapkan. Respon parsial
hanya mencapai 25% saja. Pemberian 5-FU
Universa Medicina
ternyata tidak memperpanjang usia penderita.
Oleh karenanya diberikan sitostatika secara
intra-arterial dengan beberapa keuntungan
seperti misalnya, konsentrasi sitostatika lebih
t i n g g i p a d a t a rg e t ( t u m o r ) , m e n g u r a n g i
toksisitas sistemik dan kontak antara obat
dengan tumor berlangsung lebih lama. Pada
teknik ini kateter dimasukkan per kutaneus ke
dalam arteri brachialis atau a. femoralis atau
melalui laparotomi ke arteri hepatika,
kemudian obat sitostatika disuntikkan secara
perlahan-lahan selama 10-30 menit.
Sitostatika yang disuntikkan adalah mitomisin
C 10-20 mg dikombinasikan dengan
adriablastiina 10-20 mg dicampur dengan 100200 ml larutan garam faal. Pemberian
sitostatika diulang satu bulan kemudian
sambil mengevaluasi hasil pengobatan
sebelumnya. Efek samping dari cara
pengobatan di atas tersebut dapat berupa
demam, septikemia, perdarahan, trombosis,
emboli udara. Kontraindikasi dari kemoterapi
intra-arterial adalah kaheksia, asites yang
intraktabel, dan gangguan faal hati berat.
e.
Radiasi
Terapi radiasi jarang digunakan sebagai
terapi tunggal dan tidak banyak perannya
sebab karsinoma hati tidak sensitif terhadap
radiasi dan sel-sel hati yang normal sangat
peka terhadap radiasi. Terapi radiasi dengan
menggunakan 50 Gy untuk membunuh sel-sel
kanker hati dapat menyebabkan radiation
induced hepatitis. Dosis yang diberikan
umumnya berkisar antara 30-35 Gy dan
diberikan selama 3-4 minggu. Meskipun
demikian, penderita biasanya meninggal dalam
kurun waktu 6 bulan. karena survival-nya
pendek. Teknik baru yang dengan proton
therapy adalah teknik yang menggunakan
partikel bermuatan positif untuk menghantar
energi membunuh sel-sel tumor dengan cedera
minimal pada jaringan hati yang nonneoplastik. Dengan proton therapy dosis 70-
Vol.24 No.1
80 Gy sangat aman karena sel target adalah
h a n y a s e l t u m o r. U k u r a n t u m o r d a p a t
berkurang sampai 50% dari sebelumnya, dan
efek samping yang terjadi sangat minimal
sehingga memberikan kualitas hidup yang
lebih baik.
f.
Tamofixen
Tamofixen digunakan pada penderitapenderita KHS dengan sirosis lanjut, tetapi
tidak meningkatkan survival. Tamofixen dapat
dikombinasikan dengan etoposide dan
menunjukkan perbaikan serta memberikan
toksisitas rendah dan bermanfaat sebagai
terapi paliatif. Secara in vitro, tamofixen
bermakna meningkatkan efek sitotoksik
doxorubisin pada KHS. Kombinasi antara
tamofixen dengan doxorubisin ternyata tidak
memberikan hasil yang lebih baik
dibandingkan dengan tamofixen tunggal.
g.
Injeksi asam asetat perkutaneus
Prinsip dan cara kerja metode ini sama
dengan injeksi etanol perkutan, hanya saja zat
yang disuntikkan adalah larutan asam asetat
15-50%. Pemberian pada penderita KHS
dengan tumor yang berdiameter <3 cm
menunjukkan survival rate 1 tahun sebesar
93%, 2 tahun sebesar 86%, 3 tahun sebesar
83% dan 4 tahun sebesar 64%. Efek samping
tidak dijumpai.
PROGNOSIS
Pada umumnya prognosis karsinoma hati
adalah jelek. (1,6) Tanpa pengobatan, kematian
rata-rata terjadi sesudah 6-7 bulan setelah
timbul keluhan pertama. Dengan pengobatan,
hidup penderita dapat diperpanjang sekitar 1112 bulan. Bila karsinoma hati dapat dideteksi
secara dini, usaha-usaha pengobatan seperti
pembedahan dapat segera dilakukan misalnya
dengan cara sub-segmenektomi, maka masa
hidup penderita dapat menjadi lebih panjang
41
Siregar
lagi. Sebaliknya, penderita karsinoma hati
fase lanjut mempunyai masa hidup yang lebih
singkat. Kematian umumnya disebabkan oleh
karena koma hepatik, hematemesis dan
melena, syok yang sebelumnya didahului
dengan rasa sakit hebat karena pecahnya
karsinoma hati. Oleh karena itu langkahlangkah terhadap pencegahan karsinoma hati
haruslah dilakukan. Pencegahan yang paling
utama adalah menghindarkan infeksi terhadap
HBV dan HCV serta menghindari konsumsi
alkohol untuk mencegah terjadinya sirosis.
KESIMPULAN
Karsinoma hati adalah penyakit yang
sulit diobati dan disembuhkan. Apabila
ditemukan, biasanya prognosisnya kurang
baik. Beberapa upaya pengobatan, baik secara
bedah maupun non-bedah, telah banyak
diteliti, namun hasilnya masih tidak
memuaskan. Upaya pengobatan non-bedah
efektif sebagai pengendalian sementara
terhadap penyebaran penyakit pada penderitapenderita karsinoma hepatoseluler yang kecil
tetapi tidak dapat dilakukan reseksi. Juga pada
penderita karsinoma yang sudah lanjut. Pada
penderita tumor yang besar yang tidak dapat
direseksi, teknik-teknik yang dapat
menyebabkan nekrosis tumor secara lengkap
melalui kombinasi kemoembolisasi dan PEI
mungkin dapat memberikan survival penyakit
yang lebih panjang.
Daftar Pustaka
1.
42
Di Bisceglie AM. Hepatitis C and
hepatocellular carcinoma. Hepatoloy 1997;
26:S34-S8.
Non bedah karsinoma hati
2.
Ince N, Wanda JR. The increasing incidence
of hepatocellular carcinoma. N Engl J Med
1999;340:798-9.
3. El-Serag HB, Mason AC. Rising incidence
of hepatocellular carcinoma in the United
States. N Engl J Med 1999;340:745-50.
4. Heintges T, Wands JR. Hepatitis C virus:
epidemiology and transmission. Hepatology
1997;26:521-6.
5. Kamel IR, Bluemke DA. Imaging evaluation
of hepatocellular carcinoma. J Vasc Interv
Radiol 2002;13:S73-S83.
6. Wu CG, Salvay DM, Forgues M, Valerie K,
Farnsworth J, Markin RS, et al. Distinctive
gene expression profiles associated with
Hepatitis B virus x protein. Oncogene 2001;
20:3674-82.
7. Okuda K. Hepatocellular carcinoma. J Hepat
2000; 32:S225-S7.
8. Kim TK, Kim AY, Choi BI. Hepatocellular
carcinoma: harmonic ultrasound and
contrast agent. Abdom Imaging 2002;
27:129-38.
9. Krinsky GA, Lee VS, Theise ND, Weinreb
J C , M o rg a n G R , D i f l o T, e t a l .
Hepatocellular carcinoma and dysplatic
nodules in patients with cirrhosis:
prospective diagnosis with MR imaging and
explantation correlation. Radiology 2001;
219:445-54.
10. Rilling WS, Drooz A. Multidisciplinary
management of hepatocellular carcinoma. J
Vasc Interv Radiol 2002;13:S259-S63.
11. Mor E, Kaspa RT, Sheiner P. Treatment of
hepatocellular carcinoma associated with
cirrhosis in the era of liver transplantation.
Ann Intern Med 1998;129:643-53.
12. Lai ECS, Fan ST, Lo CM, Chu KM, Liu CL,
Wo n g J . H e p a t i c r e s e c t i o n f o r h e p a t i c
cellular carcinoma: an audit of 343 patients.
Ann Surg 1995;221:291-8.
Anda mungkin juga menyukai
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Case - Intoksikasi JengkolDokumen46 halamanCase - Intoksikasi JengkolDevi Eliani Chandra100% (1)
- Referat HepatomaDokumen17 halamanReferat HepatomaKurnia Fitri Aprilliana100% (1)
- Askep HepatomaDokumen32 halamanAskep HepatomaSherlie50% (2)
- LP HepatomaDokumen21 halamanLP Hepatomaance ndapaole100% (3)
- Referat CA HeparDokumen35 halamanReferat CA HeparNurul AprilianiBelum ada peringkat
- Hepatocellular Carcinoma (HCC)Dokumen18 halamanHepatocellular Carcinoma (HCC)taufik.abdi75% (4)
- HCC (Karsinoma Hepar)Dokumen5 halamanHCC (Karsinoma Hepar)Danar Fahmi SudarsonoBelum ada peringkat
- Referat HCCDokumen24 halamanReferat HCCMohamad FachryBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Dan Asuhan Keperawatan HepatomaDokumen21 halamanLaporan Pendahuluan Dan Asuhan Keperawatan HepatomaNindia Setyaningrum100% (2)
- LP HCC (Rusmiati)Dokumen22 halamanLP HCC (Rusmiati)RusmiatiBelum ada peringkat
- Karsinoma HepatoselulerDokumen57 halamanKarsinoma HepatoselulerRhisa OvianiBelum ada peringkat
- Askep Hcc. Sukses Amiin Ya AllahDokumen18 halamanAskep Hcc. Sukses Amiin Ya AllahLutfi AssidiqiBelum ada peringkat
- Referat Karsinoma HepatoselulerDokumen17 halamanReferat Karsinoma Hepatoselulerrizki faujiah munandarBelum ada peringkat
- HCCDokumen21 halamanHCCAfik MauLana RachmanBelum ada peringkat
- Referat HepatomaDokumen20 halamanReferat HepatomaNurulAttikaBelum ada peringkat
- LAPORAN PENDAHULUAN HCC (Hepatoma)Dokumen20 halamanLAPORAN PENDAHULUAN HCC (Hepatoma)ulya islamiyahBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen24 halamanLP HepatomafadliBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen16 halamanLP HepatomaRizka Yunita91% (11)
- Referat HepatomaDokumen32 halamanReferat Hepatomatitin damayantiBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan HepatomaDokumen24 halamanLaporan Pendahuluan HepatomaTiwi Dewi WulanBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen21 halamanLP HepatomaMarnia SulfianaBelum ada peringkat
- Konsep Dasar Penyakit HepatomaDokumen23 halamanKonsep Dasar Penyakit HepatomaTrisa Bea BeoBelum ada peringkat
- Kasus HepatomaDokumen56 halamanKasus HepatomaElvhyn WikaBelum ada peringkat
- CRS - Karsinoma Hepatoseluler FuadDokumen25 halamanCRS - Karsinoma Hepatoseluler Fuadgladian yanuriskaBelum ada peringkat
- HEPATOMADokumen18 halamanHEPATOMADesy IndrawatiBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen17 halamanLP HepatomaGabi CeriaBelum ada peringkat
- LP HCCDokumen20 halamanLP HCCSony AnggenBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan HEPATOCELLULAR CARCINOMADokumen20 halamanLaporan Pendahuluan HEPATOCELLULAR CARCINOMADickyCoyBelum ada peringkat
- Kelompol 5 HEPATOMADokumen40 halamanKelompol 5 HEPATOMAulfamuzliyatiBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen30 halamanLP Hepatomaecce alikgeroriBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen17 halamanLP HepatomaradanikmaBelum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen26 halamanLP HepatomaThyas Agustina HBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Hepatoceluler Cersinoma (HCC) : Infeksi KronikDokumen26 halamanLaporan Pendahuluan Hepatoceluler Cersinoma (HCC) : Infeksi KronikRizkhy WahyuBelum ada peringkat
- HCCDokumen2 halamanHCCdian_rahayu_8Belum ada peringkat
- LP HepatomaDokumen23 halamanLP HepatomaLuh Putu Ardani100% (1)
- Referat HepatomaDokumen20 halamanReferat HepatomadeaBelum ada peringkat
- HepatomaDokumen33 halamanHepatomaAisyah RahmadillahBelum ada peringkat
- Referat HepatomaDokumen26 halamanReferat HepatomagilangBelum ada peringkat
- Skenario 2 Blok Neoplasia Karsinoma HepatoselulerDokumen15 halamanSkenario 2 Blok Neoplasia Karsinoma Hepatoselulerayukartikautami93Belum ada peringkat
- Presentasi Kasus HepatomaDokumen28 halamanPresentasi Kasus HepatomaAnggi PrasetyoBelum ada peringkat
- HepatomaDokumen56 halamanHepatomaChristian Lumban GaolBelum ada peringkat
- LK HepatomaDokumen29 halamanLK HepatomaaisyahBelum ada peringkat
- He Pa To MaDokumen9 halamanHe Pa To MaPascallindaTheniaBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan KMB HepatomaDokumen15 halamanLaporan Pendahuluan KMB HepatomaFarhanahBelum ada peringkat
- Hepatoma 1Dokumen22 halamanHepatoma 1Rahmah 'aisBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan HCCDokumen5 halamanLaporan Pendahuluan HCCerinBelum ada peringkat
- Askep Hepatoma Kelompok 3Dokumen23 halamanAskep Hepatoma Kelompok 3Laksmi Sri WardanaBelum ada peringkat
- HepatomaDokumen20 halamanHepatomavorez100% (1)
- ASUHAN KEPERAWATAN Kolorektal Prisdi SetiawanDokumen10 halamanASUHAN KEPERAWATAN Kolorektal Prisdi SetiawanPrisdi ProssBelum ada peringkat
- Referat Karsinoma Hepatoseluler IDokumen7 halamanReferat Karsinoma Hepatoseluler IDDMBelum ada peringkat
- Kanker HatiDokumen9 halamanKanker HatiEga Friesa YudhanaBelum ada peringkat
- Askep HepatomaDokumen16 halamanAskep HepatomarossiBelum ada peringkat
- 1 Laporan Kasus HepatomaDokumen34 halaman1 Laporan Kasus HepatomaKrisna Dwi SaputraBelum ada peringkat
- Lapsus Ahmad Fauzan ArifaniDokumen52 halamanLapsus Ahmad Fauzan ArifaniahmdfauzannBelum ada peringkat
- LP HepatoblastomaDokumen9 halamanLP HepatoblastomaWIJAYANTI WULANDARIBelum ada peringkat
- Karsinoma HatiDokumen2 halamanKarsinoma HatiFajri NugrahaBelum ada peringkat
- REFERAT Evaluasi Postop KatarakDokumen19 halamanREFERAT Evaluasi Postop KatarakDevi Eliani ChandraBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Ensefalitis TBDokumen39 halamanLaporan Kasus Ensefalitis TBDevi Eliani ChandraBelum ada peringkat
- Soal Obgyn Kelompok Bedah OnkologiDokumen7 halamanSoal Obgyn Kelompok Bedah OnkologiDevi Eliani ChandraBelum ada peringkat
- Keracunan Jengkol, Jengkol AcidDokumen6 halamanKeracunan Jengkol, Jengkol AcidDevi Eliani ChandraBelum ada peringkat
- Plant Survey-UkridaDokumen3 halamanPlant Survey-UkridaDevi Eliani ChandraBelum ada peringkat