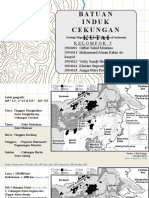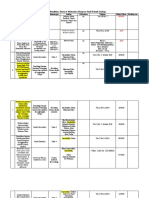Rangkuman Geokimia PDF
Rangkuman Geokimia PDF
Diunggah oleh
Miftakhul UlumuddinJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Rangkuman Geokimia PDF
Rangkuman Geokimia PDF
Diunggah oleh
Miftakhul UlumuddinHak Cipta:
Format Tersedia
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
KARAKTERISASI POTENSI BATUAN INDUK HIDROKARBON BERDASARKAN
ANALISIS GEOKIMIA MATERIAL ORGANIK SUMUR JMB, SUB-CEKUNGAN
JAMBI, CEKUNGAN SUMATRA SELATAN
Jamaluddin1*, Maria2, Hamriani Ryka1
1
Departemen Teknik Geologi, STT-Migas Balikpapan
2
Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,Universitas Hasanuddin
*
Email: jamaljamaluddin1994@gmail.com
Abstrak
Karakterisasi batuan induk di sumur JMB, sub-Cekungan Jambi sangat penting dilakukan dalam
eksplorasi hidrokarbon karena akan memberikan informasi berupa potensi batuan induk untuk
menghasilkan hidrokarbon, jenis hidrokarbon yang dihasilkan dan kondisi cekungan hidrokarbon.
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi batuan induk adalah
analisis geokimia material organik berupa kandungan karbon organik (TOC), pirolisis rock-eval
dan reflektansi vitrinit (Ro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, kuantitas
material organik, tipe material organik dan tingkat kematangan material batuan induk
berdasarkan hasil uji TOC dan pirolisis rock-eval. Berdasarkan hasil dari analisa kekayaan
material organik sebanyak 40 sampel menunjukkan nilai TOC berkisar antara 0.96-7.27% wt.
yang diinterpretasikan sebagai batuan dengan kekayaan material organik yang berpotensi baik
sampai sangat baik. Plot antara Tmaks dan indeks hydrogen (HI) menunjukkan sumur JMB
memiliki kerogen tipe III yang cenderung menghasilkan gas serta berada dalam tahap belum
matang hingga matang dengan Ro 0.16-1.22. Berdasarkan analisis geokimia material organik
pada sumur JMB, batuan induk pada Formasi Lahat, Formasi Talang Akar dan Formasi Gumai
merupakan batuan induk yang berpotensi menghasilkan hidrokarbon pada daerah tersebut.
Kata kunci: Batuan Induk, Geokimia, Hidrokarbon, Karakterisasi, Sub-Cekungan Jambi.
1. PENDAHULUAN
Sub-Cekungan Jambi merupakan salah satu Sub-Cekungan Sumatra Selatan yang merupakan
cekungan busur belakang (back arc basin) berumur Tersier yang terbentuk akibat adanya tumbukan
antara Sundaland dan Lempeng Hindia. Secara geografis Sub-Cekungan Jambi dibatasi oleh
Pegunungan Tigapuluh di sebelah Utara, Pegunungan Duabelas dan Tinggian Tamiang di bagian
selatan, Paparan sunda di sebelah timur, dan Bukit barisan di sebelah barat. Sub-cekungan ini
terbentuk hampir segiempat memanjang (sub-rectangular) yang berarah baratlaut-tenggara (Bishop,
2001).
Menurut Mirzani (2011), Sub-Cekungan Jambi memiliki potensi besar dalam menghasilkan
hidrokarbon dengan rasio kesuksesan 51% namun belum dieksplorasi secara intensif. Sub-Cekungan
Jambi telah terbukti sebagai cekungan produktif dengan beberapa formasi yang sangat berpotensi
sebagai penghasil hidrokarbon mulai dari Formasi Air Benakat, Gumai hingga Talang Akar.
Kemunculan hidrokarbon di Sub-Cekungan Jambi tidak terlepas dari pengaruh batuan induk yang
berpotensi atau mampu menggenerasikan hidrokarbon.
Batuan induk adalah salah satu parameter yang terpenting dalam petroleum system yang
berfungsi sebagai penghasil hidrokarbon atau batuan sumber. Beberapa peneliti bahkan menempatkan
batuan induk sebagai prioritas nomor satu yang harus ada dalam petroleum system (Magoon dan Dow,
1994). Batuan induk umumnya berukuran butir halus dan disusun oleh material klastik, karbonat, dan
karbon organik. Kandungan material karbon organik inilah yang secara langsung mempengaruhi
kualitas suatu batuan induk. Semakin tinggi kandungan organiknya, maka akan semakin bagus
kualitas batuan induknya. Menurut Waples (1985), batuan induk dengan kandungan organik lebih dari
0.5% mampu menggenerasikan hidrokarbon dengan kapasitas terbatas – baik. Batuan induk memiliki
peran utama dalam pembentukan hidrokarbon, sehingga keberadaan batuan yang menjadi sumber
penghasil hidrokarbon ini perlu diteliti kandungan organiknya, tingkat kematangan dan
penyebarannya dalam suatu cekungan.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 18
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakter kuantitas
material organik, tipe material dan tingkat kematangan material batuan induk berdasarkan hasil uji
total organik carbon (TOC), pirolisis rock-eval dan pantulan vitrinit sehingga penelitian ini
diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta menentukan area
yang sangat berpotensi untuk menghasilkan hidrokarbon.
2. METODE PENELITIAN
Analisis geokimia dilakukan pada 40 sampel cutting di interval kedalaman antara 190-1940 m.
Analisis laboratorium geokimia berupa kandungan karbon organik (TOC), pirolisis rock-eval dan
reflektansi vitrinit (Ro).
2.1 Analisis kandungan karbon organik (TOC)
Sampel yang akan diuji sebelumnya dicuci, dikeringkan, digerus halus, ditimbang seberat
kurang lebih 500 mg dan kandungan karbonatnya dhilangkan dengan menggunakan asam klorida. Hal
tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya interferensi CO 2 dengan karbonat pada temperatur
tinggi. Adapun alat yang digunakan dalam tahap analisis kandungan karbon organik (TOC) yaitu
LECO Carbon Determinator (WR-112).
2.2 Analisis pirolisis
Sampel yang digunakan dalam analisis tersebut dalam bentuk serbuk seberat kurang lebih 100
mg dengan menggunakan alat Rock Eval-5. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kuantitas
minyak bumi atau hidrokarbon bebas (S1), kuantitas kerogen (S2) yang keduanya dinyatakan dalam
kg/ton dan temperatur maksimum (Tmaks. oC) yaitu temperatur puncak pada saat S2 pecah. Dari data
ini dapat diketahui potensi hidrokarbon (PY) yaitu penjumlahan dari S1+S2 dan indeks hidrogen (HI)
dengan perhitungan S2/TOC x 100%. Untuk mengetahui tipe kerogen dan jenis fluida maka
digunakan diagram van Krevelen dengan cara plot silang antara data indeks hidrogen (HI) dan Tmaks.
2.3 Analisis pantulan vitrinit
Sampel yang telah dihancurkan (tidak terlalu keras) diberi larutan asam klorida (HCl) untuk
menghilangkan kandungan karbonatnya, kemudian dicuci dan dinetralisasi, maka diberi larutan asam
fluorida (HF) untuk menghilangkan kandungan silikanya. Dengan menggunakan larutan ZnBr2, maka
akan terpisahkan antara kerogen dengan yang bukan kerogen. Selanjutnya kerogen diambil dan
dibilas, kemudian dicetak dalam resin dan dipoles.
Pengukuran besarnya pantulan vitrinit dilakukan dengan menggunakan mikroskop ferleksi
Leitz-MPV2 yang dikombinasikan dengan digital counter untuk mengukur nilai pantulan vitrinit yang
ada. Data analisis ini ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Nilai yang diarsir dipakai utnuk
menentukan kematangan dan yang tidak diarsir sebagai vitrinit yang telah teroksidasi dan mengalami
daur ulang atau mungkin material yang tidak jelas identitasnya seperti bitumen padat, pseudo-vitrint
atau semi fusinit.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Suatu batuan dapat dikategorikan sebagai batuan induk jika memiliki kuantitas material
organik, kualitas untuk menghasilkan hidrokarbon, dan kematangan termal. Kuantitas dan kualitas
material suatu batuan induk sangat dipengaruhi oleh lingkungan pengendapan sedangkan tingkat
kematangan termal sangat berkaitan erat dengan keadaan geologi regional. Kuantitas material organik
umumnya dilakukan dengan cara pengukuran terhadap karbon organik total (total organic carbon,
TOC) yang terkandung dalam batuan. Kualitas ditentukan dengan mengetahui tipe kerogen yang
terkandung dalam material organik sedangkan ematangan termal umumnya dilakukan analisis
reflektansi vitrinit dan analisis pirolisis.
Material organik pada kebanyakan sedimen merupakan campuran berbagai komponen yang
berasal dari banyak sumber dengan beragam perbedaan derajat preservasi (Meyers, 2003). Eadie et al.
(1984) menyebutkan pula bahwa selama proses terendapkannya sedimen, hampir 90% material awal
dari berbagai organisme yang diendapkan mengalami remineralisasi. Lingkungan pengendapan
sebagai salah satu faktor yang mengontrol jumlah organik yang terkandung dalam suatu batuan.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 19
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
3.1 Analisis Kuantitas Material Organik
Batuan induk pada umumnya berasosiasi dengan wilayah produktivitas organik tinggi
dikombinasikan dengan pengendapan dalam lingkungan anoksik, upwelling, dan sedimentasi yang
cepat. Proses ini yang dapat menyebabkan pengendapan material organik pada suatu lingkungan
pengendapan. Berdasarkan klasifikasi kekayaan batuan oleh Peters dan Cassa (1986), sampel pada
sumur JMB memiliki nilai TOC 0.96-7.27% wt. yang menunjukkan bahwa sampel tersebut sebagai
batuan dengan kekayaan material organik yang berpotensi baik sampai sangat baik (Gambar 1).
Menurut Jamaluddin, dkk (2019), tingkat kekayaan organik di Cekungan Sumatra Selatan berkisar
antara 0.72 - 6.12 % wt. yang mengindikasikan daerah tersebut sedikit berpotensi hingga sangat baik.
Parulian, dkk (2006) melakukan studi geokimia untuk mempelajari potensi batulempung Formasi
Gumai (GUF) sebagai batuan induk di Sub-Cekungan Jambi (studi kasus di blok Jabung).
Berdasarkan data geokimia yang dimiliki, diketahui bahwa kisaran nilai Total Organic Content (TOC)
adalah 0.79-8% wt.
Gambar 1. Sebaran nilai TOC terhadap kedalaman pada sumur JMB.
Gambar 2. Plot silang potential yield (PY) terhadap TOC dalam mengenerasikan hidrokarbon.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 20
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Potential yield (PY) merupakan total dari parameter S1 dan S2 dalam mg HC/g, yang bertujuan
untuk mengetahui produksi hidrokarbon dalam batuan. Untuk potential yield dari sampel yang telah
diuji, maka dapat dilihat bahwa sampel pada sumur JMB termasuk dalam kriteria buruk hingga baik
(poor-good) dalam menggenerasikan hidrokarbon (Gambar 2). Hal tersebut kemungkinan disebabkan
karena umur sampel batuan masih muda sehingga belum terdekomposisi secara sempurna menjadi
sumber hidrokarbon.
Gambar 3. Plot silang S1 terhadap TOC yang mengindikasikan sampel termasuk kategori
indigenous hydrocarbons (autochthonous).
Parameter S1 merupakan hidrokarbon bebas yaitu senyawa hidrokarbon dan oksigen yang
dikandung dalam batuan) yang dinyatakan dalam mg HC/g. Pada plot silang antara TOC dan S1 maka
dapat dilihat bahwa sampel yang berada di sumur JMB dominan termasuk kategori indigenous
hydrocarbons (autochthonous) yang mengindikasikan bahwa sampel tersebut merupakan dry gas
generation window (Gambar 3).
3.2 Analisis Tipe Material Organik
Banyak batuan yang memiliki nilai TOC tinggi akan tetapi tidak dapat menghasilkan
hidrokarbon karena kandungan kerogennya berupa material kekayuan atau telah teroksidasi. TOC
tinggi bukan parameter utama untuk menentukan kualitas batuan induk sehingga kualitas kerogen
menjadi penting juga untuk ditentukan. Lingkungan pengendapan merupakan faktor dominan dalam
menentukan tipe material organik yang terdapat dalam batuan. Temperatur dan tekanan mengubah
material organik menjadi suatu substansi yang disebut humin yang kemudian mengalami transformasi
menjadi kerogen. Waktu dan temperatur sangat berperan penting dalam mengubah kerogen menjadi
hidrokarbon.
Berdasarkan dari plot silang antara nilai HI dan Tmaks., sampel yang berada di sumur JMB
termasuk kerogen tipe III yang dapat menghasilkan gas (Gambar 4). Berdasarkan dari klasifikasi yang
dilakukan oleh Waples (1985), material organik untuk kerogen tipe III berasal dari material tanaman
keras seperti kayu dan lingkungan pengendapan di darat. Adiwidjaya dan De Coster (1973),
membahas tentang batuan pra-Tersier yang menjadi batuan dasar di Cekungan Sumatra Selatan dan
pengendapan batuan Tersier di atasnya. Dalam kesimpulannya penelitian ini menyebutkan diantaranya
adalah Formasi Lemat diendapkan di daratan yang menjadi tipe cekungan pada Eosen sampai Awal
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 21
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Oligosen. Formasi Talangakar diendapkan pada Akhir Oligosen sampai Awal Miosen di lingkungan
fluviatil sampai laut dangkal. Menurut Jamaluddin, dkk (2018), Formasi Talang Akar memiliki nilai
HI 112-190 dan mengandung kerogen vitrinitik (tipe III) sehingga berpotensi sebagai penghasil gas
atau kondesat.
Gambar 4. Plot silang antara nilai HI dan Tmaks. untuk menentukan tipe kerogen.
Analisis juga dilakukan dengan membuat plot silang antara indeks hidrogen dan indeks oksigen
pada diagram van Krevelen untuk melihat tipe kerogen dari tiap-tiap formasi yang ada. Nilai indeks
hidrogen (HI) dan indeks oksigen (OI) merupakan suatu pengukuran berdasarkan analisis pirolisis
rock-eval yang dikombinasikan dengan nilai TOC. Nilai OI tinggi serta nilai HI rendah membuat
suatu plot pada diagram van Krevelen mengindikasikan sumur tersebut dominan kerogen tipe III
(Gambar 5). Kerogen tipe III ini merupakan suatu jenis kerogen yang akan cenderung menghasilkan
gas dibandingkan dengan minyak bumi. Berdasarkan hasil penelitian dari Jamaluddin, dkk (2018), tipe
material organik pada Formasi Talang Akar berupa tipe kerogen II/IIIb-III yang berpotensi
menghasilkan gas/minyak dan gas. Batuan sedimen Formasi Lahat pada kedalaman 3050 m – 3055 m
berpotensi bagus sebagai pembentuk hidrokarbon, sedangkan awal pembentukan minyak bumi terjadi
pada kedalaman 2575 m.
Satyana dan Purwaningsih (2013) melakukan penelitian kandungan geokimia menyatakan
bahwa Batuan induk tersusun oleh batulempung berbatubara dan batubara (tipe II dan III). Batuan
induk ini berselingan dengan reservoir dan batuan penyekat yang berkualitas baik. Pada fase awal
postrift, secara prinsip batuan induk pada zona ini merupakan endapan laut. Dalam hal ini
diperkirakan material tumbuhan darat mengalami transportasi ke lingkungan laut, kemudian
mengalami pemendaman dan preservasi sebagai material organik terestrial tipe II/III. Endapan ini
kadang mengalami transportasi ke lingkungan yang lebih dalam menjadi endapan batulempung
intradeltaic – neritic. Pada akhir dari postrift pada cekungan ini dicirikan hampir sama dengan tipe
endapan akhir synrift berupa endapan progradasi.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 22
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Gambar 5. Diagram van Krevelen untuk menentukan tipe kerogen dari sampel batuan Sumur JMB
(van Krevelen, 1997 dalam Hunt, 1996).
3.3 Analisis Kematangan Material Organik
Tingkat kematangan material organik suatu batuan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor
seperti keadan geologi regional, sejarah pemendaman dan temperatur bawah permukaan daerah
tersebut. Patra Nusa Data (2011) mengkaji ulang potensi hidrokarbon di sub-Cekungan Jambi dengan
mengevaluasi konfigurasi bawah permukaan serta evolusi dan dinamika tektonik dalam rangka
mendefinisikan sistem minyak dan gas bumi area ini dengan penekanan pada potensi batuan induk,
reservoar yang optimum dan integritas perangkap yang bersifat struktural. Kematangan diperlukan
untuk mengetahui apabila suatu batuan induk telah memasuki jendela minyak. Batas jendela minyak
ini sangat tergantung pada tipe material organiknya. Pada umumnya jendela minyak dicapai pada nilai
Ro sekitar 0,6%
Dari gambar 6, terlihat bahwa sampel berdasarkan pengkategorian oleh Peters dan Cassa (1994)
,sumur JMB telah memasuki zona kematangan pada kedalamaan ≤ 1000 m dengan rata-rata nilai Ro
0.63-1.22%. Jika dilihat dari grafik, nilai Ro bertambah besar sebanding dengan bertambah besarnya
kedalaman pada tiap sampel yang diambil. Dapat disimpulkan bahwa kedalaman sangat
mempengaruhi tingkat kematangan karena berkaitan dengan pemendaman material organik yang ada
dibawah permukaan. Berdasarkan penelitian Jamaluddin, dkk (2018), tingkat kematangan pada
Formasi Talang Akar di kedalaman ≤ 1200 m adalah belum matang, 1200- 2200 m awal matang dan
di bawah 2200 m telah matang secara termal. Clure dan Fiptiani (2001) dalam penelitiannya,
Pematangan minyak pada Formasi Talang Akar dimulai pada akhir Miosen Tengah. Model geokimia
pada area ini menunjukkan kematangan minyak pada 10.6 juta tahun yang lalu, sedangkan gas pada 4
juta tahun yang lalu. Heatflow yang tinggi akibat intrusi pada Pliosene-Pleistosene yang
mengakibatkan pematangan secara cepat batuan induk yang berlokasi di atas batuan dasar.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 23
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Gambar 6. Plot antara nilai Ro terhadap kedalaman pada sumur JMB.
Gambar 7. Tingkat kematangan sampel pada sumur JMB berdasarkan nilai Tmaks.
Temperatur maksimum untuk melepas hidrokarbon dari proses cracking kerogen yang terjadi
selama pirolisis (puncak S2). Tmaks merupakan indikasi tahapan pematangan material organik.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 24
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Pengaruh suhu yang tinggi dalam waktu yang singkat atau sebaliknya akan mengakibatkan kerogen
berubah menjadi hidrokarbon. Berdasarkan gambar 7, tingkat kematangan batuan induk pada
kedalaman 200-1000 m masih dikategorikan belum matang dengan nilai Tmaks 415-434oC sedangkan
pada interval kedalaman ≥ 1000 m dengan suhu 436 – 466oC sehingga dapat dikategorikan daerah
tersebut sudah matang. Secara umum hasil dari analisis kematangan dengan parameter Tmaks pada
tiap-tiap sampel menunjukkan memiliki kualitas kematangan yang lebih baik. Grafik antara Tmaks
berbanding lurus dengan bertambahnya kedalaman. semakin dalam batuan induk akan semakin panas
dan akhirnya menghasilkan minyak. Proses pemasakan ini tergantung suhunya dan karena suhu ini
tergantung dari besarnya gradien geothermalnya maka setiap daerah tidak sama tingkat
kematangannya. Daerah yang dingin adalah daerah yang gradien geothermalnya rendah, sedangkan
daerah yang panas memiliki gradien geothermal tinggi. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan
itu semakin dalam maka akan dipengaruhi juga dengan penambahan batuan penimbun, maka suhu
yang tinggi akan mengubah karbon yang menjadi gas. Bishop (2001), dalam publikasinya menyatakan
bahwa gradien temperatur di Cekungan Sumatra Selatan berkisar 49° C/Km. Gradien ini lebih kecil
jika dibandingkan dengan Cekungan Sumatra Tengah, sehingga minyak akan cenderung berada pada
tempat yang dalam. Formasi Batu Raja dan formasi Gumai berada dalam keadaan matang hingga awal
matang pada generasi gas termal dibeberapa bagian yang dalam dari cekungan, oleh karena itu
dimungkinkan untuk menghasilkan gas pada petroleum system.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang karakterisasi potensi batuan induk
hidrokarbon berdasarkan analisis geokimia material organik sumur JMB, Sub-Cekungan Jambi,
Cekungan Sumatra Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Sampel pada sumur JMB memiliki nilai TOC 0.96-7.27% wt. yang menunjukkan bahwa
sampel tersebut sebagai batuan dengan kekayaan material organik yang berpotensi baik
sampai sangat baik sebagai batuan induk.
b. Karakterisasi tipe material organik pada daerah penelitian dominan kerogen tipe III yang
berpotensi menghasilkan gas atau kondesat. Material organik pada tipe tersebut berasal dari
material tanaman keras seperti kayu dan mengalami proses pengendapan di darat.
c. Tingkat kematangan batuan induk pada kedalaman 200-1000 m masih dikategorikan belum
matang dengan nilai Tmaks 415-434oC dan %Ro 0.1 – 0.5 sedangkan pada interval kedalaman
≥ 1000 m dengan suhu 436 – 466 oC memiliki %Ro 0.6 – 1.22 sehingga dapat dikategorikan
daerah tersebut sudah matang.
d. Berdasarkan analisis geokimia material organik pada sumur JMB, batuan induk pada Formasi
Lahat, Formasi Talang Akar dan Formasi Gumai merupakan batuan induk yang berpotensi
menghasilkan hidrokarbon pada daerah tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Adiwidjaya, P., dan de Coster, G. L., 1973, Pre-Tertiary paleotopography and related sedimentation in
South Sumatera, Indonesian Petroleum Association Second Annual Convention, hal 89 – 103.
Bishop, M. G., 2001, South Sumatra Basin Province, Indonesia: The Lahat/Talang Akar-Cenozoic
Petroleum System, U.S. Department of The Interior,U.S Geological Survey.
Clure, J., dan Fiptiani, N., 2001, Hydrocarbon Exploration in Merang Triangle, South Sumatra basin,
Proceeding 28th Annual Convention & Exhibition, Indonesian Petroleum Association,
hal 803-824.
Eadie, B. J., 1984, Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Great Lakes. Advances in
Environmental Science and Technology, Vol.14, hal 195-211.
Hunt. J.M., 1996, Petroleum Geochemistry and Geology, Ed. 2, New York, W.H. Freeman and
Company.
Jamaluddin, Massinai., M. F. I., Syamsuddin, E., 2018, Karakterisasi serph pada Formasi Talang Akar
sebagai potensi shale hydrocarbon, Jurnal Geocelebes,Vol. 2, hal 31 – 35.
Jamaluddin, Fuqi Cheng, 2018, Organic Richness and Organic Matter Quality Studies of Shale Gas
Reservoir in South Sumatra Basin, Indonesia. Journal of Geoscience and Environment
Protection, Vol. 6,pp. 85-100.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 25
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
PROSIDING SEMINAR NASIONAL TEKNOLOGI V
Samarinda, 10 Oktober 2019
Jamaluddin, Nugraha. S.T., Maria, Umar, E.P.,2018, Prediksi total organic carbon (TOC)
menggunakan regresi multilinear dengan pendekatan data well log. Jurnal Geocelebes, Vol. 2,
hal 1 – 5.
Jamaluddin, Maria, 2019, Identifikasi zona shale prospektif berdasarkan data well log di cekungan
Sumatra Selatan. Jurnal Geocelebes, Vol. 3, hal 19 – 27.
Magoon, L.B., dan Dow,W.G.,1994, The Petroleum System From Source to Trap, American
Association of Petroleum Geologist Methods in Exploration series No.7. Tulsa, Oklahoma.
Meyers, P. A., 2003., Applications of organic geochemistry to paleolimnological reconstructions: a
summary of examples from the Laurentian Great Lakes, Organic geochemistry, Vol. 34 (2), pp
261- 289.
Mizani, Y.A., 2011, Characterization of Hydrocarbon and Source Rock in Berembang-Karangmakmur
Deep Jambi Sub Basin, AAPG International Conference and Exhibition, Milan, Italy, pp. 156-
174.
Patra Nusa Data, 2011, Hydrocarbon Potential of West Jambi-2 Exploration Operating Area Jambi.
Laporan Evaluasi Internal, Jakarta.
Parulian, Lambok., Suta, Nyoman., Satyana, A. H.,2006, Gumai Shales of Jabung Area: Potential
Source Rocks in Jambi Sub Basin and Their Contribution to the New Petroleum System.
Proceeding of the 35th IAGI. Annual Convention & Exhibition, Pekanbaru.
Peters, K. E., 1986, Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis.
AAPG Bulletin Vol. 70, pp. 318-329.
Peters, K.E. and Cassa, M.R., 1994, Applied Source Rock Geochemistry, The petroleum system-from
source to trap: AAPG, Memoir 60.
Satyana, A.H., dan Purwaningsih, M.E.M., 2013, Variability of Paleogene Source Facies of Circum of
Sundaland basins, Western Indonesia : Tectonic Sedimentary and Geochemical Constraints –
Implications of Oil Characteristic, Proceeding 37th Annual Convention & Exhibition, Indonesian
Petroleum Association, hal 427-467
Waples, D. W., 1985, Geochemistry in Petroleum Exploration, International Human Resources
Development Corporation, Boston, pp. 232.
Fakultas Teknik – Universitas Mulawarman 26
p-ISSN : 2598-7410
e-ISSN : 2598-7429
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal Petrologi Putri Tias Anita SariDokumen5 halamanJurnal Petrologi Putri Tias Anita SariImam AwangBelum ada peringkat
- Evaluasi Batuan Induk - Sumur Prabumulih - Sumsel - Univ ChinaDokumen9 halamanEvaluasi Batuan Induk - Sumur Prabumulih - Sumsel - Univ ChinaFajar ModjoBelum ada peringkat
- 736 2265 1 PB 1Dokumen7 halaman736 2265 1 PB 1yoga prasetyaBelum ada peringkat
- Perbedaan Karakteristik Batubara Pada Daerah Sawahlunto, Sumatera Barat, Dan Meulaboh, AcehDokumen6 halamanPerbedaan Karakteristik Batubara Pada Daerah Sawahlunto, Sumatera Barat, Dan Meulaboh, Acehdot cosmosBelum ada peringkat
- Tugas1 GeologiMigasDokumen4 halamanTugas1 GeologiMigasfaradiko SABelum ada peringkat
- Kunjungan Laboratorium Geokimia Dasar Lemigas JakartaDokumen10 halamanKunjungan Laboratorium Geokimia Dasar Lemigas JakartaRonata Asri WanabellaBelum ada peringkat
- 407 1056 2 PB PDFDokumen16 halaman407 1056 2 PB PDFSalman ArkanBelum ada peringkat
- Geo94 Evaluasi Batuan Induk Sample Batuan Sedimen Formasi Talang Akar Di Daerah Lengkiti, Ogan Komering Ulu, Sumatera SelatanDokumen12 halamanGeo94 Evaluasi Batuan Induk Sample Batuan Sedimen Formasi Talang Akar Di Daerah Lengkiti, Ogan Komering Ulu, Sumatera SelatanAditya Ace PumpistBelum ada peringkat
- Mutiara GMBDokumen11 halamanMutiara GMBcukup memoriBelum ada peringkat
- Batuan Induk (Source Rock) HidrokarbonDokumen10 halamanBatuan Induk (Source Rock) Hidrokarbonanang_suheBelum ada peringkat
- 74 324 1 PBDokumen11 halaman74 324 1 PBresty2pmBelum ada peringkat
- 2-TT. Hermawan Jaya Sinaga (7-13) OkDokumen7 halaman2-TT. Hermawan Jaya Sinaga (7-13) Ok111Eka Bagus WarnumBelum ada peringkat
- Hamdani Prosiding11Dokumen7 halamanHamdani Prosiding11Menanjak SejenakBelum ada peringkat
- Tugas Pelaporan Geologi: Proposal Tugas AkhirDokumen10 halamanTugas Pelaporan Geologi: Proposal Tugas AkhirIrdantyoBelum ada peringkat
- Laporan 1 GMB - Nurul AzizahDokumen7 halamanLaporan 1 GMB - Nurul Azizahnurul azizahBelum ada peringkat
- Proposal To ChevronDokumen25 halamanProposal To ChevronRain CollapseBelum ada peringkat
- 988 3452 1 PBDokumen7 halaman988 3452 1 PBJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Rangkuman Geologi Migas Dan Pabum FixxDokumen35 halamanRangkuman Geologi Migas Dan Pabum FixxUmbu Kerung PamaraBelum ada peringkat
- Analisis Kualitas Dan Perhitungan Sumberdaya Batubara Pada Lapangan X, Banko Pt. Bukit Asam (Persero) TBK., Tanjung Enim, Sumatera SelatanDokumen18 halamanAnalisis Kualitas Dan Perhitungan Sumberdaya Batubara Pada Lapangan X, Banko Pt. Bukit Asam (Persero) TBK., Tanjung Enim, Sumatera Selatanfaiq nirmalaBelum ada peringkat
- Tugas Rangkuman Kuliah Muhammad Adji Hanif - 21100117130058Dokumen13 halamanTugas Rangkuman Kuliah Muhammad Adji Hanif - 21100117130058Adji HanifBelum ada peringkat
- PAPER KIMIA BAHAN GALIAN SyifaDokumen13 halamanPAPER KIMIA BAHAN GALIAN SyifaSyifa MdnyhBelum ada peringkat
- Batuan Induk SerayuDokumen6 halamanBatuan Induk SerayuIkbar Aulia ZamanyBelum ada peringkat
- Tugas Metodologi PenelitianDokumen11 halamanTugas Metodologi PenelitianDillah PisceesBelum ada peringkat
- PROPOSAL PENELITIAN Indah PDFDokumen33 halamanPROPOSAL PENELITIAN Indah PDFKomang Wahyu Krisna BrataBelum ada peringkat
- Bab IDokumen32 halamanBab IHenricusKirunBelum ada peringkat
- Analisis Kandungan Logam Pada Limbah Tailing Red MudDokumen8 halamanAnalisis Kandungan Logam Pada Limbah Tailing Red MudNoel CookBelum ada peringkat
- LAPORAN 1 GMB - Nurul Azizah - F1D220010Dokumen7 halamanLAPORAN 1 GMB - Nurul Azizah - F1D220010NurulBelum ada peringkat
- LP 1 GMB Bener Analisa Batuan IndukDokumen9 halamanLP 1 GMB Bener Analisa Batuan Indukcukup memoriBelum ada peringkat
- Proses Terbentuknya Batu Bara Dan ManfaatnyaDokumen7 halamanProses Terbentuknya Batu Bara Dan Manfaatnyavido julian nurkholisBelum ada peringkat
- Mata Kuliah Geologi MigasDokumen7 halamanMata Kuliah Geologi MigasDuto TriadjieBelum ada peringkat
- Lingkungan Pengendapan Batubara Formasi Keruh Daerah Kuantan-Singingi Provinsi Riau Berdasarkan Analisis Petrografi Organik - Aditya Riyadi PutraDokumen10 halamanLingkungan Pengendapan Batubara Formasi Keruh Daerah Kuantan-Singingi Provinsi Riau Berdasarkan Analisis Petrografi Organik - Aditya Riyadi Putraaditya6riyadiBelum ada peringkat
- Source Rock EvaluationDokumen38 halamanSource Rock EvaluationKzrDannoBernaldoBelum ada peringkat
- Source Rock EvaluationDokumen38 halamanSource Rock EvaluationKzrDannoBernaldoBelum ada peringkat
- TugasDokumen15 halamanTugasI2O37OO32 Sesilia Yuan PetriksiaBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen15 halaman1 PBAyu PuspitaBelum ada peringkat
- Review Jurnal Pertemuan 2, Kimia Dasar, Qoori Nadhilah, 22136028Dokumen9 halamanReview Jurnal Pertemuan 2, Kimia Dasar, Qoori Nadhilah, 22136028adiesBelum ada peringkat
- Ok 3 Aplikasi Metode Geofisika Eksplorasi Batubara Kelas GADokumen10 halamanOk 3 Aplikasi Metode Geofisika Eksplorasi Batubara Kelas GAbobby xcutieBelum ada peringkat
- Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 4 No. 3Dokumen9 halamanJurnal Geologi Indonesia, Vol. 4 No. 3fahmihak100% (1)
- Air Asam TambangDokumen14 halamanAir Asam TambangJenrinaldo Yohanes SilaenBelum ada peringkat
- Tugas TKG Paper Analisa Lingkungan Pengendapan Terhadap BatubaraDokumen6 halamanTugas TKG Paper Analisa Lingkungan Pengendapan Terhadap BatubaraNadya Farah KamiliaBelum ada peringkat
- Toksisitas Abu Terbang Dan Abu Dasar Limbah Pltu BatubaraDokumen4 halamanToksisitas Abu Terbang Dan Abu Dasar Limbah Pltu BatubaramsadsetiawanBelum ada peringkat
- PROPOSAL TUGAS AKHIR Muhammad Radian 17137060Dokumen17 halamanPROPOSAL TUGAS AKHIR Muhammad Radian 17137060Muhammad RadianBelum ada peringkat
- Abi Zarkasyi 111.160.191 Kelas ADokumen8 halamanAbi Zarkasyi 111.160.191 Kelas ATaubi arham geoxactanaBelum ada peringkat
- Metode Eksplorasi GeokimiaDokumen16 halamanMetode Eksplorasi Geokimiaalbab onyonBelum ada peringkat
- Makalah BatubaraDokumen46 halamanMakalah BatubaraAnwar HasibuanBelum ada peringkat
- Geology: Sari - Di Cekungan Jawa Timur Indonesia, Batupasir Ngrayong Telah Ditargetkan Sebagai Reservoir Untuk CarbonDokumen11 halamanGeology: Sari - Di Cekungan Jawa Timur Indonesia, Batupasir Ngrayong Telah Ditargetkan Sebagai Reservoir Untuk CarbonWahyu PrayetnoBelum ada peringkat
- Laprak KarbonatDokumen25 halamanLaprak KarbonatDyakso Yudho PrastowoBelum ada peringkat
- S2 2017 372126 Introduction PDFDokumen6 halamanS2 2017 372126 Introduction PDFfriska agustinBelum ada peringkat
- Paper Sedimentasi Batubara...... Alberto A, Tambur, 072.18,03Dokumen12 halamanPaper Sedimentasi Batubara...... Alberto A, Tambur, 072.18,03Kafi AkbarBelum ada peringkat
- 5176 14087 1 SMDokumen11 halaman5176 14087 1 SMFachrel KiandraBelum ada peringkat
- Tinjauan Pustaka 5Dokumen14 halamanTinjauan Pustaka 5Moh IhsanBelum ada peringkat
- F12117040 Analisis Batuan IndukDokumen26 halamanF12117040 Analisis Batuan IndukWindi LestariBelum ada peringkat
- Batuan Induk Cekungan KutaiDokumen12 halamanBatuan Induk Cekungan KutaiAnggawhydBelum ada peringkat
- Pembentukan BatubaraDokumen4 halamanPembentukan Batubaramahmud ahlul fikri hasibuanBelum ada peringkat
- Abdimas 001Dokumen13 halamanAbdimas 001JamaluddinBelum ada peringkat
- Research 004Dokumen13 halamanResearch 004JamaluddinBelum ada peringkat
- Proposal Program Kreativitas MahasiswaDokumen26 halamanProposal Program Kreativitas MahasiswaJamaluddinBelum ada peringkat
- Research 020Dokumen12 halamanResearch 020JamaluddinBelum ada peringkat
- PKM KCDokumen10 halamanPKM KCJamaluddinBelum ada peringkat
- PKM-P Kelompok 4Dokumen15 halamanPKM-P Kelompok 4JamaluddinBelum ada peringkat
- Sharing IKA GeofisikaDokumen19 halamanSharing IKA GeofisikaJamaluddinBelum ada peringkat
- Proposal Program Kreativitas Mahasiswa "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumur Tua Louise Menggunakan Metode Decline Curve"Dokumen24 halamanProposal Program Kreativitas Mahasiswa "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumur Tua Louise Menggunakan Metode Decline Curve"JamaluddinBelum ada peringkat
- Pemanfaatan Kain Flanel Sebagai Penyaring Air Kotor Menjadi BersihDokumen20 halamanPemanfaatan Kain Flanel Sebagai Penyaring Air Kotor Menjadi BersihJamaluddinBelum ada peringkat
- LAPORAN PENGMAS 2020 Geofisika 2020 "Shallow Gas Hazard"Dokumen9 halamanLAPORAN PENGMAS 2020 Geofisika 2020 "Shallow Gas Hazard"JamaluddinBelum ada peringkat
- Proposal Program Kreativitas Mahasiswa Judul ProgramDokumen25 halamanProposal Program Kreativitas Mahasiswa Judul ProgramJamaluddinBelum ada peringkat
- Laporan Pengmas 2020 Ngobrol Santuy Mengenal Geologi Lebih DekatDokumen9 halamanLaporan Pengmas 2020 Ngobrol Santuy Mengenal Geologi Lebih DekatJamaluddinBelum ada peringkat
- Daftar Penelitian Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Teknik GeologiDokumen6 halamanDaftar Penelitian Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Teknik GeologiJamaluddinBelum ada peringkat
- Laporan Pengmas 2020 Migas Talk Aplikasi Pemodelan Geologi Dalam Kegiatan PenambanganDokumen9 halamanLaporan Pengmas 2020 Migas Talk Aplikasi Pemodelan Geologi Dalam Kegiatan PenambanganJamaluddinBelum ada peringkat
- GeoCelebes 2Dokumen10 halamanGeoCelebes 2JamaluddinBelum ada peringkat
- GeoCelebes 1Dokumen11 halamanGeoCelebes 1JamaluddinBelum ada peringkat
- 8108 23181 1 PBDokumen10 halaman8108 23181 1 PBJamaluddinBelum ada peringkat
- Persiapan YudisiumDokumen11 halamanPersiapan YudisiumJamaluddinBelum ada peringkat
- SemnastekDokumen3 halamanSemnastekJamaluddinBelum ada peringkat