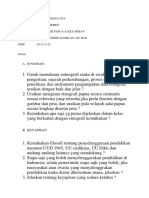119-Article Text-231-1-10-20170601
Diunggah oleh
Lalu Muh Balia FarsahinHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
119-Article Text-231-1-10-20170601
Diunggah oleh
Lalu Muh Balia FarsahinHak Cipta:
Format Tersedia
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
KONSEP DAN WAWASAN UMUM
MEMIKIRKAN KEMBALI
ETNOARKEOLOGI
Daud Aris Tanudirjo
(Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
Abstract
Up until now there is still much confusion about ethnoarchaeological research in
archaeological community in Indonesia. There are many archaeologists who could not
distinguish between ethnographic and ethnoarchaeological research. Therefore, after
the evaluation of ethnoarchaeological research done in more than 20 years ago, there
is a necessity to rethink about ethnoarchaeological research. In brief, ethnography in
archaeology is an effort to depict all of the archaeological activities and ideas which
tries to put the past (archaeology) in the context of society today (ethnography). The
ethnoarchaeological research is not a way to find the truth in the past but an effort to
increase the faith upon the phenomenon that might be happened in the past.
Keywords: ethnoarchaeology, past, present
Pendahuluan
Tahun ini usia istilah “etnoarkeologi” sudah 110 tahun. Istilah ini pertama
kali diajukan oleh Jesse Fewkes, seorang ahli arkeologi yang banyak meneliti tentang
tradisi migrasi Tusayan, salah satu komunitas Indian-Amerika. Dalam tulisannya yang
diterbitkan dalam laporan tahunan Bureau of American Ethnology 1900, Fewkes
menyebutkan “ethno-archaeologist” sebagai ahli arkeologi yang mempelajari
kehidupan masyarakat tradisional sebagai persiapan untuk meneliti dan memahami
‘masyarakat prasejarah’ yang sedang ia kaji tinggalan-tinggalannya (David dan
Kramer, 2001). Sebenarnya, upaya untuk memahami dan menafsirkan budaya yang
sudah punah (arkeologis) dengan menggunakan bandingan budaya masyarakat masa
kini (data etnografis) sudah lama diterapkan sebelum munculnya istilah etnoarkeologi.
Para perintis ilmu Arkeologi, seperti William Camden, Sven Nilsson dan Pitt Rivers,
misalnya, telah mengemukakan pentingnya mengetahui kehidupan tradisional di masa
kini untuk memahami dan menfasirkan kehidupan masa lampau (lihat Tanudirjo,
1987). Namun, cara-cara yang telah dipergunakan hampir setua ilmu arkeologi itu
sendiri tidak jarang dipertanyakan keabsahnya.
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 1
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Awalnya, para ahli arkeologi lebih banyak menggunakan data etnografi yang
dikumpulkan atau dipaparkan oleh etnografer (ahli antropologi). Sejak tahun 1940-an,
memang para ahli arkeologi merasa tidak puas dengan hasil pengamatan dan paparan
ahli lain. Alasannya, ada banyak aspek yang ingin diketahui arkeologi justru tidak
diamati atau tidak dipaparkan oleh mereka. Karena itu, para ahli arkeologi terdorong
untuk melakukan pengamatan dan mendapatkan data etnografi sendiri. Pada saat itu,
kegiatan etnoarkeologi menjadi semakin banyak dilakukan dan digunakan untuk
memecahkan masalah-masalah arkeologi (Tanudirjo, 1987).
Di Indonesia, penggunaan kajian etnoarkeologi juga cukup memegang
peran yang penting dalam memecahkan masalah arkeologi. Namun, penerapan kajian
etnoarkeologi rupanya belum dipahami dengan benar. Hal itu dapat dibuktikan dari
hasil penelitian sejumlah kajian etnoarkeologi hingga tahun 1986, yang ternyata
menunjukkan adanya kesalahan dan kerancuan penggunaan etnoarkeologi (Tanudirjo,
1987). Bahkan, sampai saat ini pun masih ada kebingungan di lingkungan arkeologi
Indonesia dalam menyikapi kajian ini. Tidak sedikit ahli arkeologi yang belum dapat
membedakan secara tepat antara penelitian etnografi dengan etnoarkeologi. Karena
itu, setelah evaluasi kajian etnoarkeologi dilakukan lebih dari 20 tahun lalu, barangkali
ada baiknya untuk memikirkan sekali lagi tentang kajian etnoarkeologi.
Pembahasan
Setelah dasarwarsa 1970-an, sesungguhnya ada banyak istilah digunakan
untuk kajian arkeologi yang menggunakan data etnografi, di antaranya “living
archaeology”, “action archaeology”, “archaeoethnography”, “ethnographic
archaeology”, dan “analogi etnografi”. Meskipun begitu banyak istilah yang
digunakan, namun satu hal yang pasti kajian ini selalu bertitiktolak dari persoalan
atau masalah arkeologi. Pemahaman ini juga dapat ditangkap dari batasan
etnoarkeologi menurut Kramer (1979) sebagai berikut
“Kajian etnoarkeologi meneliti berbagai aspek sosial-budaya masa kini dari
cara pandang arkeologi. Peneliti etnoarkeologi mencoba menentukan secara
sistematis hubungan antara perilaku dan budaya bendawi yang tidak digarap
oleh ahli etnologi, dan memastikan sejauh mana tindakan-tindakan yang
dapat diamati di masa kini dapat menghasilkan tinggalan-tinggalan yang
serupa dengan apa yang ditemukan oleh ahli arkeologi”
2 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Ahli lainnya Schiffer (1978) menyatakan “etnoarkeologi adalah kajian
tentang budaya bendawi dalam sistem budaya yang masih ada untuk mendapatkan
informasi, khusus maupun umum, yang dapat berguna bagi penelitian arkeologi”.
Etnoarkeologi menelisik hubungan antara tindakan manusia dan budaya bendawi di
masa kini untuk menyediakan prinsip-prinsip yang dibutuhkan dalam kajian tentang
masa lampau (Reid, 1995; LaMotta dan Schiffer, 2001). Karena itu, untuk menilai
apakah suatu karya penelitian bersifat etnografi atau etnoarkeologi, dapat diukur
sejauh mana penelitian etnografi itu ditujukan untuk menjawab masalah arkeologi.
Untuk memberikan gambaran perbedaan antara penelitian etnoarkeologi dan
etnografi, Thompson (1991 dalam David dan Kramer, 2001) mencoba menunjukkan
gradasi penelitian dalam ilmu antropologi yang membawahi arkeologi, etnografi,
dan linguistik (lihat Diagram 1). Dari diagram tersebut, terlihat bahwa etnoarkeologi
berbeda dengan arkeologi, karena pendekatan ini memasukkan data etnografi
untuk penelitian arkeologi. Sementara itu, penelitian etnografi dilakukan tanpa ada
perhatian tentang masalah arkeologi. Hasil kajian etnografi dapat saja memberikan
gambaran hubungan antara budaya bendawi dengan tindakan dan gagasan manusia.
Namun, itu semua tanpa disadari oleh peneliti etnografi. Data ini bisa saja kemudian
dipakai oleh ahli arkeologi untuk menafsirkan atau menjelaskan data arkeologi.
Contohnya adalah upaya S. Reinach menjelaskan fungsi lukisan gua prasejarah di
Eropa. Ia menyimpulkan lukisan prasejarah Eropa sebagai ‘magi simpatetis” melalui
perbandingan dengan data etnografis pembuatan lukisan dinding cadas oleh orang
aborijin Australia yang ditulis oleh B. Spencer dan F. Gillen (Bahn dan Vertut, 1988).
Tentu saja, ketika melakukan pengamatan etnografis Spencer dan Gillen tidak berpikir
sama sekali tentang arkeologi. Namun, datanya dapat digunakan sebagai informasi
untuk menafsirkan data arkeologi.
Dalam Diagram 1, kajian etnoarkeologi dibagi menjadi tiga kelompok.
Pertama, disebutkan kajian etnografi yang secara informal memberikan informasi
kepada ahli arkeologi. Disebut etnoarkeologi informal kalau pengamatan etnografi
dilakukan hanya sekilas saja tetapi dimaksudkan untuk kepentingan arkeologi. Kedua,
etnoarkeologi yang mengkaji secara khusus salah satu aspek tertentu dari budaya yang
masih hidup, misalnya matapencaharian, teknologi, atau religi. Ketiga, etnoarkeologi
yang menelaah secara mendalam seluruh budaya masyarakat yang masih hidup
sebagai konteks penciptaan budaya bendawi. Sementara itu, penelitian etnosain, yaitu
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 3
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
gabungan penelitian linguistik (bahasa) dan etnografi, dapat menyumbang penelitian
etnoarkeologi dengan menyediakan bandingan sistem pengetahuan, terutama sistem
kategorisasi dan konsep-konsep tradisional. Secara umum diagram Thompson dapat
memberikan gambaran kedudukan etnoarkeologi dalam hubungan dengan cabang
ilmu lainnya dan nuansa perbedaan antara kajian-kajian tersebut
Diagram 1 Gradasi Kajian Arkeologi – Etnografi – Linguistik dan posisi
kajian Etnoarkeologi
A Penelitian Arkeologi Murni, tanpa
R gunakan data etnografi
K
E E
O T
L N Pengamatan Etnografi Informal yang
O O dapat memberikan informasi bagi
G A arkeologi
I R
K
E Penelitian etnografi fokus pada salah
O satu aspek budaya masa kini untuk
L keperluan arkeologi
O
E G
T I Penelitian etnografi pada seluruh sistem
N budaya untuk memberi konteks
O penyimpulan masalah arkeologi
G
R
A
F
I
Penelitian Etnografi Murni, tanpa
peduli keperluan arkeologi
E
T
L N
I O Pengetahuan dan cara pandang
N S masyarakat tradisional terhadap budaya
G A
I bendawi
U
I N
S
T
I
K
Penelitian Linguistik Murni, tanpa
konteks budaya
4 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Namun, konsep yang digambarkan dalam Diagram Thompson tadi
seringkali dianggap sebagai kerangka pikir yang agak terlalu longgar. Ada kelompok
praktisi etnoarkeologi yang menganut batasan yang lebih ketat. Dari perspektif
kelompok ini, etnoarkeologi harus mencakup tiga langkah ilmiah, yaitu (a) dimulai
dengan merumuskan masalah yang muncul dari pengamatan data arkeologi, lalu
(b) melakukan pengamatan etnografi yang sesuai dengan masalah tadi, dan (c)
menerapkan hasil pengamatan etnografi ke data arkeologi untuk mendapatkan
pemahaman lebih baik. Selain itu, ada pula yang membatasi etnoarkeologi dengan
mensyaratkan pengamatan langsung. Artinya, data etnografis harus diperoleh dari
pengamatan langsung di lapangan, biasanya dengan metode observasi partisipatif, dan
tidak diperoleh dari data etnografis sekunder, baik dari catatan etnografi yang sudah
ada maupun benda etnografi di museum. Bagi mereka, penelitian sampah masa kini
atau kajian budaya bendawi modern (a.l. Gould dan Schiffer, 1981; Rathje, 1978).
Penggunaan data etnografis sekunder lebih digolongkan sebagai etnohistori atau
bahkan arkeologi sejarah (historical archaeology) yang menggunakan dokumen dan
arsip untuk membantu menjelaskan data arkeologi (David dan Kramer, 2001).
Apabila pengertian-pengertian di atas diterapkan sebagai tolok ukur penelitian
etnoarkeologi di Indonesia, barangkali akan lebih banyak penelitian etnoarkeologi
informal dan tidak jelas arahnya. Ada beberapa alasan yang melandasi pernyataan
itu. Pertama, tidak sedikit kajian etnoarkeologi yang didasarkan pada data etnografi
sekunder. Kedua, banyak peneliti etnoarkeologi di Indonesia yang hanya melakukan
pengamatan sekilas dan singkat. Hampir tidak ada laporan observasi partisipatif yang
menunjukkan kerja berbulan-bulan di lapangan untuk mengumpulkan data yang
komprehensif. Ketiga, pengamatan sekilas yang dilakukan seringkali tidak memfokus
pada hubungan antara benda budayawi dengan tingkah laku atau gagasan, tetapi lebih
banyak deskripsi tindakan dan gagasan saja. Keempat, banyak kajian etnoarkeologi
yang tidak merumuskan persoalan arkeologi yang dihadapi sebagai titik tolak untuk
kajian etnoarkeologi-nya. Akibatnya, banyak kajian etnoarkeologi di Indonesia yang
tidak menjawab persoalan arkeologi, tetapi lebih berbobot sebagai deksripsi etnografis
saja. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan amat terbatasnya kajian etnoarkeologi yang
fokus dan tuntas proses transformasi budaya bendawi dalam masyarakat tradisional.
Penelitian ini memang membutuhkan ketekunan dan observasi partisipatif yang cukup
lama dengan rekaman data yang cermat.
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 5
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Keadaan ini tentu amat berbeda dengan apa yang dilakukan di luar.
Binford, misalnya, melakukan penelitian yang amat teliti selama berbulan-bulan di
tengah masyarakat Nunamiut Eskimo hanya untuk mengamati terbentuknya sebaran
benda-benda hasil aktivitas mereka (1983). Demikian juga, Meehan (1982) yang
tekun mengamati dan memetakan sisa-sisa cangkang kerang yang ditinggalkan
oleh masyarakat Gidjingali di Australia Utara. Ia ingin mengetahui bagaimana
proses transformasi ekofak kerang dari habitat alamnya (shell bed) hingga menjadi
tumpukan sisa makanan (shell midden). Contoh lain adalah kerja Lee dan De Vore
di Gurun Kalahari, Afrika. Mereka berbulan-bulan mengikuti perpindahan suku
Kung Bushman yang nomaden dan merekam semua benda yang ditinggalkan di
perkemahan-perkemahan mereka.
Kajian-kajian etnoarkeologi di Indonesia yang kurang rinci dan tidak didasari
permasalah arkeologi membuktikan banyak peneliti etnoarkeologi yang kurang
memahami kedudukan kajian etnoarkeologi dalam epistemologi arkeologi. Akibatnya,
tidak jarang terjadi kerancuan dalam cara pikir kajian-kajian tersebut (Tanudirjo,
1987). Barangkali, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa etnoarkeologi didasarkan pada
penalaran analogi, sehingga disebut “analogi etnografi”. Sesungguhnya, analogi tidak
dapat menjadi bukti nyata dari hipotesis arkeologis. Analogi adalah penyimpulan
yang hanya didasari oleh elaborasi atau perluasan pikir karena adanya unsur-unsur
yang sama. Cara pikir ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
A = C1, ...., C3, C4, C5, …, C7, .…, C9, C10
E = C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 Maka, A = E
“A” adalah data arkeologi, dan “E” adalah data etnografi. Jadi, jika sejumlah
ciri data arkeologi sama dengan ciri data etnografi, maka dianggap budaya di balik data
arkeologi sama dengan budaya etnografi. Di sini, data etnografi mengisi ciri-ciri data
arkeologi yang hilang, sehingga secara keseluruhan seakan-akan sama dengan data
etnografi. Ciri-ciri yang ditambahkan oleh data etnografi (C2, C6, C8) hanya tafsiran,
tidak nyata tetapi hanya merupakan perluasan pikir saja. Karena itu, bandingan data
etnografi tidak dapat menjadi bukti nyata. Ia hanya merupakan suatu kemungkinan
(probabilitas) saja. Semakin banyak ciri-ciri yang sama, maka kemungkinan kesamaan
6 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
antara data arkeologi dengan data etnografi semakin tinggi. Contoh gambar berikut ini
mungkin dapat memberikan ilustrasi tentang analogi secara lebih jelas.
1 2 3
Data Etnografi Data arkeologi yang ditemukan “asli-nya”
Benda etnografis (gambar ujung kiri) merupakan model yang “utuh”,
memiliki semua atribut secara lengkap. Model ini menjadi analog bagi benda arkeologis
yang ditemukan. Artinya, benda-benda arkeologi yang ditemukan diasumsikan sama
dengan benda etnografis. Namun, ini hanyalah perluasan pikir saja, bukan pembuktian.
Semakin tinggi kesamaan atribut semakin tinggi kemungkinan (probabilitas) bahwa
benda arkeologis akan sama dengan benda etnografis. Benda Arkeologis 1 memiliki
hanya sebagian atribut, sehingga kemungkinan (probabilitas) asumsi tadi benar kecil.
Sementara itu, pada Benda Arkeologis 2 dengan kesamaan atribut 50 % dan Benda
Arkeologis 3 yang memiliki kesamaan atribut lebih dari 80 % dibanding benda
etnografis, tingkat kebenaran asumsi itu semakin besar. Namun, karena sebagian
atribut benda arkeologis telah hilang selamanya, maka sesungguhnya etnoarkeologi
(analogi etnografi) tidak akan pernah dapat memberikan bukti nyata bahwa benda
arkeologi itu sama dengan benda etnografi. Karena bisa saja, atribut yang sudah tidak
ada itu justru menjadi pembeda yang signifikan. Hal ini dapat dicontohkan dengan
melihat pada “benda aslinya” atau benda arkeologi jika utuh, yang ternyata berbeda
dengan benda etnografis. Jadi, cukup jelas bahwa etnoarkeologi tidak dapat menjadi
bukti yang memastikan bahwa fenomena arkeologi akan sama dengan yang dapat
diamati di masa kini (etnografi).
Dari ilustrasi di atas, dapat dimengerti bahwa analogi tidak memberikan
bukti nyata. Dengan dasar itu, ada tingkat-tingkat keabsahan tertentu dari penelitian
etnografi bagi arkeologi (etnoarkeologi). Hayden (1993) menyebutkan setidaknya
ada empat tingkatan berdasarkan kekuatan hasil penyimpulannya dan kemudahan
penerapannya. Kedua variabel ini saling bertolak belakang (Lihat Diagram 2).
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 7
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Diagram 2 Jenjang Analogi sesuai dengan Potensi Penerapan
dan Tingkat Kepastian masing
Anggapan Umum
Analogi Umum
Analogi Prinsip
(Analogi Budaya Sintetis)
Kesinambungan Sejarah
Potensi Penerapan Tingkat Kepastian
● Tingkat pertama adalah analogi anggapan umum (common sense analogy).
Di sini yang difungsikan sebagai data etnografi adalah pemikiran atau
logika umum yang kita punyai saat ini. Misalnya, anggapan semua
tombak berfungsi sama dalam komunitas pemburu. Baik mata tombak
dari batu, bambu atau logam dianggap seolah sama saja, sehingga peneliti
bisa saja menyimpulkan kehidupan berburu pada Kala Plestosen sama
dengan cara berburu masyarakat tradisional di masa kini yang sudah
menggunakan matapanah dari logam. Atau, analogi yang didasarkan
anggapan umum (yang tidak selalu benar) bahwa bangunan megalitik
selalu terkait dengan pemujaan nenek moyang, sehingga analogi hanya
ada pada ranah religi saja tidak meluas ke aspek hubungan sosial politik.
Aplikasi analogi tingkat ini memang sangat luas dan mudah, karena
hanya dilandasi prinsip-prinsip umum. Namun, dari segi epistemologi,
merupakan pembuktian yang amat sangat lemah.
● Tingkat kedua adalah analogi umum (general analogy) yang menggunakan
data etnografi di sembarang tempat dan waktu untuk menjelaskan data
arkeologi. Karena itu, bisa saja data etnografi di Eskimo saat ini (sudah
ada modernisasi) digunakan untuk menjelaskan fungsi alat yang sejenis
tetapi ditemukan di daerah tropis pada situs Masa Bercocoktanam. Di
8 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
sini setidaknya ada anggapan bentuk yang sama memiliki fungsi dan
cara pemakaian yang sama. Dari segi argumentasi, cara analogi ini lebih
kuat dibanding tingkat sebelumnya, tetapi tetap saja kurang kuat karena
ciri-ciri yang dibandingkan masih terlalu umum. Karena sifatnya masih
umum, analogi ini masih dapat diterapkan secara cukup luas.
● Tingkat ketiga adalah analogi berdasarkan prinsip (analogy from principle).
Pada tingkat ini analogi didasarkan model yang dapat dikembangkan dari
data etnografi. Model ini dimaksudkan untuk merekam aspek tertentu
dari budaya secara khusus, sehingga diperoleh prinsip-prinsip tentang
aspek budaya tersebut agar mampu menjelaskan fenomena masa lampau
(arkeologi). Misalnya, bagaimana pertukaran barang atau perdagangan
tradisional dapat mempengaruhi persebaran jenis artefak tertentu. Atau,
bagaimana proses pembuatan hingga penggunaan alat batu dapat dilihat
dari variasi bentuk alat batu yang dihasilkan. Etnoarkeologi yang benar
semestinya mencapai taraf ini, yaitu menciptakan model-model etnografi
untuk menjadi analogi bagi arkeologi. Karena sifatnya yang sudah agak
khusus, maka penerapan analogi itu menjadi lebih terbatas. Namun, dari
sebagai perangkat argumentasi, analogi ini sudah cukup kuat. Kesamaan
antara data etnografi dan arkeologi diperhatikan benar dan bahkan
menjadi salah satu fokus dalam penelitian.
● Tingkat keempat adalah analogi dengan kesinambungan budaya (direct
historical approach). Pada tingkat ini disyaratkan ada keterkaitan sejarah
antara data etnografi dengan data arkeologi. Karena itu, analogi ini paling
terbatas dalam aplikasinya, tetapi paling kuat untuk menjadi argumentasi.
Asumsinya, jika ada keterkaitan sejarah, maka sudah pasti banyak unsur-
unsur budaya yang masih sama antara budaya etnografi dengan arkeologi.
Contohnya, untuk rekonstruksi sisa-sisa kampung megalitik yang
sudah ditinggalkan di Nias atau Sumba, dapat digunakan data etnografi
kampung orang Nias atau Sumba tradisional yang sekarang masih ada.
Atau, untuk menjelaskan pola permukiman Majapahit dapat digunakan
data etnografi dari Bali. Secara epistemologis, analogi itu sangat kuat
karena dari sejarahnya masyarakat Bali sangat dekat Kerajaan Majapahit
dan mempunyai kesamaan latar keagamaannya.
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 9
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Model etnografis yang diperoleh di Bali, dapat juga dipakai untuk
menjelaskan fenomena arkeologi tinggalan Jaman Mataram Hindu di Jawa
Tengah. Dalam hal ini, kekuatan argumentasinya memang sedikit lebih
lemah karena hubungan sejarah keduanya sudah menjauh. Analogi semacam
ini disebut analogi budaya sintetis (synthetic culture analogy) yang tingkat
kesahihannya berada di bawah analogi kesinambungan sejarah.
Kedudukan kajian etnoarkeologi dalam upaya menjelaskan masa lampau
atau memecahkan persoalan arkeologi memang tidak lepas dari perdebatan sengit.
Debat ini tentu saja terkait dengan paradigma keilmuan yang mengalami perubahan
sejalan dengan perkembangan Arkeologi sendiri, terutama Arkeologi Prosesual
(Pembaharuan) dan Arkeologi pasca-Prosesual (Interpretif).
Bagi Arkeologi Prosesual, data arkeologi adalah fenomena masa kini, benda
mati yang statis, dan tidak memuat informasi apa pun. Ia tidak bisa menceritakan
masa lalu, walaupun ia mengalaminya. Karena itu, tugas arkeologi adalah mencoba
menemukan proses budaya yang menghasilkan benda-benda tersebut. Penjelasan itu
akan diperoleh jika ada teori, dalil, dan model yang dapat memberikan acuan awal.
Teori, dalil, dan model itu yang kemudian diujikan secara deduktif untuk menentukan
tingkat kebenarannya. Dengan paradigma seperti itu, kajian etnoarkeologi tentunya
ditempatkan sebagai penelitian yang menghasilkan teori, dalil atau model bagi
penjelasan. Atau, menurut Binford (1983), kajian ini merupakan teori tingkat
menengah (middle-range theory), karena etnoarkeologi dapat menyediakan data
yang menjembatani secara langsung antara yang statis (benda budayawi) dan yang
dinamis (tindakan dan gagasan). Dengan kata lain, data etnografi dapat menolong ahli
arkeologi menjelaskan fenomena masa lampau yang terkait dengan benda arkeologi.
Di sini, terdapat asumsi uniformitarian yang menyatakan bahwa proses-proses yang
terjadi di masa lampau pada prinsipnya tidak berbeda dengan yang terjadi di masa
kini. Binford (1983a) menuliskan secara puitis “letting the present serves the past”
(biarlah masa kini melayani masa lampau). Artinya, melalui kajian etnoarkeologi,
seorang aghli arkeologi akan dapat memiliki praduga atau kemungkinan awal (prior-
probability) tentang masa lampau. Tentu saja, untuk mengetahui apakah praduga
tersebut benar, maka harus diujikan lagi pada data arkeologinya. Dengan demikian,
bagi Arkeologi Prosesual, etnoarkeologi menjadi wadah untuk mendapatkan model
maupun menguji model itu pada data arkeologi.
10 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Di sisi yang lain, paradigma Arkeologi Pasca-Prosesual melihat bahwa
paradigma Arkeologi Prosesual yang menganggap dapat menemukan pengetahuan
tentang masa lalu dengan penelitian yang bersifat deduksi melalui penerapan teori-
dalil-model sebagai langkah yang keliru. Bagi Arkeologi Pasca-Prosesual, budaya
bendawi pada setiap tahapan sejarahnya selalu mengalami perubahan. Mereka
menganggap budaya bersifat khas dan tergantung pada sejarah, bahkan setiap orang
memberikan warna pada budaya itu. Karena itu, budaya harus dipahami secara
kontekstual dan bukan melalui kajian silang budaya yang didasari kerangka pikir
uniformitarian. Arkeologi harus tetap bersifat interpretif dan tidak perlu terbawa pada
cara-cara penalaran saintifik sebagaimana yang disarankan Arkeologi Prosesual (lihat
Hodder, 1999; Hodder dan Hutson, 2003; Tilley, 1993; Renfrew dan Bahn, 2004).
Dengan dasar pemikiran tersebut, mereka memilih memahami masa lampau
dengan cara-cara hermeneutik yang merupakan proses dialektika antara kerangka
pikir dan pengetahuan peneliti dengan data atau fenomena yang mereka teliti. Mereka
melihat data arkeologi sebagai teks yang harus dibaca (Shank dan Hodder, 1995;
Shank dan Tilley, 1987). Dalam kerangka pikir pendukung Arkeologi pasca-Prosesual,
etnoarkeologi tidak terlalu banyak membantu, apalagi jika diperlakukan sebagai teori,
dalil, atau model yang harus diujikan pada data arkeologi. Generalisasi hubungan
antara yang statis dan dinamis, seperti diterapkan dalam etnoarkeologi, tidak akan
mampu mengungkapkan makna data arkeologi dalam konteks-nya di masa lampau.
Etnoarkeologi dianggap hanya dapat membantu melacak sejarah budaya masyarakat
tertentu (direct-historical analogy), tetapi tidak untuk menjadi sumber teori, dalil, atau
model yang dapat diterapkan secara silang budaya (general analogy). Dalam konteks,
proses hermeneutika mungkin saja pendekatan etnoarkeologi dapat digunakan, tetapi
kedudukannya sebagai tambahan pengetahuan yang dapat memperkaya peneliti untuk
memahami masa lampau. Etnoarkeologi mungkin cukup berguna untuk menjelaskan
proses transformasi alam atau N-tranform (Schiffer, 1987), karena sifat fenomena
alam yang cenderung uniformitarian. Namun, etnoarkeologi akan cukup sulit untuk
menjelaskan transformasi budaya atau C-tranform (Schiffer, 1987), karena proses
budaya itu khusus, melibatkan peran pribadi manusia yang kreatif dan ikut ditentukan
oleh sejarah dan konteks yang dihadapi. Keadaan ini yang mengurangi peran
etnoarkeologi untuk dipakai sebagai sumber teori, dalil atau pun model (Hodder,
1999).
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 11
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Dengan memahami lebih baik kedudukan etnoarkeologi dalam konteks
Arkeologi, sebagaimana dipaparkan di atas, tentunya ada harapan bahwa para peneliti
etnoarkeologi dapat memikirkan kembali arah dan tujuan dari penelitian yang hendak
dilakukannya. Perlu ada kesadaran yang lebih baik tentang kedudukan etnoarkeologi
dalam epistemologi arkeologi. Jika tidak, mungkin sekali penelitian-penelitian
etnoarkeologi yang dilakukan tidak akan banyak membawa manfaat dan mubazir. Di
samping itu, kesadaran itu juga akan membuka pikiran para peneliti dan pengguna
hasil penelitian etnoarkeologi untuk lebih berpikir kritis untuk menempatkan hasil
penelitian itu dalam mengungkap masa lampau. Hendaknya, anggapan lama yang
melihat kajian etnoarkeologi seakan menjadi pembuktian terhadap tafsiran tentang
masa lampau dapat terkikis. Penelitian Etnoarkeologi bukan cara memperoleh
kebenaran tentang masa lampau, tetapi lebih merupakan upaya meningkatkan
keyakinan terhadap fenomena yang mungkin terjadi di masa lampau. Pemahaman ini
dapat menghindarkan kita dari kesalahan mendaku seakan kita telah “menemukan”
masa lampau itu. Barangkali, etnoarkeologi lebih tepat didudukkan sebagai salah satu
saluran atau jembatan yang dapat memfasilitasi arus dialektika antara kerangka pikir
(pengetahuan) dan data (empiris) dalam proses hermeneutika.
Kesimpulan
Sebagai catatan akhir, pada saat wacana tentang etnoarkeologi di Indonesia
masih belum mendapat kepedulian yang layak, dalam kancah Arkeologi dunia kini
telah muncul wacana baru yang mengaitkan antara etnografi dan arkeologi. Wacana
yang dimaksud adalah etnografi arkeologis (archaeological ethnography). Meskipun
istilah ini pernah hadir sebagai bagian dari kajian etnoarkeologi (lihat David dan
Kramer, 2001; Meskell, 2005), namun istilah tersebut kini mendapat pemaknaan yang
baru. Etnografi arkeologi bukan lagi dimaknai sebagai data etnografi yang berguna
sebagai pembanding (analogi) bagi data arkeologi, tetapi lebih diberi makna sebagai
“etnografi tentang komunitas arkeologi”. Etnografi arkeologi merupakan paparan
tentang kerangka pikir, tingkah laku, dan cara “kehidupan” para pelaku arkeologi.
Bahkan, bagi para ahli arkeologi sendiri, etnografi arkeologi disebut sebagai “etnografi
tentang kita” (ethnography of us). Wacana ini muncul sebagai bagian dari refleksi
para pelaku arkeologi.
12 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Etnografi arkeologi adalah penelitian refleksif yang mencoba menggambarkan
proses dan pengaruh kerja para pelaku arkeologi dalam masyarakat. Hal ini terkait
erat dengan semakin aktifnya arkeologi terlibat dalam kegiatan “memberdayakan”
masyarakat, ikut mempengaruhi struktur kekuasaan, dan memberikan makna baru
warisan budaya dalam masyarakat masa kini (Meskell, 2005).
Pada intinya, etnografi arkeologi adalah upaya menggambarkan segala
aktivitas dan gagasan arkeologi yang berupaya menghadirkan masa lampau (arkeologi)
dalam konteks kehidupan masyarakat masa kini (etnografi). Salah satu pertanyaan
yang penting dalam etnografi arkeologi adalah apa dan bagaimana peran arkeologi
bagi masyarakat masa kini ? Pertanyaan refleksif ini, memang perlu direnungkan dan
dijawab, terutama bagi para peneliti dan lembaga penelitian arkeologi. Sudahkan,
para peneliti dan penelitian arkeologi di Indonesia memberikan sumbangan yang
berarti dan nyata bagi kehidupan masyarakat kita ? Untuk menjawab pertanyaannya
ini, barangkali perlu dilakukan rintisan penelitian etnografi arkeologi di Indonesia.
Siapa mau mulai ?
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 13
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
DAFTAR PUSTAKA
Bahn, P. dan J. Vertut. 1988. Images of the Ice Age. Fact on File, New York – Oxford.
Binford, L.R. 1983. In Pursuit of the Past : Decoding the archaeological record.
New York: Academic Press.
Binford, L.R. 1983a. Working at Archaeology. New York: Academic Press.
David, N. dan C. Kramer. 2001. Ethnoarchaeology in Action. Cambridge: Cambridge
World Archaeology.
Gould, R. dan M.B. Schiffer (eds.). 1981. Modern Material Culture: The Archaeology
of Us. New York: Academic Press.
Hayden, B. 1992. Archaeology: the Science of Once and Future Things. New York:
W.H. Freeman and Company.
Hodder, I dan S. Hutson. 2003. Reading the Past. 3rd edition. Cambridge: Cambridge
University Press.
Hodder, I. 1999. The Archaeological Process: An Introduction. London: Blackwell.
Kramer, C. 1979. Introduction, dalam C. Kramer (ed.), Ethnoarchaeology:
Implications of Ethnography for Archaeology. New York: Columbia
University Press. Hlm. 1 -7.
LaMotta, V.M. dan M.B. Schiffer. 2001. Behavioral Archaeology: Toward a New
Synthesis, dalam I. Hodder (ed.), Archaeological Theory Today. London:
Blackwell. Hlm. 14 – 64.
Meehan, B. 1982. Shell Bed to Shell Midden. Canberra: Australian Institute of
Aboriginal Studies.
Meskell, L. 2005. Archaeological Ethnography: Conversations around Kruger
National Park, Archaeologies, Vol. 1 no. 1 August 2005.
Rathje, W.L. 1978. Archaeological Ethnography: because sometimes it is better to give
than to receive, dalam R.A. Gould (ed.), Exploration in Ethnoarchaeology.
Albuquerque: University of Mexico. Hlm. 49 – 76
14 Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009
Daud Aris Tanudirjo, Memikirkan Kembali Etnoarkeologi
Reid, J. 1995. Four Strategies after Twenty Years: A Return to Basics, dalam J.M.
Skibo, W.H. Walker, dan A.E. Nielsen (eds.) Expanding Archaeology. Salt
Lake City: University of Utah Press. Hlm. 15 – 21
Renfrew, C. dan P.Bahn. 2004. Archaeology: Theories, Methods, dan Practice. 4th
edition. London: Thames and Hudson.
Schiffer, M. B. 1987. Formation Processes of the Archaeological Record. Albuquerque:
University of New Mexico Press.
Schiffer, M.B. 1978. Methodological Issues in Ethnoarchaeology, dalam R.A. Gould
(ed.), Exploration in Ethnoarchaeology. Albuquerque: University of Mexico.
Hlm. 229 – 248.
Shanks, M dan C. Tilley. 1987. Re-Constructing Archaeology. Cambridge: Cambridge
University Press.
Shanks, M dan I. Hodder. 1995. Prosesual, post-Prosesual, and Interpretive
Arcaheology, dalam I. Hodder et al. (eds.), Interpeting Archaeology. London:
Routledge. Hlm. 3 – 29
Tanudirjo, D. 1987. Penerapan Etnoarkeologi di Indonesia. Laporan Penelitian.
Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
Tilley, C. 1993. Interpretation and a Poetics of the Past, dalam C. Tilley (ed.)
Interpretive Archaeology. Berg, Providence. Hlm. 1 – 27.
Papua Vol. 1 No. 2 / November 2009 15
Anda mungkin juga menyukai
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- EtnoarkeologiDokumen1 halamanEtnoarkeologiahmadyantirtaBelum ada peringkat
- Bahan Kuliah EtnoarkeologiDokumen14 halamanBahan Kuliah EtnoarkeologiMuhamad AwaluddinBelum ada peringkat
- 121-Article Text-235-1-10-20170601Dokumen13 halaman121-Article Text-235-1-10-20170601Dalila AdilahBelum ada peringkat
- Bahan Ajar Kelas XI IBBDokumen6 halamanBahan Ajar Kelas XI IBBdeysi ria tangianBelum ada peringkat
- Konsep Dasar Etnografi-1Dokumen15 halamanKonsep Dasar Etnografi-1Reesa Adib Tria AgustienBelum ada peringkat
- KONSEP ETNOGRAFI - AntropologiXIDokumen8 halamanKONSEP ETNOGRAFI - AntropologiXIGita Bintang AuliaBelum ada peringkat
- Etnografi IndonesiaDokumen3 halamanEtnografi IndonesiaYansen Pratama KoharBelum ada peringkat
- Tugas Presentasi Agama Bab 2 Kelompok 2Dokumen29 halamanTugas Presentasi Agama Bab 2 Kelompok 2sarah koiburBelum ada peringkat
- Peranan Arkeolog Dalam Ilmu SejarahDokumen6 halamanPeranan Arkeolog Dalam Ilmu Sejarahfidyawati pomontoloBelum ada peringkat
- Bab IDokumen19 halamanBab IKhusna AnantaBelum ada peringkat
- Perkembangan Antropologi RmaDokumen36 halamanPerkembangan Antropologi RmaSantriWatiBelum ada peringkat
- Arkeologi Di Masa LaluDokumen1 halamanArkeologi Di Masa Laluphtrxx HxxpitzBelum ada peringkat
- Nama: Fadjrul Maulana Kelas: A2 Manajemen Matkul: Etnografi Papua & Keyapisan Dosen: H, Syafruddin Daerlan, Se.,M.Si NPM: 18-111-123Dokumen11 halamanNama: Fadjrul Maulana Kelas: A2 Manajemen Matkul: Etnografi Papua & Keyapisan Dosen: H, Syafruddin Daerlan, Se.,M.Si NPM: 18-111-123maulanaBelum ada peringkat
- ANTROPOLOGIDokumen21 halamanANTROPOLOGIberak diaerBelum ada peringkat
- Bahan Presentasi Etnografi (Repaired)Dokumen26 halamanBahan Presentasi Etnografi (Repaired)NurHilaliahAkisBelum ada peringkat
- Etno Ke-1-1Dokumen57 halamanEtno Ke-1-1Indri ayuBelum ada peringkat
- Etnografi DokumenDokumen2 halamanEtnografi Dokumensf.taniaaBelum ada peringkat
- Bab Xii Penger - Perkem & Pembag.Dokumen61 halamanBab Xii Penger - Perkem & Pembag.Nezar AbdillahBelum ada peringkat
- Arkeologi Dan Etnografi Kalumpang PDFDokumen142 halamanArkeologi Dan Etnografi Kalumpang PDFMuhammad Nur IkhsanBelum ada peringkat
- EtnografiDokumen16 halamanEtnografijani lojiBelum ada peringkat
- Makalah EtnografiDokumen11 halamanMakalah EtnografiDintia Zarkasih75% (4)
- Hubungan Arkeologi Dengan Ilmu Sosial LainnyaDokumen7 halamanHubungan Arkeologi Dengan Ilmu Sosial LainnyaTita NurhayatiBelum ada peringkat
- Teori-Teori Anro FattDokumen4 halamanTeori-Teori Anro FattSiti Fatma BabaBelum ada peringkat
- Makalah Penelitian EtnografiDokumen24 halamanMakalah Penelitian EtnografiDesy Aprima82% (11)
- Makalah ETNOGRAFI ISSUN NEWDokumen7 halamanMakalah ETNOGRAFI ISSUN NEWIrna IrawanBelum ada peringkat
- Etnografi Dan PerkembanganDokumen14 halamanEtnografi Dan PerkembanganIkra Negara Andi Balo100% (1)
- Modul Antropologi Budaya - CompressedDokumen72 halamanModul Antropologi Budaya - CompressedBahri ZalBelum ada peringkat
- Etnografi Masyarakat Gunung Kawi Kabupaten MalangDokumen19 halamanEtnografi Masyarakat Gunung Kawi Kabupaten Malangfathin furoidahBelum ada peringkat
- Tugas Review BukuDokumen34 halamanTugas Review BukuRatna Andita FakihBelum ada peringkat
- Percabangan Antropologi Dan Antropologi Terapan 0leh: TONI SETIAWAN 2001113 Nurhasanah 2001234 Zuhri Aulia 2001114Dokumen10 halamanPercabangan Antropologi Dan Antropologi Terapan 0leh: TONI SETIAWAN 2001113 Nurhasanah 2001234 Zuhri Aulia 2001114Dinesh johnBelum ada peringkat
- Dokumen Etnografi PapuaDokumen6 halamanDokumen Etnografi Papuavia resaBelum ada peringkat
- 4463 13545 1 PBDokumen18 halaman4463 13545 1 PBSoloBelum ada peringkat
- Fiz RDokumen20 halamanFiz RajisugaradaviBelum ada peringkat
- Makalah AntropologiDokumen6 halamanMakalah Antropologiandys4sBelum ada peringkat
- Antropologi SosialDokumen21 halamanAntropologi SosialNadya PutriBelum ada peringkat
- ETNOGRAFIDokumen12 halamanETNOGRAFIPuspa KanahayaBelum ada peringkat
- CBR Dan CJR Antropobiologi Kelompok 7Dokumen21 halamanCBR Dan CJR Antropobiologi Kelompok 7Ummu AfifahBelum ada peringkat
- Antropologi Modul 2 Metode Etnografi KB 1Dokumen22 halamanAntropologi Modul 2 Metode Etnografi KB 1Winda TobingBelum ada peringkat
- 1 Pengantar Antropologi SosialDokumen21 halaman1 Pengantar Antropologi SosialadhitBelum ada peringkat
- Makalah Admin Revisi 2Dokumen8 halamanMakalah Admin Revisi 2Riyanti yanBelum ada peringkat
- Etnografi Dan Etnografi VirtualDokumen25 halamanEtnografi Dan Etnografi VirtualNatasha ElizabethBelum ada peringkat
- Kelompok 5 EtnografiDokumen11 halamanKelompok 5 EtnografiFarrij Andika RohmanBelum ada peringkat
- Ciri Khas Metode Lapangan EtnografiDokumen8 halamanCiri Khas Metode Lapangan Etnografigustyn ningrumBelum ada peringkat
- Materi Inisiasi 1Dokumen8 halamanMateri Inisiasi 1Dinas Lingkungan Hidup Kota BitungBelum ada peringkat
- ARTEFAKDokumen14 halamanARTEFAKRey bellichyaBelum ada peringkat
- KesehatanDokumen21 halamanKesehatanniaBelum ada peringkat
- ETNOGRAFIDokumen16 halamanETNOGRAFIdiah rahajengBelum ada peringkat
- Makalah Antropologi KelompokDokumen13 halamanMakalah Antropologi KelompokVera TuasikalBelum ada peringkat
- Teori Kebudayaan - Etnografi Dan Religi - KEL 3-1Dokumen14 halamanTeori Kebudayaan - Etnografi Dan Religi - KEL 3-1RizkyBelum ada peringkat
- Studi EtnografiDokumen23 halamanStudi EtnografiAbner Krey Koibur100% (1)
- PB TorajaDokumen12 halamanPB TorajaCandi wisesaBelum ada peringkat
- Pengantar AntropologiDokumen5 halamanPengantar AntropologiDyah Rumaisha Nurul AiniBelum ada peringkat
- Antrop 1-7Dokumen102 halamanAntrop 1-7Herpina RiantikaBelum ada peringkat
- Diktat Etnografi PapuaDokumen68 halamanDiktat Etnografi PapuaAlisya KarubuyBelum ada peringkat
- Slide Pengantar Antrop 2023Dokumen37 halamanSlide Pengantar Antrop 2023Rifky FadillahBelum ada peringkat
- ETNOGRAFIDokumen30 halamanETNOGRAFImaulidaBelum ada peringkat
- Pengantar ETHNOMUSICOLOGY 1-2Dokumen22 halamanPengantar ETHNOMUSICOLOGY 1-2Markus SiraitBelum ada peringkat
- Pengertian Dan Ruang Lingkup Antropologi SeniDokumen16 halamanPengertian Dan Ruang Lingkup Antropologi SeniAndiPandi0% (1)
- Ethografi Dan EtnometodologiDokumen13 halamanEthografi Dan EtnometodologiUllaIbanezBelum ada peringkat
- 3296 8682 2 PBDokumen14 halaman3296 8682 2 PBLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- Estetika Dan AbstrakDokumen16 halamanEstetika Dan AbstrakLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- 25 12675 1 SMDokumen11 halaman25 12675 1 SMRoib SantosoBelum ada peringkat
- Adegan Dan Ajaran Hukum Karma Pada Relief KarmawibhanggaDokumen129 halamanAdegan Dan Ajaran Hukum Karma Pada Relief KarmawibhanggaLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- 1029 1929 1 SMDokumen11 halaman1029 1929 1 SMLalu Muh Balia Farsahin100% (1)
- Statistik Dan Spasial Kecamatan Praya Timur 2019 IDokumen154 halamanStatistik Dan Spasial Kecamatan Praya Timur 2019 ILalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- Kluster Penelitian Dasar InterdisiplinerDokumen79 halamanKluster Penelitian Dasar InterdisiplinerLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- 25 4176 1 SMDokumen14 halaman25 4176 1 SMLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- 25 4276 1 SMDokumen11 halaman25 4276 1 SMLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- 210 621 2 PB PDFDokumen12 halaman210 621 2 PB PDFLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- Formulir Pendaftaran Cagar Budaya 1Dokumen4 halamanFormulir Pendaftaran Cagar Budaya 1Lalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat
- Aneka Warna Masyarakat Dan KebudayaanDokumen22 halamanAneka Warna Masyarakat Dan KebudayaanLalu Muh Balia FarsahinBelum ada peringkat