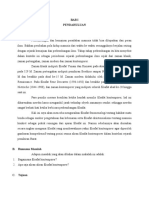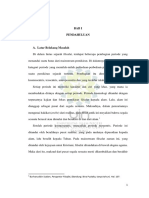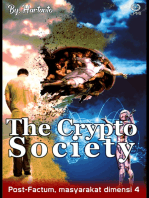Dekonstruksi
Diunggah oleh
Irene Rajagukguk0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
37 tayangan6 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
37 tayangan6 halamanDekonstruksi
Diunggah oleh
Irene RajagukgukHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 6
NAMA : IRENE RAJAGUKGUK
NIM : 50190059
MATA KULIAH : FILSAFAT ILMU
DOSEN PENGAMPU : Pdt. WAHJU S. WIBOWO, M.Hum, Ph.D
DEKONSTRUKSI
Dari Modernisme ke Postmodernisme
“Modernisme” di bidang filsafat dapat diartikan sebagai gerakan pemikiran dan gambaran dunia
tertentu yang awalnya diinspirasikan oleh Descartes, kemudian dikokohkan oleh gerakan Pencerahan dan
pada akhirnya mengabdikan diri hingga abad ke-20 melalui dominasi sains dan kapitalisme. Dari sudut
pandang filsafat, modernisme memiliki karakter khas yaitu selalu berusaha mencari dasar segala pengetahuan
(epistemé, Wissenschaft) tentang “apa” nya (ta onta) realitas, dengan cara kembali ke subjek yang
mengetahui itu sendiri (dapat dipahami secara psikologis maupun transendental). Filsafat memang berpusat
pada Epistemologi dalam modernisme. Maksudnya ialah epistelmologi yang bersandar pada gagasan tentang
subjektivitas dan objektivitas murni yang saling terpisah dan tak saling berkaitan satu sama lain.
Namun, terdapat banyak konsekuensi yang dihasilkan oleh gerakan modernisme tersebut khususnya
terhadap kehidupan manusia dan alam. I. Bambang Sugiharto dalam bukunya yang berjudul
“Postmodernisme, Tantangan bagi Filsafat” menuliskan bahwa ada 6 konsekuensi dari gambaran dunia dan
tatanan sosial yang dihasilkan oleh modernisme, yaitu: (1) krisis ekologi; (2) masyarakat cenderung menjadi
tidak manusiawi; (3) timbulnya disorientasi moral-religius yang menyebabkan meningkatnya kekerasan,
keterasingan, dan depresi mental; (4) dominasi materialisme yang menyebabkan persaingan ketat; (5)
militerisme yang dilegitimasi oleh agama; dan (6) kebangkitan Tribalisme kembali (mentalitas yang
mengunggulkan suku atau kelompok sendiri).
Kondisi dunia dengan segala konsekuensi negatif seperti pada paragraf di atas kemudian mendorong
munculnya gerakan postmodern yang bertujuan untuk merevisi paradigma modern dan juga sebagai alat
bantu untuk melihat berbagai gerakan yang ada secara lebih jernih dan global saja. Adanya klaim-klaim dari
kaum postmodernis tentang berakhirnya “modernisme” pada hakikatnya menunjukkan berakhirnya anggapan
modern tentang “subjek” dan “dunia objektif”. Lalu postmodernisme dipahami sebagai upaya-upaya untuk
mengungkapkan segala konsekuensi dan berakhirya modernisme beserta metafisika tentang fondasionalisme
dan representasionalismenya. Tidak ada yang dapat memastikan tentang kapan awal dari tumbangnya
modernisme di bidang filsafat. Bagi pihak poststrukturalis, modernisme sudah berakhir sejak serangan-
serangan awal atas fenomenologi yang dianggap semacam titik kulminasi dari Humanisme. Di lain pihak
bagi dunia yang berbahasa Inggris, modernisme tumbang bersama dengan munculnya “filsafat Post-analitik”.
Sedangkan di benua Eropa, modernisme sudah terlebih dahulu berakhir bahkan konon sejak Nietzsche
mengadakan kritik dekonstruktif atas tradisi metafisik-platonik.
Tumbangnya modernisme justru diyakinkan sejak awalnya pada saat Fenomenologi oleh Edmund
Husserl muncul dan menjadi terkenal. Karya Husserl yang menjadi teks kunci dalam hal ini adalah The Idea
of Phenomenology. Dalam karyanya itu, Husserl mencoba mengatasi persoalan subjek-objek dengan cara
membongkar secara efektif paham tentang “subjek epistemologis” dan “dunia objektif”. Namun karena
Husserl yang terlalu ambisi untuk menjadikan filsafat sebagai ilmu keras dengan logika ketat (strenge
Wissenschaft), justru malah yang terjadi Husserl mengakhirinya dan membawa dampak ambigu dalam
karyanya. Sehingga ketika Derida menyinggung tentang hal dalam mengkritik metafisik klasik fenomenologi
justru menjalankan proyek terdasar metafisika. Maksudnya ialah bahwa secara hermeneutik akan lebih baik
jika kita mengatakan fenomenologi Hsserl justru menghasilkan kritik yang memporakporandakan metafisika
itu ketika Husserl dalam upaya mewujudkan proyek terdasar metafisikanya itu. Konsekuensi radikal dari
upaya Husserl untuk menjadikan filsafat sebagai ilmu keras (rigorius science) telah dirumuskan oleh
Gadamer dengan menyatakan bahwa pemikiran filosofis sama sekali bukanlah ilmu, bahkan tidak ada klaim
tentang pengetahuan definitif kecuali satu yaitu pengakuan atas keterbatasan manusia itu sendiri.
Dengan adanya pemikiran dasar seperti di atas maka timbullah beberapa konsekuensi, yang diantaranya
ialah munculnya pertanyaan tentang bagaimana nasib upaya-upaya ilmiah–filosofis yang berusaha
mengungkapkan “kebenaran objektif hal-hal”, jika segala teoretisasi ilmiah hanyalah soal idealisasi dan
penafsiran pengalaman prailmiah? Haruskah Epistemologi sebagai disiplin ilmu yang diharapkan dapat
menjamin kebenaran objektif setiap ilmu dan wacana (discoursei) manusia kemudian mengalami
pendiskreditan? Dengan kehadiran Hermeneutika, lalu apakah segala hal menjadi soal penafsiran belaka?
Dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang demikian, justru mengindikasikan bahwa pada titik
inilah terbuka jalan.kepada kedua hal berikut yakni: 1) ke arah pluralisme ekstrem yang membawa kepada
relativisme dan nihilisme (Derrida, Lyotard), dan 2) ke arah pentingnya Hermeneutika, yang membawa
segala persoalan kepada konsep “dialog”.
Peran Hermeneutik pada masa Postmodernisme
Hermeneutika bukanlah ilmu atau pun epistemologi. Maksudnya adalah jika ilmu yang dimaksudkan
dalam hal ini adalah seperti yang diartikan episteme modern, representasi “tepat” dari kenyataan “objektif”.
Atau jika dengan epistemologi diartikan disiplin teoretis yang kerjanya menentukan syarat-syarat epistemik
yang harus dipenuhi oleh tiap disiplin ilmu untuk dapat membuat klaim-klaim tentang kebenaran yang sah.
Hermeneutik merupakan penggalian reflektif terhadap keterbatasan setiapm klaim tentang pengetahuan dan
pemahaman atas relativitas kultural dan historis dari tiap bentuk wacana manusia. Dengan demikian, maka
hermeneutik juga dapat dikatakan sebagai penolakan atas ide tentang keterukuran universal. Atau dapat
dikatakan juga bahwa hermeneutika adalah bagian sentral dari gelombang penolakan postmodern atas filsafat
tradisional. Tidak cukup sampai pada tujuan untuk mengatasi objektivisme, hermeneutik juga berniat untuk
mengatasi relativisme dan nihilisme. Dalam hermeneutika jenis inilah implikasi fenomeonologi Husserl
menjadi lebih revolusioner dan bukannya destruktif bagi pihak postmodernisme.
Hermeneutik tidak bermaksud menolak gagasan tentang rasionalitas beserta dengan pretensi
universalnya tetapi justru hendak merekontruksi gagasan kita secara radikal tentang apa artinya bersikap
“rasional”. Yang disebut dengan “rasionalitas” bagi hermeneutika adalah sekedar merupakan cara tak
langsung untuk menunjuk pada linguistikalitas setiap pengalaman manusia. Artinya adalah bahwa manusia
dapat selalu menjembatani segala perbedaan melalui dialog yang mencari persetujuan dan pengertian
bersama, itupun apabila dikehendaki. Maka dalam kenyataannya tidak ada suatu bahasa ideal yang dapat
dijadikan tolok-ukur untuk segala wacana karena pemahaman manusia senantiasa memiliki keterbatasan dan
biasanya selalu beragam. Berbeda dengan kaum relativis dan kultural, Gadamer mengingatkan kita bahwa
meskipun tiap pemahaman sifatnya terikat kepada bahasa, sangat tidaklah pantas apabila kita harus jatuh ke
dalam relativisme. Malah perbedaan rasio menjadi sumber beragamnya bahasa sehingga memunculkan dialog
yang tidak terbatas dan terbuka ke arah kebenaran sejati kita.
Hermeneutik sebagai upaya kritis dan emansipatoris yang menjadi tugas utamanya, namun juga
bertugas merawat wacana manusia. Hanya melalui percakapan yang berkesinambunganlah pemahaman diri
baru dimungkinkan. Menurut Richard Rorty, percakapan adalah konteks terdasar yang memungkinkan
pengetahuan diapahami. Dengan demikian, kewajiban filsafat sebagai hermeneutika adalah mengulur dan
memajukan percakapan antarmanusia. Maka dengan cara seperti itu, sebenarnya hermeneutika tampil sebagai
penerus tradisi dialektika, tanpa menjadi nonPlatonik. Mengapa demikian? Karena oleh beberapa pihak
seperti Protogoras, para Sofis, dan Retorisi telah memperlakukan dialektika sebagai penolakan atas filsafat
yang bercorak menolong atau atas filsafat platonik yang menganggap diri sebagai persatuan antara roh
pribadi dengan esensi-esensi onjektif, ataupun atas wacana metafisik yang otoriter. Itulah alasannya mengapa
filsafat postmodern, secara khusus hermeneutika menganggap retorika bukan lawan dari dialektika.
Demikianlah retorika kemudian bangkit menjadi karakter kuat filsafat pada abad 20.
Postmodernisme dengan Dekonstruksi
Ada 3 hal pokok yang menjadi pokok persoalan yang dihadapi filsafat pada masa postmodernisme,
yaitu: (1) isu tentang “berakhirnya filsafat”; (2) pluralisme yang tak terelakkan dalam hal rasionalitas dan
permainan-bahasa, dan (3) kematian epistemologi.
Kemunculan istilah dekonstruksi dikaitkan dengan isu tentang berakhirnya filsafat. Hal itu sebenarnya
dipengaruhi oleh istilah yang pernah digunakan oleh Heidegger yang menyatakan bahwa kontruksi dalam
filsafat harus mengalami destruksi dengan sendirinya secara serentak, yaitu dengan adanya dekonstruksi
konsep-konsep tradisional dengan cara kembali ke tradisi. Di kemudian harinya istilah tersebut menjadi
populer melalui karya Jacques Derrida sehingga berkembang menjadi metode yang akhirnya melahirkan
klaim bahwa filsafat sudah saatnya harus berakhir.
Dekonstruksi dapat dipahami sebagai cara atau metode membaca teks. Dalam pembacaan dekonstruktif
terhadap teks-teks filosofis secara khusus melacak unsur-unsur yang secara filosofis sangatlah menentukan,
atau unsur yang menjadikan sebuah teks itu menjadi filosofis. Oleh karena itu, filsafat dilihat pertama-tama
sebagai tulisan. Maksudnya adalah bahwa sebagai tulisan, filsafat tidak pernah menjadi suatu ungkapan
transparan pemikiran secara langsung. Di situ pemikiran selalu mewujud dalam sistem-sistem tanda yang
berkarakter material, baik berupa substansi grafik maupun fonik (tinta ataupun bunyi). Dan sebenarnya tanda-
tanda yang digunakan itu telah digunakan pula dalam berbagai konteks lain.
Sebagai tulisan, filsafat lalu juga bersifat tekstual. Maksudnya, satuan makna primernya bukanlah kata
ataupun kalimat melainkan kumpulan kalimat-kalimat, sebuah teks, yang pada gilirannya ditentukan pula
maknanya oleh keterkaitannya dengan teks-teks. Konsekuensi teoretis dari kenyataan itu adalah bahwa
kemampuan filsafat untuk membuat klaim-klaim yang melampaui partikularitas bahasa tekstual tadi
diragukan. Artinya segala klaim yang dibuat filsafat itu sebetulnya sangat tergantung pada sistem makna
yang dimungkinkan oleh penggunaan sistem tanda secara tertentu. Konkretnya, misalnya gagasan-gagasan
yang dilawankan antara natur dan kultur, fakta dan nilai, ideal dan material, dan sebagainya. Biasanya
merupakan dasar bagi segala makna yang kemudian muncul dari sebuah wacana filosofis.
Metode Derrida dalam membaca teks-teks filosofis merupakan cara yang bertujuan untuk melacak
struktur dan strategi pembentukan makna di balik tiap teks itu, antara lain dengan jalan membongkar sistem
perlawanan-perlawanan utama yang tersembunyi di dalamnya. Pelacakan terhadap teks-teks oleh Derida
bukanlah pertama-tama penataan sadar, tetapi terhadap tatanan teks yang tidak disadari. Alasannya adalah
karena di dalamnya terdapat asumsi-asumsi tersembunyi di balik hal-hal yang tersurat itu, Lebih tepatnya,
upaya yang dilakukan oleh Derrida adalah menampilkan tekstualitas laten di balik teks-teks. Terdapat banyak
agenda tersembunyi yang mengandung banyak kelemahan dan kepincangan di balik teks-teks yang dapat
disinyalir dalam pembacaan dekonstruksi yang belum mencapai keberhasilannya.
Sebagai kaum pragmatis, Richard Rorty membuat penafsiran dengan menyatakan bahwa pemilahan
yang dibuat Derrida sebenarnya mirip dengan pemilahan antara hubungan inferensial antarkalimat di satu
pihak, dan asosiasi noninferensial antarkata di pihak lain. Meletakkan kunci makna pada kalimat sebagai
bagian yang utama dan kemudian meletakkannya pada satuan kata, itulah pandangan Rorty terhadap Derrida
yang disinyalir menjadi menyerupai pandangan Heidegger. Hal itu terbukti dari adanya saran oleh Derrida
agar kita menggunakan pola berpikir Heideggerian yang melihat makna lebih dari permainan asosiasi
noninferensial, yaitu permainan bunyi, tipografi maupun karakter tulisan.
“Kebenaran” bagi kaum pragmatis hanyalah nama untuk ciri yang dimiliki oleh semua pernyataan yang
benar. Ada keraguan dalam diri Rorty tentang bagaimana kita mengatakan sesuatu yang bersifat umum dan
berguna tentang syarat untuk menjadi “baik” dan “benar”. Menurut Rorty suatu tindakan menjadi baik adalah
hanya dalam kondisi tertentu. Kebenaran hanyalah suatu legitimasi terhadap keyakinan yang hingga kini
terbukti berguna sehingga tidak dibutuhkan upaya lainnya untuk melegitimasi. Dengan demikian, yang
menjadi tugas selanjutnya oleh Rorty adalah bagaimana cara-cara untuk untuk mendapatkan titik pandang
yang sifatnya antifilosofis, yang dapat diungkapkan juga dalam bahasa nonfilosofis.
Dekonstruksi oleh Derrida
Derrida, pada kenyataannya, menolak untuk menuliskan biografinya. Meksipun demikian, kita dapat
mengumpulkan beberapa hal tentangnya. Jacques Derrida merupakan seorang keturunan Yahudi yang lahir di
El-Biar, sekitar Aljazair, pada tahun 1930. Ia pernah belajar di Ecole Normale Superieure (ENS), hingga
akhirnya menjadi dosen tetap di lembaga tersebut pada 1967-1992. Derrida merupakan seorang pemikir yang
kritis terhadap filsafat modern dan berbagai karya sastra tapi ia sendiri menolak disebut sebagai filsuf atau
sastrawan.
Ketertarikan Derrida untuk mengkritik filsafat modern adalah karena filsafat modern identik dengan
pandangan metafisika kehadiran (being) dan logosentrisme (percaya pada rasio). Metafisika kehadiran
menjelaskan bahwa suatu konsep atau teori akan dibenarkan jika sudah mewakili “being” (ada). Kata dan
tanda mewakili sesuatu yang “ada” itu. Derrida memiliki penolakan terhadapa pandangan tersebut,
menurutnya kata, tanda, dan konsep bukanlah kenyataan yang menghadirkan “ada” melainkan hanya berupa
“bekas”(trace). Baginya, sesuatu yang “ada” bersifat majemuk, tak berstruktur, dan tak bersistem, hingga tak
bisa sekonyong-konyong dibenarkan melalui kata, tanda, dan konsep tunggal. Maka metafisika kehadiran
biasa disebut metafisika modern tersebut harus dibongkar (dekonstruksi) untuk menemukan solusi atas
permasalahan modernitas.
Tradisi logosentrisme yang acapkali diunggulkan oleh para filsuf menonjolkan kecenderungan berpikir
binner dan hirarkis. Logosentrisme menganggap bahwa yang pertama merupakan sumber (pusat) kebenaran,
sedangkan yang berikutnya adalah kebenaran pinggiran dan selalu menjadi hal marjinal bila dibandingkan
dengan konsep awal (pertama). Apalagi logosentrisme identik dengan konsep totalitas dan konsep esensi.
Konsep totalitas menyatakan bahwa kebenaran adalah satu. Sedangkan konsep esensi menyatakan tentang
dasar sesuatu pada pengetahuan. Kedua konsep tersebut, baik totalitas maupun esensi bisa menjadi konsep-
konsep yang memaksa atas adanya sesuatu pengetahuan dan melegitimasi kekuasaan berdasarkan rasio dan
pengetahuan. Logosentrisme seringkali menjadi pandangan bagi pemikiran modern yang menimbulkan
dikotomi subyek-obyek. Subyek bisa sepuasnya mengeksploitasi obyek dan menentukan validitas
kebenrannya terhadap obyek. Kebenaran ini seringkali dicirikan dengan kebenaran tunggal, absolut, dan
universal.
Menurut Derrida, filsafat yang cenderung mencari kebenaran absolut acapkali meninggalkan pengertian
bahasa dalam menyusun konsep dan teori. Filsafat menyatakan bahwa kebenaran dan teori mampu
merepresentasikan kebenaran apa adanaya. Derrida menginginkana kebenaran tidak mesti tunggal, absolut,
dan universal. Oleh karenanya Derrida selalu bergairah untuk mendekonstruksi pemikiran modern. Proyek
dekonstruksinya diawali dengan memusatkan perhatiannya pada bahasa karena ide, gagasan, dan konsep
diungkapkan melalui bahasa. Dalam bahasa terdapat prioritas dan kepentingan. Pandangan modern
menunjukkan bahwa kata pertama menjadi fondasi, prinsip, dan dominasi terhadap kata-kata berikutnya.
Namun pandangan dekonstruksi Derrida sering disalahpahami sebagai upaya untuk mengomentari masalah
karya sastra, teks-teks bacaan, dan naskah-naskah kuno. Tapi hal itu dimentahkan oleh Derrida dengan bukti
bahwa ia turut aktif dalam penentanganterhadap apartheid, pelanggaran HAM, dan ia sendiri mendukung
gerakan feminis.Maksud Derrida sendiri ingin menyatakan juga bahwa metode deskontruksi juga bisa
berlaku terkait isu-isu sosial, politik, budaya, dan lainnya.
Pemikiran dekonstruktif Derrida berupaya untuk menunujukkan bahwa ada pemikiran lain yang bisa
menjadi pemikiran alternatif disamping pemikiran yang telah “ada”.Konsep yang ia tawarkan ini bisa
menjadi suara lebih bagi pemikiran-pemikiran yang selama ini terpinggirkan oleh pemikiran tunggal yang
menjunjung tinggi logosentrisme. Dekonstruksi tidak berarti menjurus pada penghancuran suatu konsep tanpa
solusi. Tapi dekonstruksi juga bisa menawarkan konsep baru untuk menggantikan konsep lama. Inilah yang
membedakan konsep dekonstruksi dengan nihilisme (ketiadaan) Nietzsche. Kaitannya dengan bahasa,
Derrida ingin membiarakan bahasa pada karakter yang paradoks, polisemi, dan ambigu. Jika karakter tersebut
dihidupkan kembalai dalam bahasa, ia berharap bahwa filsafat tidak akan bisa lagi diklaim sebagai suatu
otoritas kebenaran.
Filsafat modern (pemikiran) Barat identik dengan kebenaran yang tunggal, mutlak, dan absolut. Melalui
dekonstruksinya, Derrida ingin menyampaikan bahwa kebenaran lama bisa dibongkar dan hal-hal alternatif
lainnya bisa menjadi kebenaran baru. Derrida juga sepakat dengan Foulcault bahwa kebenaran yang berdasar
pada pengetahuan tidak bisa lepas dari kepentingan kekuasaan. Kelebihan dari dekonstruksi ini bisa memacu
para pemikir lain untuk andil dalam menentukan kebenaran menurut apa yang mereka butuhkan.
Dekonstruksi Derrida tentunya bisa menjadi jalan untuk menduking pluralitas pemikiran dan penyikapan
dalam berbagai bidang kehidupan. Namun banyak yang mencela konsep dekonstrusi ini karena konsep
tersebut cenderung dianggap tidak konsisten dan tidak berprinsip. Karena pandangan dekonstrusinya inilah
Derrida dianggap sebagai salah seorang tokoh posmodernisme yang pluralis. Tapi walau Derrida memiliki
pandangan tersebut,ia tidak mengiyakan bahwa konsep dekonstruksi merupakan konsep penghancuran tanpa
adanya konsep lain. Baginya konsep ini bisa mengatasi problem masyarakat modern yang terjebak oleh
kebenaran tunggal. Ia sendiri berpendapat bahwa kebenaran tunggal merupakan produk kapitalis dan
dipaksakan secara totaliter ke berbagai aspek kehidupan dan disusupkan melalui bahasa yang dipakai
manusia.
Pembacaan dekonstruktif pada dasarnya merupakan praktik membaca yang berupaya menunjukkan
bagaimana makna-makna objektif atau maksud pengarah diruntuhkan dari dalam. Dengan kalimat yang lain,
dekonstruksi berusaha membuka keran-keran kemungkinan makna-makna alternatif. Dekonstruksi sedang
mempertontonkan bahwa apa yang biasa kita ibaratkan sebagai realitas, kebenaran atau makna, ternyata
berdiri di atas landasan rapuh bernama tulisan. Mengapa tulisan disebut rapuh? Tidak lain disebabkan ia bisa
diinterpretasikan apapun dan karenanya makna tak pernah mampu menstabilkan dirinya. Derrida kemudian
menghadirkan dekonstruksi untuk menata kembali metode-metode penafsiran yang ada untuk menemukan
makna pada bahasa. Dekonstruksi oleh Derrida berupaya membongkar pembedaan-pembedaan dalam teks dan
menunjukkannya secara jelas. Perlakuan Dekonstruksi terhadap teks maupun konteks adalah sebagai wadah
yang membuka diri terhadap berbagai kemungkinan yang sulit dihubungkan.
Pembacaan dekonstruktif bahkan dijelaskan sebagai praktik pembacaan yang tidak memiliki
pengandaian teleologis seperti pada umumnya, tidak terdapat ambisiusme di dalamnya untuk menangkap
makna-makna, tidak mengarah kepada referensi yang tetap dan tentunya memiliki persebaran ke segala arah.
Loncatan-loncatan tafsir terhadap suatu teks dimungkinkan dalam dekonstruksi. Makna tetap melekat pada
teks tanpa dimaknai sebagai kehadiran, dan kemudian terus bergerak dalam proses menjadi secara terus-
menerus serta membuka diri terhadap penanda-penanda baru. Differance oleh pemikiran Derrida dianggap
sebagai suatu gerakan, aktivitas, peristiwa/kejadian (happening) tanpa subjek atau pelaku yang meruntuhkan
atau menunda makna. Aspirasi Derrida paska postmodernisme muncul mewajahkan emansipasi, pembongkaran
dominasi budaya Barat, budaya patriarki, perayaan narasi-narasi kecil, yang seluruhnya merupakan
serangkaian aspirasi yang ditawarkan Derrida dalam masa postmodernisme. Gagasan tersebut kemudian
disambut dengan pemikiran-pemikiran Derrida yang berupaya melakukan dekonstruksi terhadap bahasa atas
dasar melihat makna-makna yang terpinggirkan, terabaikan dan disembunyikan. Dengan kata lain
Dekonstruksi oleh Derrida dapat digambarkan sebagai pengusik yang terus-menerus mencemaskan segala
pencarian makna absolut.
Anda mungkin juga menyukai
- Postmodernisme Dan Konsekuensinya Bagi FilsafatDokumen4 halamanPostmodernisme Dan Konsekuensinya Bagi FilsafatHilmiBelum ada peringkat
- Makalah Postmodern Filsafat IlmuDokumen12 halamanMakalah Postmodern Filsafat Ilmutri anggi hutamiBelum ada peringkat
- Pendidikan PosmoDokumen18 halamanPendidikan PosmoReza GuantengBelum ada peringkat
- Posmodernisme EDITTEDDokumen37 halamanPosmodernisme EDITTEDPrinastiti Tia SetiawatiBelum ada peringkat
- Menjembatani Teologi Dan Sains Modern - Peters TedDokumen10 halamanMenjembatani Teologi Dan Sains Modern - Peters TedFebbyBelum ada peringkat
- Kelompok 6Dokumen7 halamanKelompok 6Fiya NidaBelum ada peringkat
- Filsafat Kontemporer (K3)Dokumen9 halamanFilsafat Kontemporer (K3)Fahima KhoirunitaBelum ada peringkat
- Paper - Paradigma Kritis Ilmu Sosial Dan KomunikasiDokumen23 halamanPaper - Paradigma Kritis Ilmu Sosial Dan KomunikasiMela ArisaBelum ada peringkat
- Filsafat Zaman KontemporerDokumen51 halamanFilsafat Zaman Kontemporer-Dody Euy-33% (3)
- Filsafat Bahasa PostmodernismeDokumen5 halamanFilsafat Bahasa PostmodernismeDuwi Prima Fradita100% (1)
- Laporan BukuDokumen31 halamanLaporan BukuFitra MarselaBelum ada peringkat
- KONTEMPORERDokumen193 halamanKONTEMPORERengelBelum ada peringkat
- Postmodernisme DewikDokumen9 halamanPostmodernisme DewikAyu Marta DewiBelum ada peringkat
- Tugas Filsafat UmumDokumen12 halamanTugas Filsafat UmumAmrul RidhaBelum ada peringkat
- Makalah FilsafatDokumen7 halamanMakalah Filsafatbhah haderssBelum ada peringkat
- Filsafat KontemporerDokumen10 halamanFilsafat KontemporerNur AnnisaBelum ada peringkat
- Tulisan Post Modern JurisprudenceDokumen22 halamanTulisan Post Modern JurisprudenceSatrio NugrohoBelum ada peringkat
- Filsafat KontemporerDokumen8 halamanFilsafat KontemporerRusdarmayeniBelum ada peringkat
- D. Fils Postmodern-KontemporerDokumen22 halamanD. Fils Postmodern-KontemporerPaian PurbaBelum ada peringkat
- TEORI Relasi KuasaDokumen6 halamanTEORI Relasi KuasaOpik angga putriBelum ada peringkat
- Filsafat KontemporerDokumen12 halamanFilsafat KontemporerSwandi Wiranata SinuratBelum ada peringkat
- Metode Kritis Dalam Ilmu Pengetahuan - KEL 6Dokumen36 halamanMetode Kritis Dalam Ilmu Pengetahuan - KEL 6Sri wahyuniBelum ada peringkat
- Abad Modern FilsafatDokumen8 halamanAbad Modern FilsafatChrystover Rianto PranotoBelum ada peringkat
- Paham Filsafat Dalam ArsitekturDokumen14 halamanPaham Filsafat Dalam ArsitekturMiftah SqrBelum ada peringkat
- Artikel FilsafatDokumen10 halamanArtikel FilsafatDullo RavinderBelum ada peringkat
- Fenomenologi Dan Kawan KawanDokumen11 halamanFenomenologi Dan Kawan Kawanlucky lintongBelum ada peringkat
- Zaman KontemporerDokumen30 halamanZaman KontemporerUnaBelum ada peringkat
- Latar BelakangDokumen10 halamanLatar BelakangDewi aprilianiBelum ada peringkat
- Ringkasan Hal 42-46Dokumen3 halamanRingkasan Hal 42-46realmenasionalBelum ada peringkat
- Bedah Anatomi Teori Derrida FixDokumen12 halamanBedah Anatomi Teori Derrida FixNaoko HaraBelum ada peringkat
- Zaman Kontemporer Umpo 2021Dokumen5 halamanZaman Kontemporer Umpo 2021Randy HarvianBelum ada peringkat
- 01 Tren-Tren Teologi Dalam Spirit Pascamodernisme (Togardo S) 125-152Dokumen28 halaman01 Tren-Tren Teologi Dalam Spirit Pascamodernisme (Togardo S) 125-152DylfardBelum ada peringkat
- Perkembangan Filsafat ModernDokumen11 halamanPerkembangan Filsafat ModernAbdul Aziz Musaihi M.M.Belum ada peringkat
- Yg JD Sosiologi KomunikasiDokumen23 halamanYg JD Sosiologi KomunikasiLiaBelum ada peringkat
- Perbezaan Pendekatan Klasik Dan Wacana Analisis PascamodenDokumen33 halamanPerbezaan Pendekatan Klasik Dan Wacana Analisis PascamodenHabiba NabihahBelum ada peringkat
- Filsafat PostmodernismeDokumen5 halamanFilsafat PostmodernismeNur HikmahBelum ada peringkat
- Critical TheoryDokumen5 halamanCritical TheoryBazari HakikiBelum ada peringkat
- Perbedaan Pemikiran Modernisme Dan Posmodernisme Serta Pemikiran Lyotard Terhadap PosmodernismeDokumen4 halamanPerbedaan Pemikiran Modernisme Dan Posmodernisme Serta Pemikiran Lyotard Terhadap PosmodernismecrystchocoBelum ada peringkat
- Paper Teologi Post ModernDokumen14 halamanPaper Teologi Post ModernSelamatBelum ada peringkat
- Paham Filsafat ArsitekturDokumen9 halamanPaham Filsafat ArsitekturRiska Aulia NajlaBelum ada peringkat
- Paham Filsafat Arsitektur PDFDokumen9 halamanPaham Filsafat Arsitektur PDFRISMAN ARSBelum ada peringkat
- Filsafat Kontemporer Di Barat Dan IslamDokumen6 halamanFilsafat Kontemporer Di Barat Dan IslamRian PratamaBelum ada peringkat
- 5 Bab1Dokumen22 halaman5 Bab1Aditya ZadiraBelum ada peringkat
- Filsafat ModernDokumen16 halamanFilsafat ModernAbdur rohmanBelum ada peringkat
- Filsafat Barat Kontemporer - Filsafat Jiwa - 1Dokumen7 halamanFilsafat Barat Kontemporer - Filsafat Jiwa - 1kikisidhartatahaBelum ada peringkat
- Filsafat FenomenologiDokumen14 halamanFilsafat FenomenologiPriyono HaryonoBelum ada peringkat
- Perubahan PascastrukturalDokumen8 halamanPerubahan PascastrukturalMarcelino William JansenBelum ada peringkat
- Perspektif InterpretatifDokumen2 halamanPerspektif InterpretatifFadhillah AdkandaryBelum ada peringkat
- Filsafat Logika 4 KhairunizahDokumen13 halamanFilsafat Logika 4 KhairunizahNisaBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat Idealisme!!!Dokumen12 halamanMakalah Filsafat Idealisme!!!Junri DanitantaBelum ada peringkat
- RMK - Epistimologi Islam FixDokumen9 halamanRMK - Epistimologi Islam FixsalsaBelum ada peringkat
- Pengertian PostmodernismeDokumen5 halamanPengertian PostmodernismeDede Nurul aisyahBelum ada peringkat
- E - BAHAN - 2019 - SEMINAR - SEMINAR - Dr. Saleeh RahamadDokumen19 halamanE - BAHAN - 2019 - SEMINAR - SEMINAR - Dr. Saleeh RahamadWinnie WongBelum ada peringkat
- 699 1523 1 SMDokumen19 halaman699 1523 1 SMBaim Daeng WarranggiBelum ada peringkat
- HeheDokumen10 halamanHeheMochammad Diaz NursyidiqBelum ada peringkat
- 4253 11259 2 PBDokumen25 halaman4253 11259 2 PBDinna AdiliaBelum ada peringkat
- Jurnal Vol 1 - Syakieb SungkarDokumen13 halamanJurnal Vol 1 - Syakieb SungkarShepia IndrianiBelum ada peringkat
- Kajian PostmodernismeDokumen45 halamanKajian Postmodernismenurul anamBelum ada peringkat
- FilsafatDokumen4 halamanFilsafatAnnisa SetiawatiBelum ada peringkat
- PEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalDokumen22 halamanPEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalIrene RajagukgukBelum ada peringkat
- PEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalDokumen22 halamanPEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalIrene RajagukgukBelum ada peringkat
- PEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalDokumen22 halamanPEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalIrene RajagukgukBelum ada peringkat
- PEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalDokumen22 halamanPEREMPUAN AGEN PERDAMAIAN ATAU AGEN KEKERASAN FinalIrene RajagukgukBelum ada peringkat
- Membangun Komunitas Orang Tua Gen Z Sebagai Sarana Pendidikan Iman KristenDokumen19 halamanMembangun Komunitas Orang Tua Gen Z Sebagai Sarana Pendidikan Iman KristenIrene RajagukgukBelum ada peringkat
- DekonstruksiDokumen6 halamanDekonstruksiIrene RajagukgukBelum ada peringkat
- Risensi RITUAL, by IreneDokumen13 halamanRisensi RITUAL, by IreneIrene RajagukgukBelum ada peringkat