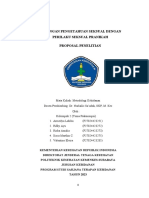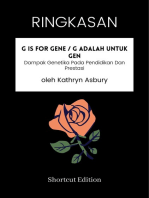34708-Article Text-86304-1-10-20191205.en - Id
34708-Article Text-86304-1-10-20191205.en - Id
Diunggah oleh
Ayu AnsyariJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
34708-Article Text-86304-1-10-20191205.en - Id
34708-Article Text-86304-1-10-20191205.en - Id
Diunggah oleh
Ayu AnsyariHak Cipta:
Format Tersedia
Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.
com
JILS (JURNALdariSTUDI HUKUM INDONESIA)
JURNAL TERAKREDITASI NASIONAL (SINTA 2)
Diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia Volume
4 Edisi 2 November 2019 ISSN (Cetak) 2548-1584 ISSN (Online) 2548-1592
ARTIKEL PENELITIAN
FASE TERGELAP UNTUK KELUARGA: ANAK
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DAN PENYEBABNYA
KOMPLEKSITAS DI INDONESIA
Dian Latifiani1-
1Jurusan
Hukum Perdata dan Dagang, Fakultas
Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
-dianlatif@mail.unnes.ac.id
Dikirim: 11 September 2019Diperbaiki: 15 Oktober 2019Diterima: 1 November 2019
ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana perkawinan anak
terjadi dan implementasi kebijakan untuk mencegah perkawinan anak.
Penelitian ini juga mengkaji beberapa kasus perkawinan anak dan
kondisinya yang kompleks, khususnya di beberapa daerah di Jawa Tengah,
Indonesia. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data utama
penelitian adalah dengan wawancara dan observasi ke lokasi utama, di Desa
Munding Kabupaten Semarang. Beberapa dinas terkait juga menjadi salah
satu sumber data. Penelitian tersebut menekankan bahwa perkawinan anak
terjadi karena pendidikan anak mempelai laki-laki, budaya lokal perkawinan
pada usia anak lebih baik daripada perkawinan di SMA, faktor ekonomi
keluarga anak dan faktor sosial atau lingkungan anak. Dampak perkawinan
anak (perempuan): rentan perceraian, masalah psikologis yang belum
mantap dalam pengelolaan rumah tangga, putusnya pendidikan formal,
belum siapnya kesehatan reproduksi. Penelitian tersebut menyoroti bahwa
budaya lokal menjadi tantangan dalam menentang pernikahan di usia anak.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh
instansi terkait melalui pengaduan pendidikan sesuai dengan tugas pokok
masing-masing instansi terkait.
Kata kunci:Perkawinan anak; alasan Perkawinan Anak; preventif;
kebijakan terpadu
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
242 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
DAFTAR ISI
ABSTRAK ………………………………………………………………. DAFTAR ISI 241
………………………………...………….….. PENDAHULUAN 242
………………………………………………………. PERKAWINAN ANAK: ALASAN 242
DAN MASALAH ………………. I. ALASAN PERKAWINAN ANAK 219
……………………………… 244
A. Mengapa Perkawinan Anak Terjadi? ………………………………... 244
B. Bagaimana Hukum Berbicara tentang Perkawinan Anak? ……………………… 245
II. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK……………………………….. 250
A. Kebijakan Terpadu Mencegah Perkawinan Anak ……………….. 250
1. Orang Tua/Sesepuh Keluarga ……………………..………………… 251
2. Aparat Desa ………………………………………………………. 252
3. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Bergas ………. 253
4. Unit Kementerian Agama Kabupaten Semarang …………… 253
5. Dewan Pendidikan ……………………………………………… 254
6. Dinas Kesehatan ………………………………………………………….. 254
KESIMPULAN ………………………………………………………………..…… DAFTAR 254
PUSTAKA …………………………………………………………………… 255
Hak Cipta © 2019 oleh Penulis
Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons
Lisensi Internasional Atribusi-BerbagiSerupa 4.0.Semua tulisan yang
diterbitkan dalam jurnal ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak
mewakili pandangan jurnal ini dan lembaga afiliasi penulis.
CARA MENGUMPULKAN:
Latifiani, D. (2019). Fase Terkelam Keluarga: Pencegahan Perkawinan
Anak dan Kompleksitasnya di Indonesia.JILS (Jurnal Bahasa Indonesia
Ilmu Hukum),4(2), 241-258. DOI: https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708.
PERKENALAN
Indonesia adalah salah satu dari sepuluh negara di dunia dengan jumlah pengantin anak
tertinggi. Ini adalah yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Diperkirakan satu
dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum mereka mencapai usia 18
tahun. Di dunia, setidaknya ada 142 juta anak perempuan menikah sebelum dewasa
dalam satu dekade ini. Di Indonesia, anak perempuan merupakan korban perkawinan
anak yang paling rentan, dengan prevalensi: 1. Anak perempuan dari pedesaan
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 243
daerah mengalami dua kali lebih rentan untuk menikah daripada daerah perkotaan.
Pengantin anak kemungkinan besar berasal dari keluarga miskin. Anak perempuan
yang berpendidikan rendah dan putus sekolah umumnya lebih rentan menjadi
pengantin anak dibandingkan mereka yang bersekolah (Candraningrum, 2016).
Namun, UNICEF saat ini melaporkan bahwa prevalensi ini bergeser terutama di
daerah perkotaan: pada tahun 2014, 25% perempuan usia 20-24 menikah di bawah
usia 18 tahun. Data SUSENAS 2012 menunjukkan bahwa sekitar 11,13% anak
perempuan menikah pada usia 10-15 tahun, dan sekitar 32,10% pada usia 16-18
tahun. Praktik perkawinan anak juga berkontribusi terhadap tingginya angka
kematian ibu (AKI) di Indonesia yang mencapai 359/100.000 kelahiran hidup dan 48
per 1.000 kelahiran untuk jumlah kelahiran usia 15-19 tahun (Candraningrum, 2016).
Pemerintah Indonesia terikat dengan Konvensi Hak Anak
(ratifikasi dengan Keppres No. 36/1990), Konvensi CEDAW (ratifikasi
dengan UU No. 7 Tahun 1984), Kovenan Internasional Hak Sipil dan
Politik (ratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005), dan The
International Covenant on Indonesian Economic, Social and Cultural
Rights telah meratifikasi hak-hak anak Indonesia yang terikat pada
tujuan kelima (berisi 9 target) dari agenda Sustainable Development
Goals (SDGs) tahun 2015 -2030 yaitu mencapai kesetaraan gender
dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan,
secara khusus dalam Target 5.3 mengacu pada target untuk
menghapus semua praktik berbahaya seperti perkawinan anak,
perkawinan paksa, dan sunat perempuan. Dalam konteks
selanjutnya,
Banyak remaja di Desa Munding khususnya di Dusun Cemanggal cenderung
melakukan perkawinan anak. Mereka belum begitu memahami makna pernikahan
yang sakral dan dampak dari pernikahan dini, seperti hubungan seksual pada usia di
bawah 20 tahun. Risiko perkawinan anak akan memicu terjadinya kanker serviks dan
penyakit menular seksual, belum lagi timbulnya penyakit lain. dampak seperti
kecemasan, stress, depresi dalam menghadapi permasalahan yang timbul dalam
keluarga yang dapat mengakibatkan perpisahan bahkan perceraian karena emosi
remaja yang labil (Minarni, 2014). Munding sendiri merupakan salah satu desa di
Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang wilayahnya terdiri dari 3 dusun yaitu
Dusun Gemawang, Dusun Munding atau Krajan, dan Dusun Cemanggal. Desa
Munding memiliki luas 178.495 Ha, dengan luas pekarangan 27.030 Ha, lapangan
seluas 72.240 Ha, dan sawah seluas 75.225 Ha yang terdiri dari 3 RW dan 18 RT. Ini
memiliki populasi sekitar 3327 orang. Desa Munding yang secara administratif
masuk dalam wilayah Kecamatan Bergas memiliki batas administratif di sebelah
utara dengan Gebugan
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
244 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
dan Desa Pagersari, sebelah timur dengan Desa BergasKidul dan sebelah selatan dan
barat berbatasan dengan Kabupaten Bandungan (munding.desa.id).
Tulisan ini membahas pencegahan perkawinan anak di era
disrupsi. Fokusnya pada masalah (1) penyebab perkawinan anak, (2)
pencegahan perkawinan anak. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe sosiologis-
yuridis. Penelitian dilakukan di Dusun Cemanggal, Desa Munding,
Kantor Urusan Agama Bergas (Kantor Urusan Agama,KUA), dan
Kementerian Agama Kabupaten Semarang sesuai dengan
permasalahan yang dikaji.
PERNIKAHAN ANAK: ALASAN DAN
MASALAH
I. ALASAN PERKAWINAN ANAK
A. Mengapa Perkawinan Anak Terjadi?
Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.
Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan lahir
dan batin. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila
dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya; dan selain
itu, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran, kematian sebagaimana yang tercantum
dalam Akta, suatu akta resmi yang juga dicantumkan dalam pendaftaran. Undang-
undang ini menganut asas monogami. Hanya bila dikehendaki oleh yang bersangkutan,
karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat
beristri lebih dari satu orang. Akan tetapi perkawinan seorang suami dengan lebih dari
seorang istri, sekalipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, hanya dapat
dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.
Undang-undang ini menganut asas, bahwa calon suami istri harus telah matang lahir
dan batinnya untuk dapat menikah, sehingga dapat mewujudkan dengan baik tujuan
perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan
sehat.
Oleh karena itu, perkawinan harus dicegah antara calon pasangan yang menikah di
bawah umur. Apalagi perkawinan berkaitan dengan masalah kependudukan. Jelas bahwa
batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah menghasilkan tingkat
kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang ini menetapkan batas usia
perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dari
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 245
Dalam Undang-Undang diatas, jelas bahwa perkawinan dan segala
ketentuannya telah diatur dengan baik bahwa perkawinan harus dilaksanakan
menurut ketentuan yang ada. Perkawinan yang calon pasangannya di bawah
batas usia termasuk dalam pernikahan dini, karena usia calon pasangan masih
dalam usia sekolah.
B. Bagaimana Hukum Berbicara tentang Perkawinan Anak?
Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-
undangan, atau perkawinan di bawah umur yang dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan
(Julijanto, 2015). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menunjukkan
batasan yang tegas tentang “kedewasaan” calon mempelai, bahwa calon mempelai yang belum
“dewasa” dapat melangsungkan perkawinan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan pengadilan dapat memberikan mereka setuju untuk menikah. Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang lahir kemudian sangat
memperhatikan masalah pendewasaan usia perkawinan (Hardani, 2015). Hal ini antara lain dapat
dilihat dari asas yang mendasari pembentukan undang-undang ini, yaitu asas nondiskriminasi; asas
kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang,
dan prinsip menghargai pendapat anak. Undang-undang menyebutkan bahwa ada beberapa hak
anak yang harus dipenuhi, yaitu: (a) Hak atas pendidikan, (b) Hak berpikir dan berekspresi, (c) Hak
mengeluarkan pendapat dan didengar, (d) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi, dan (e) Hak untuk
mendapatkan perlindungan. Terkait perkawinan anak di bawah umur, kelima hak anak di atas
dilanggar. berekspresi, dan berkreasi, dan (e) Hak mendapat perlindungan. Terkait perkawinan
anak di bawah umur, kelima hak anak di atas dilanggar. berekspresi, dan berkreasi, dan (e) Hak
mendapat perlindungan. Terkait perkawinan anak di bawah umur, kelima hak anak di atas
dilanggar.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban orang tua untuk
melindungi anak-anaknya, mendidiknya, bahkan menghidupinya sampai
pada tahap menuju kedewasaan. Anak harus dilindungi dari hal-hal yang
berdampak negatif terhadap perkembangannya, baik secara fisik maupun
psikis. Dengan pernikahan di bawah umur, perlindungan orang tua yang
tulus dan sejati berkurang dengan beralih ke suami. Anak harus dilindungi
dari pernikahan dini yang berdampak pada perkembangannya, baik secara
fisik maupun psikis.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah
mencantumkan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam hal perkawinan di bawah umur,
dalam pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa barangsiapa melakukan rayuan, tipu
muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan
perbuatan cabul, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 3) sampai
dengan 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian, UU No.
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
246 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak cukup tegas dalam memberikan
sanksi bagi pelanggarnya.
Dampak negatif pernikahan dini meliputi dampak ekonomi, sosial,
kesehatan dan budaya di setiap daerah. Faktor dominan terjadinya
perkawinan anak adalah karena belum adanya Pendidikan Kesehatan
Reproduksi dan Seksual (PKRS) sejak dini yang komprehensif guna
memberikan pemahaman yang tepat bagi remaja atas pilihannya
(Djamilah & Kartikawati, 2014).
Selain itu, dampak pernikahan dini memicu kinerja rumah tangga
kurang unggul baik dalam kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis dan
ekonomi keluarga sehingga rentan terhadap dampak perceraian dan
terabaikannya kualitas pendidikan anak. Selain itu, berdampak pada
kurangnya kematangan psikologis, kurang hati-hati dalam menyelesaikan
masalah, kurang optimal dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, emosi
mereka belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga
berturut-turut (Julijanto, 2015).
Terdapat perbedaan batasan usia menikah menurut UU Perkawinan dan
UU Perlindungan Anak. Usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2):
1. Pasal 7 ayat (1): Perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki berumur 19
tahun dan perempuan berumur 16 tahun;
2. Pasal 7 ayat (2): dalam hal terjadi penyimpangan pada ayat (1) pasal ini
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang
diminta oleh kedua orang tua calon mempelai.
Sedangkan UU Perlindungan Anak pada pasal 1 mengatur hal itu
―
anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih dalam
rahim‖ Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan sebelum seseorang mencapai usia 18 tahun
dikategorikan sebagai perkawinan anak.
Apabila anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun,
perkawinan pada usia 16 dan 17 tahun dikategorikan sebagai perkawinan usia anak.
Oleh karena itu, kiranya tepat jika ada upaya untuk meningkatkan usia perkawinan
menjadi di atas usia anak agar tidak terjadi perkawinan anak. Padahal ada konsep
lain dalam Islam yaituaqil baligh, di mana seseorang dianggap dewasa setelahnya
aqil baligh, yaitu ia harus bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban-
kewajiban pokok. Konsep dariaqil balighmemungkinkan seseorang untuk menjadi
dewasa sebelum 18 (batas usia anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak).
Secara umum,Balighpada pria dan wanita terjadi pada usia sebelum 16 tahun.
Penulis membatasi pembahasan mengenai batas usia perkawinan dari
aspek hukum/perbuatan perkawinan dan perlindungan anak. Berdasarkan data
yang diperoleh dari Desa Munding Kantor Urusan Agama (KUA)
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 247
Bergas dan Kementerian Agama Kabupaten Semarang diuraikan
sebagai berikut. Perkawinan anak dilakukan di bawah usia 18 tahun.
Perkawinan anak di Desa Munding paling banyak terjadi di Dusun
Cemanggal. Data berikut diperoleh:
Tabel 1 Jumlah Perkawinan Anak
Tahun Jumlah Perkawinan Anak
2013 13
2014 10
2015 8
2016 0
2017 2
2018 *per-Agustus 0
Sumber: Wawancara Pribadi dengan Kepala Desa Munding, Agustus 2018
Pernikahan diadakan pada usia 14-15 tahun. Adapun faktor pemicu perkawinan
anak seperti yang ditegaskan oleh Romdotun (2018) seperti: (1) Kebiasaan (budaya) adat
perkawinan di usia muda, (2) Kurangnya wawasan masyarakat tentang perkawinan anak,
(3) Tingkat pendidikan yang rendah karena lokasi perkawinan anak. Dusun Cemanggal
yang terpencil jauh dari sekolah menengah.
Alasan perkawinan anak menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Bergas yang digarisbawahi oleh Amiruddin (2018) karena: (1) Tekanan/
dorongan orang tua untuk menikah di usia muda, (2) Kekhawatiran orang
tua terhadap anaknya ketinggalan jaman yang memaksa anaknya untuk
menikah, dan (3) Kebanyakan pelaku mengalami kehamilan di luar nikah.
Sedangkan menurut Kementerian Agama Kabupaten
Semarang, alasan perkawinan anak antara lain (Ahmadi, 2018): (1)
perempuan sudah hamil sebelum waktunya, (2) sudah melakukan
zina, (3) pendidikan rendah tingkat orang tua (lulusan atau bahkan
tidak tamat SD), (4) Pandangan lingkungan sekitar bahwa jika anak
―sudah tua‖ belum menikah dianggap ―tidak laku dijual‖ maka
lebih baik menikah di usia muda.
Tingkat pendidikan mereka yang menikah di bawah umur adalah tamat SD dan
putus sekolah tetapi bekerja sebagai petani, buruh atau tukang bangunan untuk
membantu pendapatan keluarga. Sehingga mempengaruhi kesiapan psikis kedua
mempelai. Korelasi usia dengan tingkat pendidikan kedua mempelai mempengaruhi
kedewasaan mereka dan mereka tidak mengerti apa yang akan mereka hadapi. Hampir
70% di Munding berkomitmen untuk pernikahan anak di usia anak. Dengan demikian,
setiap calon pengantin harus memahami hak dan kewajiban perkawinan. Mereka juga
harus memahami bahwa risiko tersebut dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan
seperti perceraian. Perkawinan anak seperti itu berisiko tinggi terhadap perceraian.
Selain itu, aspek pendidikan agama juga memiliki
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
248 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
berpengaruh di dalamnya. Selain itu, sebelum menikah, Anda harus mempersiapkan terlebih
dahulu apa yang akan mereka hadapi.
Pilihan untuk menikah di usia muda karena anggapan bahwa selagi usia
mereka masih relatif muda maka mereka bisa memiliki cucu (anak). Padahal
perkawinan anak rentan terhadap perceraian dan bayinya lahir dalam kualitas
sumber daya manusia yang kurang (karena pengasuhan orang tua dilakukan
oleh mereka yang tingkat pendidikannya rendah).
Ada korelasi yang kompleks antara perkawinan anak dan pendidikan di Indonesia.
Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun (perkawinan anak) memiliki tingkat
prestasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum
menikah, terutama setelah sekolah dasar. Selain itu, anak yang menikah pada usia lebih
muda memiliki prestasi pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang
menikah pada usia yang lebih tua. Anak perempuan cenderung putus sekolah setelah mereka
menikah (BPS, 2016).
Menumbuhkan nilai budaya dan agama juga menjadi faktor pendorong
terjadinya perkawinan anak. Misalnya, wanita yang sudah menikah, meskipun usianya
masih muda, lebih dihargai daripada yang belum menikah. Dampak negatif seperti
perceraian dan status janda tidak pernah menjadi masalah. Pemahaman tekstual ajaran
agama merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.
Orang tua sering khawatir tentang anak-anak yang telah memasuki usia baligh, jika
mereka tidak segera menikah, mereka akan bertindak bertentangan dengan agama
(Ramadhita, 2014). Orang tua menganggap seorang perempuan jika sudah bisa
membaca dan menulis dianggap sudah cukup dewasa, tanpa harus melanjutkan ke
jenjang berikutnya, karena anak perempuan nantinya akan kembali ke dapur rumah.
Kebanyakan orang tua lebih memilih menikahkan anak perempuannya pada usia yang
relatif muda tanpa diimbangi dan memperhatikan kesiapan dan kematangan fisik dan
psikis anak (Rahmi, Saroeng, & Yoesoef, 2013).
Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur tidak
memberikan keuntungan bagi keluarga dan rumah tangga, karena perkawinan tersebut
sebenarnya rentan terhadap perceraian, dan sangat mudah goyah dalam mengarungi rumah
tangga. Karena pasangan tidak siap untuk memahami arti dan hikmah dari sebuah
pernikahan, mereka tidak dapat mencapai pernikahan yang diinginkan. Dengan demikian,
akan timbul berbagai permasalahan, karena pasangan yang menikah di usia muda secara
psikologis dan ekonomi belum siap menghadapi kehidupan baru dalam keluarga dan
masyarakat (Maardi, 2012). Sedangkan pernikahan yang berhasil akan membutuhkan
kedewasaan dan tanggung jawab lahir dan batin untuk mewujudkan harapan ideal dalam
kehidupan berumah tangga (Sulaiman, 2012).
Dalam perspektif tradisi dan budaya, perkawinan di bawah umur seringkali terjadi
karena adanya dorongan budaya masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai kelas
dua dimana masyarakat menghindari stigma disebut “perawan tua” (perempuan yang belum
menikah) dan berusaha mempercepat perkawinan untuk berbagai alasan (Inayati, 2015).
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 249
Mereka yang melalui perkawinan, terutama pada usia di bawah umur, maka
keinginannya untuk melanjutkan sekolah atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak
akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal ini dapat terjadi karena motivasi belajar mereka
akan mulai berkurang karena banyaknya tugas yang harus mereka kerjakan setelah menikah.
Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor penghambat terjadinya
proses pendidikan dan pembelajaran (Zulfiani, 2017).
International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar
menyatakan bahwa pernikahan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi
agama yang kuat dan valid dalam perspektif Islam (Ali, 2015). Ditinjau dari aspek
psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai 25 tahun. Ciri-ciri
psikologis yang paling mendasar adalah mengenai pola-pola munculnya perasaan,
pola pikir dan perilaku antara lain: kestabilan mulai timbul dan meningkat; citra diri
dan sikap yang lebih realistis, lebih dewasa dalam menghadapi masalah, dan
perasaan lebih damai (Mapreane, 1982).
Perkawinan anak memiliki dampak sebagai berikut: (1). cenderung sangat
sulit mewujudkan tujuan pernikahan dengan baik. Efeknya, pernikahan hanya
membawa penderitaan. (2).Sulit untuk memiliki keturunan yang baik dan sehat. Itu
dampaknya adalah anak-anak mereka rentan terhadap penyakit.(3). Ini berkaitan dengan masalah
kependudukan. Batasan usia perempuan yang lebih rendah untuk menikah ternyata menghasilkan
laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.
Terlepas dari pro dan kontra perkawinan anak, tanpa disadari dan
disadari, perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain:(
1). Pendidikan anak terganggu: pernikahan dini menyebabkan anak putus
sekolah sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan
akses informasi pada anak.(2).Kemiskinan: dua anak yang menikah dini
cenderung berpenghasilan kurang atau bahkan menganggur. Hal ini
menyebabkan perkawinan anak rentan terhadap kemiskinan.(3).KDRT:
dominasi pasangan akibat kondisi psikologis yang labil menimbulkan emosi
yang bias berdampak pada KDRT (Nasrullah, Muazzam, Khosa, & Khan, 2017;
Yudhanti, Arifin, & Rismadini, 2017).(4).Kesehatan psikologis anak: ibu yang
hamil di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurangnya
sosialisasi dan krisis percaya diri.(5). Anak yang dilahirkan : Bila anak yang
sedang berkembang mengalami proses kehamilan yang lebih dini, terjadi
pertentangan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat
badan ibu hamil seringkali sulit naik, yang dapat disertai dengan anemia
karena kekurangan gizi. , dan risiko melahirkan bayi dengan berat badan
lahir rendah. Ditemukan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu di bawah
usia 17 tahun kebanyakan prematur (Efevbera, 2017). Anak-anak berisiko
menderita penganiayaan dan atau kelalaian. Berbagai penelitian
menyebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan anak berisiko
mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, perilaku
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
250 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
gangguan, dan cenderung menjadi orang tua pada usia anak.(6).Kesehatan
reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko
komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada bayinya. Kehamilan pada usia yang
sangat muda ternyata berkorelasi dengan mortalitas dan morbiditas ibu. Disebutkan
bahwa anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lipat untuk
meninggal saat hamil atau melahirkan dibandingkan dengan kelompok usia 20-24
tahun, sedangkan risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19
tahun. Pasalnya, organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan
panggul belum siap untuk melahirkan. Data UNPFA tahun 2003 menunjukkan bahwa
15%-30% persalinan dini disertai dengan komplikasi kronis yaitu obstetric fistula.
Fistula adalah kerusakan organ kewanitaan yang menyebabkan keluarnya urin atau
feses ke dalam vagina (Mubasyaroh, 2016).
II. PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
A. Kebijakan Terpadu Mencegah Perkawinan Anak
Situasi perkawinan anak di Indonesia tahun 2017 menurut Badan Pusat
Statistik (BPS) adalah, (1) persebaran perkawinan anak di atas 10% merata di
seluruh Provinsi Indonesia (2) persebaran perkawinan anak di atas 25 %
berada di 23 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini berarti 67% Daerah di
Indonesia dalam keadaan darurat perkawinan anak. Selama tahun 2017,
pengentasan perkawinan anak di Indonesia tidak mengalami kemajuan
bahkan gagal dibandingkan tahun 2015 dengan angka yang ditunjukkan
semakin meningkat (Koalisi Perempuan, 2017).
Oleh karena itu, perlu untuk mencegah perkawinan anak. Tindakan preventif
dilakukan secara holistik dan bersinergi dengan berbagai instansi. Tidak mungkin diselesaikan
oleh satu pihak, karena perkawinan anak adalah masalah yang kompleks (Amin, Saha, &
Ahmed, 2018). Skema pencegahan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.
Gambar 1 Diagram Integrasi Kebijakan pencegahan perkawinan anak yang
melibatkan berbagai pihak. Sumber: Riset & Pengamatan Pribadi, 2018
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 251
Berbagai latar belakang dan berbagai aspek menyebabkan kebijakan
integrasi sebagai penyelesaian perkawinan anak, mulai dari hukum, budaya,
pendidikan, dan ekonomi. Partisipasi kolektif dari berbagai pihak untuk menghadapi
praktik-praktik tradisional yang telah membudaya dalam jangka panjang merupakan
suatu keniscayaan, baik dari pihak pemerintah maupun swasta (lembaga swadaya
masyarakat-LSM) (Hanafi, 2014).
Integrasi dimulai dari internalisasi dan kesadaran akan pentingnya kesiapan
dalam pernikahan, salah satunya dengan indikator usia. Usia pernikahan yang ideal tidak
disebutkan dalam undang-undang pernikahan. Namun, itu hanya menyebutkan tentang
batas usia untuk menikah. Untuk pria dan wanita adalah 19 tahun. Usia anak menurut
undang-undang perlindungan anak adalah di bawah 18 tahun. Secara rinci, peran
masing-masing pihak adalah sebagai berikut:
1. Orang Tua/Sesepuh Keluarga
Mereka memiliki peran penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Orang tua memberikan izin untuk pertama kali, apakah mereka bisa menikah
atau tidak. Namun di Dusun Cemanggal, Desa Munding, orang tua justru
menganjurkan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Keinginan untuk
memiliki cucu saat masih muda, menghasut anak-anak untuk menikah. Dan
anak-anak cenderung patuh kepada orang-orang mereka. Jika orang tua
memiliki paradigma kematangan psikologis, fisik, ekonomi sebagai prinsip
utama dalam membangun keluarga baru, maka perkawinan anak dapat
dihilangkan. Nilai-nilai adat yang menempatkan anak sebagai hak milik dan aset
yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh orang tua juga perlu perlahan-lahan
tergerus dan didekonstruksi dari pola pikir masyarakat. Ini termasuk bias
gender dan preferensi pria atas wanita, yang berimplikasi pada rendahnya
status perempuan dalam masyarakat adat. Semua itu perlu diubah melalui
sinergi program pemerintah dengan lembaga dan pemangku adat. Karena
mereka merupakan variabel yang berkontribusi terhadap praktik pernikahan di
bawah umur (Hanafi, 2014).
Padahal disebutkan dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak bahwa salah satu
kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan anak.
Budaya/kebiasaan menikah di usia muda dalam keluarga juga menyebabkan keturunan
yang dilahirkan mengikuti dan melaksanakan pernikahan di usia muda. Perkawinan
adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan dan akibat hukum antara suami,
istri dan anak. Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa usia perkawinan minimal 16
tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun di masyarakat Dusun
Cemanggal, budaya hukum menghormati UU Perkawinan. Budaya hukum merupakan
salah satu bagian dari budaya manusia yang begitu luas. Itu adalah tanggapan umum
yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala hukum.
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
252 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
Tanggapan tersebut merupakan kesatuan pandangan tentang nilai dan perilaku hukum. Oleh
karena itu, budaya hukum mencerminkan pola tingkah laku individu sebagai anggota masyarakat
yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang
dipraktikkan oleh masyarakat yang bersangkutan (Hadikusuma, 1986).
2. Perangkat Desa
Surat Rekomendasi dari Desa/Desa Kelurahan diperlukan untuk
penyelenggaraan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Tingkat
Kecamatan. perangkat desa (Lurah) sebagai ujung tombak tuntunan perkawinan
yang akan dilaksanakan sesuai dengan usia dewasa dalam perkawinan. Itu
membutuhkan kedewasaan dalam psikologi, ekonomi, organ seksual. Jika
administrasi berkas perkawinan mengungkapkan bahwa usia masih di bawah 18
tahun, maka Kepala Desa menyarankan dan memberikan pemahaman tentang
konsekuensi pernikahan di usia anak.
Targetnya pasangan yang ingin menikah harus menunda pernikahannya hingga
mencapai batas usia dewasa. Rencana jangka panjang pembuatan peraturan desa
tentang perkawinan anak dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalisir
perkawinan anak. Peraturan desa merupakan undang-undang sebagai alat kontrol
sosial. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum
merupakan salah satu alat kontrol sosial. Alat-alat lain tetap ada karena masih ada
pranata sosial lain yang diakui (misalnya kepercayaan, kesusilaan). Kontrol sosial
merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial. Bahkan dapat dikatakan sebagai
pemberi definisi perilaku menyimpang dan akibat-akibatnya, seperti berbagai larangan,
tuntutan, dan ganti rugi (Rahardjo, 1983).
Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia dapat
menentukan tingkah laku manusia. Perilaku ini dapat diartikan sebagai suatu hal
yang menyimpang dari kaidah hukum. Akibatnya, undang-undang dapat
memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelakunya. Oleh karena itu, undang-
undang juga menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelaku. Artinya, hukum
mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan aturan untuk mewujudkan
perdamaian. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik
jika ada hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini erat kaitannya dengan
bahan hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan.
Mereka yang akan melaksanakan undang-undang ini juga memiliki peran
masing-masing. Suatu peraturan atau undang-undang yang telah memenuhi harapan
masyarakat dan mendapat dukungan belum tentu dapat berjalan dengan baik jika tidak
didukung oleh aparat pelaksana yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan
undang-undang tersebut. Hal terakhir inilah yang sering dikeluhkan sebagian besar
masyarakat Indonesia. Pejabat terkesan dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang
seharusnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan harga diri serta
kolusi. Citra penegakan hukum masih rentan (Aspandi, 2002).
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 253
Aparat Munding terus berupaya untuk mensosialisasikan
kepada warga agar tidak menikah pada usia anak karena dianggap
kurang baik dampaknya bagi kehidupan pernikahan mereka. Cakupan
materi sosialisasinya terdiri dari 3 bidang sebagai berikut:(1)Agama
(99% penduduk desa beragama Islam);(2)Kesehatan;(3)Pendidikan (Chari,
Heath, Maertens, & Fatima, 2017). Aparat setempat juga bekerja sama
dengan ulama desa dan tokoh adat untuk mensukseskan tujuan
sosialisasi terkait penundaan jika terjadi perkawinan di usia anak agar
mereka siap lahir dan batin di kemudian hari.
3. Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Bergas
Petugas Outreach di Kantor Urusan Agama (KUA) Bergas secara rutin melakukan
program penyuluhan hukum perkawinan dan hukum keluarga agar calon pengantin
dapat mempersiapkan diri dengan baik dan membentuk ketahanan keluarga yang kokoh
untuk mencetak generasi yang tangguh. Jika ada calon pengantin yang usia
perkawinannya di bawah aturan UU Perkawinan, maka KUA melakukan pendekatan
secara personal kepada mereka. Selain itu, rencana jangka panjang dalam pencegahan
ini perlu diadakan sebagai akta bagi individu/pasangan sebagai bekal hukum sekaligus
sebagai syarat untuk menikah dan menghindari anak untuk menikah di usia muda.
KUA juga berperan dalam pencabutan izin nikah bagi yang mencatatkan
nikah di KUA Kecamatan Bergas dan tahun lalu ada dua kasus yang ditolak KUA
karena belum cukup umur. KUA sebagai alat pemerintah yang mencatatkan
perkawinan perlu memperkuat fungsi pendidikan dalam rangka pencegahan
perkawinan anak (Pranawati, 2018). Penguatan tersebut dilakukan dengan
mengembangkan pendidikan dan membangun komunikasi agar masyarakat
memiliki pandangan yang baik tentang pernikahan, yaitu pernikahan sebagai
kesepakatan agung (mistaqanghalidza). Sebagai sebuah perjanjian yang sakral,
pernikahan bukan hanya untuk menyatukan dua insan. Namun menjalankan amanat
kemanusiaan, makhluk berperadaban dan melanjutkan kehidupan moral dengan
peradaban.
4. Unit Kementerian Agama Kabupaten Semarang
Bidang Bimbingan Sosial Kementerian Agama, melakukan pembinaan
sosialisasi penyuluhan sebagai berikut: a) pembinaan wawasan perkawinan
bagi remaja pranikah (19-20), b) pembinaan pranikah dengan memberikan
penyuluhan pentingnya kesiapan perkawinan bagi calon pengantin dari
setiap kecamatan di Kabupaten Semarang (1 KUA mengirimkan 10 calon
pengantin) (Ahmadi, Wawancara Pribadi, 6 September 2018).
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
254 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bimbingan Umat Islam salah satunya
memberikan dan membimbing untuk mendirikan ‗sakinah mawaddah warahmah' atau
keluarga dengan ketenangan, cinta dan belas kasihan. Pembinaan dan pendidikan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum. Masalah pembinaan
kesadaran hukum erat kaitannya dengan berbagai faktor, terutama sikap para penegak
hukum, artinya penegakan hukum mempunyai peran yang besar dalam membina
tumbuhnya kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti
kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan peraturan hukum dengan tingkah laku anggota
masyarakat karena mencerminkan perkembangan hukum tentunya dari keberadaan
kehidupan masyarakat dimana hukum itu berlaku dan berlaku. berubah sesuai dengan
dinamika kehidupan masyarakat.
Saat ini, masih ada kesenjangan antara hukum yang seharusnya (das sollen) dan
hukum sebenarnya (das sein). Kesenjangan ini tentunya terjadi karena
ketidakharmonisan antarhukum dalam bukuDanhukum dalam tindakan. Sejalan dengan
itu, diperlukan upaya pembangunan hukum yang sering diartikan sebagai melakukan
perubahan tertentu terhadap masyarakat.hukum adalah alat rekayasa sosial), dan yang
pasti pembangunan yang diharapkan oleh hukum adalah perubahan masyarakat yang
tertib, terkendali, efektif dan efisien (Ancient, 2017).
5. Dewan Pendidikan
Memberikan informasi tentang pentingnya pendidikan pada jenjang
lanjutan baik SMP maupun SMA dan bahkan Program Penyetaraan
Diploma oleh ‗Paket KejarProgram.' Mahalnya biaya pendidikan bukan
alasan untuk putus sekolah. Kecenderungan di Dusun Cemanggal, jika
sudah lulus SD dianggap cukup dan tidak perlu sekolah menengah.
Namun salah satu hak anak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah mendapatkan
pendidikan, namun karena budaya setempat membuat anak malas untuk
bersekolah, padahal orang tua memiliki biaya yang memadai. . Dewan
Pendidikan dapat memberikan layanan pelatihan kejuruan dan program
magang bagi remaja putri dari keluarga kurang mampu untuk
memberdayakan mereka secara ekonomi (Kalamar, Lee-Rife, & Hindin,
MJ, 2016; Kristiana, 2019).
6. Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan melalui Puskesmas setempat melakukan program penyuluhan
tentang urgensi kematangan organ reproduksi dalam perkawinan. Selain itu,
secara psikologis juga mempengaruhi pembentukan yang kuat
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 255
keluarga. Bagi calon pengantin, wajib melakukan pemeriksaan
kesehatan reproduksi di puskesmas. Apabila mereka telah
memperoleh bukti bahwa pemeriksaan telah dilakukan, perkawinan
dapat diproses. Pendidikan seks, kesehatan reproduksi, dan
persiapan pranikah perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah
untuk menciptakan kesadaran di kalangan remaja tentang bahaya
dan risiko pernikahan di bawah umur melalui Program Pendidikan
Seks, Kesehatan Reproduksi, dan Pranikah (SERHAPP). Mereka
kurang matang secara psikologis, kurang teliti dalam
menyelesaikan masalah, kurang optimal dalam mengerjakan tugas.
Emosi mereka yang belum stabil dalam menyelesaikan masalah
rumah tangga secara berturut-turut membuat mereka rentan
terhadap perceraian (Julianto, 2015).
Kebijakan integrasi jika dilakukan secara sinergis akan mencegah perkawinan anak.
Dengan demikian perlindungan terhadap hak anak dapat terwujud. Anak-anak dapat
menikmati waktu sekolah yang menyenangkan bersama teman-temannya untuk mencapai
cita-citanya. Tingkat pendidikan yang tinggi dapat menghasilkan pembangunan kapasitas
yang mumpuni.
KESIMPULAN
Penelitian menyimpulkan dan menegaskan bahwa perkawinan anak terjadi karena
(1) kebiasaan (budaya) adat menikah di usia muda, (2) kurangnya wawasan
masyarakat tentang perkawinan anak, (3) kurangnya akses dan minat melanjutkan
pendidikan. Upaya preventif dilakukan dengan kebijakan integrasi yang melibatkan
berbagai pihak terkait perkawinan anak yaitu orang tua, perangkat desa, Kantor
Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.
Dengan demikian, perkawinan dapat dilaksanakan pada usia dewasa dengan
kualitas sumber daya manusia yang maksimal dan melahirkan keturunan yang
berkualitas.
REFERENSI
Amin, S., Saha, JS, & Ahmed, JA (2018). Program Pengembangan Keterampilan untuk
Kurangi Perkawinan Anak di Bangladesh: Uji Coba Terkontrol
Secara Acak.Jurnal Kesehatan Remaja, 63(3), 293–300. DOI:
10.1016/j.jadohealth.2018.05.013
Candraningrum, D. (2016). Pernikahan Anak: Status Anak Perempuan?
Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, 21(1), 4-8.
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
256 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
https://www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/jp_88-
cjp__4_.pdf
Chari, AV, Heath, R., Maertens, A., & Fatima, F. (2017. Efek Kausal
Usia Ibu saat Menikah tentang Kesejahteraan Anak: Bukti dari
India.Jurnal Ekonomi Pembangunan, 127(1), 42-55.
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2017.02.002
Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di
Indonesia.JurnalStudiPemuda,3(1),1-16.
https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32033
Efevbera, Y., Bhabha, J., Petani, PE, & Fink, G. (2017). Anak perempuan
Perkawinan sebagai Faktor Risiko Terhadap Perkembangan Anak Usia Dini
dan Stunting.Ilmu Sosial & Kedokteran,185 (Juli), 91-101. DOI: 10.1016/
j.socscimed.2017.05.027
Haikal, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas
Usia Perkawinan Anak (Perempuan).Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(3),
348-355. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i3.1363
Inayati , IN (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif
Hukum, HAM dan Kesehatan.Jurnal Bidan Jurnal Bidan,1(1), 46-53.
http://jurnal.ibijabar.org/wp-
content/uploads/2015/12/PERKAWINAN-ANAK-DI-BAWAH-
UMUR-DALAM-PERSPEKTIF-.pdf
Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika
Hukumnya.Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial,25(1), 62-72.
DOI: https://doi.org/10.2317/jpis.v25i1.822
Kalamar, AM, Lee-Rife, S., & Hindin, MJ (2016). Intervensi ke
Cegah Perkawinan Anak di Kalangan Muda di Negara Berpenghasilan
Rendah dan Menengah: Tinjauan Sistematis dari Publikasi dan Abu-abu
Literatur.Jurnal Kesehatan Remaja, 59(3), 16-21. DOI: 10.1016/
j.jadohealth.2016.06.015
Kristiana, MD (2019). Politik Hukum Kebijakan Hari Sekolah: Hukum
Reformasi Kebijakan Pendidikan Indonesia.Jurnal Hukum dan Reformasi
Hukum, 1(1), 5-24. https://doi.org/10.15294/hukum & reformasi
hukum.v1i1.35405
Mapreane, A . (1982). Psikologi Remaja. Surabaya: Usaha Nasional.
Mawardi, M. (2012). Masalah Perkawinan di Bawah Umur.Jurnal
Analisa. 19 (2), 201-212.
https://media.neliti.com/media/publications/42020-ID-problems-
ofunder-age-marriage.pdf
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019 257
Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Penyebab Pernikahan Dini Dan
Dampaknya Bagi Pelakunya.Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial
Keagamaan Yudisia, 7(2), 385-411. DOI : 10.21043/yudisia.v7i2.2161
Nasrullah, M., Muazzam, S., Khosa, F., & Khan, MM (2017). Anak
Perkawinan dan Sikap Wanita Terhadap Pemukulan Istri Dalam
Sampel Perwakilan Remaja Dan Wanita Muda Yang Saat Ini
Menikah Di Pakistan.Royal Society of Tropical Medicine & Hygiene
Int Health, 9(1), 20-28. DOI: 10.1093/inthealth/ihw047 Prayogo,
BE, Amanah, A., Pradana, TMW, & Rodiyah, R. (2019).
Peningkatan Kapasitas Hukum Bagi Masyarakat Dalam Rangka
Mewujudkan Desa Sadar Hukum dan Ramah Anak. bahasa
Indonesia Jurnal Advokasi dan Pelayanan Hukum, 1(1), 65-78.
https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33776
Raharjo, S. (1983).Permasalahan Hukum di Indonesia.Bandung: Alumni.
Ramadhita, R. (2014). Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi
Perkawinan.De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(1), 59-71.
DOI: 10.18860/j-fsh.v6i1.3192
Republik Indonesia. (1974).Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Marriage,Negara
Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3019[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran NegaraNomor3019].Tersedia online di https://
www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undang-undang
nomor-1-tahun- 1974
Republik Indonesia. (2014).Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606[
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606]. Tersedia
on line pada
https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf
Salam, S. (2017). Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif
Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam.Jurnal Hukum Pagaruyung, 1 (1),
110-124.
https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/273
Sulaiman, S. (2012). Dominasi Tradisi dalam Perkawinan di Bawah Umur.
JurnalAnalisa,19(1),15-26.
https://media.neliti.com/media/publications/42045-ID-dominationof-
tradition-in-under-age-marriage.pdf
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
258 JILS (JURNAL STUDI HUKUM INDONESIA)VOLUME 4(2) 2019
Rahmi, Z., Saroeng, AH, & Yoesoef, D. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap
Perkawinan Anak di bawah Umur (Studi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam).Jurnal
Ilmu Hukum,2(2), 65-73.
Setiawan, S., Saifunuha, MA, Kautsar, JL, & Wulandari, C. (2019).
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Kampung Ramah
Perempuan dan Anak.Jurnal Advokasi dan Pelayanan Hukum Indonesia,
1(1), 5-22. https://doi.org/10.15294/ijals.v1i1.33756 Yudhanti, R., Arifin,
S., & Rismadini, F. (2017). Perlindungan terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Gender Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional
Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Kabupaten Boyolali,
Indonesia.JILS (Jurnal Ilmu Hukum Indonesia),2(1), 15-24. https://
doi.org/10.15294/jils.v2i01.16638
Zulfiani, Z. (2017), Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di bawah
Umur Sesuai UU. No.1 Tahun 1974,Jurnal Hukum Samudera Keadilan, 12
(2), 211-222.
https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/136
Warria, A. (2017). Pernikahan anak paksa sebagai bentuk perdagangan anak.
Tinjauan Layanan Anak dan Remaja,79(Agustus), 274-279.
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.06.024
Tersedia online dihttp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Askep Keluarga Dengan Anak Remaja. Sudah RevisiDokumen36 halamanMakalah Askep Keluarga Dengan Anak Remaja. Sudah Revisiaris dwiprasetya100% (12)
- Nadila Riskya Proposal MetopelDokumen17 halamanNadila Riskya Proposal MetopelnadilariskyaBelum ada peringkat
- 2142 NJBDokumen7 halaman2142 NJBARINI AriefBelum ada peringkat
- Artikel Pengantar Hukum Indonesia Kelompok 11Dokumen21 halamanArtikel Pengantar Hukum Indonesia Kelompok 11Ingrid EmmanuelaBelum ada peringkat
- Makalah2 BKDokumen14 halamanMakalah2 BKPUTRI APRILISIA ZAHRABelum ada peringkat
- Buku Saku F Losu DKKDokumen63 halamanBuku Saku F Losu DKKDesty KomarBelum ada peringkat
- Artikel Pengantar Hukum Indonesia Phi Kelompok 11Dokumen21 halamanArtikel Pengantar Hukum Indonesia Phi Kelompok 11Ingrid EmmanuelaBelum ada peringkat
- Makalah DaspenDokumen10 halamanMakalah DaspenlenovokeyshaBelum ada peringkat
- 189 - Kembang Seri - Laporan Akhir - Aldi Dwi Patrian Agusta - B1a019222Dokumen33 halaman189 - Kembang Seri - Laporan Akhir - Aldi Dwi Patrian Agusta - B1a019222Aldi DwipaBelum ada peringkat
- 25593-Article Text-73877-1-10-20211230Dokumen17 halaman25593-Article Text-73877-1-10-20211230Mal BerthaBelum ada peringkat
- Proposal AgaDokumen10 halamanProposal AgaAnugrah AkbarBelum ada peringkat
- MAKALAH (Kelompok 10)Dokumen27 halamanMAKALAH (Kelompok 10)Ramadhani AhmadBelum ada peringkat
- 01-Marisa-Perlindungan Anak NasionalDokumen14 halaman01-Marisa-Perlindungan Anak Nasionalmadrasah ibtidaiyahswastaBelum ada peringkat
- Masalah Bias Gender Sebagai Faktor Penghambat Implementasi Convention On The Right of The ChildDokumen47 halamanMasalah Bias Gender Sebagai Faktor Penghambat Implementasi Convention On The Right of The ChildReyna NovianaBelum ada peringkat
- Bismillah Proposal Acc Aamiin PrintDokumen30 halamanBismillah Proposal Acc Aamiin PrintGinuk WatiBelum ada peringkat
- Kelompok 2 - Askep Pada Anak Dengan Kekerasan Seksual - 2a 2019Dokumen49 halamanKelompok 2 - Askep Pada Anak Dengan Kekerasan Seksual - 2a 2019Puti MahagandhiBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian PerceraianDokumen23 halamanProposal Penelitian Perceraiandinda pristyBelum ada peringkat
- Amuna Safura - Universitas Almuslim - PKM-RSHDokumen18 halamanAmuna Safura - Universitas Almuslim - PKM-RSHriski firdausBelum ada peringkat
- Kel. 4 LP Kasus Broken Home Dan PerceraianDokumen28 halamanKel. 4 LP Kasus Broken Home Dan PerceraianmirzaBelum ada peringkat
- Nurlaela - Kemitraan Stimulus - Fakultas Psikologi - 2022Dokumen20 halamanNurlaela - Kemitraan Stimulus - Fakultas Psikologi - 2022Fitriana PutriBelum ada peringkat
- Pernikahan Di Usia Muda - Kelompok 2 - Tugas Psikologi Kesehatan PDFDokumen9 halamanPernikahan Di Usia Muda - Kelompok 2 - Tugas Psikologi Kesehatan PDFAlvina Salsabila AKBelum ada peringkat
- Analisis Jurnal Serlin Susmila CahyaniDokumen19 halamanAnalisis Jurnal Serlin Susmila CahyaniSerlinBelum ada peringkat
- Peran Komunikasi Dalam KeluargaDokumen10 halamanPeran Komunikasi Dalam KeluargaAndi AndiBelum ada peringkat
- Aurelia Ramadila (P05120320007) - Sex Education Pada Anak PDFDokumen15 halamanAurelia Ramadila (P05120320007) - Sex Education Pada Anak PDFAURELIA RAMADILABelum ada peringkat
- Salin Ulang Revisi Sempro ArdiansyahDokumen27 halamanSalin Ulang Revisi Sempro Ardiansyahihsansyach hukamaBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - Proposal PenelitianDokumen15 halamanKelompok 1 - Proposal Penelitianastri rahmawatiBelum ada peringkat
- ArticleDokumen11 halamanArticleSiprianus Adi Wardhana JabarmaseBelum ada peringkat
- Skripsi UIDokumen123 halamanSkripsi UIPujiyantoBelum ada peringkat
- Marginalisasi Khitbah Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara BaratDokumen17 halamanMarginalisasi Khitbah Dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara BaratEdi HaqBelum ada peringkat
- Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 1 MargaDokumen27 halamanGambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini Di SMA Negeri 1 MargaRiska YantiBelum ada peringkat
- PROPOSALDokumen21 halamanPROPOSALDian UtamiBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen3 halamanTugas 1Syifa AnindyaBelum ada peringkat
- KDRT Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota BengkuluDokumen14 halamanKDRT Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota BengkuluCynthia AmandaBelum ada peringkat
- Makalah Kep. Anak Child AbuseDokumen27 halamanMakalah Kep. Anak Child AbuseNovia Harum SalsabillaBelum ada peringkat
- PKM GT Kelompok 1Dokumen5 halamanPKM GT Kelompok 1Brigitta IsmiBelum ada peringkat
- Kel.9 Askep Sexual Abuse Pada AnakDokumen44 halamanKel.9 Askep Sexual Abuse Pada Anakmoh syafiuddinBelum ada peringkat
- Melly-Perlindungan Anak NasionalDokumen15 halamanMelly-Perlindungan Anak Nasionalmuhammad azmiBelum ada peringkat
- 7667 16559 1 PBDokumen21 halaman7667 16559 1 PBsalwa sakinahBelum ada peringkat
- Proposal Kualitatif (2) - 1Dokumen34 halamanProposal Kualitatif (2) - 1Ivana Ika Cahya PutriBelum ada peringkat
- KELOMPOK 2 - PROPOSAL SURVEI EPIDEMIOLOGI-dikonversiDokumen29 halamanKELOMPOK 2 - PROPOSAL SURVEI EPIDEMIOLOGI-dikonversiWidhyBelum ada peringkat
- Askep Keluarga Dengan Anak Usia RemajaDokumen55 halamanAskep Keluarga Dengan Anak Usia RemajaHavy BahyBelum ada peringkat
- Askep Kel Tri Bab 1 Bab 2 Salinan (1) DaaDokumen71 halamanAskep Kel Tri Bab 1 Bab 2 Salinan (1) DaaBobby KurNiawanBelum ada peringkat
- K2 Prakonsepsi - Hubungan Pengetahuan Seksual Dengan Perilaku Seksual PranikahDokumen17 halamanK2 Prakonsepsi - Hubungan Pengetahuan Seksual Dengan Perilaku Seksual PranikahRiska amaliaBelum ada peringkat
- Tugas-1-Studi Kasus-Aditya Saputra-22200930310027Dokumen10 halamanTugas-1-Studi Kasus-Aditya Saputra-22200930310027aditya saputraBelum ada peringkat
- Pornografi Pada AnakDokumen19 halamanPornografi Pada AnakRiandra TisyahraBelum ada peringkat
- Komisi 9 - Ketahaanan Keluarga-2Dokumen62 halamanKomisi 9 - Ketahaanan Keluarga-2Binsar Nur SaimBelum ada peringkat
- PKM GT Kelompok 1-Manajemen B MalamDokumen10 halamanPKM GT Kelompok 1-Manajemen B MalamBrigitta IsmiBelum ada peringkat
- Tugas Kti Faishol Sidoarjo - LengkapDokumen29 halamanTugas Kti Faishol Sidoarjo - LengkapArthur EnglandBelum ada peringkat
- Fixs ProposalDokumen45 halamanFixs ProposalToko MilenialBelum ada peringkat
- Kelompok 9 PPKNDokumen8 halamanKelompok 9 PPKNmochmuchtar883Belum ada peringkat
- Proposal Skripsi Utama D3Dokumen74 halamanProposal Skripsi Utama D3Siska PratiwiBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian ResaDokumen22 halamanProposal Penelitian ResaReza Wahyu MaulidaBelum ada peringkat
- Essay Tentang Pengaruh Mental Anak Terhadap Pernikahan Dini Orang TuanyaDokumen9 halamanEssay Tentang Pengaruh Mental Anak Terhadap Pernikahan Dini Orang Tuanyablackpinkoreo915Belum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Keluarga Pada Tahap Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia SekolahDokumen35 halamanAsuhan Keperawatan Keluarga Pada Tahap Perkembangan Keluarga Dengan Anak Usia Sekolahbaiq lastri zuhriaBelum ada peringkat
- Bab 1 Skripsi Adelwine René (Final Revised 3)Dokumen6 halamanBab 1 Skripsi Adelwine René (Final Revised 3)Rene ReneBelum ada peringkat
- Tugas Case Methot AnnaDokumen16 halamanTugas Case Methot Annaandunggio 12Belum ada peringkat
- Proposal Penelitian Andi MalarangengDokumen8 halamanProposal Penelitian Andi MalarangengAndi Ma LarangengBelum ada peringkat
- Form Pengajuan Outline Syari'ah RINADokumen9 halamanForm Pengajuan Outline Syari'ah RINAIndana Nur UmahBelum ada peringkat
- BUKU20YEKTI2012029Dokumen58 halamanBUKU20YEKTI201202911 - Hasnah bungaBelum ada peringkat
- RINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyDari EverandRINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyBelum ada peringkat
- CohenandUphoffshortversionrev en IdDokumen26 halamanCohenandUphoffshortversionrev en IdAyu AnsyariBelum ada peringkat
- Jurnal Indah Dwi HandayaniDokumen13 halamanJurnal Indah Dwi HandayaniAyu AnsyariBelum ada peringkat
- s12517 020 05519 Z.en - IdDokumen13 halamans12517 020 05519 Z.en - IdAyu AnsyariBelum ada peringkat
- Kerangka TeoriDokumen12 halamanKerangka TeoriAyu AnsyariBelum ada peringkat