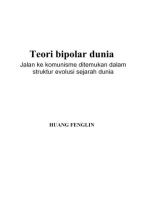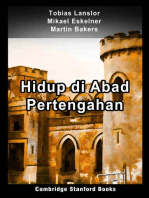COC - Menyelami Konflik Di Tanduk Afrika
COC - Menyelami Konflik Di Tanduk Afrika
Diunggah oleh
Arinatul UlyaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
COC - Menyelami Konflik Di Tanduk Afrika
COC - Menyelami Konflik Di Tanduk Afrika
Diunggah oleh
Arinatul UlyaHak Cipta:
Format Tersedia
Menyelami Konflik di Tanduk Afrika
Oleh Arinatul Ulya
Identitas pada dasarnya melekat dalam diri manusia, yang mencakup bagaimana suatu
individu atau kelompok mengidentifikasi dirinya sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh
individu atau kelompok lain. Berbagai macam bentuk identitas yang selama ini banyak
dikenal mulai dari gender, etnis, agama, budaya, dan politik, membantu manusia saling
“melabeli” satu sama lain, mempengaruhi cara mereka dalam memandang dan memahami
realitas dunia yang ada, serta menjadi pembeda antar individu atau kelompok. Sebagaimana
manusia, identitas juga menawarkan cara pandang yang kompleks seiring waktu berjalan.
Seseorang mungkin memiliki banyak identitas yang berbeda dan identitas tersebut bisa saja
bertumpang tindih. Pentingnya identitas kemudian menjadi perhatian Samuel Huntington dan
ia tuliskan ke dalam buku yang berjudul The Clash of Civilizations and the Remaking of the
World Order.
Tesis utama yang diangkat Huntington dalam buku The Clash of Civilizations and the
Remaking of the World Order adalah perbedaan fundamental di antara masyarakat yang tidak
lagi terletak pada ideologi, politik, atau ekonomi, melainkan pada budaya. Perbedaan budaya
ini menurut Huntington akan memicu konflik antar peradaban di kemudian hari. Huntington
sendiri mendefinisikan peradaban sebagai sebuah entitas budaya, bentuk pengelompokan
tertinggi di mana masyarakat atau sekumpulan orang memiliki identitas paling luas sehingga
hal tersebut membedakan dia dari spesies lain. Berdasarkan definisi tersebut, Huntington
membuat pengelompokan dunia menjadi 8 peradaban “besar” untuk menyederhanakan
realitas dan dijadikan sebagai “peta”. Delapan peradaban besar tersebut terdiri dari Barat,
Jepang, Afrika, Hindu, Amerika Latin, Konfusius, Kristen Ortodoks, dan Islam. Mengikuti
penjelasan mengenai klasifikasi peradaban, Huntington melanjutkan pemaparan mengenai
relasi antar peradaban. Sebelum 1500 M, peradaban-peradaban tersebut terpisah secara
geografis, sehingga interaksi antar peradaban memakan waktu yang lama. Baru setelah
1500M, kemunculan penelitian dan teknologi menjadi katalisator perkembangan model
interaksi antar peradaban seperti ekspansi nilai-nilai, gagasan, dan agama.
Dalam merumuskan teori yang menggambarkan potensi konflik antar peradaban di
dunia pasca Perang Dingin, Huntington cenderung lebih berfokus pada peradaban-peradaban
yang dianggapnya memiliki potensi untuk bersaing secara global, seperti Barat, Islam, dan
Tiongkok. Dalam konteks ini, Afrika sebagai benua yang sangat beragam secara etnis,
budaya, dan agama dianggap sebagai daerah yang kurang memiliki daya saing dalam
persaingan global. Meskipun ada masalah serius di berbagai negara Afrika, seperti perang
saudara, ketegangan etnis, dan masalah kemanusiaan, dinamika konflik-konflik ini tidak
dibahas secara rinci mendalam dalam analisis Huntington.
Seperti konflik di Tanduk Afrika antara Eritrea dan Ethiopia misalnya. Konflik antara
Eritrea dan Ethiopia dimulai pada tahun 1950-an ketika Eritrea, sebuah wilayah di tepi Laut
Merah yang sebelumnya dijajah oleh Italia, digabungkan dengan Ethiopia dalam sebuah
federasi bernama Federasi Eritrea - Ethiopia. Pada mulanya Eritrea yang mayoritas
penduduknya Muslim diberikan otonomi dan status politik yang setara dengan Ethiopia yang
mayoritas penduduknya beragama Kristen. Akan tetapi, Ethiopia tampaknya ingin
memperkuat kendali dan dominasinya atas Eritrea. Upaya tersebut dilakukan dengan
menghilangkan pendidikan Bahasa Arab yang merupakan salah satu bahasa resmi Eritrea dari
sekolah-sekolah, memprioritaskan orang-orang Kristen Eritrea untuk menempati jabatan
strategis di pemerintahan, hingga pengejaran dan intimidasi terhadap tokoh-tokoh pencetus
kemerdekaan Eritrea untuk mencegah perlawanan.
Federasi Eritrea - Ethiopia tidak bertahan lama, Ethiopia akhirnya mengintegrasikan
wilayah tersebut sebagai provinsi Ethiopia. Keputusan ini memicu ketidakpuasan di antara
penduduk Eritrea yang ingin mempertahankan identitas dan otonomi mereka sendiri. Pada
tahun 1961, gerakan perlawanan Eritrea yang dikenal sebagai Front Pembebasan Eritrea
(Eritrean Liberation Front - ELF) mulai berjuang melawan pemerintah Ethiopia untuk
mencapai kemerdekaan. Konflik ini berlangsung selama lebih dari tiga dekade, dengan
perjuangan sengit dan pertempuran di seluruh wilayah Eritrea. Selama konflik ini, pada tahun
1974, rezim Ethiopia mengalami perubahan besar ketika Kaisar Haile Selassie digulingkan
dan digantikan oleh pemerintahan komunis yang dipimpin oleh Derg. Meskipun rezim baru
ini menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Eritrea, konflik berlanjut. Pada tahun 1991,
pasukan gerilyawan Eritrea, terutama yang dipimpin oleh Front Pembebasan Rakyat Eritrea
(Eritrean People's Liberation Front - EPLF), berhasil merebut kembali sebagian besar
wilayah Eritrea dari Ethiopia. Ini mengakhiri pemerintahan komunis Derg di Ethiopia.
Namun, perdamaian tidak berlangsung lama. Pada tahun 1998, konflik meletus kembali
ketika Ethiopia dan Eritrea terlibat dalam perang perbatasan yang mematikan di sekitar
wilayah perbatasan yang dipersengketakan, terutama di Badme. Pertempuran ini
mengakibatkan ribuan kematian di kedua belah pihak dan menyebabkan penderitaan yang
besar.
Meskipun ada upaya mediasi internasional untuk mengakhiri konflik ini, ketegangan
berlanjut selama beberapa tahun. Akhirnya, pada tahun 2000, kedua belah pihak setuju untuk
mengakhiri konflik dan menandatangani Perjanjian Algiers, yang mengakhiri pertempuran
aktif. Namun, meskipun perjanjian tersebut mengakhiri pertempuran langsung, konflik antara
Eritrea dan Ethiopia tetap berlarut-larut dalam bentuk konflik perbatasan yang belum
terselesaikan. Wilayah perbatasan yang dipersengketakan tetap menjadi sumber ketegangan
dan konflik regional. Pada tahun 2018, ada perkembangan mengejutkan ketika Ethiopia di
bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed mengumumkan niatnya untuk memulai
kembali hubungan baik dengan Eritrea. Inisiatif damai ini akhirnya menghasilkan perjanjian
damai yang menyatukan kedua negara dan membuka kembali perbatasan mereka.
Selama tahun 1990-an, saat buku The Clash of Civilizations and the Remaking of the
World Order diterbitkan, Afrika memang mengalami sejumlah konflik dan krisis, termasuk
perang saudara, konflik etnis, dan masalah-masalah kemanusiaan. Namun, Huntington
tampaknya lebih tertarik pada konflik-konflik yang lebih besar dan geopolitis di luar benua
Afrika, seperti konflik Timur Tengah dan hubungan antara Barat dan dunia Muslim. Selain
itu, Huntington mungkin mengabaikan Afrika dalam bukunya karena peradaban di benua ini
sering kali lebih kompleks dan sulit untuk dibagi secara jelas dalam kerangka peradaban yang
diajukannya. Afrika adalah benua yang sangat beragam dengan ratusan kelompok etnis,
bahasa, dan budaya yang berbeda. Hal ini membuat sulit untuk mengidentifikasi satu
peradaban Afrika yang homogen dalam pandangan Huntington. Hal ini membuat argumen
bahwa dalam "The Clash of Civilizations," Huntington tidak banyak menyinggung tentang
Afrika sebagai daerah rawan konflik, sehingga mengurangi kelengkapan teorinya dalam
menggambarkan potensi konflik global.
Anda mungkin juga menyukai
- Clash of CivilizationDokumen8 halamanClash of CivilizationBayu WicaksonoBelum ada peringkat
- Resensi Buku: "Pengantar Studi Hubungan Internasional" Robert Jackson & Georg SorensenDokumen24 halamanResensi Buku: "Pengantar Studi Hubungan Internasional" Robert Jackson & Georg SorensenYuda Fauzan100% (1)
- Sejarah - Pendidikan - Multikultural DuniaDokumen8 halamanSejarah - Pendidikan - Multikultural DuniaSudarinah SudarinahBelum ada peringkat
- UTS HIBUD - Nisrina Nahdah Amanillah - HI 3ADokumen6 halamanUTS HIBUD - Nisrina Nahdah Amanillah - HI 3AnsrnahdaamnBelum ada peringkat
- Gerakan Pemisahan Berdasarkan EtnikDokumen9 halamanGerakan Pemisahan Berdasarkan EtnikSufian TractorBelum ada peringkat
- Presentation 1Dokumen17 halamanPresentation 1wahyu_vernando_zegaBelum ada peringkat
- Review Benturan Antar Peradaban HuntingtonDokumen4 halamanReview Benturan Antar Peradaban HuntingtonUjang Fahmi0% (2)
- Sejarah Pendidikan MultikulturalDokumen10 halamanSejarah Pendidikan MultikulturalMahdavikiaBelum ada peringkat
- Review BukuDokumen13 halamanReview BukuAlya Raissa AbielBelum ada peringkat
- Conflict IndonesianDokumen12 halamanConflict IndonesianMohd HanifBelum ada peringkat
- Muslim Minoritas Di Afrika TimurDokumen27 halamanMuslim Minoritas Di Afrika TimurIkhsan RamadanBelum ada peringkat
- Makalah Latar Belakang Masyarakat MultikulturalDokumen6 halamanMakalah Latar Belakang Masyarakat MultikulturalNurdianaBelum ada peringkat
- The Clash ofDokumen10 halamanThe Clash ofkurnia ramadaniBelum ada peringkat
- ISBD Bab 7Dokumen15 halamanISBD Bab 7Achmad CahyoBelum ada peringkat
- Tugas Baca Kelompok MulticulturalismDokumen2 halamanTugas Baca Kelompok MulticulturalismRosa ArdikaBelum ada peringkat
- Konflik Antar Agama: PendahuluanDokumen17 halamanKonflik Antar Agama: PendahuluanMonika Ten, S.agBelum ada peringkat
- CulturalismDokumen11 halamanCulturalismrayasha.bismaBelum ada peringkat
- Sejarah 5Dokumen8 halamanSejarah 5Imelda IndahBelum ada peringkat
- Multikulturalisme 1Dokumen29 halamanMultikulturalisme 1Renny Krismila10Belum ada peringkat
- Upaya Responsibility To Protect (R2P) Dalam Menangani Konflik Ethiopia Raihani Hafidzah, Nisa Sa'diahDokumen10 halamanUpaya Responsibility To Protect (R2P) Dalam Menangani Konflik Ethiopia Raihani Hafidzah, Nisa Sa'diahAdelia MaharaniBelum ada peringkat
- Makalah Presentasi KelompokDokumen16 halamanMakalah Presentasi KelompokIlham AkbarBelum ada peringkat
- Materi Pat PPKNDokumen29 halamanMateri Pat PPKNNoviBelum ada peringkat
- Bab 9 PPKN Fix BGT SuerDokumen11 halamanBab 9 PPKN Fix BGT SuerZazaezam100% (1)
- A - Arya Yuda - D1e120045 - Tugas PBMDokumen5 halamanA - Arya Yuda - D1e120045 - Tugas PBMLuthor DavidBelum ada peringkat
- 370 1380 2 PBDokumen17 halaman370 1380 2 PBAzzahra AfifahBelum ada peringkat
- Pengertian MultikulturalismeDokumen7 halamanPengertian MultikulturalismeLaxzone TMBelum ada peringkat
- Umi Faizah - MultikulturalismeDokumen5 halamanUmi Faizah - MultikulturalismeMOH. RIZAL BADIUZZAMAN Pengembangan Masyarakat IslamBelum ada peringkat
- Makalah Kel.3 KONFLIK SAMPITDokumen15 halamanMakalah Kel.3 KONFLIK SAMPITSilvy Dwi FazriyahBelum ada peringkat
- Multikulturalisme 1Dokumen29 halamanMultikulturalisme 1Habib MilanistiBelum ada peringkat
- Analisis Konflik RwandaDokumen11 halamanAnalisis Konflik RwandaMasykur Rahim100% (2)
- Tugas PKNDokumen3 halamanTugas PKNzen ZehbiBelum ada peringkat
- Tugas Pendidikan KewarganegaraanDokumen6 halamanTugas Pendidikan KewarganegaraanDesy AnggraeniBelum ada peringkat
- Makalah Tugas 2Dokumen8 halamanMakalah Tugas 2Abdulloh Sya'banaBelum ada peringkat
- Bab 8 - DIALOG - PERADABAN-20200211094134Dokumen16 halamanBab 8 - DIALOG - PERADABAN-20200211094134MOHAMAD FAIZI BIN ZAIDIBelum ada peringkat
- Dinama Relativitas HamDokumen8 halamanDinama Relativitas HamMaria RinceBelum ada peringkat
- Artikel Masyarakat MultikulturalDokumen5 halamanArtikel Masyarakat MultikulturalSyafnaqbanddariminang CihuyBelum ada peringkat
- UAS PKNDokumen2 halamanUAS PKNNald KPBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Etnisitas (Devioniza, Delra, Franky)Dokumen10 halamanTugas Kelompok Etnisitas (Devioniza, Delra, Franky)Andi AlmerBelum ada peringkat
- Dinasti Ayu Tunggal Dewi (2111b0046) Artikel 2Dokumen6 halamanDinasti Ayu Tunggal Dewi (2111b0046) Artikel 2Edy NugrohoBelum ada peringkat
- YunaniDokumen11 halamanYunaniNindya Nastiti PuspitasariBelum ada peringkat
- Integrasi Sosial Masyarakat IndonesiaDokumen3 halamanIntegrasi Sosial Masyarakat IndonesiaDwi Jaka PranataBelum ada peringkat
- Konflik Agama, Politik, Sosial Dan BudayaDokumen11 halamanKonflik Agama, Politik, Sosial Dan Budayaurang calakBelum ada peringkat
- Etnis Tionghoa Di Era ReformasiDokumen17 halamanEtnis Tionghoa Di Era ReformasiPeter Kasenda100% (3)
- Bab IiDokumen5 halamanBab IiSatria MahardhikaBelum ada peringkat
- Kemunculan Gerakan Nasionalisme Dan Perjuangan Kemerdekaan Di Kalangan Masyarakat Muslim Di Kawasan Afrika UtaraDokumen7 halamanKemunculan Gerakan Nasionalisme Dan Perjuangan Kemerdekaan Di Kalangan Masyarakat Muslim Di Kawasan Afrika UtaraBilqisthi NMBelum ada peringkat
- Makalah Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar PDFDokumen19 halamanMakalah Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar PDFnita minawati dewiBelum ada peringkat
- Bab 4 Bersatu Keragaman Dan DemokrasiDokumen5 halamanBab 4 Bersatu Keragaman Dan DemokrasiAlfiyandi AlfiyandiBelum ada peringkat
- Ketidaksetaraan Ras Dan EtnisDokumen8 halamanKetidaksetaraan Ras Dan Etnisgreedy manBelum ada peringkat
- Hotel Rwanda AnalysisDokumen10 halamanHotel Rwanda AnalysisJoshua DanielBelum ada peringkat
- Masyarakat Multikultural - 0 PDFDokumen13 halamanMasyarakat Multikultural - 0 PDFmohfarisarfandhyfBelum ada peringkat
- Manusia, Keberagaman, Dan KesetaraanDokumen1 halamanManusia, Keberagaman, Dan Kesetaraanpangeran syukurBelum ada peringkat
- Persentasi Studi Islam BaratDokumen12 halamanPersentasi Studi Islam BaratDzaky RezaBelum ada peringkat
- Hegemoni Barat Dan Respon IslamDokumen6 halamanHegemoni Barat Dan Respon IslamAcil GmpBelum ada peringkat
- Makalah Agama (Budaya Dan Peradaban Islam)Dokumen7 halamanMakalah Agama (Budaya Dan Peradaban Islam)Rafli AkbarBelum ada peringkat
- Negara KebangsaanDokumen4 halamanNegara KebangsaanKekePuspitasariBelum ada peringkat
- Imperialisme Di Palestina Dan Jalan Buntu Diplomasi PBBDokumen10 halamanImperialisme Di Palestina Dan Jalan Buntu Diplomasi PBBRizaldi AgengBelum ada peringkat
- Antropologi MasyarakatDokumen10 halamanAntropologi MasyarakatSaiiah Anaag SaniihBelum ada peringkat
- Nasionalisme "Dalam Perspektif Islam"Dokumen14 halamanNasionalisme "Dalam Perspektif Islam"romiBelum ada peringkat
- Teori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaDari EverandTeori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)