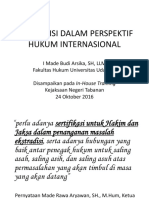Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Diunggah oleh
julio0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
10 tayangan178 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
10 tayangan178 halamanEkstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Diunggah oleh
julioHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 178
Pertemuan Kedelapan
EKSTRADISI DALAM
SISTEM PERADILAN
PIDANA
DR.BASUKI,S.E, S.H, M.H, CLA
A. Definisi
1. Istilah ekstradisi berasal dari bahasa lain, “extradere” atau penyerahan.
Secara etimilogis, kata ekstradisi berasal dari dua suku kata yaitu “extra” dan
“tradition”. Ekstradisi adalah sebuah konsep yang berbeda dengan tradisi yang
telah berabad abad di priaktikan di antara bangsa-bangsa. Praktik tersebut adalah
kewajiban setiap negara untuk menjadi “asylum”(pelindung) bagi siapa saja yang
memohon perlindungan dan tradisi untuk memelihara kehormatan (hospitality)
sebagai negara (tuan rumah) atas mereka yang memohon perlindungan tersebut.
Praktik asylum yang mendahului ekstradisi menunjukan bahwa ekstradisi
merupakan kekecualian dari asylum.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sebagai mana
dinyatakan dalam pasal 1 undang-undang tersebut memberikan definisi
ekstradisi sebagai penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang
meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena
melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di
dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena
Selanjutnya Pasal 2 mengatur bahwa ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian
ataupun atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia
menghendakinya.
3. L. Oppenheim:
Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose
territory he is alleged to have committed, or to habe been convicted of a crime by the state
on whose territory the alleged criminal happens for the time to be. (Ekstradisi adalah
penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara diwilayah mana ia suatu waktu berada,
kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum
karena perbuatan kejahatan)
4. J.G. Starke:
Extradirion is the process where by under treaty or upom a basis of reciprocity one state
surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence
committed against the law of the requesting state competent to try alleged offender.
(Ekstradisi menunjukan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan atas permintaan
negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-
undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.
Biasanya kejahatan yang berwenang untuk mengadili penjahatan tersebut yang dilakukannya
B.1. Ada 2 Elemen mendasarkan dalam ekstradisi yang satu dan lainnya tidak
dapat dipisahkan:
a. Elemen kerja sama antarnegara;
b. Elemen penegakan hukum.
B.2. Ada 2 Aspek Ekstradisi sebagai bentuk kerja sama antar negara:
1) Dari aspek landasan pelaksanaan ekstadisi, yaitu adanya perjanjian atau dasar
hubungan baik dan jika kepentingan negara menghendakinya;
2) Dari aspek ekstradisi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dapat
disimpulkan dari tujuan dilaksanakannya ekstradisi tersebut atas kejahatan yang
dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan
tersebut.
C. 5 Unsur dalam Ekstradisi
a. Subjek Hukum
Dilihar dari unsur subjek hukumnya, yaitu subjek-subjek hukum yang terlibat dalam
suatu kasus ekstradisi, terdiri atas:
1. Negara peminta sebagai negara yang berkepentingan untuk mengadili atau
menghukumnya;
2. Negara diminta sebagai negara tempat sipelaku kejahatan itu berada.
b. Objek Hukum
Unsur objek hukumnya, sebagai orang yang diminta, boleh jadi berstatus seabgai
tersangka, tertuduh, terdakwa ataupun sebagai terhukum. Dalam hubungan ini
kedudukannya adalah sebagai onjek atau sasaran dari permintaan negara peminta
kepada negara uang dimintai ekstradisi maupun sebagai objek dari pengestradisian
atas dirinya oleh negara peminta itu dikabulkan oleh negara yang di mintai
ekstradisi. Secara singkat orang ini disebut sebagai “orang yang di minta” (the
requested person).
c. Tata Cara/Prosedur
Unsur tata cara atau prosedur meliputi tata cara untuk mengajukan permintaan
dengan segala persyaratannya, tata cara untuk memberitahukan apakah permintaan
itu dikabulkan ataukah ditolak, dan jika dikabulkan selanjutnya adalah tata cara untuk
menyerahkan orang yang diminta. Dengan demikian ada suatu prosedur atau tata
cara formalitas tertentu yang harus dipenuhi atau diikuti oleh kedua pihak. Itulah
sebabnya permintaan ataupun penyerahannya lazim disebut permintaan ataupun
penyerahan yang dilakukan secara formal.
Prosedur dilakukan dengan cara:
1. Saluran diplomatik;
2. Inisiatif dilakukan oleh negara yang memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan;
3. Negara tempat pelaku kejahatan berada tidak boleh melakukan penangkapan
sepanjang keberadaan pelaku dinegara tersebut tidak menggangu kepentingan
nasional ataupun melanggar hukum;
4. Masalah ekstradisi baru muncul apabila ada permohonan dari negara peminta
secara formal
d. Maksud dan Tujuan
Unsur maksud dan tujuan, dimana permintaan negara peminta ataupun penyerahan
oleh negara yang dimintai ekstradisi atas diri orang yang diminta adalah dengan
maksud dan tujuan untuk mengadilinya atas kejahatan yang telah dilakukan yang
menjadi yurisdiksi dari negara peminta, atau jika dia sudah bersatuts sebagai
terhukum adalah dengan maksud dan tujuan untuk pelaksanaan hukuman atau sisa
hukumannya di negara peminta. Jika hal itu sudah berhasil dilakukan berati maksud
dan tujuan dari ekstradisi itu sudah tercapai.
e. Dasar/Landasan
Unsur dasar atau landasan yaitu bisa berupa perjanjian ekstradisi yang sudah ada
sebelumnya antara kedua pihak atau jika perjanjian ekstradisi itu tidak atau belum
ada, sepanjang para pihak bersedia dapat juga didasarkan atas hubungan baik secara
timbal balik. Apabila para pihak (negara peminta dan negara yang dimintai ekstradisi)
sebelumnya sudah terikat pada suatu perjanjian ekstradisi ternyata pada suatu
waktu menghadapi suatu kasus ekstradiksi, penyelesaiannya haruslah berdasarkan
pada perjanjian tersebut. Sebaliknya jika para pihak setuju proses mengacu pada
prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum tak tertulis tentang ekstradisi
D. Kedudukan Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Kedudukan Ekstradisi Dalam Sistem Peradilan Pidana tidak semata-
mata mendasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
yang secara eksplisit tidak mengatur terkait dengan penghormatan
terhadap hak asasi subjek hukum yang akan di ekstradisi namun
ekstradisi dalam system peradilan pidana telah secara alamiah tunduk
dan mengikatkan diri dengan peraturan perundangan yang mengatur
penghormatan terhadap hak asasi subjek hukum yang menjadi subjek
dalam system peradilan pidana, yaitu terikat dan tunduk terhadap:
1) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kuhap dan Konvenan
Internasional tentang hak-hak sipil dan politik International
Convention On Civil and Poltical (ICCPR) yang telah diratifikasi
dengan Undang-undang No 12 Tahun 2005 yang mewajibkan
Indonesia untuk segera menyesuaikan ketentuan hukum positif
yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ICCPR;
2) Komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi penghormatan
terhadap HAM dalam proses peradilan pidana yang makna
hukumnya adalah bahwa tujuan penegakan hukum bukan semata-
mata untuk menghukum para pelaku kejahatan, akan tetapi usaha
perlindungan harus diimbangi dengan Procendural safeguards
against the arbitrary was conduct of the state (prosedur usaha
perlindungan sebagai wasit terhadap tingkah laku/tindakan negara),
yang artinya bahwa adanya prosedur usaha perlindungan terhadap
hak-hak individu dari tersangka ataupun terdakwa yang terlibat
didalamnya dari bentuk kesewenang wenangan negara, yang
diwujudkan melalui proses hukum yang adil (due process of law),
serta pembatasan jangka waktu penahanan yang dapat dilakukan
oleh negara
Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak mengatur tentang
tentang pembatasan penahanan, sehingga dengan diundangkan Undang-undang No
8 Tahun 1981 dan Undang-undang No 12 Tahun 2005, maka praktek pelaksanaan
ekstradisi, telah mempedomaninya due process of law, dan terhadap tersangka atau
terdakwa dapat menempuh upaya pra peradilan, yang dapat membuktikan bahwa
proses pemeriksaan perkara ekstradisi telah mengarah pada proses peradilan pada
umumnya. Ada referensi pelaksanaan ekstradisi dalam system peradilan pidana
Indonesia yaitu:
a. Putusan Pengadilan Negeri Batam No 01/Prd.Pra/2015/PN BTM tanggal 20 April
2015 telah mengabulkan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh
termohon Ekstradisi, atas nama Lim Yong Nam warga negara Singapura yang
dimintakan ekstradisi oleh pemerintah Amerika Serikat atas kejahatan penipuan,
yang amar putusannya bahwa penangkapan dan penahanan oleh polda kepri
tidak sah.
b. Penggadilan Tinggi DKI No 16/Pid/plw/2014/PT Dki mengabulkan keberatan JPU
atas penetapan PN Jaksel No 01/Pid.C/Fks/2013/PN Jkt selasa tanggal 11 Juli
2013 dalam perkara Ekstradisi atas nama Sayed Abbas Azad bin Sayed Abdul
Peraturan Dalam Undang-undang Ekstradisi yang mengatur lembaga otoritas pusat
(central authority) maupun model Treaty On Extradiction yang diterbitkan oleh
Majelis Umum PBB (Resolusi 45/116 Tahun 1960) yang juga menggunakan
pendekatan Central authority dengan mekanisme bantuan timbal balik dalam
masalah-masalah pidana (Mutual Legal Assistance/MLA), dimana dalam model ini
tidak mengatur tentang penghormatan terhadap hak-hak asasi subjek hukum yang
dimintakan ekstradisi kecuali hanya mengatur bahwa permintaan ekstradisi
dilakukan melalui saluran diplomatik yang didukung dengan dokumen
pendukungnya yaitu dilaksanakan secara langsung antar Menteri Kehakiman atau
Lembaga lain yang ditunjuk oleh pihak. Model ini mewajibkan negara untuk
memilih saluran komunikasi yang digunakan dalam proses ekstradisi apakah
memalui saluran diplomatik atau secara langsung kepada Lembaga pemerintah
yang berwenang.
Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam interpretasi yang diberikan oleh United
Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC), 2012, Manual on Mutual Legal
Assistance and Extradiction, United Nations, New York, hal 36:
Outgoing or incoming mutual legal assistance or extradition request will
essentially be a legal exercise involving domestic criminal law and procedure,
such as the rules of evidence and search an seizure, of at least two States,
along with the applicable domestic laws, if any, pertaining directly to mutual
legal assistance or extradition. Issues of international criminal practice such
as the interpretation of a treaty, or perhaps a number of treaties, in an
attempt to either find standing to make a request or respond to a request,
may also have to be considered. In many cases, there will also be interaction
with police, appearances before magistrates and judges, negotiations with
defence counsel, communication with prosecutors and witnesses and the
management and assessment of legal documentation, pleadings and exhibits.
Bantuan hukum timbal balik yang keluar atau masuk atau permintaan ekstradisi
pada dasarnya adalah suatu pelaksanaan hukum yang melibatkan hukum dan acara
pidana dalam negeri, seperti aturan pembuktian dan penggeledahan suatu
penyitaan, di setidaknya dua Negara, bersama dengan undang-undang domestik
yang berlaku, jika ada, berkenaan dengan hal tersebut. langsung pada bantuan
hukum timbal balik atau ekstradisi. Persoalan praktik kriminal internasional seperti
penafsiran suatu perjanjian, atau mungkin sejumlah perjanjian, dalam upaya untuk
mendapatkan alasan untuk mengajukan permintaan atau menanggapi permintaan,
mungkin juga harus dipertimbangkan. Dalam banyak kasus, juga akan ada interaksi
dengan polisi, kehadiran di hadapan hakim dan hakim, negosiasi dengan penasihat
hukum, komunikasi dengan jaksa dan saksi serta pengelolaan dan penilaian
dokumentasi hukum, pembelaan dan bukti
The role responsibilities of such an office have been described above, along
with the suggested profile of the counsel who should staff if. Given the nature
and type previously mentioned, as well as already established domestic line of
communication to the courts, prosecutors, police and other investigative
agencies, all bolster the concept of housing the central authority in this
department. (Tanggung jawab peran dari kantor tersebut telah dijelaskan di
atas, bersama dengan profil penasihat yang disarankan yang harus menjadi
stafnya. Mengingat sifat dan jenis yang disebutkan sebelumnya, serta jalur
komunikasi domestik yang sudah terjalin dengan pengadilan, jaksa, polisi dan
lembaga investigasi lainnya, semuanya mendukung konsep perumahan
otoritas pusat di departemen ini.)
EKSTRADISI DALAM HUKUM
INTERNASIONAL
A. KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELAKSANAKAN EKSTRADISI
Praktek ekstradisi pada awalnya bukan merupakan budaya barat, melainkan
dilakukan oleh negara-negara seperti Mesir, China. Kasdim, dan Babilonia.
Dalam penerapannya, penyerahan seseorang yang diminta oleh negara
asalnya dilakukan melalui sebuah upacara yang digelar secara besar-besaran.
Ekstradisi biasanya dilakukan perjanjian atau kesepakatan, namun dapat pula
dilandaskan pada hubungan timbal balik atau untuk menunjukan niat baik
dan persahabatan antar negara-negara yang berdaulat.
Pelaksanaan ekstradisi yang pertama kali tercatat dalam sejarah terjadi pada
tahun 1280 sebelum Masehi. Dalam dokumen tertua kedua dalam sejarah
diplomasi internasional, ditulis bahwa Ramses II, Fiuraun dari Mesir
menandatangani perjanjian damai dengan suku Het, setelah ia berhasil upaya
mereka untuk menyerbu Mesir. Dokumen ini ditulis dalam bahasa Hieroglyphik
dan dipahat pada kuil Ammon di Maka dan juga disimpan dalam bentuk sebuah
loh batu di arsip yang disimpan oleh suku Het di Boghazkoi. Perjanjian damai
tersebut secara tegas menyatakan mengenai kesepakatan untuk menyerahkan
orang yang dicari oleh masing-masing negara yang mencari suaka ke negara
lainnya.
Setelah masa itu, konsep ekstradisi tidak banyak mendapat perhatian sampai
dengan kejayaan Kekaisaran Roma sekitar tahun 400 – 100 sebelum Masehi. Salah
satu pelaksanaan ekstradisi yang terkenal pada masa itu adalah permintaan Roma
untuk mengembalikan Hannibal dari Suria sesuai dengan perjanjian pasca perang
yang ditandatangani antara kedua negara. Hukum Roma yang berlaku pada masa
itu memperbolehkan untuk mengekstradisi warga negara Roma yang melakukan
kejahatan terhadap para Duta Besar yang berada di wilayah kekuasaan Romawi
Dalam perjalanannya, praktik ekstradisi yang awalnya didasarkan pada sebuah
perjanjian, ternyata dapat pula dilakukan atas dasar hubungan baik antara kedua
negara. Praktik saling mengekstradisi ini kemudian berlanjut secara terus menerus
dan berkembang menjadi suatu pranata hukum ekstradisi sebagai hukum kebiasaan.
Kebiasaan tersebut selanjutnya diperkuat dengan pendapat ahli hukum internasional
masa itu yaitu Hugo de Groot atau yang lebih dikenal dengan Grotius yang
memperkenalkan konsep hukum internasional yakni aut dedere aut puniere (bahwa
setiap pelaku kejahatan dimanapun berada atau ditemukan haruslah dihukum).
Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648, juga memberikan dampak positif
terhadap perkembangan hukum tentang ekstradisi, di mana dengan adanya perjanjian
tersebut, melahirkan prinsip penghormatan kedaulatan tiap negara sehingga setiap
negara yang seharusnya memiliki yurisdiksi untuk mengadili para buronan (fugitive
offenders) yang bersembunyi di negara lain, tidak dengan mudah masuk ke negara
lain tersebut dan kemudian menangkap serta membawa buronan itu ke wilayahnya,
melainkan dibutuhkan pranata hukum ekstradisi sebagai upaya kedua negara untuk
menegakan hukum dengan tidak melanggar batas kedaulatan negara tetangga
Gagasan untuk menggunakan ekstradisi sebagai instrumen dalam
mendukung upaya penegakan hukum mulai mencul pada periode Tahun
1833 sampai 1948. Pada periode ini, mulai tumbuh kesadaran bersama untuk
menggunakan ekstradisi sebagai instrumen internasional guna menekan
tingginya angka kejahatan, termasuk kejahatan konvensional.
Setelah Perang Dunia II Lembaga hukum Ekstradisi diwarnai dengan Hak
Asasi Manusia sebagai manifestasi dari Deklarasi Universal tentang Hak-hak
Asasi Manusia (DUHAM), dimana terdapat beberapa point penting dari
perkembangan hukum ekstradisi akibat pengaruh pengakuan, perlindungan
serta jaminan terhadap HAM.
Sebagai perkembangannya, terdapat beberapa asas-asas ekstradisi yang selanjutnya
menjadi asas baku yang diakui dan diterima oleh masyarakat Internasional, antara
lain sebagai berikut:
1. Asas kejahatan ganda (double criminality principle);
2. Asas kekhususan (Speciallity principle/ rule of speciality);
3. Asas tidak mengesktradisikan pelaku kejahatan politik (non extradition of
political criminal);
4. Asas tidak mengekstradisikan warga negara dari negara yang di mintai ekstradisi;
5. Asas kadaluarsa (laps of time principle);
6. Asas ne bis in idem;
7. Terhadap kejahatan yang diancam hukuman mati, jika menurut negara yang
dimintai ekstradisi kejahatan tersebut tidak diancam hukuman mati, sementara
menurut hukum negara peminta, kejahatan tersebut diancam hukuman mati,
maka negara yang di mintai ekstradisi dapat menolak penyerahan (ekstradisi)
kecuali negara peminta dapat menjamin bahwa pelaku tidak pidana tersebut tidak
dijatuhi hukuman mati.
Selanjutnya, Model Law on Extradition yang diterbitkan oleh Majelis Umum
PBB mengatur mengenai beberapa landasan untuk menolak permintaan
ekstradisi, yaitu sebagai berikut:
a. Ekstradisi tidak akan diberikan jika menurut pandangan dari Pejabat yang
berwenang dari negara yang diminta, orang yang dicari/buronan tersebut
tidak akan menerima standard minimum untuk dilakukan proses
peradilan yang adil dari negara yang meminta dilakukannya ekstradisi
tersebut.
b. Ekstradisi dapat ditolak, jika kejahatan dilakukan diluar batas teritorial
dari negara peminta dan hukum dari negara yang dimintai ekstradisi
tidak mengijinkan penuntutan untuk kejahatan yang sama tersebut Ketika
dilakukan diluar teritorial dari sebuah Negara.
c. Asas-asas tersebut dapat dikesampingkan semua yaitu terhadap pelaku
tindak pidana yang akan diserahkan kepada Pengadilan kejahatan
internasional (International Criminal Court or Tribunal).
Dalam Model Law Treaty juga mengatur mengenai bentuk kejahatan yang
dapat diekstradisikan, yaitu apabila:
a. Kejahatan tersebut dapat dijatuhi pidana berdasarkan hukum dari negara
peminta dengan pidana penjara atau perampasan kemerdekaan lainnya
unutk jangka waktu maksimum paling sedikit satu atau dua tahun, atau
hukuman yang lebih berat lainnya;
b. Perbuatan tersebut tergolong sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana
berdasarkan hukum dari negara yang diminta dengan pidana penjara atau
bentuk pidana perampasan kemerdekaan lainnya untuk jangka waktu
maksimum paling sedikit satu/dua tahun, atau hukuman yang lebih berat
lainnya;
c. Terhadap seseorang buronan yang telah dijatuhi hukuman penjara atau
hukuman perampasan kemerdekaan lainnya berdasarkan kejahatan yang
telah dilakukannya tersebut, tidak dapat dilakukan ekstradisi kecuali masih
ada jangka waktu untuk menjalani hukuman minimal 6 (enam) bulan atau
lebih;
d. Dalam menentukan apakah satu kejahatan adalah kejahatan yang dapat
dipidana oleh hukum yang berlaku di negara yang dimintai ekstradisi dan
hukum yang berlaku di negara yang meminta, tindaklah perlu diperhatikan,
apakah terhadap kejahatan tersebut memiliki kesamaan kategori kejahatan,
terminology, definisi atau karakteristik yang sama dari kedua Negara;
e. Perbuatan yang melanggar hukum dari negara peminta terkait dengan pajak,
bea cukai, dapat menjadi kejahatan yang bisa dikenakan ekstradisi apabila
kejahatan tersebut memiliki kesamaan nuansa dengan hukum dari negara yang
dimintai ektradisi;
f. Apabila permintaan ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang dapat
dikenakan pidana oleh hukum dari negara peminta, namun demikian kejahatan
tersebut untuk sebagaian tidak sesuai dengan ketentuan atas, yaitu adanya
pidana maksumum paling sedikit lamanya 1 (satu) atau 2 (dua) tahun atau
lebih, maka ektradisi tetap dapat diberikan.
Dalam perkembangannya, konsep menggunakan esktradisi sebagai
instrumen dalam mendukung upaya penegakan hukum diwujudkan dengan
munculnya berbagai konvensi internasional yang mewajibkan negara pihak
dalam konvensi tersebut untuk mendorong efektivitas ekstradisi sebagai
salah satu bentuk kerja sama internasional di bidang penegakan hukum.
Diantara berbagai konvensi tersebut, dua konvensi yang dapat dikatakan
memberikan landasan bagi pengembangan ekstradisi sebagai instumen kerja
sama penegakan hukum adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan
Transnasional (United Nations Convention against Transnational Organized
Crime, disingkat UNTOC) yang ditandatangani di Palermi, Italia pada tahun
2000 dan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention
Against Corruption, disingkat UNCAC) yang ditandatangani di Merida,
Meksiko pada tahun 2003.
Kedua konvensi internasional tersebut dikatakan sebagai tonggak
perkembangan ekstradisi sebagai instrumen dalam upaya penegakan hukum
mengingat jumlah negara yang menandatangani dan meratifikasi kedua
konvensi terbilang cukup besar. UNTOC yang pada saat pengesahannya
ditandatangani oleh 140 negara, sampai dengan bulan April 2015 telah
diratifikasi oleh 175 negara di dunia.
Kedua konvensi Internasional tersebut menyatakan bahwa dalam hal sebuah
negara mengatur ekstradisi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan
perjanjian, maka negara tersebut pada saat ratifikasi konvensi tersebut
dapat menganggap konvensi tersebut sebagai perjanjian ekstradisi dengan
negara-negara pihak lainnya. Dari ketentuan tersebut maka jelaslah bahwa
dalam perspektif internasional, telah menjadi instrumen utama dalam kerja
sama pengakan hukum internasional yang pelaksanaannya tidak lagi hanya
sebatas ada atau tidak adanya kemauan dua negara untuk bekerja sama,
melainkan sebuah kesepakatan internasional yang diharuskan terlembaga
dalam sistem hukum di setiap negara.
Kedua konsep dalam memandang ekstradisi tersebut, yaitu di satu sisi
sebagai bentuk kerja sama antaranegara dan di lain sisi sebagai bagian tidak
terpisahkan dari upaya penegakan hukum pada gilirannya menimbulkan
diskursus dalam memahami ekstradisi yaitu antara konsep tradisional
ekstradisi dan konsepnya yang modern.
Dalam konsepnya yang tradisional, dimana ekstradisi masih dipahami
sebagai kerja sama antar negara, maka pelaksanaan ekstradisi merupakan
kewenangan pemerintah yang dalam hal ini berhak untuk mengabulkan atau
menolak permintaan ekstradisi merupakan keputusan eksekutif yang
melekat pada Pemerintah.
Konsep ekstradisi dalam bentuknya yang tradisional tersebut tidak dapat
dilepaskan dari azas “non intervensi” yang dikenal dalam hukum
internasional. Menurut asas ini, maka suatu negara tidak boleh campur
tangan atas masalah dalam negeri negara lain, kecuali di negara itu sendiri
menyetujui secara tegas.
Mengingat yurisdiksi hukum sebuah negara hanya dapat diterapkan dalam
batas wilayah negara tersebut, maka Ketika pelaku kejahatan telah keluar
dari batas yurisdiksi negara yang berhak mengadilinya, upaya memulangkan
orang tersebut tidak lagi dipandang sebagai permasalahan penegakan
hukum melainkan telah menjadi ruang lingkup hubungan diplomatik antar
negara yang pelaksanaannya diserahkan pada keputusan politik
Pemerintah.
Sebaliknya, dalam konsepnya yang modern, di mana ekstradisi di anggap
merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum, maka pelaksanaan
ektradisi harus dilakukan sesuai prinsip proses hukum yang adil (due
process of law) yang menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan
hak asasi manusia termasuk orang yang dimintakan ekstradisi.
Telah menjadi pehamanan yang diterima secara umum bahwa sejuah mana
upaya perlindungan hak-hak asasi manusia di sebuah negara dapat dilihat
dari sistem peradilan pidana yang berlaku di negara tersebut.
Dalam konteks perlindungan hak-hak manusia tersebut maka negara pada dasarnya
memiliki dua macam kewajiban yaitu di satu sisi negara dan aparaturnya dilarang
untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan di lain sisi
negara wajib memberikan perlindungan atau mencegah pelangagran hak-hak asasi
manusia yang dilakukan terhadap seseorang oleh siapapun. Oleh karena itulah, maka
jaminan procedural yang terlembaga dalam proses penegakan hukum seperti hak
atas persidangan yang adil (fair trial) dan batasan waktu penahanan merupakan
fundamental mendasarkan dalam upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia
tersebut.
Pemahaman yang memandang ekstradisi sebagai bagian integral dari upaya
penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kesadaran aparat
penegakan hukum di seluruh dunia bahwa untuk mengatasi perkembangan kejahatan
yang telah memasuki dimensi baru di tengah era globalisasi saat ini, maka upaya
penegakan hukum tidak boleh dibatasi oleh kendala yurisdiksi dan batasan antar
negara. Di kala pelaku kejahatan dapat mudahnya berpindah tempat dan
mengendalikan kegiatan kejahatannya atau dengan memanfaatkan kecanggihan
teknologi, maka penegakan hukum pun harus dilakukan dengan sama lintas negara.
Organisasi Penegak Hukum yang berskala internasional seperti Asosiasi Jaksa
Internasional (International asspciation of prosecutor disingkat, IAP) telah
menyatakan kebulatan tekad untuk menigkatkan kerja sama di antara mereka
dalam upaya memberantas kejahatan.
Dalam Deklarasi Busan tentang Kerjasama Antara Para Pimpinan Kejasaan (The
Busan Declaration On Cooperation Among High Level Prosecutors) yang dihasilkan
pada Konferensi Regional IAP Asia Pasifik kelima di Seoul, Korea Selatan, 8 – 12 Juni
2008, para Pimpinan Kejaksaan di seluruh dunia sepakat untuk menciptakan
kerjasama yang lebih erat dan kuat di masa yang akan datang termasuk memperkuat
dengan pondasi hukum sebagai dasar kerja sama bilateral, jika memungkinkan
dengan memperluas jangkauan dari perjanjian ekstradisi dan perjanjian Bantuan
Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana untuk kerjasama yang lebih sukses.
Dalam penerapannya saat ini, konsep mana yang dipilih dalam pengaturan ektradisi
di berbagai belahan dunia pun masih beragam. Sebagai contoh, Amerika Serikat
sampai saat ini masih menerapkan ekstradisi hanya berdasarkan perjanjian bilateral,
sedangkan negara Uni Eropa Mulai mengembagkan pelaksanaan ekstradisi atas dasar
perjanjian multilateral.
Sementara itu pelaksanaan ekstradisi yang dilandaskan pada prinsip
resiprositas pun telah banyak dilakukan oleh negara-negara di berbagai
belahan dunia.
Disamping itu, walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang
sebagai bagian dari hukum internasional tetap peninjauan dan
pembahasannya tidaklah mungkin hanya ditekankan pada segi-segi hukum
internasional saja, sebab ada hal-hal yang tidak mungkin diatur atau
dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi terutama hal-
hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing negara yang
bersangkutan, yaitu antara lain penangkapan dan penahanan orang yang
diminta, keputusan tentang penentuan kejahatannya apakah termasuk
kejahatan politik atau tidak, tentang lembaga atau instansi yang berwenang
untuk memutuskan apakah permintaan akan diterima atau ditolak dan lain-
lainnya.
B. PERKEMBANGAN EKSTRADISI SEBAGAI
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
Ekstradisi pada dasarnya memiliki dua elemen mendasar yang satu sama lain
tidak dapat dipisahkan yaitu elemen kerja sama antarnegara dan elemen
penegakan hukum. Ekstradisi sebagai bentuk kerja sama antara negara dapat
dilihat dari landasan pelaksanaan ektradisi, yaitu adanya perjanjian atau
dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia
menghendakinya. Sementara itu, ekstradisi sebagai bagian dari upaya
penegakan hukum dapat disimpulkan dari tujuan dilaksanakannya ekstradisi
tersebut yaitu untuk mengadili dan memidana seseorang karena disangka
atau dipidana atas kejahatan yang dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah
negara yang meminta penyerahan tersebut.
Sebagai bentuk kerja sama antar negara untuk saling menyerahkan orang
yang diminta oleh salah satu pihak, maka konsep ekstradisi justru pada
awalnya merefleksikan hubungan politik antara kedua negara.
Ekstadisi seringkali digunakan untuk meminta pengembalian musuh-musuh
politik atau musuh keagamaan dari golongan yang berkuasa, sedangkan para
pelaku kejahatan konvensional jarang dicari dan di mintakan ekstradisi karena
dianggap perbuatan mereka hanya merugikan individu dan tidak mengancam
kepentingan negara atau kepentingan umum.
Sementara itu, gagasan unutk menggunakan ekstradisi sebagai instrumen
dalam mendukung upaya penegakan hukum mulai muncul pada periode
Tahun 1833 sampai 1948. Pada periode ini, mulai tumbuh kesadaran bersama
untuk menggunakan ekstradisi sebagai instrumen internasional guna
menekan tingginya angka kejahatan, termasuk kejahatan konvensional.
Dalam perkembangannya, konsep menggunakan ekstradisi sebagai dalam
mendukung upaya penegakan hukum diwujudkan dengan munculnya
berbagai konvensi internasional yang mewajibkan negara pihak dalam
konvensi tersebut untuk mendorong efektifitas ekstradisi sebagai salah satu
bentuk kerja sama internasional di bidang penegakan hukum.
Di antara berbagai konvensi tersebut, dua konvensi yang dapat dikatakan
memberikan landasan bagi pengembangan ekstradisi sebagai instrumen kerja
sama penegakan hukum adalah Konvensi PBB tentang Kejahatan
Transnasional (United Nations Convention Against Transnational Organized,
disingkat UNTOC) yang ditandatangani di Palermo, Italia pada tahun 2000 dan
Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention Against
Corruption, disingkat UNCAC) yang ditandatangani di Merida, Meksiko pada
tahun 2003.
Kedua konvensi internasional tersebut dikatakan sebagai tonggak
perkembangan ekstradisi sebagai instrumen dalam upaya penegakan hukum
mengingat jumlah negara yang menandatangani dan meratifikasi kedua
konvensi terbilang cukup besar. UNTOC yang pada saat pengesahannya
ditandatangani oleh 147 negara, sampai dengan bulan April 2015 telah
diratifikasi oleh 185 negara di dunia. Sedangkan UNTAC yang pada saat
pengesahannya ditandatangani oleh 140 negara, sampai dengan bulan April
2015 telah diratifikasi oleh 175 negara di dunia.
Kedua konvensi Internasional tersebut menyatakan bahwa dalam hal sebuah negara
mengatur ekstradisi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian, maka negara
tersebut pada saat ratifikasi konvensi tersebut dapat menganggap konvensi tersebut
sebagai perjanjian ekstradisi dengan negara-negara pihak lainnya. Dari ketentuan
tersebut maka jelaslah bahwa dalam perspektif internasional, telah menjadi instrumen
utama dalam kerja sama pengakan hukum internasional yang pelaksanaannya tidak lagi
hanya sebatas ada atau tidak adanya kemauan dua negara untuk bekerja sama,
melainkan sebuah kesepakatan internasional yang diharuskan terlembaga dalam sistem
hukum di setiap negara.
Dalam konsepnya yang tradisional, dimana ekstradisi masih dipahami sebagai kerja
sama antar negara, maka pelaksanaan ekstradisi merupakan kewenangan pemerintah
yang dalam hal ini berhak untuk mengabulkan atau menolak permintaan ekstradisi
berdasarkan pertimbangan kepentingan. Dengan demikian maka sesuai konsep
tersebut, ekstradisi merupakan keputusan eksekutif yang melekat pada pemeritah.
Konsep ekstradisi dalam bentuknya yang tradisional tersebut tidak dapat dilepaskan
dari azas “non intervensi” yang dikenal dalam hukum internasional. Menurut asas ini,
maka suatu negara tidak boleh campur tangan atas masalah dalam negeri negara lain,
kecuali di negara itu sendiri menyetujui secara tegas.
Mengingat yurisdiksi hukum sebuah negara hanya dapat diterapkan dalam
batas wilayah negara tersebut, maka Ketika pelaku kejahatan telah keluar dari
batas yurisdiksi negara yang berhak mengadilinya, upaya memulangkan orang
tersebut tidak lagi dipandang sebagai permasalahan penegakan hukum
melainkan telah menjadi ruang lingkup hubungan diplomatik antar negara
yang pelaksanaannya diserahkan pada keputusan politik Pemerintah.
Sebaliknya, dalam konsepnya yang modern, di mana ekstradisi di anggap
merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum, maka pelaksanaan
ektradisi harus dilakukan sesuai prinsip proses hukum yang adil (due process
of law) yang menjunjung tinggi penghormatan dan perlindungan hak asasi
manusia termasuk orang yang dimintakan ekstradisi.
Telah menjadi pehamanan yang diterima secara umum bahwa sejuah mana
upaya perlindungan hak-hak asasi manusia di sebuah negara dapat dilihat
dari sistem peradilan pidana yang berlaku di negara tersebut.
Dalam konteks perlindungan hak-hak manusia tersebut maka negara pada dasarnya
memiliki dua macam kewajiban yaitu di satu sisi negara dan aparaturnya dilarang
untuk melakukan tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia dan di lain sisi
negara wajib memberikan perlindungan atau mencegah pelangagran hak-hak asasi
manusia yang dilakukan terhadap seseorang oleh siapapun. Oleh karena itulah,
maka jaminan procedural yang terlembaga dalam proses penegakan hukum seperti
hak atas persidangan yang adil (fair trial) dan batasan waktu penahanan
merupakan fundamental mendasarkan dalam upaya perlindungan terhadap hak
asasi manusia tersebut.
Pemahaman yang memandang ekstradisi sebagai bagian integral dari upaya
penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kesadaran aparat
penegakan hukum di seluruh dunia bahwa untuk mengatasi perkembangan
kejahatan yang telah memasuki dimensi baru di tengah era globalisasi saat ini,
maka upaya penegakan hukum tidak boleh dibatasi oleh kendala yurisdiksi dan
batasan antar negara. Di kala pelaku kejahatan dapat mudahnya berpindah tempat
dan mengendalikan kegiatan kejahatannya atau dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi, maka penegakan hukum pun harus dilakukan dengan sama
Organisasi Penegak Hukum yang berskala internasional seperti Asosiasi Jaksa
Internasional (International asspciation of prosecutor disingkat, IAP) telah
menyatakan kebulatan tekad untuk menigkatkan kerja sama di antara mereka dalam
upaya memberantas kejahatan.
Dalam Deklarasi Busan tentang Kerjasama Antara Para Pimpinan Kejasaan (The
Busan Declaration On Cooperation Among High Level Prosecutors) yang dihasilkan
pada Konferensi Regional IAP Asia Pasifik kelima di Seoul, Korea Selatan, 8 – 12 Juni
2008, para Pimpinan Kejaksaan di seluruh dunia sepakat untuk menciptakan
kerjasama yang lebih erat dan kuat di masa yang akan datang termasuk
memperkuat dengan pondasi hukum sebagai dasar kerja sama bilateral, jika
memungkinkan dengan memperluas jangkauan dari perjanjian ekstradisi dan
perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam masalah pidana untuk kerjasama
yang lebih sukses.
Dalam penerapannya saat ini, konsep mana yang dipilih dalam pengaturan ektradisi
di berbagai belahan dunia pun masih beragam. Sebagai contoh, Amerika Serikat
sampai saat ini masih menerapkan ekstradisi hanya berdasarkan perjanjian bilateral,
sedangkan negara Uni Eropa Mulai mengembangkan pelaksanaan ekstradisi atas
Sementara itu pelaksanaan ekstradisi yang dilandaskan pada prinsip
resiprositas pun telah banyak dilakukan oleh negara-negara di berbagai
belahan dunia.
Disamping itu, walaupun masalah ekstradisi pada dasarnya dipandang
sebagai bagian dari hukum internasional tetap peninjauan dan
pembahasannya tidaklah mungkin hanya ditekankan pada segi-segi hukum
internasional saja, sebab ada hal-hal yang tidak mungkin diatur atau
dirumuskan sepenuhnya dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi terutama hal-
hal yang merupakan masalah dalam negeri masing-masing negara yang
bersangkutan, yaitu antara lain penangkapan dan penahanan orang yang
diminta, keputusan tentang penentuan kejahatannya apakah termasuk
kejahatan politik atau tidak, tentang lembaga atau instansi yang berwenang
untuk memutuskan apakah permintaan akan diterima atau ditolak dan lain-
lainnya.
C. LEMBAGA PELAKSANA
EKSTRADISI
Ekstradisi merupakan bentuk kerja sama penegakan hukum internasional
dengan mekanisme yang komplek dan mencakup lintas kewenangan yang
tersebut di berbagai instansi terkait. Permasalahan mengenai siapakah yang
berwenang mengajukan, menerima, memproses serta memutuskan dapat atau
tidaknya ekstradisi dilaksanakan merupakan pertanyaan dengan jawaban yang
beragam tergantung dari hukum positif yang berlaku di masing-masing negara,
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, subjek dalam pelaksanaan ekstradisi
pada dasarnya menyangkut dua negara, yaitu negara peminta dan negara yang
dimintai ekstradisi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa selain aspek hukum
internasional yang mengatur hubungan antar negara, ekstradisi juga berkait
dengan hukum positif yang berlaku di masing-masing negara, baik terkait
mekanisme kerja sama internasional, birokrasi pemerintah maupun hukum
acara pidana yang mengatur cara bekerjanya kepolisian, kejaksaan serta
pemeriksaan di persidangan dalam memproses pemintaan ekstradisi tersebut.
Bervariasi pengaturan tentang mekanisme kerja sama internasional serta lembaga
yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama tersebut, mendorong PBB untuk
mengeluarkan Model Treaty on Extradition berdasarkan Resolusi Nomor 45/116 Tahun
1990, yang memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mewujudkan
keseragaman pengaturan tentang proses ekstradisi sehingga diharapkan dalam
meningkatkan efektivitas pelaksamaam ekstradisi sebagai sebuah instrumen
internasional.
Pasal 5 Model perjajian Ekstradisi mengatur bahwa permintaan ekstradisim dokumen
pendukung dan komunikasi selanjutnya dilakukan melalui saluran diplomatik, secara
langsung antar Menteri kehakiman ataupun lembaga lain yang ditunjuk oleh para
pihak. Dengan demikian maka Model Ekstradisi yang dikeluarkan PBB tersebut
mewajibkan negara untuk memilik saluran komunikasi yang digunakan dalam proses
ekstradisi yaitu apakah melalui a) saluran diplomatik atau b) secara langsung kepada
lembaga pemerintah yang bewenang, yang dalam hal ini dapat merupakan Menteri
Kehakiman ataupun lembaga lain yang ditunjuk. Selanjutnya Pasal 10 Model Perjanjian
Ekstradisi mengatur bahwa negara yang dimintai ekstradisi menangani permintaan
ekstradisi sesuai dengan prosesdur yang berlaku menurut hukum positifnya, dan wajib
untuk secepatnya memberitahukan tentang keputusannya kepada negara peminta.
Dari ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa secara garis besar, proses
pelaksanaan ekstradisi melibatkan 2 (dua) lembaga, yaitu:
a. Saluran komunikasi (transmitting autority), yang berwenang untuk menerima,
menyalurkan serta memberitahukan keputusan tentang permintaan ekstradisi;
dan,
b. Lembaga yang berwenang melakukan proses ekstradisi (competent authority),
yaitu lembaga yang ada kenyataannya melaksanakan proses ektradisi, termasuk
berbagai upaya paksa serta pemeriksaan yang diperlukan dalam pengambilam
keputusan terkait ekstradisi, sesuai dengan hukum positif yang berlaku di
masing-masing negara.
Selanjutnya, didorong oleh komitmen untuk mewujudkan mekanisme kerja sama
yang efektif, konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional
Terorganisir atau United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime (selanjutnya disebut UNTOC) mengatur mengenai kewajiban negara pihak
untuk membentuk central authority di masing-masing negara yang berperan
sebagai pusat informasi dan koordinasi terhadap mekanisme kerja sama
Konsep central authority walaupun menurut UNTOC hanya dikenal dalam mekanime
bantuan timbal balik dalam masalah-masalah pidana, namun dalam perkembangannya
juga disarankan untuk diterapkan dalam mekanisme ekstradisi.
Selanjutnya menurut Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition yang diterbitkan
oleh UNODC pada tahun 2007, karakteristik otoritas pusat seharusnya mempunyai tugas
dan fungsi sebagai berikut:
1. Authoritis with “the responsibility and power to execute request or to transmit them to
the competent authorities fox execution (otoritas-otoritas yang memiliki tanggung
jawab dan kewenangan dalam mengeksekusi permintaan atau untuk menyampaikan
permintaan kepada otoritas berwenang untuk pelaksanaannya);
2. The central authority should effectively be a national central coordinating office,
wether its competency is no make request, execute the or merenly transmit
them”(Otoritas pusat harus secara efektif sebagai kantor pusat koordinasi nasional,
baik kompetensinya untuk membuat permintaan, melaksanakan/menjalankan
permintaan atau hanya menyampaikan permintaan).
3. Central Authority should have a number of key additional functions to those referred to
(Otoritas pusat harus memiliki beberapa fungsi pokok tambahan seperti hal-hal
berikut):
a. to receive, review and transmit request (menerima, mengkaji, dan
menyampaikan permintaan);
b. advise its international counterparts on the legal and other requirements and
constraints relevant to the making or effective execution of international
requests (memberikan masukan untuk pihak counterpart internasional tentang
hukum dan persyaratan-persyaratan lain dan hal relevan lain yang terkait untuk
pembuatan atau pelaksanaan permintaan internasional yang efektif);
c. if it is not itself able to execute the request, advise which other, if any, domestic
authority could (jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan suatu
permintaan sendiri, menyerahkan pada pihak lain, jika ada, pada otoritas
domestic lain yang dapat melaksanakannya);and
d. carry out a leadership, liaison, co-ordination and quality control role
domestically to ensure thath outgoing request from the requesting state can be
executed as quickly and effectively as Possible in the requested state
(menjalankan kepemimpinan, pemnghubung, koordinasi dan secara domestic
peran pengendalian kualitas untuk memjamin permintaan keluar dari negara
peminta dapat dilaksanakan secepat dan seefektif mungkin pada negara yang
BAB 3
KEJAHATAN LINTAS NEGARA
A. PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
Secara konseptual, transnational crime atau kejahatan transnasional adalah
tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini
diperkenalkan pertama kali secara internasional di tahun 1990an dalam The
Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment
of Offenders. Kejahatan transnasional menurut kongres tersebut diartikan
sebagai the large-scale and complex criminal activities carried out by tightly
or loosely organized associations and aimed at the establishment, supply and
exploitation of illegal markets at the expense of society (aktivitas kejahatan
yang berskala besar dan komples, dilakukan oleh organisasi kejahatan baik
yang bersifat tertutup maupun terbuka, dan ditujukan untuk membentuk,
mengsuplai dan ekspolitasi pasar gelap yang merugikan masyarakat).
Menurut Gergard O.W.Mueller dalam Transnational crimel:Definitions and
Concepts, pada pertengahan tahun 1990an, banyak peneliti mendefinisikan
“kejahatan transnasional” untuk menyebut offences whose inception, prevention,
and/or direct or indirect effects involve more than one country. Mueller sendiri
menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi certain
criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws of
several states or having an impact on another country. (sebuah fenomena
kejahatan yang melampaui Batasan negara, melanggar hukum dari beebrapa
negara atau kejahatan yang berdampak pada negara lain).
Namun demikian, sebelum berkembangannya istilah transnational crime tersebut,
pada sekitar tahun 1970an telah lebih dulu berkembang istilah organized crime
yang oleh PBB diartikan sebagai the large-scale and complex criminal activity
carried on by groups of those participating and at the expense of the community
and its members.
Istilah “transnational crime” diperkenalkan untuk menjelaswkan kaitan kompleks
yang ada antara organized crime , white—collar crime dan korupsi yang merupakan
masalah serius yang dimunculkan akibat “kejahatan sebagai bisnis” (crime as
business). Pengaturan kegiatan kejahatan melangkaui perbatasan negara dan
berdampak pada pelanggaran hukum berbagai negara, telah menjadi karakteristik
yang paling membahayakan dari kelompok kejahatan yang bergiat di tingkatan
internasional.
Selanjutnya, James O. Finckenauer menggagaskan bahwa terdapat sejumlah
tantangan yang menurutnya unik dalam mencegah atau menanggulangi fenomena
kejahatan transnasional, yaitu sebagai berikut:
a. kondisi pengalaman sosial dan kultural, berikut dengan pengalaman-
pengalaman yang menyertainnya, berbeda antara satu negara dengan yang lain.
Seperti peribahasa yang dikenal di Indonesia “lain padang, lain ilalang”;
b. Terdapatnya kejahatan yang tidak terikat dalam batas suatu negara, seperti
kejahatan yang dihasilkan melalui teknologi telekomunikasi, yaitu contohnya
cybercrime.
c. Semakin mudahnya perjalanan dan berkomunikasi secara global,
mempermudah keinginan-keinginan untuk menyembunyikan kejahatan dan
menghindari penegakkan hukum;
d. Arahan atau orientasi dari hukum dan penegakkan hukum suatu negara, selain
juga permasalahan hukum antar negara seperti ekstradisi.
Berdasarkan sejumlah paparan tersebut, makan tepatlah bila dapat dikatakan
membicarakan transnational crime bukanlah terpaku pada satu bentuk kejahatan
saja, namun lebih kepada cara suatu kelompok kejahatab beroperasi, seperti yang
dikemukakan oleh Louise L. Shelly, bahwa kelompok-kelompok transnational crime
adalah sebagai berikut:
e. Bermakarkas besar di satu negara;
f. Terlibat tindak kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara yang
kondisi pasarnya lebih menjanjikan;
g. melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko “penangkapan”.
Selanjutnya menurut Sardjono, kejahatan transnasional dapat di artikan secara luas
sebagai keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat
lintas batas negara. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan transnasional
menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan
hanya domestic dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain.
Selain istilah kejahatan transnasional, juga dikenal terminology kejahatan
internasional, yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang memang diperangi oleh
seluruh umat manusia yaitu kejahatan seperti perang, penjajahan dan perbudakan.
Kejahatan Internasional seperti ini dapat dikategorikan dalam hukum humaniter
yang membahas secara khusus mengenai hukum perang internasional. Ada pula
kejahatan internasional perkembangan dari dari bentuk kejahatan yang dikenal
secara domestic yang berubah sifatnya dan berkembang menjadi ancaman
masyarakat internasional secara umum seperti perdagangan orang dan peredaran
obat bius.
I Wayan Parthiana dalam bukunya, Hukum Pidana Internasional merumuskan
definisi dan klasifikasi kejahatan internasional sebagai berikut:
Pertama, Dimensi-dimensi internasional dari hukum pidana nasional bisa saja pada
hukum pidana nasional itu yang diberlakukan keluar batas-batas wilayah Negara yang
bersangkutan. Misalnya pemberlakuan hukum pidana nasional terhadap kejahatan yang
terjadi di dalam wilayah negara tetapi menimbulkan korban yang berada di luar wilayah
negara, seperti korban-korban di laut lepas atau di ruang udara di atas laut lepas.
Kedua, Dimensi-dimensi internasional dari kejahatannya adalah kejahatan dengan
segala akibatnya itu tidak terjadi semata-mata di dalam batas wilayah negara yang
bersangkutan, tetapi juga di wilayah neagra lain, sehingga tersangkut kepentingan atau
hukum nasional negara atau negara-negara lainnya, misalnya kejahatan yang dilakukan
di suatu negara ternyata menimbulkan korban di pelbagai negara. Sebagai contoh
adalah Kejahatan pemalsuan mata uang yang dilakukan di wilayah suatu negara dan
kemudian diedarkan ke negara-negara yang mata uangnya dipalsukan.
Ketiga, bahkan dimensi internasionalnya itu bisa terjadi pada subjek hukumnya, baik
subjek hukum sebagai si pelaku maupun korban dari kejahatan tersebut. Misalnya,
beberapa orang yang berada di wilayah negara yang berbeda-beda, bekerja sama
melakukan kejahatan yang menimbulkan korban juga di pelbagai negara. Dalam hal
ini,tersangkut kepentingan lebih dari satu negara dengan hukum nasionalnya masing-
masing.
Keempat, kombinasi dari pertama, kedua, dan ketiga. Dalam kenyataan hidup
sehari-hari, dapat dijumpai pelbagai jenis kejahatan yang boleh jadi menampakan
semua aspek seperti dipaparkan diatas.
Prof. Dr. H.R. Abdussalam dalam bukunya Hukum Pidana Internasional
memberikan juga Batasan definisi dari kejahatan internasional yang juga berbeda
aspek procedural penegakan hukumnya menjadi:
a. Tindak pidana internasional yang merupakan pelanggarah hukum hak asasi
manusia dalam keadaan damai yang dikenal dengan istilah transnational
crimes. Elemen-elemen dari transnational crime, antara lain conduct affecting
more than one state, conduct including or affecting citizen of more than one
state, means and methods tranced national boundaries
b. Tindak pidana internasional yang merupakan penaggaran hukum hak asasi
manusia dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional
disebut juga pelangagran hukum humaniter internasional (pelanggaran tehadap
konvensi-konvensi dan protokol).
Dengan perkemmbangannya yang demikian pesat, kejahatan lintas negara
(transnational crimes) dewasa ini telah menjadi salah satu ancaman serius
terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah
Transnational Organized Crimes (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum
internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu konvensi PBB mengenai
Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (United Nations Convention on Transnational
Organized Crime- UNTOC).
UNTOC menyebutkan bahwa transnational organized crime (TOC) atau kejahatan
lintas negara terorganisir adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu
kelompok yang terstruktur, terdiri atas tiga orang atau lebih, dalam kurun waktu
tertentu dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan unutk melakukan satu
atau lebih kejahatan serius sebagaimana yang dimaksud di dalam konvensi dalam
rangka memperoleh, secara langsung maupun tak langsung, keuntungan finansial
atau material lainnya.
Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangant kompleks. Beberapa
factor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara
antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta
perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat.
Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah
kompleksitas tersebut.
Pada Pertemuan Tingkat Tinggi yang diselenggarakan di Majelis Umum PBB tanggal
17 Juni 2010, sekretaris Jendral PBB Ban Ki-Moon menyebutkan bahwa di satu sisi
ancaman kejahatan lintas negara semakin meningkat namum di sisi lain
kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangant
penting bagi negara-negara untuk meningkatkan Kerjasama internasional untuk
secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara
tersebut.
UNTOC yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No.5 Tahun 2009 menyebutkan
sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara
terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan stwa
liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (cultural property),
perdanganan manusia, penyeludupan migran serta produksi dan perdaganan gelap
senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas
negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat
berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelapnarkoba tidak dirujuk dalam
Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan
bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dam tiga konvensi terkait narkoba sebelum
disepakatinya UNTOC, yaitu Single Convention on Narcotic Drugs, Covention on
psychotropic substances 1971 melalui UU No. 8 Tahun 1971, Convention against
the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988.
Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan lintas negara lainnya
yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan
pencurian dan penyeludupan objek-objek budaya, pedagangan organ tubuh
manusia, environmental crime (seperti illegal logging dan illegal fishing),cyber crime
Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas
beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas
kepada non-violent crime yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.
Semakin beragam dan meluasnya tindak kejahatan lintas negara tersebut telah
menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan Kerjasama
untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan
multilateral.
Di tingkat multilateral, PBB memprakarsai dan melakukan Langkah-Langkah
peningkatan kerja sama internasional memberantas kejahatan lintas negara,
sejalan dengan implementasi Konvensi-konvensi terkait yang ada, seperti : UNTOC
dan 3 Protokolnya, UNCAC, Single Convention on Narcotics Drugs 1961, Convention
on Psychotropic Subtances 1971 dan UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substance 1988. Terkait dengan itu, juga telah dibangun
jejaring antar intansi focal point masing-masing negara sebagaimana yang
dimandatkan oleh masing-masing konvensi, yang dihadapkan dapat mempercepat
penanganan terhadap kejahatan lintas negara.
Indonesia terus mempertegas komitmennya dan mendorong upaya untuk
mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir. Dalam
kaitan itu, Indonesia telah meratifikasi UNTOC melalui UU No. 5 Tahun 2009, selain
itu, terdapat sejumlah instrumen hukum internasional lainnya, yang telah
ditandatangani dan juga diratifikasi Indonesia seperti:
a. Single Convention on Narcotic Drugs 1961 melalui UU No. 8 Tahun 1976 tentang
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang
mengubahnya;
b. Convention on Psychotropic Subtance 1971 melalui UU No.8 tahun 1996
tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971;
c. Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance 1988 melalui UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United
Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic
Substance, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan
Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1998).
d. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children melalui UU No .14 Tahun 2009 tentang Pengesahan
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum
Perdagangan orang Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi
Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang
Terorganisasi);
e. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea melalui UU
No. 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land, Air and Sea (Protokol Menentang Penyeludupan Migran
Melalui Darat, Laut, dan Udara, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-
bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi);
f. United Nations Convention against Corruption 2003 melalui UU No. 7 Tahun
2006.
Dengan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan yang dibentuk tentunya
berdampak pula pada semakin sukarnya melakukan upaya pencegahan dan
pemberantasan kejahatan ini. Oleh karena itu, dalam upaya mencegah dan
memberantas kejahatan transnasional teroganisasi, kerja sama di antara negara-
negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral merupakan hal yang sangat
penting untuk segara direalisasikan.
Model kerja sama internasional dalam kaitan pencegahan dan pemberantasan
kejhatan transnasional terorganisasi memiliki banyak bentuk, diantaranya:
perjanjian ekstradisi, perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
(mutual assistance in criminal matters), perjanjian tentang transfer dalam proses
beracara, dan sebagainya. Di antara model-model perjanjian tersebut, perjanjian
ekstradisi dan perjanjian bantual timbal balik dalam masalah pidana merupakan
perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional
terorganisasi karena telah terbukti efektif sebagai cara untuk mencegah,
menangkap, dan menjatuhi pidana terhadap pelaku kejahatan transnasional.
B. KEJAHATAN TERKAIT
YURISDIKSI ASING
Yurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara kedaulatan
negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki jurisdiksi,
persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan
berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (equal
states don’t have jurisdiction over each other), dan prinsip tidak turut campur
negara terhadap urusan domestic negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari
prinsip hukum “par in parem non habet imperium”.
Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum “par in parem non habet imperium” ini
memiliki beberapa pengertian.
Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan jurisdiksi melalui pengadilannya
terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya.
Kedua, suatu pengadilan yang bentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak
dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau
peserta dari perjanjian internasional tersebut.
Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan
suatu negara lain yang dilaksanakan di dalm wilayah negaranya.
Anthony Csafani, dalam bukunya “The Concept of State Jurisdiction in Internasional
Space Law” mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi negara dengan
menyatakan sebagai berikut:”Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berati
hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah
dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu,
milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak
semata-mata merupakan masalah dalam negeri”.
Yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau
kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang
berdasarkan atas hukum yang berlaku. Didalamnya terdapat pula batas-batas ruang
lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum
Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah
mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk
mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Di samping itu, ada
beberapa orang (subjek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi
wilayah suatu negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.
Menurut Rebecca M.M Wallace, yurisdiksi merupakan atribut kedaulatan suatu
negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk
mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini
mencakup yurisdiksi untuk menentuka (dan melarang), untuk mengadili dan
melaksanakan undang-undang.
Setiap negara berdaulat yang tekag diakui pasti memiliki yurisdiksi untuk
memunjukan kewibawaannya pada rakyatnya atau pada masyrakat internasional.
Diakui secara universal baik setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatur
tindakan-tindakan dalam teritorinya sendiri dan tidakan lainnya yang dapat
merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.
Dalam kaitannya dengan prinsip dasar kedaulatan negara, suatu negara yang berdaulat
menjalankan yurisdiksi/kewenangannya dalam wilayah negara itu. Berdasarkan
kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, atau kewenangan negara
untuk mengatur masalah intern dan ekstren. Dengan kata lain dari kedaulatannya
itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negeri. Dengan hak, kekuasaan, atau dengan
yurisdiksi tersebut suatu negara mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah
yang dihadapinya sehingga terwujur apa yang menjadi tujuan negara itu.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya negara berdaulat yang dapat
memiliki yurisdiksi menurut hukum internasional. Ciri pokok dari kedaulatan dalam
batas-batas ini, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan
benda di dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdulat, bahwa
negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda didalam batas-batas
teritorialnya, dan dalam semua perkara berdata dan pidanayang timbul didalam batas-
batas teritorial ini. Prinsip yurisdiksi teritorial ini adalah prinsip yang paling mapan dan
penting dalam hukum internasional, yaitu bahwa suatu negara memiliki yurisdiksi
terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas
wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat.
Dari uraian diatas terdapat hubungan yang sangat erat antara wilayah suatu negara
dengan kewenangan yurisdiksinya. Menurut Glanville Williams hubungan yang erat
tersebut dapat dijelaskan karena adanya faktor-faktor berikut:
1. Negara dimana suatu perbuatan tindak pidana kejahatan dilakukan biasanya
mempunyai kepentingan paling kuat untuk menghukumnya;
2. Biasanya sipelaku penjahat ditemukan dinegara tempat yang melakukan tindak
pidana;
3. Biasanya pengadilan setempat (local forum) dimana tindak pidana terjadi
adalah yang paling tepat, karena saksi-saksi (dan mungkin barang buktinya)
dapat ditemukan dinegara tersebut;
4. Adanya fakta bahwa dengan tersangkutnya lebih dari satu sistem hukum yang
berbeda, maka akan janggal bila seseorang tundak pada dua sistem.
Namun demikian, adakalanya yurisdiksi itu harus tunduk kepadapembatasan
tertentu yang ditetapkan oleh hukum internasional. Dalamhal ini yang dimaksud
adalah "hak-hak istimewa ekstrateritorial", yaknisuatu istilah yang dipakai untuk
melukiskan suatu keadaan dimanastatus seseorang atau benda yang secara fisik
terdapat di dalam suatu wilayah negara, tetapi seluruhnya atau sebagian
dikeluarkan dari yurisdiksi negara tersebut oleh ketentuan hukum
internasional.Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun
keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya. Negara-negara lain pun dapat mempunyai
yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan luar negeri Di samping
itu, ada beberapa orang (subjek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap
yurisdiksi wilayah suatu negara meskipunmereka berada di dalam negara
tersebut.Oleh karena itulah, selain prinsip yurisdiksi teritoial, juga dikenalprinsip
yurisdiksi personal, yaitu suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena
kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga.Sebaliknya, adalah kewajiban
negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di
luar negeri.
Yurisdiksi personal, berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah bergantung Pada
kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum.Kualitas ini dapat
membenarkan suatu negara-negara menjalankan yurisdiksinya apabila orang itu
berada dalam kekuasaan negara dan proses peradilan dapat dilaksanakan
terhadapnya. Hal ini pada umumnyaterjadi apabila seorang individu memasuki
wilayah negara tersebut, baiksecara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.
Menurut praktik internasional dewasa ini yurisdiksi terhadapindividu dilaksanakan
berdasarkan prinsip prinsip berikut:
a. Prinsip nasional aktif. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi
terhadap warga negaranya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum
internasional kepada semua negara yang hendak memberlakukannya. Semua
prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa negara tidak wajib
menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana
diluar negeri;
b. Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan
yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian hukum
internasional mengakui prinsip ini tetapi dengan beberapa pembatasan. Dalam
Cutting case tampat bahwa negara yang tidak mengakui prinsip ini, juga tidak
wajib memberikan pengakuan terhadap peradilan yang dilaksanakan oleh
negara lain terhadap warga negaranya. Dasar pembenar prinsip nasionalitas
pasif adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya diluar
negeri, dan apabila negara teritorial dimana tindak pidana itu terjadi tidak
menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut maka negara asal
korban berwenang menghukum tidak pidana itu, apabila orang itu berada
diwilayahnya. Tetapi sebagai keberatan dapat dikemukakan bahwa kepentingan
umum negara tidak terganggu, karena salah seorang warga negara itu dirugikan
Disamping yurisdiksi teritorial dan personal, dalam perkembangan yang juga
dikenal yurisdiksi disebut menurut prinsip perlindungan dan prinsip yurisdiksi
internasional
Menurut prinsip perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya
terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan diluar negeri yang diduga
dapat mengancam kepentingan keamanan. integritas, dan kemerdekaan negara.
Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu
negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada
umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di
dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan,
integritas, dan kemerdekaan orang lain. Sementara itu, menurut prinsip Yurisdiksi
Universal setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang
mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana
kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip
yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat
internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan
internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang
(individu). Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk
pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan
kejahatan perang.
Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum
internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan
pembajakan dilaut, Kejahatan perang juga telah diterima universal sebagai
kejahatan yang tunduk kepada yurisdiksi setiap negara meskipun jenis kejahatan ini
sangat sensitif dan lebih berat bobot politiknya. Sebagai tambahan, Indonesia telah
menandatangani beberapa perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal
balik dalam masalah Pidana, di antaranya: Perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah
Malaysia yang dimuat dalam Undang-undang No . 9 Tahun 1974, perjanjian
ekstradisi dengan pemerintah Philipina melalui Undang-undang No.10 Tahun 1976,
perjanjian ektradisi dengan pemerintah kerajaan Thailand melalui Undang-undang
No. 2 Tahun 1978, serta pejanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dengan pemerintah Australia pada Tahun 1995.
C. PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG
EKSTRADISI DI BERBAGAI NEGARA
1. Ekstradisi di Amerika Serikat
Proses ektradisi kepada Amerika Serikat dimulai dengan permintaan disampaikan
oleh negara peminta kepada menteri luar negeri Amerika Serikat dokumentasi yang
diperlukan oleh perjanjian. Dalam hal terdapat kekawatiran bahwa orang yang
dicari akan dapat melarikan diri, maka sebelum dikirimkannya permintaan
ekstradisi secara formal, negara peminta dapat terlebih dahulu mengirimkan
permintaan secara informal disertai permohonan penangkapan sementara dengan
jaminan bahwa akan segera ditindaklanjuti dengan dokumen resmi permintaan
ekstradisi yang di perlukan. Dalam kedua kondisi tersebut, menteri Luar Negeri
sesuai dengan pertimbangannya, dapat meneruskan permintaan tersebut kepada
Jaksa Agung untuk memulai prosedur penangkapan buronan dengan tujuan bahwa
permintaan tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan
Pedoman bagi Para Jaksa (The united states Attorneys Manual) selanjutnya mengatur
peranan Jaksa Agung terhadap proses ekstradisi tersebut, sebagai berikut:
1. Kantor Urusan Internasional (Office of Internatinal Affairs, disingkat OIA) Departemen
Kehakiman meneliti kelengkapan syarat-syarat permintaan ekstradisi dan
menerukannya kepada Kantor Kejaksaan di wilayah dimana buronan tersebut
ditemukan;
2. Setelah memperoleh surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan,
maka Jaksa yang ditugaskan untuk menagani kasus tersebut dapat menangkap orang
yang dicari dan membawanya kepada hakim magistrat atau hakim distrik, dimana
Pemerintah dapat mengajukan penolakan terhadap kemungkinan pelepasan dengan
jaminan terhadap orang tersebut.
Bedasarkan ketentuan 18 U.S.C §3184, sebuah sidang peradilan akan diselenggarakan
untuk menentukan apakah buronan tersebut di ekstradisikan. Tujuan dari pemeriksaan di
persidangan tersebut adalah untuk menentukan apakah terdapat dasar-dasar yang kuat
(probable cause) untuk meyakini bahwa termohon ektradisi benar-benar melakukan
tindak pidana yang diatur dalam perjanjian ekstradisi. Dalam konteks tersebut, termohon
ektradisi dapat megemukakan pendapat dan bukti-bukti atau menolak mengakui
keberadaan dasar-dasar yang diajukan negara peminta tersebut.
Namun demikian kesempatan untuk melakukan pembelaan secara lengkap
sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana tidak dikenal dalam pemeriksaan
persidangan ekstradisi.
Dalam hal pengadilan menganggap bahwa tidak terdapat halangan bagi
pelaksanaan ekstradisi, maka termohon ekstradisi tidak dapat mengajukan banding
ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun demikian, ia tetap memiliki hak yang
mengajukan peninjauan ulang secara terbatas berdasarkan prinsip Habeas corpus,
yang pada dasarnya menyangkut pertimbangan atas kewenangan pengadilan untuk
mengadili, apakah tindak pidana yang dituduhkan termasuk dalam perjanjian
ekstradiksi, dam dalam hal yang sangat terbatas, apakah terdapat bukti-bukti yang
kuat sebagai dasar ketetapan hakim yang menyatakan bahwa terdapat dasar-dasar
yang layak (reasoneable ground) untuk meyakini bahwa permohon ektradisi
bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Terhadapan putusan
Pengadilan distrik atas keberatan termohon ekstradisi yang diajukan berdasarkan
prinsip habeas corpus, termohon ekstradisi dapat mengajukan banding kepada
pengadilan yang lebih tinggi.
Dalam perkembangannya, sebagai konsekuensi diratifikasinya Konvensi PBB anti
penyiksaan (U.N.Conventions against torture, singkat CAT) , kongres Amerika
Serikat memberlakukan § 2422 atas pembaruan ketentuan hubungan internasional
(the Foreign Affairs Act of 1998, disingkat FARRA), yang mewajibkan seluruh
lembaga federal untuk menyesuaikan prosedur yang berlaku menyesuaikan
prosedur yang berlaku dalam hubungan internasional untuk melaksanakan
kebijakan tersebut.
CAT sendiri mengajukan bahwa negara pihak tidak boleh mengusir, mengembalikan
atau melaksanakan ektradisi terhadap seseorang pada negara lain dimana terdapat
alasan mendasar untuk meyakini bahwa orang tersebut akan menghadapi
kemungkinan penyiksaan.
Selanjutnya, setelah pengadilan mengeluarkan ketetapan bahwa orang tersebut
bahwa orang tersebut dapat ektradisi, maka pengadilan meneruskan ketetapan
tersebut kepada menteri luar negeri yang diberikan kewenangan untuk mengambil
kebijakan apakah akan menyerahkan buronan kepada negara peminta.
Dalam hal menteri luar negeri memutuskan untuk menyerahkan orang tersebut
kepada negara peminta, maka kantor urusan internasional (office of International
Affairs, disingkat OIA) Departemen Kehakiman memberitahukan negara peminta
untuk mempersiapkan serah terima termohon ekstradisi sesuai dengan jangka
waktu yang ditentukan dalam perjanjian ektradiksi, dengan ketentuan bahwa
termohon ekstradisi dapat dibebaskan jika dalam jangka waktu tertentu,negara
peminta tidak dapat melaksanakan serah terima tersebut namun dalam beberapa
kasus, atas dasar Konvensi PBB Anti Penyiksaan dan Undang- Undang Hubungan
Luar Negeri 1998, pada kenyataannya termohon ekstradisi kembali dapat
mengajukan keberatan atas keputusan Menteri Luar Negeri yang diambil pasca
terbitnya ketetapan Pengadilan. Dengan demikian, maka keberadaan konvensi
tersebut serta peraturan pelaksanaannya oleh sebagian kalangan dianggap
memperluas kewenangan pengadilan untuk mempertimbangkan pelaksanaan
ekstradisi, walaupun dalam hal ini masih terdapat perbedaan pandangan apakah
peninjauan ulang berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan PBB tersebut dapat
dibenarkan.
2. Ekstradisi di Filipina
Ketentuan ekstradisi dalam hukum Filipina diatur dalam Keputusan Presiden
Nomor 1069 Tahun 1977 (Presidential Decree No. 1069, c. 1977).Pasal 4 ketentuan
tersebut mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi yang diajukan kepada
Fillipina oleh negara peminta, yaitu sebagai berikut.
1. Setiap negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi denganfilipina atau
konvensi terkait ekstradisi dimana Filipina menjadi pihaknya, dapat mengajukan
permintaan ektradisi terhadap seseorang yang diduga berada di wilayah hukum
filipina
2. Permintaan harus diajukan melalui saluan diplomatik negara peminta, ditujukan
kepada Menteri Luar Negeri dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang
dipersyaratkan. Selanjutnya, Pasal 20 mengatur bahwa dalam keadaan darurat
Negara peminta dapat meminta penahanan sementara kepada Pemerintah
Filipina sebelum diajukannya permintaan ekstradisi secara resmi.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pemintaan penahanan sementara tersebut akan
dikirimkan kepada Direktur Biru Investigasi nasional di Manila baik melalui saluran
diplomatik atau dikirmkan langsung melalui telegram.
Setelah telah menerima permintaan penahan sementara tersebut, Direktu Biro
Invenstigasi nasional atau Pejabat untuk yang ditunjuk olehnya, segera meminta
surat perintah penangkapan diri Hakim pada pengadilan regional di Provinsi atau
distrik yang wilayah hukumnya meliputi tempat pemohon ektradisi diduga berada.
Direktu Biro Investigasi Nasional melalui menteri luar negeri selanjutnya
meberitahukan hal tersebut kepada negara peminta.
Jika dalam 20 hari setelah penahan sementara terhadap permohon ektradisi,
menteri luar negeri belum menerima permintaan ekstradisi secara resmi serta
dokumen dimaksud dalam Pasal 4 dari negera peminta, maka termohon ekstradisi
harus segara dilepaskan dari penahanan sementara. Namun demikian pelepasan
dari penahanan sementara tersebut tidak menutup kemungkinan untuk kembali
melakukan penangkapan serta pelaksanaan ektradisi secara resmi telah diterima
sesuai dengan perjanjian ataupun konvensi terkait
Pasal 5 selanjutnya mengatur bahwa kecuali jika menurut menteri luar negeri,
permintaan ekstradisi yang diajukan tidak memenuhi syarat yang diajukan dalam
peraturan ini serta perjanjian ekstradisi ataupun konvensi terkait, maka menteri
luar negeri wajib meneruskan permintaan ekstradisi tersebut serta dokumen-
dokumen kelengkapannya kepada Jaksa Agung yang kemudian segara menunjuk
seorang Jaksa untuk menangani perkara tersebut.
Jaksa yang telah ditunjuk kemudia mengajukan permintaan secara tertulis disertai
dengan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada pengadilan
regional di provinsi atau distrik yang wilayah hukumnya meliputi tempat termohon
ektradisi diduga berada, dengan permintaan agar pengadilan memeriksa dan
mempertimbangkan permintaan ekstradisi tersebut.
Menurut Pasal 6, setelah menerima permintaan tertulis dari jaksa terkait
permohonan ekstradisi, hakim pada Pengadilan Regional sesegera mungkin,
memanggil termohon ektradisi untuk menghadap ke pengadilan dan memberikan
tanggapannya atas permohonan ekstradisi terhadap dirinya tersebut pada waktu
dan tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan.
Hakim tersebut dapat menerbitkan perintah penahanan terhadap termohon
ekstradisi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Filipina jika menurutnya, bahwa
penahanan terhadap termohon ektradisi dibutuhkan untuk menjamin kelancaran
penanganan perkara. Sejalan dengan hal tersebut, maka jika termohon ektradisi
tidak memenuhi panggilan pada waktu sidang yang telag ditentukan, atau jika ia
tidak berada dalam penahanan, maka Pengadilan selanjutnya dapat mengeluarkan
perintah penahanan terhadap yang berlaku di seluruh wilayah hukum Filipina
(Pasal 8).
Berdasarkan ketentuan Pasal 9, dalam persidangan perkara ektradisi, ketentuan
hukum acara pidana yang berlaku dapat diterapkan selama mungkin untuk
diterapkan serta tidak bertentangan dengan sifat kesederhanaan pemeriksaan
perkara ektradisi, dan jalannya persidangan harus dilakukan dalam cara yang
menjamin pemeriksaan yang adil seta azas perdilan cepat. Alat bukti berupa
keterangan di bawah sumpah dapat digunakan dalam perkara ektradisi jika
dianggap layak dan diotentikaso secara hukum oleh Kepala Diplomatik atau Pejabat
Konsuleran Republik Filipina yang ditunjuk untuk menangani permintaan dari
negara peminta.
Selanjutnya Pasal 10 jo. Pasal 11 mengatur bahwa Keputusan Pengadilan segera
diberitahukan kepada termohon ektradisi, jika ia tidak hadir pada saat pembaca
putusan, dan Panitera Pengadilan harus segera menyampaikan keputusan
Pengadilan tersebut kepada Menteri Luar Negeri melaui Jaksa Agung, atas putusan
pengadilan tersebut. Maka termohon ekstradisi, dalam waktu 10 hari setelah
menerima putusan dari pengadilan regional, berhak untuk mengajukan banding
Pengajuan banding dari termohon ekstradisi menunda pelaksanaan putusan dari
Pengadilan Regional tersebut. Dalam hal sebaliknya, putusan Pengadilan Regional
menjadi berkuatan hukum tetap dan dapat segera dilaksanakan (Pasal 12).
Menurut Pasal 16, setelah keputusan pengadilan dalam perkara ektradisi bersifat
final dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka termohon ektradisi diserahkan
kepada otoritas Negara Peminta pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh
Mentri Luar Negeri, setelah berkonsultasi dengan Diplomat dari Negera Peminta.
3. Ekstradisi di Australia
Proses Pelaksanaan Ekstradisi oleh Australia dalam kapasitas sebagai negara yang diminta
ekstradisi, pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu:
Menurut pasal 16 UU Ektradisi 1988, setelah menerima permintaan kepada semua hakim
magistrat (hakim pengadilan tingkat pertama di Australia) bahwa permintaan ektradisi atas
seseorang telah diterima dari negara lain.
Namun demikian, menurut Pasal 12 Ayat (1) UU ekstradisi 1988 seorang Hakim Magistrat,
setelah menerima permohonan penahanan sementara yang diajukan oleh negara peminta,
dapat menerbitkan pemerintah penahanan, dalam hal ia menilai bahwa informasi yang
diberikan dalam affidavit (penjelasan resmi dari negara perminta) tersebut bahwa orang yang
dimintakan penangkapannya oleh negara peminta merupakan orang yang dapat diekstradisi.
Setelah mengeluarkan surat perintah penahanan, Hakim Magistrat wajib melaporkan hal
tersebut kepada Jaksa Agung dengan melampirkan fotocopy affidavit dari negara peminta
Jaksa Agung, setelah menerima laporan dari Hakim Magistrat ataupun dengan cara lain
mengetahui mengenai adanya penerbitan perintah penahanan tersebut, dapat
memerintahkan hakim magistrat untuk membatalkan perintah tersebut jika menurut
pendapatnya penahanan tersebut tidak diperlukan atau tidak dapat dilakukan.
Selanjutnya menurut Pasal 19 Undang-undang Ekstradisi 1988, dalam hal
seseorang sebelumnya telah dilakukan penahanan atas dasar permintaan yang
diajukan oleh negara peminta (Pasal 12), ataupun Hakim Magistrat telah menerima
pemberitahuan dari Jaksa Agung sebagaimana dimaksud Pasal 16, ataupun
Magistrat menerima permohonan dari orang yang dimohonkan ekstradisi ataupun
negara peminta agar pemeriksaan dilakukan terkait permintaan ekstradisi dari
negara lain dan Magistrat menilai telah cukup waktu bagi orang yang di mintakan
ekstradisi untuk mempersiapkan diri guna kepentingan pemeriksaan tersebut,
maka Magistrat menggelar pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan aoa
terhadap orang tersebut dapat dilakukan ektradisi kepada negara peminta.
Dalam hal Hakim Magistrat menilai bahwa terhadap orang tersebut dapat
dilakukan ekstradisi, maka Hakim Magistratdapat memerintahkan bahwa orang
tersebut tetap berada dalam tahanan sampai dengan diterbitkannya surat perintah
penyerahan atau penyerahan sementara oleh Jaksa Agung, atau sebaliknya dalam
hal Jaksa Agung menilai bahwa orang tersebut tidak dapat dilakukan ektradisi,
maka Jaksa Agung dapat memerintahkan agar orang tersebut dilepaskan dari
tahanan
Namum demikian, menurut Pasal 16 UU Ekstradisi 1988, seseorang dapat saj
menyatakan kepada Magistrat bersedia secara sukarela untuk diserahkan kepada
negara permintaan ekstradisi yang dimohonkan terhadap dirinya oleh negara
peminta.
Dalam keadaan tersebut, maka kecuali meyakini bahwa permintaan tersebut
dilakukan atas dasar paksaan, hakim Magistrat wajib menjelaskan kepada orang
tersebut bahwa persetujuan yang diberikan oleh orang tersebut dapat berakibat
pada:
a. Orang tersebut akan dimasukkan ke dalam tahanan tanpa melakukan proses
pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, yaitu untuk menilai dapat
atau tidaknya ia di ekstradisi.
b. Dalam hak Jaksa Agung menerbitkan perintah penyerahan, maka orang
tersebut akan segera diserahkan kepada negara peminta.
Dalam hal setelah mendengar penjelasan tersebut, ternyata orang yang
bersangkutan tetap bersedia untuk secara sukarela menyerahkan diri, maka orang
tersebut segera dimasukan ke dalam tahanan daru kejahatan yang oleh orang
Menurut Pasal 22 UU Ekstradisi 1988, Jaksa Agung sesegera mungkin setelah
mengetahui bahwa seseorang dinyatakan dapat dilakukan ekstradisi (baik karena
persetujuan secara sukarela dari orang tersebut sebagaimana diatur Pasal 18
ataupun karena Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 19)
menentukan apakah orang tersebut dapat diserahkan untuk kejahatan-kejahatan
yang menjadi dasar permintaan ekstradisi tersebut.
Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Ekstradisi 1988, memberikan kesempatan kepada
orang yang dimintakan ekstradisi ataupun negara peminta ekstradisi untuk dalam
waktu 15 hari sejak dikeluarkannya keputusan oleh Hakim Magistrat mengenai
dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi, mengajukan banding kepada
Pengadilan federal (fedaral court) ataupun Mahkamah Agung Negara Bagian atau
wilayah, untuk meninjau ulang perintah tersebut.
Menurut Pasal 21 Ayat (3) terhadap Putusan Banding yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Federal ataupun Mahkamah Agung Negara Bagian atau wilayah, maka
termohon ekstradisi maupun negara peminta dapat kembali mengajukan banding
ke Persidangan Penuh Pengadilan
Ferderal (full Court of the Federal Court) dalam waktu 15 hari setelah
dikeluarkannya keputusan Banding oleh Pengadilan federal (Federal Court) ataupun
Mahkamah Agung Negara Bagian atau Wilayah tersebut.
Selanjutnya menurut Pasal 21 Ayat (5) terhadap Putusan Pengadilan di tingkat
banding tersebut, termohon ekstradisi ataupun negara peminta, dapat pula
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Australia (High Court of Australia) setelah
sebelumnya diberikan persetujuan (special leave) untuk itu oleh Mahkamah Agung
Australia.
Bab 4
Proses Ekstradisi di
Indonesia
A. PRINSIP-PRINSIP EKSTRADISI MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA
Ketentuan mengenai ekstradisi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang disahkan pada Tanggal 18 Febuari 1979
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3130), Undang-undang Nomor Tahun 1979
tersebut di bentuk untuk menggantikan Koninklijk Besluit van 8 Mei 1883 No. 26
(Staatblad 1883 – 188) tentang “Uitlevering van Vreemdelingen” (Peraturan
kerajaan dengan Penyerahan Orang Asing), yang dianggap tidak sesuai lagi dengan
tata hukum dan dengan perkembangan Negara Republik Indonesia yang merdeka.
Definisi ekstradisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979, adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta
penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu
kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah
Karena berwenang untuk mengadili dan memidananya. Dari definisi tersebut, maka
unsur dalam ekstradisi menurut hukum Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Negara yang meminta penyerahan seseorang;
2. Negara yang diminta untuk menyerahkan, yaitu negara tempat orang tersebut
diketahui atau diduga berada;
3. Tujuan penyerahan adalah untuk mengadili atau memidana orang tersebut karena
disangka atau dipidana melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang
menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan
tersebut.
Menurut penulis, dari ketiga unsur dapat dijabarkan dalam tiga unsur pokok, yaitu
unsur negara, unsur orang dan unsur tujuan, yang masing-masing sebagai berikut:
4. Unsur “Negara”
Unsur negara meliputi negara yang meminta penyerahan dan negara yang diminta
untuk menyerahkan seseorang. Hubungan antar kedua negara tersebut menurut Pasal
2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 dibangun atas dasar suatu perjanjian,
(“treaty”) yang diadakan oleh Negara Republik Indonesia dengan negara lain dan yang
Selanjutnya penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 menyatakan
bahwa Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum
bagi pembuatan [erjanjian dengan Negara-negara asing maupun untuk
menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian.
Dalam hal belum terdapat perjanjian ekstradisi, maka ekstradisi dapat dilakukan
atas dasar hubungan baik dan jika kepentinfan Negara Republik Indonesia
menghendakinya. Namun demikian, Undang-undang ternyata tidak memberikan
definisi lebih lanjut ataupun batasan mengenai yang dimaksud dengan “jika
kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.”
2. Unsur “Orang”
Menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, orang yang dapat
diekstradisikan ialah mereka yang oleh penjabat yang berwenang dari negara asing
diminta karena disangka melakukan kejahatan atau untuk menjalani pidana atau
perintah penahanan. Pasal 3 Ayat (2) memberikan perluasan terhadap pengertian
“disangka melakukan kejahatan”yaitu meliputi juga orang yang disangka melakukan
atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan
jahatan untuk melakukan kejahatan tersebut, sepanjang perbantuan, percobaan,
dan permufakatan jahata itu dapat dipidana menurut hukum Negara Repulik
Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.
Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, permintaan ekstradisi pada
dasarnya tidak dapat dilakukan terhadap warga negara Republik Indonesia. Hal ini
dilakukan guna kepentingan perlindungan warga negara sendiri sehingga dianggap
lebih baik, apabila yang bersangkutan diadili di negaranya sendiri.
Namun demikian ketentuan tersebut dapat disampingi, dalam orang yang
bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan.
Menurut penjelasan Pasal 7 Ayat (2) pertimbangan untuk menyerahkan warga
negara Indonesia untuk diadili di negara lain(di negara peminta) didasari
pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan neagra, hukum dan keadilan, dan
pelaksanaan penyerahan tersebut didasarkan pada asas timbal balik (resiprositas).
Sementara itu, permintaan ektradisi dapat ditolak jika orang yang diminta sedang
di proses di Negara Republik Indonesia untuk kejahatan yang di mintakan ekstradisi
atau jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam
wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 8 jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979). Selanjutnya Pasal 17 mengatur bahwa permintaan ekstradisi yang
telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa
atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di
Indonesia.
3. Unsur “tujuan”
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tujuan penyerahan dalam ekstradisi adalah
untuk mengadili atau memidana orang tersebut karena disangka atau pidana
melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam
yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 menganut prinsip bahwa tidak semua
kejahatan dapat diektradisikan, melainkan kejahatan-kejahatan berat yang secara
khusus diatur dalam Undang-undang maupun perjanjian ekstradisi antar kedua
negara.
Menurut Lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, terdapat 32 Jenis
kejahatan yang dapat dimintakan ekstradisi, yaitu sebagai berikut:
4. Pembunuhan;
5. Pembunuhan yang direncanakan;
6. Penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang;
7. Pemerkosaan, pembuatan cabul dengan kekerasan;
5. Persetubuhan dengan seorang Wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan
cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya
atau orang itu belum berumur 15 Tahun atau belum mampu dikawinkan
6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh cukup umur dengan orang lain sama kelamin
yang belum cukup umur;
7. Memberikan atau mempergunakan obat-obatan atau alat-alat dengan maksud
menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita;
8. Melarikan wanita dengan kekerasan ancaman kekerasan atau tipu muslihat dengan
sengaja melarikan sesorang yang belum cukup umur;
9. Perdaganan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur;
10. Penculikan dan penahanan melawan hukum;
11. Perbudakan;
12. Pemerasan dan pengancaman;
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas neger atau uang kertas bank
atau mengedarkan mata uang kertas negeri asal kertas bank yang ditiru atau
dipalsukan
14. Menyimpan atau memalsukan uang ke Indonesia yang telah ditiru atau
dipalsukan;
15. Pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan;
16. Sumpah palsu;
17. Penipuan;
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan;
19. Penggelapan;
20. Pencurian perampokan;
21. Pembakaran dengan sengaja;
22. Pengerusakan barang atau bangunan dengan sengaja;
23. Penyeludupan;
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan
keselamatan kereta api, kapal laut, atau kapal terbang dengan penumpang-
penumpangnya;
25. Menengelamkan atau merusak kapal di tengah laut;
26. Penganiayaan diatas kapal ditengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa
atau meyebabkan luka berat
27. Pemberontakan atau termufakatan untuk memberontak oleh dua orang atau
lebih diatas kapal ditengah laut menentang kuasa nahkoda penghasutan untuk
memberontak;
28. Pembajakan laut;
29. Pembajakan udara kejahatan penerbangan kejahatan terhadap sarana atau
prasaranan penerbangan;
30. Tindak pidana korupsi;
31. Tindak pidana narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya;
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-undang senjata api, bahan-
bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.
Namun demikian menurut Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomot 1 Tahun 1979
ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta
berhadap kejahatan yang lain tidak disebut dalam daftar kejahatan, sedangkan
melalui peraturan pemerintah, daftar kejahatan sebagaimana diatur dalam
lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tersebut dapat ditambah dengan
jenis perbuatan yang lain oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai kejahatan.
Selain hal-hal diuraikan diatas beberapa asas mendasar yang di atur dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1979 antara lain:
1. Ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik (Pasal 5)
2. Permintaan ekstradisi ditolak jika putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Republik Indonesia yang berwenang mengenai kejahatan yang dimintakan
eksradisinya telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Pasal 10);
3. Pemintaan ekstradisinya ditolak apabila orang yang dimintakan ekstradisinya
telah diadili dan bebaskan telah atau telah selesai menjalani pidananya di
negara lain mengenai kejahatan yang tindakan ekstradisinya. (asas nebis in
idem, Pasa 11)
4. Permintaan ekstradisi ditolak jika menurut hukum negara Repbulik Indonesia hak untuk
menuntut atau melaksanakan putusan pidana telah kadaluarsa ( Pasal 12);
5. Pemintaan ekstradisi ditolak jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi diancam dipidana
mati menurut hukum mendarat peminta sedangkan menurut negara Republik Indonesia
kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati tidak selalu dilaksanakan kecuali jika
negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan bahwa pidana mati tidak
akan dilaksanakan (Pasal 13);
6. Permintaan esktradisi ditolak jika menurut instansi yang berwenang berdapat sangkaan
yang lebih kuat bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut dipidana atau
dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan
politiknya atau kewarganegaraannya ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau
golongan penduduk tertentu (Pasal 14);
7. Permintan ekstradisi ditolak jika orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut dipidana
atau ditahan karena melakukan kejahatan lain daripada kejahatan yang karenanya ia
dimintakan ektradisinya kecuali dengan izin presiden (Asas khususan Pasal 15);
8. Permintaan ekstradisi ditolak jika orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan
kepada negara ketiga untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan sebelum ia
dimintakan ekstradisi itu (Pasal 16)
B. PELAKSANA PROSES EKTRADISI
Mencermati mekanisme proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No 1 Tahun 1979 maka disimpulkan bahwa proses pelaksanaan
ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang diminta ekstradisi dapat
dibagi 3 tahapan pokok yaitu sebagai berikut:
1. Tahap peneriman permintaan ekstradisi
Termasuk dalam tahap ini adalah dari negara melalui saluran diplomatik kepada
Menteri Kehakiman yang dilanjutkan dengan penelitian pelengkapan dokumen
dan syaratan ekstradisi oleh Menteri Kehakiman;
2. Tahap pemeriksaan perkara ektradisi
Termasuk dalam tahap ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian
terhadap orang yang dimohokan ekstradisi berdasarkan dokumen tertulis yang
diterima dari negara peminta, penyerahan berita acara hasil pemeriksaan
kepada Kejaksaan, pemeriksaan di muka pengadilan berdasarkan pemerintahan
terlulis dari Jaksa serta keluarnya penetapan pengadilan mengenai dapat atau
tidaknya dilakukan ekstradisi terhadap orang yang bersangkutan.
3. Tahap Persetujuan Presiden
Termasuk dalam tahap ini adalah diterimanya penetapan pengadilan oleh
Menteri Kehakiman dan masuknya pertimbangan dari berbagai instansi terkait
yaitu Menteri Luar Negeri, Kapolri Jaksa Agung disertai Menteri Kehakiman
sendiri, yang kemudian diajukan kepada presiden untuk memperoleh keputusan
mengenai apakah permintaan ekstradisi dapat disetujui atau ditolak.
Dari berbagai tahapan proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diuraikan diats,
maka dapat terlihat peran beberapa institusi yang terlibat secara langsung dalam
proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979 yaitu sebagai berikut:
a. Menteri Luar Negeri, dengan peranan:
‒ Meneruskan permintaan ekstradisi dari negara peminta kepada Menteri
Kehakiman;
‒ Dalam hal permintaan ekstradisi diajukan oleh negara yang belum memiliki
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka Menteri Luar Negeri memberikan
pertimbangan kepada Menteri Kehakiman mengenai dapat atau tidaknya
‒ Turut memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai dapat disetujui atau
ditolaknya permintaan ekstradisi sebagai bahan pertimbangan bersama-sama
dengan penetapan pengadilan;
‒ Menyampaikan keputusan Presiden mengenai disetujui atau ditolaknya
permintaan ekstradisi kepada negara peminta.
b. Menteri Kehakiman, dengan peranan:
‒ Menerima permintaan ekstradisi yang diajukan oleh negara peminta;
‒ Melakukan penelitian terhadap syarat-syarat permintaan ekstradisi serta dapat
meminta kepada negara peminta untuk melengkapi dokumen-dokumen yang
dibutuhkan untuk proses pelaksanaan ekstradisi;
‒ Dalam hal permintaan ekstradisi diajukan oleh negara yang belum memiliki
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka Menteri kehakiman melaporkan
permintaan tersebut kepada Presiden guna memperoleh persetujuan, dengan
disertai pertimbangannya serta pertimbangan Menteri Luar Negeri;
− Dalam hal permintaan ekstradisi yang diajukan oleh negara yang belum memiliki
perjanjian ekstradisi dengan disetujui oleh Presiden, maka Menteri Kehakiman
memperoses lebih lamjut seperti halnya adanya perjanjian ekstradisi antara
negara peminta dengan Negara Republik Indonesia. Sebaliknya dalam hal
Presiden menolak permintaan ekstradisi tersebut, Menteri Kehakiman
meneruskan keputusan tersebut kepada negara peminta melalui Menteri Luar
Negeri;
− Sesudah menerima penetapan Pengadilan tentang dapat atau tidaknya seseorang
diekstradisi, Menteri kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan;
− Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan
tetapi Menteri Kehakiman memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri
Kehakiman republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara
peminta dalam waktu yang dianggap cukup;
− Memberitahukan Keputusan Presiden mengenai disetujui atau ditolaknya
permintaan ekstradisi kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatik;
− Meberitahukan Keputusan Presiden mengenai disetujui atau ditolaknya permintaan
ekstradisi kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatic;
− Memberitahukan Keputusan Presiden mengenai disetujui atau ditolaknya
permintaan ekstradisi kepada Menteri Luar Negeri , Jaksa Agung, dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia;
− Menyerahkan orang yang dimintakan ekstradisi kepada Pejabat yang bersangkutan
dari nehara peminta, ditempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman.
c. Kepolisian, dengan peranan:
− Berdasarkan permintaan penahanan negara yang meminta yang disampaikan
melalui saluran Interpol Indonesia atau melalu saluran Diplomatik atau langsung
dengan pos atau telegram, dapat melakukan penahanan dengan alasan mendesak,
sebelum diterimanya permintaan ekstradisi;
− Setelah diterimanya permintaan ekstradisi dari negara peminta, melakukan
penahanan terhdap orang yang diminta apabila diajukan permintaan penahanan
terhadap orang yang diminta apabila diajukan permintaan penahanan oleh negara
− Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya dengan
dicatat dalam berita acara serta segera diserahkan kepada Kejaksaan Republik
Indonesia setempat;
− Turut memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai dpat disetujui atau
ditolaknya permintaan ekstradisi sebagai bahan pertimbangan Bersama-sama
dengan penetapan pengadilan.
d. Kejaksaan, dengan peranan:
− Berdasarkan permintaan penahanan negara yang meminta yang disampaikan
melalui saluran Interpol Indonesia atau melalui diplomatik atau langsung dengan
pos atau telegram, dapat melakukan penahanan dengan alasam mendesak,
sebelum diterimanya permintaan ekstradisi;
− Setelah diterimanya permintaan ekstradisi dari negara peminta, melakukan
penahanan terhadap orang yang diminta apabila diajukan permintaan penahanan
oleh negara peminta;
− Meminta penetapan perpanjangan penahanan kepada Hakim untuk setiap kali
selama 30 hari, dalam hal belum adanya penetapan Pengadilan mengenai
permintaan ekstradisi atau permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum
dapat dilaksanakan;
− Dalam hal penahanan dilakukan berdasarkan perintah Jaksa Agung, maka
melakukan pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya dengan
dicatat dalam berita acara serta segera diserahkan kepada Pengadilan untuk
dimintakan penetapan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan;
− Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh kepolisan, maka dalam waktu 7 (tujuh)
hari setelah menerima berita acara tersebut Kejaksaan dengan mengemukakan
alasannya secara tulis, meminta kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat
ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau
tidaknya orang tersebut diekstradisikan ;
− Jaksa menghadiri sidang pemeriksaan ekstradisi dipengadilan dan
mengemukakan pendapatnya;
− Melaksanakan penetapan hakim dengan cara menyampaikan pengadilan tersebut
kepada Menteri kehakiman untuk diteruskan kepada presiden;
− Turut memberikan pertimbangan keapda Presiden mengenai dapat disetujui atau
ditolaknya peermintaan ekstradisi sebagai bahan pertimbangan Bersama-sama
dengan penetapan pengadilan
e. Pengadilan Negeri, dengan peranan:
− Berdasarkan permintaan Jaksa mengeluarkan penetapan perpanjangan,
penahanan untuk setiap kali selama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal belum adanya
penetapan pengadilan mengenai permintaan ekstradisi atau permintaan
ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan;
− Berdasarkan permintaan jaksa, melakukan pemeriksaan kepada orang yang
dimintakan ekstradisi pada sidang yang terbuka untuk umum untuk menetapkan
dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi , dengan objek pemeriksaan
terdiri atas:
a. Identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstraddisi itu sesuai
dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
b. Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat di ekstradisi menurut
Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
c. Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum
kadaluwarsa;
d. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum
diajatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
e. Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di
Indonesia tidak;
f. Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.
Sementara itu, panjanganya birokrasi dalam proses ekstradisi yang membuat proses
ekstradisi menjadi tidak efektif juga patut mendapatkan perhatian khusus mengingat
efektivitas kecepatan dan ketepatan dalam mempersiapkan, memproses dan
mengeksekusi sebuah permintaan ekstradisi akan sangat berpengaruh bagi
terungkapnya proseesnpenanganan perkara kejahatan antar negara. Tidak terpenuhinya
efektivitas dan efiensi dalam proses di atas, akan mengakibatkan menguatnya persepsi
negative dari kalangan penegak hukum negara lain, terhadap keseriusan kegiatan
penegakan hukum dan kredibilitas penegak hukum di suatu negara.
Mengenai hal tersebut, Geoff Gilbert menulis bahwa walaupun ekstradisi merupakan
mekanisme utama dalam upaya negara tempat kejahatan dilakukan untuk meminta
Penyerahan elaku kejahatan tersebut dari negara lain, namun dalam kenyataanya,
pelaksanaan ekstradisi dapat menjadi sangat lambat yang berpotensi memberikan
kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melarikan diri atau justru hilangnya
kesempatan bagi negara peminta untuk mengadili atau memidana orang tersebut.
Dalam kondisi tersebut, mereka tidak jarang sebuah negara akhirnya menempuh
cara-cara pemulangan lain di luar mekanisme tradisi baik dengan deportasi
terselubung maupun penculikan.
Menurut I Wayan Parthiana, Proses ekstradisi di Indonesia, mengandung beberapa
kelemahan, yaitu antara lain:
a. Pertama, persyratan materiil yang terlalu banyak dan jika dalah satu saja todak
terpenuhi meskipun yang lain semuanya terpenuhi maka pengekstradisian tidak
akan bisa dilakukan. Hampir sebagian besar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum
tentang ekstradisi berisi persyratan yang harusdipenuhi terutama oleh negara
peminta untuk sampai pada keputusan apakah akan mengajukan permintaan
ataukah tidak. Meskipun menurut negara pemintasemua persyaratan sudah
b. Kedua, prosedut dan mekanismenya terlalu Panjang dan birokratis yakni melalui
saluran diplomatik mengingat masalah ekstradisi adalahmasalah antarnegara.
Mulai dari maksud negara peminta untuk meminta pengekstradisian orang yang
diminta, selanjutnya pemenuhan atas segala persyaratan meteriil yang
dibutuhkan, kemudian mengenai prosedur untuk mengajukan permintaan
sampai dengan keputusan dari negara yang dimintai ekstradisi terhadap
permintaan negara peminta yang ditindaklanjuti dengan pemberitahuannya
oleh negara yang dimintai ekstradisi kepada negara yang dimintai ekstradisi
kepada negara peminta dikabulkan oleh negara yang dimintai ekstradisi;
c. Ketiga, sebagai konsekuensi dari pertama dan kedua diatas dibutuhkan biaya,
tenaga dan pikiran yang cukup besar terutama karena banyaknya persyaratan
yang harus dipenuhi serta lamanya waktu yang dibutuhkan kadang-kadang bisa
lebih dari satu tahun apalagi jika hukum nasional negara yang dimintai
ekstradisi mewajibkan proses yang harus ditempuh melalui pemeriksaan oleh
badan peradilan nasionalnya dari badan peradilan tingkatan yang paling rendah
hingga paling tinggi;
d. Keempat, dalam beberapa hal, pranata hukum ekstradisi ini, terutama dalam
pengimplematasiannya sangat dipengaruhi oleh factor politik subjektif dari negara
yang dimintai. Bagaimanapun juga harus disadari, bahwa kenyataanya orang yang
diminta berada dalam wilayah negara yang dimintai ekstradisi memainkan posisi
kunci dalam memutuskan apakah akan dikabulkan atau tidak.
C. TAHAPAN DALAM PROSES EKSTRADISI
Walaupun dalam proses pelaksana ekstradisi, Indonesia dapat berkedudukan sebagai
negara yang meminta penyerahan ekstradisi (selanjutnya, disebut negara peminta)
maupun negara yang diminta untuk melakukan penyerahan (selanjutnya disebut a,
negara yang dimintai ekstradisi) namun Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 dalam
penjabarannya lebih banyak mengatur mengenai proses pelaksanaan ekstradisi dalam
kapasitas Indinesia sebagai negara yang diminta, sedangkan prosedur pengajuan
ekstradisi yang diminta oleh Indonesia kepada negara lain sebagaimana diatur dalam
Bab X Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 hanya terdiri tiga pasal yang pada pokoknya
hanya mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh Menteri Kehakimamn atas nama
Presiden mellui saluran diplomatic, sedangkan mengenai tata cara permintaan
penyerahan dan penerimaan diserahkan kepada Peraturan Pemerintah, yang ternyata
sampai dengan lebih dari tiga dasarwarsa, tidak pernah dibuat oleh Pemerintah.
Apabila melihat proses pelaksanaan ekstradisi yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1979 dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang dimintai
ekstradisi, maka pada proses pelaksanaan ekstradisi pada dasarnya dapat dibagi
dalam beberapa tahapan yaitu prapermintaan ekstradisi, permintaan ekstradisi,
pemeriksaan ekstradisi, persetujuan ekstradisi dan penyerahan ekstradisi. Masing-
masing tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Tahap Pra Permintaan Ekstradisi
Menurut Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, sebelum di terimanta
permintaan ekstradisi dari sebuah negara, Kapolri ataupun Jaksa Agung dapat
memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan
yang mendesak jika penahanan itu tidak bertantangan dengan hukum Negara
Republik Indonesia, dengan ketentyan bahwa ddalam ermintaan untuk penahanan
itu, negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen permintaan ekstradisi
sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu dekat akan
menyampaikan permintaan ekstradisi
Selanjutnya, menurut Pasal 19, setelah menerima permintaan penahanan yang
disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dari negara peminta yang disampaikan
melalui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan
pos atau telegram, Kapolri atau Jaksa Agung dapat mengeluarkan surat perintah
untuk menangkap dan atau menahan orang yang bersangkutan berdasarkan
ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.
Menyimpang dari ketentuan Hukum Acaara Pidana Indonesia yang berlaku, maka
terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diektradisikan dapat
dilakukan penahanan, dengan ketantuan orang tersebut dibebaskan jika dalam
waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri
Kehakiman tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen yang
dibutuhkan dari negara peminta.
2. Tahap Permintaan Ekstradisi
Menurut Pasal 22, surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis
melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk
diteruskan kepada Presiden. Permintaan tersebut hanya akan dipertimbangkan,
apabila memenuhi syarat-syarat seperti berikut:
a. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk
menjalani pidana harus disertai:
Lembaran asli atau Salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa
pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan
orang yang dimintakan ekstradisinya;
Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang
dikeluarkan oleh Pejabat yang berwnang dari negara peminta.
b. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus
disertai:
Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang dari negara peminta uraian dari kejahatan yang
dimintakan ekstradisi dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan
dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian
tidak mungkin, is idari hukum yang diterapkan keterangan-keterangan saksi dibawah
sumpah mengenai pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan;
Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan indentitas dan kewarganegaraan
orang yang dimintakan ekstradisinya;
Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
Menurut Pasal 23 jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman surat yang
diserahkan itu tidak memenuhi syarat atau syarat lain yang ditetapkan dalam
perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk
melengkapi sura-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh
Selanjutnya setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dipenuhi, Menteri
kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta
surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa
Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.
Namun demikian, kerangka prosedur sebagaimana diuraikan di atas, menjadi
berubah dalam hal permintaan ekstrasisi diajukan oleh negara yang belum
memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia Menurut Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1979, dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara
peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan
melalui saulran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangan.
Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara
peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia
melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi tersebut dan setelah
mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman
mengenai permintaan ekstradisi dimaksud, Presiden dapat menyetujui atau tidak
menyetujui permintaan tersebut.
Dalam hal permintaan ekstradisi disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri
Kehakiman memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara
negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, namun dalam hal permintaan
ekstradisi tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri
Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan
hal itu kepada negara peminta
3. Tahap Pemeriksaan Ekstradisi
Sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah syarat-syarat dan surat-surat terkait
permintaan ekstradisi dipenuhi (atau bagi permintaan dari negara yang belum
meiliki perjanjian ekstradisi, maka setelah terbitnya persetujuan Presiden), Menteri
Kehakiman mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-suraat
lampirannya kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk mengadakan pemeriksaan.
Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, apabila kejahatan
merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurt Hukum Acara
Pidana Indonesia dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, maka
terhadap orang tersebut dikenakan penahanan.
Menurut Pasal 34, penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 tersebut
baru dicabut, jika diperintahkan oleh Pengadilan,sudah berjalan selama 30 (tiga
puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa atau
permintaan ekstradisi di tolak oleh presiden.
Sementara itu, terkait dengan perpanjangan penahanan yang diberikan oleh
Pengadilan atas permintaan Jaksa, pasal 35 mengatur bahwa jangka waktu
penahanan tersebut setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari
dalam hal belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi,
diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36
Ayat (3), ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan
keputusannya atau dalam hal permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi
belum dapat dilaksanakan.
Menarik dicermaati bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 ternyata
mengatur mengenai 2 (dua) jenis penahanan, yaitu sebagai berikut:
a. Penahanan karena alasan mendesak
Penahanan karena alasan mendesak sebagaimana diatur dalammPasal 18 dapat
dilakukan sebelum diterimanya permintaan ekstradisi dari negara peminta, namun
cukup berdasarkan permintaan untuk penahanan disampikan oleh Pejabat yang
berwenang dari negara peminta kepadda Kapolri atau Jaksa Agung melakui
INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos
atau telegram.
Penahanan yang dilakukan berdasarkan alasan mendesak tersebut dapat dilakukan
terhadap semua kejahatan yang dapat diekstradisi sebagaimana diatur dalam
lampiran Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979.
b. Penahanan dalam rangka pemeriksaan ekstradisi
Penahanan dalam rangka pemeriksaan ekstradisi sebagaimana diatur dalam Pasal
25 hanya dapat dilakukan setelah permintaan ekstradisi diterima dan diteruskan
oleh Menteri Kehakiman kepada Kepolisian atau Kejaksaan untuk dilakukan
pemeriksaan. Penahanan dalam rangka pemeriksaan tersebut hanya dpat
dilakukan apabila kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat dikenakan
penahanan menurut hukum acara pidana Indonesia dan diajukan permintaan
penahanan oleh negara peminta.
Selanjutnya menurut Pasal 26, apabila yang melakukan penahanan tersebut adalah
Kepolisian, maka setelah menerima surat permintaan ekstradisi, kepolisian
mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan atau bukti
dari negara peminta, selanjutnya hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara dan
segera diserahkan kepada Kejaksaan setempat. Pasal 27 mengatur bahwa
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut,
Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada
Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan
kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diektradisikan.
Cara pemeriksaan di Pengadilan ini tidak merupakan pemeriksaan peradilan seperti
peradilan biasa, tetapi Pengadilan mendasarkan pemeriksaannya kepada
keterangan tertulis besaerta bukti-buktinya dari negara peminta yang diajukan oleh
Jaksa dengan disertai pendapatnya, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:
a) Identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstraaadisi itu sesuai
dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
b) Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan
menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
c) Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum
kadaluwarsa;
d) Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau
belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
pasti;
e) Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan
di Indonesia tidak;
f) Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.
Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa perkara-perkara
ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan. Pemeriksaan oleh
Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang
menganggap perlu sidang dilakukan tertutup, dengan dihadiri Jaksa dan Orang
yang dimintakan ekstradisi. Menurut Pasal 29 Kejaksaan menyampaikan surat
panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadapnPengadilan pada
hari siding dan suraat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh orang yang
bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
Setelah Pengadilan menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut di ekstradisi,
penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu
segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan
pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.
Menarik untuk dicermati bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979,
penetapan pengadilan dalam perkara ekstradisi memiliki kekuatan eksekutorial
(mengikat dan dapat dilaksanakan), mengingatpenetapan pengadilan tersebut
hanya digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh Presiden yang oleh
Undang-undang tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan
atau menolak perkara ekstradisi.
Penegasan bahwa keputusan akhir untuk menyetujui atau tidak menyetujui ada di
tangan Presiden dan bukan pengadilan, dinyatakan dalam penjelasan Umum
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 yaitu bahwa keputusan tentang permintaan
ekstradisi adalah bukan keputusan badanjudikatif tapi merupakan keputusan badan
eksekutif, oleh sebab itu pada tarafterakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah
mendapat nasehat jurisdis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan
Pengadilan.
4. Tahap Persetujuan Ekstradisi
Sebagaimana diuraikan diatas, dalam sistem Indonesia, keputusan tentang
permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan judikatif tapi merupakan
keputusan badan ekskutif, sedangkan penetapan yang dikeluarkan pengadilan hanya
sebatas salah bahan petimbangan bagi presiden dalm memutuskan memberikan
perssetujuan atau menolak permintaan ekstradisi yang diajukan di negara lain
Menurut Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, sesudah menerima
penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segerra
menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-
pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh Keputusan.
Namun demikian, jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat
dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman memerlukan tambahan keterangan, maka
sebelum menyampaikan penetapan pengadilan tersebut kepada Presiden, Menteri
Kehakiman dapat meminta keterangan dimaksud kepada negara meminta dalam
waktu yang dianggap cukup
Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan
Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian
Republik Indonesia, maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang di
ekstradisi. Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh
Menteri Kehakiman kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.
Menurut Pasal 37, jika 2 (dua) negara atau lebih meminta ekstradisi seseorang,
bekenaan dengan kejahatan yang sama atau yang berlainan dalam waktu yang
bersamaan, maka dalam menolak atau mengabulkan permintaan ekstradisi
Presiden dengan mempertimbangkan demi kepentingan keadilan memperlihatkan
berat ringannya kejahatan tempat dilakukannya kejahatan, waktu mengajukan
permintaan ekstradisi, kewaarganegaraan orang yang diminta, dan kemungkinan
diekstradisikannya orang yang di minta oleh negara peminta kepada negara lainnya.
Menarik untuk dicermati bahwa dalam hal permintaan ekstradisi diajukan oleh
negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka
terdapat dua bentuk keputusan Presiden terkait permintaan ekstradisi tersebut,
yaitu sebagai berikut:
a. Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1979, yang diperlukan untuk memulai proses
pemeriksaan terhadap orang yang diminta.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2, maksud dari persetujuan Presiden
tersebut adalah mempertimbangkan dapat dilakukannya ekstradisi atas
dasar hubungan baik dan kepentingan Negara Republik Indonesia. Dalam hal
Presiden menyetujui permintaan ekstradisi tersebut maka Presiden
memerintahkan Menteri Kehakiman memproses lebih lanjut seperti halnya
ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik
Indonesia, yaitu dalam hal ini menyerahkan permintaan ekstradisi tersebut
kepada Kepolsian atau Kejaksaan guna pemeriksaan lebih lanjut
b. Pesetujuan Presiden sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 36 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1979, sebagai keputusan final mengenai dapat tidaknya
seseorang di ekstradisikan, yang diambil setelah menerima penetapan
Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, menteri
Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
5. Tahap Penyerahan Ekstradisi
Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, jika permintaan ekstradisi
disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang
bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan [ada waktu yang ditetapkan oleh
Menteri Kehakiman. Jika orang yang dimintakan ekstradisinya tidak diambil pada
tanggal yang ditentukan, maka ia dapat dilepaskan sesudah lampau 15 (lima belas)
hari dan bagaimana pun juga ia wajib dilepaskan sesudah llampau 30 (tiga puluh)
hari. Permintaan ekstradisi berikutnya terhadap kejahatan yang sama, setelah
dilampauinya waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, dapat ditolak oleh Presiden.
Selanjutnya Pasal 41 mengatur bahwa jika keadaan di luar kemampuan kedua
negara baik negara peminta untuk mengambil maupun Negra yang diminta untuk
menyerahkan orang yang bersangkutan, negara dimaksud wajib memberitahukan
kepada negara lainnya dan kedua negara akan memutuskan Bersama tanggal yang
lain untuk pengambilan atau menyerahkan yang dimaksud. Dalam hal demikian
berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (3) yang waktunya dihitung sejak
tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut.
Selain dari penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979 juga mengatur mengenai penyerahan barang-barang yang diperlukan
sebagai bukti yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya.
Menurut Pasal 42, dalam hal negara peminta juga menghendaki diserahkannya
barang-barang yang terdapat pada orang yang dimintakan ekstradisinya untuk
dipergunakan sebagai barang bukti, maka permintaan tersebut dinyatakan secara
tegas dalam permintaan ekstradisi untuk dipetimbangkan oelh Pengadilan
bersamaan dengan permintaan pokok ekstradisi. Selanjutnya, dalam penetapannya
mengenai permintaan ekstradisi, Pengadilan Negeri menetapkan pula barang-
barang yang diserahkan kepada negara peminta dan yang dikembalikan kepada
orang yang bersangkutan. Pengadilan Negeri dapat pula menetapkan bahwa
barang-barang tertentu hanya diserhkan kepada negara peminta dengan syarat
bahwa barang-barang tersebut segera akan dikembalikan sesudah selesai
digunakan.
Bab 5
Ekstradisi dan Sistem Peradilan
Pidana
A. KONFIGURASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PROSES EKSTRADISI
Sebagaimana disebutkan dalam konsiderannya, ketentuan Undang-undang yang
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Undang-undang ekstradisi adalah
sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 2289);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2951).
Selanjutnya walaupun dalam ketentuan pasalnya banyak menyinggung mengenai
hukum acara pidana di Indonesia, namun konsideran Undang-undang Nomor 1
Tahun 1979 ternyata tidak memasukan hukum acara pidana yang berlaku saat itu
yaitu Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sebagaimana diatur dalam Staatsblad
tahun 1941 Nomor 44 pada bagian konsiderannya. HIR sendiri masih diberlakukan
di Indonesia berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 (drt) tahun
1951, yang mengatur bahwa HIR seberapa mungkin diambil sebagai pedoman
tentang acara perkara pidanansipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan negeri
dalam wilayah Republik Indonesia kecuali atas beberapa penambahan dan
perubahannya.
Oleh karena itu, dapat memahami secara utuh Undang-undang Ekstradisi, tentunya
tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai pemahaman para pembentuk
undang-undang mengenai sistem peradilan pidana yang saat itu berlaku di
Indonesia, khususnya dari konfigurasi hubungan-hubungan antara berbagai
subsistem yang terlibat di dalamnya.
Perlu diingat, bahwa di dalam HIR tidak dikenal pemisahan yang tegas antara fungsi
penyidikan dan penuntutan. Kedua kewenangan tersebut pada dasarnya
merupakan bagian dari tugas kepolisian represif yang diatur dalam bab Kedua HIR
di bawah judul “Tentang Mencari Kejahatan dan Pelanggaran”. Menurut HIR,
pengusutan/penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa sendiri atau oleh pejabat-
pejabat lain sebagaimana ditunjuk oleh Pasal 39 HIR, yang dapat dikelompokan
menjadi (1) pegawai penyidik biasa, dan (2) pegawai penyidik penuntutumum di
penyidik jaksa pembantu. Mengenai pegawai penyidik penuntut umum, Pasal 46
HIR menyatakan bahwa apabila tidak ditentukan lain, yang dimaksud dengan
pegawai penuntut umum dalam reglemen ini (HIR) adalah jaksa-jaksa pada
pengadilan negeri.
Selanjutnya menurut Pasal 55 HIR, dalam hal pemeriksaan terhadap suatu perkara
dilakukan oleh pembantu jaksa, maka jaksa pembantu dengan segera mengirimkan
pemberitahuan, proses-perbal, dan akte-akte yang lain yang dibuatnya, demikian
juga barang-barang yang disitanya, kepada jaksa pada pengadilan negeri.
Sebaliknya, menurut Pasal 56 Ayat (1) HIR, pegawai penuntut umum (jaksa) pada
pengadilan negeri berhak untuk meminta jaksa-pembantu untuk memberi
keterangan kepadanya mengenai pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh jaksa
pembantu, dalam hal pemeriksaan perkara tersebut berada dalam kewenangan
jaksa selaku pegawai penuntut umum.
Ketentuan penahanan yang diatur dalam HIR pada dasarnya mengikuti pula badan
kewenangan sebagaimana digambarkan diatas, yaitu terbagi atas:
1. Penahanan yang dapat dilakukan oleh petugas penyidik biasa (selain pegawai
penuntut umum dan jaksa pembantu) terhadap seseorang yang kedapatan
tengah berbuat (tertangkap tangan), yang kerap disebut sebagai “penahanan
tanpa surat perintah” terbatas hanya untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:
a. Supaya seorangpun walaupun siapa juga tidak noleh meninggalkan rumah itu
atau pergi dari tempat kejahatan itu dilakukan, selama pemeriksaan di tempat
itu belum selesai (Pasal 59 HIR);
b. Untuk kepentingan membawanya kepada salah seorang pegawai penuntut
umum atau kepada salah seorang jaksa-pembantu (Pasal 60 HIR)
2. Penahanan sementara yang dilakukan oleh pegawai penuntut umum atau jaksa
pembantu untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Menurut Psal 62 HIR,
kewenangan untuk mengeluarkan perintah penahanan selama 20 hari terhadap
tersangka yang kedapatan tertangkap tangan tersebut melekat pada pegawai
penuntut umum. Namun demikian berdasarkan Pasal 71 HIR, pembantu jaksa
berhak dan wajib melakukan segala sesuatu yang boleh dan harus dilakukan
oleh pegawai penuntut umum terkait dengan proses terhadap seseorang yang
tertangkap tangan tersebut, yaitu apabila pada saat tersangka dihadapkan
kepadanya, ia masih harus menunggu kedatangan atau surat perintah dari
pegawai penuntut umum.
Dalam keadaan yang demikian, maka pembantu jaksa harus segera
memberitahukan mengenai pelaksanaan tugasnya tersebut kepada pegawai
penuntut umum.
Selanjutnya, muenurut Pasal 75 Ayat (1) HIR, dalam hal tersangka tidak kedapatan
tengah berbebuat (tertangkap tangan), maka penahaan terhadapnya hanya dapat
dilakukan atas dasar surat perintah dari pegawai penuntut umum atau pembantu jaksa.
Selanjutnya Pasal 75 Ayat (2) HIR mengatur bahwa Peraturan dalam pasal-pasal 62, 71
Ayat (2) dan 72 berlaku untuk perintah penahanan tersebut. Dengan demikian maka
penahanan terhadap seseorang yang tidak tertangkap tangan juga berlaku untuk paling
lama 20 (dua puluh) hari.
3. Penahanan oleh jaksa untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari).
Menurut Paasal 83 c (1) HIR, bila terhadap tersangka ada hal-hal yang sangat
memberatkan dan cukup pasti bahwa perbuatan itu masuk pada yang diterangkan
dalam ayat (2) Pasal 62 dan perkara itu diduga tidak akan dapat diperiksa
pengadilan dalam waktu yang ditetapkan dalam Pasal 72, maka untuk kepentingan
pemeriksaan atau mencegah supaya perbuatan itu tidak akan diulangi atau untuk
mencegah supaya si tertunduh tidak melarikan diri, jaksa dapat memerintahkan
menagkap si tertuduh, atau (lau ia sudah ditangkap, ditahan buat sementara),
memerintahkan supaya ia tetap ditahan. Menurut Pasal 83 c ayat (4) HIR perintah
penahanan yang keluar oleh Jaksa tersebut tidak dapat berlaku lebih lama dari tiga
puluh hari, terhitung mulai dari hari perintah itu dijalankan.
4. Menurut Pasal 83 c Ayat (4) HIR, apabilapemeriksaan belum juga selesai, jaksa
dapat memohon agar penahanan tesebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan
Negeri unutk tiap-tiap kali selama 30 (tiga puluh) hari.
Berdasarkan ketetuan Pasal 83 c Ayat(1) jo ayat (4) HIR tersebut, maka jelaslah
bahwa setelah lewat masa penahanan selama 20 hari berdasarkan perintah
penahanan yang dilekuarkan oleh pegawa penuntut umum atau pembantu jaksa,
maka penahanan hanya dapat dilanjutkan berdasarkan perintah dari jaksa, yang
berlaku untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan apabila pemeriksaan belum juga
selesai, jaksa dapat memohon agar penahanan tersebut diperpanjang oleh Ketua
Pengadilan Negeri untuk tiap-tiap kali selama 30 (tiga puluh) hari. Di sinilah terlihat
kurangnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa di dalam HIR,
mengingat HIR tidak membatasi untuk berapa kalikah Ketua Pengadilan Negeri
dapat memberikan-memberikan perpanjangan penahanan, dengan demikian pada
dasarnya penahanan tersebut dapat berlangsung selama berbulan-bulan bahkan
bertahun-tahun.
Selanjutnya pada tahun 1961, terjadi perubahan besar dalam konfigurasi sistem
peradilan pidana di indoensia, mengingat pada tahun itu, pemerintah secara
hampir bersamaan mensahkan dua undang-undang pokok kelembagaan penegak
hukum, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan
pokok kepolisian Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961tentang
ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-
undang Pokok Kepolisian 1961, Kepolisian merupakan institusi yang berdiri sendiri
yang berada di bawah Menteri Kepolisian, memegang pimpinan penyelenggaraan
tugas Kepolisian Negara, baik pencegahan (preventif) maupun pemberantasan
(represif). Di bidang dalam bidang perdilan, kepolisian berwenang mengadakan
penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara, sementara
penyelidikan perkara dilakukan oleh penjabat-penjabat Kepolisian tersebut,
Undang-undang Pokok Kepolisian tersebut, Undang-undang Pokok Kejaksaan
(Undang-udang Nomor 15 Tahun 1961) menyatakan bahwa Kejaksaan adalah alat
negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
Dengan demikian maka jelaslah keberadaan kedua undang-undang pokok teresbut
mengubah konfigurasi hubungan antara Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan
diberikannya kewenangan penuh keapda kelolisian untuk melakukan penyedikan,
maka tidaklah dapat lagi mereka disebut sebagai sebagai jaksa pembantu.
Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Kepolisian menyebutkan hubungan
kerja antara Kepolisian dan Kejaksaan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi
kerja sama yang sederajat, sesuai dengan semangat gotong royong sebagai unsur
kepribadian Indonesia. Sebaliknya jaksa tetap berwenang serta mengawaso dan
mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut kentuan-ketentuan dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
Setelah memahami mengenai konfigurasi penahanan dan kewenangan di bidang
peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka dapatlah dimengerti
mengenai sebabnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
mengatur bahwa penahanan dalam ekstradisi dapat dilakukan untuk jangka waktu
30 (tiga puluh) hari dan setiap waktu dapat diperpanjang oelh Pengadilan
berdasarkan permintaan Jaksa.
Apabila dihubungkan dengan ketentuan penahanan yang saat itu berlaku, yaitu
sebagaimana diatur dalam HIR, maka dapat disimpulkan bahwa pedoman yang
digunakan adalah jangka waktu penahanan yang dilakukan Jaksa sebagaimana diatur
dalam pasal 83 c Ayat (4) HIR, yaitu untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan
apabila pemeriksaan belum juga selesai, jaksa dapat memohon agar penahanan
tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk tiap-tiap kali selama 30
(tiga puluh) hari.
Sejalan dengan hal tersebut, dapat pula dipahami mengenai sebabnya penahanan
maupun pemeriksaan ekstradisi dapat dilakukan oleh Kepolisian atau kejaksaan,
mengingat pada saat itu, kedua lembaga penegak hukum masing-masing memiliki
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana,
yaitu Kepolisian berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Kejaksaan
berdasarkan HIR dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961.
Sementara itu, menarik untuk dicermati mengenai sebabnya Undang-undang Nomor
1 Tahun 1979 ikut memasukan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 pada bagian
konsiderannya, walaupun dalam penjabarannya ternyata ketentuan dalam Undang-
undang Ekstradisi banyak menyimpangi prinsip-prinsip sebagaiman diatur dalam
Disamping tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya menurut Pasal 2 Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970, Badan-badan peradilan memang dapat diserahi
tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peratuan perundangan.
Sementara itu Pasal 25 mengatur bahwa semua pengadilan dapat memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum Lembaga
Negara lainnya apabila diminta.
Apabila dikaitkan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979,
maka jelaslah bahwa kedudukan penetapan pengadilan dalam proses pelaksanaan
ekstradisi, hanya sebatas bahan bagi Menteri Kehakiman dalam meberikan nasihat
yuridis kepada Presiden, atau dikaitkan dengan konteks Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970 tersebut maka dapat dianggap bahwa dalam perkara ekstradisi, maka
pengadilan menjalankan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1970, yaitu memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-
nasehat tentang soal-soal hukum kepada Lembaga Negara lainnya.
Karakteristik penetapan pengadilan dalam perkara ekstradisi yang berbeda dengan
bentuk produk Pengadilan pada umumnya juga dapat disimpulkan dari penjelasan
umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa cara
pemeriksaan peradilan seperti peradilan biasa, tetapi Pengadilan mendasarkan
pemeriksaan kepada keterangan tertulis beserta bukti-buktinya dari negara
peminta yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya.
Namun demikian pemahaman tersebut tidak dapat sepenuhnya dipertahankan,
mengingat secara tegas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa
produk dari pemeriksaan pengadilan dalam perkara ekstradisi dituangkan dalam
bentuk Penetapan Pengadilan yang dihasilkan melalui siding yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Jaksa maupun orang yang dimintakan penyerahannya.
denganKarakteristik sebagai sebuah penetapan, maka jelaslah bahwa prosuk
pengadilan dalam perkara ekstradisi memiliki implikasi dan kekuatan hukum yang
wajib dijungjung tinggi oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini
lembaga pemerintahan.
B. PERKEMBANGAN DAN REALITAS PELAKSANAAN EKSTRADISI DI INDONESIA
1. Red Notice
Pemberitahuan (Notice) merupakan sebuah istilah yang digunakan terhadap
instumen yang digunakan Interpol untuk berbagi informasi penting terkait kerja
sama penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan antara negara-negara
anggota. Pemberitahuan (notice) diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Interpol atas
permintaan Biro Pusat Nasional (NCB) dan badan yang berwenang serta
dipublikasikan dalam bahwa resmi yang digunakan oleh Interpol yaitu Arab, Inggris,
Perancis dan Spanyol.
Penerbitan Red Notice (Pemberitahuan Merah) dilakukan terhadap orang yang
diinginkan oleh suatu yurisdiksi nasional untuk penuntutan atau menjalani
hukuman berdasarkan surat perintah penangkapan atau putusan pengadilan. Peran
Interpol adalah untuk membantu penegak hukum negara anggota dalam
mengindetifikasi dan menemukan orang tersebut dengan maksud untuk
penangkapan dan ekstradisi atau tindakan hukum serupa.
Dasar hukum untuk penerbitan Red Notice adalah surat perintah penangkapan
ataupun perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas peradilan di negara
yang bersangkutan. Banyak negara-negara anggota Interpol mempertimbangkan
Red Notice untuk menjadi permintaan yang sah untuk melakukan penangkapan
sementara (provisional arrest).
Adapun Tata Cara Permintaan Penerbitan Interpol Notices, dapat diuraikan sebagai
berikut:
a. Permintaan penerbitan red notice dapat diajukan terhadap tersangka, terdakwa
atau terpidana yang diduga melarikan diri ke luar negeri dengan maksud agar
dilakukan pencarian untuk menangkap, menahan atau mengekstradisi;
b. Permintaan penerbitan red notice dapat diajukan oleh penyidik atau instansi
lain yang terkait dengan criminal justice system;
c. Permintaan penerbitan red notice disertai dengan kelengkapan atau perysratan-
persyaratan sebagaimana tersebut dalam formular permintaan red notice;
d. Dalam hal permintaan penerbitan red notice kurang memenuhi persyaratan
atau terdapat kekurangan, maka NCB akan segera memberitahukan kekurangan
tersebut dan meminta instansi terkait untuk melengkapinya;
e. Setelah persyaratan permintaan penerbitan red notice lengkap, NCB negara
anggota yang bersangkutan segera mengajukannya kepada Sekretariat Jenderal
Interpol sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
f. Lembaran asli red notice yang diterima dari Sekretariat Jenderal Interpol, akan
dikirimkan kepada neagra yang meminta;
g. Segala perkembangan yang terjadi setelah penerbitan red notice, akan segera
diinformasikan kepada negara yang mengajukan permintaan;
h. Dalam hal diperoleh informasi bahwa tersangka atau terdakwa atau terpidana
yang dimintakan red notice berhasil ditangkap oleh negara tertentu, maka NCB
negara bersangkutan akan segera mempersiapkan pengajuan permintaan
ekstradisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Interpol sendiri merupakan organisasi dunia yang menagani kejahatan
internasional terorganisir (ICPO) yang berkantor pusat di Lyon,Perancis, dan
mempunyai keanggotaan yang terdiri dari 188 negara. Kegiatan Interpol juga
dilaksanakan oleh masing-masing badan pelaksana disetiap negara anggota yang
disebut NCB (National Central Bureau).
Secara yuridis pembentukan National Central Buerau (NCB) di suatu negara
didasarkan pada Pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap
negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat
Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam
negeri, dengan NCB negara lain, dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.
Di Indonesia, Kepala NCB adalah Kapolri, sesuai SK Perdana Menteri RI tanggal 5
Oktober 1954 No 2451 PM/1954. Surat keputusan itu menunjuk Djawatan
Kepolisian Negara sebagai NCB, mewakili Pemerintah RI, dengan pelaksana harian
Kepala Sekretariat NCB-Interpol yang secara operasional di bawah kendali langsung
Kapolri.
Salah satu terobosan yang dilakuka oleh Interpol dalam meningkatkan efektivitas
informasi Red Notice di antara negara-negara anggota adalag melalui Sistem
Komunikasi yang terkoneksi ke instansipenegak hukum di 188 negara anggota
ICPO-Interpol untuk berbagi informasi penting tentang kejahatan dan aktivitas
kejahatan sealam 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dengan menggunakan I-24/7,
NCB-Interpol Indonesia dapat melakukan pencarian dan pengecekan data dengan
akses langsung ke database Interpol yang memuat data tentang buronan,
pencarian orang, sidik jari, DNA dokumen perjalanan yang hilang atau dicuri,
kendaraan bermotor yang dicuri, benda seni yang dicuri dan lain-lain.
Sesuai dengan Pasal 18 jo. pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, Kapolri
atau Jaksa Agung dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara
lain atas dasar alasan yang mendesak berdasarkan permintaan yang disampaikan
oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kapolri atau Jaksa Agung
melaui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan
pos atau telegram.
Kentuan Pasal 18 jo. Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, dalam
kenyataanya menjadi dasar bagi Kepolisian RI untuk melakukan penangkapan dan
penahanan terhadap seseorang berdasarkan Red Notice yang diterbitkan oleh
Interpol sepanjang dalam Red Notice tersebut dicantumkan mengenai surat
perintah penangkapan atau penahanan yang diterbitkan oleh otoritas yang
berwenang di negara peminta. Dengan demikian, maka Red Notice dipersamakan
dengan surat permintaan resmi dari negara peminta untuk melakukan
penangkapan atau penahanan terhadap seseorang yang dimintakan ekstradisi.
Namun demikian, permasalahan menjadi menarik mengingat tidak semua negara
yang meminta penangkapan melalui penerbitan Red Notice memiliki perjanjian
ekstradisi dengan Indonesia, sedangkan menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor
1 Tahun 1979, proses terhadap permintaan ekstradisi dengan Indonesia terlebih
dahulu harus mendapat persetujuan dari Presiden sebelum dapat diteruskan sesuai
mekanisme yang berlaku selayaknya negara yang telah memiliki perjanjian
ekstradisi dengan Indonesia.
Dalam Konteks tersebut di atas, maka penangkapan yang dilakuka oleh Kepolisian
berdasarkan Red Notice yang dimintakan oleh negara yang belum memiliki
perjanjian ekstradisi dengan Indonesia menimbulkan sebuah problematika
tersendiri mengingat rangkaian mekanisme proses pelaksanaan ekstradisi baru
dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan presiden. Dengan demikian
maka persetujuan Presiden terhadap permintaan ekstradisi yang diajukan oleh
negara peminta yang belum memiliki perjanjian ekstradisi merupakan dasar bagi
keseluruhan proses pelaksanaan ekstradisi, termasuk dasar bagi penangkapan yang
dapat dilakukan oleh Kepolisian.
Sebaliknya, walaupun tujuan dari penerbitan Red Notice adalah penyerahan orang
yang dicari untuk diserahkan kepada negara peminta, namun demikian Interpol
tidak secara tegas membatasi Teknik penyerahan harus melalui jalur ekstradisi.
Dalam kenyataanya, apabila proses ekstradisi dinilai sulit untuk dilakukan, maka
Kepolisian dapat mengambil diskresi untuk menempuh cara-cara lain dalam
menyerahkan lain yang dalam praktik biasanya dikenal dengan istilah “Handing
Over” atau “Disguished Extradition” (ekstradisi terselubung)
Diskresi yang dapat dilakukan oleh Kepolisian untuk menempuh Teknik penyerahan
di luar ekstradisi dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur
bahwa untuk kepentingan umum dan dalam keadaan yang sangat perlu, pejabat
Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan
wewenanganya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Penyerahan atas permintaan penahanan diberitahukan kepada negara peminta oleh
Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui
Interpol Indonesia atau saluran diplomatik atau langsung dengan pos dan telegram.
Dengan ketentuan bahwa baik permintaan penahanan maupun pemberitahuan atas
keputusan permintaan penahanan yang dapat dilakukan secara langsung melalui
mekanisme Interpol maupun lewat surat ataupun telegram, maka jelaslah terdapat
diskresi yang begitu luas pada lembaga Kepolisian untuk memilik jalur pelaksanaan
penyerahan selain ekstradisi tanpa proses pengawasan ataupun “check and balance”
dari lembaga lain terkait tindakan penangkapan maupun penahanan yang dilakukan
2. Kedudukan Menteri Kehakiman sebagai “Filtering Authority”
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 memberikan peranan yang strategis kepada
Menteri Kehakiman dalam proses pelaksanaan ekstradisi yaitu sebagai pintu masuk
penerimaan permintaan ekstradisi, penyaringan dokumen, memberikan masukan
kepada Presiden dan pintu keluar penyampaian Keputusan Presiden terkait
disetujui atau ditolaknya permintaan ekstradisi tersebut. Dominannya kedudukan
Menteri Kehakiman tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep ekstradisi
sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun
1979, yaitu bahwa keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan
keputusan badan judikatif tetapi merupakan keputusan badan eksekutif. Oleh
sebab itu, pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat
nasihat juridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan Pengadilan.
Menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, pada saat mengajukan
permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, negara
peminta harus menyertakan kelengkapan dokumen sebagai berikut.
1. Surat Permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk
menjalani pidana harus disertai:
a. Lembaran asli atau Salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa
pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan
kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
c. Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
2. Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejhatan
harus disertai:
a. Lembaran asli atau Salinan otentik dari surat perintah penahanan yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
b. Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu
dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan
c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal
demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
d. Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya
tentang kejahatan yang dilakukan;
e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan
orang yang dimintakan ekstradisinya;
f. Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan.
Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, jika menurut
pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu
tidak memenuhi syrat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam
perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk
melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang di pandang cukup oleh
Menteri Kehakiman.
Selanjutnya Pasal 24 mengatur bahwa setelah syarat-syarat dan surat-surat
dimaksud dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat
permintaan ekstradisi besarta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian
Republik Indonesia dan jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan
pemeriksaan.
dari bagian pada halaman 99, maka jelaslah kecermatan Menteri Kehakiman dalam
melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh
Negara peminta sangat menentukan bagi keberhasilan proses ekstradisi,mengingat
kelengkapan dokumen dan persyaratan ekstradisi yang diserahkan dari negara
peminta tersebut merupakan dasar bagi Kepolisian maupun Kejaksaan dalam
melakukan pemeriksaan serta dasar pembuktian di muka persidangan Pengadilan
dalam menilai dapat atau tidaknya ekstradisi tersebut dilakukan.
Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun
1979, berbeda peradilan biasa, pemeriksaan peradilan dalam perkara ekstradisi
mendasarkan pemeriksaannya kepada keterangan tertulis beserta bukti-buktinya
dari negara peminta yang diajukan oleh Jaksa dengan disertai pendapatnya.
Dengan demikian maka dokimen-dokumen yang diserahkan oleh negara peminta
tersebut harus dapat meyakinkan Pengadilan dalam menilai hal-hal sebagai
berikut.
a. Identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstrasdisi itu sesuai
dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
b. Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan
menurut Pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
c. Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum
kadaluwarsa;
d. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau
belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
pasti;
e. Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan
di Indonesia tidak;
f. Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.
Menarik untuk dicermati, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tidak
menyediakan mekanisme bagi Kepolisian ataupun Kejaksaan untuk menilai lebih
lanjut mengenai kelengkapan dokumen yang di serahkan oleh negara peminta serta
meminta Kembali negara peminta untuk melengkapi dokumen tambahan.
Ketentuan tersebut merupakan sebuah hal yang logis mengingat menurut Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1979, perkara ekstradisi merupakan perkara yang
didahulukan sehingga pemeriksaanya harus dilakukan secara capat. Dengan
demikian setelah Menteri Kehakiman menyerahkan permintaan ekstradisi kepada
Kepolisian ataupun Kejaksaan, maka diharapkan Kepolisian atau Kejaksaan dapat
menjadi dasar yang cukup bagi Kepolisian ataupun Kejaksaan dalam melakukan
dan menyelesaikan pemeriksaan terhadap perkara ekstradisi tersebut.
Namun demikian permasalah menjadi menarik mengingat walaupun kelangkapan
dokumen dari negara peminta sangat berkaitan dengan teknis pembuktian di muka
persidangan, dalam kenyataannya penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut
dilakukan oleh Pejabat yang lingkup tugasnya terbatas pada bidang administrasi hukum
dan bukan mereka yang secara nyata berkecimpung di dunia peradilan. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan pada Kementerian Hukum dan HAM RI, penerimaan dan
peneliatian berkas permintaan ekstradisi dari negara peminta ditangani oleh Direktorat
Jendral Administrasi Hukum Umum, khususnya Direktorat Hukum Internasional dan
Otoritas Pusat. Secara faktual, pejabat yang melakukan penelitian terhadap kelengkapan
persyaratan permintaan ekstradisi pada Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas
Pusat adalah analis ekstradisi dan TSP yang berada di bawah Kepala Seksi Ekstradisi dan
TSP.
Apabila mencermati Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dijadikan dasar dalam
penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, maka secara fungsional Menteri
Kehakiman memang sejak awal tidak terlibat langsung dalam pelaksana proses
peradulan, namun demikian tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kekuasaan kehakiman pada saat itu, mengingat Menteri kehakiman bertanggung jawab
atas pembinaan organisatoris, administratif dan finansial badan-badan peradilan umum
Pemisahan fungsi Menteri Kehakiman dari sistem kekuasaan kehakiman yang ada
di Indonesia mulai terlihat sejak disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengalihkan pembinaan
organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan kepada Mahkamah
Agung, yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-
undang tersebut mulai berlaku.
Untuk melaksanakan amant Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, pada tanggal
23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Ri No.21
Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan
lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadalin Agama ke
Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan
organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan
Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
Dengan demikian, maka jelaslah bahwa sejak disahkannya Undang-undang Nomor
35 Tahun 1999, Menteri Kehakiman hanya melakukan pembinaan terhadap
huhkum dan perundangan-undangan dan tidak memiliki fungsi di bidang peradilan.
Kondisi ini kemudian mendorong Pemerintah menyesuaikan nomenklatur Menteri
Kehakiman sesuai dengan fungsinya yang baru, yaitu Menteri Hukum dan
Perundang-undangan (1999-2004), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
(2001-2004) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-sekarang).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010, Kemneterian Hukum dan
Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak
asasi manusia;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa kedudukan Menteri Hukum dan
HAM dalam fungsinya saat ini telah sangat jauh berbeda dari fungsinya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menjadi
dasar penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979. Kenyataan bahwa pernan
Menteri Hukum dan Ham secara teknis tidak bersentuhan dengan fungsi peradilan
dan tidak lagi manjdi bagian dari kekuasaan kehakiman jelas mempenharuhi
tingkat kecermatan dan ketepatan Kementerian Hukum dan Ham dalam menilai
dan mempertimbangkan kebutuhan lembaga penegak hukum terkait pembuktian
di muka persidangan pengadilan
3. Penelitian Berkas Perkara oleh Kejaksaan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur bahwa setelah
Kepolisian mengadakan pemeriksaan tentang orang tersebut atas dasar keterangan
atau bukti dari negara peminta, maka berita acara hasil pemeriksaan tersebut
segera diserahkan kepada kejaksaan setempat. Selanjutnya, Kejaksaan dalam
waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil pemeriksaan tersebut segera meminta
kepada Pengadilan Negeri di daerah tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa
dan kemudia menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan.
Perlu untuk dicermati bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 disahkan pada
saat konfigurasi hubungan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam sistem peradilan
pidana di Indonesia masih menggunakan Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
yang kemudian dalam beberapa hal diubah dengan keluarnya Undang-undang
Nomor 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan, jaksa
berwenang untuk mengadakan penyidikan lanjutan terhadap berkas perkara hasil
penyelidik yang diserahkan oleh Kepolisian serta mengawasi dan mengoordinasikan
alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
Apabila ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tersebut dihubungkan
dengan Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1979 maka jelaslah bahwa jangka waktu 7
(tujuh) hari bagi jaksa untuk melimpahkan perkara ekstradisi tersebut kepada
pengadilan, adalah untuk memberikan kesempatan bagi jaksa melakukan
pemeriksaan dan persiapan membuat permintaan tertulis sebagai dasar
melimpahkan perkara ekstradisitersebut ke pengadilan.
Dalam pekembangannya setelah berlakunya Undang-undang Nmor 8 Tahun 1981
tentang hukum acara pidana yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-
undang Hukum acara pidana (KUHAP), maka hubungan antara kepolisain dan
kejaksaan disusun berdasarkan prinsip diferensiasi fungsial mengalami perubahan
yang mendasar, yang kemudian dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum pada saat memulai
penyidikan (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP);
2. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera
menyerahkan berkas pekara itu kepada penuntut umum, atau lebih dikenal
dengan istilah tahap I (Pasal 110 Ayat (1) KUHAP);
3. Dalam hal penunut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut
ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas
perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk unutk dilengkapi, atau lebih
dikenal dengan istilah Pra Penuntutan (Pasal 110 Ayat(2) KUHAP);
4. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasill penyidikan untuk dilengkapi,
penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesaui dengan petunjuk
dari penuntut umum, atau lebih dikenal dengan istilah penyidikan tambahan
(Pasal 110 Ayat (3) KUHAP);
5. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari
penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebulam
batas waktu tersebut berakhir telaha ad pemberitahuan hal itu dari penuntut
Selanjutnya, menururt pasal 8 KUHAP, penyerahan berkas perkara dari Kepolisian
pada Kejaksaan dapat dibedakan 2 tahap, yaitu pada Tahap pertama penyidik
hanya menyerahkan berksa perkara, dan dalm hal penyidikan sudah dianggap
selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan banrang bukti
kepada penyidik umum.
Dalam perakteknya, walaup pun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 hanya
mengatur hubungan antara kepolisian dan kejaksaan secara sederhana, namun
ternyata dilapangan,hubungan koordinasi yang dibangun antara kepolisian dan
Kejaksaan dalam penanganan perkara ekstradisi menyesuaikan dengan, konfigurasi
sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu diawali dengan pemberitahuan dimulainya
penyidikan (SPDP), penyerahan berkas tahap I Pra Penuntutan dan penyerahan
tahap II atas orang yang dimohonkan ekstradisi.
Dalam konteks tersebut maka apabila kejaksaan menilai masih terdapat
kekurangan dapam hasil pemeriksa yang dilakukan oleh kepolisian dalam
penanganan perkara ekstradisi,
Kejaksaan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada Kepolisian unutk
dilengkapi oleh Kepolisian sebagaimana proseedur yang berlaku di dalam KUHAP.
Dengan demikian maka jangka waktu 7 (tujuh) hari bagi jaksa untuk melimpahkan
perkara ekstradisi ke Pengadilan bukan lagi diitung sejak Kpolisian menyerahkan
berkas perkara ekstradisi, melainkan dihitng dari sejak saat penyerahan terhadap 11
yaitu penyerahan tanggung jawab atas orang yang dimohonkan ekstradisi.
Permasalahan menajdi menarik mengingat sebagaimana dijelaskan di muka,
Kepolisian sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tidak berwenang
untuk berhubungan secara langsung dengan Negara peminta, melainkan harus
dilakukan melalui Menteri Hukum dam HAM RI yang kemudian akan meneruskan
kepada Negara Pemintah untuk dipenuhi. Dalam Kondisi tersebut, pada akhirnya
terdapat dua kali penelitian yang terhadap kelengkapan dokumen ekstradisi, yaitu:
1. Penelitian dokumen kelengkapan perkara ekstradisi yang dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM
Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, jika menurut pertimbangan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan oleh Negara Peminta itu
tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen ekstradisi atau syarat lain yang di
maka kepada pejabat negara pemintadiberikan kesempatan untuk melengkapi
surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandangcukup oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia.
Selanjutnya Pasal 24 mengatur bahwa setelah syarat-syarat dan surat-surat
dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.
2. Dalam hal Jaksa menilai bahwa berkas perkara yang diserahkan oleh Kepolisian
dalam perkara ekstradisi masih terdapat kekurangan, maka Jaksa memberikan
petunjuuk keapda Kepolisian untuk segera melangkapi berkas perkara
dimaksud, yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan melalui Menteri Hukum
dan HAM untuk dipernuhi oleh negara peminta.
Dari uraian di atas, maka dimingkunkan terdapat pengulangan penelitian terhadap
kelengkpana dokumen permintaan ekstradisi dari negara pemintah, dalam hal
menurut pendapat Jaksa, dokumen yang telah diserahkan belum cukup memenuhi
kebutuhan untuk membuktkan terpenuhinya prinsip-prinsip ekstradisi di muka
persidangan.
Hal ini menurut hemat Penulis disebabkan karena penelitian dokumen sejak awal
bukan dilakukan oleh Pejabat yang tugas dan fungsi terkait dengan proses
kelengkapan dan kekuatan hukum dokume-dokumen yang di butuhkan untuk
proses pembuktian di muka persidangan
4. Pra Peradilan terhadap Sah atau Tidaknya Penahanan dalam Perkara
Ekstradisi
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 yang diterbitkan sebelum berlakunya KUHAP,
sangat sedikit memuat pengaturan mengenai hak-hak termohon ekstradisi dalam
proses pemeriksaan ekstradisi. Pengaturan mengenai hak termohon ekstradisi
hanya ditemukan dalam ketentuan Pasal 29 yang mengatur mengenai hak
termohon ekstradisi untuk diberitahukan dalam waktu layak untuk menghadap ke
muka Persidangan ekstradisi terhadap dirinya di muka persidangan. Undang-
undang ekstradisi sebaliknya tidak mengatur mengenai hak termohon ekstradisi
untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan paksa yang dikenakan terhadap
dirinya dalam perkara ekstradisi, yaitu khususnya mengenai penahanan.
Tidak diaturnya mengenai hak-hak termohon ekstradisi untuk mengajukan
keberatan atas penahanan yang dikenakan terhadap dirinya dapat dipahami
mengigat hukum acara pidana yang dijadikan acuan dalam penyusunan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1979 adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur
dalam HIR yang sebagaimana telah dikemukakan di atas, sangat sedikit sekali
memuat pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu seorang
tersangka atau terdakwa atas penahanan yang dilakukan terhada[ dirinya.
Kenyataan bahwa HIR juga tidak mengatur mengenai Batasan jangka waktu
penahanan mengakibatkan penahanan dapat berlangsung tanpa kepastian hukum
dan tanpa hak bagi orang yang dikenakan penahanan untuk mengajukan keberatan
atas upaya paksa tersebut.
Mengenai praktik penahanan selama berlakunya HIR, Sutomo Surtiatimodjo
menulis sebagai berikut:
“Praktik penahanan di Indonesia menurut HIR, sedemikian rupa sehingga kadang
kala sampai berkalan berminggu berbulan bahkan pernah terjadi bertahun-tahun
tanpa pemeriksaan di muka siding pengadilan. Praktik-praktik yang demikian itu
sudah barang tentu sangat bertentangan dengan idea-idea hukum; bagaimana
dapat dibayangkan seseorang yang hanya mencuri barang yang relatif tidak
seberapa harganya sampai tertahan bertahun-tahun tanpa dipersidangkan satu
kalipun. Mungkin hal itu terjadi karena kelengahan pejabat yang berkewajiban
melaksanakan atau kurangnya pengawasan dari atasannya, atau kesengajaan
seperti yang biasanya terhadap tahanan-tahanan politik; tetapi yang terang
penahanan berlarut-larut tersebut biasa terjadi karena hukumnya memang
memberi kemungkinan.”
Kondisi tersebut tentunya berbeda sejak berlakunya KUHAP yang selain mengatur
secara tegas mengenai Batasan penahanan yang dapat dilakukan di setiap
pemeriksaan juga memberikan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk
mengajukan keberatan atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya yaitu
melalui jalur pra peradilan.
Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang dimaksud dengan pra peradilan adalah
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang a) sah atau
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain atas kuasan tersangka,b) sah atau tidaknya suatu
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi
tegaknya hukum dan keadulatan, dan c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi
oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.
Namun demikian, permasalah menjadi menarik mengingatnya Peradilan
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut merupakan
pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang
dilakukan dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan
dalam perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah yurisdiksi Indonesia dan bukan
dalam perkara ekstradisi di mana kejahatan yang dilakukan oleh termohon
dilakukan diwilayah yurisdiksi negara lain
Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah ketentuan pra peradilan sebagaimana
diatur dalam KUHAP sebenarnya tidak dapat dilakukan dalam perkara ekstradisi,
bahkan sebaliknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa dalam
hal pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh termohon
ekstradisi sedang dilakukan di Negara Republik Indonesia, maka hal tersebut
merupakan salah alasan yang dapat digunakan untuk menolak permintaan
ekstradisi.
Namun demikian dalam kenyataannya, dalam Putusan nomor
01/Pid.Pra/2015/PN.BTM tanggal 20 April 2015, Pengadilan Negeri Batam telah
mengabulkan permohonan pra preadilan yang diajukan oleh termohon ekstradisi
Lim Yong Nam, yang telah ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan
Riau sejak tanggal 24 Oktober 2014, Lim Yong Nam adalah warga negara Singapura
yang ditangkap dari Pemerintah Amerika Serikat Nomor:A-5633/9-2013, tanggal 12
September 2013 Ia dalam daftar Interpol termasuk orang yang dicari oleh Amerika
Serikat dituduh melanggar UU Amerika Serikat karena melakukan konsipirasi
penipuan, penyeludupan, dan pemberian di Singapura membeli 6.000 modul
frekuensi radio dari Amerika Serikat.
Ribuan modul itu belakangan diketahui diekspor ke Iran yang sudah diembargo
Amerika Serikat.
Walaupun Lim Young Nam telah ditahan sejak 24 Oktober 2414, namun dalam
kenyataannya proses pemeriksaan administrative dalam perkara Lim Yong Nam
menjadi berbelit-belit. Sehingga persetujuan Presiden untuk melanjutkan
permintaan ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Amerika Serikat (hal ini sesuai
Pasal 39 Undang-undang Ekstradisi wajib dilakukan mengingat Amerika Serikat
belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia) baru dapat diterbitkan pada
tanggal 20 Maret 2015, yaitu hamper 4 (empat) bulan Lim Yong Nam ditahan di
Polda Kepulauan Riau.
Permohonan Pra Peradilan diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon Ekstradisi ke
Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 April 2015 dengan alasan penahanan
dilakukan tanpa bukti yang cukup dan penahanan tanpa jangka waktu yang pasti,
yang dianggap bertentangan dengan KUHAP. Dalam amar putusannya, Hakim
Pengadilan Negeri Batam menyatakan menerima dan mengabulkan sebagaian
permohonan pemohon, serta menyatakan penangkapan dan penahanan yang
diajukan dalam pra preadilan tidak sah dan oleh kareanya memerintahkan untuk
Adapun salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim adalah bahwa dalam
penangkapan dan penahanan dilakukan oleh penyidik Polda Kepri tanpa bukti yang cukup
mengingat di muka persidangan, Polda Kepulauan Riau tidak dapat menunjukan
dokumen-dokumen “copie collatione” sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 22 ayat
(4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 sebagai dasar melakukan penahanan terhadap
termohon ekstradisi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1979 tentang Ekstradisi.
Dapat diajukan dan dikabulkannya permohonan pra peradilan atas penahanan yang
dilakukan dalam perkara ekstradisi, jenis menunjukan perubahan paradigma dalam
memandang ketentuan penahanan dalam Undang-undang nomor 1979, yaitu bahwa
proses pelaksanaan ekstradisi perlu dilakukan dengan menjunjung tinggi penghormatan
terhadap jak-hak asasi manusia termasuk syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur
dalam KUHAP.
Selanjutnya, pesan penting lain yang dapat ditangkap dari putusan peradilan atas nama
termohon ekstradisi Lim Yong Nam tersebut, menunjukan bahwa proses penahanan
dalam ekstradisi dianggap tidak berbeda dengan proses penahanan dalam ekstradisi
dianggap tidak berbeda dengan proses penahanan dalam ekstradisi dianggap tidak
berbeda dengan proses penahanan dalam penyidilan ataupun penuntutan perkara pidana
Hal ini menunjukan bahwa dalam kenyataannya, Pengadilan memandang proses
pelaksanaan ekstradisi tunduk pada hukum acara pidana yang berlaku, sehingga
ketentuan hukum acara pidana pidana dapat pula diterapkan dalam proses
pelaksanaan ekstradisi.
5. Upaya Hukum terhadap Penetapan Pengadilan
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979,
hakikat ekstradisi di Indonesia menempatkan keputusan tentang permintaan
ekstradisi sebagai keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir dalam
tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis daari Menteri Kehakiman
berdasarkan penetapan Pengadilan.
Menurut penjelasan Pasal 33 Undang-undang Ekstradisi, penetapan pengadilan dalam
perkara ekstradisi adalah merupakan bentuk dari apa yang dinyatakan oleh
Pengadilan, sedang isinya adalah merupakan pernyataan dan atau pendapat.
Pemahaman bahwa pengadilan dapat memberikan pendapat kepada Pemerintah
tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa semua pengadilan dapat
memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum
Dengan menempatkan Penetapan Pengadilan hanya sebatas sebuah pernyataan
ataupun pendapat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 memberikan
kekeluasaan bagi pihak eksekutif (dalam hal ini adlah Menteri Kehakiman) untuk
memilih menggunakan atau tidak menggunakan penetapan yang telah dibuat oleh
pengadilan tersebut. Hal tersebut antara lain terlihat dengan jelas dari ketentuan
Pasal 36 ayat (3) yang mengatur bahwa jika menurut penetapan Pengadilan
Permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetrapi Mentari kehamikan Republik
Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri kehakiman Republik
Indonesia meminta keterangan yang dimaksud kepada negara peminta dalam
waktu yang dianggap cukup.
Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 juga menadapatkan penetapan
Pengadilan sejajar dengan pertimbangan instansi lainnya yaitu Menteri Luar Negeri,
Menteri Kehakiman, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pasal 36 Ayat (1) mengatur bahwa
sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri
Kehakiman segara menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan
disertai pertimbangan-pertimbangan . Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri,
Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh
Selanjutnya Pasal 36 Ayat (2) mengatur bahwa setelah menerima penetapan
pengadilan Bersama pertimbangan-pertmbangan yang dimaksud dalam ayat (1),
maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan.
Dalam konteks tersebut diatas , maka tidaklah mengehrankan apabila Undang-
undnag Nomor 1 Tahun 1979 tidak memberikan ruang bagi upaya hukum terhadap
penetapan pengadilan, mengingat pada akhirnya penetapan pengadilan tersebut
tidak menerima kekuasaan mengikat terhadap pihak-pihak yang berpekara (dalam
hal ini, jaksa di satu pihak dan orang yang dimintakan ekstradisi, dilain pihak) dan
hanya berlaku sebagai pendapat , yang Bersama-sama dengan pertimbangan dari
instansi lainnya, menjadi bahan bagi Presiden untuk menyetujui atau menolak
pemintaan ekstradisi tersebut.
Kondisi tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan
dalam perkara ekstradisi, dan bertentangan dengan tujuan diadakannya
pemeriksaan pengadilan dalam perkara ekstradisi itu sendiri sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 yaitu:
1. Memberikan kesempatan bagi termohon ekstradisi untuk menyampaikan
pendapat/pembelaan;
2. Pemeriksaan dilakukan secara objektif dan dengan mendengar keterangan dua
belah pihak, yang antara lain tercermindalam dari beberapa ketentuan, yaitu;
a. Pemeriksaan dilakukan dengan susunan majelis;
b. Pemeriksaan dihadiri oleh jaksa dan termohon ekstradisi
3. Mewujudkan peradilan yang bebas dan penghormatan Hak Asasi Manusia, yang
tercermin dari beberapa ketentuan, antara lain;
c. pemeriksaan dilakukan dalam siding yang terbuka untuk umum;
d. Pemeriksaan terhadap prinsip prinsip dasar dalam ektrasidi, yaitu Dual
Criminatity, bukan kejahatan pemimpin politik, kadaluarsa, Nebis In Idem, dan
sebagainya.
Dari berbagai ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa tujuan dilakukannya
pemeriksaan dimuka pengadilan adalah menjamin terselenggaraannya proses
hukum yang adil (due prrocces of law) dalam perkara ekstradiksi, sehingga
ketentuan yang mengatur bahwa penetapan pengadilan yang dihasilkan oleh
proses hukum tersebut ternyata dapat dengan mudah dikesampingkan dan hanya
berlaku sebagai sebuah pendapat, jelaskan dirasakan kontradiktif dengan tujuan
tersebut.
Namun demikian, dalam perkembangannya paradikma bahwa penetapan hakim
dalam perkara ekstradiksi hanya sebuah pendapat dan oleh karena nya tidak dapat
dilakukan upaya hukum mulai mengalami perubahan setelah pada tanggal 17
Februari 2014, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor :
16/Pide/Plw/2014/PT.DKI mengabulkan keberatan jaksa penuntut umum atas
penetapan Pengadilan Negri Jakarta Selatan Nomor :
01/Pid/C/Ekst/2013/PR.JKT.SEL tanggal 11 Juli 2013. Dalam perkara ekstradisi atas
nama Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid.
Surat permintaan ekstradisi Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia
atas nama Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid diterima pada bulan Juni
2010 melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Australia di Jakarta Nomor
P036/2010 tanggal 08 Juni 2010 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kemudian dengan surat Nomor: AHU5.AH.08.02.-84 tanggal 25 Juni 2010, Direktur
Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia meminta kepada Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik
Indonesia untuk menindaklanjuti permohonan ekstradisi atas nama Sayeed Abbas
Azad bin Sayed Abdul Hamid.
Sehubungan dengan diterimanya permintaan penahanan sementara dari
Pemerintah Australia melalui Nota Diplomatik Kedutaan Besar Australia Nomor
P091/2009 tanggal 10 November 2009 kepada kementrian luar negeri Republik
Indonesia, maka Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan surat dari Dirjen
Administrasi Hukum Umum Nomor UHU.5.AHA.08.02-44 tanggal 09 April 2010
telah melakukan penangkapan terhadap termohon ekstradisi Sayeed Abbas Azad
bin Sayed Abdul Hamid pada tanggal 10 Mei Pukul 05.45 WIB di Stadiun Jakarta
Barat.
Berdasarkan penyerahan berkas perkara dari kepolisian pada tanggal 19 April 2013,
Jaksa melimpahkan perkara ekstradisi tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan pada tanggal 25 April 2013 dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
menetapkan hari sidang 08 Mei 2013.
Pada tanggal 11 Juni 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan
penetapan Nomor: 01/Pid.C/Ekst/2013/PN.JKT.Sel tanggal 11 Juni 2013 yang
amarnya sebagai berikut:
1. Menolak permohonan estradisi dari pemohon Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan termohon ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid
warga negara Afghanistan tidak dapat di ekstradiksi ke Australia;
3. Memerintahkan agar Termohon ekstradiksi Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul
Hamid dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Australia
diserahkan Kembali kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai
bahwa azas dual criminality (kejahatan ganda) tidak terpenuhi mengingat tindak
pidana penyeludupan manusia (people smuggling) bukan merupakan salah satu
tindak pidana yang diatur dalam lampiran Undang-undang Nomor 1tahun 1979
tentang ekstradisi dan tidak ada kebijaksanaan Negara yang diwujudkan dengan
suatu keputusan yang besar Presiden yang menyatakan bahwa tindak pidana
penyeludupan manusia (people smuggling) merupakan tindak pidana yang
dimintakan ekstradiksi.
Atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pada tanggal 18 Juli
2013, jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan perlawanan
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta
Permintaan Banding Perlawanan Nomor.54/Akta.Pid.Pw/PN.JKT.Sel tanggal 18 Juli
2013.
Hak untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri
tersebut jelas tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979, namun
demikian sesuai Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada
atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Dalam memori perlawanannya, Jaksa menyatakan bahwa walaupun tindak pidana
penyeludupan manusia (People Smuggling) bukan merupakan salah satu Tindakan
pidana yang diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang
ekstradisi, namun Pemerintah Republik Indonesia (pada tanggal 20 April 2009)
maupun Pemerintah Australia (pada tanggal 27 Mei 2004) telah meratifikasi United
Nation Convention Againts Transnational Organized Crime (UNCTOC) annex 1.
Konvensi tersebut mengacu pada Protocol Againts The Smuggling of Migrant by
Land, Sea, and Air, Supplementing The UN Convention Againts Transnational
Organized Crime yang juga diratifikasi oleh Australia pada tanggal 27 Mei 2004 dan
Indonesia pada tanggal 28 September 2009.
Berdasarkan konfensi tersebut negara pihak diwajibkan mengkriminalisasi atau
melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan penyeludupan manusia.
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undan Nomor 6 tahun 2011
tentang keimigrasian telah mengatur ketentuan kejahatan penyeludupan manusia
sebagai suatu perbuatan yang dapat di jatuhi pidana.
Pada tanggal 25 Februari 2014, berdasarkan putusan Nomor:
16/Pid/Plw/2014/PT.DKI, Pengambilan Tinggi DKI Jakarta atas permohonan
perlawanan Jaksa tersebut, dalam amarnya menyatakan sebagai berikut:
1. Menyatakan permohonan perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor;
01/Pid.C/Ekst/2013/PN.JKT.Sel tanggal 11 Juli 2013 tersebut;
3. Mengabulkan permintaan ekstradisi Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan atas nama Termohon Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul
Hamid;
4. Memerintahkan Termohon Sayeed Abbas Azad bin Sayed Abdul Hamid di ekstradisi
ke Negara Australia;
5. Membebankan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada pemohon,
yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000 (Lima Ribu Rupiah).
Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 1
tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak mengatur mekanisme upaya hukum terdapat
penetapan pengadilan negeri dalam menerima permohonan perlawanan yang diajukan
oleh pihak dalam perkara ekstadisi (dalam perkara ini adalahJaksa pada Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan) dan membatalkan penetapan pengadilan di bawahnya.
Dalam konteks sistem peradilan pidana, maka mekanisme pengujian putusan
pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi, merupakan salah satu unsur pokok dari
proses hukum yang adil (due process of law) yang memandang bahwa setiap tahapan
dalam sistem peradilan dalam perkara ekstradisi dapat diuji oleh pengadilan pengadilan
yang lebih tinggi melalui mekanisme proses hukum yang adil tersebut menunjukan
bahwa kedudukan penetapan pengadilan dalam perkara ekstradisi tidak dapat lagi
dipandang sebagai sebuah pendapat yang dapat dengan mudah dikempangingkan oleh
Pemerintah dalam memutuskan menyetujui atau menolak permintaan ekstradisi dari
6. Persetujuan Presiden dalma Perkara Ekstradisi
Dalam mekanisme proses pelaksanaan ektradisi sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1979, maka dapat disimpukan bahwwa proses pelaksanaan
ekstradisi dalam kapasias Indonesia sebagai negara yang dimintai ekstradisi dalam
kapasitas Indonesia sebagai negara yang dimintai ekstradisi, dapat dibagi menjadi 3
(tiga) tahapan pokok, yaitu:
7. Tahap Penerimaa Permintaan Ekstradisi
Termasuk dalam tahap ini adalah diterimanya permintaan ekstradisi dari negara melalui
saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman yang dilanjutkan dengan penelitian
kelengkapan dokumen dan persyaratan ekstradisi oleh Menteri Kehakiman;
2. Tahap Pemeriksaan Perkara Ekstradisi
Termasuk dalam tahap ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap
orang yang dimohonkan ekstradisi berdasarkan dokumen tertulis yang diterima dari
negara peminta, penyerahan berita acara hasil pemeriksaan kepada Kejaksaan,
pemeriksaan di muka pengadilan berdasarkan permintaan tertulis dari jaksa serta
keluarnya penetapan pengadilan mengenai dapat atau tidaknya dilakukan ekstradisi
terhadap orang yang bersangkutan.
3. Tahap Persetujuan Presiden
Termasuk dalam tahap ini adalah diterimanya penetapan pengadilan oleh Menteri
Kehakiman dan masuknya pertimbangan dari berbagai instansi terkait yaitu
Menteri Luar Negeri, Kapolri, Jaksa Agung disertai Menteri Kehakiman sendiri, yang
kemudian diajukan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan mengenai
apakah permintaan ekstradisi dapat disetujui atau ditolak.
Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa proses
pelaksanaan ekstradisi harus diselesaikan secara cepat, hal tersebut antara lain
dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan sebagai berikut:
₋ Pasal 28;
Perkara-perkara ekstradisi termasuk
Anda mungkin juga menyukai
- Quiz 2 HpiDokumen6 halamanQuiz 2 Hpimasjid ponpesBelum ada peringkat
- Dalam Hukum Internasional Suatu Negara Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Menyerahkan Tersanga Pelaku Kejahatan Kepada Negara AsingDokumen3 halamanDalam Hukum Internasional Suatu Negara Tidak Memiliki Kewajiban Untuk Menyerahkan Tersanga Pelaku Kejahatan Kepada Negara AsingDeafani Perdana LubisBelum ada peringkat
- EkstradisiDokumen7 halamanEkstradisin0tale ActivityBelum ada peringkat
- EKTRADISIDokumen9 halamanEKTRADISIAdila RizqiBelum ada peringkat
- Ekstra DisiDokumen12 halamanEkstra DisiElsaBelum ada peringkat
- Jurnal EkstradisiDokumen12 halamanJurnal EkstradisiMajid FatihBelum ada peringkat
- Tugas Ekstradisi Hukum Pidana InternasionalDokumen2 halamanTugas Ekstradisi Hukum Pidana InternasionalAyu AngreniBelum ada peringkat
- EkstradisiDokumen25 halamanEkstradisiBountik ZeeBelum ada peringkat
- Mekanisme Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Pidana InternasionalDokumen11 halamanMekanisme Kerjasama Internasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasionalmaruly001Belum ada peringkat
- Ekstradisi (Asas-Asas)Dokumen4 halamanEkstradisi (Asas-Asas)Leon ManaoBelum ada peringkat
- Makalah EkstradisiDokumen9 halamanMakalah EkstradisiLia apriyaniBelum ada peringkat
- ID Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Republik KorDokumen19 halamanID Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dan Republik KorMr DBelum ada peringkat
- Ekstradisi Perpektif HK InternasionalDokumen46 halamanEkstradisi Perpektif HK InternasionalRama PrakasaBelum ada peringkat
- Perbandingan Hukum. TugasDokumen15 halamanPerbandingan Hukum. TugasdewiBelum ada peringkat
- Makalah HK Acara PidanaDokumen14 halamanMakalah HK Acara Pidanaatika zhara afinaBelum ada peringkat
- Pengertian EkstradisiDokumen2 halamanPengertian EkstradisiAnde KusumaBelum ada peringkat
- Mutual Legal AssistanceDokumen23 halamanMutual Legal AssistanceEka An AqimuddinBelum ada peringkat
- Bab 5-8 PidinDokumen32 halamanBab 5-8 Pidinangelos gogo siregarBelum ada peringkat
- EKSTRADISI F541e0Dokumen6 halamanEKSTRADISI F541e0Ryantama Gadang AlfiRaBelum ada peringkat
- Materi 2 PLKH 7 - Penyelidikan, Penyidikan, Praperadilan, PenuntutanDokumen36 halamanMateri 2 PLKH 7 - Penyelidikan, Penyidikan, Praperadilan, PenuntutanAmi SusantiBelum ada peringkat
- Inisiasi Tuton Ke - 7 Mata Kuliah: Tindak Pidana Korupsi Program Studi: Ilmu Hukum Fakultas: HISIPDokumen15 halamanInisiasi Tuton Ke - 7 Mata Kuliah: Tindak Pidana Korupsi Program Studi: Ilmu Hukum Fakultas: HISIPEkho Marapu TfttBelum ada peringkat
- DokumenDokumen6 halamanDokumenM ZulkarnainBelum ada peringkat
- A.Muh - Faturrachman B011221023 TugasInterDokumen6 halamanA.Muh - Faturrachman B011221023 TugasInterM.N Arrijalu BakhtiarBelum ada peringkat
- Ujian Hukum PidanaDokumen4 halamanUjian Hukum PidanaBeauty ExcelentBelum ada peringkat
- Topic 15 Hukum AcaraDokumen11 halamanTopic 15 Hukum Acaranurfebry0952Belum ada peringkat
- Analisanya TransnasionalDokumen13 halamanAnalisanya Transnasionalprofesi nersBelum ada peringkat
- Tugas 6 705210234 Anisa HusnulDokumen5 halamanTugas 6 705210234 Anisa HusnultogappeterBelum ada peringkat
- Hukum Acara PidanaDokumen36 halamanHukum Acara PidanaSayyidah Kaamilah100% (1)
- Tugas Kelompok 5 MK Hukum Pidana InternationalDokumen14 halamanTugas Kelompok 5 MK Hukum Pidana InternationalBerkah Ats-tsairunBelum ada peringkat
- UAS Ehsan Faturahman (2102021007)Dokumen4 halamanUAS Ehsan Faturahman (2102021007)ehsan faturahmanBelum ada peringkat
- Makalah Pemeriksaan Perkara PidanaDokumen10 halamanMakalah Pemeriksaan Perkara Pidanasaimi duaBelum ada peringkat
- Modul 13Dokumen4 halamanModul 13Apa AjaBelum ada peringkat
- Tugas Resume PhiDokumen21 halamanTugas Resume PhiAis FathimahBelum ada peringkat
- Dak WaanDokumen48 halamanDak Waanalprindo MBelum ada peringkat
- Yuridiksi Negara Dalam Hukum InternationalDokumen13 halamanYuridiksi Negara Dalam Hukum InternationalAlfarizi Nabawi YusufBelum ada peringkat
- Hukum Acara PidanaDokumen11 halamanHukum Acara PidanaNongki SuekBelum ada peringkat
- MAKALAH-Hukum InternasionalDokumen14 halamanMAKALAH-Hukum InternasionalPutra Umarsyam difinubunBelum ada peringkat
- Analisa Kasus PencabulanDokumen20 halamanAnalisa Kasus Pencabulanmoh. ghiyaz romzi albarqiBelum ada peringkat
- 3 Pengertian EkstradisiDokumen4 halaman3 Pengertian EkstradisiAndika Setiawan PambudiBelum ada peringkat
- Cara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak PidanaDokumen5 halamanCara Menuntut Ganti Rugi Jika Menjadi Korban Tindak Pidanadoddy harizkyBelum ada peringkat
- Hukum Internasional Tugas 9Dokumen9 halamanHukum Internasional Tugas 9angelicahasan07Belum ada peringkat
- Hukum Pidana InternasionalDokumen7 halamanHukum Pidana InternasionalAlimas Rifatun 03Belum ada peringkat
- Arti PRA PERADILANDokumen8 halamanArti PRA PERADILANHamba SahayaBelum ada peringkat
- Muhammad Fatih Izzulhaq - Hukum Acara Pidana - D - Book Resume Pt4Dokumen6 halamanMuhammad Fatih Izzulhaq - Hukum Acara Pidana - D - Book Resume Pt4fatihBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen25 halamanBab 2iqbal prasetyoBelum ada peringkat
- Zamzawir Akbar (201912056) JWB UasDokumen5 halamanZamzawir Akbar (201912056) JWB UasZamzawir AkbarBelum ada peringkat
- Materi Hukum Acara PidanaDokumen69 halamanMateri Hukum Acara PidanaOra PopoBelum ada peringkat
- Mutual Legal AsistenDokumen21 halamanMutual Legal AsistenastrinatsirBelum ada peringkat
- Ekstradisi Adalah Perjanjian Penyerahan Antara Negara Yg Satu DGN Negara Yg Lain Perihal Atau Pelaku Kejahatan Dri Pelaku Yg Satu DGN Pelaku Yg LainDokumen11 halamanEkstradisi Adalah Perjanjian Penyerahan Antara Negara Yg Satu DGN Negara Yg Lain Perihal Atau Pelaku Kejahatan Dri Pelaku Yg Satu DGN Pelaku Yg LainLilis Lestari GustiBelum ada peringkat
- Resume Bab Praperadilan Pak SumardanDokumen20 halamanResume Bab Praperadilan Pak Sumardanmoh. ghiyaz romzi albarqiBelum ada peringkat
- Penahanan (HAPID)Dokumen13 halamanPenahanan (HAPID)RahayuBelum ada peringkat
- Hukum Acara PidanaDokumen10 halamanHukum Acara PidanaBOS FH UNTARBelum ada peringkat
- CATATANDokumen5 halamanCATATANyayasanais106Belum ada peringkat
- Kamus HukumDokumen20 halamanKamus HukumIcruel WahyudiBelum ada peringkat
- Diskusi 1,2,3,4,5,6,7,8 Hukum Perdata InternasionalDokumen11 halamanDiskusi 1,2,3,4,5,6,7,8 Hukum Perdata Internasionalfrengky 14Belum ada peringkat
- Materi Hukum Acara PidanaDokumen11 halamanMateri Hukum Acara PidanaRusdi HasniBelum ada peringkat
- Materi Hukum Acara PidanaDokumen9 halamanMateri Hukum Acara PidanaMuhamad Iip Ibnu SetiawanBelum ada peringkat
- Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020Dokumen68 halamanPenerapan Restorative Justice Berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020SilviBelum ada peringkat
- LS - Penguatan Perlindungan Harta Kekayaan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tipikor Dan TPPUDokumen6 halamanLS - Penguatan Perlindungan Harta Kekayaan Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Perkara Tipikor Dan TPPUnew aromaticBelum ada peringkat