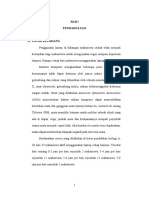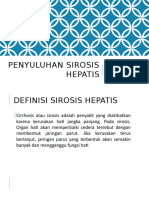Overactif Bladder
Overactif Bladder
Diunggah oleh
Meutia PutriHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Overactif Bladder
Overactif Bladder
Diunggah oleh
Meutia PutriHak Cipta:
Format Tersedia
I.
PENDAHULUAN
Overactive bladder adalah salah satu sebab dari inkontinensia urine dan
merupakan penyebab kedua sesudah kelemahan sfingter uretra. Kandung kemih
berfungsi sebagai alat penyimpanan urine dan akan berkontraksi hanya selama
berkemih dibawah pengontrolan persyarafan.
1,4
International Continence Society
mengklasifikasikan overactive bladder sebagai suatu sindrom dimana tak ada
penyebab pasti yang ditemukan, dengan abnormalitas lokal yang didapatkan saat
evaluasi diagnostik.
3
Prevalensi dan perjalanan penyakit tidak diteliti dengan baik sampai saat ini.
Pada survei melalui telepon pada 16.776 orang dewasa berusia 40 tahun atau lebih
di Eropa, 16 % laki-laki dan 17 % wanita dilaporkan mengalami sindroma sugestif
dari overactive bladder. Prevalensinya sebesar 3 % pada pria berumur 40-44
tahun, 9 % pada wanita 40-44 tahun, 42 % pada pria 75 tahun atau lebih dan 31 %
pada wanita 75 tahun atau lebih. Data yang hampir sama pada prevalensi
overactive bladder dilaporkan di Amerika Serikat.
3
Overactive bladder merupakan kondisi yang menyusahkan penderitanya.
Kondisi ini membatasi dan menganggu kehidupan sehari-hari penderitanya, dan
menyebabkan perasaan malu, cemas, takut, mudah marah, frustasi dan depresi
yang berat. Keadaan basah itu sendiri jelas merupakan aspek terburuk dalam
masalah ini, tapi keinginan kuat untuk buang air, panik mencari toilet dan
ketakutan tak mampu menemukannya tepat waktu juga mempunyai peran.
3
II. DEFINISI DAN GAMBARAN KLINIK
Overactive bladder merupakan suatu jenis urge incontinence (keluarnya urine
secara tidak sadar, terjadi ketika tekanan kandung kemih melebihi tekanan uretra
selama fase pengisian) yang dihubungkan dengan keinginan kuat untuk buang air
kecil dan berhubungan dengan overaktif otot detrusor.
3
2
Gejala yang terjadi pada overactive bladder antara lain :
1
1. Frekuensi: berkemih amat sering, dengan jumlah lebih dari 8 kali dalam
waktu 24 jam.
2. Nokturia: malam hari sering bangun lebih dari satu kali untuk berkemih.
3. Urgensi: keinginan yang kuat dan tiba-tiba untuk berkemih walaupun
penderita belum lama sudah berkemih dan kandung kemih belum terisi
penuh seperti keadaan normal.
4. Urge inkontinensia: dorongan yang kuat sekali unuk berkemih dan tidak
dapat ditahan sehingga kadang kadang sebelum sampai ke toilet urine
telah keluar lebih dulu.
Orang dengan overactive bladder mengalami kontraksi yang tak teratur pada
kandung kemih selama fase pengisian dalam siklus miksi. Urge inkontinensia
merupakan gejala akhir pada overactive bladder.
3
J umlah urine yang keluar pada
overactive bladder biasanya lebih banyak daripada kapasitas kandung kemih yang
menyebabkan kandung kemih berkontraksi untuk mengeluarkan urine. Pasien
dengan overactive bladder pada mulanya kontraksi otot detrusor sejalan dengan
kuatnya keinginan untuk berkemih, akan tetapi pada beberapa pasien mereka
menyadari kontraksi detrusor ini secara volunter berusaha membantu sfingter
untuk menahan urine keluar serta menghambat kontraksi otot detrusor, sehingga
keluhan yang menonjol hanya urgensi dan frekuansi yaitu lebih kurang 80 %.
Nokturia hampir ditemukan 70 % pada kasus overactive bladder dan simptom
nokturia sangat erat hubungannya dengan nokturnal enuresis. Keluhan urge
inkontinensia ditemukan hanya pada sepertiga kasus overactive bladder.
1
III. NEUROFISIOLOGI MIKSI
A. FISIOLOGI MIKSI
Proses miksi merupakan aktifitas dari proses neurofisiologi yang kompleks dan
terkoordinasi dengan sangat tepat dan melibatkan aktifitas neuronal mulai dari
3
korteks serebri, batang otak, medula spinalis dan saraf-saraf tepi baik otonom
maupun somatik.
4
Fungsi penyimpanan dan pengeluaran urine merupakan dua fungsi buli-
buli yang diatur oleh sistem refleks yang kompleks. Pengaturan ini
menghasilkan koordinasi antara kontraksi otot polos dan lurik yang berakhir
dengan terjadinya miksi pada tekanan intra uretra yang rendah dan fungsi
kandung kemih yang terkontrol. Fisiologi kandung kemih terdiri atas
neurofisiologi mekanisme refleks miksi dan fisiologi detrusor serta otot lurik
periuretra.
4,5
Tekanan yang dihasilkan oleh otot polos dan lurik disekitar dan pada
uretra membuat jaringan penunjang dan pembuluh darah yang ada di bagian
dalam dinding uretra terjepit sehingga epitel uretra menjadi seperti tutup yang
kedap air. Semua faktor ini akan menjadi faktor penting terjadinya
kontinensia. Tekanan intra uretra dalam keadaan istirahat adalah antara 50-100
cm H
2
O, suatu tekanan yang cukup bila diingat bahwa tekanan intravesika
maksimal adalah 50 cm H
2
O.
4
Sfingter uretra disokong oleh otot, ligamen, dan fasia dasar panggul dan
pengalaman klinis menunjukkan bahwa hal ini penting untuk mekanisme
kontinensia yang efisien. Lebih dari itu kontraksi otot levator ani mengangkat,
memanjangkan dan menekan uretra sehingga berperan penting pada terjadinya
kontinensia pada saat kondisi stress misalnya pada peningkatan tekanan intra-
abdominal secara tiba-tiba.
4
Tekanan yang dihasilkan oleh mekanisme sfingter proksimal pada leher
kandung kemih jauh lebih rendah dibanding mekanisme sfingter distal.
Tertutupnya leher kandung kemih hanya tergantung fungsi detrusor. Selama
detrusor tidak berkonsentrasi leher kandung kemih akan tetap tertutup
walaupun terjadinya kenaikan tekanan intravesikal yang ekstrim seperti
mengedan, batuk dan lain-lain. Hanya dengan kontraksi detrusor terjadi
pembukaan leher kandung kemih.
4
4
Kandung kemih dapat penyimpanan pertambahan jumlah urine tanpa
diikuti kenaikan tekanan intravesika. Hal ini dapat terjadi karena sifat
elastisitas otot kandung kemih yang dapat meregang. Selain itu kandung kemih
dalam keadaan kosong bukanlah berupa organ yang berkontraksi, tetapi lebih
berupa kantong yang terlipat. Oleh karenanya pengisian urine dalam jumlah
yang sedikit hanya mengubah bentuk kandung kemih yang terlipat tanpa perlu
meregangkan dindingnya, begitu volume urinee bertambah banyak barulah
kandung kemih akan meregang untuk menjamin tertampungnya urinee tanpa
mengakibatkan kenaikan tekanan intervesika. Diluar kedua faktor, elastisitas
dan kemampuan merubah bentuk kandung kemih, diduga faktor persarafan
juga berperan dalam menghambat terjadinya kontraksi detrusor atau secara
aktif membuat relaksasi detrusor selama fase pengisian urine.
4
B. MEKANISME PENGOSONGAN KANDUNG KEMIH
Kandung kemih terisi dengan kecepatan 1 ml/menit dan pada awalnya tanpa
adanya sensasi apapun. Sesuai dengan bertambahnya jumlah urine dalam
kandung kemih akan timbul sensasi samar yang timbul di daerah perineum
atau dalam rongga pelvik. Lama kelamaan sensasi ini makin jelas dan sulit
untuk diabaikan dan dalam keadaan normal ini saat untuk miksi. Bila kandung
kemih dibiarkan terisi terus maka timbul sensasi regangan daerah abdomen
bawah yang timbul dari saraf simpatis ke kolum lateral dan mungkin berasal
dari reseptor regangan di trigonum. Bila tidak juga terjadi miksi akan terdapat
sensasi miksi yang sulit tertahan. Sensasi ini berasal dari uretra atau otot lurik
periuretra. Serat aferen untuk sensasi ini berjalan bersama nervus pudendus
menuju kolum dorsal medula spinalis. Ketiga sensasi ini mempunyai alur saraf
berbeda dan dapat terjadi tanpa kenaikan tekanan intravesikal. Sensasi pertama
adalah yang terpenting. Rangsangan untuk ketiga sensasi adalah distensi
kandung kemih. Walaupun distensi saja sudah merupakan rangsangan yang
cukup tapi faktor pertambahan volume yang dihubungkan dengan frekuensi
kontraksi ritmin detrusor dengan amplitudo rendah juga memegang peranan.
4
5
1. Fase pengisisan
Persarafan menyebabkan kandung kemih mampu menahan urine di kandung
kemih sampai distensi kandung kemih mencapai titik batasnya. Mekanisme
saraf yang menjaga saraf parasimpatis postganglionik tetap tidak aktif
melibatkan tiga faktor. Pertama adanya inhibisi berulang terhadap saraf
postganglionik dengan menghambat hubungan antar saraf di
intermediolateral grey columns. Penghambatan ini terjadi pada volume
kandung kemih kecil dan akan hilang waktu terjadinya miksi. Faktor kedua
adalah peranan ganglion parasimpatik yang berfungsi sebagai filter, impuls
preganglion yang rendah tidak akan diteruskan. Faktor ini merupakan faktor
terpenting yang juga akan hilang waktu terjadinya miksi. Faktor ketiga
adalah inhibisi oleh saraf simpatis terhadap parasimpatis ganglioner.
4,5
Tekanan penutupan uretra meningkat pada beberapa keadaan seperti
pengisian buli-buli secara cepat, peningkatan tekanan intra abdomen,
aktifitas fisik dan kontraksi volunter otot dasar panggul. Kenaikan tekanan
sebagai respon terhadap pengisian buli-buli terjadi melalui refleks eferen
dan nervus pelvikus.
4
Aktivitas neural mempertahankan tekanan intravesikal lebih rendah dari
tekanan uretral. Perbedaan tekanan intravesikal dengan tekanan uretral
disebut sebagai urethral closure pressure. Tekanan intra uretral
dipertahankan tinggi pada proses pengisian kandung kemih disebabkan
elastisitas jaringan ikat mukosa uretral, sedang yang aktif mempertahankan
tekanan intra uretral adalah tonus otot-otot polos dan otot lurik intra
uretral.
4,5
Peninggian mendadak tekanan intra andomen akan ditransmisikan dan
didistribusikan secara sama ke arah kandung kemih dan ke uretral, sehingga
pengaruh terhadap urethral closure pressure tidak ada. Transmisi tekanan
ini tergantung pada komponen aktif yaitu kontraksi otot-otot lurik dan
komponen pasif yaitu posisi intra abdominal leher buli-buli dan uretra. J ika
6
otot-otot dan fasia pada dasar pelvis melemah, penurunan posisi leher
kandung kemih dan uretral akan disertai dengan distribusi tekanan intra
abdominal yang tidak sama berakibat timbulnya stress inkontinensia.
4
2. Fase pengosongan
Pengosongan kandung kemih terjadi dengan adanya peningkatan tekanan
intravesika yang bertahan sampai kandung kemih kosong disertai penurunan
tekanan intra uretra. Miksi dimulai dengan penurunan tekanan intra uretra
yang mendahului kenaikan tekanan intravesika beberapa detik walaupun
kadang kadang terjadi bersamaan. Bila tekanan intravesika sampai batas
tertentu maka leher buli-buli akan membuka dan miksi dimulai. Pada saat
miksi selesai uretra pada daerah sfingter distal akan menutup dan penutupan
ini diikuti bagian yang lebih proksimal dan terakhir tertutupnya leher
kandung kemih.
4
IV. PATOFISIOLOGI OVERACTIVE BALDDER
Gejala overactive bladder biasanya berhubungan dengan kontraksi involunter otot
detrusor. Overactive otot detrusor, baik neurogenik maupun idiopatik, dapat
menyebabkan inkontinensia urgensi, tergantung pada respon sfinkter. Overaktifitas
detrusor dapat disebabkan miogenik. Kontraksi detrusor dapat menjadi lemah
akibat kontraktibilitas yang terganggu. Pemeriksaan urodinamik menunjukkan
hampir separuh pasien usia lanjut dengan overaktifitas detrusor mengosongkan
kurang dari sepertiga isi buli-bulinya dengan kontraksi invonlunter. Pengosongan
yang tidak lengkap dapat menyebabkan frekuensi dengan menurunnya fungsi
kapasitas buli-buli.
3,10
Berbagai jalur eferen dan aferen saraf, refleks, dan neurotransmiter sentral dan
perifer terlibat dalam penyimpanan urine dan pengosongan buli-buli. Hubungan
antara faktor tersebut tidak dimengerti. Glutamat merupakan neurotransmiter
eksitator pada jalur yang mengatur saluran kemih bawah. Aktifitas serotonergis
memfasilitasi penyimpanan urine dengan bantuan refleks simpatik dan
7
menghambat jalur parasimpatik. J alur dopaminergik dapat memberikan efek
inhibitor dan fasilitator pada miksi. Reseptor dopamin D1 memiliki peran menekan
aktifitas buli-buli dimana reseptor dopamin D2 memfasilitasi miksi.
3,10
Gambar 1. Konsep kontribusi saraf otonom terhadap kontraksi kandung kemih
dan pengisian urine, dikutip dari Ouslander
3
Asetilkolin, yang berinteraksi dengan reseptor muskarinik pada otot detrusor,
merupakan neurotransmiter perifer yang bertanggung jawab pada kontraksi buli-
buli. Keadaan patologis dapat mengubah sensitifitas stimulasi muskarinik.
Contohnya, obstruksi aliran buli-buli tampak menambah respon terhadap
asetikolin, suatu fenomena yang mirip dengan denervasi suprasensitif. Normalnya,
hanya proporsi kecil kontraksi buli-buli yang tahan terhadap atropin, mungkin
akibat interaksi ATP dengan reseptor purineergik. Namun, ATP dapat memliki
peran lebih dalam kontraksi buli-buli pada pasien overactive bladder. Contohnya,
8
buli-buli pasien dengan overaktifitas detrusor tampak memiliki gap junction antar
sel otot polos yang abnormal.
3,7
Perhatian lebih telah diberikan pada saraf aferen sensori pada miksi normal
dan overaktifitas buli-buli. Selama pengisian buli-buli, aktifitas aferen pada buli-
buli dan uretra mencapai saraf spinal melalui saraf pelvis. Input sensor selama
pengisian buli-buli mengakibatkan peningkatan tonus simpatis, yang menghambat
saraf motorik parasimpatis, menyebabkan kontraksi dasar buli dan uretra.
3,7
Gambar 2. Konsep persarafan sensorik pada kandung kemih
dikutip dari Ouslander
3
Aktifitas adrenergik dapat menyebabkan relaksasi detrusor akibat stimulasi
reseptor -adrenergik. Serabut sensor A delta bermyelin memberi respon pada
peregangan pasif dan kontraksi aktif otot detrusor. Serat C yang tak bermyelin
9
mempunyai ambang mekanik yang lebih tinggi dan merespon berbagai
neurotransmiter. Serat C relatif tidak aktif selama miksi normal, tapi memiliki
peran penting dalam gejala overactive bladder pada pasien dengan kelainan saraf
dan lainnya. Beberapa tipe reseptor telah diidentifikasi pada saraf aferen, meliputi
reseptor vanilloid, yang diaktifasi oleh kapsaisin dan mungkin anandamide
endogen, reseptor purigenik (P2X), yang diaktivasi oleh ATP, reseptror
neurokinin, yang merespon substansi P dan neurokinin A, protein gen kalsitonin,
dan faktor neurotropik otak , juga memiliki peran penting dalam modulasi aferen
sensoris pada detrusor manusia.
3
V. ETIOLOGI
Pada dasarnya overactive bladder adalah gangguan atau kerusakan pada susunan
saraf yang ikut mengontrol kandung kemih dan kelainan yang belum diketahui
sebabnya sampai saat ini (idiopatik). Kelainan klinik yang erat hubungannya
dengan gejala overactive bladder antara lain :
6,11
1. Kelainan traktus urinearius bagian bawah
Infeksi, obstruksi, kontraktiltas kandung kemih yang berlebihan, defisiensi
estrogen, kelemahan sfingter, hipertropi prostat.
2. Kelainan neurologis
Otak (stroke, alzaimer, demensia multiinfark, parkinson, multipel
sklerosis), medula spinalis (sklerosis servikal atau lumbal, trauma, multipel
sklerosis), dan persarafan perifer (diebetes neuropati, trauma saraf).
3. Kelainan sistemik
Gagal jantung, insufisiensi vena, diabetes melitus, gangguan tidur,
abnormalitas arginin vasopresin.
4. Kondisi fungsional dan tingkah laku
Konsumsi alkohol dan kafein berlebihan, kebiasaan makan yang buruk dan
konstipasi, gangguan mobilitas, kondisi psikologis.
10
5. Efek samping pengobatan
Diuretik, antikolionergik, narkotika, kalsium chanel bloker, inhibitor
kolinestrase.
Peneliti lain mengemukakan teori lain berkenaan dengan abnormalitas kandung
kemih intrinsik, hal ini termasuk :
3,6
1. Kelainan ganglia kandung kemih
Peranan neuropeptida sebagai neurotransmiter pada tingkat yang bervariasi dari
arkus reflek miksi sentral, ganglia- ganglia tersebut terletak dikandung kemih
itu sendiri. Polipeptida intestinal vasoaktif suatu neuropeptida sebagi sel
ganglia kholinergik dan berfungsi sebagai agen inhibisi dari jalur
parasimpatomimetik dan pada penderita overactive bladder konsentrasi
polipeptida intestinal vasoaktif rendah, enkephalin juga dapat dilepas dari
ganglia kandung kemih berfungsi sebagai agen inhibisi dengan cara menekan
asetilkolin dari syaraf ganglia.
2. Kelainan pada sel pacemaker
Kelainan ini menjelaskan bahwa kandung kemih tidak pernah istirahat total.
Pada penelitian invitro dan invivo menunjukan bahwa kandung kemih berada
dalam aktifitas kontraksi ritmik yang terjadi terus menerus. Van Duyl
menyatakan bahwa kontraksi regional yang sempit dari pacemaker yang
mungkin dapat merupakan sumber dari kontraksi kandung kemih yang luas
pada pendeita overactive bladder terjadi kontraksi terus menerus tidak
terkontrol ini dapat dikaitkan dengan penyimpangan kontrol dari sel pace
maker.
3. Kelainan otot polos
Sebaian besar penderita irritable bowel syndroma memiliki keluhan berkemih,
termasuk tidak dapat menahan berkemih dan serinng buang air kecil pada
malam hari. Menurut penelitian Whorwell dkk menemukan 50% penderita
overactive bladder merupakan efek lanjut dari kelainan otot polos difus.
11
4. Peningkatan Aktifitas syaraf sensorik
Moore dkk menemukan bahwa densitas subepitelial syaraf sensorik pada
kandung kemih lebih besar dan tebal pada penderita overactive bladder.
5. Defisiensi produksi Prostasiklin
Penderita overaktif kandung kemih memiliki defisiensi dalam produksi
prostasiklin.
6. Iritasi kandung kemih lokal
Iritasi kandung kemih atau uretra terutama uretra proksimal dan sudut segitiga
kandung kemih menyebabkan ketidakstabilan kandung kemih akibat
peningkatan rangsangan sensorik.
7. Penyebab lain psikosomatis.
VI. DIAGNOSIS
Semua penderita dengan simptom overactive bladder harus melewati evaluasi
dasar sebagai kerangka penentuan yang dianjurakan Agency on Health Care Policy
and Research yang meliputi riwayat pemeriksaan fisik, pengukuran volume residu
sesudah pengosongan dan urinealisis. Riwayat klasik dari overactive bladder
adalah usaha kuat untuk pengosongkan kandung kemih atau frekuensi
pengosongan lebih dari 8 kali miksi dalam 24 jam dapat dikaitkan keluarnya urinee
secara tiba tiba. Riwayat juga harus meliputi hal seperti :
6
1. Riwayat spesifik medis, neurologis dan genitourineari dan riwayat obat-
obatan.
2. Ekplorasi mendalam dari gejala overactive bladder termasuk durasi.
3. Penilaian kualitas hidup.
4. Gejala yang terkait, misalnya inkontinensia akibat stress dan prolapsus organ
pelvik.
5. Pola pemasukan cairan dengan catatan pengosongan dalam 24 jam 72 jam.
6. Penilaian mobilitas, lingkungan hidup, faktor sosial.
12
Pemeriksaan fisik harus meliputi :
6
1. Evaluasi neurologis pada segmen bawah sakrum, termasuk bulbocavernosus
dan reflek spinter anus.
2. Pemeriksaan status mental.
3. Pemeriksaan abdomen untuk mengevaluasi massa atau kumpulan cairan, yang
dapat mempengaruhi tekanan intra abdomen dan fungsi detrusor.
4. Pemeriksaan pelvis yang biasanya normal pada penderita overaktif kandung
kemih, untuk menilai adakah kontribusi dari gejala overaktif kandung kemih
dan juga pemeriksaan rectal harus dinilai.
5. Test penekanan akibat batuk, untuk menilai adakah inkontinensia akibat
stress.
6. Estimasi volume residu setelah pengosongan baik melalui kateter atau
ultrasound pelvis, residu < 50 cc normal, residu 100 cc 200 cc dianggap
pengosongan kandung kemih tidak sempurna.
Pemeriksaan penunjang meliputi :
6.11
1. Urinealisis dan kultur digunakan untuk menyingkirkan hematuria (karena
tumor atau batu pada traktus urenarius), glukosuria (yang mungkin
menyebabkan peningkatan frekuensi pengosongan), pyuria dan bakteriuria.
2. Test lanjutan.
a. Pemeriksaan sistoskopi
b. Test Urodynamic dan cytometry
Menurut National Womens Health Report, diagnosis dan terapi overactive
bladder dapat ditegakkan oleh sejumlah pemberi pelayanan kesehatan, termasuk
dokter pada pelayanan primer, perawat, geriatris, gerontologis, urologis,
ginekologis, pedriatris, neurologis, fisioterapis, perawat kontinensia, dan psikolog.
Pemberi pelayanan primer dapat mendiagnosis overactive bladder dengan
pemeriksaan riwayat medis yang lengkap dan menggunakan tabel penilaian gejala.
13
Tes yang biasanya dilakukan adalah urinealisa (tes urine untuk menetukan apakah
gejalanya disebabkan oleh overactive bladder, atau masalah lain, seperti infeksi
saluran kemih atau batu kandung kemih). Bila urinealisa normal, seorang pemberi
pelayanan primer dapat menentukan untuk mengobati pasien atau merujuknya
untuk pemeriksaan gejala lebih lanjut.
3,8
Pada beberapa pasien, pemeriksaan fisik yang terfokus pada saluran kemih
bagian bawah, termasuk penilaian neurologis pada tungkai dan perineum, juga
diperlukan. Sebagai tambahan , pasien dapat diminta untuk mengisi buku harian
kandung kemih (catan tertulis intake cairan, jumlah dan seringnya buang air kecil,
dan sensasi urgensi) selama beberapa hari untuk mendapatkan data mengenai
gejala. Bila setelah langkah tadi diagnosis definitif masih belum dapat ditegakkan,
pasien dapat dirujuk ke spesialis untuk penilaian urodinamis. Tes ini akan
memberikan data mengenai tekanan/ volume dan hubungan tekanan/ aliran di
dalam kandung kemih. Pengukuran tekanan detrusor selama sistometri digunakan
untuk mengkonfirmasi diagnosis overaktifitas detrusor.
2,11
VII. PENATALAKSANAAN
Terapi optimal untuk overactive bladder tergantung pada evaluasi menyeluruh,
diikuti terapi semua penyebab yang ada dan faktor yang berperan. Timbulnya
gejala overactive bladder biasanya multifaktor, dan terapi multimodal yang
meliputi Konservatif dan operatif dapat diberikan.
3
A. KONSERVATIF
1. Bladder training (Waktu miksi)
Ada tiga komponen utama blader training: edukasi, jadwal miksi dengan
sistematik jadual miksi yang tertunda dan tenaga tambahan yang positif. Bagian
edukasi mengkombinasikan tulisan, lisan, instruksi verbal yang melayani untuk
membiasakan pasien dengan anatomi dan fisiologi dari traktus urinearius bagian
bawah. Pasien lalu diminta untuk melawan atau menahan sesuai urgensi,
menunda miksi, dan miksi berdasarkan waktu yang tepat lebih baik daripada
14
miksi yang mendesak. Penyesuaian pada muatan cairan dan penundaan miksi
untuk meningkatkan jumlah volume buli-buli dapat saja digunakan untuk
memperjelas terapi ini. Pasien juga diminta untuk melengkapi catatan harian.
3,6,9
Program bladder training yang efektif yang telah menghasilkan hasil baik
terdiri dari 6 minggu protokol miksi pasien rawat jalan. Hal ini mewakili pasien
sebagai arti untuk mendapatkan kembali kontrol kortikal yang lebih dari
detrusor dan ditawarkan sebagai penatalaksanaan primer pada pasien dengan
overactive bladder. Pasien diatur dengan suatu jadwal miksi berdasarkan
interval miksi merela sehari-harinya; mereka biasanya diminta untuk memulai
dengan miksi setiap jam saat bangun selama 2 minggu pertama.
3,6
Instruksi kepada pasien mencakup :
1. Kosongkan kandung kemih pada waktu yang terjadwal apakah ya atau
tidak saat merasakan miksi yang mendesak.
2. Aspek yang penting adalah inisiasi miksi yang volunter, bukan jumlah
miksi.
3. Menghindari ke kamar mandi antara waktu yang terjadwal, dan menekan
desakan pada waktu yang lain.
4. J angan merasa malu jika gagal.
Protokol membutuhkan follow up setiap 2 minggu sampai efek keinginan
unuk miksi didapat. Karena hal ini suatu pola dari terapi tingkah laku, tenaga
tambahan sangat diperlukan. Interval miksi meningkat 15 sampai 30 menit,
tergantung bagaimana baiknya pasien bertindak pada 2 minggu pertama.
Kombinasi terapi ini dengan latihan Kegel dapat meningkatkan kemampuan
pasien untuk menjadi berkelanjutan karena peningkatan tonus otot dasar
panggul akan meningkatkan kemampuan pasien untuk menahan urine.
Pengobatan ini dapat berhasil jika pasien memiliki interval miksi 2,5 sampai 3
jam dan bebas dari gejala overactive bladder.
3,6
15
2. Modifikasi tingkah laku pada pasien usia lanjut
Keseluruhan insiden overactive bladder meningkat dengan umur dan pada
pasien yang lebih tua, defisit kognitif, dan penurunan mobilits lebih sering
menyebabkan inkontinensia urine. Hadley menjelaskan empat rejimen terjadwal
secara spesifik terkait pada kemampuan pasien. Antara lain meliputi modifikasi
tingkah laku, digunakan secara kognitif ambulatori pasien yang intak, sampai
pada waktunya miksi, digunakan pada pasien dengan kognitif berat dan
perbaikan mobilitas. Pada suatu rancangan studi longitudinal, waktu miksi telah
digunakan untuk 2 minggu pertama tunggal. Lalu oxybutinin ditambahkan pada
rejimen waktu miksi. Secara signifikan waktu miksi mengurangi episode
inkontinensia, dan penambahan oxybutirin klorid tidak memberikan tambahan
yang menguntungkan.
6
Tabel 1. Contoh tabel harian berkemih
Dikutip dari Junizaf
1
16
3. Neuromodulasi sakrum
Neuromodulasi sarum dipertegas sebagai suatu alat terapi yang bermanfat
dalam pengobatan overactive bladder.Tidak diketahui secara pasti bagaimana
kerja neuromodulasi, tetapi sedikitnya dua mekanisme potensial yang
memungkinkan :
3,6,14
1. Aktifasi serabut eferen terhadap sfingter urera secra refleks menyebabkan
relasksasi otot otot detrusor.
2. Aktifasi serabut aferen menyebabkan inhibisi pada level spinal atau
supraspinal.
4. Terapi Obat
Banyak kelas obat yang diteliti atau diusulkan untuk pengobatan gejala
overactive bladder. Kebanyakan percobaan klinis telah mentargetkan gejala
inkontinensia urine, walau percobaan terakhir secara spesifik memasukaan
subjek dengan overactive bladder. Beberapa kelemahan menyertai kualitas
studi. Grup ahli telah mengusulkan standar metodologi untuk memperbaiki
keilmuan terapi obat pada overactive bladder. Obat-obatan yang
direkomendasikan pada kasus overactive bladder antara lain :
3,6,9,12,13
a. Antikolinergik
Agen antikolinergik direkomendasikan sebagai terapi medis pertama kalinya
untuk overactive bladder dengan bekerja pada reseptor ganglion untuk
memblok kontraksi detrusor baik pada kandung kemih normal dan juga
overactive bladder . Pengobatan ini dikontraindikasikan pada pasien dengan
glaukom sudut sempit yang tidak diobati. Semua obat antikolinergik
memiliki efek samping, meskipun mulut kering adalah yang paling sering,
konstipasi, refluks gastoesofageal, pandangan mengabur, retensi urine, dan
efek samping kognitif juga dapat terjadi. Overactive bladder dan demensia
sering ditemukan pada pasie usia lanjut. Karena banyak bentuk demensia
yang diterapi dengan inhibitor kolinesterase secara rutin, kemungkinan efek
samping kognitif dan delirium akibat obat antimuskarinik menjadi perhatian
17
khusus pada populasi ini. Walaupun obat ini tidak mempunyai efek samping
kognisi pada percobaan klinis yang melibatkan dewasa tua yang relatif
sehat, dapat terjadi perubahan fungsi yang penting. Data kuantitatif EEG
meunjukkan oxybutinin memiliki efek pada SSP diabandingkan trospium
atau tolterodine. Agen antikolinergik kerja lama dan yang terbaru, agen
antimuskarinik yang lebih selektif harus diperiksa secara klinis untuk efek
samping kognitif, terutama pada pasien lanjut.
3,6
Di antara obat antikolinergik, hanya oxybutinin, propiverin, tolterodin,
dan trospium yang memiliki level rekomendasi klinis yang tinggi dan bukti
efikasi. Oxybutinin dan tolterodine telah dipelajari dengan luas. Terdapat
dalam sediaan segera dan bentuk absorbsi lambat, juga transdermal patch.
Oxybutynin absorbsi cepat (dosis umum dewasa, 5 mg tiga kali sehari)
tampak efektif dalam terapi overaktifitas detrusor neurogenik dan non
neurogenik dengan inkontinensia urgensi. Karena inilah, oxybutinin
memberikan perbaikan yang signifikan, berupa reduksi episode
inkontinensia sebesar lebih dari 50%, pada hampir 60 hingga 80% subjek
studi. Efikasi oxybutynin absorbsi cepat memiliki efek samping
antimuskarinik pada obat parenteral dan metabolit aktifnya (N-
desetiloxybutynin), mulut kering, sebagai contoh, pada hampir dua pertiga
subjek percobaan klinis. Oxybutynin absorbsi cepat yang generik relatif
murah dan bermanfaat pada pasien yang gejalanya paling baik diatasi
dengan obat kerja singkat (misalnya gejala yang mengganggu hanya bila
pasien jauh dari rumah atau malam hari).
3,6,12,13
Sediaan oxybutyrin absorbsi lambat sehari sekali tampak memiliki efek
manfaat yang sama dengan absorbsi cepat, dengan efek samping lebih
sedikit. Kebanyakan studi oxybutynin lepas terkontrol melaporkan reduksi
episode inkontinensia urgensi hampir 70%. Oxybutynin transdermal patch
juga ada yang sama efektif dengan oxybutynin absorbsi cepat tapi dengan
insidens mulut kering separuhnya.
3,6
18
Tolterodine adalah antagonis muskarinik yang tersedia dalam preparat
kerja singkat (2 kali sehari) dan kerja lama (sekali sehari). Kedua bentuk
memiliki efek klinis dan statistik yang signifikan pada gejala overactive
bladder pada percobaan multipel, acak, terkontrol. Efek samping mirip
dengan oxybutynin kerja singkat dengan 20 hingga 25% mulut kering, dan
penghentian akibat efek samping sama dengan placebo (5 hingga 6%).
Tolterodine tampak sama efektif pada subjek tua dan muda dan ditoleransi
dengan baik pada satu percobaan dengan pasien yang tinggal di perawatan.
Dua studi tersponsor oleh industri yang dipublikasi, telah membandingkan
bentuk kerja cepat tolterodine dengan oxybutynin. Dalam satu studi,
dokternya diacak, wanita (mean usia 60 tahun) diacak dan menerima satu
atau agen yang lainnya. Hasil kedua percobaan menunjukkan efikasi dan
efektifitas yang sama. Tambahan, keduanya tampak efektif ketika
dikombinasikan dengan berbagai intervensi perilaku.
3,6
Trial acak, terkontrol mengindikasikan propiverine dan trospium efektif
untuk terapi inontinensia urgensi dan memiliki efek samping lebih sedikit
daripada oxybutinin kerja singkat. Walaupun hyosciamin, seperti oxybutynin
kerja singkat, dapat bermanfaat bagi beberapa pasien dengan gejala
intermiten, dapat disertai efek samping. Propanteline terbukti efektif dalam
terapi inkontinensia urgensi, tapi perlu dosis multipel per harinya dan
memiliki insiden efek samping yang lebih tinggi bila dihentikan.
6
Wanita postmenopause dengan gejala overactive bladder sering diterapi
estrogen oral atau topikal, tapi data tentang efektfitas agen tersebut masih
sedikit. Terapi nokturia, gejala overactive bladder yang paling mengganggu
pada pasien, tergantung pada penyakit dasar overaktivitas detrusor,
poliuria nokturna, gangguan tidur primer, atau kombinasi kondisi tersebut.
Nokturia yang berhubungan dengan overaktivitas detrusor diterapi dengan
anti kolinergik.
6
19
b. Antidepresan trisiklik
Efek antidepresan trisiklik pada traktus urinearius bawah adalah 2 kali lipat
antikolinergik dan efek alfa adrenergik, untuk meningkatkan tonus uretra
dan leher kandung kemih. Dua studi kontrol yang random mengungkapkan
keefektifan doxepin dan imipramin dalam mengurangi nokturnal
inkontinensia pada pasien overactive bladder. Efek samping yang dapat
ditimbulkan antara lain fatigue, xerostomia, pusing, pandangan kabur,
nausea, dan insomnia. Dosis oral biasanya 10-25 mg 1-3 kali perhari,
dengan total dosis perhari biasanya 25-100 mg.
3,6
c. Anti inflamasi nonsteroid
Obat anti inflamsi nonsteroid efektif untuk overactive bladder karena efek
inhibisinya terhadap prostaglandin sintetase sehingga mengganggu peranan
prostaglandin untuk kontraksi kandung kemih. Penelitian yang telah
dilakukan sangat terbatas, dan pada umumnya penggunaan obat ini tidak
sukses. Dosis yang efektif untuk mengurangi kontraksi kandung kemih
menimbulkan efek samping gastritis dan ulserasi.
6
d. Kalsium-channel bloker
Kalsiun-channel bloker menghentikan influk kalsium ekstraseluler yang
dibutuhkan untuk proses kontraksi derusor dan juga mencegah pemindahan
dari penyimpanan kalsium intraseluler dengan hasil adanya hambatan
kontraksi eksitasi. Obat-obat ini khusus digunakan pada pengobatan angina
karena kemampuannya untuk mencegah perpindahan kalsium intraseluler
melalui saluran lambat pada membran. Walaupun demikian, peneliti telah
menggunakan obat-obat ini pada pengobatan overactive bladder, karena
tidak dihambatnya kandung kemih telah menunjukkan adanya
ketergantungan pada influks kalsium. Tidak ada studi kontrol nifedipin,
verapamil, ataupun diltiazem yang ditampilkan, dan penggunaannya untuk
inkontinensia urgensi tidak direkomendasikan untuk saat ini.
3,6
20
B. OPERATIF
Pembedahan harus diprtimbngkan jika terapi perilaku atau terapi pengobatan
telah gagal karena adanya morbiditas lanjut pada terapi ini.
11
Pilihan
pembedahan bervariasi antara lain :
6
1. Augmentasi Sitoplasti
Direkomendasikan pada pasien overactive bladder yang berat atau bagi
mereka dengan kompliansi kandung kemih yang rendah, dengan tujuan unuk
menciptakan unit penyimpanan urine yang komplians dan dengan kapasitas
yang besar. Hampir semua segmen traktus gastrointestinal, seperti ureter,
telah digunakan untuk augmentsi., tetapi tidak ada satu segmen yang mewakili
substitusi ideal karena masing-masing memiliki komplikasi sendiri. Evaluasi
preoperatif harus termasuk penilaian fungsi renal (kreatinin serum urine 24
jam, elektrolit serum, blood urea nitrogen), penilaian fungsi saluran cerna
(sigmoidoskopi dan barium enema), sitoskopi untuk melihat adanya
abnormalits intravesikal, dan kultur urine. Selama pembedahan kandung
kemih dibagi dua melalui insisi secara sagital dari 3 cm diatau leher buli-buli
sampai 2 cm di atas trigonum. Pada ileosistoplasti dipilih ileum terminal yang
panjangnya sekitar 20-40 cm dan sedikitnya 15 cm proksimal ke katup
ileosekal. Usus dibagi dan penganastomosisan kembali ujung ke ujung pada
sisa usus dilakukan untuk menimbulkan kontinuitas usus. Segmen ileum yang
dipilih kemudian dibuka pada sisi anti mesenteriknya dan dibentuk menjadi
bentuk U atau S, menjaga agar suplai darahnya intak, yang kemudian
dianastomosiskan ke kandung kemih. Pada ileosistoplasti, kantung caecum
dibuat bersama-sama dengan segmen ileum terminal dan dianastomosiskan ke
kandung kemih. Tujuan augmentasi sitoplasti pada pasien instabilitas detrusor
dengan lesi neuromotorik di bawah atau disinergis sfingter detrusor yaitu
untuk menginduksi retensi urine dan mengizinkan pasien untuk
mngososngkan kandung kemih sendiri dengan menggunakan kateter
sementara. Komplikasi post operatif dari augmentasi intestinositoplasti
21
termasuk infeksi traktus urinearius, pembentukan batu, dan masalah
metabolik. Kontra indikasinya termasuk insufisiensi renal, penyakit usus, dan
ketidakmampuan untuk melakukan kateter sendiri. Rata-rata penyembuhannya
adalah 77,2 %; rata-rata pemulihannya adalah 80,9 %.
6
2. Diversi urine
Diversisi urine umunya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir pada pasien
yang bukan calon yang baik untuk rekonstruksi traktus urinearius bawah dan
dapat diobati dengan bentuk terapi lain. Dua tipe diversi urine adalah diversi
urine yang kontinen dan yang tidak kontinen, yang pertama membutuhkan alat
pengumpul eksterna. Bricker mempubliksikan pipa ileus sebagai metode
untuk diversi urine yang nonkontinen pada tahun 1950. Tehnik terkini
mengikitkan isolasi 15-20 cm ileum terminal, 10-15 cm dari anastomosis
ileocaecal. Ureter ditranseksi 3-4 cm dari kandung kemih dan
dianastomosiskan baik ke perbatasan antimesenterik loop ileal atau akhir
proksimal loop ileal. Usus yang tersisa kemudian dianastomosiskan kembali
dan sebuah lubang dibuat pada diniding anterior abdomen dengan
menggunakan loop ileum. Komplikasi prosedur ini adalah adanya infeksi
luka, kebocoran uretroileal, obstruksi intestinal, stenosis, retraksi, dan hernia.
Kompliksi yang jarang terjadi adalah urolithiasis termasuk adanya pipa dan
transformsi maligna dari loop ileum.
6
Keuntungan utama dari diversi urine kontinen daripada yang nonkontinen
adalah dihilangkannya peralatan pengumpul urine eksterna. Beberapa
penampung dirancang dengan berbagi kombinasi berbeda dari ileum, caecum,
kolon, sigmoid dan rektum untuk menggantungkannya. Penampung yang
ideal harus mempunyai tekanan intrinsik yang rendah dan juga kapasitas
adekuat untuk menyediakan kontinensia dan mencegah refluks. Biasanya 40
cm ileum atau 20 cm usus besar atau kombinasinya dibutuhkan untuk
menciptakan penampung dengan kapasitas yang adekuat.
6
22
3. Denervasi kandung kemih
Denervasi kandung kemih dapat diselesaikan dengan rhizotomi sakral selektif,
injeksi foramen S-3, atau denervsi paravaginal. Komplikasinya termasuk
hiperestesia perineal, infeksi luka, dan perdarahan intraoperatif. Pengawasan
jangka panjang menyatakan bahwa 50 % telah menjadi persisten atau menjadi
inkontinensia, dan sebagai tambahan 20 % menjadi kering dengan
penambahan antikolinergik.
6
VIII. RINGKASAN
Gejala overactive bladder berupa frekuensi, urgensi, nokturia, dan urge
inkontinnsia dapat sangat mengganggu dan berhubungan dengan konsekuensi
buruk serius. Gejala ini dapat disebabkan banyak faktor, termasuk kelainan
saluran kemih bawah, kondisi saraf, faktor perilaku seperti intake kafein, dan
berbagai obat yang diresepkan. Proses patofisiologis pada pasien seringkali
multifaktor. Evaluasi diagnosis meliputi riwayat penyakit terfokus, pemeriksaan
fisik, dan urinealisa. Pasien tertentu harus ditentukan sisa urine post miksi, dan
beberapa terpaksa menjalani sitoskopi (seperti yang dengan hematuria) atau test
urodinamik yang rumit (seperti mereka dengan kelainan saraf atau retensi uri).
Pasien dengan overactive bladder sering diatasi secara konservatif seperti
bladder training, edukasi tingkah laku, dan pemberian obat-obatan Pilihan
pertama terapi obat adalah agen antimuskarinik. Dua agen yang diterliti dengan
baik adalah oxybutynin dan tolterodine, keduanya terbukti efektif pada preparat
kerja singkat maupun lama. Preparat lepas diperpanjang dan oxybutynin skin
patch biasanya dapat ditolerir baik, tapi semua obat antikolinergik memiliki efek
samping yang sedikit mengganggu. Efek agen tersebut pada fungsi kognitif
sering pada pasien usia lanjut. Terapi pembedahan digunakan apabila langkah
yang ditempuh melalui terapi konservatif tidak membuahkan hasil.
23
IX. RUJUKAN
1. J unizaf. Overactive bladder. Dalam : Buku Ajar Neurofisiologi Uroginekologi I.
J akarta : Subbagian Uroginekologi-Rekonstruksi Bagian Obsteri dan Ginekologi
FKUI/ RSUPN-CM. 2002; 88-89
2. Overactive bladder/Urge incontinence criteria for its acceptance for self medication.
Workshop 13-14 September 2001. Development of an information policy for
medicinal product. 2002; 1-13
3. Ouslander J G. Management of overactive bladder. N Engl J Med. 2004; 350: 786-
799
4. Taher A. Anatomi dan fisiologi miksi. Dalam : Simposium diagnosis dan
penatalaksanaan mutakhir inkontinensia urine. J akarta: 2000
5. Wise B. The neurology of the lower urineary tract : innervation, neuropharmacology
and neurophysiology. In: Cardozo L. Urogynecology 1
th
ed. New york : Churchill
livingstone, 1997;41-49
6. Montella J M. Management of overactive bladder. In : Ostergrads urogynecology and
pelvic floor dysfunction. 5
th
ed. Philadelphia : Lippincot William & Wilkuns.
2003;293-307
7. Bent AE. Pathophysiology. In : Ostergrads urogynecology and pelvic floor
dysfunction. 5
th
ed. Philadelphia : Lippincot William & Wilkuns. 2003; 43-51
8. Weinberger MW. Differential diagnosis of urineary incontinence. In : Ostergrads
urogynecology and pelvic floor dysfunction. 5
th
ed. Philadelphia : Lippincot William
& Wilkuns. 2003; 61-69
9. Amuzu BJ . Nonsurgical therapies for urineary incontinence. Clin Obstet Gynecol.
1998; 41: 702-710
10. Goldberg RP, Sand PK. Pathophysiology of the overactive bladder. Clin Obstet
Gynecol. 2002; 45: 182-192
11. Dwyer Pl, Rosamilia A. Evaluation and diagnosis of the overactive bladder. Clin
Obstet Gynecol. 2002; 45: 193-204
12. Cannon Tw, Chancellor MB. Pharmacotherapy of the overactive bladder and
advanced in drug delivery Clin Obstet Gynecol. 2002; 45: 205-207
13. Weinberger MW. Conservative treatment of urineary incontinence. Clin Obstet
Gynecol 1995; 38: 179-187
14. Mc Lennan MT. Sacral neuromodulation. In : Ostergrads urogynecology and pelvic
floor dysfunction. 5
th
ed. Philadelphia : Lippincot William & Wilkuns. 2003; 325-
341
Anda mungkin juga menyukai
- Ppi IadpDokumen35 halamanPpi IadpAkhmad Syarif100% (1)
- Aspek MedikolegalDokumen22 halamanAspek Medikolegaltria claresiaBelum ada peringkat
- Overactive BladderDokumen11 halamanOveractive BladderAmita Shindu KusumaBelum ada peringkat
- Overactive BladderDokumen12 halamanOveractive BladderDaramarissaBelum ada peringkat
- Overactive BladderDokumen14 halamanOveractive BladderIAAM_17Belum ada peringkat
- Septik ArthritisDokumen24 halamanSeptik ArthritisRhadezahara PatrisaBelum ada peringkat
- Infeksi NosokomialDokumen20 halamanInfeksi NosokomialAgus SalimBelum ada peringkat
- 2023 Pedoman Penulisan Visum Et RepertumDokumen24 halaman2023 Pedoman Penulisan Visum Et RepertumMia HaKas MalintaBelum ada peringkat
- Hubungan Lama Penggunaan Laptop Dengan Ketajaman PenglihatanDokumen47 halamanHubungan Lama Penggunaan Laptop Dengan Ketajaman Penglihatanasih rahayuBelum ada peringkat
- Proposal Sosialisasi Hukum KesehatanDokumen7 halamanProposal Sosialisasi Hukum KesehatanwixwokBelum ada peringkat
- Mekanisme Gangguan Otak Pada Penggunaan NapzaDokumen17 halamanMekanisme Gangguan Otak Pada Penggunaan NapzaSarah Rahmayani SiregarBelum ada peringkat
- Bahan Flam GeigerDokumen1 halamanBahan Flam Geigerinna muthmainnahBelum ada peringkat
- Pengaruh Tingkat Stres Dengan Kejadian GastritisDokumen14 halamanPengaruh Tingkat Stres Dengan Kejadian GastritisFahni IndriyaniBelum ada peringkat
- Makalah SlideDokumen23 halamanMakalah SlidesaidilloBelum ada peringkat
- Moral, Etika Dan Disiplin Profesi DokterDokumen50 halamanMoral, Etika Dan Disiplin Profesi DokterAnonymous ZAi7cEa100% (1)
- Pedoman Standar Pelayanan PublikDokumen11 halamanPedoman Standar Pelayanan PublikMomen AnimeBelum ada peringkat
- Referat Embalming Forensik KariadiDokumen57 halamanReferat Embalming Forensik KariadiMaa LviinBelum ada peringkat
- Morning Report AppendicitisDokumen15 halamanMorning Report AppendicitisHananya ManroeBelum ada peringkat
- Bab III Metode Penelitian MixedDokumen18 halamanBab III Metode Penelitian MixedAhmad Nurdianto100% (1)
- Olah Tempat Kejadian PerkaraDokumen18 halamanOlah Tempat Kejadian PerkaraLatifah Khusnul KBelum ada peringkat
- CRPDokumen4 halamanCRPAzizatul AuliaBelum ada peringkat
- Dimanaakankucari PDFDokumen61 halamanDimanaakankucari PDFAgung SatriaBelum ada peringkat
- EmbalmingDokumen12 halamanEmbalmingAmarita Sridevi LaksmawatiBelum ada peringkat
- Laporan KasusDokumen10 halamanLaporan Kasuslindung85Belum ada peringkat
- Peran Dokter Di TKPDokumen10 halamanPeran Dokter Di TKPTrias Putra PamungkasBelum ada peringkat
- PPT Etik Dan MedikolegalDokumen18 halamanPPT Etik Dan MedikolegalAndi MuhammadBelum ada peringkat
- Embalming 1Dokumen30 halamanEmbalming 1fellamuqhnyBelum ada peringkat
- Soal Ujian Koas Stase EmergencyDokumen3 halamanSoal Ujian Koas Stase EmergencyyuleesatrioBelum ada peringkat
- Disfungsi Ereksi Dan Gangguan PsikiatriDokumen49 halamanDisfungsi Ereksi Dan Gangguan PsikiatriTinnekeBelum ada peringkat
- Def, Fungsi, Alur Pembuatan VerDokumen12 halamanDef, Fungsi, Alur Pembuatan VerCynthia OktariszaBelum ada peringkat
- Overactive BladderDokumen34 halamanOveractive BladderKurnia Sari SyaifulBelum ada peringkat
- FastDokumen53 halamanFastFANNY ALFIONITABelum ada peringkat
- Penyuluhan Sirosis HepatisDokumen12 halamanPenyuluhan Sirosis Hepatisreni permanaBelum ada peringkat
- Referat Siklus Sirkadian RahelDokumen25 halamanReferat Siklus Sirkadian RahelArihta Wulan GintingBelum ada peringkat
- Perbaikan PROPOSAL ANALISIS DNA SEBAGAI BUKTI YURIDIS DALAM ANALISIS FORENSIK SESUAI DENGAN KAJIAN PASAL 184 KUHPDokumen38 halamanPerbaikan PROPOSAL ANALISIS DNA SEBAGAI BUKTI YURIDIS DALAM ANALISIS FORENSIK SESUAI DENGAN KAJIAN PASAL 184 KUHPProgram PTMBelum ada peringkat
- Pelaporan Insiden Kejadian PasienDokumen8 halamanPelaporan Insiden Kejadian PasienJihan AisyBelum ada peringkat
- Bagian Ilmu Kedokteran ForensikDokumen13 halamanBagian Ilmu Kedokteran ForensikCeline NyokoBelum ada peringkat
- Identifikasi Risiko p2pDokumen14 halamanIdentifikasi Risiko p2pDjatiningsih SetyoriniBelum ada peringkat
- Skenario Kulit Kelompok X-4Dokumen11 halamanSkenario Kulit Kelompok X-4Khairul MustafaBelum ada peringkat
- Tinjauan Pustaka - Visum Et RepertumDokumen22 halamanTinjauan Pustaka - Visum Et RepertumCokorda Agung Arbi MaranggiBelum ada peringkat
- UTS PHI - Rohul Andri AldiDokumen7 halamanUTS PHI - Rohul Andri AldiNabila ImaninaBelum ada peringkat
- Gabungan (Etika Komunikasi & Kode Etik Kedokteran)Dokumen26 halamanGabungan (Etika Komunikasi & Kode Etik Kedokteran)Raysha RamadhaniBelum ada peringkat
- Simulasi Kasus Kegawatan Sirkulasi WS ALTEMDokumen8 halamanSimulasi Kasus Kegawatan Sirkulasi WS ALTEMAziz AndriyantoBelum ada peringkat
- UroflowmetriDokumen1 halamanUroflowmetriJulia HutabaratBelum ada peringkat
- Etika Profesi KedokteranDokumen23 halamanEtika Profesi KedokteranClaudia Lintang100% (1)
- (123doc - VN) Penentuan Tinggi Badan Berdasarkan Panjang Telapak TanganDokumen82 halaman(123doc - VN) Penentuan Tinggi Badan Berdasarkan Panjang Telapak TanganMardhatillah MarsaBelum ada peringkat
- PPK Anak - AsihDokumen26 halamanPPK Anak - AsihwahiraBelum ada peringkat
- Hubungan Dokter Dan Perusahaan Farmasi Ditinjau Dari Aspek Etika Dan HukumDokumen12 halamanHubungan Dokter Dan Perusahaan Farmasi Ditinjau Dari Aspek Etika Dan HukumhattaBelum ada peringkat
- Superimposisi Dalam Identifikasi WajahDokumen22 halamanSuperimposisi Dalam Identifikasi WajahLaurencia ViolettaBelum ada peringkat
- Torsio TestisDokumen30 halamanTorsio TestisTiara RahmawatiBelum ada peringkat
- Evidence Based MedicineDokumen7 halamanEvidence Based MedicineTubagus Arif GoodBelum ada peringkat
- Analisa Kasus Malpraktek Dan KelalaianDokumen23 halamanAnalisa Kasus Malpraktek Dan KelalaiankurniawatiBelum ada peringkat
- Entomologi ForensikDokumen32 halamanEntomologi ForensikDian Pertiwi Alty0% (1)
- Odontologi Forensik Visum HidupDokumen25 halamanOdontologi Forensik Visum Hidupnur handayaniBelum ada peringkat
- Tugas Dan Peran Idi Dalam Pembinaan Dan IanDokumen48 halamanTugas Dan Peran Idi Dalam Pembinaan Dan IanHani Ariindra100% (1)
- Referat OABDokumen30 halamanReferat OABUtari Gita MutiaraBelum ada peringkat
- Oab FixDokumen25 halamanOab FixAncha Ayu AmishintaBelum ada peringkat
- Inkontinensia UrineDokumen19 halamanInkontinensia Urinedwirinanti90215100% (1)
- Inkontinensia UrinDokumen33 halamanInkontinensia UrinRonald WorkmanBelum ada peringkat