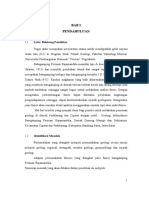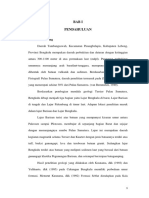Parangkusumo
Parangkusumo
Diunggah oleh
Supri YantoJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Parangkusumo
Parangkusumo
Diunggah oleh
Supri YantoHak Cipta:
Format Tersedia
i
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOLOGI
LABORATORIUM GEOLOGI DINAMIK
LAPORAN FIELDTRIP GEOMORFOLOGI
IMOGIRI PANGGANG PARANGTRITIS PARANGKUSUMO
DISUSUN OLEH:
RAMADAN SARI
08/269208/TK/34338
KELOMPOK :
1
ASISTEN KELOMPOK :
ROSMELIA CIPTA
YOGYAKARTA
JUNI
2009
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini sebagai tugas laporan
kegiatan field trip praktikum geologi struktur yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei
2009. Kegiatan field trip ini dilaksanakan di Kali Oyo, Imogiri; Panggang; Parangtritis;
Parangkusumo.. Kegiatan field trip sendiri dilakukan dalam rangka memenuhi teori
teori yang didapat di dalam kelas dengan cara terjun langsung ke lapangan dan
melakukan pengamatan langsung serta pengaplikasian penggunaan peralatan lapangan.
Laporan ini merupakan hasil dari pengamatan langsung di lapangan dan penulis
berusaha untuk mendeskripsikan obyek dan menganalisis data yang telah diamati di
lapangan dalam laporan ini
Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari pengarahan, bimbingan,
dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan
terima kasih kepada :
1. Bapak Ir. Srijono selaku dosen pengampu mata kuliah geomorfologi.
2. Bapak Salahuddin Husein, ST. M.Sc,, selaku dosen pengampu mata kuliah
Geologi Struktur yang telah memberikan kuliah di dalam kelas.
3. Para asisten praktikum Geomorfologi yang telah membimbing dan memberikan
penjelasan selama di lapangan.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini
Tiada gading yang tidak retak, tentu saja masih terdapat banyak kekurangan
dalam penyusunan laporan ini, untuk itu penulis memerlukan kritik dan saran sebagai
perbaikan untuk yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bemanfaat
untuk kita semua
Yogyakarta, 2 Juni 2009
Penulis
iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Gambar / Tabel v
BAB I. Pendahuluan 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Maksud dan Tujuan 1
I.3 Waktu dan Kesampaian Daerah 1
I.4 Alat dan Bahan 1
BAB II. Geologi Regional 3
II.1 Geomorfologi Regional 3
II.2 Stratigrafi Regional 5
II.3 Struktur Geologi Regional 6
BAB III. Pembahasan Setiap Stasiun Pengamatan 11
III.1 Stasiun Pengamatan 1 11
III.2 Stasiun Pengamatan 2 12
III.3 Stasiun Pengamatan 3 14
III.4 Stasiun Pengamatan 4 16
iv
BAB IV. Kesimpulan 19
Daftar Pustaka 20
v
DAFTAR GAMBAR
Foto 1 11
Foto 2 13
Foto 3 13
Foto 4 14
Foto 5 16
Foto 6 17
Sketsa stasiun pengamatan 1 12
Sketsa stasiun pengamatan 2 14
Sketsa stasiun pengamatan 3 15
Sketsa stasiun pengamatan 4 18
vi
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Kegiatan field trip dilakukan dalam rangka memenuhi teori teori yang didapat
di dalam kelas dengan cara terjun langsung ke lapangan serta pengaplikasian
penggunaan peralatan lapangan. Selain itu, di alam, kadangkala teori yang didapat di
dalam kuliah mempunyai kontradiksi dengan data yang didapat dari lapangan.
Kontradiksi kontradiksi tersebut merupkan tugas kita sebagai geologist untuk
mengetahui penyebab timbulnya kontradiksi tersebut.
I.2 Maksud dan Tujuan
Maksud diadakannya field trip Geomorfologi ini adalah agar peserta field trip
dapat mengenal dan mengamati seluruh keadaan geologi yang terdapat di lokasi
pengamatan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan gambaran secara umum
fenomena geologi yang nyata dan melalui kegiatan ini juga diharapkan kita bisa
menerapkan teori yang selama ini didapat dibangku kuliah. Tujuan Fieldtrip kali ini
adalah untuk mengamati bentang alam, struktural, fluvial, kars, pantai dan eolian
Pengamatan meliputi proses yang terjadi, litologi, dan potensi daerah. Adapun manfaat
yang juga di dapat dari kegiatan ini adalah dapat menambah pengalaman praktikan
dalam kegiatan kegiatan lapangan
I.3 Waktu dan Kesampaian Daerah
Kegiatan field trip ini dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2009. Keberangkatan
dari kampus pukul 07.00 WIB dan pulang kembali ke kampus sekitar pukul 16.00 WIB.
Lokasi field trip adalah Imogiri Panggang Parangtritis Parangkusumo.
I.4 Alat dan Bahan
Peralatan Perkelompok yang dibawa pada saat field trip ini adalah :
1. Kompas Geologi, berfungsi sebagai penentuan arah, ploting, penentuan
besar sudut, den mengukur kedudukan lapisan batuan.
2. Palu geologi, berfungsi sebagai alat untuk mengambil sampel batuan.
vii
3. Plastik, untuk tempat batu sampel.
4. Larutan HCl, untuk mengetahui kandungan karbonat dalam suatu batuan.
5. Lup, yang berguna untuk membantu dalam pengamatan batuan dengan
pembesaran 10 kali.
6. Peta Lapangan, sebagai alat untuk menentukan lokasi dan pengeplotan data.
7. Clipboard, untuk alas tulis ataupun medium pembantu untuk mencari strike
dan dip suatu perlapisan.
8. Buku lapangan dan alat-alat tulis, berfungsi untuk mencatat data lapangan.
9. Kamera / foto
Peralatan individu yang dibawa saat field trip :
1. Pensil dengan kekerasan sedang
2. Pensil warna
3. Sepasang mistar segitiga
4. Busur derajat
5. Karet penghapus
6. Ballpoint
7. Buku catatan lapangan
8. Clip Board
9. Mantel \ Ponco.
viii
BAB II
GEOLOGI REGIONAL
II.1 Geomorfologi Regional
Van Bemmelen (1970) membagi fisiografi Pulau Jawa menjadi beberapa
zonasi, daerah kunjungan terletak pada zona Pegunungan Selatan. Zona
Pegunungan Selatan merupakan pegunungan struktural yang memanjang dari
barat ke timur searah bentuk geometri Pulau Jawa dan terbagi menjadi
Pegunungan Selatan Jawa Timur dan Pegungang Selatan Jawa Barat. Daerah
kunjungan termasuk pada bagian barat Pegunungan Selatan Jawa Timur, yang
secara fisiografi masih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :
1. Bagian utara yang ditandai oleh rangkaian Pegunungan Baturagung Masif
Panggung Masif, dicirikan oleh relief yang kuat dan tersusun oleh batuan
volkanik klastik.
2. Bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang tersusun oleh
perselingan batupasir berlapis dan napal.
3. Bagian selatan yang disebut sebagai komplek Gunung Sewu, memiliki
karakteristik bentang alam karst, tersusun oleh batugamping terumbu dan
batugamping berlapis.
Pegunungan Selatan
Daerah Pegunungan Selatan ini membujur dari E W (dari Pacitan
hingga Parangtritis). Daerah ini merupakan daerah perbukitan yang di bagian
selatan dibatasi oleh Samudra Hindia dengan pantai yang curam dan di sebelah
utara oleh dataran Wonosari dan Batureno.
Daerah Pegunungan Selatan termasuk Formasi Wonosari, yang pada bagian
bawahnya tersusun oleh batugamping berlapis dan disebut anggota Oyo. Ke arah
lebih muda, anggota Oyo bergradasi menjadi dua fasies berbeda. Di daerah
Wonosari, semakin ke selatan berubah menjadi batugamping terumbu dan
dinamakan anggota Wonosari. Di barat daya Wonosari, batugamping terumbu
ini berubah fasies menjadi batugamping berlapis yang bergradasi menjadi napal
dan disebut anggota Kepek (Rahardjo dan Wijono, 1993). Secara keseluruhan,
Formasi Wonosari terbentuk selama miosen akhir.
ix
Daerah ini memperlihatkan topografi karst berupa bukit-bukit berbentuk
kerucut dan setengah bola (hemisfer), cekungan-cekungan membulat dan
memanjang yang sebagian terisi air (telaga), sungai bawah tanah, dan gua-gua
bawah tanah (Pudjianto, 2001).
Pembentukan topografi karst (karstifikasi) sangat tergantung pada proses
pelarutan yang dikontrol oleh beberapa faktor, diantaranya komposisi mineral,
penyusun batuan, iklim, adanya bidang perlapisan, dan rekahan batuan.
Batuan yang dapat menghasilkan topografi karst adalah batuan yang mudah larut
seperti batugamping (White, 1988). Meskipun demikian, tidak semua daerah
yang tersusun oleh batugamping dapat membentuk topografi karst, hanya
batugamping yang mempunyai komposisi mineral, porositas, dan permeabelitas,
serta kekuatan batuan tertentu yang dapat menghasilkan topografi karst.
Menurut Sweeting (1968) di dalam Ritter (1979), untuk menghasilkan
topografi karst diperlukan syarat-syarat batuan sebagai berikut :
1. batuan harus masif, seperti batugamping murni yang keras dan kristalin.
2. lapisan batuan yang larut harus tebal, diperkirakan lebih dari 100 m.
3. batuan harus mempunyai perlapisan batuan yang baik dan banyak rekahan.
4. batuan harus berada pada ketinggian (di atas base level) yang cukup besar
yang memungkinkan sirkulasi air berlangsung dengan baik.
Selain faktor batuan, iklim dan vegetasi juga ikut berperan dalam proses
karstifikaisi. Proses karstifikasi memerlukan air yang cukup banyak untuk
sirkulasi dalam batuan. Disamping sebagai pelarut, air juga memberi peluang
pertumbuhan vegetasi dan aktifitas mikroorganisme dalam tanah yang
memberikan tambahan CO
2
.
Batugamping umumnya tersusun oleh dua penyusun utama, yaitu kalsit
(CaCO
3
) dan dolomit [CaMg(CO
3
)
2
], dimana keduanya memiliki sifat mudah
larut dalam air yang mengandung asam karbonat (Selby, 1985). Adapun
prosesnya adalah :
CaCO
3
+ H
2
CO
3
Ca
+
+ 2HCO
3
CaMg(CO
3
)
2
+ 2H
2
CO
3
Ca
+
+ 4HCO
3
x
Asam karbonat (H
2
CO
3
) dibentuk dari pelarutan CO
2
yang berasal dari udara
yang bereaksi dengan air :
CO
2
+ H
2
O H
2
CO
3
Sartono (1964) dalam Brahmantyo dkk (1998) berpendapat bahwa bukit-
bukit karst yang berbentuk kerucut dan hemisfer tersebut merupakan inti
terumbu koral. Namun, menurut Pudjianto (2001) bahwa berdasarkan
pengamatan lapangan dan analisa petrografi, bukit-bukit karst tersebut tersusun
oleh batugamping berlapis. Bentuk bukit karst yang khas tersebut kemungkinan
besar dikontrol oleh adanya kekar, bidang perlapisan dan variasi litologi.
Pannekoek (1949) menduga selain dikontrol oleh struktur seperti kekar, bentuk
bukit karst tadi juga dikontrol oleh pola penyaluran permukaan.
Morfologi depresi tertutup (dolina) yang tersebar di sini umumnya
memiliki diameter 100-500 m. Sebagian besar dolina ini terdapat lubang tempat
masuknya air ke dalam tanah yang sering disebut sebagai luweng. Pada
umumnya dalam setiap dolina mempunyai satu luweng. Terkadang luweng ini
tertutup oleh tanah hasil pelapukan yang tertransport dari tempat yang lebih
tinggi sehingga terbentuk lapisan kedap air yang pada akhirnya membentuk
telaga pada dolina tersebut.
Selby (1985) mengelompokkan berbagai jenis dolina dalam 4 jenis
berdasarkan genesanya yaitu dolina pelarutan (solutional dolines), dolina
runtuhan (collapse dolines), dolina amblesan (subsidence dolines) dan dolin
akibat masuknya sungai permukaan ke bawah tanah (alluvial streamsink
dolines). Bila dua atau lebih dolina bergabung maka akan terbentuk morfologi
uvala. Di daerah tropis, kehadiran dolina terkadang tergantikan oleh kehadiran
depresi berbentuk bintang yang tidak beraturan dengan kemunculan bukit-bukit
karst di sekelilingnya. Depresi yang tidak beraturan ini dinamakan cockpits dan
bukit-bukit karst yang mengelilingi dinamakan cones. Secara keseluruhan,
mereka dinamakan cockpits karst.
Pantai Parangkusumo
Batas daerah kunjungan di bagian selatan merupakan daerah pesisir yang
sebagian besar merupakan pantai curam. Pantai Parangkusumo terletak di
xi
sebelah barat Pantai Parangtritis. Kedua pantai tersebut dipisahkan oleh
kehadiran sungai kecil. Perbedaan moroflogi pada kedua pantai terletak pada
kehadiran bentang alam eolian dalam bentuk komplek gumuk pasir (coastal
dune). Gumuk pasir lebih ekstensif di Parangkusumo. Morfologi kedua pantai
tersebut dipisahkan oleh tebing batugamping di sebelah timur dan muara Sungai
Opak di sebelah barat. Sementara di sebelah utara dibatasi oleh gawir sesar
Parangtritis dan gawir sesar Girijati yang berarah N S (Sudarno,1997).
II.2 Stratigrafi Regional
Mengacu pada panduan Ekskursi Geologi Regional (1996), daerah
Pegunungan Selatan bagian barat tersusun oleh batuan yang hampir seluruhnya
terbentuk pengendapan gaya berat (grafity deposite process) setebal kurang lebih
4000 m, yang hampir sama seluruhnya mempunyai kemiringan ke selatan.
Stratigrafi daerah ini mulai dari tua ke muda adalah sebagai berikut :
1. Formasi Kebo Butak
Formasi ini secara umum terdiri dari konglomerat, batupasir, batulempung,
yang menampakan pengendapan arus turbid maupun pengendapan gaya
berat lainnya. Di bagian bawah yang oleh Bothe disebut sebagai Kebo Beds,
terdiri dari perselingan antara batupasir, batulanau, dan batulempung yang
khas menunjuka struktur turbidit dengan perselingan batupasir
konglomeratan yang mengandung klastika lempung. Bagian bawah diterobos
oleh sill batuan beku.
Bagian atas dari formasi ini disebut sebagai anggota Butak, yang tersusun
oleh batupasirkonglomeratan yang bergradasi menjadi lempung atau lanau.
Ketebalan dari formasi ini kurang lebih 800 m. Batuan yang membentuk
formasi ini ditafsirkan terbentuk pada lingkungan lower submarine fan
dengan beberapa interupsi pengendapan tipe mid fan yang terbentuk pada
akhir oligosen.
2. Formasi Semilir
Formasi ini tersusun oleh batupasir dan batulanau yang bersifat tufaan,
ringan dan kadang-kadang dijumpai breksi. Fragmen yang membentuk
breksi maupun batupasir pada umumnya berupa fragmen batuapung yang
xii
bersifat asam. Di lapangan menunjukkan perlapisan yang baik. Umur dari
formasi ini diperkirakan awal meosen berdasarkan terdapatnya
Globigerinoides Primordius pada bagian yang bersifat lempungan di daerah
Piyungan. Formasi semilir menumpang secara tidak selaras pada formasi
Kebo-Butak.
3. Formasi Nglanggran
Formasi ini dicirikan oleh penyusun utama terdiri dari breksi dengan
material-material penyusunnya berupa material vulkanik, menunjukkan
perlapisan yang kurang baik dengan ketebalan yang cukup tebal. Breksinya
hampir seluruhnya tersusun oleh bongkahan-bongkahan lava andesit dan
juga bom andesit. Di antara massa dasar penyusun breksi tersebut ditemukan
sisipan lava yang sebagian besar telah mengalami breksiasi. Kontaknya
dengan formasi Semilir yang berada I bawahnya berupa kontak taham
sehingga sering dianggap tidak selaras dengan formasi semilir. Namun,
kontak ini dapat terjadi akibat berubahnya mekanisme pengendapan dari
energi rendah atau dari energi yang tinggi tanpa harus melalui waktu yang
lama. Umur dari formasi ini ditafsirkan sebagai hasil dapi pengendapan
aliran rombakan yang berasal dari gunung api bawah laut dan proses
pengedapannya masih berlangsung di lingkungan laut dalam serta
berlangsung dengan cepat pada masa meosen. Perubahan litologi penyusun
formasi Nglanggran menjadi formasi Sambipitu-Oyo ditandai dengan
perubahan secars bertahap dari breksi gunung api yang mengalami gradasi
bongkah sampai pasir menjadi perulangan gradasi batupasir serpih sehingga
terbentuk hubungan selaras atau menjari antar kedua formasi tersebut.
4. Formasi Sambipitu-Formasi Oyo
Ciri umum dari formasi Sambipitu-Oyo adalah perulangan batupasir dan
serpih. Batupasir hampir seluruhnya terdiri dari jenis graywacke. Batuan ini
berwarna abu-abu kehitam-hitaman dan kadang-kadang bersifat gampingan.
Pada setiap perlapisannya batupasir ini secara bertahap berubah menjadi
serpih berwarna abu-abu dengan bidang dasar umumnya mempunyai kontak
yang tegas dan bergelombang. Adanya sifat gampingan pada batupasir dan
serpih dengan kandungan foraminifera planktonik dan bentonit yang cukup
xiii
banyak memberikan indikasi lingkungan pengendapan laut. Seri graywacke
yang bergradasi menjadi serpih adalah merupakan hasil endapan arus turbid
dengan kepekatan tinggi.
Kenampakan fisik dari batas Formasi Sambipitu Oyo di lapangan terdiri
dari kenampakan menjari dan tidak selaras di beberapa tempat. Formasi
Sambipitu tersusun oleh batupasir yang bergradasi menjadi batulanau dan
batulempung. Di bagian bawah batupasir masih menunjukkan sifat volkanik,
sedangkan ke arah atas berubah menjadi batupasir bersifat gampingan.
Formasi Sambipitu berubah secara gradasional menjadi Formasi Wonosari
(anggota Oyo) seperti terlihat di Sungai Widoro. Formasi Sambipitu
terbentuk selama kala meosen.
5. Formasi Wonosari
Selaras di atas Formasi Sambipitu Oyo, terdapat Formasi Wonosari yang
terdiri dari batugamping berlapis, napal, dan batugamping terumbu. Hamper
sebagian besar dari Formasi Wonosari membentuk morfologi kerucut karst
di kawasan Gunung Sewu. Kandungan foraminifera besar umumnya berupa
Lepidocyclina sp dan Miogypsinas sp disamping kandungan foraminifera
kecil dan Molusca.
6. Formasi Kepek
Formasi Kepek merupakan formasi sediment tersier yang termuda di
Pegunungan Selatan dan tersigkap baik di Wonosari Playen Paliyan.
Litologi berupa batugamping berlapis bergradasi menjadi napal kaya
foraminifera kecil. Formasi ini terendapkan pada lingkungan laut dalam
selama kala meosen atas.
7. Endapan Fluvio Vulkanik Yogyakarta
Produk fluvio vulkanik dari material rombakan Gunung Merapi mengisi
graben Yogyakarta dan membentuk dataran rendah fluvio volkanik dan
berasosiasi dengan endapan fluvial. Material penyusunnya berupa material
sediment lepas-lepas berukuran pasir kerakal yang terbawa aliran sungai
dari lereng merapi hasil erosi lahar maupun endapan volkanik lainnya yang
diendapkan jauh dari tubuh Gunung Merapi.
xiv
Daerah Pegunungan Selatan pernah mengalami pengangkatan sebanyak
empat kali. Pertama, berlangsung sebelum pengendapan Formasi Kebo, yaitu
pada kala eosin dengan intensitas pengangkatan lemah. Kedua, berlangsung
setelah pengendapan Formasi Butak, yaitu pada kala oligisen meosen
dengan pengangkatan tidak terlalu kuat, sehingga tidak mengganggu
perlapisan urutan batuan. Ketiga, terjadi setelah pengendapan Formasi
Sambipitu dengan formasi-formasi yang lebih muda. Pengangkatan keempat
terjadi setelah pengendapan Formasi Kepek. Pengangkatan ini memiliki
intensitas yang cukup besar yang mengakibatkan terjadi dataran.
II.3 Struktur Geologi Regional
Secara umum, pola struktur daerah Pegunungan Selatan masih
dipengaruhi oleh pola struktur regional Pulau Jawa. Pola struktur ini dilihat dari
hasil penelitian gaya berat menunjukkan arah yang paling dominan pada
Pegunungan Selatan ini adalah barat timur. Pola arah barat timur ini
diperkirakan dipengaruhi oleh pergerakan lempeng yang membentuk Pola Jawa.
Pola Jawa iu sendiri merupakan pola yang dibentuk oleh penunjaman antara
Lempeng Eurasia dan Lempeng Hindia Australia. Pola kekar yang ada di
Pegunungan Selatan menurut Sukandar Asikin (1974), polanya membentuk
sudut kurang lebih 15
0
sampai 30
0
dari gaya utama pembentuk pola struktur
regional, yaitu utara selatan.
Penyelidikan gaya berat untuk mengetahui pola struktur regional di
Pulau Jawa dan juga di Pegunungan Selatan menghasilkan suatu jalur anomaly
negatif regional yang mempunyai dimensi regional 100 km sampai 250 km di
bagian selatan Pulau Jawa, secara regional anomali gaya berat tersebut berimpit
dengan pulau-pulau di sebelah barat Sumatra dan selatan Jawa. Pulau-pulau
tersebut diperkiran merupakan trench slope break.
Daerah Pegunungan Selatan sendiri mengindikasikan pola khusus pada
penelitian gaya berat yang dilakukan sejak 1965 oleh Direktorat Geologi, yaitu
membentuk jalur anomali gaya berat selatan dengan + 90 mgal sampai + 170
mgal. Jalur ini secara khas berimpit dengan Pegunngan Selatan. Anomali positif
yang cukup tinggi yang terdapat pada bagian selatan Pulau Jawa, menurut
xv
Asikin (1974), dapat ditafsirkan sebagai suatu struktur grabben dan horst yang
sekaligus juga menunjukkan adanya gejala pengangkatan secara menerus.
xvi
BAB III
PEMBAHASAN SETIAP STASIUN PENGAMATAN
III.1 Stasiun Pengamatan 1
Lokasi pengamatan
Terletak di daerah aliran Sungai oyo, tepatnya di sebelah barat Sungai Oyo,
sekitar 100 m dari jembatan Sungai Oyo, Trukan. Di sebelah barat merupakan
dataran dan di sebelah timur merupakan perbukitan.
Foto 1. point bar dan dataran banjir di Kali Oyo
Morfologi
Merupakan lembah sungai dan merupakan perbatasan antara dua morfologi yaitu
perbukitan dan dataran yang dibatasi oleh aliran Sungai Oyo. Sungai Oyo
termasuk ke dalam stadia dewasa dan terdapat channel bar dan point bar dengan
dataran banjir yang sudah cukup meluas, bermeander, dan memiliki teras sungai
dengan arah aliran timur laut barat daya kemudian berbelok menjadi timur
barat. Hal tersebut dipengaruhi oleh pola kelurusan barat timur sehinga arah
aliran sungai bisa berbelok. Proses yang berkembang pada daerah ini adalah
erosi, transportasi dan deposisi. Erosi lebih dominan lateral daripada vertical,
transportasi oleh arus sungai dengan arus traksi melalui bed load dan suspended
load, dan mendeposisikan pasir sampai berangkal. Perbukitan memiliki slope
36 sehingga termasuk perbukitan bergelombang lemah. Stadia daerah ini adalah
dewasa.
xvii
Litologi
Pada tubuh sungai : material lepas lepas berukuran pasir sampai berangkal
antara lain andesit, batugamping, dan batupasir berbentuk subangular rounded.
Pada bukit : merupakan breksi dengan fragmen andesit, fenokris berupa feldspar
dan massa dasar mineral mafik berukuran halus.
Struktur geologi
Pola kelurusan barat timur searah dengan arah pembelokan aliran sungai
Potensi positif dan negatif
Potensi positif : sawah, perkebunan, pemancingan
Potensi negatif : banjir
Sketsa
III.2 Stasiun Pengamatan 2
Lokasi pengamatan
Berada di salah satu bukit pada daerah Panggang, Imogiri
Morfologi
Pada stasiun pengamatan ini terlihat kerucut karst dan kerucut karst tersebut
berbaris membentuk pola pelurusan. Hal tersebut sesuai dengan syarat
pembentukan morfologi karst, yaitu selain litologinya batuan mudah larut seperti
batugamping, harus ada kekar untuk membantu pelarutan litologi tersebut. Pada
xviii
saat hujan akan terlihat pola penyaluran multi basinal. Stadia daerah dewasa
karena sudah cukup intensif pelarutan batugamping di daerah ini sehingga
membentuk kerucut kerucut karst.
Foto 2. Barisan kerucut karst yang memanjang
Foto 3. Barisan kerucut karst yang memanjang
Litologi
Batu gamping berukuran berangkal sampai bongkah, berwrna abu abu,
tersusun oleh mineral karbonatan, massif.
Struktur geologi
Pola kelurusan N90E dan N110E berhubungan dengan arah terbentuknya
kerucut karst yang berbaris.
Potensi positif dan negatif
Potensi positif : perkebunan
Potensi negatif : gerakan massa
xix
Sketsa
III.3 Stasiun Pengamatan 3
Lokasi pengamatan
Terletak di sebuah tinggian di dekat Pantai Parangtritis dibatasi di sebelah utara
oleh tinggian, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur perbukitan dan di
sebelah barat merupakan dataran dan pantai.
Foto 4. Interaksi antara 5 bentang alam di Stasiun Pengamatan 3
xx
Morfologi
Morfologi yang ditemui pada daerah ini termasuk bentang alam fluvial,
struktural, karst, eolian serta pesisir dan pantai. Proses fluviatil di daerah ini
tidak menghasilkan bentukan delta dikarenakan pengaruh ombak yang cukup
besar dikarenakan Samudera Hindia merupakan laut lepas, namun terlihat
morfologi spit pada mulut sungai dikarenakan aktifitas ombak dan suplai
sedimen yang cukup banyak. Pada stasiun pengamatan ini juga dapat dilihat
gawir sesar yang merupakan pertanda akan adanya sesar, selain itu juga terdapat
perbedaan tinggi yang sangat mencolok. Untuk morfologi karst, walaupun
tinggian tinggian di daerah ini tersusun oleh batugamping, tidak terbentuk
bentukan khas dari morfologi karst, mungkin dikarenakan adanya struktur yang
sangat besar. Dari kejauhan terkihat gumuk pasir, namun hanya kecil
pelamparannya dibandingkan di Pantai Parangkusumo. Stadia daerah adalah
dewasa.
Litologi
Batu gamping berukuran berangkal sampai bongkah, berwrna abu abu,
tersusun oleh mineral karbonatan, massif.
Struktur geologi
Pola kelurusan yang searah dengan gawir sesar pada sebuah tinggian.
Potensi positif dan negatif
Potensi positif : pariwisata
Potensi negatif : tsunami
Sketsa
xxi
III.4 Stasiun Pengamatan 4
Lokasi pengamatan
Gumuk pasir di Pantai Parangkusumo
Morfologi
Merupakan bentang alam eolian dan terdapat gumuk pasir dengan struktur ripple
marks. Semakin ke utara, gumuk pasir semakin tinggi dan dibatasi oleh tinggian
dengan litologi batugamping dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra
Hindia. Arah angin pada stasiun pengamatan ini cenderung ke selatan utara dan
ripple marks timur barat sehingga ripple marks di tempat ini merupakan jenis
transversal.
Foto 5. Ripple marks di satsiun pengamatan 4
xxii
Foto 6. Salah satu bentukan dune di Stasiun Pengamatan 4
Litologi
Berupa material sediment berukuran pasir (1/16 2 mm) berwarna coklat
kehitaman. Material pasir tersebut mengandung magnetit, hematite, feldspar dan
kuarsa serta litik subangular rounded.
Struktur geologi
Pelurusan pada tinggian di sebelah utara yang membatasi daerah gumuk pasir.
Kedudukan ripple marks N50E/14.
Hasil pengukuran backslope dan foreslope pada ripple marks adalah sebagai
berikut :
Backslope 7 cm 10 cm 3 cm 25 cm 9 cm 22 cm
Foreslope 5 cm 3 cm 4 cm 2 cm 5 cm 4,5 cm
Potensi positif dan negative
Potensi positif : pariwisata
Potensi negative : tsunami
xxiii
Sketsa
xxiv
BAB IV
KESIMPULAN
1. Pada stasiun pengamatan 1 dapat dilihat bahwa pola pelurusan dapat menjadi
tanda adanya struktur dikarenakan searah dengan pembelokan arah aliran
sungai dan pemisahan satuan morfologi.
2. Pembentukan morfologi karst di stasiun pengamatan 2 telah terjadi dalam
waktu yang lama dan terpengaruh juga oleh kontrol strukur. Bentukan
morfologi yang terlihat adalah barisan kerucut karst yang memanjang timur
laut barat daya.
3. Stasiun pengamatan 3 merupakan interaksi antara 5 bentang alam, yaitu
bentang alam struktural, fluvial, eolian, karst dan pesisir. Terlihat beberapa
bentukan morfologi seperti spit, lagoon dan dune. Selain itu terlihat gawir
sesar yang sangat besar.
4. Stasiun pengamatan 4 merupakan bentang alam eolian karena muncul
beberapa kenampakan seperti transversal dune dan parabolic
dune.Pembentukannya dipengaruhi oleh vegetasi, suplai sedimen dan
kekuatan hembusan angin.
xxv
DAFTAR PUSTAKA
Flint, R.F. dan Skinner, B.J., 1977, Physical Geology, 2 ed, John Willey & Sons, New
York, p. 594.
Pannekoek, A.J. Outline of the Geomorphology of Java. Reprint from Tijdschrift Van
Het Koninlijk Nederlandsch Aadrijksundig Gootschap. Col LXVI, part 3. E.J.,
Brill, Leiden.
Thornbury, W.D. , 1969, Principles of Geomorphology 2
nd
ed. , John Wiley and
Sons, Inc. , New York.
Twidale, C.R., 1978. Analysis of Landforms. John Willeys and Sons : Brisbane.
Van Bemmelen, R.W..1970, The Geology of Indonesia. Vol. I A, General geology of
Indonesia and Adjacent Archipelagoes, 2 nd. Martinus Njhoff. The Haque.
Staf Asisten,1999,Panduan Praktikum Geomorfologi,Laboratorium Geologi Dinamik
Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta.
Anda mungkin juga menyukai
- laporan fieldtrip complit mikropalDokumen19 halamanlaporan fieldtrip complit mikropalMoch Hasmannoor RBelum ada peringkat
- Geologi Struktur CinamboDokumen13 halamanGeologi Struktur CinamboDavid H. Butar ButarBelum ada peringkat
- LAPORAN KRISMIN (Repaired)Dokumen36 halamanLAPORAN KRISMIN (Repaired)Moch Hasmannoor RBelum ada peringkat
- Field Trip GeostrukDokumen17 halamanField Trip GeostrukFAISAL FADILAHBelum ada peringkat
- Fieldtrip GeodasDokumen26 halamanFieldtrip GeodasMoch Hasmannoor RBelum ada peringkat
- LPDokumen62 halamanLPLuth Alfaridzi SammanaBelum ada peringkat
- Geo RekDokumen25 halamanGeo RekadelarisaBelum ada peringkat
- Fieldtrip Geologi StruktursDokumen28 halamanFieldtrip Geologi StruktursMulyawan WIdiasmanBelum ada peringkat
- Laporan Bab 1-3 Ruzik Wirdando Musfa D061191012Dokumen25 halamanLaporan Bab 1-3 Ruzik Wirdando Musfa D061191012Ruzik WirdandoBelum ada peringkat
- Bab 1 TaDokumen7 halamanBab 1 TaRio Aji PangestuBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan Laporan PemetaanDokumen8 halamanBab I Pendahuluan Laporan PemetaanFrans Edward RicardoBelum ada peringkat
- Field Trip GeostrukDokumen17 halamanField Trip GeostruksugiartossBelum ada peringkat
- BAB II GEOLOGI EKSPLORASI-1 RevisiDokumen18 halamanBAB II GEOLOGI EKSPLORASI-1 Revisijusta ramlanBelum ada peringkat
- Proposal Alf Utk LaporanDokumen29 halamanProposal Alf Utk LaporanAlfa DarojatinBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum GeohidrologiDokumen28 halamanLaporan Praktikum GeohidrologiAchmad Noviari AkbarBelum ada peringkat
- Laporan Kuliah Lapangan FixDokumen26 halamanLaporan Kuliah Lapangan FixBagastio ラマダーンBelum ada peringkat
- Laporan MakroDokumen15 halamanLaporan MakroMaya Siti NurrahmahBelum ada peringkat
- Khoirunnisa Hanifah Salma Nabila (Desain Survey)Dokumen24 halamanKhoirunnisa Hanifah Salma Nabila (Desain Survey)belanabilaBelum ada peringkat
- Format Proposal PKM PNBP UNJA 2021Dokumen21 halamanFormat Proposal PKM PNBP UNJA 2021Lucy WulandariBelum ada peringkat
- Laporan Pengenalan Pengukuran Statigrafi - Kelompok 5ADokumen21 halamanLaporan Pengenalan Pengukuran Statigrafi - Kelompok 5AMUHAMMAD DAFFABelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen6 halamanBab 1Be ClintonBelum ada peringkat
- Kuat Mental Vol 2Dokumen22 halamanKuat Mental Vol 2Fakhri Anwar PutraBelum ada peringkat
- Bab IDokumen6 halamanBab IFajri Zharfan AkbarBelum ada peringkat
- Laporan Fieldtrip PetrologiDokumen26 halamanLaporan Fieldtrip PetrologiFahmi A MBelum ada peringkat
- Depan Revisi1Dokumen13 halamanDepan Revisi1Alfa DarojatinBelum ada peringkat
- Laporan PLG BismillahDokumen28 halamanLaporan PLG BismillahElisa AnanditaBelum ada peringkat
- Laporan KrisminDokumen21 halamanLaporan Krisminardiansyah rezaBelum ada peringkat
- Geologi RajawanaDokumen13 halamanGeologi RajawanaLisa Aprilia AprisaBelum ada peringkat
- Geomorf Karst FluvialDokumen19 halamanGeomorf Karst Fluvialpuspo soputanBelum ada peringkat
- BAB 1.docx (99%)Dokumen6 halamanBAB 1.docx (99%)Sewa Proyektor Jogja Harga NegoBelum ada peringkat
- 3 Bab I Pendahuluan Pemetaan Daerah BengkuluDokumen12 halaman3 Bab I Pendahuluan Pemetaan Daerah BengkuluKarmilana MilaBelum ada peringkat
- Laporan KrisminDokumen36 halamanLaporan KrisminRaja SusatioBelum ada peringkat
- Laporan Lapangan Geologi Struktur Daerah Lumpue Kotamadya Pare-Pare Sulsel IndoskripsiDokumen19 halamanLaporan Lapangan Geologi Struktur Daerah Lumpue Kotamadya Pare-Pare Sulsel IndoskripsiYusuf RudyantoBelum ada peringkat
- Laporan Hasil Field TripDokumen14 halamanLaporan Hasil Field TripLia FItria RahmatillahBelum ada peringkat
- Geologi RegionalDokumen35 halamanGeologi RegionalAhmad Rifai Fachruddin100% (2)
- Laporan Stratigrafi 2wDokumen17 halamanLaporan Stratigrafi 2wSabarBelum ada peringkat
- LAPORAN EKSKURSI LAPANGAN SEDIMENTOLOGI REza (Repaired)Dokumen19 halamanLAPORAN EKSKURSI LAPANGAN SEDIMENTOLOGI REza (Repaired)Adsis SetiadiBelum ada peringkat
- #2 MAKALAH PENTINGNYA PEMETAAN GEOLOGI UNTUK PERENCANAAN BENDUNGAN Dan EMBUNGDokumen13 halaman#2 MAKALAH PENTINGNYA PEMETAAN GEOLOGI UNTUK PERENCANAAN BENDUNGAN Dan EMBUNGPaska SorminBelum ada peringkat
- Laporan KL 2Dokumen20 halamanLaporan KL 2Andreas TambunanBelum ada peringkat
- Laporan Geologi StrukturDokumen34 halamanLaporan Geologi StrukturMulyawan WIdiasmanBelum ada peringkat
- LAPORAN FT GEODAS - Bill Jhon-2Dokumen45 halamanLAPORAN FT GEODAS - Bill Jhon-2Muh Syukur DamrisBelum ada peringkat
- 2019 1 1 34201 471413015 Bab1 09102019101622 PDFDokumen10 halaman2019 1 1 34201 471413015 Bab1 09102019101622 PDFFerdi YuyunBelum ada peringkat
- Kata Pengantar EodasDokumen7 halamanKata Pengantar Eodasfarhan FadllurahmanBelum ada peringkat
- Kuliah Lapangan Geologi DasarDokumen6 halamanKuliah Lapangan Geologi DasarSetho Linggi Allo0% (1)
- Laporan Pengantar GeofisikaDokumen12 halamanLaporan Pengantar GeofisikaMiliyanti Putri A. MansurBelum ada peringkat
- Laporan Ekskursi PatarDokumen26 halamanLaporan Ekskursi PatarNaibaho Tar100% (2)
- Laporan StratigrafiDokumen20 halamanLaporan Stratigrafiayib.smartBelum ada peringkat
- Makalah Laporan Praktikum GeomorfologiDokumen17 halamanMakalah Laporan Praktikum GeomorfologiChandy'Akbar Bigman Fortiuz100% (2)
- 8 - Bab I Pendahuluan FixDokumen11 halaman8 - Bab I Pendahuluan FixSukandarBelum ada peringkat
- Bhima PunyaDokumen49 halamanBhima PunyaAbrar RamadhanBelum ada peringkat
- Proposal KarangsambungDokumen26 halamanProposal KarangsambungMuhammad Lukman BaihaqiBelum ada peringkat
- 2016 1 2 34201 471409002 Bab1 23112016115501Dokumen9 halaman2016 1 2 34201 471409002 Bab1 23112016115501Ferdino Diwa YanwarBelum ada peringkat
- Laporan Geomor Field TripDokumen22 halamanLaporan Geomor Field TripAngelino Reynold Engelbertho NajaBelum ada peringkat
- Final Laporan KarsamDokumen78 halamanFinal Laporan Karsamputri aprilliaBelum ada peringkat
- Tugas Endapan-Kelompok 2-2Dokumen21 halamanTugas Endapan-Kelompok 2-2Sartia GeologiBelum ada peringkat
- Proposal Skripsi OkDokumen27 halamanProposal Skripsi OkYollyver KotarumalosBelum ada peringkat
- (On Going) Laporan Eks Profil Zaini BaruDokumen52 halaman(On Going) Laporan Eks Profil Zaini BaruNuraida LubisBelum ada peringkat
- Jurnal 1Dokumen14 halamanJurnal 1Yusup Maulana YuliansyahBelum ada peringkat
- Vektor Dimensi 3Dokumen5 halamanVektor Dimensi 3Setya100% (1)
- JURNALDokumen9 halamanJURNALSetyaBelum ada peringkat
- ADC UbbenSesetDokumen8 halamanADC UbbenSesetSetyaBelum ada peringkat
- Metamorfisme Adalah Proses Yang Menyebabkan Perubahan Tekstur Perubahan Mineralogi Atau Keduanya Yang Terjadi Pada Batuan Dengan Limit Bawahnya Diagenesis Dan Pelapukan Dan Limit Atasnya Adalah MeltingDokumen2 halamanMetamorfisme Adalah Proses Yang Menyebabkan Perubahan Tekstur Perubahan Mineralogi Atau Keduanya Yang Terjadi Pada Batuan Dengan Limit Bawahnya Diagenesis Dan Pelapukan Dan Limit Atasnya Adalah MeltingSetyaBelum ada peringkat
- Kelompok PiroxenoidDokumen2 halamanKelompok PiroxenoidSetyaBelum ada peringkat