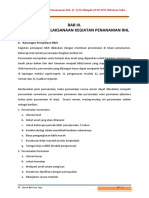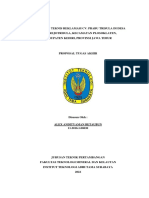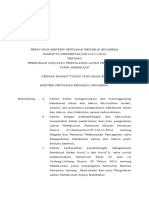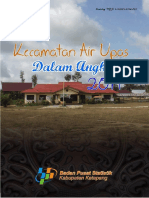Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Diunggah oleh
Magfirah IsmayantiHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Diunggah oleh
Magfirah IsmayantiHak Cipta:
Format Tersedia
Pemetaan Daerah Rawan
Kebakaran
Solichin
Laut Tarigan
Paul Kimman
Bona Firman
Radian Bagyono
Manual
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Solichin
Laut Tarigan
Paul Kimman
Bona Firman
Radian Bagyono
2007
South Sumatra Forest Fire Management Project
Manual ini disertai CD
Untuk memperoleh buku ini atau informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
South Sumatra Forest Fire Management Project
Jl. Jendral Sudirman Km 3,5 No 2837 Palembang 30129
Telp/fax: 0711-377821 / 0711-353 176
ssffmp.eu@telkom.net
http://www.ssffmp.or.id
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kol. H. Burlian Km 6.5 Punti Kayu Palembang
Telp/fax: 0711-411476 / 411479
http://www.dishutsumsel.go.id
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II
Jl. Kol. H. Burlian Km 6 PO Box 95 Palembang
Telp/fax: 0711-410819 / 418219
bpkh2_plb@yahoo.com
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Kata Pengantar
South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) merupakan
proyek kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Uni Eropa yang bertujuan untuk mengurangi dampak akibat
kebakaran hutan dan lahan. Salah satu komponen di dalam proyek
SSFFMP adalah Sistem Informasi Kebakaran yang berperan di dalam
mendukung dan mengembangkan kapasitas instansi terkait di dalam
pengumpulan, pengolahan serta penyebaran informasi terkait dengan
kebakaran.
Pengembangan kapasitas atau kemampuan pihak terkait di dalam
menjalankan operasi-operasi pengelolaan kebakaran hutan merupakan hal
penting yang dilakukan oleh SSFFMP. Selain kegiatan pengembangan
organisasi, pelatihan, dan penyediaan alat, penyusunan prosedur operasi
atau panduan pelaksanaan juga sangat diperlukan untuk menjamin
keberlangsungan kegiatan. Karenanya penyusunan manual ini diharapkan
dapat dimanfaatkan bagi instansi terkait di dalam pemantapan kapasitas
pengendalian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di dalam
pengembangan sistem informasi kebakaran.
Diharapkan buku panduan ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait serta
memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pengendalian kebakaran
hutan dan lahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.
EU Co-Director
Dr. Karl-Heinz Steinmann
National Co-Director
Dr. Dodi Supriadi
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Daftar Isi
Kata Pengantar............................................................................................i
Daftar Isi ..................................................................................................... ii
1. Pendahuluan...........................................................................................1
A. Latar Belakang ....................................................................................1
B. Tujuan .................................................................................................2
C. Penggunaan Manual ...........................................................................2
2. Analisa Penyebab Kebakaran .................................................................3
A. Pemicu Kebakaran ..............................................................................3
B. Kondisi Pendukung..............................................................................5
3. Metodologi ..............................................................................................8
A. Metode ................................................................................................8
B. Data yang Diperlukan ..........................................................................9
C. Hardware dan Software.....................................................................11
4. Penyiapan Data ....................................................................................12
A. Memulai ArcView dan ModelBuilder ..................................................12
B. Konversi Data Penutupan Lahan (Shapefile ke GRID) ......................13
C. Klasifikasi Ulang (Reclass) Data Ketinggian ......................................18
D. Memasukan Data Penyebaran Lahan Gambut..................................24
5. Pembobotan dan Penilaian ( Weighting/Scoring) ..................................26
A. Memulai Proses Weighted Overlay....................................................26
B. Pembobotan dan Penilaian Peta Ketinggian......................................30
C. Pembobotan dan Penilaian Peta Tanah ............................................31
6. Menyimpan dan Menjalankan Model.....................................................37
A. Menyimpan Project ModelBuilder .....................................................37
B. Menjalankan Model ...........................................................................37
7. Hasil dan Pembahasan .........................................................................40
Bahan Bacaan ..........................................................................................44
Lampiran...................................................................................................45
1. Sebaran Hotspot Berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2006 ..............45
2. Sebaran Hotspot Berdasarkan Jenis Tanah Tahun 2006...................45
3. Sebaran Hotspot Berdasarkan Ketinggian Tahun 2006 .....................46
4. Tabel penyebaran daerah rawan kebakaran di Sumatera Selatan .....47
ii
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
1. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Kesadaran akan perlunya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan oleh pihak pemerintah baik di pusat sudah lebih tinggi
dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari cukup
banyaknya upaya pengalokasian sumberdaya pemadaman di provinsiprovinsi rawan kebakaran. Anggaran untuk kegiatan pencegahan dan
pemadaman juga banyak dianggarkan oleh pemerintah daerah.
Hanya saja, kegiatan perencanaan untuk pencegahan dan pemadaman
kebakaran memerlukan informasi yang akurat, aktual serta mudah
dipahami oleh pengambil keputusan. Seringkali informasi mengenai
daerah rawan kebakaran tidak disajikan secara jelas, serta tidak
didasari atas metode pengolahan yang secara metodologi tidak
konsisten, sehingga cenderung subyektif dan tergantung dari pengolah
data.
Informasi mengenai daerah rawan kebakaran merupakan informasi
yang sangat penting dan diperlukan oleh fire manager atau pengambil
keputusan di dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Saat musim kemarau panjang, kebakaran besar bisa terjadi di areal
yang luas dan sulit dijangkau. Keterbatasan sumberdaya pemadaman
menjadi salah satu kendala yang paling sering dihadapi di lapangan.
Karena itu kegiatan pengendalian perlu difokuskan ke wilayah-wilayah
yang rawan kebakaran.
Peta daerah rawan kebakaran karenanya berperan penting di dalam
membantu fire manager di dalam mengambil keputusan tersebut.
Penyajian secara spasial akan lebih membantu memberikan gambaran
1
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
yang jelas dan akurat mengenai lokasi, jarak serta aksesibilitas antara
lokasi daerah rawan dengan sumber daya pemadaman yang ada di
lapangan.
Permasalahan selanjutnya muncul saat peta tersebut tidak akurat lagi,
akibat adanya perubahan dari faktor-faktor yang digunakan untuk peta
rawan kebakaran tersebut. Sebagai contoh, penutupan lahan cederung
akan cepat berubah sehingga akan memiliki karakteristik yang berbeda
terhadap perilaku kebakaran. Untuk itu diperlukan kemampuan bagi
operator Sistem Informasi Kebakaran untuk melakukan pemutakhiran
(updating) peta sesuai dengan perubahan yang terjadi, sehingga
menjadi lebih akurat.
B. Tujuan
Manual ini disusun untuk mendokumentasikan prosedur pemetaan
daerah rawan kebakaran yang telah dibuat oleh SSFFMP pada tahun
2005 dan 2007. Pendokumentasian prosedur atau metodologi ini
diperlukan agar upaya perbaikan data dapat dilakukan, atau paling tidak
metode pemetaan tersebut dapat diketahui dan dipahami.
C. Penggunaan Manual
Manual ini disertai CD yang berisi data-data yang diperlukan untuk
penyusunan peta rawan kebakaran. Dalam manual akan dijelaskan
langkah-langkah untuk menyusun peta rawan kebakaran menggunakan
extensi ModelBuilder. Langkah-langkah tersebut dijelaskan secara
lengkap dan sistematis, sehingga pengguna dapat lebih mudah
mengikutinya. Namun terdapat istilah atau langkah standar yang tidak
dijelaskan, karenanya diperlukan pemahaman dasar tentang aplikasi
dalam Windows ,GIS serta software ArcView GIS 3.x sebelumnya.
2
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
2. Analisa Penyebab Kebakaran
A. Pemicu Kebakaran
Secara umum faktor utama terjadinya kebakaran bisa digolongkan menjadi
2 kelompok, yaitu pemicu kebakaran dan kondisi pendukung. Pemicu
kebakaran merupakan faktor yang secara langsung mempengaruhi
terjadinya penyulutan api. Aktifitas manusia merupakan porsi terbesar di
dalam penyulutan api, dibandingkan secara alami. Kebakaran yang berasal
dari batubara yang terbakar, halilintar ataupun gesekan ranting kering,
sangatlah jarang terjadi, terlebih di Sumatera Selatan. Karenanya
penyulutan oleh alam cenderung dapat diabaikan.
Penyulutan api oleh manusia juga dikelompokkan menjadi 2 komponen
yaitu kesengajaan dan kecerobohan. Walaupun seringkali kebakaran besar
diawali dari upaya yang disengaja dan akibat ketidakpahaman pembakar
mengenai kondisi yang ada, sehingga menjadi kecerobohan yang
menyebabkan kebakaran merambat ke tempat lain.
Motivasi dari pembakaran/kebakaran yang disengaja dan biasa dijumpai di
Sumatera Selatan meliputi beberapa hal, antara lain:
1. Penyiapan lahan baik oleh perusahaan maupun oleh masyarakat. Ini
merupakan kasus terbanyak yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.
Sejak berkembangnya budidaya kelapa sawit, kebutuhan akan lahan
yang sesuai dan menguntungkan sangatlah tinggi. Seringkali lahan
yang ditutupi hutan menjadi incaran bagi investasi tersebut. Tiga hal
yang mendasari pemikiran tersebut, yaitu: (1) biasanya lahan berhutan
relatif jauh dari masyarakat sehingga memiliki resiko konflik lahan yang
rendah, (2) dengan adanya penutupan hutan, unsur hara yang
dikandung tanah lapisan atasnya sangatlah subur,dan (3) potensi kayu
yang dapat ditebang juga sangat menarik untuk dijadikan keuntungan
3
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
tambahan sebelum pemanenan hasil penanaman. Penyiapan lahan
oleh masyarakat cenderung lebih bijaksana, terkendali serta berdampak
kecil. Selain itu penyiapan lahan dengan membakar dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan primer masyarakat kecil. Namun, terlepas dari
kontroversi penggunaan api oleh masyarakat, ada tiga hal yang perlu
disikapi secara tegas, pertama pembakaran di lahan gambut walaupun
oleh masyarakat, termasuk sonor, harus dihindari mengingat sulitnya
upaya pembakaran terkendali di lahan gambut, kedua pengaturan
jadwal pembakaran perlu dilakukan agar tetap berdampak kecil, ketiga
perlunya
mengantisipasi
pembakaran
oleh
pelaku
yang
mengatasnamakan masyarakat kecil yang dibayar untuk membakar
lahan milik perusahaan atau juragan pemilik lahan. Hal yang demikian
juga mulai banyak terjadi.
2. Pembukaan akses untuk mencari kayu, ikan ataupun berburu. Di areal
hutan gambut yang telah terdegradasi seperti di Padang Sugihan dan
Padang Sugihan OKI, pencari kayu mulai mencari kayu tenggelam yang
sudah terendam beberapa tahun sebelumnya, baik akibat roboh secara
alami ataupun sisa bekas tebangan yang tidak termanfaatkan. Karena
berada dalam kondisi anaerob akibat terendam air, maka tidak terjadi
pelapukan terhadap kayu tenggelam tersebut. Selain itu, di Kecamatan
Bayung Lencir juga banyak dijumpai masyarakat yang memanfaatkan
kayu gelam (Melaleuca sp) di lahan gambut sekunder untuk dijual
sebagai bahan bangunan. Untuk keperluan membuka akses yang lebih
baik, pembakaran dilakukan untuk di lahan-lahan gambut tersebut.
3. Berburu dan mencari ikan merupakan aktifitas masyarakat yang masih
bisa dijumpai di sekitar kawasan hutan. Penggunaan api sebenarnya
tidak secara langsung digunakan untuk berburu, melainkan untuk
membakar semak atau rumput sehingga memungkinkan munculnya
tunas-tunas atau rumput muda yang disukai oleh hewan-hewan
4
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
ungulata, seperti rusa dan kijang. Beberapa literatur menyatakan bahwa
pembakaran semak di sekitar rawa juga dilakukan oleh pencari ikan,
dan diperkirakan juga untuk menarik perhatian ikan akibat abu hasil
pembakaran. Namun, di wilayah pesisir Sumatera Selatan, sebagian
besar
pencari
ikan
melakukan pembakaran semak
agar
lebih
memudahkan menemukan ceruk-ceruk tempat ikan berkumpul di musim
kemarau.
4. Spekulan tanah, konflik lahan dan arson juga merupakan motivasi
pembakaran yang dilakukan manusia. Tanah yang cenderung bersih
dari semak belukar cenderung dihargai lebih tinggi sekaligus sebagai
penanda bahwa lahan tersebut ada pemiliknya. Spekulasi tanah
tersebut tidak hanya terjadi di lahan mineral, namun sudah merambah
hingga ke lahan gambut. Konflik lahan dan arson memang jarang
dijumpai atau sulit dibuktikan sebagai penyebab kebakaran. Arson
merupakan orang yang dengan sengaja melakukan pembakaran untuk
kepentingan dirinya sendiri, baik karena hobi atau kesenangan belaka.
B. Kondisi Pendukung
Faktor kedua penyebab kebakaran adalah Kondisi Pendukung yang juga
dipengaruhi oleh alam (iklim) dan juga manusia. Kemarau dan kekeringan
yang disebabkan oleh adanya fluktuasi iklim sebenarnya sudah lama
terjadi, namun kebakaran besar di daerah tropis tidak banyak tercatat oleh
para peneliti sebelum tahun 70an. Kejadian kebakaran hutan tropis mulai
sering muncul setelah tahun 1982/1983. Hal ini disebabkan adanya
perubahan vegetasi dan tapak yang sangat drastis serta pengaruh sosial
ekonomi masyarakat.
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Perubahan Tutupan Lahan
Perubahan tapak yang dimaksud meliputi perubahan tutupan lahan dan
perubahan hodrologi khususnya di lahan gambut. Indonesia yang dulunya
sebagian besar merupakan hutan hujan tropis primer menjadi hutan bekas
tebangan atau terdegradasi akibat pengusahaan hutan dan exploitasi kayu
secara besar-besaran sejak awal tahun 70an. Hilangnya tajuk atau kanopi
pohon besar menyebabkan kondisi hutan menjadi lebih terbuka terhadap
sinar matahari dan iklim mikro menjadi lebih kering. Limbah bekas
tebangan juga seringkali menjadi bahan bakar yang sangat potensial
meningkatkan intensitas kebakaran. Di hutan yang terdegradasi menjadi
semak belukar, bahkan menjadi lebih rawan lagi terhadap kebakaran,
karena mudahnya penyulutan dan penyebaran api.
Perubahan Hidrologi
Perubahan hidrologi khususnya di lahan gambut juga merupakan kondisi
yang sangat mendukung terjadinya kebakaran. Akibat terbatasnya lahan
untuk pertanian, perkebunan dan hutan tanaman, banyak lahan gambut
dalam yang dikeringkan (drained) dengan membuat kanal-kanal yang
membelah kubah gambut. Selain mengeringkan lahan gambut, kanal juga
berfungsi sebagai aksesibilitas bagi masyarakat untuk masuk ke lebih jauh
ke dalam areal lahan gambut untuk melakukan aktifitas yang seringkali
juga menimbulkan kebakaran.
Pengaruh Sosial Ekonomi dan Budaya
Sebagai salah satu faktor utama di dalam penyebab kebakaran, perilaku
manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi serta budaya.
Faktor kemiskinan sering diusung sebagai faktor utama yang mengarahkan
perilaku membakar hutan. Karenanya banyak pendekatan pencegahan
kebakaran dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
Namun demikian, budaya penggunaan api sebenarnya juga sudah lama
diterapkan oleh banyak masyarakat tradisional yang hidup di sekitar hutan
6
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
atau peladang berpindah. Bahkan hukum dan aturan adat juga telah dibuat
sehingga pembakaran yang mereka lakukan memiliki dampak yang kecil
terhadap masyarakat dan lingkungan.
Di banyak tempat di Sumatra dan Kalimantan, dimana lahan pertanian
menjadi lebih terbatas, masyarakat baik lokal maupun pendatang juga
mulai merambah areal lahan gambut, baik untuk mencari kayu, berburu,
mencari ikan dan bahkan pertanian. Pertanian di lahan gambut bukanlah
tradisi dan budaya masyarakat tradisional di Sumatra dan Kalimantan.
Karena itu upaya pencegahan dan penyadaran akan bahaya kebakaran
hutan dan lahan perlu difokuskan di wilayah ini.
Selain itu budaya pemahaman dampak akibat asap juga masih sangat
rendah. Masyarakat seringkali tidak peduli dengan dampak pembakaran
yang mereka lakukan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Contoh
kecil yang sering kita lihat adalah, masih banyaknya masyarakat di kota
yang masih membakar sampahnya, apalagi masyarakat di daerah
pedesaan yang tidak memiliki akses dan teknologi untuk membersihkan
lahan secara mekanis. Akibatnya, undang-undang dan peraturan yang
melarang masyarakat melakukan pembakaran, mendapat resistensi di
dalam penerapannya.
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
3. Metodologi
Tidak ada tekhnologi lain kecuali GIS (Geographic Information System)
yang mampu melakukan visualisasi secara efektif mengenai kondisi
geografis yang akurat, kejadian bencana kebakaran, ataupun perkiraan
ancaman kebakaran yang yang akan terjadi. Informasi spasial tersebut
akan sangat membantu fire manager di dalam melakukan identifikasi dan
perencanaan, pencegahan, persiapan, respon serta restorasi (Greene,
2002).
A. Metode
Peta rawan kebakaran merupakan model spasial yang digunakan untuk
merepresentasikan kondisi di lapangan terkait dengan resiko terjadinya
kebakaran hutan dan lahan. Model ini dibuat menggunakan aplikasi GIS
untuk
memudahkan
proses
overlay
antar
faktor-faktor
penyebab
kebakaran. Karenanya, memahami faktor-faktor penyebab dan perilaku
kebakaran merupakan hal yang sangat utama di dalam melakukan
permodelan ini.
Mengingat keterbatasan data yang ada, pendekatan dilakukan dengan
menerapkan beberapa asumsi untuk melengkapi keterwakilan data. Model
peta rawan kebakaran ini tidak secara khusus memperhatikan potensi
penyulutan, melainkan lebih secara luas memprediksi kemungkinan
kebakaran akan terjadi serta kemungkinan intensitas serta dampak yang
ditimbulkan. Potensi penyulutan juga dikembangkan sebagai salah satu
komponen di dalam Sistem Analisa Ancaman Kebakaran (Ruecker, 2007)
yang dikembangkan oleh SSFFMP.
Rawan Kebakaran = (0.4 * [Penutupan Lahan]) + (0.3 * [Lahan Gambut]) +
(0.3 [Zona Iklim/Elevasi])
8
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Penilaian (scoring) dilakukan dengan menggunakan hasil analisa dari
penyebaran hotspot selama musim kemarau panjang, yang lebih menarik
dan relevan bagi fire manager untuk bahan pertimbangan musim
kebakaran selanjutnya. Hasil analisa frekuensi hotspot dari berbagai faktor
tersebut selanjutnya di klasifikasi ke dalam beberapa kelas nilai (misalnya
1-5). Sedangkan pembobotan (weighting) dilakukan dengan menggunakan
penilaian berdasarkan pengetahuan serta kondisi yang terjadi di lapangan
(expert judgement). Faktor dengan pengaruh lebih besar mendapatkan
pembobotan yang lebih besar dibandingkan faktor lainnya. Dalam hal ini
pengaruh penutupan lahan dianggap lebih besar dibanding faktor lainnya,
mengingat selain terkat dengan data vegetasi, penutupan lahan juga terkait
dengan penggunaan lahan, seperti pertanian, perkebunan, HTI, dll.
B. Data yang Diperlukan
Data data tematik yang diperlukan hanya terdiri dari 3 jenis data yang
relatif mudah untuk didapatkan. Yaitu peta penutupan lahan, penyebaran
gambut serta ketinggian. Data-data tersebut harus dalam format GIS serta
memiliki sistem koordinat dan proyeksi yang sama.
Penutupan Lahan yang diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit yang
dilakukan oleh BPKH II, digunakan sebagai salah satu faktor yang
terkait dengan penggunaan lahan aktual. Wilayah yang terdegradasi
dan tidak memiliki pola pemanfaatan intensif cenderung rawan
terhadap kebakaran.
Lahan Gambut merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap
intensitas dan dampak kebakaran yang terjadi. Kebakaran lahan
gambut sangat sulit dipadamkan dan menyebabkan polusi kabut
asap. Selain itu dampak emisi karbon akibat kebakaran lahan
gambut juga berpotensi terhadap peningkatan gas rumah kaca.
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Informasi penyebaran lahan gambut diperoleh dari peta unit lahan
yang dikeluarkan oleh Puslitanak.
Elevasi atau ketinggian diperoleh dari data Digital Elevation Model (DEM)
SRTM. Informasi ketinggian digunakan untuk membedakan dataran
rendah (0-25) daerah lahan kering (25 -1000 m) dan dataran tinggi
atau pegunungan (1000 3000 m). Pembagian tiga zona ketinggian
ini terkait dengan pembagian zona iklim, mengingat curah hujan di
Sumatera dipengaruhi oleh topografi yang berkisar antara 6000 mm
per tahun di wilayah barat atau sekitar bukit Barisan hingga 1500 mm
di bagian timur (Whitten et al, 2000).
Legenda
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E
Seperti terlihat pada peta di atas yang merupakan peta pembagian zona
iklim di Sumatera, untuk Provinsi Sumatera Selatan terdapat 3 zona iklim
(Whitten et al, 2000).
Batas Provinsi atau batas lainnya digunakan hanya sebagai batas areal
yang akan dianalisa, sehingga peta yang dihasilkan memiliki areal sesuai
10
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
dengan yang kita inginkan. Format batas tersebut harus dalam bentuk
ESRI GRID. Dalam hal ini digunakan batas Provinsi Sumsel.
C. Hardware dan Software
ArcView 3.x dan ArcView Spatial Analyst diperlukan untuk penyusunan
peta rawan kebakaran ini. Untuk menjalankan program ArcView 3.3 dan
Spatial Analyst dalam platform PC-Intel, paling tidak diperlukan komputer
yang memiliki sistem operasi Windows 2000 atau yang terbaru (kecuali
Windows Vista). Sehingga persyaratan minimal PC yang diperlukan antara
lain: Memory / RAM sebesar 64 MB serta free disk space sekitar 300 MB.
11
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
4. Penyiapan Data
Sebelum memulai, pastikan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan
analisa ini terpenuhi. Semua data yang digunakan dalam penjelasan ini
dapat diperoleh di dalam CD yang menyertai manual.
A. Memulai ArcView dan ModelBuilder
1. Start ArcView
Atur properties melalui menu View > Properties :
Map Unit
: Meter
Distance Unit : Kilometer
3.Klik OK
4. Aktifkan extension yang diperlukan:File > Extension > beri tanda check
pada ModelBuilder dan Spatial Analyst.
12
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
5. Klik OK
6. Masukan data ke dalam tampilan View. Contoh data dapat diperoleh di
CD yang disertakan dalam manual ini:
-Penutupan
lahan
atau
vegetasi
dalam
format
shapefile
(landcover.shp).
-Elevasi atau data ketinggian dalam format GRID yang diperoleh dari
data SRTM (elevasi).
-Data penyebaran gambut yang diperoleh dari peta Land Unit Puslitanak
dalam format GRID (tanah).
-Batas Provinsi Sumsel sebagai batas areal yang ingin dianalisa dalam
format GRID (sumsel)
8.
Mulai
ModelBuilder
dengan
mengklik
menu
Model
>
Start
ModelBuilder
Selanjutnya, jendela ModelBuilder akan muncul.
B. Konversi Data Penutupan Lahan (Shapefile ke GRID)
Untuk pengolahan data menggunakan Spatial Analyst, diperlukan data
dengan format GRID ESRI. Kecuali data elevasi dan tanah, landcover
masih dalam format shapefile.
1. Klik menu Add Process > Data Coversion > Vector to Grid
\
2. Di jendela Vector Conversion yang muncul, klik Next
13
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
3. Pilih shapefile apa yang akan di konversi
Choose the input theme : Landcover
Choose the input field
: Kelas_new
Lalu klik Next.
14
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
4. Klik Next pada jendela yang muncul.
5. Klik Next pada jendela yang muncul.
15
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
6. Tentukan layar yang akan digunakan sebagai batas analisis.
The extent of this theme : Sumsel
Lalu klik Next
7. Tentukan cell size, atau resolusi rasternya.
The cell size of this theme : Sumsel
Lalu klik Next.
16
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
8. Beri nama untuk peta dan file penutupan lahan yang akan dibuat.
Enter the theme name
: Peta Landcover
Enter the file name
: lc_grd
Lalu klik OK.
Hal yang perlu diperhatikan untuk penamaan file atau folder terkait dengan
data format GRID, adalah harus sesuai dengan kaidah penamaan DOS,
dimana hanya terbatas sebanyak 8 karakter dan tanpa spasi.
Setelah proses diatas selesai dilakukan, maka pada halaman ModelBuilder
akan muncul Flowchart / bagan alur tentang proses konversi yang kita
lakukan yaitu konversi data landcover dalam format shapefile berdasarkan
kolom Nama_Kelas menjadi Peta landcover dalam format GRID.
17
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
C. Klasifikasi Ulang (Reclass) Data Ketinggian
Pengklasifikasian ulang data ketinggian dilakukan untuk mendapatkan
layer sebaran kelas ketinggian yang terkait dengan perbedaan zonasi iklim.
Untuk wilayah Sumatera Selatan, zonasi iklim dikategorikan ke dalam 3
zona, yaitu zona dataran rendah (0 - 25 m), lahan kering (25 - 500 m) dan
pegunungan (500 3000 m).
1.Klik Add Process > Reclassification
Lalu klik Next
2. Pilih data ketinggian yang akan diklasifikasi ulang (reclass)
Choose the input theme: Ketinggian
18
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Lalu klik Next
3. Tentukan kolom input yang akan digunakan untuk proses analisa.
Choose the input field: Value
Lalu klik Next.
4. Tentukan jenis metode klasifikasi yang diinginkan.
19
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Pilih: Group value into ranges
Selanjutnya klik Next, maka akan muncul jendela di bawah ini:
Secara default akan muncul klasifikasi ketinggian seperti yang diatas.
Mengingat kita hanya membutuhkan 3 kelas ketinggian, maka kita harus
menghapus kelas-kelas yang tidak kita butuhkan, dan mengeditnya
sebagian.
20
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
5. Klik pada ujung baris yang akan dihapus sampai baris yang dipilih akan
terblok warna biru, lalu klik tombol Delete Class
Demikian seterusnya, hingga jumlah baris kelas yang ada menjadi 3
kelas ketinggian saja.
6. Isikan nilai pada kolom Class Start Value dan Class End Value sesuai
nilai pada gambar dibawah ini:
Selanjutnya klik Next.
21
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
7. Tentukan batas analisis, dengan memilih batas sumsel.
The extend of this theme: Sumsel
8. Tentukan tingkat resolusi yang diinginkan (sesuai dengan resolusi data
Sumsel).
The cell size of this theme : Sumsel
22
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Selanjutnya klik Next.
9. Beri nama layer (theme name) dan nama file (file name) sesuai dengan
gambar dibawah:
Perhatikan kembali kaidah penamaan file (file name) GRID, yang
dibatasi hanya 8 karakter dan tanpa spasi.
9. Selanjutnya klik Finish.
Sebuah bagan alur yang menggambarkan proses Reclass dari data
Elevasi menjadi sebuah Peta Ketinggian, akan muncul dan
menambahkan dari bagan alur yang sebelumnya dibuat.
23
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Proses tersebut membuat sebuah layer baru yang diberi nama Peta
Ketinggian yang hanya memiliki 3 kelas ketinggian dan mewakili 3 zona
iklim di Sumatera Selatan.
D. Memasukan Data Penyebaran Lahan Gambut
Lahan gambut merupakan falah satu faktor penting terjadinya kebakaran
besar yang mengakibatkan kabut asap di Sumatera Selatan. Untuk itu,
penyebaran lahan gambut sangat penting untuk dimasukkan ke dalam
model daerah rawan kebakaran ini. Data gambut diperoleh dari data jenis
tanah yang diperoleh dari Puslitanak Bogor. Dalam hal ini, data tanah
sudah dalam format GRID.
1. Klik tombol Add data (tombol dengan logo kotak biru)
2. Arahkan mouse ke bagian kosong di View project yang kita kerjakan
saat ini (misalnya di bagian atas flow chart yang sudah ada, lalu Klik
kiri, maka
akan muncul kotak kosong pada halaman ModelBuilder
dengan nama Data.
24
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
3. Arahkan mouse ke kotak Data tersebut, lalu Klik kanan, dan pilih
Theme.
4. Klik kanan pada kotak Theme yang baru, lalu pilih Properties
5. Tentukan data yang ingin digunakan sebagai data penyebaran lahan
gambut.
25
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Enter the project data name : Peta Tanah
Choose the input theme : Tanah
Choose the input field : Status
Lalu klik OK.
5. Pembobotan dan Penilaian ( Weighting/Scoring)
Setelah semua data lengkap, selanjutnya dilakukan proses pembobotan
dan penilaian terhadap masing-masing faktor dan parameternya. Proses
dilakukan menggunakan metode Weighted Overlay, dimana selain kita
memberi nilai dari tiap parameter yang ada, kita juga dapat memberi
bobot dari
pengaruh suatu faktor
terhadap tingkat kerawanan
kebakaran.
Rawan Kebakaran = (0.4 * [Penutupan Lahan]) + (0.3 * [Lahan
Gambut]) + (0.3 [Zona Iklim/Elevasi])
Untuk itu kita perlu memberikan nilai dan bobot dari ketiga faktor yang
sebelumnya telah kita masukkan. Sesuai dengan rumus diatas, maka
nilai bobot yang diterapkan adalah:
1. Peta Landcover (40%)
2. Peta Ketinggian (30%)
3. Peta Tanah (30%)
A. Memulai Proses Weighted Overlay
1. Klik menu Add Process > Overlay > Weighted Overlay
26
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Lalu klik Next.
2. Pilih Skala Evaluasi (Evaluation Scale) yang ingin digunakan.
Choose a predefined evaluation scale : 1 to 5
Lalu klik Next. Maka akan muncul jendela Weighted Overlay yang
masih kosong.
27
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Pembobotan dan Penilaian Peta Landcover
1. Klik tombol Add Theme
Masukan paramater pertama yaitu Peta Landcover
Choose the input theme
: Peta Landcover
Choose the input field
: Value
2. Klik OK
Pada jendela yang muncul, perhatikan 2 kolom yang harus diisi dengan
nilai yang sesuai, yaitu kolom % Inf atau % of influence yang
merupakan nilai untuk pembobotan dari sebuah faktor atau layer, serta
Scale Value yang merupakan nilai tiap unsur dari faktor tertentu.
3. Untuk merubah nilai pada kolom % Inf, klik sel kosong di bawahnya,
lalu ketik angka 40. Untuk merubah nilai Scale Value, klik di sel yang
ingin dirubah, lalu pilih nilai dari daftar nilai yang ada (drop down list)
yang berkisar anatar 1-5 dan restricted.
28
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Tentukan nilai % Inf sesuai dengan nilai bobot masing-masing layer
pada rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini ketik
angka 40 untuk memberi bobot sebesar 40% bagi penutupan lahan.
Selanjutnya rubah nilai Scale Value dari masing-masing nilai seperti
gambar dibawah ini. Nilai-nilai tersebut diperoleh dari hasil analisa data
penyebaran hotspot tahun 2006.
29
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
B. Pembobotan dan Penilaian Peta Ketinggian
Setelah selesai memberi nilai dan bobot pada Peta Landcover, kita masih
harus menambahkan layer-layer berikutnya. Selanjutnya kita akan
menambahkan Peta Ketinggian ke dalam Weighted Overlay.
1. Dari jendela Weighted Overlay, Klik Add theme
2. Pilih nama layer Peta Ketinggian yang ingin dimasukkan.
Choose the input theme : Peta Ketinggian
Choose the input field : Value
30
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Lalu klik OK.
Tentukan nilai % Inf sesuai dengan nilai bobot masing-masing layer pada
rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini ketik angka 30
untuk memberi bobot sebesar 30% bagi Peta Ketinggian atau Zonasi Iklim.
Selanjutnya rubah nilai Scale Value dari masing-masing nilai seperti
gambar di atas.
C. Pembobotan dan Penilaian Peta Tanah
Selanjutnya kita akan menambahkan Peta Ketinggian ke dalam Weighted
Overlay.
1. Klik Add theme dari jendela Weighted Overlay.
2. Pilih layer Tanah dan kolom Status.
31
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Choose the input theme : Tanah
Choose the input field
: Status
Lalu klik OK.
3. Tentukan nilai % Inf sesuai dengan nilai bobot masing-masing layer
pada rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini ketik
angka 30 untuk memberi bobot sebesar 30% bagi Peta Tanah atau
Penyebaran Gambut. Selanjutnya rubah nilai Scale Value dari
masing-masing nilai seperti gambar di bawah.
Saat ini kita telah memasukkan 3 layer untuk digunakan dalam proses
Weighted Overlay, yaitu Peta Landcover, Peta Ketinggian, serta Peta
Tanah atau penyebaran gambut. Selain memberi bobot, kita juga telah
memberi nilai dari masing-masing kelas dari layer-layer tersebut, seperti
pada gambar berikut.
32
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
4. Selanjutnya, Klik OK
33
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
5. Pilih salah satu gradasi warna yang akan digunakan untuk peta
keluaran. Lalu klik Next.
6. Pilih batasan areal yang akan dianalisa.
The extent of this theme : Sumsel
34
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
7. Tentukan resolusi yang diinginkan. Pilih layer Sumsel. Lalu klik Next
The cell size of this theme : Sumsel
8. Beri nama peta (Peta Rawan Kebakaran) dan nama file output
(FDR_grd). Lalu klik Finish.
35
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Sebuah model Peta Rawan Kebakaran yang lengkap telah disusun dan
siap dijalankan. Namun sebelumnya kita dapat mengklik kedua tombol di
bawah ini untuk merapihkan diagram alur yang kita susun.
36
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
6. Menyimpan dan Menjalankan Model
A. Menyimpan Project ModelBuilder
Project yang telah disusun bisa disimpan ke dalam hard disk, sehingga
bisa dibuka kembali kapan pun untuk melakukan pembaharuan atau
updating peta.
1. Klik File > Save As
2. Masukan lokasi harddrive tempat data permodelan akan disimpan
Drives
: tentukan drive
Save In
: tentukan foldernya
Model name
: firerisk atau petarawan
B. Menjalankan Model
Setelah semua prosedur dijalankan dan model sudah lengkap, langkah
selanjutnya adalah menjalankan model secara keseluruhan.
Pastikan
seluruh komponen dalam bagan alur memiliki warna, yang berarti tidak ada
kesalahan dari input data.
37
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
1. Klik menu Model > Run Entire Model
Secara otomatis ArcView akan menjalankan proses penyusunan peta
rawan kebakaran berdasarkan model yang telah disusun sebelumnya.
Biasanya diperlukan waktu beberapa menit tergantung dari spesifikasi
komputer yang digunakan. Jika proses berhasil, maka akan tampil
sebuah layer peta rawan kebakaran baru.
2. Untuk memudahkan klasifikasi kelas di dalam tampilan peta, ubah
legenda peta dengan merubah warna dan label dari nilai-nilai layer
tersebut seperti tabel di berikut ini.
38
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Nilai
Label
Warna
Tidak Rawan
Hijau
Rendah
Kuning
Sedang
Jingga
Tinggi
Merah
Sangat Rawan
Merah Tua / Coklat
Selanjutnya, tampilan peta rawan yang dibuat akan seperti pada gambar di
atas. Secara visual, tingkat kerawanan kebakaran ditampilkan dengan
warna hijau, kuning, jingga, merah dan coklat untuk mewakili tingkat rawan
kebakaran mulai dari tidak rawan, rendah, sedang, tinggi dan sangat
rawan. Sehingga lebih memudahkan interpretasi peta oleh pengguna akhir.
39
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
7. Hasil dan Pembahasan
Ketiga kabupaten prioritas SSFFMP, yaitu Musi Banyuasin, Banyuasin dan
Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan daerah dengan tingkat kerawanan
kebakaran yang tinggi. Terlihat dari grafik di bawah ini, yang merupakan
hasil analisis daerah rawan kebakaran. Tingkat rawan tinggi dan sedang
sebagian besar tersebar pada ketiga kabupaten prioritas tersebut. Karena
keterbatasan sumberdaya pemadaman yang ada, maka diperlukan
pengkonsentrasian kegiatan pencegahan dan pemadaman di wilayahwilayah tersebut.
Luas Areal Rawan Kebakaran
900000
800000
Ha
Tidak Rawan
700000
Rendah
600000
Sedang
Tinggi
500000
Sangat Rawan
400000
300000
200000
100000
Prabumulih
Palembang
Pagar Alam
OKU Timur
OKU Selatan
OKU
Ogan Ilir
Musi Rawas
Muara Enim
Lubuk Linggau
Lahat
Ogan Komering Ilir
Banyuasin
Musi Banyuasin
Kabupaten
Grafik penyebaran daerah rawan kebakaran per kabupaten di Sumatera
Selatan.
Kabupaten OKI memiliki daerah sangat rawan kebakaran yang sangat
luas, lebih dari 470 ribu hektar. Hal ini akibat cukup luasnya areal lahan
40
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
gambut terdegradasi, khususnya di kecamatan Tulung Selapan. Selain itu,
kriteria tinggi juga didominasi oleh Kabupaten OKI dengan luasan lebih dari
650 ribu hektar (lihat Lampiran 4 tentang tabel penyebaran daerah rawan
kebakaran). Sebagian besar penyebab kebakaran di wilayah ini adalah
kegiatan masyarakat yang terkait dengan penanaman padi sonor, mencari
ikan, serta membuat akses di lahan gambut untuk mencari kayu atau
berburu. Upaya pencegahan melalui pengembangan masyarakat melalui
upaya pemberian altenatif
matapencaharian sekitar
lahan gambut
sangatlah penting untuk menghindari terpicunya kebakaran gambut oleh
masyarakat saat musim kemarau. Peningkatan kesadaran masyarakat
sekitar akan bahaya kebakaran gambut serta pentingnya ekosistem bagi
lingkungan global juga perlu diterapkan.
Rendahnya aksesibilitas yang dapat dilalui oleh regu-regu pemadam juga
menyulitkan upaya pemadaman oleh regu Manggala Agni. Ditambah lagi
dengan terbatasnya sumber air di lahan gambut saat kemarau,
mengakibatkan regu pemadam hanya mampu menjangkau areal lahan
gambut tidak lebih dari 500 meter dari di pinggir jalan dan kanal. Alternatif
transportasi bagi regu pemadam, selain akses jalan, karenanya sangat
perlu diperhatikan, mengingat sulitnya aksesibilitas menuju areal lahan
gambut yang terdegradasi. Namun, upaya pencegahan perlu diprioritaskan
di wilayah ini.
Tidak semua areal dataran rendah di wilayah pesisir timur Sumatera
Selatan berada dalam tingkat rawan kebakaran yang tinggi. Taman
Nasional Sembilang (TNS) sebagian besar masih berada dalam tingkat
rawan sang rendah. Hal ini karena wilayah TNS masih didominasi oleh
hutan bakau (mangrove) yang masih
Sementara itu, Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Rawas serta OKU
Selatan memiliki daerah yang tidak rawan kebakaran yang masih cukup
41
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
banyak. Cukup masuk akal, mengingat sebagian wilayah kabupaten
tersebut berada di daerah pegunungan atau memiliki areal berhutan yang
masih relatif cukup baik kondisinya. Namun demikian di Kabupaten Muara
Enim dan Musi Rawas juga masih terdapat areal dengan tingkat kebakaran
tinggi bahkan sangat rawan, khususnya di daerah gambut sepanjang
sungai Musi. Sebenarnya lahan gambut di wilayah ini relatif aman dari
kebakaran besar dibandingkan lahan gambut yang berada di pesisir timur.
Kebakaran di wilayah ini biasanya dimulai atau paling tidak dipicu oleh
pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Hal ini dapat dilihat dari
kumulatif penyebaran hotspot di wilayah tersebut, dimana terdapat
kumpulan (cluster) hotspot yang sangat rapat di areal yang dibuka untuk
perkebunan. Kebijakan zero burning karenanya harus diterapkan untuk
keperluan tersebut, tentunya dengan dibarengi upaya penegakkan hukum.
Daerah dengan tingkat rawan tinggi juga terdapat di OKU Timur. Hal ini
disebabkan banyaknya hotspot yang terdeteksi akibat pembakaran di
lahan persawahan di kecamatan Belitang yang merupakan lahan
pertanian. Seperti halnya pertanian intensif lainnya hal ini tidak memiliki
dampak yang cukup besar, mengingat bukan di lahan gambut.
Evaluasi peta rawan kebakaran juga dilakukan untuk mengetahui kualitas
informasi terkait dengan penyebaran hotspot. Dengan menggunakan peta
rawan kebakaran yang disusun menggunakan hasil analisa penyebaran
hotspot tahun 2004, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat
keakurasian prediksi penyebaran hotspot tahun 2006. Sebagian besar
hotspot (hampir 90%) berada di daerah dengan tingkat rawan kebakaran
sangat tinggi.
Korelasi yang tinggi antara peta rawan kebakaran dengan penyebaran
hotspot pada musim kemarau berikutnya, dapat dilihat dari grafik di atas,
42
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
dimana sebaliknya di areal dengan tingkat rawan yang rendah dan tidak
rawan, kerapatan penyebaran hotspot sangatlah rendah.
100
89.14
90
80
Kerapatan per 10 Km 2
70
60
50
36.86
40
30
20
10
12.51
12.63
Rendah
Sedang
5.03
0
Tidak Rawan
Rawan
Sangat Rawan
Tingkat Kerawanan Kebakaran
Grafik evaluasi penyebaran hotspot tahun 2006 dengan peta rawan
kebakaran yang dibuat tahun 2005.
Karenanya peta rawan kebakaran tersebut dapat digunakan untuk
keperluan
identifikasi
areal
prioritas
dan
perencanaan
kegiatan
pencegahan, alokasi sumberdaya pemadaman ataupun perencanaan
kebijakan dan strategis lainnya. Selain itu, bagi fire manager yang sudah
lebih
mumpuni
(advanced),
Sistem
Analisa
Ancaman
Kebakaran
merupakan informasi tambahan yang sangat detail dan bermanfaat untuk
keperluan perencanaan pada skala yang lebih rinci.
Kehidupan nyata selalu dinamis dan mengalami perubahan. Berbeda
dengan peta atau model yang dibuat, hanya mewakili suatu kondisi dalam
waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan pembaharuan data dan peta
secara reguler, sehingga akurasi dan aktualitas menjadi lebih baik.
43
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Bahan Bacaan
Anderson, I. P., M.R. Bowen, I.D. Imanda dan Muhnandar. 1999.
Vegetation Fires in Indonesia: The Fire History of the Sumatra
Province 1996 1998 as a Predictor of Future Areas at Risk. FFPCP
Report. Palembang.
ESRI. 2002. Using ArcView GIS. Environmental Systems Research
Institute, Inc. Redlands California.
Greene, R. W. 2002. Confronting Catastrophe: A GIS Handbook. ESRI
Press. Redlands California.
Nuarsa, I Wayan. 2005. Belajar Sendiri Menganalisis Data Spasial dengan
ArcView 3.3 untuk Pemula. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
Ormsby, T dan Alvi, J. 1999. Extending ArcView GIS. ESRI Press.
Redlands California.
Prahasta, Edy. 2002. Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis.
Informatika. Bandung.
Prahasta, Edy. 2003. Sistem Informasi Geografis: Tutorial ArcView.
Informatika Bandung.
Ruecker, G. 2007. Ekstensi Sistem Analisa Ancaman Kebakaran untuk
ArcView GIS 3.x: Panduan bagi Pengguna dan Administrator.
SSFFMP. Palembang.
Solichin, Hasanuddin dan Christiana. 2007. Manual Pengumpulan
Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Internet. SSFFMP.
Palembang.
Solichin dan P. Kimman. 2003. Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan
Lahan. SSFFMP. Palembang.
Whitten, T. 2000. The Ecology of Sumatra. Periplus Edition. Singapore.
44
Hutan Mangrove Prim 0.043
Hutan Mangrove Sekun 0.037
Hutan Primer
Hutan Rawa Primer
0.083
0.811
3.637
Hutan Rawa Sekunder
Hutan Sekunder
0.774
4.451
Hutan Tanaman
Pemukiman
Pertanian Campuran
1.22
0.862
1.904
Pertanian Lahan Keri
4.858
Rawa
Sawah
1.263
4.347
Semak Rawa
Tambak
0.74
1.126
3.325
Tanah Terbuka
Transmigrasi
0.809
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
Perkebunan
0.59
Lampiran.
4.738
Belukar Rawa
1. Sebaran Hotspot Berdasarkan Tutupan Lahan Tahun 2006
1.889
Frekuensi Hotspot 2006 Berdasarkan Daerah Tutupan
Lahan
0.825
0.374
Belukar
Tambang
Water body
0.186
0.502
0.631
Volcanic
0.269
slop
0.504
Very steep
1.18
Awan
Tutupan Lahan
5.763
Air
0.259
Frekuensi
0
2.245
Frekuensi Sebaran Hotspot Tahun 2006 Berdasarkan
Jenis Tanah
Je nis Tanah
Urban Area
2.723
Peat Domes
SEA/RIVERS
1.059
Marin
Plain
2.027
Karst
Montain/Plateau
1.45
Alluvial
Hilly
0
Acid Tuff Plain
2. Sebaran Hotspot Berdasarkan Jenis Tanah Tahun 2006
Frekuensi
45
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
3. Sebaran Hotspot Berdasarkan Ketinggian Tahun 2006
3.5
3.153
Frekuensi Sebaran Hotspot Tahun 2006 Berdasarkan
Kelas Ketinggian
0.07
0
2000 - 3200
m
0.5
1000 - 2000
m
0.269
1.558
0.679
1.5
1.337
1.048
500 - 1000 m
200 - 500 m
100 - 200 m
50 - 100 m
25 - 50 m
0
0 - 25 m
Frekuensi
2.5
Ke las Ke tinggian
46
Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran
4. Tabel penyebaran daerah rawan kebakaran di Sumatera Selatan
Kabupaten
Tidak Rawan
Ha
Musi Banyuasin
Rendah
Ha
Sedang
Ha
Tinggi
Ha
Sangat Rawan
Ha
Total Luas
Kabupaten
0.0
772138
53.0
348678
23.9
277074
19.0
39804
2.7
1457975
222
0.0
301731
25.1
362395
30.2
395708
33.0
78511
6.5
1199983
0.0
329110
18.9
267951
15.4
659769
37.9
473144
27.1
1743107
349185
52.9
218355
33.1
38487
5.8
41391
6.3
0.0
660748
7971
19.0
30098
71.8
1349
3.2
0.0
0.0
41898
Muara Enim
108844
12.7
463361
54.0
138710
16.2
94513
11.0
42501
5.0
858563
Musi Rawas
251708
20.6
674964
55.2
192136
15.7
91257
7.5
3417
0.3
1222890
0.0
79132
33.3
79585
33.4
76636
32.2
275
0.1
238022
63702
22.0
133823
46.2
71374
24.7
19165
6.6
0.0
289588
181321
34.2
188337
35.5
106439
20.1
13488
2.5
0.0
530386
OKU Timur
0.0
145725
45.2
56193
17.4
111594
34.6
0.0
322540
Pagar Alam
56969
94.7
2357
3.9
0.0
0.0
0.0
60148
Palembang
0.0
19846
52.3
15207
40.0
926
2.4
0.0
37983
Prabumulih
0.0
36952
87.1
3396
8.0
1946
4.6
0.0
42412
Banyuasin
OKI
Lahat
Lubuk Linggau
Ogan Ilir
OKU
OKU Selatan
Total
1019926
3395928
1681900
1783467
637652
8706242
47
Anda mungkin juga menyukai
- Istilah Dalam PertambanganDokumen44 halamanIstilah Dalam PertambanganEta Fanani AR100% (10)
- Petunjuk Pelaksanaan CSR Bidang LingkunganDokumen90 halamanPetunjuk Pelaksanaan CSR Bidang LingkunganEta Fanani AR100% (1)
- Laporan Pendahuluan Updating Das KahayanDokumen54 halamanLaporan Pendahuluan Updating Das KahayanRaden Mas Jhoko Hadiningrat100% (2)
- 978 979 582 221 9Dokumen60 halaman978 979 582 221 9Andri UskaBelum ada peringkat
- Laporan Monitoring Pengelolaan DAS 2022Dokumen74 halamanLaporan Monitoring Pengelolaan DAS 2022khabibi nurBelum ada peringkat
- Jasa EkosistemDokumen36 halamanJasa Ekosistembunga djasmin ramadhantyBelum ada peringkat
- FA Buku Tata Kelola Ekosistem Gambut - PELANGI HIRES - CompressedDokumen84 halamanFA Buku Tata Kelola Ekosistem Gambut - PELANGI HIRES - CompressedBiru100% (1)
- Tugas PPM Pentagon AsetnjjkjhkDokumen7 halamanTugas PPM Pentagon AsetnjjkjhkHilmy Ammar RamadhanyBelum ada peringkat
- BAB 3 Rancangan Pelaksanaan ADokumen39 halamanBAB 3 Rancangan Pelaksanaan ANenk NisaBelum ada peringkat
- Alternatif RMUDokumen25 halamanAlternatif RMUMul YadiBelum ada peringkat
- Faktor Emisi Solar Per LiterDokumen9 halamanFaktor Emisi Solar Per LiterNurul maghfirohBelum ada peringkat
- Budidaya Bambu Komersial PDFDokumen52 halamanBudidaya Bambu Komersial PDFEta Fanani ARBelum ada peringkat
- PS Permen 09 Tahun 2021Dokumen62 halamanPS Permen 09 Tahun 2021GustiBelum ada peringkat
- Daftar Peta SbeDokumen13 halamanDaftar Peta SbesenoscribdBelum ada peringkat
- Sertifikasi Hutan RakyatDokumen149 halamanSertifikasi Hutan Rakyatkrisnagunara100% (1)
- Pemetaan Resiko Kebakaran HutanDokumen20 halamanPemetaan Resiko Kebakaran HutanArif BseBelum ada peringkat
- Booklet PersemaianDokumen20 halamanBooklet PersemaianFarhah MaulydyaBelum ada peringkat
- Permenhut 2006Dokumen7 halamanPermenhut 2006avastarleyBelum ada peringkat
- Sni 19-6728.2-2002Dokumen30 halamanSni 19-6728.2-2002agus_saputra_35Belum ada peringkat
- Pedoman Inventarisasi MangroveDokumen14 halamanPedoman Inventarisasi MangroveJokoSusiloBelum ada peringkat
- Juknis SengonDokumen21 halamanJuknis SengonAgung SerulinkBelum ada peringkat
- Statistik KLHK Tahun 2015Dokumen344 halamanStatistik KLHK Tahun 2015Mengky Mangarek100% (1)
- BisnissengDokumen200 halamanBisnissengJagoan NeonBelum ada peringkat
- Rehabilitasi MangroveDokumen22 halamanRehabilitasi MangroveRahalScribdBelum ada peringkat
- Ketua Harian 2Dokumen23 halamanKetua Harian 2don karlBelum ada peringkat
- Kumpulan Peraturan Rehabilitasi Das Bagi Pemegang IppkhDokumen1 halamanKumpulan Peraturan Rehabilitasi Das Bagi Pemegang IppkhboyBelum ada peringkat
- Rancangan Teknis Reklamasi - Alex Andityaman BetaubunDokumen39 halamanRancangan Teknis Reklamasi - Alex Andityaman Betaubunaprilia dwi astutiBelum ada peringkat
- Sarana Dan Prasarana Persemaian ModernDokumen12 halamanSarana Dan Prasarana Persemaian Moderncicks damBelum ada peringkat
- RPHJP Dolago TanggunungDokumen341 halamanRPHJP Dolago TanggunungPakdhe IbenBelum ada peringkat
- KLHK Report 2017 PDFDokumen203 halamanKLHK Report 2017 PDFLocke Holey FristantoBelum ada peringkat
- Panduan Rehabilitasi Pantai (UNEP2006)Dokumen92 halamanPanduan Rehabilitasi Pantai (UNEP2006)Eko Bayu Prastyo100% (1)
- Profil KTH DarungDokumen10 halamanProfil KTH DarungRosidiBelum ada peringkat
- Program UnggulanDokumen26 halamanProgram UnggulanyholicBelum ada peringkat
- Bpdashl Benain Noelmina Lahan Kritis 2018Dokumen17 halamanBpdashl Benain Noelmina Lahan Kritis 2018Muh WidodoBelum ada peringkat
- 2021pmlhk008 Menlhk 06102021121117Dokumen911 halaman2021pmlhk008 Menlhk 06102021121117Johanwi Penyuluh Kehutanan MilenialBelum ada peringkat
- Modul Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan ProduksiDokumen129 halamanModul Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Hutan ProduksiNanang SetiawanBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Profil Kahati Gunung Sumbing - Edit NencyDokumen104 halamanLaporan Akhir Profil Kahati Gunung Sumbing - Edit Nencyfotocopy mellaaBelum ada peringkat
- Kebijakan Gambut PuuDokumen19 halamanKebijakan Gambut Puuhadie akbar ariantoBelum ada peringkat
- Pelaksanaan Penanaman Perum PerhutaniDokumen15 halamanPelaksanaan Penanaman Perum Perhutanitambora wish100% (1)
- Proposal Hutan Pantai - Cikaret 2020Dokumen10 halamanProposal Hutan Pantai - Cikaret 2020Toni FaisalBelum ada peringkat
- Stek Pucuk Meranti BSNDokumen12 halamanStek Pucuk Meranti BSNFarahnaz Mustika100% (1)
- Laporan Praktik Kerja Lapang PT. Gunung MerantiDokumen54 halamanLaporan Praktik Kerja Lapang PT. Gunung MerantiMaulana Rasta Y100% (1)
- Sosialisasi Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan SosialDokumen28 halamanSosialisasi Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan SosialAnggi PutraBelum ada peringkat
- Daerah Ekoregion Kalimantan 2021Dokumen22 halamanDaerah Ekoregion Kalimantan 2021keiishiiBelum ada peringkat
- Pemeliharaan Bibit Stek Pucuk JPP Di KPH MadiunDokumen73 halamanPemeliharaan Bibit Stek Pucuk JPP Di KPH MadiunGedhe AlorBelum ada peringkat
- Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS TerpaduDokumen18 halamanPedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS TerpaduAwu LupVa100% (3)
- Reklamasi Lahan Bekas TambangDokumen15 halamanReklamasi Lahan Bekas TambangPermata Plastikplus100% (1)
- Buku Statistik 2012 PDFDokumen323 halamanBuku Statistik 2012 PDFhairilteaholicBelum ada peringkat
- Pengelolaan Zona Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Melalui Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Kepiting Bakau Scylla Serrata Di Taman Nasional Kutai ProvinsiDokumen293 halamanPengelolaan Zona Pemanfaatan Ekosistem Mangrove Melalui Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Kepiting Bakau Scylla Serrata Di Taman Nasional Kutai ProvinsiiqbalBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Impact Assesment RHL 2022Dokumen62 halamanLaporan Akhir Impact Assesment RHL 2022khabibi nurBelum ada peringkat
- Identifikasi Sumber Pencemaran Di Wilayah Mangrove Wana Tirta Kulon Progo YogyakartaDokumen7 halamanIdentifikasi Sumber Pencemaran Di Wilayah Mangrove Wana Tirta Kulon Progo YogyakartaPanji PangestuBelum ada peringkat
- Produksi Oksigen Vegetasi KotaDokumen3 halamanProduksi Oksigen Vegetasi Kotageografi2007Belum ada peringkat
- Alur Izin IUPHHK-HA PDFDokumen1 halamanAlur Izin IUPHHK-HA PDFGilangBelum ada peringkat
- Stat 2017Dokumen529 halamanStat 2017David Erick Grohl0% (1)
- BUKU IRBI 2018 (Publish 30 Des) Resize PDFDokumen328 halamanBUKU IRBI 2018 (Publish 30 Des) Resize PDFBlack PlagueBelum ada peringkat
- Kawasan Lebah Madu Milik MaDokumen14 halamanKawasan Lebah Madu Milik MaUlil AmriBelum ada peringkat
- HJD Kayu Bundar Perhutani 2016. Kayu Rimba DamarDokumen3 halamanHJD Kayu Bundar Perhutani 2016. Kayu Rimba DamarSatria Ardhi PermanaBelum ada peringkat
- Artikel Implementasi Proklim Di Purbalingga Hijrah Utama P2a017001Dokumen21 halamanArtikel Implementasi Proklim Di Purbalingga Hijrah Utama P2a017001Hijrah UtamaBelum ada peringkat
- Kuliah 5 Morfologi Dan Ekologi Primata Dan UngulataDokumen63 halamanKuliah 5 Morfologi Dan Ekologi Primata Dan UngulataRoni Antono100% (1)
- Laporan Desa Karang Bintang1Dokumen15 halamanLaporan Desa Karang Bintang1yusriyanti fikaisaBelum ada peringkat
- PKM REVISI NewDokumen21 halamanPKM REVISI NewFadhillah HazrinaBelum ada peringkat
- Makalah Kajian Kebakaran Hutan Di TNTPDokumen18 halamanMakalah Kajian Kebakaran Hutan Di TNTPsunaryoBelum ada peringkat
- Laporan Patroli Pencegahan Segah 2-4 Sept 2021Dokumen11 halamanLaporan Patroli Pencegahan Segah 2-4 Sept 2021Anggi PutraBelum ada peringkat
- Permentan 5 Tahun 2018Dokumen48 halamanPermentan 5 Tahun 2018Eta Fanani AR67% (3)
- Permentan 5 Tahun 2018Dokumen48 halamanPermentan 5 Tahun 2018Eta Fanani AR67% (3)
- Pengelolaan Tanah PucukDokumen24 halamanPengelolaan Tanah PucukEta Fanani ARBelum ada peringkat
- Bahan AntimoniDokumen14 halamanBahan AntimoniEta Fanani ARBelum ada peringkat
- Pemisahan Dan Karakterisasi Emas Dari Batuan Alam Dengan Metode Natrium BisulfitDokumen11 halamanPemisahan Dan Karakterisasi Emas Dari Batuan Alam Dengan Metode Natrium BisulfitJundiBelum ada peringkat
- Pengelolaan Tanah PucukDokumen24 halamanPengelolaan Tanah PucukEta Fanani ARBelum ada peringkat
- Draft Permen Sawit Lampiran 5 Mekanisme IzinDokumen34 halamanDraft Permen Sawit Lampiran 5 Mekanisme IzinEta Fanani AR100% (1)
- Pabrik Kelapa Sawit Continuous SystemDokumen6 halamanPabrik Kelapa Sawit Continuous SystemEta Fanani ARBelum ada peringkat
- Air Upas Dalam Angka 2014Dokumen166 halamanAir Upas Dalam Angka 2014Eta Fanani AR100% (1)