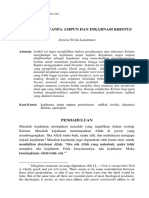Apa Yg Mutlak Menurut Imanuel Khan
Diunggah oleh
Timotius Winanto0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
850 tayangan11 halamanHak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
850 tayangan11 halamanApa Yg Mutlak Menurut Imanuel Khan
Diunggah oleh
Timotius WinantoHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 11
C.
Teori perkembangan moral Immanuel Kahn
1. Deontologi
Semua sistem etika yang dibahas sampai di sini mempehatikan hasil perbuatan. Baik tidaknya
perbuatan dianggap tergantung pada konsekuensinya. Karena itu system-sistem ini disebut juga
system konsekuensialistis. Masih ada cara lain untuk mengatakan hal yang sama. Sistem-sistem
etika yang di bicarakan sebelumnya semua berorientasi pada tujuan perbuatan. Dalam
utilatarisme, umpamanya, tujuan perbuatan-perbuatan moral adalah memaksimalkan
kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Karena itu bisa dikatakan juga
bahwa semua system itu bersifat teleologis (= terarah pada tujuan).
Sekarang kita akan memandang suatu sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu
perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam
melakukan perbuatan tersebut. Kita bisa mengatakan juga bahwa sistem ini tidak menyoroti
tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan kita, melainkan semata-mata wajib tidaknya
perbuatan dan keputusan kita. Teori yang dimaksudkan ini biasanya disebut deontologi (kata
yunani deon berarti : apa yang harus dilakukan; kewajiban )
Yang menciptakan sistem moral ini adalah filsuf besar dari Jerman, Immanuel Kant (1724-
1804). Pemikirannya tidak mudah tapi sangat berpengaruh, sehingga ia bisa dianggap sebagai
salah seorang pemikir terbesar di bidang filsafat moral.
Menurut Kant, yang bisa disebut baik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik,
semua hal lain disebut baik secara terbatas atau dengan syarat. Kesehatan, kekayaan, atau
intelegensi, misalnya adalah baik, jika digunakan . Dengan baik oleh kehendak manusia, tapi
jika dipakai oleh kehendak yang jahat semua hal itu bisa menjadi jelek sekali. Bahkan
keutamaan-keutamaan bisa disalahgunakan oleh kehendak yang jahat.
Pertanyaan pertama yang timbul sekarang adalah: apa yang membuat kehendak menjadi baik?
Menurut Kant kehendak menjadi baik, jika bertindak karena kewajiban. Kalau perbuatan
dilakukan dengan suatu maksud atau motif lain, perbuatan itu tidak bisa disebut baik,
betapapun luhur atau terpuji motif itu.
Misalnya, kalau perbuatan dilakukan karena kecenderungan atau watak, perbuatan itu secara
moral tidak baik. Mungkin sifat watak saya demikian , sehingga saya selalu senang membantu
orang lain. Mungkin sifat altruistis itu adalah kecenderungan spontan saya. Bagi Kant,
perbuatan-perbuatan yang berasal dari kecenderungan macam itu tdak bisa disebut baik, btapi
dari sudut moral bersifat netral saja. Atau mungkin saya memberi derma kepada pengemis ,
karena hati saya bergerak oleh keadannya yang menyedihkan.
Atau mungkin sata mengembalaikan buku yang saya pinjam dari perpustakaan, karena takut
akan terkena denda, bila terlambat dikembalikan. Semua perbuatan seperti itu tidak patut
disebut baik. Perbuatan adalah baik jika hanya dilakukan karena wajib dilakukan. Jadi, belum
cukup jika suatu perbuatan sesuai dengan kewajiban . Seharusnya perbutan dilakukan
berdasarkan kewajiban . Bertindak sesuai dengan kewajiban oleh Kant disebut legalitas.
Dengan legalitas kita memenuhi norma hukum . Misalnya, tidak penting dengan motif apa saya
membayar pajak, asal saja saya bayar jumlah uang yang sesuai dengan kewajiban saya. Tetapi
dengan itu saya belum memenuhi norma moral . Saya baru memasuki taraf moralitas, jika saya
melakukan perbuatan semata-mata karena kewajiban. Kata Kahn , suatu perbuatan bersifat
moral, jika dilakukan semata-mata “karena hormat untuk hokum moral “. Dengan hukum moral
dimaksudkannya kewajiban.
Terkenal juga pembedaan yang diajukan Kant antara imperatif ketegoris dan imperative
hipotersis. Kewajiban moral mengandung suatu imperatif kategoris artinya , imperatif
(perintah) yang mewajibkan begitu saja, tanpa syarat. Sebaliknya, imperatif hipotesis selalu
diikutsertakan sebuah syarat. Bentuknya adalah: “kalau engkau ingin mencapai tujuan , maka
engkau harus menghendaki juga sarana-sarana yang menuju ke tujuan tersebut”. Jika kita ingin
lulus untuk ujian, misalnya, kita harus belajar dengan tekun. Tapi sarana itu (belajar) hanya
mewajibkan kita sejauh kita ingin mencapai tujuan (lulus). Belum tentu kita semua mempunyai
tujuan itu.
Bisa saja, saya hanya terdaftar sebagai mahasiswa untuk mengisi waktu, untuk dapat menikmati
berbagai fasilitas, atau untuk bisa ikut dalam pertandingan olah raga mahasiswa sedunia, bukan
untuk menyelesaikan studi di suatu fakultas. Kalau sata tidak mempunyai tujuan itu (lulus),
saya juga tidak wajib menghendaki sarana (belajar) di sini kewajibannya hanya hipotesis
(kalau…., maka ), bertentangan dengan imperataif kategoris yang mengikat kita tanpa syarat
apap pun. Bentuk imperative terakhir ini adalah: “engkau harus begiyu sdaja!” (du sollst!).
Imperative katagoris ini menjiwai semua peraturan etis. Misalnya, janji harus ditepati (senang
atau tidak senang); barang yang dipinjam harus dikembalikan (juga bila pemiliknya sudah
lupa). Di bidang moral, tungkah laku manusia hanya dinbimbing oleh norma yang mewajibkan
begitu saja, bukian oleh pertimbangan lain.
Langkah berikut dalam pemikitran moral Kant ini adalah menyimpulkan otonomi kehendak .
Kalau hukum moral harus dipahami sebagai nimperatif kategoris. Maka dalam bertindak secara
moral kehendak harus otonom dan bukan heteronom. Kehendak bersifat otonom bila
menentukan dirinya sendiri, sedangkan kehendak heteronom membiarkan diri ditentukan oleh
faktor dari luar dirinya seperti kecenderungan atau emosi.
Menurut Kant , kehendak itu otonom dengan memberikan hukum moral kepada dirinya sendiri.
Manusia itu legislator moral bagi dirinya sendiri. Hal itu tentu tidak boleh dimengerti tentang
manusia perorangan , seolah-olah setiap manusia memembuat hukum moral sendiri-sendiri.
Kalau begitu, pemikiran Kant akan ditafsirkan dalam arti subyektivistik dean dengan itu
meleset sama sekali dari maksudnya.
Yang dimaksudkan Kant dengan otonomi manusia secara umum membuat hokum moral dan
menaklukkan diri kepadanya . dengan hidup menurut hukum moral, manusia tidak
menyerahkan diri kepada sesuatu yang asing baginya (heteronom), melainkan mengikuti
hukumnya sendiri. Dalam tingkah laku moralnya , manusia tidak menaklikkan diri kepada
instansi lain, melkainkan hanya ikepada hukumnya sendiri.
Dengan menemukan otonomi kehendak, Kant serentak juga menemukan kebebasan manusia.
Otonomi kehendak pada dasarnya sama dengan kebebasan manusia, sebab kebebasan adalah
kesanggupan untuk bertindak terlepas dari penguasaan oleh sebab-sebab asing. Manusia itu
bebas, karena mengikat dirinya sendiri dengan hukum moral. Menurut Kant, kebebasan tidak
berarti bebas dari segala ikatan. Sebaliknya, manusia itu bebas dengan mentaati hukum moral.
Kehendak bebas dan kehendak yang menundukkan diri kepada hukum moral, bagi Kant
mempunyai arti yang sama. (K Bartens, 2007: 254-256)
Lebih lanjut, berbicara mengenai kategoris diduga menghasilkan dua aturan berbuat yang lain,
dan seraya kita bahas Kant kita boleh juga mengkajinya. Yang pertama adalah : “berbuatlah
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kemanusiaan, baik dirimu sendiri ataupun orang lain,
dalam setiap kasus sebgai tujuan, tidak pernah hanya sebagai asrana.”
Ewing mengatakan pada kita bahwa :
Perkataan Kant ini memiliki pengaruh yang sangat besar, mungkin yang terbesar dari kalimat
yang di tulis oleh seorang filsuf ; perkataan tersebut sebenarnya berperan sebagai slogan dari
seluruh gerakan liberal dan demokratik dewasa ini. Mereka menolak perbudakan, eksploitasi,
pelanggaran terhadap martabat dan pribadi orang lain , membuat individu hanya sebagai alat
bagi Negara, pelanggaran hak asasi. Mereka merumuskan ide moral yang terbesar dewasa ini,
mungkin orang dapat menambahkan ide moral yang terbesar (sebagai yang dibedakan dengan
“religious”) dari agama Kristen.
Kant sendiri mengatakan pada kita bahwa maksimnya menolak janji bohong pada orang lain
dan penyerangan kebebasan atau kepemilikan orang lain.
Namun dua persolan mendesakkan diri mereka sendiri. Yang pertama, apakah kita memerlukan
maksim ini untuk menetapakan amoralitas kebohongan, pencurian, kekerasan. Apakah aturan
yang sebagainya, dengan kata lain, hanya merupakan akibat wajar dari maksim kant? Atau
dapatkah aturan-aturan itu ditetapakn sama sekali lepas dari maksim ini?
Persoalan yang kedua adalah apakah maksim Kant dilihat secara tersendiri sebagai sesuatu yang
pasti, memadai atau bahkan benar. Kita terus menerus menggunakan yang satu dan yang lain
hanya sebagai sarana. Hal ini secara praktis merupakan hakikat semua “hubungsan bisnis”. Kita
menggunakan tukang angkat untuk mengangkat barang kita dari stasion; kita memakai sopir
taksi, pelayan, sebalikmya menggunakan kita hanya sebagai saran untuk memperoleh
pendapatan yang dengan itu kemudian mereka mungkin untuk menggunakan orang untuk
menyediakan kebutuhan yang mereka ingini.
Kita semua saling menggunakan orang lain “hanya” sebagai sarana untuk menjamin kebutuhan
kita. Sebaliknya, kita semua menyediakan diri atau sumber yang kita milki untuk memenuhi
kebutuhan orang lain sebagai sarana tdak langsung untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri .
inlah yang menjadi kerjasama sosial.
Tentunya kita memerlakukan kawan dekat kita dan para anggota keluarga langsung kita sebagai
“tujuan” maupun sebagai srana. Kita bahkan mungkin dikatakan harus memerlukan pedagang
serbagai tujuan ketika kita memeperhatikan kesehatan merekas dan anak-anak mereka. Kita
perlihatkan kepada orang lain , sekalipun (dan secara khusus) ketika mereka berada dalam
posisi sebagai pelayan atau yang lebih rendah, dengan memerlakukan mereka selalu dengan
sopan, ramah, dan menghormati harkat kemanusiaan mereka. Tentu saja, kita harus senantiasa
mengakui dan menghormati hak orang lain.
Dunia dapat memperoleh, kewajiban yang diakui ini dan aturan yang secara luas tanpa
mengambil keuntungan dari maksim Kant. Namun mungkin maksim-maksim trsebut
membantu untuk menjelaskan dan menyatukannya.
Maksim Kant yang ketiga, atau bentuk ketiga dari imperatif kategoris, “berbuatlah sebagai
anggota kerajaan tujuan,” tampak lebih sempit daraipada bentuk maksim yang kedua. Kita
seharusnya memperlakuan diri sendiri dan orang lain sebagai tujuan; kita seharusnya
memandang setiap orang memiliki hak yang sama; kita seharusnya memandang kebaikan orang
lain sebagai kebaikan kita sendiri. Hal ini tampak hanya merupakan ara lain untuk
mengkerakakan syarat dan persamaaan di depan hukum. (Henry Hazlitt, 2003)
2. Tinjauan Kritis
Pemikiran moral Kant- yang tentu jauh lebih kaya dari pada yang bisa dilukiskan di sini-
merupakan sistem etika yang sangat menarik. Inti deontologi ini cocok dengan pengalaman
moral kita, terutama sebagaimana tampak dalam hati nurtani.
Kita memang sering merasa terikat dengan kewajiban dalam perilaku moral kita, sehingga tidak
bisa di sangkal bahwa kewajiban merupakan aspek penting dalam hidup moral kita. Tapi ada
juga kritik serius terhadap teorinya. Kritik itu tidak ditujukan pada peranan kewajiban itu
sendiri, melainkan pada peranan eksklusif kewajiban di bidang moral. Di bawah ini K Bartens
menyebut dua keberatan penting.
a. Sistem moral Kant merupakan suatu etika yang suram dan kaku. Diberi kesan seolah-olah
kita berlakukan baik hanya jika semata-mata melakukan karena kewajiban, melawan
kecenderungan spontan kita. Tapi apakah tidak mungkin juga kita berlaku dengan baik karena
kita senang berbuat baik? Apakah tidak mungkin kita berbuat baik karena cinta atau belas
kasih? Orang yang pamrih membaktikan seluruh tenaganya kepada anak-anak yatim piatu atau
anak-anak cacat , patuhlah kita anggap orang yang berkualitas moral tinggi. Tapi menurut Kant
bertindak karena cinta atau belas kasih berarti bertindak berdasarakan kecenderungan saja
dank arena itu tidak bebas. Memang benar, perbutan yang tidak bebas tidak bisa dianggap
perbuatan moral juga. Tapi Kant disini mempunyai pengertian terlalu sempit tentang kebebasan
eksistensial.
b. Sulit juga untuk diterima bahwa konsekuensi bisa diabaikan saja dalam menilai moralitas
perbuatan kita. Andaikan situsi sebagai berikut. Dalam keadaan perang Negara kita diduduki
oleh musuh. Saya menyembunyikan di rumah saya seorang teman yang dicari oleh musuh. Jika
ia jatuh dalam tamngan mereka pastia ia dibunuh , biarpun belum pernah ia melakukan
tindakan yang melanggar hukum. Pada suatu hari ada orang ketok rumah saya . seorang tentara
musuh berdiri disitu dan berytanya apakah di rumah saya ada X (ia sebut nama teman saya).
Apa yang harus saya perbuat? Saya tidak boleh berbohong, memang , tapi dengan mengatakan
kebenaran akan saya celakakan teman saaya yang todak bermasalah sedikit pun. Pada akhir
hidupnya Kant menulis karangan kecil berjudul “tentang yang disebut hak untuk beerbohong
karena cinta kepada sesama “ (1979). Di dsitu ia menegaskan bahwa kita wajib mengatakan
kebenraran dalam situasi apa pun juga dan tidak pernah boleh berbohong. Menurut dia, dalam
kasus seperti tadi juga saya harus mengatakan yang benar. Jika orang lain menjadi korban dari
kewajiban saya, maka itu bukan tanggung jawab saya. Bukan saya yang mencelakakan dia.
Pandangan W.D. Ross
Kesimpulan terakhir yang rigorus itu sulit untuk di terima. Menurut penilaian moral yang
umum, tidak perlu dan barangkali malah tidak boleh membiarkan konsekuensi jelek dari
perbuatan yang sebenarnya baik (mengatakan yang benar), jika saya mempunyai kemungkinan
untuk mencegahnya . seorang filsuf inggris abad ke-20, Wiliam David Ross (1877-1971)
mengusulkan jalan keluar yang menarik dari kesulitan semacam itu. Ross juga menerima teori
deontologi , tapi ia menambah sebuah nuansa yang penting.
Kewajiban itu selalu merupakan kewajiban prima facie (pada pandangan pertama), artinya
suatu kewajiban untuk sementara, dan hanya berlaku sampai timbul kewajiban lebih penting
lagi yang mengalahkan kewajiban yang pertama tadi. Dalam contoh di atas terjadi konflik
antara dua kewajiban yang tidak bisa dipenuhi dua sekaligus. Di satu pihak saya wajib
mengatakan yang benar dan dio lain pihak saya wajib menyelamatkan teman yangt tidak
bersalah. Ross mengatajkan bahwa kewajiban untuk mengatakan kebenaran merupakan
kewajiban prima facie yang berlaku sanpai ada kewajiban yang lebih penting. Dan kita semua
akan menyetujui bahwa kewajiban untuk menyelamatkan teman di sini merupakan kewajiban
yang jauh lebih mendesak. Karena itu kewajiban pertama itu di sini tidak berlaku lagi.
Ross menyusun sebuah daftar kewajiban yang semuanya merupakan kewajiban prima facie :
1) Kewajiban kesetiaan :kita harus menepati janji yang diadakan dengan bebas.
2) Kewajiban ganti rugi : kita harus melunasi utang moril dan materiil.
3) Kewajiban terima kasih : kita harus berterima kasih kepada orang yang berbuat baik
terhadap kita.
4) Kewajiban keadilan : kita harus membagikan hal-hal yang menyenangkan sesuai dengan jasa
orang-orang bersangkutan.
5) Kewajiban berbuat baik : kita harus membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita .
6) Kewajiban mengembangkan dirinya : kita harus mengembangkan bakat kita ddi bidang
keutamaan, inteligensi, dan sebagianya.
7) Kewajiban untuk tidak merugikan : kita tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan
orang lain (satu-satunya kewajian yang dirumuskan Ross dalam bentuk negatif)
Menurut Ross, setiap manusia mempunyai intuisi tentang kewajiban-kewajiban itu, artinya,
semua kewajiban itu berlaku langsung bagi kita. Tapi kita tidak mempunyai intuisi tentang ap
yang terbaik dalam situasi konkret. Untuk itu perlu kita pergunakan akal budi. Kita harus
mempertimbangkan dalam setiap kasus mana kewajiban yang paling penting, jika tidak
mungkin memenuhi semua kewajoban sekaligus. Kewajiban-kewajiban lain harus kalah
terhadap kewajiban yang dinilai paling penting itu.
Pandangan Ross ini merupakan kemajuan terhadap rigorisme dan Kant. Konflik antara
kewajiban-kewajiban dengan demikian dapat diatasi. Tapi pandangan itu sendiri tidak tanpa
kesulitan juga . Ross mengakui bahwa ia tidak bisa menunujukkan norma untuk menentukan
kewajiban apa yang berlaku di atas kewajiban prima facie lainnya. Tidak ada jalan lain daripada
mencari alasannya dalam setiap situasi konkret.
3. Persamaan dan perbedaan Kant dan Al Ghazali
Telaah kritis karya-karya Ghazali dan Immanuel Kant memperlihatkan persamaan alur
pemikiran antara keduanya. Keduanya sangat mempertanyakan sekaligus menolak keabsahan
konsepsi metafisika spekulatif yang dirumuskan para pendahulunya. Ghazali dengan penuh
semangat menyanggah konsepsi metafisika emanatif-spekulatif Ibn Sina (980-1037) dalam
bukunya Tahafut Al-falasifah , sedang Kant dengan sangat teliti menyanggah konsepsi
metafisika spekulatif Cristian Wolff (1679-1751) dalam magnum opusnya, Kritik der Reinen
vernunft. Sudah barang tentu kritik Kant terhadap teori-teori metafisika yang dirumuskan para
pendahulunya lebih menggigit dibandingkan kritik Ghazali, karena mengandung aspek-aspek
espitomologis yang begitu fundamental, yang tidak dimiliki oleh Ghazali. Sebenarnya, dalam
dunia filsafat, kritik terhadap teori-teori metafisika sering kali muncul. Sebagai contoh, aliran
filsafat yang disebut Positivisme-Logis (Logikal Positivism) di lingkaran Wina, juga menyanggah
segala macam teori metafisika, namun pada saat yang sama juga menyanggah keabsahan etika.
Dilihat dari sudut alur pemikiran positivism logis ini, Ghazali dan Kant, sekali lagi,
menunjukkan kesamaan alur pemikiran mereka. Setelah menyanggah teori matafisika,
keduanya malah menggaris bawahi betapa pentingnya etika dalam kehidupan manusia. Dalam
bidang etika, Ghazali dengan gambling menulis karya monumentalnya Ihya ‘Ulul al-Din juga
Mizan al-Amal sedang Kant menulis kritik der praktischen Vernunft serta kritik der
Urtbeilskraft.
Meskipun dalam penolakan teori metafisika, Ghazali dan Kahn menunjukkan segi-segi
persamaan, namun ketika mereka membangun teori etika mereka menunjukkan perbedaan
yang tajam. Ghazali membangun teori etika yang bersifat rasional.
Dalam sejarah pemikiran manusia, hal tersebut cukup unik dan menbarik untuk dikaji secara
mendalam mengingat Ghazali adalah tokoh pemikir produk abad pertengahan yang buah
pikirannya hingga kini masih hidup subur bahkan tertancap kuat dalam masyrakat sunni
Muslim, sedang Immanuel Kant adalah merupakan figure filsuf Barat di awal abad modern yang
buah pikirannya hingga kini masih menjadi topik hangat percaturan filosofis. Terlebih pokok
lagi pertanyaan yang sangat menggoda untuk dicari jawabnya: mengapa dasar pemikiran
filosofis yang semula sama-sama dirumuskan untuk menolak secara sistematis teori metafisika
–spekulatif, kemudian berujung pada pembentukan konsepsi etika yang berbeda?
Ada kecendedurangan sementara pihak beranggapan bahwa pendekatan “Mistik” pasti agamis.
Sedangkan , pendekatan “rasional” berkonotasi sekuler, alias bukan agamis. Setidaknya, dalam
kasus Immanuel Kant, penglihatan dan anggapan yang stereo-type seperti itu tidak mempunyai
landasan yang kuat.
Terdengar agak ganjil memang, karena justru formulasi etika Kant yang “rasional”ini malah
menempatkan postulasi “personal God” (tuhan), kehiduapan setelah mati (immortal-ity) serta
kebebasan (freedom) pada posisi sentral. Sedang Ghazali sendiri, juga menempatkan Tuhan
sebagai tujuan primernya, karena system etikanya mengau pada cinta Tuhan, bahkan
penglihatan Tuhan, lewat praktek-praktek ajaran mistik yang rumit berjenjang dan mengikat
secara ketat.
Jika hasil akhir kedua sistem etika ini berujung pada tujuan yang relatif sama, lalu apa urgensi
“dialog” pemikiran filosofis antara Ghazali dan Kant?
4. Metodologi Pendekatan yang Berbeda
Pada lapisan permukaan, antara Ghazali dan Kant memang tampak tidak mempunyai
perbedaan yang berarti karena mereka sama-sama menolak teori metafisika spekulatif dan
sama-sam memjunjung tinggi kekudusan Tuhan, tetapi arus gelombang yang ada dibawah
lapisan permukaan tersebut sangat berbeda. Metode pendekatan mereka dalam membedah dan
mengurai persoalan-persoalan ilosofis yang pelik asngat berbeda, untuk tidak mengatakn
berlawanan.
Dalam pemikiran etikanya, Ghazali menggunakan metode pendekatan yang bersifat Hypotesis,
Sedangkan Immanuel Kant menggunakan metode pendekatan yang bersifat Analitis.
Perbedaan metodologi pendekatan ini bukannya tidak mempunyai konsekuensi yang tajam
dalam andilnya membentuk system of thought (cara berpikir) bagi para pendukungnya ,
terutama jika kita kaitkan dengan konsekunsi kenyataan sosiologis yang menyertainya.
Jika kita melacak lebih jauh ke belkang, kita akan menemukan asal-usul perbedaan model
pendekatan tersebut. Usaha pelacakan ini perlu untuk mendapatkan jawaban yang tepat serta
memperoleh gambaran yang jernih mengapa etika Ghazali bersifat rasional. Ada titik kunci yang
menjadkan mereka mempunyai perbedaan persepsi tentang etika. Hal itu bisa dilihat dalam
kritik mereka terhadap teori metafisika. Ketika mereka menyusun argument untuk menolak
teori-teori metafisika , Kant dan Ghazali mempunyai konsep yang sangat berbeda tentang,
“kausalitas”. Mata rantai perbedaan ini akan mencuat kembali ketika mereka mempersoalkan
norma-norma etika yang bersifat universal (the idea of universality of ethical norms).
Secara serta merta Ghazali menolak konsepsi ksualitas yang disususn Ibn Sina, karena
kecenderungan konsepsi kasualitas Ibn Sina dan kawan-kawan filsuf Muslim aliran peripatetic
yang menepikan kemahakuasaan dan kehendak Tuhan. Banyak peneliti sekarang seperti
Michael E. Marmura, Majid Fakhri dan Fazlur Rahman memepertanyakan secara serius
konsepsi kausalitas Ghazali yang bersifat otomistis dan okkasional, terutama dalam kaitannya
dengan etos ilmu dan etos kerja dan bukan dalam kaitannya dengan kemahakuasaan Tuhan.
Tanpa disadari, konsepsi kausalitas Ghazali mengantarkannya pada benturan tembok dialektis.
Sadar akan adanya benturan dialektis ini, Imanuel Kant dapat mengarahkan bentuk rumusan
kasualitasnya sehingga tidak sampai terbentur pada tembok yang sam. Kalaupun Ghazali ada
pada pihak yang benar dalam benturan dialektis tersebut, tetapi dia tidak dapat member kondisi
yang favourable bagi manusia untuk berpkir secar serius , mencari , berpetualang untuk
menemukan dan merumuskan hokum kausalitas berdasarkan studi empiris terhadap alam dan
seluk beluk kehidupan pribadi dan social manusia.
Konsepsi kasualitas Ghazali berbenturan dengan konsepsi kasualitas Ibn Sina secara dialektis
seperti itu yang oleh Kant disebut dengan antinomy. Dalam benturan argument secara dialektis
seperti itu, kedua belah pihak merasa benar sendiri dan sampai-sampai tidak sempat member
peluang untuk munculnya alternative ketiga yang barang kali lebih menyejukkan dan
konstruktif.
Immanuel Kant bukannya tidak sadar dengan adanya kenyataan benturan ide seperti yang
dialami oleh Ghazali dan Ibn Sina. The antynomies of pure reasen menjelaskan panjang lebar
tentang hak ini. Benturan yang tidak terletakkan itu adalah sebagai akibat langsung dari bentuk
pemikiran dialektis yang ia sebut dalam The transcrendental Dialectic.
Kajian yang mendalam dalam bidang ini mengantarkan Kant oada suatu kesimpulan yang
strategis, yakni dengan cara membatasi tapal batas weilayah pengetahuan manusia. Menurut
Kant, pengetahuan manusia Cuma bisa sampai batas yang ia sebut “phenomena” bukan “
neomena”. Meskipun tidak sesofistikasi konsepsi Kant, budaya Muslim juga mempunyai
konsepsi yang agaknya parallel dengan apa yang dikemikakan Kant. Hadis Nabi yang menyebut
“Tafakkaru fi khalqi I-lahi wa la tafakkaru fi dzatihi” agaknya mirip dengan konsepsi Kant.
Orang bisa amengklaim, jika memang begitu hasil akhir pemikiran Kant, maka antara Ghazali
dan Kant tidak banyak berbeda. Tetapi penyelidikan kita masih bisa mengungkap aspek-aspek
pemikiran yang tidak dipunyai Ghazali tapi justru digarisbawahi oleh Kant. Agaknya, yang akan
digarisbawahi Kant ini juga tidak terdapat dalam konsepsi Mu”tazilah sekalipun.
Immanuel kant tidak berhenti sampai di sini. Dia mampu melompati pagar kesulitan
epistemologis yang selalu dihadapi manusia dan mengarahkannya kea rah yang lebih praktis
dan berdampak positif bagi pengembangan potensi manusia yang masih terpendam . ada lasan
kuat mengapa Kant mengambil langkah demikian. “Copernican Revolution” meberi inspirasi
kuat dan mempengaruhi jalan pikran kant. Daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk
beradu argumentasi Cuma untuk memeprtahankan ide yang oleh masing-masing pihak diyakini
dan dipertahankan kebenarannya secara mutlak, tanpa member manfaat yang nyata bagi
kehidupan manusia yang praktis, maka Kant lebih menggarisbawahi konsepsi yang
menekankan bahwa “hokum kasualitas” adalah merupakan jantung kehidupan lmu
pengetahuan, dan inti kehidupan etika dan agama serta sekaligus merupakan saripati dinamika
kehidupan pribadi dan social manusioa secara luas.
Hukum kausalitas bukannya hanya sekadar jatuh dari langit. Hokum kausalitas seperti itu lebih
banyak ditentukan factor subjektif manusia untuk merumuskannya. Tanpa campur tangan
manusia tidak mungkin terbentuk hokum kausalitas yang termanifestasikan dalam kaidah ilu
pengetahuan seperti yang kita saksikan seperti sekarang ini. Orang biasa melihat buah jeruk
atau apel selalu jatuh kebawah , tapi tanpa kreativitas subjektif manusia , tidak mungkin hokum
gravitasi seperti f=m.a, akan terbentuk seperti sekarang ini sudah tentu semua hukum
kausalitas bentukan manusia tersebut adalah tidak akn bersifat final, dan justru karena
statusnya yang tidak pernah final itu memberikan inspirasi kepada Thomas Kuhn menyusun
teori filsafat ilmu yang melawan arus. Rumusan Kuhn tentang adanya “normal sience”,
revolution ary science” dalam bukunya The Structure of Scientifik Revolutions merupakan
pertanda bahwa ilmu pengetahuan manusia yang berintikan hokum kausalitas yang ia bentuk
sendiri adlah tidak final dan tidak permanen.
Daripada berkutat pada ide Ghazali yang menekankan bahwa hokum kausalitas itu adalah
sepenuhnya hak momopoli Tuhan-di mana hal demikian oleh Kant sudah dianggap sebagai
“taken for granted”- Kant mencoba mengalirkan “genangan” benturan ide yang semata-mata
bersifat dialektis-spekulatif. Factor manusianya yang didorong oleh Kant untuk menemukan
dan merumuskan hokum kausalitas, lewat berbagai hasil kerja keras dan cucuran keringatnya
sendiri tanpa harus kehilangan nuansa kedalaman nilai religiusitasnya. (M. Amin
Abdullah,2003)
4 Sistem Etika Sebagai Cermin Pola Berpikir
Menurut para ahli etika modern, pada hakikatnya, etika tidaklah melulu bersangkut paut
dengan pengetahuan tentang “baik” dan “buruk”. Etika bukan Cuma terbatas pada
sisi”normatif”nya saja. Etika pada dasaarnya, menyangkut bidang kehidupan yang luas . Paling
tidak, seperti yang dikemukakan oleh Alasdair Macintyre, etika juga menyangkut analisis-
konseptual mengenal hubungan yang dinamis antara manusia sebagai subjek yang aktif dengan
pikiran-pikirannya sendiri, dengan dorongan dan motivasi dasar tingkah lakunya, dengan cita-
cita dan tujuan hidupnya serta dengan perbuatan-perbuatannya.
Kesemuanya itu mengandaikan adanya interaksi yang dinamis dan saling terkait antara yang
asatu dengan lainnya, lagi pula merupakan organisme yang hidup dan berlaku secara actual
dalam kehidupan pribadi dan sosial. Singkatnya, ada keterkaitan erta antara etika dan system
atau pola berpikir yang dianut oleh pribadi, kelompok atau masyarakat.
Sistem etika yang menempatkan manusia sebagai subjek atau pelaku yang aktif, dinamis,
kreatif, dan otonom sangat dikedepankan oleh Immanuel Kant, tanpa harus mngesampingkan
nilai kedalaman relijiusitas seseorang. Justru dalam konsepsi etika rasional Kant, inilah
kekuatan cengkeraman imanensi ajaran moral keagamaan teras tertancap kuat dalam hidup
keseharian manusia. Uraian Kant tentang antynomi of practical reason memberi landasan kuat
untuk hidup agamis, utamanya dalam menghadapi keputusan moral (moral despair).
Kekutan konsepsi etika rasional Kant, sebenarnya terletak dalam perbedaannya dengan
konsepsi etika yang dikemukakan Stoic, Epicurus dan para pemikir Yunani lainnya. Kant secara
eksplisit menjelaskan dalam Second Critique, bahwa konsepsi etika mereka tidak dapat
membedakan secara tegas antara “virtue” (kabaiakan tertinggi) yang bersifat conditioned, tak
bersyarat , otonom universal (berlaku untuk semua orangtanpa memandang perbedaan agama,
ras, suku atau bangsa) dan “happiness” (kebahagian) yang bersifat Conditioned , bersyarat ,
heteronom dan particular (berbeda antara yang diinginkan oleh orang yang stud an yang lain,
antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain). Dengan lain kata, hubungan antara Vertue
dan happiness tidak begitu jelas dalam konsepsi yang dikemukakan para pemikir yunanai.
Mereka cenderung untuk menyamaratakan saja antara keduanya. Paling banter, di antara
mereka hanya Aristoteleslah yang maju selangkah dengan cara membuat klasifikasi nilai-nila
mortal, seperti kebijaksanaan (wisdom), keberanian (courage), kesederhanaan (temperance),
dan keadilan (justice).
Klasifikasi Aristotesles ini pulalah, menurut penelitian Muhamed Ahmed Sherif, yang diikuti
Ghazali dengan disertai perubahan di sana sini. Disesuaikan dengan ajaran mistiknya. Dalam
klasifikasi ini tidak begitu jelas perbedaan antara nilai-nilai mana yang berfungsi sebagai
sumber air mata, dan mana yang cuma berfungsi sebagai aliran sungai yang bersal dari sumber
aslinya. Tidak jelas pula mana yang bersifat “universal “, yang berlaku dan mengikat nsemua
orang dan mana yang “particular” yang berlaku hanya pada sekelompok tertentu atau
nsegolongan orang saja. Juga tidak jelas mana yang “tujuan “ dan mana pula yang berfungsi
sebagai “alat”. Klasifikasi Aristoteles yang diikuti Ghazali ini tidak menyentuh persoalan ini
sama sekali.
Kahn membedakan secara tegas antara virtue (moraliches gut) yang bersifat universal ,
unconditioned, otonom , kategoris; dan happiness (physiches gut) yang bersifat particular
conditioned (bersyarat), heteronom dan hypothesis. Menurut Knat, keduanya tidak dapat
dicampuradukkan. Jant melihat bahwa virtue adalah ibarat sumber mata air yang tiada habis-
habisnya bagi happiness yang beraneka ragam itu. Bukan sebaliknya. Dan Kant lebih tajam lagi
pengamatannya dengan mengatakan bahwa hubungan antara keduanay adalah mengandaiakan
hubungan kausalitas. Yang pertama berfungsi sebagai landasan (ground), sedang yang kedua
Cuma sebagai “konsekuensi” yang menyertainya.
Tanpa adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk meraih “virtue”, maka happiness tidak
akan mempunyai kekuatan dan landasan yang kokoh dalam dirinya sendiri. Logikanya, bukan
karena adanya happiness yang selalu didambakan oleh banyak orang dan yang seringkali
bertentangan antara idola yang diinginkan oleh orang yang satu dengan orang yang lain, lalu
baru muncul kemudian virtue, tapi sebaliknya, karena adanya virtue-lah maka happiness dapat
menyrtainya. Bagi Kant, keduanya membentuk hubungan kausalitas yang sistematis. Jika
terpisah, maka happiness, apa pun bentuknya, akan kehilangan arah.
Happiness, menurut Kant, adalah heteronom, tidak otonom. Kebahagiaan (happiness) bagi
segolongan orang, dalam kenyataannya, memang berbeda dari sebagian golongan yang lain.
Ada orang yang memandang harta harta (ekonomi), ada yang kekuasaan (politik) atau status
sosial, ada yang wanita, anak, keluarga, dan ada pula yang ilmu sebagai indikasi diperolehnya
kebahagiaan.
Karena beraneka ragam demikian, maka tak satu pun dari mereka yang bisa dijadikan landasan
atau patokan tolok ukur untuk diperolehnya kebahagiaan dalam arti sesungguhnya. Bagi Kant,
ada sesuatu yang fundamental yang hilang begitu saja, jika happiness yang beraneka ragam itu
dijadikan penyebab dilakukannya suatu perbuatan . kehidupan etika menjadi chaos, tak teratur
karena berbenturannya antara nilai yang satu dengan lainnya.
Lantaran sifatnya heterogen dan tidak berdiri sendiri itulah maka Kant menolak untuk
dijadikan sebagai pedoman yang kokoh atau tolok ukur untuk diperolehnya kebahagiaan yang
sesungguhnya. Kant lebih memilih virtue (yang dalam budaya muslim disebut “Khairat” atau
“hasanab”) sebagai sumber motivasi daripada segala mavcam happiness (sa’adah) yang
heteronom tersebut. Virtue mengatasi segala aneka ragam happiness yang saling berbenturan
tadi.
Hubungan antara virtue dan happiness, menurut Kant, adalah kausal, dalam arti bahwa
hubungan itu mempunyai struktur yang transparan yang dapat ditangkap akal-budi manusia.
Tatanan hokum ini perlu dirumuskan dan dikontruksi oleh akal manusia sendiri. Ibarat adanya
kesemrawutan arus lalu lintas di sebuah kota, maka warga kota tersebut perlu “menciptakan”,
“merumuskan” dan “membangun” sendiri aturan lalu lintas untuk memperlancar arus
tranportasi. Tidak Cuma berhenti dis situ. Setelah dirumuskan, aturan-aturan itu perlu mereka
taati sendiri, jika mereka menginginkan tujuan mereka tercapai, yakni lancarnya arus lalu lintas
transportasi dalam kota tersebut.
Orang yang menginginkan virtue yang bersifat universal perlu bertindak dan berbuat aktif
untuk meraihnya dengan sekuat tenaga. Dalam usahanya itu, ia perlu sdelalu waspada akan
adanya kemungkinan benturan lalu lintas nilai-nilai happiness yang kadang tidak akur tadi;
juga perlu waspada akan timbulnya sikap berlebih-lebihan yang ekstrim. Dan siapa pun yang
berusaha sekuat tenga untuk mencapai virtue (khairat) dengan mentaati hokum-hukum
tertentu, dia boleh berharap meraih happiness apa pun bentuknya.
Disini titik berat etika rasional Kant untuk mulai kembali. Sistem ini mulai menggaris bawahi
perlunya manusia sebagai subjek bahwa untuk bertindak secara aktif, kreatif dan dinamis.
Virtue (khairat, hasanah) tidak akan datang dengan sendirinya, jika manusia sebagai pelaku
atau subjek tidak bertindak secara aktif, kreatif dan dinamis untuk meraihnya sendiri. Jika
sampai benturan antara nilai-nilai happiness yang heteronom dalam diri seseorang, yang
kadang bisa membuatnya kehilanagan arah tujuan, maka dia secara otonom diharapakan dapat
melerai benang kusut dal;am pikirannya sendiri, untuk dapat mengembalikan kepada arah yang
sebenarnya, lewat pemahaman nilai virtue yang trasendental tadi.
Dalam puncak kematangan sistem etika rasional Kant, dimensi ketuhanaan dan keagamaam
mulai menampakkan sosoknya secara nyata, Kant menghadapi kenyataan yang tidak bisa
dipikirnya. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, manusia menghadapi berbagai macam tindakan
dan perilaku yang amoral. Menghadapi kenyataan yang tidak bisa dihindari manusia kadang
tergoda untuk jatuh kedalam keputusan moral. Dia menjadi skeptik dan menyamaratakan saja
antara yang baik dan yang buruk.
Menghadapi keputusan moral yang akut itu, Kant hanya mempunyai satu alternatif yakni
percaya sepenuhnya kepada adanya Tuhan yang menjamin kokohnya sendi-sendi hukum dan
perbuatan moral. Lebih dari itu, Kant berkeyakinan bahwa justru adanya kenyataan hokum
moral yang universal, yang mengikat semua orang tanpa pandang bulu itulah yang menjadi
bukti otentik tentang keberadaan Tuhan. Dimensi ketuhanan ini yangn sebenranya mendorong
manusia untuk tidak begitu saja menyerah kalah kepada tuntutan keputasan moral. Dengan
adanay dimensi Tuhan ini, manusia lalu lebih memilih sikap berharap (raja) daripada sikap
putus asa (khauf).
Dalam Third Critique, Kant menonjolkan dimensi trust ketika member pengertian tentang
“faith”. Dalam titik kunci ini pulalah yang membedakan Kant dengan para filsuf Barat yang lain.
Dalam istilah trust, Kant menggarisbawahi adanya unsur hubungan personal antara Tuhan dan
manusia.
Dalam karyanya yang lain, Lectures on Ethics dia menerangakan bahwa “faith denotes trust in
God that be will supply our deficience in things beyond our power provided we have all within
our power”.
Penekanan adanya struktur yang trasparan, kemampuan akal untuk menemukan dan
merumuskannya serta perlunya mentaati hukum-hukum moral yang dirumuskan tersebut
merupakan ciri khas konsepsi etika Kant yang bersifat rasional. Bagi Kant kehidupan moralitas
manusia memang tidak banyak bedanya seperti kehidupan fisik dan organisme yang lain, di
mana di dalamnya ada struktur-struktur fundamental dan hukum-hukum tertentu yang perlu
dirumuskan dan ditemukan sendiri oleh manusia, yang kemudian untuk dipatuhi dan
dimafaatkan sendiri oleh mereka.
C. Kesimpulan
Tidak ada sistem etika yang sempurna. Menghadapi keputusan moral yang akut, Kant hanya
mempunyai satu alternatif yakni percaya sepenuhnya kepada adanya Tuhan yang menjamin
kokohnya sendi-sendi hukum dan perbuatan moral.
Anda mungkin juga menyukai
- TEOLOGI PEMBEBASANDokumen7 halamanTEOLOGI PEMBEBASANAbayz El HimmaBelum ada peringkat
- PLURALISME AGAMADokumen16 halamanPLURALISME AGAMAAli WardanaBelum ada peringkat
- 92-Article Text-110-1-10-20200114Dokumen30 halaman92-Article Text-110-1-10-20200114RusselBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Agama Agama 1Dokumen22 halamanMakalah Sejarah Agama Agama 1Cornelius KisaranBelum ada peringkat
- Apologetika Prasuposisional Triperspektivalisme John M. FrameDokumen19 halamanApologetika Prasuposisional Triperspektivalisme John M. FrameSilviaBelum ada peringkat
- 387 1758 1 PBDokumen17 halaman387 1758 1 PBYuliana BubuBelum ada peringkat
- TOKOH FilsafatDokumen6 halamanTOKOH FilsafatIchaansBelum ada peringkat
- EKSISITENSI DAN SUBSTANSI MANUSIA MENURUT ILMU PENGETAHUANDokumen43 halamanEKSISITENSI DAN SUBSTANSI MANUSIA MENURUT ILMU PENGETAHUANRebecca SBelum ada peringkat
- Filsafat ManusiaDokumen5 halamanFilsafat ManusiaPhiNo LupHt DindudBelum ada peringkat
- Eksistensialisme SartreDokumen10 halamanEksistensialisme SartreRiska MelaniBelum ada peringkat
- 17 12 15 NietzscheDokumen83 halaman17 12 15 NietzscheIkaBelum ada peringkat
- Perspektif Biblikal Toleransi Antara Umat BeragamaDokumen60 halamanPerspektif Biblikal Toleransi Antara Umat BeragamaFati AroBelum ada peringkat
- Perkembangan - Psikologi - Agama KLP 3Dokumen12 halamanPerkembangan - Psikologi - Agama KLP 3Rahmi FadilahBelum ada peringkat
- Pentingnya SyahadatDokumen4 halamanPentingnya SyahadatAm'alia Jassey TristyBelum ada peringkat
- Teladan Nabi MuhammadDokumen3 halamanTeladan Nabi MuhammadLinda Wahyu UtamiiBelum ada peringkat
- Konsep Anugerah Allah Dari CalvinismeDokumen38 halamanKonsep Anugerah Allah Dari CalvinismeDance DaimaBelum ada peringkat
- Pendekatan Psikologi Dalam Studi Islam AuliaDokumen12 halamanPendekatan Psikologi Dalam Studi Islam AuliaSiti NurainiBelum ada peringkat
- Sikap Beragama dan EtikaDokumen17 halamanSikap Beragama dan EtikaR9 S1 KeperawatanBelum ada peringkat
- AllahDokumen45 halamanAllahEzra SilalahiBelum ada peringkat
- SEJARAH AL-SALAFDokumen17 halamanSEJARAH AL-SALAFNovella IMBelum ada peringkat
- PERKEMBANGAN SKEPTISISMEDokumen3 halamanPERKEMBANGAN SKEPTISISMEretno purwaningsihBelum ada peringkat
- MODUL Filkom Sesi 3Dokumen21 halamanMODUL Filkom Sesi 3Safira SalamunBelum ada peringkat
- Hubungan Interpersonal KeluargaDokumen15 halamanHubungan Interpersonal KeluargaFahra Zainun Faqiha100% (1)
- Pengantar Kuliah Etika KristenDokumen11 halamanPengantar Kuliah Etika KristenNadia CeciliaBelum ada peringkat
- Teologi Plural Is Me John HickDokumen19 halamanTeologi Plural Is Me John HickDzikri AbadiBelum ada peringkat
- Makalah Analisis Isi Kelompok 1Dokumen14 halamanMakalah Analisis Isi Kelompok 1Cut002Belum ada peringkat
- PENYIMPULANDokumen37 halamanPENYIMPULANStefanyWijayaBelum ada peringkat
- NietzcheDokumen12 halamanNietzcheRatadiajo ManullangBelum ada peringkat
- Mengenal Agama-Agama Besar DuniaDokumen14 halamanMengenal Agama-Agama Besar Duniamawadddah rahmiBelum ada peringkat
- TaoismeDokumen8 halamanTaoismeRohmatun MLinaBelum ada peringkat
- Filsafat Abad PertengahanDokumen14 halamanFilsafat Abad PertengahanAnnisya MuthmainnahBelum ada peringkat
- REFLEKSI BULTMANNDokumen3 halamanREFLEKSI BULTMANNUchank LoboBelum ada peringkat
- TEOLOGISISTEMATIKADokumen2 halamanTEOLOGISISTEMATIKATim Skripsi0% (1)
- Aliran FilsafatDokumen11 halamanAliran Filsafatagfin89Belum ada peringkat
- INSTITUSI SOSIAL DAN AGAMADokumen15 halamanINSTITUSI SOSIAL DAN AGAMARATU FURY SYIFAUNNAFSI 2020Belum ada peringkat
- Peristiwa-Peristiwa KejiwaanDokumen9 halamanPeristiwa-Peristiwa KejiwaanWILDAN FAKIH100% (1)
- Biografi Sigmund FreudDokumen11 halamanBiografi Sigmund FreudDevi VebriantiBelum ada peringkat
- Konsep Dan Obyek Kajian SosiologiDokumen14 halamanKonsep Dan Obyek Kajian SosiologiHiqmatul WahdaBelum ada peringkat
- Hubungan antara Iman dan IbadahDokumen15 halamanHubungan antara Iman dan IbadahAlunaficha Melody KiraniaBelum ada peringkat
- TEORI DAN HIPOTESISDokumen11 halamanTEORI DAN HIPOTESISRiza AinurrahmanBelum ada peringkat
- AgamaDokumen11 halamanAgamaWadah KosongBelum ada peringkat
- Peran Umat Islam Dalam Perkembangan Filsafat Barat ModernDokumen5 halamanPeran Umat Islam Dalam Perkembangan Filsafat Barat ModernTsalsaBelum ada peringkat
- FILSAFAT PATRISTIK DAN TOKOH-TOKOHNYADokumen10 halamanFILSAFAT PATRISTIK DAN TOKOH-TOKOHNYAainun masyrifahBelum ada peringkat
- Faedah AgamaDokumen9 halamanFaedah AgamaIrfan AguztianBelum ada peringkat
- Logika Adalah Ilmu Pengetahuan Dan Kecakapan Untuk Berpikir LurusDokumen10 halamanLogika Adalah Ilmu Pengetahuan Dan Kecakapan Untuk Berpikir LurusArio RioBelum ada peringkat
- TUGAS 1 MK FILSAFAT ILMU (Ringkasan Buku)Dokumen11 halamanTUGAS 1 MK FILSAFAT ILMU (Ringkasan Buku)Shalomyta Monangin100% (1)
- 05 Kejahatan Tanpa AmpunDokumen22 halaman05 Kejahatan Tanpa AmpunMuhammad Firdaus100% (1)
- Antropologi PDFDokumen17 halamanAntropologi PDFKezia Cerla PantasBelum ada peringkat
- Pengertian Ilmu FilsafatDokumen22 halamanPengertian Ilmu Filsafatnabila munaBelum ada peringkat
- 2 Siapakah ManusiaDokumen28 halaman2 Siapakah ManusiaGilang PradanaBelum ada peringkat
- Mendamaikan Sains Dan AgamaDokumen3 halamanMendamaikan Sains Dan AgamamuhsasiBelum ada peringkat
- Naturalisme Humanisme Dan Eksistensialisme Problem Kejahatan Pluralitas AgamaDokumen22 halamanNaturalisme Humanisme Dan Eksistensialisme Problem Kejahatan Pluralitas AgamaAndika PrasetiawanBelum ada peringkat
- Dampak Media Sosial Bagi MahasiswaDokumen11 halamanDampak Media Sosial Bagi MahasiswaLutfi HakimBelum ada peringkat
- Ar RaziDokumen11 halamanAr RaziImam WahyudiBelum ada peringkat
- Filsafat ManusiaDokumen17 halamanFilsafat ManusiaGabriel Brilland HollandBelum ada peringkat
- SM 3 Argumen Filosofis Tentang Eksistensi TuhanDokumen14 halamanSM 3 Argumen Filosofis Tentang Eksistensi TuhanParluhutan SiregarBelum ada peringkat
- Psikologi AgamaDokumen19 halamanPsikologi AgamaZakia Pembela100% (1)
- Makalah TasawufDokumen17 halamanMakalah TasawufSarah VioletBelum ada peringkat
- Makalah KhilafiahDokumen24 halamanMakalah KhilafiahKurnia SeruyaningtyasBelum ada peringkat
- Tujuan Dan Manfaat Mempelajari EtikaDokumen10 halamanTujuan Dan Manfaat Mempelajari Etikaandre munthe67% (3)