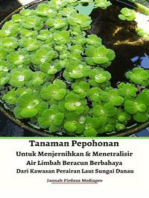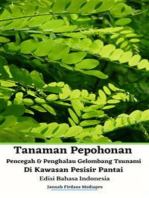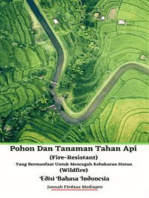Chapter III PDF
Chapter III PDF
Diunggah oleh
fadillaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Chapter III PDF
Chapter III PDF
Diunggah oleh
fadillaHak Cipta:
Format Tersedia
BAB II
TINJAUN PUSTAKA
2.1 Uraian Tumbuhan
2.1.1 Habitat
Tumbuhan srikaya (Annona reticulata L.) adalah tumbuhan yang tumbuh
di benua Amerika terutama kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan
juga di Asia tropis diantaranya Thailand, Malasia dan Indonesia. Di Indonesia
terdapat di berbagai daerah yang umumnya ditanam di pekarangan, dibudidayakan
dan mempunyai tinggi 2-7 meter (Rukmana,2002).
2.1.2 Morfologi
Ciri-ciri morfologi tumbuhan srikaya sebagai berikut (Yuniarti T, 2008):
Batang : Batang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah, kulit batang coklat
muda.
Daun : Daun srikaya bulat memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi rata,
panjang 6-17cm dan lebar 2,5-7,5 cm, tangkai daun pendek, tulang
daun menyirip, permukaan bawah agak kasar, permukaan daun
warnanya hijau, bagian bawah hijau kebiruan.
Bunga : Bunga tunggal, dalam berkas 1-2 berhadapan atau disamping daun,
dasar bentuk tugu (tinggi), benang sari berjumlah banyak.
Buahnya : Buahnya berbentuk bola atau kerucut, permukaan berbenjolbenjol,
warnanya hijau berserbuk putih, jika sudah masak anak buah akan
memisahkan diri satu dengan yang lainnya, daging buah berwarna
putih, rasanya manis, bijinya berwarna hitam mengkilap.
19
Universitas Sumatera Utara
2.1.3 Sistematika Tumbuhan
Divisio : Spermatophyta
Sub division : Angiospermae
Kelas : Dycotyledonae
Bangsa : Ranunculales
Suku : Annonaceae
Marga : Annona
Jenis : Annona reticulata L.,
2.1.4 Nama Daerah
Nama daerah dari tumbuhan srikaya adalah sebagai berikut: Delima
bintang, serikaya (Sumatera), sarikaya, srikaya, serkaya (Jawa), sarikaya
(Kalimantan), sirikaya, delima srikaya (Sulawesi), atisi (Maluku). (Yuniarti T,
2008)
2.1.5 Kandungan kimia
Akar dan kulit srikaya mengandung senyawa flavonoid, borneol,
camphor, terpen dan alkaloid, disamping itu akarnya juga mengandung saponin,
tannin dan polifenol. Biji mengandung minyak, resin, dan bahan beracun yang
bersifat iritan. Buah mengandung asam amino, gula buah dan mucilago (Anonim
2010).
2.1.6 Khasiat Tumbuhan
Akar berkhasiat sebagai antiradang, antidepresi, daun berkhasiat sebagai
astringen, antelmentik, antiradang, mempercepat pematangan bisul, asbes, kudis,
luka, borok dan ekzema. Biji berhasiat memacu encim pencernaan, antelmentikum
20
Universitas Sumatera Utara
dan insektisida. Kulit kayu berkhasiat astringen dan tonikum. Buah muda
berkhasiat sebagai disentri dan gangguan pencernaan.
2.2 Ekstraksi
Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut
sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Senyawa
aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam
golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid dan lain-lain. Diketahuinya senyawa
aktif yang dikandung oleh simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut dan
cara ekstraksi yang tepat. Simplisia yang lunak seperti rimpang dan daun mudah
diserap oleh pelarut, karena itu pada proses ekstraksi tidak perlu diserbuk sampai
halus. Simplisia yang keras seperti biji, kulit kayu dan kulit akar susah diserap
oleh pelarut, karena itu perlu diserbuk sampai halus (Depkes, 2000).
Menurut Depkes (2000), ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara.
1. Maserasi
Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan cara perendaman
menggunakan pelarut dengan pengadukan pada temperatur kamar. Maserasi
yang dilakukan pengadukan secara terus menerus disebut maserasi kinetic
sedangkan yang dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan
penyarian terhadap maserat pertama dan selanjutnya remaserasi.
2. Perkolasi
Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna,
umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prosesnya terdiri dari beberapa
tahapan, yaitu pengembangan bahan, maserasi antara, dan perkolasi sebenarnya
(penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh perkolat.
21
Universitas Sumatera Utara
3. Refluks
Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama
waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya
pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama
sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.
4. Sokletasi
Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya
dilakukan menggunakan alat khusus, sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan
jumlah pelarut relatif konstan dan adanya pendingin balik.
5. Digesti
Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang
lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu 40-500C.
6. Infuns
Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana
infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-980C)
selama waktu tertentu biasanya 15-20 menit.
7. Dekok
Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (> 30omenit) dan
temperatur sampai titik didih air.
2.3 Gel
Gel didefenisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari
suatu dispersi yang tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau moleikul
organik yang besar dan saling diresapi cairan. Gel umumnya merupakan suatu
sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya dan mengandung zat aktif,
22
Universitas Sumatera Utara
merupakan dispersi koloid mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan
yang saling berikatan pada fase terdispersi. Makromoleikul pada sediaan gel
disebarkan keseluruh cairan sampai tidak terlihat ada batas diantaranya, disebut
dengan gel satu fase. Jika massa gel terdiri dari kelompok-kelompok partikel kecil
yang berbeda maka gel ini dikelompokkan dalam dua fase (Ansel 1989).
Polimerpolimer yang biasa digunakan untuk membuat gelgel farmasetik
meliputi gom alam tragakan, pectin, karagen, agar, asam alginat, serta bahan
bahan sintesis dan semi sintesis seperti metil selulosa, hidroksimetilselulosa,
karboksimetilselulosa, dan karbopol yang merupakan polimer vinil sintesis
dengan gugus karboksil yang terionisasi. Gel dibuat dengan proses peleburan atau
diperlukan suatu prosedur khusus berkenaan dengan sifat mengembang dari gel
(Lachman., dkk, 1994).
Dasar gel yang umum digunakan adalah gel hidrofobik dan hidrofilik.
1. Dasar gel hidrofobik
Dasar gel hidrofobik umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik.
Bila ditambahkan kedalam fase pendispersi, hanya sedikit sekali interaksi
antara kedua fase. Berbeda dengan hidrofilik, bahan hidrofobik tidak
secara spontan menyebar tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang
khusus (Ansel, 1989).
2. Dasar gel hidrofilik umumnya terdiri dari moleikul organik dari fase
pendispersi. Istilah hidrofilik berarti suka pada pelarut (air). Umumnya
daya tarik menarik pada pelarut bahan-bahan hidrofilik kebalikan dari
tidak adanya daya tarik menarik dari bahan hidrofobik. Sistem koloid
hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang
23
Universitas Sumatera Utara
lebih besar (Ansel, 1989). Gel hidrofilik umumnya mengandung
komponen bahan pengembang, air, humektan dan bahan pengawet
(Voigt,1994).
Keuntungan sediaan gel :
Beberapa keuntungan sediaan gel (Voight, 1994) adalah sebagai berikut:
Kemampuan penyebarannya baik pada kulit
Efek dingin, yang dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit
Tidak ada penghambatan fungsi rambut secara fisiologis
Kemudahan pencuciannya dengan air baik
Pelepasan obatnya baik.
Tingginya kandungan air dalam sediaan gel dapat menyebabkan terjadinya
kontaminasi mikrobial, yang secara efektif dapat dihindari dengan penambahan
bahan pengawet. Untuk upaya stabilisasi dari segi mikrobial disamping
penggunaan bahan-bahan seperti balsam, khususnya untuk basis in sangat cocok
pemakaian metil dan propil paraben yang umumnya disatukan dalam bentuk
larutan pengawet. Upaya lain yang dilakukan adalah perlindungan terhadap
penguapan yaitu untuk menghindari masalah pengeringan. Oleh karena itu untuk
menyimpannya lebih baik menggunakan tube. Pengisian kedalam botol, meskipun
telah tertutup baik tetap tidak menjamin perlindungan yang memuaskan (voigt,
1994).
2.3.1 Hidroksi propil metilselulose (HPMC)
HPMC merupakan turunan dari metilselulosa yang memiliki ciri-ciri
serbuk atau butiran putih, tidak memiliki bau dan rasa. Sangat sukar larut dalam
eter, etanol atau aseton. Dapat mudah larut dalam air panas dan akan segera
24
Universitas Sumatera Utara
menggumpal dan membentuk koloid. Mampu menjaga penguapan air sehingga
secara luas banyak digunakan. HPMC digunakan sebagai agen pengemulsi, agen
pensuspensi dan sebagai agen penstabil pada sediaan topikal seperti gel dan salep.
Sebagai koloid pelindung yang dapat mencegah tetesan air dan partikel dari
penggabungan atau agromerasi, sehingga menghambat pembentukan sedimen
(Rowe., dkk, 2005).
Gambar 1. Struktur kimia hidroksipropilmetilselulosa (HPMC) (Nisperos
Carriedo dalam Krochta et al., 1994)
2.3.2 Propilen glikol
Propilen glikol banyak yang digunakan sebagai pelarut dan pembawa
dalam pembuatan sediaan farmasi dan kosmetik, khususnya untuk zat-zat yang
tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air. Propilenglikol adalah cairan bening,
tidak berwarna kental dan hampir tdak berwarna, kental dan hampir tidak berbau.
Memiliki rasa manis sedikit tajam menyerupai gliserol. Dalam kondisi biasa
propilen glikol stabil dalam wadah yang tertutup baik, dan juga merupakan suatu
zat kimia yang stabil bila dicampur dengan gliserin, air dan alkohol.
Propilenglikol juga digunakan sebagai penghambat pertumbuhan jamur. Data
25
Universitas Sumatera Utara
klinis telah menunjukkan reaksi iritasi kulit pada permukaan propilen glikol
dibawah 10% dan dermatitis dibawah 2%. (Loden, 2009).
H H H
H C C C H
H H H
Gambar 2. Rumua bangun propilenglikol (Rowe.,dkk, 2005).
2.3.3 Metil paraben
Metil paraben memiliki ciri-ciri serbuk hablur halus, berwarna putih,
hampir tidak berwarna dan tidak mempunyai rasa kemudian agak membakar
diikuti rasa tebal (Depkes, 1979; Rowe.,dkk, 2005).
O OCH3
OH
Gambar 3. Rumus bangun Metil Paraben (Rowe., dkk, 2005)
Metil paraben banyak digunakan sebagai antimikroba dalam kosmetik,
prodak makanan dan formulasi farmasi dan baik digunakan dalam kombinasi
dengan antimikroba lain. Metil paraben meningkatkan aktivitas antimikroba
dengan panjangnya rantai alkil. Namun dapat menurunkan kelarutan terhadap air
sehingga paraben sering dicampur dengan bahan tambahan yang berfungsi
26
Universitas Sumatera Utara
meningkatkan kelarutan. Kemampuan pengawet metil paraben ditingkatkan
dengan penambahan propilenglikol (Rowe.,dkk, 2005).
2.4 Nata De Coco
Nata adalah produk hasil fermentasi menggunakan mikroba Acetobacter
xylinum. Nata dapat dibuat dengan menggunakan bahan baku air kelapa, limbah
air tahu, limbah industri nanas. Nata de coco adalah nata yang dibuat dengan
bahan baku air kelapa, sebenarnya tidak memiliki rasa, namun karena diolah
menjadi minuman dengan tambahan bahan-bahan perasa maka produk yang
dihasilkan mempunyai rasa yang enak (Suryani dkk, 2005). Nata de coco berasal
dari Filipina, kata coco berasal dari Cocos nucifera, nama latin dari kelapa.
Sementara nama nata diambil dari nama tuan Nata yang telah berhasil
menciptakan nata de coco. Nata de coco memiliki bentuk padat, berwarna putih
seperti kolang-kaling dan terasa kenyal, yang mengandung air cukup banyak
(80%), dan dapat disimpan lama. Nata de coco mengandung nilai nutrisi yang
cukup banyak (Warisno, 2004). Seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Kandungan nutrisi nata de coco
No. Nutrisi Kandungan Nutrisi (per 100 gram bahan)
1 Kalori 146 kal
2 Lemak 0,2 %
3 Karbohidrat 36,1 mg
4 Kalsium 12 mg
5 Fosfor 2 mg
6 Fe (zat besi) 0,5 mg
Nata de coco adalah selulosa bakteri yang merupakan hasil sintesa dari
gula oleh bakteri pembentuk nata yaitu Acetobakter xylinum (Wahyudi, 2003).
Bakteri Acetobacter xylinum dapat merubah gula sebesar 19% pada medium
menjadi selulosa. Selulosa yang terbentuk dalam media tersebut berupa benang-
benang yang membentuk jalinan-jalinan yang akan menebal menjadi lapisan nata.
27
Universitas Sumatera Utara
Aktivitas pembuatan nata hanya terjadi pada kisaran pH antara 3,5-7,5. Sedangkan
pH optimum untuk pembentukan nata adalah 4. Suhu yang memungkinkan untuk
pembentukan nata adalah pada suhu kamar antara 28-32oC (Multazam, 2009).
Beberapa industri telah menggunakan selulosa bakteri, misalnya Sony
Corporation mengembangkan audio pembicara (Headphone) dengan
menggunakan selulosa bakteri. Pada awal 1980-an Johnson & Johnson
menggunakan selulosa bakteri sebagai pembawa obat dan perawatan luka.
Ajinomoto Co bersama dengan Mitsubishi Paper Mills di Jepang juga
mengembangkan selulosa bakteri untuk produk kertas (Brown, 1989).
2.5 Kulit
Kulit merupakan organ besar yang berlapis-lapis, menutupi permukaan lebih
dari 20.000 cm2 yang mempunyai bermacam-macam fungsi dan kegunaan.
Merupakan jaringan pelindung yang lentur dan elastis, melindungi seluruh
permukaan tubuh dan mempunyai berat 5% dari berat total badan. Secara anatomi,
kulit terdiri dari banyak lapisan jaringan, tetapi pada umumnya kulit dibagi dalam
tiga lapisan jaringan yaitu: epidermis, dermis dan hipodermis (Lachman, dkk,
1994).
Lapisan epidermis terdiri atas :
1. Stratum korneum (lapisan tanduk)
Stratum korneum adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas
beberapa sel yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah
menjadi keratin (zat tanduk).
2. Stratum lusidum
28
Universitas Sumatera Utara
Stratum lusidum terdapat langsung di bawah stratum korneum, merupakan
lapisan sel tanpa inti.
3. Stratum granulosum
Statum granulosum merupakan 2 atau 3 lapis sel dengan sitoplasma
berbutir kasar dan terdapat inti sel diantaranya.
4. Statum granulosum terdiri atas beberapa sel berbentuk poligonal.
5. Stratum basalis terdiri atas selsel kubus yang tersusun vertikal dan
berbaris seperti pagar ( palisade ). (Acherman, 1987).
Dermis atau korium merupakan serabut kolagen yang bertanggung jawab
untuk sifatsifat penting dari kulit. Dermis mengandung pembuluh darah,
pembuluh limfe, folikel rambut, kelenjar lemak, kelenjar keringat, otot dan
serabut saraf (Anief, 2000).
Lapisan sub kutan (hipodermis) merupakan lapisan kulit yang terdalam.
Lapisan ini terutamanya adalah lapisan adipose, yang memberikan bantalan dan
isolator panas (Anief 2000).
2.5.1 Fungsi kulit
Kulit menutupi dan melindungi permukaan tubuh dan bersambung dengan
selaput lender yang melapisi rongga-rongga dan lubang masuk. Kulit mempunyai
banyak fungsi yaitu di dalamnya tedapat ujung saraf peraba, membantu mengatur
suhu dan mengendalikan hilanggnya air dari tubuh, juga mempunyai sedikit
ekstori, sekretori dan absorbs (Pearce, 2004).
2.5.1 Kulit merupakan organ terbesar yang meliputi bagian luar dan dari seluruh
tubuh dan juga membentuk pelindung terhadap lingkungan. Bagian luar yang kuat
dan kering menandakan sifat fisik kulit. Morfologi dan ketebalan kulit berbeda
29
Universitas Sumatera Utara
pada setiap bagian tubuh. Kulit mempertahankan karakterisasi fisiko kimia seperti
struktur, suhu, pH dan keseimbangan oksigen dan karbondioksida. Sifat asam dari
kulit ditemukan pertama sekali oleh Heus pada tahun 1882 dan kemudian
disahkan oleh Schade dan Marchionini pada tahun 1928, yang dianggap bahwa
keasaman digunakan sebagai pelindung dan menyebutnya sebagai pelindung
asam dan beberapa literature saat ini menyatakan bahwa pH permukaan kulit
sebahagian besar asam antara 5,4 dan 5,9.
Sebuah variasi permukaan pH kulit terjadi pada setiap orang karena tidak
semua permukaan kulit orang terkena kondisi yang sama seperti perbedaan cuaca.
Banyak penelitian mengatakan bahwa pH kulit alami adalah pada rata-rata 4,7 dan
sering dilaporkan bahwa pH kulit antara 5,0 dan 6,8, pH permukaan kulit tidak
hanya bervariasi di lokasi yang berbeda, tetapi dapat juga mempengaruhi profil
pH di stratum corneum. (Ansari.,dkk, 2009).
2.6 Absorpsi Obat Melalui Kulit
Tujuan utama penggunaan obat topikal pada terapi adalah untuk menghasilkan
efek teraupetik pada tempattempat spesifik di jaringan epidermis dan dermis,
sedangkan obatobat topikal tertentu seperti emoliens ( pelembab), antimikroba
dan deodorant terutama bekerja di permukaan kulit saja. Hal ini memerlukan
penetrasi difusi dari kulit atau absorbsi perkutan (Lachman, dkk., 1994).
Absorbsi obat melalui kulit umumnya disebabkan oleh penetrasi langsung
obat melalui stratum korneum yang terdiri dari kurang lebih 40% protein
(umumnya keratin) dan 40% air. Stratum korneum sebagai jaringan keratin
bersifat semi fermiabel dan moleikul obat berpenetrasi dengan cara difusi pasif.
30
Universitas Sumatera Utara
Jumlah obat dapat menyebrangi lapisan kulit tergantung pada konsentrasi
obat, kelarutannya dalam air. Bahanbahan yang mempunyai sifat larut dalam
keduanya minyak dan air merupakan bahan yang baik untuk difusi melalui
stratum korneum seperti epidermis dan lapisan- lapisan kulit.
Penetrasi obat kedalam kulit dengan cara difusi adalah melalui :
a. Penetrasi transeluler (menyebrangi sel)
b. Penetrasi intraseluler (antarsel)
c. Penetrasi transappendageal yaitu melalui folikel rambut, keringat, dan
kelenjar lemak (Ansel, 1989).
Faktor-faktor yang mempengaruhi penetrasi kulit sangat bergantung dari
sifat fisika kimia obat dan juga bergantung pada zat pembawa, pH dan
konsentrasi. Perbedaan fisiologis melibatkan kondisi kulit yakni apakah kulit
dalam keadaan baik atau terluka, umur kulit, perbedaan spesies dan kelembaban
yang dikandung oleh kulit (Lachman, dkk., 1994).
2.7 Luka
Luka merupakan rusaknya sebahagian dari jaringan tubuh. Luka sering sekali
terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan penyebabnya luka dapat dibagi
atas karena zat kimia, luka termis dan luka mekanis. Pada luka mekanis
berdasarkan luka yang terjadi bervariasi bentuk dan dalamnya, sesuai dengan
benda yang mengenainya.
Terminologi luka yang dihubungkan dengan waktu penyembuhan dapat dibagi
menjadi :
Luka akut : Luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep
penyembuhan yang telah disepakati. Kriteria luka akut adalah luka
31
Universitas Sumatera Utara
baru, mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang
diperkirakan, contoh : Luka sayat, luka bakar, luka tusuk.
Luka kronis : Luka yang mengalami kegagalan setelah penyembuhan,
dapat karena factor eksogen. Pada luka kronik luka gagal sembuh pada
waktu yang diperkirakan, tidak berespon baik terhadap terapi dan
punya tendensi untuk timbul kembali, contoh : ulkus dekubitus, ulkus
diabetic, ulkus venous dan lain-lain (Prabakti Yudhi, 2005).
2.8 Penyembuhan Luka
Penyembuhan luka dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan infeksi adalah sebab
yang paling penting dari penghambatan penyembuhan luka karena infeksi
mengakibatkan inflamasi dan dapat menyebabkan cidera jaringan. Rangsangan
eksogen dan endogen dapat menimbulkan kerusakan sel selanjutnya memicu
reaksi vaskuler kompleks pada jaringan ikat yang ada pembuluh darahnya. Reaksi
inflamasi berguna sebagai proteksi terhadap jaringan yang mengalami kerusakan
untuk tidak mengalami infeksi meluas tak terkendali. Proses inflamasi sangat
berhubungan erat dengan penyembuhan luka. Tanpa adanya inflamasi tidak akan
terjadi proses penyembuhan luka, luka akan tetap menjadi sumber nyeri sehingga
proses inflamasi dan penyembuhan luka akan cendrung menimbulkan nyeri.
(Anonim 2010)
Proses penyembuhan luka dibagi dalam tiga fase yaitu fase inflamasi
poliferasi dan penyudahan yang merupakan penyerupan kembali (remodeling)
atau maturasi jaringan.
32
Universitas Sumatera Utara
1. Fase infamasi
Fase inflamasi berlangsung sejak terjadinya luka sampai hari
kelima. Pembuluh darah yang terputus pada luka menyebabkan
pendarahan, dan tubuh akan berusaha menghentikannya dengan
vasokontriksi. Pengerutan pembuluh yang terputus dan reaksi hemostatis.
Hemostatis tejadi karena trombosit yang keluar dari pembuluh darah saling
melengket dan bersamaan dengan jalan fibrin yang terbentuk membekukan
darah.
Sel mast dalam jaringan ikat menghasilkan serotonin dan histamin
yang meningkatkan fermiabilitas kapiler sehingga terjadi eksudasi cairan,
pembentukan sel radang disertai vasodilatasi setempat menyebabkan
pembengkakan.
2. Fase poliferasi
Fase poliferasi disebut juga fibroflasia karena yang menonjol adalah
proses poliferase fibrolas. Fase ini berakhir dari akhir fase inflamasi
sampai kirakira akhir minggu ketiga. Pada fase ini serat kolagen yang
mempertahankan tepi luka.
3. Fase penyudahan
Pada fase ini terjadi proses pematangan yang terdiri dari penyerapan
kembali jaringan yang berlebih dan pembentukan jaringan baru, Fase ini
dapat berlangsung berbulanbulan dan dinyatakan berakhir kalau semua
tanda radang sudah lenyap. Tubuh berusaha menormalkan kembali semua
yang menjadi abnormal karena proses penyembuhan (Sjamsuhidajat dan
Wim, 1997).
33
Universitas Sumatera Utara
Penyembuhan luka merupakan suatu proses penggantian jaringan yang
mati atau rusak dengan jaringan baru oleh tubuh dengan jalan regenerasi. Luka
dikatakan sembuh apabila permukaannya dapat bersatu kembali dan didapatkan
kekuatan jaringan yang mencapai normal. Setiap kejadian luka, mekanisme tubuh
akan mengupayakan mengembalikan komponen-komponen jaringan yang rusak
tersebut dengan membentuk struktur baru, dan fungsional sama dengan keadaan
sebelumnya. Proses penyembuhan tidak hanya terbatas pada proses regenarasi
yang bersifat lokal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh factor endogen seperti
umur, nutrisi, imunologi, pemakaian obat-obatan dan kondisi metabolik (Anonim
2010).
34
Universitas Sumatera Utara
Anda mungkin juga menyukai
- Bab 2 GelDokumen20 halamanBab 2 Gelella_alaydrusBelum ada peringkat
- BAB II Tinjauan PustakaDokumen11 halamanBAB II Tinjauan Pustakaalmashuri2Belum ada peringkat
- Laporan Lengkap Tekbal SirupDokumen23 halamanLaporan Lengkap Tekbal SirupSri HastantyBelum ada peringkat
- ID Strategi Pemasaran Perusahaan Tahu Studi Kasus Tahubulu Laga Di Kecamatan LembahDokumen20 halamanID Strategi Pemasaran Perusahaan Tahu Studi Kasus Tahubulu Laga Di Kecamatan LembahM SyauqiBelum ada peringkat
- Maserasi B1.1Dokumen9 halamanMaserasi B1.1AjengLstr10Belum ada peringkat
- Bab 2Dokumen13 halamanBab 2Doni AnandaBelum ada peringkat
- 1Dokumen20 halaman1rosi rahayu100% (1)
- Bab IiDokumen19 halamanBab IiYUSUBBelum ada peringkat
- Proposal P Senyawa Anti Kanker Dari MangroveDokumen8 halamanProposal P Senyawa Anti Kanker Dari MangroveMarmut AntiiqBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen16 halamanBab IidwindamalikazuhraBelum ada peringkat
- Fitokimia KunyitDokumen29 halamanFitokimia KunyitAlvian VianBelum ada peringkat
- Laporan EkstraksiDokumen15 halamanLaporan EkstraksiKaef Bdl03Belum ada peringkat
- GadarDokumen13 halamanGadarDesy RinawatyBelum ada peringkat
- Metode RefluksDokumen11 halamanMetode RefluksDessy UlhijrahBelum ada peringkat
- Proposal Proyek FTSF Gel SterilDokumen9 halamanProposal Proyek FTSF Gel SterilAstiAprilliaBelum ada peringkat
- Karakteristik GelDokumen14 halamanKarakteristik GellilisBelum ada peringkat
- Assainapratiwi 1118005681 Infundasi SementaraDokumen11 halamanAssainapratiwi 1118005681 Infundasi SementaraAssaina PratiwwiBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen13 halamanBab 2fitraBelum ada peringkat
- AntibakteriDokumen9 halamanAntibakteriNilla CNBelum ada peringkat
- Bab IIDokumen19 halamanBab IIadisstassyaBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTIKUM KOSMETIK (SEDIAAN GEL) - DikonversiDokumen20 halamanLAPORAN PRAKTIKUM KOSMETIK (SEDIAAN GEL) - DikonversiAulia Nurtafani ReformaBelum ada peringkat
- Nanoenkapsulasi Buah KecombrangDokumen10 halamanNanoenkapsulasi Buah KecombrangBellaBelum ada peringkat
- Laporan Daun Leilem Kimia OrganikDokumen19 halamanLaporan Daun Leilem Kimia OrganikSemuel HarpandiBelum ada peringkat
- Gel FIXDokumen5 halamanGel FIXmuhammadmufidBelum ada peringkat
- LengkuasDokumen15 halamanLengkuasAldianaMabrukahBelum ada peringkat
- Bab 2 SkripsiDokumen23 halamanBab 2 SkripsisheilaBelum ada peringkat
- 2 Bab 2Dokumen9 halaman2 Bab 2Henny monalisaBelum ada peringkat
- Fitokimia 1Dokumen19 halamanFitokimia 1danial isaBelum ada peringkat
- Kelompok 4 Farmasi Bahari-LamunDokumen21 halamanKelompok 4 Farmasi Bahari-Lamunzeby kurniantiBelum ada peringkat
- Bab II MellaDokumen26 halamanBab II MellaEmy OktavianiBelum ada peringkat
- C-2018 - 153-Muhammad Firdaus-JurnalDokumen19 halamanC-2018 - 153-Muhammad Firdaus-JurnalFyan VergarraBelum ada peringkat
- Bab 11Dokumen11 halamanBab 11Tubagus Adil AL AminBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Fitokimia Ekstraksi STF Muhammadiyah CirebonDokumen19 halamanLaporan Praktikum Fitokimia Ekstraksi STF Muhammadiyah CirebonIis SugiartiBelum ada peringkat
- Bab II CiplukanDokumen10 halamanBab II CiplukanTessa Putri DeniaBelum ada peringkat
- Pembagian Jurnal GelDokumen16 halamanPembagian Jurnal GelnikeBelum ada peringkat
- Adoc - Pub - Bab II Tinjauan PustakaDokumen12 halamanAdoc - Pub - Bab II Tinjauan Pustakaayu faidaBelum ada peringkat
- BAB V Heniii BDokumen17 halamanBAB V Heniii BHeni ApriyantiBelum ada peringkat
- Nur Hutami Bab IiDokumen10 halamanNur Hutami Bab IiMilka VerawatiBelum ada peringkat
- Kulit ManggisDokumen11 halamanKulit ManggisTessasilfia 29042019Belum ada peringkat
- Bab IiDokumen10 halamanBab IiReza FirmansyahBelum ada peringkat
- Daun Rambutan AcehDokumen14 halamanDaun Rambutan AcehlalaBelum ada peringkat
- Proposal Rahayu Paramita RasyidDokumen64 halamanProposal Rahayu Paramita RasyidrahayuBelum ada peringkat
- Bab Ii FixDokumen14 halamanBab Ii FixWahyudiprtmBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen9 halamanBab Iimrizkyal270Belum ada peringkat
- Laporan Partisi MutiaDokumen12 halamanLaporan Partisi MutiaMutiia AnggrainiBelum ada peringkat
- Dari HanifatiDokumen26 halamanDari HanifatiRESSA PERMATABelum ada peringkat
- Uas FitokimiaDokumen8 halamanUas FitokimiaTri Nanda PutraBelum ada peringkat
- Ekstraksi Umma PerbaikanDokumen24 halamanEkstraksi Umma PerbaikanPuput mopanggaBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen37 halamanBab 2Mahdhun ShiddiqBelum ada peringkat
- Laporan Uji Pelepasan Gel F4Dokumen29 halamanLaporan Uji Pelepasan Gel F4Umul Achmad NurullahBelum ada peringkat
- Sktiring TelangDokumen16 halamanSktiring TelangRio DwiBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Fitokimia Daun Kumis KucingDokumen37 halamanLaporan Praktikum Fitokimia Daun Kumis KucingBayu HarimuBelum ada peringkat
- Klasifikasi TaninDokumen20 halamanKlasifikasi TaninAisyah Noenk100% (1)
- Laporan FitofarDokumen32 halamanLaporan FitofarTri AnandaBelum ada peringkat
- Kemangi Ocimum BasilicumDokumen10 halamanKemangi Ocimum Basilicumcha0% (1)
- Proposal Masker KangkungDokumen20 halamanProposal Masker KangkungRamaza AlmeiraBelum ada peringkat
- Tanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauDari EverandTanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauBelum ada peringkat
- Tanaman Pepohonan Pencegah & Penghalau Gelombang Tsunami Di Kawasan Pesisir Pantai Edisi Bahasa IndonesiaDari EverandTanaman Pepohonan Pencegah & Penghalau Gelombang Tsunami Di Kawasan Pesisir Pantai Edisi Bahasa IndonesiaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (3)
- Teknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Dari EverandTeknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Pohon Dan Tanaman Tahan Api (Fire-Resistant) Yang Bermanfaat Untuk Mencegah Kebakaran Hutan (Wildfire) Edisi Bahasa IndonesiaDari EverandPohon Dan Tanaman Tahan Api (Fire-Resistant) Yang Bermanfaat Untuk Mencegah Kebakaran Hutan (Wildfire) Edisi Bahasa IndonesiaBelum ada peringkat