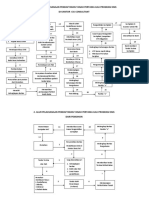Kasus Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Nabire
Diunggah oleh
raga dewwandanu putra utoyo0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
17 tayangan5 halamanJudul Asli
92042994-Kasus-Sengketa-Tanah-Ulayat-Di-Kabupaten-Nabire.docx
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
17 tayangan5 halamanKasus Sengketa Tanah Ulayat Di Kabupaten Nabire
Diunggah oleh
raga dewwandanu putra utoyoHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
KASUS SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN NABIRE, PAPUA
Sengketa tanah hak ulayat masyarakat persekutuan hukum adat di
Kabupaten Nabire berawal dari tuntutan masyarakat terhadap salah satu bagian
dari tanah-tanah yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanahnya pada tahun
1966, dimana diatas tanah tersebut telah dibangun Bandar Udara Nabire.
Berdasarkan Surat Keputusan bersama dari Kepala Kampung Oyehe bersama
seluruh rakyat Nabire, tertanggal 6 Mei 1966 No. 001/KPTS/5/1966 yang
berisikan penyerahan 3 (tiga) bidang tanah kepada Pemerintah dengan sukarela
tanpa menuntut ganti kerugian untuk kepentingan Proyek Pembangunan Nabire.
Tiga bagian tanah yang telah diserahkan secara sukarela oleh masyarakat Nabire
adalah :
1. 5 (lima) kilometer lebar terhitung dari sungai Oyehe melebar ke Timur
Kejurusan Napan-Weinami dan membujur panjang kedaratan sampai
dikaki Gunung Tinggi ± 150 (seratus lima puluh) kilometer.
2. 5 (lima) kilometer lebar terhitung dari sungai Nabire melebar ke Barat
kejurusan Kampung Hamuku dan membujur panjang ke daratan sampai di
Kaki Gunung Tinggi ± 150 (seratus lima puluh) kilometer.
3. Tanah-tanah yang dihimpit oleh sungai Oyehe dan Sungai Nabire ( tanah
yang terletak di antara sungai Oyehe dan Sungai Nabire), terhitung dari
pantai membujur panjang kedaratan sampai di kaki Gunung Tinggi ± 150
(seratus lima puluh) kilometer.
Surat pelepasan hak atas tanah tersebut telah disepakati oleh Kepala Adat
Suku Wate (Christian Waray) bersama dengan 14 suku yang berada dibawah
Suku besar Wate. Tanah-tanah yang telah melalui proses pelepasan hak atas tanah
tersebut saat ini telah menjadi ibukota Kabupaten Nabire, dimana diatas tanah-
tanah tersebut telah berdiri berbagai macam hak atas tanah dengan sertifikat tanah
sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kepastian hukum.
Dalam perkembangannya, salah satu bagian tanah yang telah dilepaskan
tersebut, dituntut oleh Suku besar Wate dan Suku Yeresiam agar diberi ganti rugi.
Bagian dari tanah yang di tuntut oleh Suku Wate dan Suku Yeresiam adalah
tanah yang saat ini berada dalam penguasaan Bandara Udara Nabire yang telah
bersertifikat atas nama Departemen Perhubungan cq. Bandar Udara Nabire
dengan perincian sebagai berikut :
Sertifikat No. 27/OYH/NBR/93 seluas 540.479 m²
Sertifikat No. 26/OYH/NBR/93 seluas 14.680 m²
Sertifikat No. 25/OYH/NBR/93 seluas 3.553 m²
Sertifikat No. HP.98/1988 seluas 4.717 m²
Belum Sertifikat seluas 20.500 m²
Luas Tanah Adat yang keseluruhnya seluas 583.929 m² terlebih dahulu
harus dikurangi dengan tanah milik MAF (Mission Aviation of Fellowship) seluas
11.811 m² dan tanah milik AMA (American Mission of Aviation) seluas 5.093 m²
sehingga luas Tanah Adat yang dituntut oleh masyarakat adat dan harus
dibayarkan oleh Bandara Udara Nabire sebagai bentuk kompensasi adalah seluas
571.525 m² dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh
ribu rupiah) per meter persegi atau sebesar Rp. 15.431.175.000,- (lima belas
milyar empat ratus tiga puluh satu seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan
pernyataan bahwa diatas tanah tersebut terdapat berbagai macam tanaman umur
pendek dan umur panjang yang merupakan hasil dari kegiatan bercocok tanam
masyarakat pada saat itu belum mendapat ganti kerugian. Sehingga sudah
sewajarnya pihak Bandara Udara memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada
masyarakat adat, sebagai bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Sebab pada
tahun 1966, masyarakat Adat Suku Wate telah memberikan tanah kepada negara
tanpa meminta ganti kerugian.
Pada saat proses pembangunan Bandar Udara Nabire yang dimulai pada
tahun 1948-1966, dimana pada saat itu pembukaan lahan Bandara dilakukan,
dengan mempekerjakan warga masyarakat Adat, pihak pemerintah Belanda tidak
membayar upah para pekerja tersebut (orang tua mereka), sehingga pihak Bandara
Udara perlu membayar kepada mereka sebagai bentuk kompensasi atas upah yang
belum dibayarkan pada waktu itu. Kemudian dalam proses pembangunan
Bandara Udara, mengakibatkan warga penggarap yaitu termasuk didalamnya
penebang, penggusur, pemukim yang berada di lokasi pembangunan Bandar
Udara Nabire harus keluar dari lokasi tersebut sehingga perlu adanya ganti
kerugian atas hilangnya mata pencaharian sehari-hari termasuk ganti kerugian
atas tanaman-tanaman baik umur pendek maupun umur panjang yang termasuk
didalam lokasi Bandar Udara Nabire. Hal ini yang menjadi dasar tuntutan warga
masyarakat Adat, sehingga pihak Bandara Udara sebagai pihak yang saat ini
menguasai dan berada di lokasi tersebut perlu membayar hak-hak masyarakat adat
yang seharusnya diterima oleh mereka.
Hal ini dikuatkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Adat Suku Wate
Nomor : Kep.01/BMASW/IX/2005 tentang Pembentukan Lembaga Kesaksian
Perintis Lapangan Bandar Udara Nabire yang berisi mengenai bukti penggarap,
penggusur, pekerja dilokasi Bandar Udara Nabire pada tahun 1948-1966 serta
saksi-saksi yang merupakan para tetua adat / orang tua yang masih ada dan hidup
mengetahui dengan pasti para penggarap, penebang,penggusur dan pekerja.
ANALISIS KASUS SENGKETA TANAH HAK ULAYAT DI KABUPATEN
NABIRE, PAPUA
Dari penjelasan sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire, Papua
dapat ditari beberapa alasan yang menyebabkan sengketa tersebut terjadi. Alasan-
alasan tuntutan terhadap pengelola Bandara Udara Nabire dipengaruhi oleh
beberapa faktor, antara lain :
1. Alasan Ekonomi
Beralihnya fungsi tanah dari fungsi sosial ke fungsi ekonomi seiring
dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat menimbulkan
ketidakpuasan masyarakat adat. Sebab pada saat pelepasan hak atas tanah
pada tahun 1966, yang dikuatkan dengan Surat Keputusan bersama dari
Kepala Kampung Oyehe bersama seluruh rakyat nabire, tertanggal 6 Mei
1966 No. 001/KPTS/5/1966 tentang penyerahan 3 (tiga) bidang tanah
kepada Pemerintah dengan sukarela tanpa menuntut ganti kerugian, telah
jelas disebutkan bahwa proses pelepasan hak atas tanah tersebut dilakukan
secara sukarela tanpa ganti kerugian. Oleh negara, tanah-tanah tersebut
kemudian diberikan kepada instansi-instansi maupun kepada
perseorangan. Proses pembangunan dan perkembangan masyarakat
membuat harga tanah semakin hari semakin meningkat, yang memberikan
keuntungan materi kepada pemiliknya. Hal ini yang memicu munculnya
tuntutan masyarakat adat, sebab pada saat itu tanah diserahkan secara
sukarela.
2. Kecemburuan Sosial
Tanah-tanah yang diserahkan kepada negara secara sukarela tanpa ganti
rugi tersebut, dalam perkembangannya telah beralih kepada perseorangan
dengan status Hak Milik, yang memberikan kewenangan kepada pemilik
tanah untuk mengalihkan tanahnya termasuk melalui jual beli, dimana
memberikan keuntungan bagi pemilik tanah tersebut. Hal ini menimbulkan
kecemburuan sosial, sebab pada tahun 1966, yaitu pada saat pelepasan hak
atas tanah dari masyarakat adat Suku Wate kepada Pemerintah,
masyarakat Adat tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk materi
seperti yang diperoleh pemilik tanah saat ini. Tuntutan masyarakat adat
juga terjadi terhadap aset dari Departemen Perhubungan Kabupaten Nabire
salah satunya adalah Pelabuhan Laut Samabusa. Hal ini menunjukkan
bahwa permasalahan tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire telah
mengalami perkembangan yang mengkhawatirkan, sebab pihak
masyarakat adat dalam kenyataannya hanya menuntut aset-aset tertentu
saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pemerintah Daerah
Kabupaten Nabire perlu bertindak tegas dengan tidak mentolerir segala
bentuk tuntutan masyarakat adat dikemudian hari, artinya setiap bentuk
tuntutan serta klaim dari pihak manapun termasuk pihak masyarakat adat
setempat khususnya terhadap tanah-tanah negara, harus diselesaikan dalam
koridor hukum yang berlaku, yaitu melalui jalur pengadilan, sehingga
penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, dan memberikan pelajaran
dari segi hukum bagi semua pihak.
Alasan penyebab sengketa tanah hak ulayat yang terjadi di Kabupaten
Nabire, Papau ini tidak lagi terjadi karena kecintaan masyarakat adat terhadap
tanahnya tetapi telah berubah kearah yang lebih kompleks dimana terjadinya
kecemburuan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat ke arah tingkatan
ekonomi. Masyarakt menggunakan kekuasaan dan hukum adat sebagai tameng
yang digunakan untuk menuntut pemerintah daerah dengan memeberikan ganti
rugi. Hukum adat disalah artikan tidak lagi sebagai bentuk kecintaan terhadapa
tanah milik adat tetapi untuk memperoleh keuntungan kelompok ataupun individu
tertentu.Perlunya penegakan hukum agraria di wilayah kabupaten Nabire dan
penjelasan lebiih lanjut pengertiaan hukum adat kepada masyarakat adat yang
menuntut hak ganti kerugikan. Mengubah kembali pola pikir masayarakat tersebut
kearah yang bener dengan memberikan pengertian dan arti sebenarnya hukum
adat.
Anda mungkin juga menyukai
- Soal UTS HUKUM PERUSAHAAN 3PPADokumen1 halamanSoal UTS HUKUM PERUSAHAAN 3PPARyo ArfinBelum ada peringkat
- Unud-1124-1414565835-Tesis Ni Made Irpiana PrahandariDokumen153 halamanUnud-1124-1414565835-Tesis Ni Made Irpiana PrahandariFrisco Binalay100% (1)
- Kontradiktur DelimitasiDokumen20 halamanKontradiktur DelimitasiSanti AzzahrahBelum ada peringkat
- Pencabutan Hak Atas TanahDokumen9 halamanPencabutan Hak Atas TanahMaratussholihah Tri Pujiastuti100% (1)
- Contoh Kasus Jual GadaiDokumen1 halamanContoh Kasus Jual GadaiIwan RachmantoBelum ada peringkat
- Sengketa Jual Beli Tanah AdatDokumen20 halamanSengketa Jual Beli Tanah AdatYogi Oktopianto100% (2)
- Hak-Hak Khusus para Ahli WarisDokumen13 halamanHak-Hak Khusus para Ahli WarisJunaidi HisyamBelum ada peringkat
- Hukum AgrariaDokumen2 halamanHukum AgrariatakipurwanegaraBelum ada peringkat
- Hukum Tata Guna TanahDokumen59 halamanHukum Tata Guna TanahPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)100% (1)
- Analisis Hukum Landreform Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Studi Redistribusi Tanah Di Kota Medan 2007-2008Dokumen183 halamanAnalisis Hukum Landreform Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. Studi Redistribusi Tanah Di Kota Medan 2007-2008PUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)100% (1)
- Bahan Ajar PTUNDokumen23 halamanBahan Ajar PTUNrangga galih20Belum ada peringkat
- Seputar Pertanyaan Tentang Notaris Dan PPATDokumen2 halamanSeputar Pertanyaan Tentang Notaris Dan PPATNickBelum ada peringkat
- Hak Menguasai NegaraDokumen17 halamanHak Menguasai NegaraMutiara Cecilya SamosirBelum ada peringkat
- Kasus Pembakaran Hutan Oleh PT Kallista Alam Dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum LingkunganDokumen25 halamanKasus Pembakaran Hutan Oleh PT Kallista Alam Dan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum LingkunganBarto Gees100% (9)
- Pendaftaran TanahDokumen30 halamanPendaftaran TanahNina ChanBelum ada peringkat
- Juknis Tanah TimbulDokumen56 halamanJuknis Tanah TimbulEunji JungBelum ada peringkat
- Bentuk Dan Substansi Perjanjian JaminanDokumen1 halamanBentuk Dan Substansi Perjanjian JaminanSriayu AriTha PanggabeanBelum ada peringkat
- LEGAL OPINION RevisiDokumen18 halamanLEGAL OPINION Revisimarchelia yusaBelum ada peringkat
- Hukum Agraria NasionalDokumen8 halamanHukum Agraria NasionalTesa_Ardiansya_1731Belum ada peringkat
- Hubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah NasionalDokumen4 halamanHubungan Antara Hukum Adat Dan Hukum Tanah Nasionaldian_hertzBelum ada peringkat
- Eksaminasi PERDATA NEW 1Dokumen18 halamanEksaminasi PERDATA NEW 1Hadi SugoroBelum ada peringkat
- Alur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Program SmsDokumen7 halamanAlur Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Program SmsTasrifin MuhammadBelum ada peringkat
- Made Ayu Citra Putri Sani - 1804551427 - HAM LANJUTANDokumen4 halamanMade Ayu Citra Putri Sani - 1804551427 - HAM LANJUTANcitraputrisani0% (1)
- Sengketa Status Dan Pemanfaatan Perairan Silala Antara Bolivia VS ChiliDokumen20 halamanSengketa Status Dan Pemanfaatan Perairan Silala Antara Bolivia VS Chilipapu'0% (1)
- Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di IndonesiaDokumen17 halamanSejarah Perkembangan Hukum Agraria Di IndonesiaAriqBelum ada peringkat
- Putusan Nomor 36 G 2017 Ptun SRG PDFDokumen30 halamanPutusan Nomor 36 G 2017 Ptun SRG PDFYoga S IrwandaBelum ada peringkat
- Analisa Putusan Arbitrase From JoeDokumen6 halamanAnalisa Putusan Arbitrase From JoeTupai Buye DtmBelum ada peringkat
- Buku AgrariaDokumen192 halamanBuku AgrariaAnisWilujengD'Behonkz100% (2)
- Tanah Adat BaliDokumen7 halamanTanah Adat BaliNgurah Agung Peranian100% (3)
- Tinjauan Pustaka Pembaharuan Agraria Di IndonesiaDokumen42 halamanTinjauan Pustaka Pembaharuan Agraria Di IndonesiaPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)Belum ada peringkat
- A. Domisili 1. Dasar Hukum Dan Pengertian DomisiliDokumen20 halamanA. Domisili 1. Dasar Hukum Dan Pengertian DomisiliTri AlfianBelum ada peringkat
- Perbandingan MOUdan PerjanjianDokumen9 halamanPerbandingan MOUdan Perjanjiancakfarid@gmail.comBelum ada peringkat
- Hi - Studi Kasus MV Saiga Case 1999Dokumen11 halamanHi - Studi Kasus MV Saiga Case 1999Nicholas PattersonBelum ada peringkat
- Hibah Diatur Oleh Pasal 1666 KUHPerdataDokumen7 halamanHibah Diatur Oleh Pasal 1666 KUHPerdataRinoFebriantoBelum ada peringkat
- Hak Atas Tanah MenurutDokumen4 halamanHak Atas Tanah MenurutAgussalim AddinBelum ada peringkat
- Naskah Akademik PKLDokumen23 halamanNaskah Akademik PKLsigit_m451112Belum ada peringkat
- Testament (Surat Wasiat)Dokumen14 halamanTestament (Surat Wasiat)mirandaBelum ada peringkat
- Konflik Tanah Di Hutan Pubabu: Masyarakat Adat Besipae VS Pemerintah Provinsi NTTDokumen11 halamanKonflik Tanah Di Hutan Pubabu: Masyarakat Adat Besipae VS Pemerintah Provinsi NTTheri28Belum ada peringkat
- Bukuphpu PDFDokumen162 halamanBukuphpu PDFMuhammad Ubbadah Al AlaBelum ada peringkat
- Pertemuan Ke-12 - Penatagunaan TanahDokumen10 halamanPertemuan Ke-12 - Penatagunaan TanahFather & SonBelum ada peringkat
- Surat GugatanDokumen4 halamanSurat Gugatandewi maesyarohBelum ada peringkat
- Makalah Agraria Pengadaan Tanah 1Dokumen16 halamanMakalah Agraria Pengadaan Tanah 1Prakoso Dewantoro100% (2)
- PLKH Perdata RevisiDokumen6 halamanPLKH Perdata RevisiAnis DwiBelum ada peringkat
- Makalah LelangDokumen22 halamanMakalah LelangNilna Firkhana SorayaBelum ada peringkat
- Kelompok 2 - PPT Hak TanggunganDokumen19 halamanKelompok 2 - PPT Hak TanggunganMaria DwinoverinBelum ada peringkat
- Tata Cara Memperoleh TanahDokumen18 halamanTata Cara Memperoleh TanahAldin Derilianto100% (1)
- Tugas Makalah Hukum Perdata InternasionalDokumen7 halamanTugas Makalah Hukum Perdata InternasionalRAY KEN100% (1)
- Akta Perjanjian Sewa RumahDokumen1 halamanAkta Perjanjian Sewa RumahTyas AndriansyahBelum ada peringkat
- Analisis Putusan Mahkamah AgungDokumen3 halamanAnalisis Putusan Mahkamah AgungMuhammad YahusafatBelum ada peringkat
- Background Somalia Vs KenyaDokumen6 halamanBackground Somalia Vs KenyaAprialdi SiagianBelum ada peringkat
- Perbedaan Antara PP No 10 Tahun 1961 Dan PP No 24 Tahun 1997Dokumen4 halamanPerbedaan Antara PP No 10 Tahun 1961 Dan PP No 24 Tahun 1997Vera100% (1)
- TUGAS Materi PHPU - Nadya SalsabilaDokumen6 halamanTUGAS Materi PHPU - Nadya SalsabilaNadya SalsabilaBelum ada peringkat
- Hukum Perikatan 07Dokumen24 halamanHukum Perikatan 07jesBelum ada peringkat
- Perjanjian Jual Beli MobilDokumen4 halamanPerjanjian Jual Beli MobilRismaHaryWardaniBelum ada peringkat
- Rechtsverwerking Dan Acquisitive Verjaring Ditinjau Dari Aspek Hukum Tanah NasionalDokumen8 halamanRechtsverwerking Dan Acquisitive Verjaring Ditinjau Dari Aspek Hukum Tanah NasionalCherrystBelum ada peringkat
- Contract DraftingDokumen6 halamanContract DraftingGladys OliviaBelum ada peringkat
- PP No 24 Tahun 1997 TTG PENDAFTARAN TANAHDokumen63 halamanPP No 24 Tahun 1997 TTG PENDAFTARAN TANAHHerman Andreij Adriansyah100% (3)
- Materi Kuliah 5Dokumen16 halamanMateri Kuliah 5Petta fachryBelum ada peringkat
- Tugas Agraria KireiDokumen6 halamanTugas Agraria KireiKirei Litvia U SBelum ada peringkat
- Final AgrariaDokumen3 halamanFinal AgrariaMasnatan MBelum ada peringkat