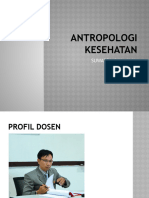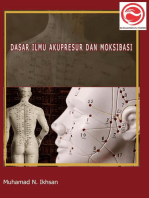KDK 3 Antropologi
KDK 3 Antropologi
Diunggah oleh
Juliana Rahmat0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan5 halamanJudul Asli
KDK 3 ANTROPOLOGI.docx
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan5 halamanKDK 3 Antropologi
KDK 3 Antropologi
Diunggah oleh
Juliana RahmatHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
KONSEP DASAR KEPERAWATAN
“ILMU PERKEMBANGAN MANUSIA ANTROPOLOGI”
DOSEN PENGAMPU :
Ns. Pipit Feriani, S.Kep, MARS
DISUSUN OLEH :
KELOMPOK 3
ANDRIANA DWI YUNITA 1911102411188
HERDA YANTI 1911102411135
JULIANA SAPUTRI 1911102411199
LUTFIA NOVI RAHMAWATI 1911102411139
NOVITA PUSPITASARI 1911102411155
SUGIONO 1911102411140
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS KESEHATAN DAN FARMASI
S1 ALIH JENJANG KEPERAWATAN
TAHUN 2019
A. Pengertian Antropologi
Antropologi Secara Etimologis Berasal Dari Kata Yunani, Yaitu
Anthropos Yang Berarti Manusia Dan Logos Yang Berarti Ilmu. Jadi
Antropologi Adalah Ilmu Yang Mempelajari Manusia. Menurut
Koentjaraningrat (1984) Mengatakan bahwa ilmu antropologi mempelajari
manusia dari aspek, sosial, budaya.
pengertian antropologi kesehatan menurut Anderson, antropologi
kesehatan mengakaji masalah-masalah kesehatan dan penyakit dari dua kutub
yang berbeda yaitu kutub biologi dan kutub sosial budaya. Antropologi
kesehatan menurut Weaver (1959) adalah cabang dari antropologi terapan yang
menangani berbagai aspek dari kesehatan dan menyakit.
Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa antrpologi adalah
ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisik serta kebudayaan (
cara berperilaku, tradisi-tradisi dan nilai-nilai) yang dihasilkan
B. Tujuan dan Fungsi Antropologi
Tujuan antropologi mengacu pendapat Koentjaraningrat (2009:5) adalah
sesuai dengan tahap perkembangan antropologi yang keempat, yaitu
antropologi memiliki dua tujuan. Pertama, tujuan akademis yakni berusaha
mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan
mempelajari berbagai bentuk fisiknya, masyarakat dan kebudayaannya. Kedua,
tujuan praktis yakni mempelajari manusia di berbagai masyarakat suku bangsa
di dunia guna membangun masyarakat itu sendiri.
Fungsi antropologi secara garis besar dinyatakan bahwa fungsi antropologi
adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik
(biologis) maupun secara sosio-kultural.
C. Manfaat Antropologi
Manfaat antropologi antara lain:
1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat
secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat
(suku bangsa)
2. Dapat mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan
harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang.
3. Dapat memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh
dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan sesuai dengan karakteristik
daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi.
4. Dapat mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki
kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil
inisiatif pemecahan masalah.
D.Ilmu Perkembangan Antropologi
Secara epistemologi, paradigma yang terdapat dalam antropologi
dibedakan menjadi dua, yakni paradigma positivisme dan paradigma
antipositivisme. Positivisme pertama kali dikembangkan oleh Comte, yaitu
suatu metode pengkajian ilmiah dan suatu tingkatan dalam perkembangan
pemikiran manusia (Saeffudin, 2005). Tahapan-tahapan perkembangan dalam
berpikir melalui tahap-tahap teologis, metafisika dan positivis. Pada tahap
teologis, fenomena dijelaskan dalam konteks entitas supranatural seperti roh
dan Tuhan. Dalam tahap metafisika eksplanasi dibangun dalam konsep-konsep
yang abstrak, kekuatan-kekuatan personifikasi dalam alam seperti hukum
moral. Selanjutnya, pada tahap positivisme, eksplanasi dinyatakan dalam
konteks hukum-hukum yang menghubungkan fakta satu dengan fakta yang
lain. Dalam pandangan para ahli antropologi penganut paradigma positivisme
fenomena sosial memiliki kemiripan dengan fenomena alam, yaitu memiliki
keteraturan, keterulangan dan dapat diprediksi. Oleh karena itu fenomena sosial
dapat diamati (observable) dan dapat diukur (measurable). Jika dalam
fenomena alam dapat dicari hukum-hukumnya, maka dalam fenomena sosial
pun dapat ditemukan hukum-hukumnya yang bersifat universal. Misalnya,
Teori-teori evolusi, Difusi, dan Fungsionalisme. Kritikan yang sangat keras
ditujukan pada para ahli yang tergabung dalam aliran 15 positivisme oleh ahli
antropologi yang beraliran antipositivisme. Clifford geertz adalah tokoh
penting dalam kelompok anti positivisme. Paradigma antipositivisme
berpandangan bahwa fenomena sosial berbeda dengan fenomena alam. Oleh
karena itu, gagasan-gagasan, teori-teori maupun metode-metode yang terdapat
dalam ilmu alam tidak dapat diterapkan begitu saja dalam ilmu sosial.
Mengapa? Paradigma antipositivisme berpendapat bahwa alam tidak dapat
memaknai dirinya sendiri, sedangkan manusia dapat memberikan pemaknaan
terhadap dirinya sendiri dan dunia sosialnya. Hal ini disebabkan manusia
adalah mahluk simbolik. Oleh karena itu tindakan manusia harus dipahami
dalam konteks sosialnya. Teori-teori yang termasuk dalam paradigma
antipositivisme antara lain Fenomenologi, interaksi simbolik, pertukaran sosial,
hemeneutik, semiotic, historisme, antropologi simbolik maupun
posmodernisme
DAFTAR PUSTAKA
Soerjasih, Indrijati. dkk.2017. Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
Jakarta. Kementriaan Pendidikan dan Kebudayaan.
Suari, I Gusti Ayu Gede. dkk. 2015. Konsep Antropologi Sosial Dan Antropologi
Kesehatan. Denpasar. Kementerian Kesehatan RI
Anda mungkin juga menyukai
- Antropologi Budaya Resume Ela Manis Cantik GemoyDokumen6 halamanAntropologi Budaya Resume Ela Manis Cantik GemoysanthetjurnalBelum ada peringkat
- Resume Konsep Dasar Antropologi KesehatanDokumen9 halamanResume Konsep Dasar Antropologi KesehatanChykita PutriBelum ada peringkat
- Makalah Antropologi HukumDokumen10 halamanMakalah Antropologi HukumAnis NasihahBelum ada peringkat
- Kelompok 5 Antropologi Kesehatan Dan SoalDokumen9 halamanKelompok 5 Antropologi Kesehatan Dan SoalLidya Margareta MahulaeBelum ada peringkat
- Antropologi Keperawatan Kel-2Dokumen15 halamanAntropologi Keperawatan Kel-2Risna WidiyastutiBelum ada peringkat
- Tugas RPL Mata Kuliah Antropobiologi-Rahmawati AgustinaDokumen41 halamanTugas RPL Mata Kuliah Antropobiologi-Rahmawati Agustinaricca67760Belum ada peringkat
- Sosiologi Pertemuan Ke 5Dokumen4 halamanSosiologi Pertemuan Ke 5Nutrisia Maharaja nutrisia maharajaBelum ada peringkat
- Bab 2 Pembahasan Makalah AntropologiDokumen13 halamanBab 2 Pembahasan Makalah Antropologiindri pijuBelum ada peringkat
- Ips Klmpok 8Dokumen10 halamanIps Klmpok 8Raihan FadhilahBelum ada peringkat
- Makalah IPSDokumen16 halamanMakalah IPSDegs GituBelum ada peringkat
- Modul Antropologi FinalDokumen81 halamanModul Antropologi FinalNurjuliati SianturiBelum ada peringkat
- Artikel Leonardo ArmandoDokumen7 halamanArtikel Leonardo ArmandoMUHAMMAD BAIHAQI ALBANNA Ekonomi SyariahBelum ada peringkat
- Studi Islam Dengan Pendekatan Sosiologi Dan AntropologiDokumen20 halamanStudi Islam Dengan Pendekatan Sosiologi Dan AntropologiSrimurni HandayaniBelum ada peringkat
- Uas - Ivandikarahmad - 1H8 - Antropologi HukumDokumen8 halamanUas - Ivandikarahmad - 1H8 - Antropologi HukumShella Pratiwi sBelum ada peringkat
- Pendekatan Sosiiologi Dan AntropologiDokumen23 halamanPendekatan Sosiiologi Dan AntropologiPutu FinaBelum ada peringkat
- AntropologiDokumen8 halamanAntropologiLisa AuliaBelum ada peringkat
- Pendekatan Antropologi Dalam Kajian IslamDokumen11 halamanPendekatan Antropologi Dalam Kajian IslamAnnisa Faudhila KhairiBelum ada peringkat
- LP KelompokDokumen34 halamanLP KelompokHerdinanPratama Wijaya TAMAMBelum ada peringkat
- Filsafat AntropologiDokumen7 halamanFilsafat AntropologiJiBelum ada peringkat
- Makalah Antro Nadiyya Zahara 1bDokumen23 halamanMakalah Antro Nadiyya Zahara 1bNadiyya zaharaBelum ada peringkat
- P13337420120060 - Ivania Ayu Paninggar - Pert 1Dokumen6 halamanP13337420120060 - Ivania Ayu Paninggar - Pert 1Ivania Ayu paninggarBelum ada peringkat
- Tugas Pengantar Antropologi KesehatanDokumen2 halamanTugas Pengantar Antropologi KesehatanAmaliah Chairul Nusu100% (1)
- Pengertian SosiologiDokumen27 halamanPengertian Sosiologimeiki silwantoBelum ada peringkat
- Pembahasan Antropologi Kesehatan Bab 1Dokumen9 halamanPembahasan Antropologi Kesehatan Bab 1MegaaBelum ada peringkat
- Antropkes Kelompok 3 - 1aDokumen14 halamanAntropkes Kelompok 3 - 1aRiham MarhamahBelum ada peringkat
- Makalah Revisi Antropologi Kel 11Dokumen24 halamanMakalah Revisi Antropologi Kel 11Dini HendianiBelum ada peringkat
- Antropologi Dan Sosiologi Di Bidang KesehatanDokumen12 halamanAntropologi Dan Sosiologi Di Bidang KesehatanReyna Nursyifa DewiBelum ada peringkat
- 8 Makalah I, Metopenag Senin 13.00 RiskaDokumen7 halaman8 Makalah I, Metopenag Senin 13.00 RiskaMeri AngkasaBelum ada peringkat
- Materi Antropologi KesehatanDokumen12 halamanMateri Antropologi Kesehatanrus andrainiBelum ada peringkat
- Konsep Antropologi Sosial Dan Antropologi KesehatanDokumen15 halamanKonsep Antropologi Sosial Dan Antropologi KesehatankrisnaindrayaniBelum ada peringkat
- Antropologi ViaDokumen12 halamanAntropologi ViaUF ViaBelum ada peringkat
- ANTROPOLOGIDokumen9 halamanANTROPOLOGIAdha Nur LintangBelum ada peringkat
- Antropologi Hukum PrankispDokumen7 halamanAntropologi Hukum PrankispanomtrilksmiBelum ada peringkat
- Hubungan Ilmu Antropolgi Hukum Dengan Ilmu LainnyaDokumen11 halamanHubungan Ilmu Antropolgi Hukum Dengan Ilmu Lainnyasabar juntakBelum ada peringkat
- Esensi Dan Konsep DasarDokumen4 halamanEsensi Dan Konsep DasarNurul Fahmi AriefBelum ada peringkat
- Jurnal Soosio FiksDokumen22 halamanJurnal Soosio FiksM. Adil HusainBelum ada peringkat
- UTS Fahma Mutia Wardah 289 FDokumen9 halamanUTS Fahma Mutia Wardah 289 FFahma MutiaBelum ada peringkat
- METODOLOGI KL 9 RevisiDokumen15 halamanMETODOLOGI KL 9 Revisitiian ArBelum ada peringkat
- Pengertian AntropologiDokumen6 halamanPengertian AntropologiRina AviyaniBelum ada peringkat
- Penugasan Kelompok Pengantar Ilmu SosialDokumen7 halamanPenugasan Kelompok Pengantar Ilmu SosialRisma Putri AnggrianiBelum ada peringkat
- Tugas Antrofologi Dan SosialDokumen17 halamanTugas Antrofologi Dan SosialFerdy ArrdinataBelum ada peringkat
- Antropologi-M Usman-Tugas 3Dokumen11 halamanAntropologi-M Usman-Tugas 3DIVA ASTYABelum ada peringkat
- Antropologi KesehatanDokumen33 halamanAntropologi KesehatansuwardiBelum ada peringkat
- Resume Pengantar Ilmu AntropologiDokumen4 halamanResume Pengantar Ilmu AntropologiANis ARiestantoBelum ada peringkat
- Makalah Sosiologi & Antropologi PsikologiDokumen19 halamanMakalah Sosiologi & Antropologi Psikologiputriamandaastri33Belum ada peringkat
- Antropologi HukumDokumen7 halamanAntropologi HukumsiskaBelum ada peringkat
- Konsep Antropologi Sosial Dan Antropologi KesehatanDokumen14 halamanKonsep Antropologi Sosial Dan Antropologi KesehatandeviBelum ada peringkat
- Tgas Antropologi SuprianiDokumen5 halamanTgas Antropologi SuprianiNurul Hidayatullah SamsiahBelum ada peringkat
- Kel 4 AntropologiDokumen6 halamanKel 4 AntropologiMuhammad Nadim MajidBelum ada peringkat
- Sosiologi-Antropologi Kesehatan-2019-1Dokumen38 halamanSosiologi-Antropologi Kesehatan-2019-1Ulinnuha MuhammadBelum ada peringkat
- JejakDokumen11 halamanJejakArsyila Romeesa FarzanaBelum ada peringkat
- Pengertian Sosiologi Dan AntropologiDokumen5 halamanPengertian Sosiologi Dan AntropologiArwan XaviestaBelum ada peringkat
- Tugas Sosio AntropologiDokumen10 halamanTugas Sosio AntropologiAkbar AdriantoBelum ada peringkat
- Pengertian ISBDDokumen11 halamanPengertian ISBDAstri DesmayantiBelum ada peringkat
- Sosiologi AntropologiDokumen11 halamanSosiologi AntropologiAji Handoko100% (1)
- Makalah Antropologi Hukum - Wenika Cindy MeydiaDokumen10 halamanMakalah Antropologi Hukum - Wenika Cindy MeydiaAndhika Noor PrasetyoBelum ada peringkat
- Pengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- Bab 2 Konsep KeluargaDokumen4 halamanBab 2 Konsep KeluargaJuliana RahmatBelum ada peringkat
- Dapus PDFDokumen1 halamanDapus PDFJuliana RahmatBelum ada peringkat
- Poster Kerja Keras Kerja CerdasDokumen1 halamanPoster Kerja Keras Kerja CerdasJuliana RahmatBelum ada peringkat
- LEMBAR BALIK Nyeri SendiDokumen12 halamanLEMBAR BALIK Nyeri SendiJuliana RahmatBelum ada peringkat
- Brosur Kewirausahaan BoluDokumen1 halamanBrosur Kewirausahaan BoluJuliana RahmatBelum ada peringkat
- Brosur KewirausahaanDokumen1 halamanBrosur KewirausahaanJuliana RahmatBelum ada peringkat
- Rom Aktif Rom PasifDokumen2 halamanRom Aktif Rom PasifJuliana RahmatBelum ada peringkat