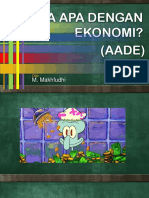1938 5446 1 PB
Diunggah oleh
alvin 258Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
1938 5446 1 PB
Diunggah oleh
alvin 258Hak Cipta:
Format Tersedia
IMPLEMENTASI MEKANISME PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
INDONESIA DALAM MENGATASI KESENJANGAN SOSIAL
Ervina Dwi Indriati
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
e-mail: ervinaindriati@gmail.com
ABSTRAK
Keberadaan masyarakat adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mendapat pengakuan dan
penghormatan, termasuk dalam Pasal 18 B ayat (2). Pasal ini memberikan posisi konstitusional kepada
masyarakat adat dalam hubungannya dengan Negara. Kehadiran masyarakat adat merupakan suatu
kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Pemerintah Daerah diberi
kewenangan regulasi untuk penentuan keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup da nada
di masyarakat. Sejak era reformasi masyarakat hukum adat seluruh Indonesia banyak melakukan
penuntutan-penuntutan pengakuan kembali hak mereka yang telah dirampas secara paksa atau dengan cara
lain, baik pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu.
Kata kunci: Pengakuan Hak; Masyarakat Adat; Pemerintah Daerah
ABSTRACT
The existence of indigenous peoples in the amended 1945 Constitution has received recognition and respect,
including in Article 18 B paragraph (2). This article gives indigenous peoples a constitutional position in relation
to the State. The presence of indigenous peoples is a historical fact that cannot be avoided or denied by the
government. Local governments are given regulatory authority to determine the existence of a customary law
community who is still alive and well in the community. Since the era of reform, indigenous peoples throughout
Indonesia have carried out many demands for the recognition of their rights that have been taken away by force
or by other means, both the government and certain groups.
Keywords: Recognition of Rights; Indigenous Peoples; Local Government
A. PENDAHULUAN
Masyarakat adat di Indonesia merupakan komunitas-komunitas yang hidup
berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat. Mereka
memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan kehidupan sosial budaya yang diatur
oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan
masyarakatnya.
Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), anggota mereka
berjumlah 2.359 komunitas adat di seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 17 juta
anggota individu yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, eksistensi mereka terancam di
tengah banyak upaya penjarahan sumberdaya alam dan pengalihan fungsi hutan yang
menyingkirkan hak-hak masyarakat adat.
Hingga kini, masih banyak masyarakat adat yang terusir dari lahan mereka sendiri
akibat ekspansi lahan pertambangan atau perkebunan kelapa sawit skala besar di
This is an open access article under the CC BY-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
Kalimantan dan Sumatra. Tahun 2016, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham)
telah merilis Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di
Kawasan Hutan memperlihatkan realitas adanya pelanggaran hak masyarakat adat yang
disertai pendekatan kekerasan, intimidasi dan bahkan kriminalisasi.
Sebanyak 125 masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi akibat konflik lahan yang
tersebar di Bengkulu, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa
Tenggara Timur.
Presiden Joko “Jokowi” Widodo sudah berusaha melindungi hak-hak masyarakat adat
dengan berbagai inisiatif baik, seperti memberikan pengakuan hak atas akses tanah
komunal atau kolektif saat mengundang sejumlah masyarakat adat ke istana negara untuk
mendapatkan akses hak sumberdaya alam.
Undangan itu untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu.
Jokowi sudah mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Masyarakat Adat. UU yang mengatur pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak
masyarakat adat tersebut sudah dua kali masuk dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) di bawah kepemimpinan Jokowi, yaitu tahun 2014 dan 2019. Namun sampai
saat ini belum juga disahkan.
Tapi, kedua hal itu tidak cukup. Ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi oleh
pemerintahan Jokowi agar aturan dan inisiatif yang ditawarkan benar-benar dapat
melindungi masyarakat adat.
Selaras dengan UUD 1945
Secara khusus, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan
negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak
tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara, pasal 28I ayat 3 UUD NRI 1945
mengatur Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban. Kedua pasal merupakan dasar hukum dalam
melindungi masyarakat adat dari segala bentuk penindasan perampasan hak.
Selama ini, berdasarkan studi lapangan yang dilakukan bersama tim Epistema,
perlindungan hak-hak masyarakat adat di UUD 1945 masih terbentur dalam bentuk
pengakuan bersyarat, melalui frase berlapis dan penuh pertarungan politik kepentingan di
tingkat lokal. Intinya, negara yang berperan penuh dalam mendefinisikan, mengakui hingga
melegitimasi eksistensi masyarakat adat sepanjang mereka mau “menuruti” regulasi
negara.
Paradigma ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan otonomi yang ada dalam
demokrasi. Pengakuan hak masyarakat adat seharusnya dikaitkan dengan substansi hak
asasi manusia yang juga tercantum dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Artinya, aturan yang ada tak sebatas meneguhkan pengakuan hak atas unit sosial tertentu
(hak ulayat dan hak atas sumberdaya alam) sebagai hak konstitusional masyarakat adat.
Namun, juga menjangkau hak-hak lain yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas
jaminan kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk mengembangkan kehidupan dan
budayanya, hak untuk setara di muka hukum dan pemerintahan, dan hak-hak asasi manusia
Ervina Dwi Indriati 292
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
lainnya. Ditambah lagi, ada proses yang disebut sebagai ‘negaraisasi hukum adat’, yaitu
memaksakan hukum negara (peraturan daerah, peraturan gubernur, dan peraturan
lainnya) sebagai dasar hukum. Proses ini mengabaikan hukum adat yang sebenarnya sudah
diterapkan oleh masyarakat adat secara turun-temurun.
Contohnya, peraturan kementerian dalam negeri tentang kelembagaan adat desa di
tahun 2018. Aturan tersebut hanya mengurus adat istiadat, upacara seremonial, dan budaya
tapi belum menyentuh aspek perlindungan hukum atau berlakunya hukum adat atau
hukum lokal. Akibatnya, banyak peraturan tersebut justru menindas karena menyulitkan
masyarakat adat kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Belum lagi, tumpah tindih peraturan dalam implementasi di lapangan menambah
komplikasi perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat. Alih-alih sebagai
pengakuan dan perlindungan, kerap dijumpai masyarakat adat yang mengalami terus
berbagai pelanggaran HAM.
B. PERUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di
Indonesia dalam mengatasi kesenjangan sosial.
C. PEMBAHASAN
Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia
Haruslah dipahami bahwa proses identifikasi dan verifikasi diletakkan sebagai bagian
dari proses menuju pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Prinsip utamanya
adalah Hak Masyarakat Adat Untuk Mengidentifikasi Diri Sendiri karena tidaklah mungkin
ada pihak lain di luar komunitas masyarakat adat bersangkutan yang mengenal mereka
lebih baik dari komunitas masyarakat adat itu sendiri.
Namun demikian, untuk menghindari ada pihak-pihak lain yang juga mengklaim diri
sebagai masyarakat adat tetapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kriteria dasar
masyarakat adat maka diperlukan proses verifikasi. Proses verifikasi dimaknai sebagai batu
uji bagi tiap komunitas masyarakat adat. Dengan proses verifikasi ini mereka akan dinilai
apakah sesuai dengan kriteria dasar sebagai masyarakat adat atau tidak. Proses verifikasi
ini pada prinsipnya haruslah dilakukan oleh satu lembaga yang bersifat independen untuk
menghindari tindakan-tindakan manipulasi dan kesewenang-wenangan yang justeru
kontraproduktif dari tujuan dibentuknya UU ini.
Identifikasi yang dilakukan secara tidak hati-hati dan tidak dilakukan sendiri oleh
masyarakat adat dapat berakibat buruk pada masyarakat adat. Sebagai contoh, penelitian
mengenai keberadaan hak ulayat di Paser, kaltim. Di manapara penelitinya berkesimpulan
bahwa tidak ada tanah ulayat lagi di Kabupaten Paser. Implikasinya adalah tidak ada lagi
masyarakat adat di Paser karena salah satu indikator keberadaan masyarakat adat adalah
adanya tanah ulayat. Temuan tersebut tentu saja mengejutkan karena tidak
menggambarkan realitas faktual di lapangan.
Pengaturan mengenai identifikasi, verifikasi dan penetapan keberadaan masyarakat
adat pada prinsipnya sangatlah sentralistik dan menjadi monopoli negara. Disebut
monopoli karena proses-proses itu dilakukan oleh pemerintah dan penetapan keberadaan
masyarakat adat dilakukan melalui Keputusan Presiden. Tidak bisa dibayangkan berapa
jumlah Surat Keputusan Presiden yang akan dikeluarkan sebagai akibat dari UU ini
nantinya. Idealnya, penetapan ini dilakukan di tingkat daerah melalui Keputusan Bupati.
Lagi pula akan lebih baik jika tanggungjawab untuk menetapkan keberadaan sebagai
Ervina Dwi Indriati 293
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
konsekuensi logis dari adanya pengakuan terhadap masyarakat adat itu diletakkan ke
pemerintah daerah supaya sejalan dengan gagasan desentralisasi.
Pengaturan mengenai identifikasi dan verifikasi yang dalam draf yang sekarang menjadi
sangat berjenjang dan menjadi monopoli pemerintah. Kelemahan dari proses ini adalah
birokrasinya terlalu panjang dan berbelit belit dan tidak menjamin pada keterlibatan penuh
masyarakat adat, sementara yang diidentifikasi adalah masyarakat adat itu sendiri. Karena
itu gagasan identifikasi diri dan verifikasi oleh lembaga independen seperti Komisi Daerah
Masyarakat Adat adalah satu gagasan yang harus dipertimbangkan untuk mengurangi
resiko dari proses yang berbelit-belit dalam birokrasi pemerintahan, dan juga supaya
proses identifikasi itu dilakukan sendiri oleh masyarakat adat. Dengan begitu maka kedua
proses, identifikasi dan verifikasi, dapat menemukan siapa sesungguhnya masyarakat adat
itu dan hak-hak nya.
Jika keseluruhan pengaturan mengenai identifikasi, verifikasi dan penetapan
keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya masih menggunakan ketentuan dalam draf
yang ada saat ini maka yang akan terjadi adalah sebagai berikut:
1. Akan ada ribuan Keputusan Presiden untuk menetapkan keberadaan masyarakat adat
dan hak-haknya;
2. Karena proses keberatan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan maka
tidaklah sulit untuk memahami bahwa keberatan terhadap SK Penetapan Presiden
akan diajukan kepada PTUN;
3. Jika demikian, bukankah dengan demikian RUU ini hanya menambah masalah dan
menjadi beban sektor peradilan.
Peraturan Pemerintah dan Peraturan daerah (sebagaimana disebut dalam Pasal 9) yang
akan dibuat itu pada prinsipnya haruslah sesuai dengan apa yang hendak dicapai dari
tujuan umum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu maka penting
agar batasan-batasan mengenai identifikasi dan verifikasi harus pula dimuat dalam UU ini.
Oleh karena itu maka apa yang diusulkan pada kolom masukan dan usulan perubahan di
samping mestinya menjadi pertimbangan untuk diatur dalam UU ini karena usulan yang
disampaikan itu berisi prinsip-prinsip mendasar dari proses identifikasi dan verifikasi, dan
juga mengatur mengenai pihak mana saja (masyarakat adat dan komnas dan atau komda
masyarakat adat) yang akan melakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi dimaksud.
Perkembangan legislasi mengenai pengakuan masyarakat hukum adat (MHA) dalam
kurun waktu sepuluh tahun terakhir masih ditandai dengan perkembangan pada sisi
jumlah. Dalam kurun waktu tersebut, sejumlah daerah seperti Kalimantan Tengah dan
Papua, mengundangkan produk hukum daerah berkenaan dengan pengakuan MHA. Pada
tingkat nasional, diundangkan legislasi setingkat UU, seperti UU No. 6/2014 tentang Desa.
Penambahan jumlah legislasi yang mengatur atau memuat klausul mengenai pengakuan
MHA, merupakan kelanjutan praktek yang sudah berlangsung semenjak awal Era
Reformasi.
Namun, bila dibandingkan dengan dekade sebelumnya, kurun waktu sepuluh tahun
terakhir ditandai dengan paling tidak tiga hal baru. Pertama, legislasi daerah
menyederhanakan prosedur pengakuan hak. Contoh untuk ini adalah Perda Kalimantan
Tengah No. 16/2008 tentang Kelembagaan Adat di Kalimantan Tengah, dan Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah No. 13/2009 tentang Tanah-Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di
atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi
Ervina Dwi Indriati 294
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
yang mengoreksi sejumlah undang-undang karena dianggap bertentangan dengan UUD
1945. Sebagai contoh adalah putusan No. 45/PUU-IX/2001 dan No. 35/PUU-X/2012. Kedua
putusan tersebut terkait dengan uji materiil atas UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
Dalam konsep rule of law, putusan-putusan tersebut dapat dimaknai juga sebagai kontrol
lembaga yudisial atas institusi pembuat undang-undang agar tidak melakukan
penyelahgunaan kewenangan lewat produk legislasi. Ketiga, Implementasi hukum dalam
bentuk pembuat peraturan pelaksana (regulatory implementation of law)1, khususnya
setingkat peraturan menteri, berkembang signifikan.
Selain ketiga hal di atas, sesuatu yang baru juga terjadi pada pemahaman atas kriteria
MHA. Sebelumnya, kriteria MHA yang terdiri dari beberapa, bersifat kumulatif. UU Desa
merubahnya menjadi gabungan antara kumulatif dan opsional. Kriteria ‘wilayah’ yang
bersifat wajib dipasangkan dengan satu kriteria lainnya yang bersifat opsional.
Perkembangan yang kedua yaitu lahirnya peraturan pelaksana mengenai pengakuan
MHA. Dari segi waktu, peraturan pelaksana tersebut lahir hanya dalam kurun waktu dua
tahun terakhir. Peraturan pelaksana tersebut adalah:
i. Peraturan Bersama tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
yang Berada di dalam Kawasan Hutan;
ii. Permendagri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat
Hukum Adat;
iii. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.
9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu; dan (iv) Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32/2015 tentang Hutan Hak.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hal Ulayat Masyarakat Hukum adat merupakan satusatunya peraturan setingkat
menteri mengenai pengakuan MHA. Permenag tersebut hanya ditemani oleh satu peraturan
kebijakan (policy rule) yaitu Surat Edaran Menteri Kehutanan No. S.75/Menhut II/2004
perihal Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti Rugi oleh Masyarakat
Hukum Adat.
Pengundangan empat peraturan pelaksana setingkat peraturan menteri tersebut
mempunyai dua makna. Pertama, merupakan pengakuan tidak langsung dari pemerintah
pusat bahwa bola pengakuan MHA tidak semata-mata berada di tangan pemerintah daerah.
Sebelumnya, sejumlah menteri dan pejabat departemen berargumen bahwa departemen
menunggu pemerintah daerah mengukuhkan atau menetapkan keberadaan MHA. Kedua,
mencairkan kemacetan regulatory implementation of law yang tak kunjung bergerak pasca
amandemen UUD 1945 dan pembuatan sejumlah UU sektoral.
Sebagai peraturan pelaksana (adminsitartive rule), keempat peraturan setingkat
peraturan menteri di atas ditempatkan sebagai instrumen agar kelompok sasaran
(regulated group) merasakan dampak dari UU. Dengan demikian, keempat peraturan
1
Selain regulatory implementation of law, bentuk kedua implementation of law adalah administrative
implementation. Mengenai perbedaan kedua bentuk tersebut bisa dilihat pada Julia Black (2002), ‘Critical
Reflections on Regulation’, Australian Journal of Legal Philosophy 27: 1-36.
Ervina Dwi Indriati 295
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
pelaksana tersebut merupakan instrumen bagi negara untuk menjangkau kelompok
sasaran.2
Sehubungan dengan itu, perlu diperiksa seberapa jauh legislasi yang dibuat dalam
kurun waktu satu dekade terakhir, khususnya keempat peraturan pelaksana tersebut,dapat
diberlakukan (implementable) sehingga mendatangkan efek pada kelompok sasaran.3
Pengaturan hukum mengenai pengakuan MHA mencakup legislasi atau peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim. Fakta bahwa ada beberapa skema pengakuan
MHA bukan merupakan sesuatu yang direncanakan melainkan ekses dari egoisme sektoral.
Sebelumnya sudah ditengarai ekses tersebut berupa pengaturan MHA yang tidak bersifat
holistik melainkan parsial. Ada peraturan-perundangan yang hanya mengatur hukum atau
kelembagaan adat, dan yang lain mengatur hak-hak MHA.4 Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) mengusulkan pembentukan UU tersendiri untuk mesyarakat hukum
adat untuk mengakhiri parsialisme tersebut.
Ada beberapa petanda yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi variasi skema
pengakuan.5 Petanda pertama adalah bentuk produk hukum pengukuhan atau penetapan
keberadaan MHA. Adapun pertanda kedua adalah jenis kewenangan atau hak yang diakui.
Untuk pertanda yang pertama yaitu bentuk produk hukum, paling tidak ada 3 kelompok
peraturan perundangan, yaitu:
i. Kelompok yang menentukan bahwa pengukuhan atau penetapan keberadaan MHA
dengan peraturan daerah. Contoh untuk ini adalah UU Kehutanan dan UU Perkebunan.
Di luar produk legislasi, putusan MK 35/PUUX/2012 menegaskan ketentuan
pengukuhan dengan Perda tersebut;
ii. Kelompok yang menentukan bahwa pengukuhan dilakukan dengan Keputusan Kepala
Daerah (Bupati/Walikota). Contohnya adalah Permendagri No. 52/2014; dan
iii. Kelompok yang menentukan pengukuhan atau penetapan keberadaan dapat dilakukan
oleh sebuah Tim bentukan Bupati/Walikota. Contoh untuk ini adalah Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 9/2015.
Petanda ketiga adalah perbedaan kewenangan atau hak yang diakui. Variasi karena
perbedaan pada hal tersebut bisa dibagi ke dalam dua, yaitu:
i. Peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengakuan hak atas sumberdaya
alam. Contohnya adalah Perber tahun 2014, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang
No. 9/2015 dan Perarturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 31/2015
tentang Hutan Hak; dan
2
Rikardo Simarmata (2012), Indonesian Law and Reality in the Delta: a socio-legal inquiries into laws, local
bureaucrats and natural resources menagament in the Mahakam Delta, East Kalimantan. Leiden: Leiden University
Press.
3
Ada empat karakteristik suatu peraturan perundang-undangan bisa dikatakan implementable, yaitu
adequacy, feasibility, legal certainty dan adaptability. Uraian lebih lanjut mengenai empat karakteristik tersebut
dapat dilihat pada Benjamin Van Rooij (2006), Regulating Land and Pollution in China, LawmakingCompliance,
and Enforcement; Theory and Cases. Leiden: Leiden University Press.
4
Rikardo Simarmata (2006), Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia. Jakarta: UNDP-
RIPP.
5
Uraian mengenai sebagian petanda tersebut bisa juga dibaca pada Agung Wibowo et al. (2015), ‘Penetapan
Hutan Adat Menuju Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Kertas Kebijakan, Perkumpulan HUMA.
Ervina Dwi Indriati 296
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
ii. Peraturan perundangan yang mengatur pengakuan MHA sebagai self-governing
community dan dengan demikian diakui kewenangannya untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan. Contohnya adalah UU Desa.6
Selain melalui dua petanda di atas, variasi juga bisa dikenali dari jenis hak yang
diakui. Perber tahun 2014 memberi peluang pada pengakuan hak-hak atas tanah
perorangan, sementara Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.
9/2015 dan Peraturan Menteri LHK No. 32/2015 mengatur mengenai pengakuan hak
kolektif dan hak komunal. Istilah ‘mekanisme’ merujuk pada tahapan dan proses.
Tahapan pengakuan MHA secara garis besar bisa dibagi ke dalam dua, yaitu:
i. Pengukuhan atau penetapan keberadaan; dan
ii. Pengakuan hak atau kewenangan.
Berikut uraian kedua tahapan tersebut. Pengukuhan atau penetapan keberadaan pada
dasarnya adalah proses untuk memeriksa pemenuhan kriteria MHA oleh suatu komunitas.
Kriteria untuk memeriksa keberadaan merupakan tuntutan dari ketentuan dalam konstitusi
dan peraturan perundangan lainnya yang mensyaratkan ‘masih hidup’ untuk mengakui
MHA. Dengan demikian, keadaan masih hidup diukur dengan sejumlah kriteria. Ujung
tahapan pengukuhan atau penetapan keberadaan adalah kejelasan unit sosial yang akan
berperan sebagai subyek hukum.7
Dengan diperjelasnya unit sosial yang akan menjadi subyek hukum, tahapan ini
menyiapkan jalan ke tahapan kedua yaitu pengakuan kewenangan dan hak. Tahapan kedua
memerlukan kejelasan subyek yang akan diakui hak-haknya atas sumber daya alam atau
hak-hak tradisional lainnya, atau kewenangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat 3 variasi pada peraturan
perundangan mengenai bentuk produk hukum untuk mengukuhkan atau menetapkan
keberadaan MHA. Mayoritas peraturan perundangan menentukan peraturan daerah sebagai
instrumen legislasi untuk melakukan pengukuhan atau penetapan keberadaan. Permendari
No. 52/2014 keluar dari arus utama tersebut dengan hanya mensyaratkan Keputusan
Kepala Daerah. Langkah lebih jauh dilakukan oleh Peraturan Menteri Agraria&Tata
Ruang/Kepala BPN No. 9/2015 yang memberikan kewenangan kepada Tim Inventarisasi
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk memutuskan
atau menyimpulkan pemenuhan kriteria keberadaan.
Peraturan perundangan terbaru yang mengatur mengenai bentuk produk hukum
pengukuhan atau penetapan keberadaan adalah Peraturan Menteri LHK No. 32/2015.
Peraturan ini memperluas produk hukum yang bisa dipakai untuk pengukuhan atau
penetapan keberadaan, menjadi produk hukum daerah. Sesuai ketentuan Permendagri No.
1/2014 produk hukum daerah mencakup perda atau nama lainnya, Peraturan kepala
6
AMAN membagi rute pengakuan MHA ke dalam tiga. Rute pertama menggunakan Permen Agraria/Kepala
BPN No. 5/1999; rute kedua menggunakan UU Kehutanan, dan rute ketiga UU Desa dan Permendagri No. 52/2014.
Lihat dalam Muh. Arman. AR, ‘Peluang dan Tantangan Pengakuan dan Perlindungan Hukum bagi Masyarakat Adat
melalui Desa Adat. Presentasi pada lokakarya Tantangan Masyarakat Adat dan Pembaharuan Agraria dalam
Pelaksanaan Putusan MK 35 dan UU Desa, Jakarta, 3- 4 Februari 2015.
7
Deskripsi mengenai konsep dan praktek masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum dapat dilihat pada
Rikardo Simarmata dan Bernadinus Steni, ‘Konsep Subyek Hukum dan Masyarakat Hukum Adat sebagai Subyek
Hukum. Draf concept paper.
Ervina Dwi Indriati 297
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
daerah, peraturan bersama kepala daerah, Peraturan DPRD dan keputusan. Keputusan
sendiri meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
Selain perbedaan pada bentuk produk hukum, tahapan pengukuhan atau penetapan
keberadaan juga bisa dibedakan berdasarkan cara mengaitkannya dengan tahapan kedua.
Permendagri No. 52/2014 tidak menghubungkannya pengukuhan atau penetapan
keberadaan dengan tahapan pengakuan atas kewenangan. Hal ini berbeda dengan
Perarturan Menteri Agraria&Tata Ruang/Kepala BPN No. 9/2015 yang menempatkan
pengukuhan atau penetapan keberadaan sebagai syarat untuk mengakui hak komunal atas
tanah.
Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa tahapan pengakuan kewenangan
atau hak dilakukan setelah ada kejelasan mengenai siapa subyek hukum yang akan memiliki
kewenangan atau hak. Subyek yang akan mendapatkan pengakuan kewenangan atau hak
adalah yang sudah dikukuhkan atau ditetapkan sebagai MHA. Istilah pengakuan
kewenangan merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diatur
dalam UU Desa dan peraturan pelaksananya. Pengakuan atas kewenangan tersebut
khususnya merujuk pada kewenangan berdasarkan asal-usul.
UU Desa termasuk salah satu peraturan perundangan yang mengkaitkan langsung
pengakuan kewenangan dengan pengukuhan atau penetapan keberadaan dengan cara
menjadikan yang terakhir sebagai syarat bagi pengakuan kewenangan. Dengan menentukan
bahwa desa adat sebagai pemilik aset seperti hak ulayat, hutan dan mata air milik desa,
maka UU Desa juga sekaligus melakukan pengakuan atas hak badan hukum publik.
Adapun istilah pengakuan hak merujuk pada hak atas tanah dan sumberdaya alam
lainnya, dan hak-hak tradisional lainnya. Dalam kerangka legislasi yang berlaku saat ini,
pengakuan hak menunjuk pada pengakuan atas hak komunal (Peraturan Menteri
Agraria&Tata Ruang/Kepala BPN No. 9/2015) dan atas hutan adat (Perber 2014; Peraturan
Menteri LHK No. 32/2015). Hak tersebut mencakup hak perotangan (Perber 2014) dan hak
komunal (Peraturan Menteri Agraria&Tata Ruang/Kepala BPN No. 9/2015). Sesuai dengan
Peraturan Menteri Agraia&Tata Ruang/Kepala BPN No. 9/2015, tahapan pengakuan hak
mencakup juga pendaftaran hak atas tanahnya untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Sementara Perber 2014 dan Peraturan Menteri LHK No. 32/2015 tidak menentukan bahwa
pengakuan atas tanah-tanah hak yang sebelumnya berada di dalam kawasan hutan, diakhiri
dengan pendaftaran hak atas tanahnya.
D. KESIMPULAN
Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang”. Kemudian ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat
dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dari masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain ada
beberapa undang-undang sektoral yang memberikan jaminan hak-hak masyarakat hukum
adat, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Ervina Dwi Indriati 298
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan perundangan terbaru yang mengatur mengenai bentuk produk hukum
pengukuhan atau penetapan keberadaan adalah Peraturan Menteri LHK No. 32/2015.
Peraturan ini memperluas produk hukum yang bisa dipakai untuk pengukuhan atau
penetapan keberadaan, menjadi produk hukum daerah. Sesuai ketentuan Permendagri No.
1/2014 produk hukum daerah mencakup perda atau nama lainnya, Peraturan kepala
daerah, peraturan bersama kepala daerah, Peraturan DPRD dan keputusan.
Keputusan sendiri meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan
Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Selain perbedaan pada bentuk
produk hukum, tahapan pengukuhan atau penetapan keberadaan juga bisa dibedakan
berdasarkan cara mengaitkannya dengan tahapan kedua. Permendagri No. 52/2014 tidak
menghubungkannya pengukuhan atau penetapan keberadaan dengan tahapan pengakuan
atas kewenangan. Hal ini berbeda dengan Perarturan Menteri Agraria & Tata Ruang/Kepala
BPN No. 9/2015 yang menempatkan pengukuhan atau penetapan keberadaan sebagai
syarat untuk mengakui hak komunal atas tanah.
Ervina Dwi Indriati 299
Volume 1 | No. 03 | Desember 2020 e-ISSN 2721-6098
DAFTAR PUSTAKA
A. Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Sumber Daya Alam Dalam Politik Hukum
Nasional (disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2007).
Abdurrahman, Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, majalah Hukum
Nasional No.1 Tahun 2007, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1981.
F. Budi Herman, Posisi Struktur Suku Bangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa Dalam Kehidupan Kebangsaan
dan Kenegaraan di Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Filsafat, dalam Ignas Tri (Penyunting), Hubungan
Struktur Masyarakat Adat, Suku Bangsa, Bangsa, dan Negara (Ditinjau dari perspektif Hak Asasi
Manusia). Jakarta, Komnas HAM, 2006.
Charles Tylor, Multiculturalism : Examining the Politics of Recognition, (Princeton : Princeton University Press,
1994).
Husein Alting, Dinamika Hukum dan penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas
Tanah, Yogyakarta 2010.
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, (Bandung : CV Mandar Maju, 2003).
Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di
Mahkamah Konstitusi (Jakarta : Salemba Humanika, 2010).
I Nyoman Nurjaya, Antropologi Hukum : Tema Kajian, Metodologi, dan Penggunaannya Untuk Memahami
Fenomena Hukum di Indonesia. Makalah dipresentasikan dalam Serial Kuliah Tamu, dengan tema :
“Kajian Hukum, Politik dan Organisasi Sosial dalam Tinjauan Antropologi”, diselenggarakan oleh
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya pada tanggal 6 April 2013.
Irfan Nurrahman, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang
Ervina Dwi Indriati 300
Anda mungkin juga menyukai
- Sistem Hukum Indonesia 42Dokumen7 halamanSistem Hukum Indonesia 42Lisma Wati100% (1)
- Dasar Dasar AkuntansiDokumen200 halamanDasar Dasar AkuntansiSurvianto Graha PuraBelum ada peringkat
- Masyarakat Hukum Adat Atau Biasa Disebut Masyarakat Adat Merupakan Suatu Kelompok Yang Berada Di Wilayah Tertentu Dan Memiliki Hak Untuk Mengelola Dan Menikmati Hasil Dari Sumber Daya AlamnyaDokumen4 halamanMasyarakat Hukum Adat Atau Biasa Disebut Masyarakat Adat Merupakan Suatu Kelompok Yang Berada Di Wilayah Tertentu Dan Memiliki Hak Untuk Mengelola Dan Menikmati Hasil Dari Sumber Daya AlamnyaFafaBelum ada peringkat
- Corak Masyarakat Hukum AdatDokumen16 halamanCorak Masyarakat Hukum Adatsandy.maulana757Belum ada peringkat
- Makalah Hukum Humaniter InternasionalDokumen12 halamanMakalah Hukum Humaniter InternasionalChikabintBelum ada peringkat
- Tugas 1 Sistem Hukum Indonesia - Layar MutiaraDokumen5 halamanTugas 1 Sistem Hukum Indonesia - Layar MutiaraLayar MutiaraBelum ada peringkat
- Tugas I Sistem Hukum Indonesia Isip4131 Tri Selamat Zebua Nim 040983595Dokumen5 halamanTugas I Sistem Hukum Indonesia Isip4131 Tri Selamat Zebua Nim 040983595triselamat zebua100% (1)
- BABIDokumen9 halamanBABInurmasari suaebBelum ada peringkat
- Minipaper Adat DLM Putusan MK SM 13Dokumen5 halamanMinipaper Adat DLM Putusan MK SM 13MR NalllBelum ada peringkat
- Implementasi PengakuanDokumen2 halamanImplementasi PengakuanAdley RamliBelum ada peringkat
- Mengapa Masih Terjadi PelanggaranDokumen2 halamanMengapa Masih Terjadi PelanggaranSandy SyamBelum ada peringkat
- Esai Saya Tentang DemokrasiDokumen9 halamanEsai Saya Tentang DemokrasiSugeng MaxBelum ada peringkat
- Draft Naskah Prakebijakan 131022Dokumen52 halamanDraft Naskah Prakebijakan 131022Hendro PurbaBelum ada peringkat
- Artikel UTS HAMDokumen3 halamanArtikel UTS HAMMuhammadrobykusuma RobyBelum ada peringkat
- Tugas PKN 3Dokumen18 halamanTugas PKN 3Adiraka DwinandaBelum ada peringkat
- 11523-Article Text-30808-1-10-20201230Dokumen12 halaman11523-Article Text-30808-1-10-20201230La Ode HaeruddinBelum ada peringkat
- Nur Febryanti BurhanuddinDokumen6 halamanNur Febryanti BurhanuddinResky SaputraBelum ada peringkat
- Penanaman ModalDokumen20 halamanPenanaman ModalDewi NovitaBelum ada peringkat
- Makalah Masyarakat Adat Dan Wilayah AdatDokumen13 halamanMakalah Masyarakat Adat Dan Wilayah AdatAgung AnugrahBelum ada peringkat
- Dinamika Masyarakat Hukum AdatDokumen15 halamanDinamika Masyarakat Hukum Adatdodispakning1Belum ada peringkat
- Makalah AntropologiDokumen8 halamanMakalah AntropologiArti HastutiBelum ada peringkat
- Cara Memperbaiki Mesin Mobil - PDFDokumen17 halamanCara Memperbaiki Mesin Mobil - PDFAnton SigaBelum ada peringkat
- Sejarah Dan Hukum Adat Dayak AgabagDokumen85 halamanSejarah Dan Hukum Adat Dayak AgabagLumbis100% (1)
- Hukum AgrariaDokumen8 halamanHukum AgrariaGem DogruyolBelum ada peringkat
- UAS HK Adat Laela Azmi (D1A021180)Dokumen8 halamanUAS HK Adat Laela Azmi (D1A021180)Fahrii GamingsBelum ada peringkat
- Desa Adat Dan Hukum Adat Di Kabupaten Lamandau / Inventarisasi Hukum Adat Di Kabupaten LamandauDokumen76 halamanDesa Adat Dan Hukum Adat Di Kabupaten Lamandau / Inventarisasi Hukum Adat Di Kabupaten LamandauAndrey JuniartoBelum ada peringkat
- Tugas 1 Sistem Hukum IndonesiaDokumen2 halamanTugas 1 Sistem Hukum IndonesiaMuhammad RizkanBelum ada peringkat
- Makalah PKN HK Sosial BudayaDokumen13 halamanMakalah PKN HK Sosial Budayananda100% (2)
- 101 - 2310414310016 - Jourdy Januariadi 1Dokumen8 halaman101 - 2310414310016 - Jourdy Januariadi 1jordanjahmetBelum ada peringkat
- Jawaban Tugas 3 Pengantar Ilmu HukumDokumen4 halamanJawaban Tugas 3 Pengantar Ilmu Hukummitch silvaBelum ada peringkat
- Rangkuman Bab 7Dokumen2 halamanRangkuman Bab 7MclfrBelum ada peringkat
- HKM AdatDokumen58 halamanHKM AdatPatrice LumubaBelum ada peringkat
- Tugas Uts HK AdatDokumen3 halamanTugas Uts HK AdatFahrii GamingsBelum ada peringkat
- 1 - Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Demi Terciptanya Keadilan Sosia1Dokumen29 halaman1 - Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Demi Terciptanya Keadilan Sosia1lisalilies12Belum ada peringkat
- Essay Hak Dan Kewajiban Warga NegaraDokumen4 halamanEssay Hak Dan Kewajiban Warga NegaraazrieliqbalwinataBelum ada peringkat
- PKNNDokumen7 halamanPKNNhartinaBelum ada peringkat
- Sifa Siti Nasifah, Xii Iis 4, Tuga Resume PKNDokumen19 halamanSifa Siti Nasifah, Xii Iis 4, Tuga Resume PKNSalwa WaBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - SIAPAKAH WARGA NEGARA INDONESIADokumen6 halamanKelompok 1 - SIAPAKAH WARGA NEGARA INDONESIAMerdiana NursyamsiahBelum ada peringkat
- Bhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik IndonesiaDokumen7 halamanBhineka Tunggal Ika Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik IndonesiafhiaalisyaBelum ada peringkat
- Tugas 1 - SHI - Igne Amalia Ade Putri - 051506799Dokumen4 halamanTugas 1 - SHI - Igne Amalia Ade Putri - 051506799adepigneamaliaBelum ada peringkat
- Ham Bidang Ekonomi Sosial - MD Subawa - Jan 2009 WRDDokumen7 halamanHam Bidang Ekonomi Sosial - MD Subawa - Jan 2009 WRDAnton BanderasBelum ada peringkat
- Ubi Societas Ibi IusDokumen63 halamanUbi Societas Ibi IusLita SibliBelum ada peringkat
- Hukum Adat LengkapDokumen85 halamanHukum Adat LengkapIda Bagus WiratamaBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Pidana Adat (Andrew Pebriantho)Dokumen30 halamanMakalah Hukum Pidana Adat (Andrew Pebriantho)ristaBelum ada peringkat
- Agshal Putra - 202021603 - 6J - Perancangan UUDokumen28 halamanAgshal Putra - 202021603 - 6J - Perancangan UUGitadheaBelum ada peringkat
- Kata Kunci: Pengakuan Hukum, Hak Ulayat Masyarakat Hukum AdatDokumen10 halamanKata Kunci: Pengakuan Hukum, Hak Ulayat Masyarakat Hukum AdatChaca AnnisaBelum ada peringkat
- Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraDokumen12 halamanPengingkaran Kewajiban Warga Negaraanon_89385850Belum ada peringkat
- Bab I TinaDokumen6 halamanBab I TinaThinalaenBelum ada peringkat
- JURNALDokumen28 halamanJURNALtrustissue321Belum ada peringkat
- Dfar Perda Kab Konawe Berbaisis HamDokumen9 halamanDfar Perda Kab Konawe Berbaisis HamAnton BandaBelum ada peringkat
- PANCASILA KLMPK 3 Revisi1Dokumen27 halamanPANCASILA KLMPK 3 Revisi1Komang Agus ErawanBelum ada peringkat
- Tugas 3 Pengantar Ilmu HukumDokumen11 halamanTugas 3 Pengantar Ilmu Hukumgeren fieriBelum ada peringkat
- 4-Article Text-6-1-10-20171210Dokumen18 halaman4-Article Text-6-1-10-20171210Iwan AnwarBelum ada peringkat
- Tugas 3 Ilmu HukumDokumen8 halamanTugas 3 Ilmu Hukumpuputoctavia24Belum ada peringkat
- TT 2 Pembelajaran PKN Di SDDokumen5 halamanTT 2 Pembelajaran PKN Di SDIndriy FitriBelum ada peringkat
- PKN Zahwadzahabiyyah Krywnsmstr2Dokumen35 halamanPKN Zahwadzahabiyyah Krywnsmstr2dadan sondanaBelum ada peringkat
- Jenny M - Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya AlamDokumen16 halamanJenny M - Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya AlamDwi DimasBelum ada peringkat
- Bab 2 No. 2Dokumen9 halamanBab 2 No. 2hasnah nurapriliaBelum ada peringkat
- Hukum Adat Lembar JawabanDokumen2 halamanHukum Adat Lembar JawabanFriesca ChahyaniBelum ada peringkat
- Politik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal KontemporerDari EverandPolitik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal KontemporerPenilaian: 3 dari 5 bintang3/5 (2)
- Diet EsDokumen5 halamanDiet Esalvin 258Belum ada peringkat
- Tabel Total HPP Dan HPJ Bar N CafeDokumen5 halamanTabel Total HPP Dan HPJ Bar N Cafealvin 258Belum ada peringkat
- MaskerDokumen6 halamanMaskeralvin 258Belum ada peringkat
- Opini PublikDokumen123 halamanOpini Publikalvin 258Belum ada peringkat
- Diet HormonDokumen8 halamanDiet Hormonalvin 258Belum ada peringkat
- Tabel HPP Dan HJPDokumen4 halamanTabel HPP Dan HJPalvin 258Belum ada peringkat
- Kata Kata MutiaraDokumen1 halamanKata Kata Mutiaraalvin 258Belum ada peringkat
- 2279-Article Text-5263-2-10-20200630Dokumen36 halaman2279-Article Text-5263-2-10-20200630kim kaiBelum ada peringkat
- MolnuvipairDokumen5 halamanMolnuvipairalvin 258Belum ada peringkat
- 5 Manfaat Meminum Kopi Selain Sebagai Teman NyantaiDokumen1 halaman5 Manfaat Meminum Kopi Selain Sebagai Teman Nyantaialvin 258Belum ada peringkat
- 2279-Article Text-5263-2-10-20200630Dokumen36 halaman2279-Article Text-5263-2-10-20200630kim kaiBelum ada peringkat
- Bab 3Dokumen12 halamanBab 3Novy S Roga NgodeBelum ada peringkat
- Wirausaha & Ciri2 Seorang WirausahawanDokumen5 halamanWirausaha & Ciri2 Seorang Wirausahawanalvin 258Belum ada peringkat
- 5 Manfaat Meminum Kopi Selain Sebagai Teman NyantaiDokumen1 halaman5 Manfaat Meminum Kopi Selain Sebagai Teman Nyantaialvin 258Belum ada peringkat
- Communicate Ebook CARA NGOBROL AJAIB Revisi Ke 1Dokumen26 halamanCommunicate Ebook CARA NGOBROL AJAIB Revisi Ke 1alvin 258Belum ada peringkat
- 2009 Soal Olimpiade Ekonomi ProvinsiDokumen15 halaman2009 Soal Olimpiade Ekonomi ProvinsiYustamar RamatsuyBelum ada peringkat
- Soal Olim Eko TK Prov 2007Dokumen25 halamanSoal Olim Eko TK Prov 2007Agiel Pradana LukasBelum ada peringkat
- Contoh Pidato Tentang Narkoba Bahasa IndonesiaDokumen10 halamanContoh Pidato Tentang Narkoba Bahasa Indonesianatam13Belum ada peringkat
- SoalDokumen18 halamanSoalalvin 258Belum ada peringkat
- Scarcity Opportunity Cost Economics Problems Needs, Economics Economics System Circular Flow DiagramDokumen18 halamanScarcity Opportunity Cost Economics Problems Needs, Economics Economics System Circular Flow Diagramalvin 258Belum ada peringkat
- SoalDokumen14 halamanSoalalvin 258Belum ada peringkat
- Bill of Rights (Philippines)Dokumen2 halamanBill of Rights (Philippines)Jen100% (3)
- Sejarah Perkembangan Muka BumiDokumen22 halamanSejarah Perkembangan Muka Bumialvin 258Belum ada peringkat
- Teori Perilaku Konsumen Teori Perilaku ProdusenDokumen10 halamanTeori Perilaku Konsumen Teori Perilaku Produsenalvin 258Belum ada peringkat
- Communicate Ebook CARA NGOBROL AJAIB Revisi Ke 1Dokumen26 halamanCommunicate Ebook CARA NGOBROL AJAIB Revisi Ke 1alvin 258Belum ada peringkat
- Modul Pengantar GeografiDokumen46 halamanModul Pengantar Geografialvin 258100% (1)
- MatrikDokumen34 halamanMatrikalvin 258Belum ada peringkat
- MatrikDokumen34 halamanMatrikalvin 258Belum ada peringkat
- Materi MatrikulasiDokumen18 halamanMateri MatrikulasiFudhi AldianoBelum ada peringkat