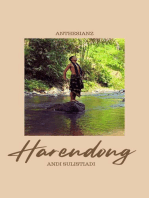Amdal Bidang Ekonomi
Amdal Bidang Ekonomi
Diunggah oleh
Zahara Fibryana PutriJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Amdal Bidang Ekonomi
Amdal Bidang Ekonomi
Diunggah oleh
Zahara Fibryana PutriHak Cipta:
Format Tersedia
AMDAL
Dampak Pembangunan Ekonomi terhadap Lingkungan Hidup
KELOMPOK 2 Deni Dita Amelia Eva Bai Syarifah Hidayatur Rahmah Subagyo Zahara Fibryana Putri 109095000017 109095000021 108095000027 109095000002 109095000046 109095000034
PROGRAM STUDI BIOLOGI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2012 M/ 1433 H
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Menjelang awal abad ke-21, negara-negara berkembang termasuk
Indonesia, terjadi suatu perubahan paradigma pembangunan secara drastis. Pada awal masa kemerdekaan, paradigma pembagunan lebih dominan ke arah industrialisasi. Selain diharapkan dapat mengangkat harkat hidup penduduk di negara-negara berkembang, secara politis indutrialisasi juga akan menyejajarkan kedudukan negara-negara tersebut dengan negara barat. Pembangunan drastis yang terjadi di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia namun berbagai permasalahan baik di bidang lingkungan, sosial budaya serta bidang pertanian. Dalam bidang lingkungan terjadi berbagai pencemaran seperti pencemaran udara, air, tanah dari berbagai industri berskala besar sampai industri rumah tangga. Industri saat ini tidak hanya berlokasi di kota-kota besar namun juga di pedesaan. Wilayah yang memiliki tanah produktif banyak yang berubah menjadi wilayah industri baik tekstil, makanan, perumahan, atau perkantoran yang menyebabkan dampak dibidang ekonomi masyarakat serta perusakan lingkungan. Masyarakat memiliki mata pencarian dari tanah yang masih produktif tersebut, setelah berubah fungsi lahan menyebabkan petani tidak bisa menggarap lahannya sehingga produktivitas pertanian Indonesia berkurang. Di sisi lain, dengan adanya
pembangunan dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bidang lingkungan, tidak banyak limbah hasil industri yang dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Pembuangan limbah beracun di badan air seperti sungai dan kali menyebabkan kematian bagi biota air dan berbagai penyakit bagi masyarakat sekitar. Banyak kasus pencemaran limbah air yang menyebabkan diare, muntaber, keracunan logam berat sampai alergi kulit. Dalam kasus seperti ini diperlukan analisis mengenai dampak lingkungan agar di ketauhi solusi serta pencegahan pencemaran yang merugikan. Menghadapi masalahmasalah hasil pembangunan tersebut perlu adanya kajian mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat.
1.2
Tujuan Tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui lingkungan. 2. Mengetahui dampak pembangunan Indonesia dalam sektor ekonomi. dampak pembangunan Indonesia dalam sektor
BAB II Tinjauan Pustaka
2.1
AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada dasarnya setiap pembangunan menyebabkan terjadinya perubahan
lingkungan. Dampak pembangunan ini ada yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, setiap rencana pembangunan perlu disertai dengan wawasan jauh ke depan tentang perkiraan timbulnya dampak tersebut. Wawasan ini diterapkan dengan mengadakan analisis perkiraan dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Analisis tersebut harus dilakukan secara terperinci tentang dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul, sehingga sejak dini dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulanginya (Supardi, 2003). Pembangunan kita perlukan untuk mengatasi banyak masalah, termasuk masalah lingkungan, namun pengalaman menunjukkan, pembangunan
mempunyai dampak negatif. Dengan adanya dampak negatif tersebut, haruslah kita waspada. Pada satu pihak kita tidak boleh takut untuk melakukan pembangunan, karena tanpa pembangunan tingkat kesejahteraan kita akan terus merosot, pada lain pihak kita harus memperhitungkan dampak negatif dan berusaha untuk menekannya menjadi sekecil-kecilnya. Pembangunan itu harus berwawasan lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan salah satu alat dalam upaya dilakukannya pembangunan berwawasan lingkungan (Soemarwoto, 1999).
2.2
Pembangunan Pembangunan pada hakekatnya adalah merubah lingkungan. Tidak ada
pembangunan yang tidak merubah lingkungan (Soemarwoto, 1983). Sumber daya alam (SDA) adalah pedesaan. Oleh sumber penghidupan khususnya bagi petani di daerah itu pembangunan yang dilaksanakan dengan
karena
memanfaatkan sumber daya alam akan melibatkan aspek fisik dan aspek sosial. Dari segi fisik, aset yang terkena pembangunan umumnya tanah milik dan penduduk yang bermukim didalamnya harus pindah karena tergusur. Begitu juga populasi yang bermukim disekitar pembangunan yang mempunyai aset dan akses di daerah tapak pembangunan kehilangan sumber penghidupannya. Agar pembangunan itu tidak merugikan rakyat, maka diberikan ganti rugi (Kepres, 1993). Pembangunan merupakan suatu perubahan, perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik atau usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Kemajuan yang dimaksud seringkali dikaitkan dengan kemajuan material, sehingga pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat dibidang ekonomi (Budiman, 2000: 1). Untuk mencapai sasaran tersebut, kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan baik dinegara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Namun persoalan yang dihadapinya oleh masing-masing negara berlainan. Bagi negara yang sudah maju (kapitalis)
persoalannya adalah bagaimana melakukan ekspansi lebih lanjut bagi kehidupan ekonominya yang sudah mapan, sedangkan pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, adalah bagaimana bertahan hidup atau bagaimana meletakan
dasar-dasar ekonominya agar dapat bertahan hidup supaya bisa bersaing dipasar internasional. Peletakan dasar pembangunan semestinya tidak hanya mementingkan aspek ekonomi akan tetapi juga aspek mengutamakan ekonomi dapat sosial. Pembangunan yang hanya instabilitas dan dapat
menimbulkan
menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai (Budiman, 2000). Pembangunan dibidang sosial yang selama ini termarginalisasikan, dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Melalui pendidikan formal dapat meningkatkan mutu modal manusia dan melalui pendidikan non-formal meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keakhlian (Skill), sehingga mampu hidup mandiri (Ananta, 1986). Budiman (2000:2-9) mengkonsepsikan bahwa keberhasilan pembangunan seyogyanya mengacu kepada 5 hal, yaitu : i). Kekayaan rata-rata. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dengan tolok ukurnya produktivitas masyarakat dan atau produktivitas negara setiap tahunnya, melalui Gross National Product (GNP) dan melalui Gross Domestik Product (GDP). Tolok ukur tersebut dapat dipergunakan untuk membandingkan negara yang satu dengan negara yang lainnya. ii). Pemerataan. Munculnya kesenjangan sosial adalah tidak meratanya kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksikan oleh semua penduduk. Sebagian kecil masyarakat memiliki kekayaan yang berlimpah sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Hal ini dapat dijumpai dalam
suatu negara yang PNB / kapitanya tinggi, tetapi dimana-mana orang hidup miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal. iii). Kualitas kehidupan. Tolok ukur kesejahteraan penduduk suatu negara dengan mempergunakan Physical Quality of Life Index (PQLI). Tolok ukur yang dikembangkan oleh Moris (1979, dalam Todaro 1992:102) ini mengenai rata-rata harapan hidup, rata-rata jumlah kematian bayi dan rata-rata prosentase buta huruf dan melek huruf. iv). Kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat terjadi baik dinegara maju maupun dinegara sedang berkembang. Kerusakan lingkungan dinegara maju karena mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dengan produktivitas yang tinggi tetapi tidak memperhatikan lingkungan. Begitupula pada negara sedang berkembang, mengeksploitasi sumber daya alam secara besarbesaran dengan produktivitas yang rendah tanpa memperhatikan lingkungan, lingkungan menjadi rusak. Ketidakpedulian terhadap lingkungan sekalipun dengan produktivitas yang tinggi dan menjadikan 6 suatu negara itu menjadi kaya akan mengalami kehancuran. v). Keadilan sosial dan kesinambungan. Faktor lingkungan dan keadilan sosial berfungsi untuk melestarikan pembangunan agar pembangunan itu
berkesinambungan
(Sustainable). Keadilan sosial bukan hanya pertimbangan
moral saja, akan tetapi berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Melebarnya kesenjangan yang kaya dengan yang miskin rentan terhadap kestabilan politis. Gejolak politik dan instabilitas sosial atau ganguan kamtibmas dapat menghancurkan pembangunan yang sudah dicapai, sehingga kerusakan
alam
dan ketidakadilan
merupakan kerusakan sosial dapat mengganggu
kesinambungan pembangunan.
2.3
Perekonomian
BAB III PEMBAHASAN
3.1
Lingkungan Konversi hutan alam menjadi berbagai peruntukan terus berlanjut dengan
laju yang sangat cepat. Setiap menitnya hutan alam seluas enam kali lapangan sepak bola rusak atau berubah menjadi peruntukan lain. Bank Dunia menaksir bahwa hutan alam dataran rendah Sumatera habis pada tahun 2005 dan menyusul Kalimantan pada tahun 2010. Data terakhir menyebutkan bahwa laju deforestasi di Indonesia sudah mencapai 2,83 juta ha per tahun (Dephut, 2005). Tingginya konversi hutan alam menjadi berbagai peruntukan lahan tersebut diyakini menjadi penyebab utama tingginya intensitas dan frekuensi bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana kini banyak terjadi di berbagai wilayah di bumi pertiwi.. Indonesia yang beriklim tropika basah memiliki intensitas hujan yang sangat tinggi. Kondisi curah hujan seperti ini, apabila tidak diimbangi dengan penata-kelolaan lahan yang baik terbukti berdampak pada kerusakan lahan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Sebenarnya alam telah diciptakan dengan penuh harmoni dan keseimbangan, tingginya intensitas hujan di wilayah tropis, telah diimbangi dengan penutupan hutan alam yang begitu luas. Sayangnya, hutan alam yang berperan sebagai gudang sumberdaya genetik dan pendukung ekosistem kehidupan ini sering menjadi korban kepentingan pragmatis jangka pendek, termasuk diantaranya adalah konversi menjadi perkebunan kelapa sawit, di lain pihak masih banyak tersedia lahan lain
selain hutan alam, termasuk diantaranya adalah lahan kritis yang kini telah mencapai 30 juta ha. Hutan alam, dibandingkan dengan penutupan lahan apapun, memiliki berbagai kelebihan dalam meredam tingginya intensitas hujan dan mengendalikan terjadinya banjir, erosi, sedimentasi dan tanah longsor. Hutan alam, khususnya yang berada di pegunungan bukan hanya berfungsi sebagai pengatur tata air (regulate water), namun juga penghasil air (produce water). Hutan alam memberikan kemungkinan terbaik bagi perbaikan sifat tanah, khususnya dalam menyimpan air, hutan alam memberikan tawaran penggunaan lahan yang paling aman secara ekologis. Penyebab hutan alam memiliki dampak yang baik bagi lingkungan yakni : 1. Pepohonan pada hutan alam menghasilkan serasah yang cukup tinggi sehingga mampu meningkatkan kandungan bahan organik lantai hutan, sedemikian rupa sehingga lantai hutan memiliki kapasitas peresapan air (infiltrasi) yang jauh lebih tinggi dibandingkan penutupan lahan nonhutan. Tebalnya lapisan serasah juga meningkatkan aktivitas biologi tanah, sedangkan siklus hidup/pergantian perakaran pohon (tree root turnover) yang amat dinamis dalam jangka waktu yang lama, membuat tanah hutan memiliki banyak pori-pori berukuran besar (macroporosity), sehingga tanah hutan memiliki laju penyerapan air/pengisian air tanah (perkolasi) yang jauh lebih tinggi. 2. Stratifikasi hutan alam (bervariasinya umur dan ketinggian tajuk hutan), tingginya serasah dan tumbuhan bawah pada hutan alam memberikan
penutupan lahan secara ganda, sehingga berfungsi efektif untuk mengendalikan erosivitas hujan (daya rusak hujan), laju aliran permukaan dan erosi. 3. Dari sisi bentang lahan (landscape), hutan memberikan tawaran penggunaan lahan yang paling aman secara ekologis, dalam hutan alam sangat sedikit sekali ditemukan jalan-jalan setapak, tidak ada saluran irigasi, apalagi jalan berukuran besar yang diperkeras sehingga pada saat hujan besar berperan sebagai saluran drainase. Biomasa hutan yang tidak beraturan juga berperan sebagal filterpergerakan air dan sedimen. Di dalam hutan alam juga tidak dilakukan pengolahan tanah yang membuat lahan lebih peka terhadap erosi. Hutan dalam kondisi yang tidak terganggu juga lebih tahan terhadap kekeringan sehingga tidak mudah terbakar.
Pembangunan kebun kelapa sawit yang dilakukan dengan mengkonversi hutan alam, selain merusak habitat hutan alam yang berarti menghancurkan seluruh kekayaan hayati hutan yang tidak ternilai harga dan manfaatnya, juga akan merubah landscape hutan alam secara total. Proses ini apabila tidak dilakukan dengan baik (dan biasanya memang demikian) akan berdampak pada kerusakan seluruh ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di bawahnya. Dampaknya, antara lain adalah meningkatnya aliran permukaan (surface runoff), tanah longsor, erosi dan sedimentasi. Kondisi ini semakin parah, apabila pembersihan lahan (setelah kayunya ditebang) dilakukan dengan cara pembakaran.
Dalam setiap perkebunan yang dikelola secara intensif, rumput dan tumbuhan bawah secara menerus akan dibersihkan, karena akan berperan sebagai gulma tanaman pokok. Di lain pihak, rumput dan tumbuhan bawah ini justru berperan sangat penting untuk mengendalikan laju erosi dan aliran permukaan. Keberadaan pepohonan yang tanpa diimbangi oleh pembentukan serasah dan tumbuhan bawah justru malah meningkatkan laju erosi permukaan. Mengingat energi kinetik tetesan hujan dari pohon setinggi lebih dari 7 meter justru lebih besar dibandingkan tetesan hujan yang jatuh bebas di luar hutan. Dalam kondisi ini, tetesan air tajuk (crown-drip) memperoleh kembali energi kinetiknya sebesar 90% dari enerji kinetik semula, di samping itu butir-butir air yang tertahan di daun akan saling terkumpul membentuk butiran air (leaf-drip) yang lebih besar, sebingga secara total justru meningkatkan erosivitas hujan. Pembangunan perkebunan memerlukan pembangunan jalan, dari jalan utama hingga jalan inspeksi, serta pembangunan infrastruktur (perkantoran, perumahan), termasuk saluran drainase. Kondisi ini apabila tidak dilakukan dengan baik (lagi-lagi biasanya memang demikian) akan berdampak pada semakin cepatnya air hujan mengalir menuju ke hilir. Implikasinya, peresapan air menjadi terbatas dan peluang terjadinya banjir dan tanah longsor akan meningkat. Di lain pihak, pohon kelapa sawit sebagai pohon yang cepat tumbuh (fast growing species) dikenal sebagai pohon yang rakus air, artinya pohon ini memiliki laju evapotranspirasi (penguap-keringatan) yang tinggi. Setiap pohon sawit memerlukan 20-30 liter air setiap harinya. Dengan demikian konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit dapat mengurangi ketersediaan air
khususnya di musim kemarau. Sumber-sumber air di sekitar kebun kelapa sawit terancam lenyap, seiring dengan pertambahan luas dan bertambahnya umur pohon kelapa sawit.
3.2
Ekonomi Indonesia kini dikenal sebagai penghasil dan pengekspor minyak sawit
(Eleais quinensis Jack) kedua terbesar di dunia setelah Malaysia. Untuk mendukung pengembangan industri sawit, Departemen Pertanian tahun 2006 telah menyiapkan anggaran Rp. 380 miliar. Pengembangan itu berkaitan juga dengan pencetakan energy farming, khususnya biodisel dari minyak sawit. Bahkan, pemerintah baru-baru ini berencana untuk mencetak kebun kelapa sawit seluas dua juta hektar di wilayah perbatasan Kalimantan. Memperhatikan tingginya target perluasan perkebunan sawit, tidak menutup kemungkinan bahwa hutanhutan alam yang masih tersisa saat ini menjadi sasaran konversi. Di wilayah lain, termasuk di Propinsi Sulawesi Tenggara, konversi hutan alam menjadi kebun kelapa sawit juga sedang marak terjadi, sebagaimana di Kabupaten Konawe dan Kolaka dan kemungkinan akan pula terjadi di Kabupaten Buton. Dengan besarnya produksi kelapa sawit di Indonesia memberikan dampak positf dibidang ekonomi yakni penyerapan tenaga kerja, perbaikan taraf hidup masyarakat sekitar dengan menjadi buruh perkebunan, meningkatnya devisa ngera dari penjualan minyak kelapa sawit.
BAB IV KESIMPULAN
Dampak bagi lingkungan dari konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit adalah kerusakan lahan dan berbagai bencana lingkungan seperti banjir dan tanah longsor.
Pertumbuhan ekonomi meningkat dengan dibangunnya perkebunan kelapa sawit dengan menyediakan lapangan pekerjaan, perbaikan taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan dan meningkatkan devisa negara dari hasil penjualan kelapa sawit.
DAFTAR PUSTAKA
Syahza, Almasdi. 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau. Jurnal Ekonomi, Th.X/03
Yusuf, Helmi., Kooswardhono Moedikdjo., M Sri Saeni Dan Lutfi I. Nasution. 2005. Dampak Pembangunan Pelabuhan Peri Kanan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pendapatan Masyarakat(Stud; Kasus D; Pelabuhan Perlkanan Lempaslng, Bandar Lampung). Buletin Ekonomi Perikanan Vol. Vi. No. 1
Suherman, Agus Dan Adhyaksa Dault. 2009. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan Jembrana Bali. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 4, No. 2, 2009 : 24 - 32
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Dan ManusiaDokumen6 halamanMakalah Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan Dan ManusiaChintia100% (1)
- Dampak Positif Dan Negatif Dari Pembangunan EkonomiDokumen14 halamanDampak Positif Dan Negatif Dari Pembangunan EkonomiArsal Maulana100% (1)
- Makalah Pembangunan Ekonomi (Makro)Dokumen17 halamanMakalah Pembangunan Ekonomi (Makro)Cut Intan HayaturrahmiBelum ada peringkat
- Makalah Kembang ApiDokumen8 halamanMakalah Kembang Apikristina zendratoBelum ada peringkat
- Makalah PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN SOLUSIDokumen12 halamanMakalah PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN SOLUSIAndi Muh Ishak YusmaBelum ada peringkat
- Dampak Pembangunan LingkunganDokumen12 halamanDampak Pembangunan Lingkunganundari sastaBelum ada peringkat
- Thineza Vira E - UTSDokumen18 halamanThineza Vira E - UTSThineza ViraBelum ada peringkat
- Vigor 1904010080Dokumen4 halamanVigor 1904010080Muhammad ArdiBelum ada peringkat
- Makalah Ekonomi PembangunanDokumen11 halamanMakalah Ekonomi PembangunanIin Agustian100% (1)
- Lingkungan Dan PembangunanDokumen5 halamanLingkungan Dan PembangunanOgi Bin AhmadBelum ada peringkat
- Kaajian Lingkungan Hidup IiDokumen11 halamanKaajian Lingkungan Hidup Iiyuliarnol alikBelum ada peringkat
- Makalah IadDokumen10 halamanMakalah IadMuhammad GozaliBelum ada peringkat
- Makalah Pembangunan BerkelanjutanDokumen23 halamanMakalah Pembangunan BerkelanjutanMuhammad AzhariBelum ada peringkat
- Makalah Pembangunan BerkelanjutanDokumen10 halamanMakalah Pembangunan Berkelanjutanfauziah zeinBelum ada peringkat
- Pokok Bahasan IV Sub 1Dokumen28 halamanPokok Bahasan IV Sub 1Arsita R. PutriBelum ada peringkat
- Pembangunan BerkelanjutanDokumen10 halamanPembangunan BerkelanjutanAmesta Ramadhani0% (1)
- Pendekatan AgroekosistemDokumen12 halamanPendekatan Agroekosistemmr.andBelum ada peringkat
- Makalah Ekonomi HijauDokumen17 halamanMakalah Ekonomi HijauHollowAnggaraBelum ada peringkat
- Hubungan Lingkungan Dan PembangunanDokumen8 halamanHubungan Lingkungan Dan PembangunanAdi SetiadiBelum ada peringkat
- Pembangunan Berkelanjutan Dan Pendidikan Kewarganegaraan GlobalDokumen7 halamanPembangunan Berkelanjutan Dan Pendidikan Kewarganegaraan GlobalmaqrifawpBelum ada peringkat
- Analisis Dampak LingkunganDokumen11 halamanAnalisis Dampak LingkunganTing Gapi Unhik WprLimatujuhBelum ada peringkat
- Kata PengantarDokumen15 halamanKata PengantarCendra IrawanBelum ada peringkat
- Makalah Pengetahuan LingkunganDokumen13 halamanMakalah Pengetahuan Lingkunganbertha tandi100% (1)
- Apakah Green Economy Bisa Menjadi Solusi Tepat Untuk Stabilitas Sektor Keuangan Dalam Sustainable Development GoalsDokumen10 halamanApakah Green Economy Bisa Menjadi Solusi Tepat Untuk Stabilitas Sektor Keuangan Dalam Sustainable Development GoalsMifta AmaliaBelum ada peringkat
- Terhambatnya Proses Pendidikan Akibat Konflik Rencana Pembangunan RempangDokumen8 halamanTerhambatnya Proses Pendidikan Akibat Konflik Rencana Pembangunan RempangRosa AmeliaBelum ada peringkat
- Disusun OlehDokumen11 halamanDisusun OlehNalendra BayuBelum ada peringkat
- Mengatasi Ketidakadilan Sosial Ekonomidan EkologiDokumen12 halamanMengatasi Ketidakadilan Sosial Ekonomidan EkologiIntanBelum ada peringkat
- Teori-Teori Pembangunan MasyarakatDokumen25 halamanTeori-Teori Pembangunan MasyarakatPolce BettyBelum ada peringkat
- EkonomiDokumen2 halamanEkonomiMellinia FebriantiBelum ada peringkat
- Pembangunan Berkelanjutan Dan Bisnis GlobalDokumen18 halamanPembangunan Berkelanjutan Dan Bisnis GlobalAnnisa Tri MarlinaBelum ada peringkat
- Makalah Lingkungan Dan PembangunanDokumen38 halamanMakalah Lingkungan Dan PembangunanVieza Saestika100% (1)
- Contoh Makalah Pembangunan BerkelanjutanDokumen14 halamanContoh Makalah Pembangunan BerkelanjutanRezal R Ramdhan100% (7)
- Tugas Filsafat Ilmu EkonomiDokumen18 halamanTugas Filsafat Ilmu EkonomiSanisa WilogeniBelum ada peringkat
- Makalah Pembangunan BerkelanjutanDokumen12 halamanMakalah Pembangunan BerkelanjutanViva Queenika Mutiara100% (1)
- Publik - Makalah Green & Clean - PancasilaDokumen22 halamanPublik - Makalah Green & Clean - PancasilaYustika PrawestiBelum ada peringkat
- Makalah KelompokDokumen12 halamanMakalah KelompoksazeayukiraBelum ada peringkat
- Mengulas Buku Ecology, Economy, EquityDokumen14 halamanMengulas Buku Ecology, Economy, EquitySETIYANA HAYUNING TRIBUANABelum ada peringkat
- Pembangunan BerkelanjutanDokumen26 halamanPembangunan BerkelanjutanS BamBelum ada peringkat
- Tugas 01, Sejarah PerkotaanDokumen4 halamanTugas 01, Sejarah PerkotaanSri wahyuniBelum ada peringkat
- Pembangunan Dan Kemiskinan 12Dokumen16 halamanPembangunan Dan Kemiskinan 12lalaBelum ada peringkat
- Makalah LingkunganDokumen15 halamanMakalah LingkunganAhmad MubarakBelum ada peringkat
- Antara Pembangunan Ekonomi Dan Degradasi 287bbe4eDokumen8 halamanAntara Pembangunan Ekonomi Dan Degradasi 287bbe4eArippeBelum ada peringkat
- Makalah Hubungan Lingkungan Dan PembangunanDokumen9 halamanMakalah Hubungan Lingkungan Dan PembangunanAdi Setiadi100% (3)
- RevisianDokumen10 halamanRevisianHindhuBelum ada peringkat
- Makalah Perspektif Global IsuDokumen6 halamanMakalah Perspektif Global IsuNila Nilam SariBelum ada peringkat
- Tugas Debarnal Pembangunan BerkelanjutanDokumen20 halamanTugas Debarnal Pembangunan BerkelanjutanTimorensia SinagaBelum ada peringkat
- Makalah Hubungan Lingkungan Dan PembangunanDokumen9 halamanMakalah Hubungan Lingkungan Dan Pembangunanrx91Belum ada peringkat
- Tugas Jurnal KelompokDokumen3 halamanTugas Jurnal KelompokAGLESIUS BAMOLELE 147Belum ada peringkat
- Tio Pradena Putra 2220842002Dokumen6 halamanTio Pradena Putra 2220842002Gembel VlogBelum ada peringkat
- Kel. 5 Makalah Sosiologi - Kependudukan Dan Lingkungan HidupDokumen14 halamanKel. 5 Makalah Sosiologi - Kependudukan Dan Lingkungan HidupRiiska TrianaBelum ada peringkat
- Jawaban UAS SDGs - Singgih AbiyuwonoDokumen4 halamanJawaban UAS SDGs - Singgih AbiyuwonoSinggih AbiyuwonoBelum ada peringkat
- Mengatasi Masalah Lingkungan Akibat PembangunanDokumen14 halamanMengatasi Masalah Lingkungan Akibat PembangunanBrian christhopel PalawaBelum ada peringkat
- Jasamiadr PembangunanDokumen13 halamanJasamiadr PembangunanErBelum ada peringkat
- Musafidin EKP tgl26Dokumen12 halamanMusafidin EKP tgl26winda herfia septianiBelum ada peringkat
- MAKALAH Negara Maju Dan BerkembangDokumen14 halamanMAKALAH Negara Maju Dan BerkembangArief Knight100% (1)
- Pembangunan Dan Dampak Terhadap LingkunganDokumen6 halamanPembangunan Dan Dampak Terhadap Lingkunganlaptop hpBelum ada peringkat
- Makalah HidayDokumen16 halamanMakalah HidayPonPes Nasyrul UlumBelum ada peringkat
- Ketimpangan Sosial Dalam MasyarakatDokumen7 halamanKetimpangan Sosial Dalam MasyarakatHanin PutriBelum ada peringkat