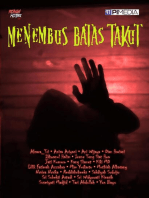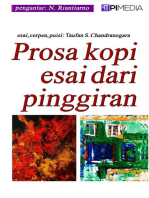In Memoriam Marianne Katoppo
Diunggah oleh
elpiwin1490 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
331 tayangan6 halamanHak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
331 tayangan6 halamanIn Memoriam Marianne Katoppo
Diunggah oleh
elpiwin149Hak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 6
In memoriam Marianne Katoppo:
Seorang Perempuan Telah Pergi
Oleh
Elpiwin Adela
Untuk membuka tulisan ini saya ingin menceritakan kisah yang
dituturkan Arief Budiman tentang adiknya yang mati muda: Soe Hok Gie. Soe
Hok Gie pergi ke pendakian Semeru yang merenggut jiwanya setelah bercerita
tentang kesepian sebagai intelektual kritis yang makin lama punya semakin
banyak musuh dan semakin sedikit kawan. Ia berangkat dengan
mempertanyakan apa tujuan dari segala yang ia lakukan, apakah hidupnya sia-
sia saja. Arief Budiman menjawab pertanyaan adiknya dengan kesaksian.
Sewaktu jenazah Soe diinapkan di rumah seorang Kepala Desa di
Malang, tukang peti yang mengetahui bahwa itu adalah jenazah Soe menangis
dan terus menangis ketika ditanya mengapa. Ia hanya sempat bilang, “Dia
orang berani. Sayang dia meninggal...”
Lalu ketika jenazah itu dibawa terbang oleh pesawat AURI dan singgah di
Yogya, pilot yang mengemudikan pesawat duduk-duduk bersama Arief,
menyatakan kesedihannya, “Saya kenal namanya. Saya senang membaca
karangan-karangannya. Sayang sekali dia meninggal. Dia mungkin bisa
berbuat lebih banyak jika hidup terus....”
Saya adalah tukang peti mati dan pilot itu. Suara mereka sekarang
adalah suara saya untuk Henriette Marianne Katoppo. Saya tidak tahu apakah
Ibu Marianne sebagai aktivis yang sering berlawanan dengan mainstream juga
kesepian seperti Soe Hok Gie, saya yang tidak pernah berjumpa dengannya
hanya ingin menuliskan penghormatan saya untuk beliau.
Henriette Marianne Katoppo sebagai perempuan adalah sosok yang
menarik perhatian saya pada waktu saya masih belia. Saya mengenalnya
melalui Malam, novel Elie Wiesel yang menceritakan penderitaan orang Yahudi
dalam kamp Nazi, novel yang dalam pengantarnya disebut Mochtar Lubis
“seharusnya menjadi bacaan wajib bagi setiap anak manusia.....” Saya ingat
saya membaca novel terjemahan ini dengan sangat nyaman, sebuah tanda
hasil penerjemahan yang sangat baik. Ketika saya membaca nama
penerjemahnya, saya langsung menandainya sebagai perempuan yang hebat,
hebat dalam berbahasa dan dalam memilih karya untuk diterjemahkan.
Saya lalu mendengar namanya lagi dalam buku pelajaran sastra
Indonesia. Raumanen. Novel pertamanya langsung memenangkan Lomba
Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 1975, Hadiah Yayasan Buku Utama tahun
1978, dan South East Asian Write Award tahun 1982 (ia satu-satunya
perempuan Indonesia yang pernah menerima hadiah ini). Saya mencari buku
itu dan menemukannya. Itu adalah jenis buku yang tidak akan disetujui ibu
saya untuk dibaca seorang anak SMP.
Setelah membaca Raumanen, saya kehilangan jejak karya-karyanya.
Saya lalu mengabaikannya, tidak mencari tahu lebih banyak lagi tentang
beliau. Saya hanya membaca tentang dia sambil lalu, bahwa ia mahir 10
bahasa (!) dan adik dari Aristides Katoppo, mantan Pemred Sinar Harapan yang
dibredel tahun 1986. Saya lalu membaca Ayu Utami dan Djenar tapi seperti
rasa kopi lama, saya ingat ada ”roso” dari Raumanen yang tidak saya
dapatkan dari para penulis perempuan itu.
Dalam pertemuan saya dengan karya lain yang luar biasa, saya kembali
berjumpa dengan namanya. Saya membaca Lapar dari Knut Hamsun dan lagi-
lagi saya menemukan bahwa Ibu Marianne Katoppo-lah adalah penerjemah
novel itu. Kemampuan berbahasanya sangat mengagumkan, menerjemahkan
Lapar bukan hal yang mudah. Novel itu novel psikologis dari seseorang yang
berasal dari Skandinavia yang tentu saja memiliki budaya dan ”roso” yang jauh
dari kita tapi saya tidak menemukan cela dalam terjemahannya.
Itu masih belum cukup untuk membuat saya mencari tahu lebih banyak
lagi tentang beliau. Kedatangan saya ke tanah Minahasa juga tidak membuat
saya mencari tahu tentang jejaknya di tanah kelahirannya. Sampai beberapa
hari lalu saya membaca sebuah obituari di koran lokal, bukan di halaman
pertama atau kedua, tempat yang sering mereka berikan untuk obituari
mantan pejabat, tapi di halaman kedua sebelum terakhir. Saya membaca
tulisan seorang pendeta.
Saya terkejut dan menyesal. Semakin saya membaca lebih jauh semakin
besar penyesalan saya. Dari tulisan itu saya tahu bahwa ia adalah seorang
teolog feminis pertama di Asia. Dari tulisan itu saya tahu bukunya,
”Compassionate and Free” menjadi textbook sekolah-sekolah teologi Asia
bahkan dunia. Saya, orang yang belum pernah bertemu dengan beliau
menyesal karena tidak mencari tahu lebih banyak tentang dia sedari dulu.
Saya merasakan penyesalan yang sama seperti penyesalan yang saya rasakan
ketika Romo Mangun wafat. Saya juga sedih ketika membaca bahwa ia begitu
berkeinginan untuk kembali ke tanah kelahirannya, mengajar di Universitas
Kristen Tomohon, keinginan yang tidak kesampaian. Untuk menghormatinya,
saya mengumpulkan beberapa tulisan dan mulai menuliskan ini:
“Saya sering disebut sebagai musuh Kartini,” begitu pengakuannya
dalam sebuah wawancara. Agak getir. Ia mendapat sebutan itu karena
menyatakan bahwa peranan Kartini tidak sebesar yang diduga orang. Ada
perempuan-perempuan lain yang menurutnya lebih revolusioner dalam
memperjuangkan haknya, menyatukan pemikiran dengan tindakan seperti
Dewi Sartika di Pasundan dan Tjoet Nyak Dhien di tanah rencong. Jadi bukan
berarti ia tidak menghormati Kartini. Ia, dalam kewajiban keilmuannya, sebagai
orang yang tahu lebih banyak, berkewajiban menyampaikan bahwa Kartini
bukan satu-satunya pejuang perempuan Indonesia dan bahwa publikasi
tentang Kartini barangkali tidak bebas dari tujuan pelaksanaan politik etis
Belanda. Kartini adalah sosok yang dekat dengan Belanda sementara ada
perempuan-perempuan lain yang nonkooperatif dengan Belanda kurang
mendapatkan publikasi meski karya-karya mereka lebih nyata dari Kartini.
Adalah beban pengetahuan juga yang menyebabkan ia semenjak tahun
1978, berkeras menggunakan kata “perempuan” ketimbang “wanita”. Ia
mengetahui asal muasal kedua kata itu sementara banyak dari kita tidak
mengetahuinya. Perempuan menurutnya berarti sangat dalam dan sama sekali
berbeda dengan wanita. Perempuan adalah “empu”, seorang ahli.
Perumpamaannya adalah Mpu jari (jempol), fungsi mpu jari dalam semua
aktivitas jari tangan sangat menentukan. Jika maknanya disejajarkan,
perempuan adalah orang yang memiliki otoritas atas diri dan tubuhnya.
Berbeda dengan “wanita” yang dalam terminologi Jawa berasal dari “wani nek
ditoto” (berani jika ditata, keberaniannya hanya ada kalau orang lain
memintanya). Perempuan adalah subjek yang melakoni sesuatu, yang
mempengaruhi sesuatu sementara “wanita” adalah objek yang hampir tidak
memiliki kehendak, bergerak hanya karena kekuatan di luar dirinya. Dia hanya
mau dipuja, diagungkan, dan –dalam bahasa sekarang- dieksploitasi.
Pengetahuan, pemahaman akan jaman, dan compassion juga
membawanya ke Manila pada tahun 1995. Ia mewakili Pramoedya Ananta Toer
yang masih kena cekal, menerima penghargaan Ramon Magsaysay dari
pemerintah Filipina. Cukup berat tentu salib yang dipikulnya karena
penghargaan itu di tanah air menuai protes yang sangat keras baik dari
kalangan sastrawan maupun masyarakat awam sastra.
Jalan seorang intelektual yang bebas mungkin memang jalan yang sunyi,
seperti yang Gie bilang. Bukunya, “Compassionate and Free, Asian Women
Theology” yang ditulisnya dan diterbitkan Dewan Gereja Dunia di Jenewa Swiss
pada tahun 1979, menjadi textbook teologi feminis di banyak negara, telah
diterjemahkan ke dalam 30 bahasa tapi di Indonesia sendiri buku itu dilarang.
Di dalam modul teolog feminis alamamaternya, Sekolah Tinggi Teologia
Jakarta, tidak ada nama Marianne Katoppo....
Tapi seorang Marianne Katoppo dengan lakon yang telah saya sebutkan
di atas bukan orang yang layu karena kritik. Ia seorang penulis kawakan yang
mulai menulis sejak usia 8 tahun. Selain Raumanen, ia menulis pula Dunia Tak
Bermusim (1974), Anggrek Tak Pernah Berdusta (1977), Terbangnya Punai
(1978), dan Rumah di Atas Jembatan (1981).
Jika iman adalah sesuatu yang dinamis maka Marianne Katoppo adalah
orang yang rajin menuliskan dinamika imannya. Baik dalam Raumanen
maupun dalam Compassionate and Free, dengan berani ia membedah imannya
yang berarti membedah dirinya sendiri, suka dan lukanya sebagai seorang
perempuan Asia yang Kristen. Dalam karya-karyanya sebagai seorang aktivis
feminis, Marianne menegaskan pentingnya kemandirian perempuan, termasuk
kemandirian dalam iman yang berarti keberanian melepaskan diri dari
kungkungan kebudayaan luar yang asing. Perempuan harus bisa
membebaskan dirinya dari nilai-nilai pinjaman atau ideologi yang tidak ia
akrabi, begitu sering ia tegaskan.
Perjalanan imannya adalah perjalanan yang jauh. Tahun 1963 setamat
Sekolah Theologi Jakarta ia melanjutkan pendidikannya ke International
Christian University di Tokyo. Ia kemudian bekerja sebagai peneliti naskah di
salah satu penerbitan tertua dunia, British and Foreign Bible Society. Kemudian
ia pindah bekerja menjadi salah seorang Sales Assistant Svenska Pressbyran,
Swedia (1972-1974). Ia juga pernah bekerja selama 3 tahun sebagai editor di
Yayasan Obor Indonesia, membantu Mochtar Lubis. Pengalamannya berkeliling
berbagai negara membuat ia menguasai setidaknya 10 bahasa asing termasuk
bahasa Yunani dan Ibrani. Marianne Katoppo yang sering dipanggil Jettie di
antara teman dan keluarganya juga adalah anggota pendiri dan mantan
Koordinator Eucumenical Association of Third World Theologians (EATWOT)
Indonesia (1982), pendiri Forum Demokrasi bersama Gus Dur dkk (1991),
Kelompok Hapus Hukuman Mati (HATI) (1980), dan International Council World
Conference for Religion and Peace (1989-1994).
Teman-temannya bukan saja dari kalangan Protestan, tetapi Katolik dan
Ortodoks, kalangan Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu, Sikh.
Karyanya menunjukkan iman tidak beku sebagai hal yang melulu
eksklusif, individualis, tapi cair jadi hal yang ditunjukkan pada orang banyak
dan diperjuangkan. Dalam sosoknya yang bebas ia menunjukkan sosok Tuhan
yang mampu bikin tunduk dalam kemerdekaan kita.
Keterlibatannya pada pergumulan pluralisme dan multikulturalisme
adalah sejalan dengan teologi pembebasannya: teologi perempuan. Berangkat
dari pilihan ini ia menyerukan agar konsep Imago Dei diterjemahkan dalam
perjuangan untuk mencapai kondisi manusia yang penuh, utuh, Liberation
Theology Toward Full Humanity. Ia menyeru agar iman dibawa dan
diimplementasikan dalam dunia, hidup sehari-hari, dalam karya untuk
kemanusiaan yang penuh.
Semoga, dalam kondisi telah mencapai ”live life to the fullest” inilah
beliau dipanggil oleh Tete manis sehingga ia tergolong dalam kelompok orang
yang dapat menyanyikan puisi (saya lupa penulisnya) ”segalanya telah
dibersihkan, meja telah siap, biarlah malam datang”.
Anda mungkin juga menyukai
- Kritik SastraDokumen32 halamanKritik SastraLatifahdinarBelum ada peringkat
- TERBAKAR AMARAHDokumen11 halamanTERBAKAR AMARAHfianBelum ada peringkat
- Analisis Karya Sastra Marianne KatoppoDokumen49 halamanAnalisis Karya Sastra Marianne KatoppoDian NovitasariBelum ada peringkat
- Tugas IndividuDokumen6 halamanTugas IndividuDindaBelum ada peringkat
- Citra Perempuan Jawa Modern Dalam Novel Pada Sebuah KapalDokumen5 halamanCitra Perempuan Jawa Modern Dalam Novel Pada Sebuah KapalFatma Eka SafiraBelum ada peringkat
- Teks Biografi Struktur dan Unsur KebahasaanDokumen2 halamanTeks Biografi Struktur dan Unsur KebahasaanHanania DesainBelum ada peringkat
- BiografiDokumen8 halamanBiografiDwi Puspa NingrumBelum ada peringkat
- ANALISIS SOSIOLOGIDokumen11 halamanANALISIS SOSIOLOGIFarrah MawaBelum ada peringkat
- Artikel Novel AyatDokumen15 halamanArtikel Novel AyatNovi YudiaBelum ada peringkat
- editorsnpasca,+4.+ARTIKEL+SEMNAS+2019_SUMARTINI_331-333Dokumen3 halamaneditorsnpasca,+4.+ARTIKEL+SEMNAS+2019_SUMARTINI_331-333anandyaprijandokoBelum ada peringkat
- SasbanDokumen12 halamanSasbanAhmad Arief RifaldiBelum ada peringkat
- KAJIAN TASAWUFDokumen15 halamanKAJIAN TASAWUFIbtisaamatin LadzidzahBelum ada peringkat
- Biografi Achdiat Karta MiharjaDokumen2 halamanBiografi Achdiat Karta MiharjaNamaku WanddiBelum ada peringkat
- Interteks Layar Terkembang Dan BelengguDokumen14 halamanInterteks Layar Terkembang Dan BelengguAhmad Arief Rifaldi100% (1)
- WajahKemanusiaanDokumen11 halamanWajahKemanusiaanIbiroma WamlaBelum ada peringkat
- AndikaDokumen20 halamanAndikaMuhammad Imam Syafi'iBelum ada peringkat
- Akbar NavisDokumen7 halamanAkbar NavisPutra Dianda PratamaBelum ada peringkat
- Helvy's ThreadsDokumen8 halamanHelvy's ThreadsAnita AnitaBelum ada peringkat
- Jevan Alandro - Tugas Membuat AbstrakDokumen5 halamanJevan Alandro - Tugas Membuat Abstrak2209 Jevan AlandroBelum ada peringkat
- Resensi Buku Fiksi IndonesiaDokumen3 halamanResensi Buku Fiksi IndonesiaNabila putri DistariBelum ada peringkat
- Resensi Novel Cinta SaniaDokumen3 halamanResensi Novel Cinta SaniaBayu SaputraBelum ada peringkat
- 25 Novita Firdaus Nasrillah x5Dokumen7 halaman25 Novita Firdaus Nasrillah x5SwullyBelum ada peringkat
- Tugas 1-Farijihan Ardiyanti Putri-13010119130067Dokumen9 halamanTugas 1-Farijihan Ardiyanti Putri-13010119130067Farijihan Ardiyanti PutriBelum ada peringkat
- Review Buku Laut Bercerita Karya Leila SDokumen3 halamanReview Buku Laut Bercerita Karya Leila S01. Abrar Rajwaa TamaBelum ada peringkat
- Review Buku Habis Gelap Terbitlah TerangDokumen2 halamanReview Buku Habis Gelap Terbitlah TerangArief SuhardimanBelum ada peringkat
- Resensi Novel Spiritual Rahasia Cinta Dan HatiDokumen5 halamanResensi Novel Spiritual Rahasia Cinta Dan HatiCharizma Monica100% (1)
- Biografi PahlawanDokumen81 halamanBiografi Pahlawanhery rahmanBelum ada peringkat
- Kartini InspirasiDokumen12 halamanKartini InspirasiArief nugrahaBelum ada peringkat
- Latar Belakang Masalah Robohnya Surau KamiDokumen12 halamanLatar Belakang Masalah Robohnya Surau KamiWeny Harianty100% (1)
- Biografi R.A KartiniDokumen3 halamanBiografi R.A KartiniANNABILA ANISABelum ada peringkat
- Analisis Cerpen Robohnya Surau KamiDokumen20 halamanAnalisis Cerpen Robohnya Surau KamiTalita KumalaBelum ada peringkat
- KelasC RiyanApriliyan 24071121100 1 DikonversiDokumen3 halamanKelasC RiyanApriliyan 24071121100 1 Dikonversi24071122046Belum ada peringkat
- Analisis Cerpen Robohnya SurauDokumen24 halamanAnalisis Cerpen Robohnya SurauHendrasYamatoBelum ada peringkat
- Dari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke RomaDokumen31 halamanDari Ave Maria Ke Jalan Lain Ke RomaEvander TampubolonBelum ada peringkat
- aziz rio kausarDokumen3 halamanaziz rio kausarkhalfi SyahrinBelum ada peringkat
- Analisis Cerpen Robohnya Surau KamiDokumen18 halamanAnalisis Cerpen Robohnya Surau KamiMulkan Andika Situmorang100% (1)
- Bab IDokumen9 halamanBab IAYEESHA KARIMABelum ada peringkat
- Cerpen SurauDokumen22 halamanCerpen SurauRatih Paramitha IdaAyuuBelum ada peringkat
- Biografi R.A KartiniDokumen10 halamanBiografi R.A KartiniAyer Indarto100% (2)
- Perempuan Yang Termarginalkan Dalam Cerpen Karya Utuy Tatang SontaniDokumen10 halamanPerempuan Yang Termarginalkan Dalam Cerpen Karya Utuy Tatang Sontanitenanki100% (2)
- IBU KITDokumen4 halamanIBU KITIdha KwecielBelum ada peringkat
- Resensi 3 BukuDokumen3 halamanResensi 3 BukuFedi KurniawanBelum ada peringkat
- KETERWAKILAN, Kita Dan Pengrajin Kata-KataDokumen6 halamanKETERWAKILAN, Kita Dan Pengrajin Kata-KataMerchantimorBelum ada peringkat
- Analisis Novel AtheisDokumen14 halamanAnalisis Novel AtheisUtsmanul Fatih Nak UltrasBelum ada peringkat
- Raden Ajeng KartiniDokumen11 halamanRaden Ajeng KartiniAyer IndartoBelum ada peringkat
- Tulisan Untuk Anna DeslianiDokumen3 halamanTulisan Untuk Anna DeslianiMoh MahfudBelum ada peringkat
- Mas Gagah Perwira PratamaDokumen3 halamanMas Gagah Perwira PratamaDzakiBelum ada peringkat
- M. Aji Firdianto-200301110089Dokumen19 halamanM. Aji Firdianto-200301110089Muhamad Aji FirdiantoBelum ada peringkat
- Tokoh SastraDokumen21 halamanTokoh SastraNur Leni AnggraeniBelum ada peringkat
- RA KartiniDokumen7 halamanRA KartiniEgi VoorheesBelum ada peringkat
- Resensi Novel Laut BerceritaDokumen9 halamanResensi Novel Laut BerceritaLia Nadjwa100% (4)
- KEPENTINGAN SASTERADokumen6 halamanKEPENTINGAN SASTERAsardimpblBelum ada peringkat
- Tugas Biodata Bahasa IndonesiaDokumen7 halamanTugas Biodata Bahasa IndonesiaAku ArinBelum ada peringkat
- Kontroversi KartiniDokumen48 halamanKontroversi KartiniSaori HaraBelum ada peringkat
- Biografi Dan KArya-karya Iwan SimatupangDokumen7 halamanBiografi Dan KArya-karya Iwan SimatupangGita TrisnawatiBelum ada peringkat
- Ada Apa Dibalik Peringatan Hari Kartini 21Dokumen10 halamanAda Apa Dibalik Peringatan Hari Kartini 21Helmon Chan100% (1)
- Yuyun PermanasariDokumen10 halamanYuyun Permanasaridasepsatriana100% (1)