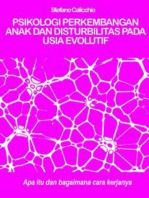2082 6092 1 PB
2082 6092 1 PB
Diunggah oleh
Imo AndersonJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
2082 6092 1 PB
2082 6092 1 PB
Diunggah oleh
Imo AndersonHak Cipta:
Format Tersedia
Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional
I Putu Agus Aryatnaya Giri1, Ni Luh Ardini2, Ni Wayan Kertiani3
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar 1,
Kementerian Agama Kabupaten Tabanan2,3
putugiri46@gmail.com1, luhardini@gmail.com2, kertianiwayan@gmail.com3
Keywords: ABSTRACT
Pancasila; The foundation of philosophy in education is very important.
Philosophical The foundation of educational philosophy will direct humans or
Basis; National educators to think deeply or rooted about the nature of education.
Education In addition, the existence of a nation is reflected in the educational
philosophy adopted. Likewise, a good education reflects the
foundation of a strong and solid educational philosophy.
Education is said to be good, when it is able to produce ideal
quality humans. The results of the analysis describe that the
Indonesian nation has Pancasila as the country's philosophy.
Pancasila should be the soul of the Indonesian nation, to be
enthusiastic in working in all fields, especially education. The
practice of Pancasila must be in the whole and integrity of the five
precepts in the Pancasila, as formulated in the preamble to the
1945 Constitution, namely God Almighty, just and civilized
humanity, Indonesian unity, democracy led by wisdom in
deliberation / representation, and Social justice for all the people of
Indonesia. For the education sector, this is very important because
there will be certainty of values that will guide the
implementation of education.
Kata Kunci ABSTRAK
Pancasila; Landasan filsafat dalam dunia pendidikan sangat
Landasan penting keberadaannya. Landasan filsafat pendidikan akan
Filosofis; mengarahkan manusia atau pendidik untuk berfikir yang
Pendidikan dalam atau mengakar mengenai hakikat dari pendidikan.
Nasional Selain itu eksistensi suatu bangsa terefleksi dari filsafat
pendidikan yang dianut. Demikian juga pendidikan yang
baik mencerminkan dari landasan filsafat pendidikan yang
kuat dan kokoh. Pendidikan dikatakan baik, ketika mampu
113 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
mencetak manusia yang berkualitas ideal. Hasil analisis
menguraikan bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila
sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa
Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala
bidang, khususnya bidang pendidikan. Pengamalan
Pancasila itu haruslah dalam arti keseluruhan dan keutuhan
kelima sila dalam Pancasila itu, sebagai yang dirumuskan
dalam pembukaan UUD 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, dan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi bidang
pendidikan, hal ini sangat penting karena akan terdapat
kepastian nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan
pendidikan.
I. PENDAHULUAN
Paradigma klasik tentang pendidikan, pada umumnya dikatakan sebagai
pranata yang dapat menjalankan tiga fungi sekaligus. Pertama, mempersiapkan
generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu pada masa
mendatang. Kedua, mentransfer pengetahuan, sesuai dengan peranan yang
diharapkan. Ketiga, mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan
dan kesatuan masyarakat sebagai prasyarat bagi kelangsungan hidup
masyarakat dan peradaban. Butir kedua dan ketiga tersebut memberikan
pengertian bahwa pendidikan bukan hanya transfer of knowledge tetapi juga
transfer of value. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi helper bagi umat
manusia.
Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memiliki
kedudukan sangat penting yang disediakan guna kepentingan manusia itu
sendiri. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah cara manusia dalam
melangsungkan hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan yang
berkualitas tentunya memerlukan landasan yang kuat dalam upaya
membangun konstruksi pendidikan secara utuh. Landasan filsafat pendidikan
adalah penting untuk dipahami selain landasan penting lainnya. Mengingat
bahwa filsafat pendidikan akan mengarahkan manusia atau pendidik untuk
berfikir yang dalam atau mengakar mengenai hakikat dari pendidikan. Selain
itu eksistensi suatu bangsa terefleksi dari filsafat pendidikan yang dianut.
Demikian juga pendidikan yang baik mencerminkan dari landasan filsafat
pendidikan yang kuat dan kokoh. Pendidikan dikatakan baik, ketika mampu
mencetak manusia yang berkualitas ideal. Kesadaran moral dan sikap mental
yang menjadi kriteria manusia ideal dalam sistem nilai suatu bangsa bersumber
pada filsafat pendidikan itu sendiri. Untuk menjamin supaya pendidikan itu
benar dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan filosofis dan landasan
ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan.
Bangsa Indonesia memiliki asas ideologi Pancasila sebagai landasan
falsafah bangsa. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa
114 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan
bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan
(Semadi, 2019). Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan landasan
fundamental bangsa dalam mengembangkan pendidikan agar dapat mencapai
tujuan pendidikan nasional. Pancasila juga sebagai ideologi bangsa dapat
dijadikan formuliasi dalam mengembangkan pendidikan yang tentunya
berbasis nilai-nilai yang ada dalam Pancasila atau kebhinekaan. Landasan
filsafat pendidikan yang berbasis Pancasila dapat pula dijadikan landasan
ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman dalam menjalankan proses
pendidikan agar menjadi lebih baik.
II. METODE
Metode yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah studi
kepustakaan. Studi kepustakaan, yaitu menelaah sumber-sumber bacaan, baik
itu buku, artikel jurnal, maupun referensi-referensi yang berkaitan dengan
Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Kajian penelitian
sejenis juga dilakukan agar mendapat simpulan yang valid dan akurat.
III. PEMBAHASAN
Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat karena filsafat
mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan
pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Rumusan tentang harkat dan
martabat manusia beserta masyarakatnya ikut menentukan tujuan dan cara-
cara penyelenggaraan pendidikan, dan dari sisi lain pendidikan merupakan
proses memanusiakan manusia. Filsafat pendidikan merupakan jawaban secara
kritis dan mendasar berbagai pertanyaan pokok sekitar pendidikan, seperti apa,
mengapa, kemana, dan bagaimana, dan sebagainya dari pendidikan itu.
Kejelasan berbagai hal itu sangat perlu untuk menjadi landasan berbagai
keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam pendidikan. Hal itu sangat
penting karena hasil pendidikan itu akan segera tampak, sehingga setiap
keputusan dan tindakan itu harus diyakinkan kebenaran dan ketepatanya
meskipun hasilnya belum dapat dipastikan.
3.1 Terminologi Landasan Filsafat Pendidikan
Sebelum mendeskripsikan filsafat pendidikan lebih jauh, terlebih dahulu
akan diuraikan terminologi dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan terdiri
dari dua frase kata, yaitu filsafat dan pendidikan. Filsafat membahas sesuatu
dari segala aspeknya yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat
adalah kebenaran ilmu yang sifatnya relatif. Karena kebenaran ilmu hanya
ditinjau dari segi yang biasa diamati hanya sebagian kecil saja. Diibaratkan
mengamati gunung es, hanya mampu melihat yang diatas permukaaan laut
saja. Sementara itu filsafat mencoba menyelami sampai kedasar gunung es itu
untuk meraba segala sesuatu yang ada melalui pikiran dan renungan yang
kritis. Mengacu pada hal itu sebagaimana menurut Sadulloh (2012: 16),
menguraikan bahwa filsafat dapat diartikan sebagai cinta yang sangat
mendalam terhadap kearifan atau kebijaksanaan. Lebih jauh dijelaskan bahwa
115 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
filsafat sering digunakan secara popular dalam kehidupan sehari-hari baik
secara sadar maupun tidak sadar. Hal itu didasarkan dari etimologi kata filsafat
yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan shopia. Philos artinya
cinta yang sangat mendalam, dan shopia artinya kearifan atau kebijaksanaan.
Menurut pandangan tokoh-tokoh filsuf dunia, sebagaimana menurut Plato (427
– 348 SM), filsafat dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berminat
mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan menurut Aristoteles (382 – 322 SM),
filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung
dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik dan estetika.
Demikian juga menurut Yamin (dalam Watra, 2007: 4), filsafat adalah
pemusatan pikiran, sehingga manusia menemui kepribadiannya.
Sedangkan pendidikan dapat dilihat dalam pengertian secara khusus dan
secara luas. Dalam arti khusus, menurut Langevelg (dalam Sadulloh, 2012: 54),
menguraikan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang
dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya.
Selanjutnya pendidikan dapat pula diartikan sebagai mendidik atau membantu
anak supaya kelak anak tersebut cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas
tanggung jawab sendiri. Demikian pula pendidikan dapat diartikan memberi
tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan
perkembangan, sampai tercapainya kedewasaan dalam arti jasmani dan rohani.
Jadi, pendidikan dalam artian khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang
dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa dalam mencapai
kedewasaannya.
Pendidikan dalam artian luas merupakan usaha manusia untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung sepanjang hayat. Hal
tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Henderson (dalam Sadulloh,
2012: 55), sebagai berikut :
Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan,
sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan ingkungan
fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia terlahir. Warisan sosial
merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, dan alat bagi manusia
untuk pengembangan manusia yang terbaik dan intelegen, dan untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Dalam GBHN Tahun 1973 disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya
adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan
manusia, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan
berlangsung seumur hidup (Sadulloh, 2012: 56).
Berdasarkan pada terminologi tersebut di atas, maka filsafat pendidikan
dapat dikatakan sebagai usaha untuk mendalami segala aspek dalam dunia
pendidikan atau proses pendidikan. Demikian juga filsafat pendidikan adalah
usaha untuk mendalami konsep pendidikan. Senada dengan itu, Al-Syaibany
(dalam Sadulloh, 2012: 72), menguraikan bahwa filsafat pendidikan, seperti
halnya filsafat umum, berusaha mencari yang hakiki dan hakikat serta masalah
yang berkaitan dengan proses pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha untuk
mendalami konsep-konsep pendidikan dan memahami sebab-sebab yang
hakiki dari masalah pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha juga membahas
116 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
tentang segala yang mungkin mengarahkan proses pendidikan. Pada bagian
lain, Al-Syaibany (dalam Sadulloh,2012: 71), juga menguraikan bahwa filsafat
itu mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan
metitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-
kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan
masalah-masalah pendidikan secara paraktis. Jadi, filsafat pendidikan adalah
disiplin ilmu yang secara fundamental mendalami hakikat serta masalah yang
terkait dengan pendidikan.
Hal senada juga disampaikan oleh Muhmidayeli (2011: 34), bahwasannya
filsafat pendidikan secara langsung memberikan perhatiannya pada upaya-
upaya kritis, sistematis, radikal, dan universal berkenaan dengan persoalan
yang bersingungan dengan seluk beluk dunia pendidikan. Pada bagian lain
juga diuraikan, bahwasanya filsafat pendidikan bersandarkan pada filsafat
formal atau filsafat umum dalam artian bahwa masalah-masalah pendidikan
merupakan karakter dari filsafat. Masalah-masalah pendidikan akan memiliki
koherenitas dengan masalah-masalah filsafat umum, seperti: (a) Hakikat
kehidupan yang labih baik, karena pendidikan akan berusaha mencapainya; (b)
Hakikat dari manusia, karena manusia sebagai makhluk yang menerima
pendidikan; (c) Hakikat masyarakat, karena pendidikan pada dasarnya
merupakan suatu proses sosial; dan (d) Hakikat realitas akhir, karena semua
pengetahuan akan berusaha mencapainya (Muhmidayeli,2011: 33).
3.2 Rumusan Filsafat Pendidikan Nasional
Merumuskan filsafat pendidikan sangat perlu dilakukan, agar tujuan
pendidikan memiliki arah yang jelas. Disamping itu, merumuskan filsafat
pendidikan adalah sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
menentukan secara jelas tujuan dari pendidikan yang hendak dituju. Nilai
tersebutlah diwujudkan atau ditumbuhkembangkan dalam pribadi peserta
didik. Proses pendidikan tidak akan mungkin berlangsung tanpa adanya arah
dan tujuan yang hendak dicapai sebagai garis kebijakan. Tujuan pendidikan
dalam isinya atau rumusannya tidak mungkin dapat ditetapkan tanpa
mengetahui nilai-nilai tersebut secara tepat. Nilai-nilai yang dimaksud dalam
hal ini tentunya nilai kebhinekaan dan keragaman yang disatukan dibawah
ideologi Pancasila.
Didasarkan pada genealogis historis keberadaan bangsa Indonesia tidak
akan dapat dipisahkan dari pengalaman sejarahnya yang panjang. Mulai dari
jaman kerajaan sampai zaman klonial, maka hal itu sangat berpengaruh
terhadap rumusan filosofi atau filsafat pendidikan di Indonesia. Mengacu
uraian Sukardjo dan Komarudin (2012: 12), menyebutkan bahwa berdasarkan
pada pengalaman sejarah yang dialami bangsa Indonesia memberikan
pengaruh terhadap filsafat pendidikan di Indonesia yang terdiri dari beribu-
ribu pulau, suku, budaya, etnis dan sejenisnya. Berdasarkan pada hal itu, sudah
barang tentu para pendiri republik ini telah menentukan filsafat pendidikan
nasional yang bertitik tolak dari akar budaya nasional Indonesia. oleh karena
itu, rumusan filsafat pendidikan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari akar
budaya yang berbhineka atau multikultur.
117 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
Disamping rumusan filsafat pendidikan yang bertolak ukur terhadap akar
budaya yang multikulturalisme, filsafat pendidikan nasional memperhatikan
pula kehidupan bangsa-bangsa lain. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Sukardjo
dan Komarudin (2012: 12), bahwa filsafat pendidikan selain menempatkan akar
budaya sebagai tolak ukur, filsafat pendidikan nasional memperhatikan pula
bangsa-bangsa lain, sehingga pendidikan di Indonesia dapat dimengerti,
dipahami, dan memiliki kualitas yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Dengan kata lain, outcome dari pendidikan diharapkan dapat diterima dan
dikembangkan untuk menjadi bagian pendidikan dunia. Dengan demikian,
nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan falsafah
pendidikan nasional, dapat berinteraksi dengan nilai moral yang berlaku
universal.
Rumusan filsafat pendidikan nasional bersifat perenialisme yang berpusat
pada pelestarian dan pengembangan budaya dan sifat pendidikan yang
progresif yang berpusat pada pengembangan subjek didik perlu
disempurnakan. Filsafat pendidikan perenialisme yang progresif melihat subjek
didik sebagai bagian dari warga dunia, dan mengingatkan warga negara tidak
didikte oleh perubahan dan tetap mempertahankan akar budaya nasional.
Berdasarkan pada hal tersebut, rumusan filsafat pendidikan nasional bersifat
perenialisme yang progresif, yang mana pelestarian dan pengembagan budaya
dapat ditumbuhkan dalam subjek didik, disamping juga mengarahkan subjek
didik untuk melihat perkembangan bangsa lain. Hal itu dapat diskemakan
sebagai berikut :
Filosofi Pendidikan Nasional
Filosofi Filosofi Pendidikan
Pendidikan Asing
Lokal
Gambar 1. Rumusan Filosofi Pendidikan Nasional
Sumber: Sukardjo dan Komarudin (2012 : 13)
3.3 Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional
Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara ialah
Pancasila sebagai falsafah Negara, Pancasila patut menjadi jiwa bangsa
Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 UU-
RI No. 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan Nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu
tercantum dalam penjelasan UU-RI No. 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa
pembangunan nasional termasuk dibidang pendidikan adalah pengamalan
118 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain:
“Pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi
kualitasnya dan mampu mandiri”. Sedangkan ketetapan MPR-RI
No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila
menegaskan pula bahwa pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia,
kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar
Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala gagasan
mengenai wujud bangsa manusia dan masyarakat yang dianggap baik, sumber
dari segala sumber nilai yang menjadi pangkal serta muara dari setiap
keputusan dan tindakan dalam pendidikan dengan kata lain : Pancasila sebagai
sumber sistem nilai dalam pendidikan.
Setiap butir Pancasila memiliki tujuan yang sesuai sebagai dasar
pelaksanaan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas secara kognitif
maupun moralnya, uraiannya sebagi berikut:
1. Ketuhanan yang Maha Esa, dalam sila yang pertama pendidikan memilih
pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu
menngutamakan hal-hal yang dapat memperkuat nilai-nilai keimanan
bagi peserta didik agar selalu takwa dan beriman sesuai dengan
kepercayaannya masing-masing, selain itu agar peserta didik mampu
memaknai suatu pendidikan dengan didasarkan pada kewajiban mereka
sebagai makhluk Tuhan untuk selalu menuntut ilmu dan dengan adanya
pendidikan yang didasarkan pada sila ini maka output yang akan
dihasilkan yaitu terciptanya insan atau peserta didik yang berakhlak
mulia.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sila kedua pendidikan
menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus
mampu membentuk setiap peserta didik yang mampu untuk memberikan
perlakuan sebagaimana layaknya manusia dan nantinya seseorang yang
telah mendapatkan pendidikan itu dapat menghargai hak manusia yang
sesuai dengan makna dari sila ini, ketika seseorang dapat memahami hak
dan kewajiban diri sendiri dan orang lain maka orang tersebut mampu
memberikan perlakuan yang sesuai sehingga menjadikan setiap manusia
menjadi beradab dan dapat memperlakukan setiap manusia sama tanpa
pandang bulu.
3. Persatuan Indonesia, dalam sila ketiga pendidikan menjadikan pancasila
sebagai dasar pendidikan karena pendidikan harus mampu untuk
menjadikan peserta didiknya dapat bersatu dengan peserta didik lainnya,
hal Ini menunjukkan bahwa ketika terjadinya proses pendidikan maka
ada saat mereka harus belajar dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan
sosial yang ada maka ia akan belajar sendiri menengenai pengetahuan
maupun nilai-nilai yang ada dalam suatu masyarakat dan hal ini
memungkinkan setiap orang untuk bersatu dan meminimalisir adanya
diskrimantif antar perbedaan yang menjadi corak dari bangsa Indonesia,
sehingga terbuktilah dengan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika yang
dapat dimaknai bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman sehingga
di dalam proses pendidikan harus ada proses saling bertukar
119 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
pengetahuan dan sebagainya yang menungkinkan setiap orang dapat
menjalin kebersatuan untuk memenuhi suatu kebutuhan pendidikan.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan, dalam sila keempat pendidikan
menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena mengharuskan
suatu pendidikan dapat menjadikan setiap orang menjadi lebih
demokratis, aktif, dan kritis di dalam memberikan solusi pada setiap
masalah yang sedang terjadi di Indonesia, tetapi dalam pandangan yang
lain dapat dikatakan bahwa di dalam proses pendidikan mengharapkan
memunculkan output cendekiawan yang mampu mengkritisi segala
permasalahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI hal ini dapat
dilakukan dengan usaha dari dalam maupun dari luar, maka biasannya
pendidikan di 3 pusat lingkungan tersebut telah memberikan berbagai
usaha agar seseorang dapat lebih kritis lagi seperti dimasyarakat bahwa
terdapat organisasi yang memungkinkan partisipasi oleh setiap orang
untuk mengatasi hal-hal yang bersangkutan dengan program atau kinerja
dari setiap organisasi tersebut, adanya penyuluhan mengenai pemilu dan
sebagainya.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam sila ke lima
pendidikan menjadikan pancasila sebagai dasar pendidikan karena
mengungkapkan secara abstrak bahwa suatu pendidikan harus mampu
menciptakan bibit yang mampu memberikan keadilan sosial bagi
lingkungan yang ditempatinya dalam arti bahwa ketika seseorang sedang
berbaur dengan temannya maka orang itu tidak boleh membedakan yang
satu dengan yang lainnya.sehingga biasanya hal yang dapat dilakukan
yaitu dengan menanamkan sejak kecil bahwa seseorang tidak bisa hidup
sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga jika memilih
teman harus adil dan tidak boleh memandang pangkat maupun
derajatnya (Wasmana, 2018 : 28-29).
Mengacu pada Sadulloh (2012 : 193-196), menyebutkan bahwa kajian
filsafat terhadap Pancasila berangkat dari pemahaman tentang lapangan filsafat
yang mencakup metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika berkenaan
dengan sila pertama, yakni Ketuahan Yang Maha Esa merupakan asas dan
sumber dari segala eksistensi kehidupan dan kesemestaan. Ketuhanan bersifat
supranatral dan trancedental, yang dihayati oleh manusia dengan hati nurani.
Demikian juga Tuhan sebagai prema causa sumber dari segala sumber segalanya
ini. Selanjutnya sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang mana bangsa
Indonesia memiliki ciri yang khas, yakni adil dan beradab. Adil dan beradab
ditunjukkan dalam perilaku yang tidak hanya mementingkan kepentingan
jasmani saja, akan tetapi juga mengutamakan kepentingan rohani. Berikutnya
adalah sila Persatuan Indonesia, pada hakikatnya bangsa Indonesia terdiri dari
beragam suku, adat, tradisi, budaya, agama, kepercayaan dan yang lainnya,
akan tetapi semuanya itu adalah satu kesatuan. Sila keempat, yaitu Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
/perwakilan menunjukkan kebersamaan dalam memecahkan persoalan atas
dasar musyawarah dan mufakat. Sila terakhir adalah Keadilan Sosial Bagi
120 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
Seluruh Rakyat Indonesia, esensinya adalah adil, dalam artian
menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
Kajian epistemologi secara keseluruhan menyebutkan bahwa manusia
secara kodrati memiliki potensi untuk pengetahuan, mengolahnya dan
mengembangkannya. Demikian juga manusia berusaha mencari pengetahuan
dan kebenaran, yang dapat diperolehnya melalui berbagai sumber. Kajian
aksiologi didasarkan pada nilai etika dan estetika. Dari segi etika, Pancasila
merupakan seperangkat nilai sebagai landasan dalam berkehidupan. Dari
sudut moral, Pancasila merupakan seperangkat nilai yang dapat dijadikan
pedoman dalam berperilaku, dan merupakan norma-norma kehidupan yang
harus dilaksanakan. Dengan Ketuhanan Yang Maha Esa didalamnya
terkandung makna akan nilai-nilai ketuhanan yang diberikan tempat yang
agung. Sila ini sekaligus mendidik masyarakat agar tunduk kepada Tuhan
dengan agama yang dianutnya masing-masing. Selanjutnya dengan sila
Kemanusiaan merupakan hakikat manusia yang dapat dipandang dari segi
moral. Perbuatan yang baik bagi kepentingan kemanusiaan dinamakan
perbuatan berperikemanusiaan. Sila ketiga Persatuan Indonesia, yang mana
persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang kuat untuk memepertahankan
kemerdekaan dan persatuan ini sangat erat dengan ajaran moralitas. Sila
keempat Kerakyatan, dimana nilai kehidupan hendaknya didasari oleh
kepentingan rakyat dan hidup berdemokrasi. Sila terakhir Keadilan Sosial,
yang mana keadilan itu sendiri adalah tuntutan dari hati nurani rakyat.
Sejauh ini belum ada upaya mengoperasionalkan Pancasila agar mudah
diterapkan dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, termasuk penerapanya
dalam dunia pendidikan. Kalaupun ada bidang studi menyangkut moral
Pancasila, sebagian besar diterapkan seperti melaksanakan bidang-bidang studi
lain. Pendidik mengajarkannya kemudian peserta didik berusaha menjawab
pertanyaan-pertanyaan pendidik dalam ujian-ujian. Sementara itu dunia
pendidikan di Indonesia nampaknya belum punya konsep atau teori-teori
sendiri yang cocok dengan kondisi, kebiasaan atau budaya Indonesia tentang
pengertian dan cara-cara mencapai tujuan pendidikan. Sebagian dari konsep
atau teori pendidikan diimpor dari luar negeri sehingga belum tentu valid
untuk diterapkan di Indonesia.
Teori-teori biasa didapat dengan cara belajar diluar negeri, atau dengan
cara melakukan studi banding, dan yang paling banyak dilakukan adalah
dengan mendatangkan buku atau membeli buku dari negara lain. Inilah
sumber konsep pendidikan di Indonesia. Kalaupun ada usaha menyusun
sendiri konsep pendidikan sebagian besar juga bersumber dari buku-buku ini.
Begitu pula tentang konsep-konsep pendidikan yang ditatarkan dalam
penataran-penataran pendidikan juga bersumber dari buku-buku. Dengan
demikian dapat diibaratkan membuat manusia Indonesia yang dicita-citakan
seperti menerpa patung dengan cetakan luar negeri. Hasilnya tentu tidak sama
persis seperti manusia yang dicita-citakan, karena cetakan itu sendiri belum ada
di Indonesia. Pendidikan di Indonesia baru dalam tahap perhatian. Perhatian-
perhatian terhadap perlunya filsafat pendidikan itupun baru muncul disana-
sini belum terkoordinasi menjadi suatu perhatian besar untuk segera
121 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
mewujudkanya. Kondisi seperti ini tidak terlepas dari kesimpangsiuran
pandangan para pendidik terhadap pendidikan itu sendiri.
IV. PENUTUP
Filsafat pendidikan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mendalami
segala aspek dalam dunia pendidikan atau proses pendidikan. Demikian juga
filsafat pendidikan adalah usaha untuk mendalami konsep pendidikan, dan
berusaha mencari yang hakiki dan hakikat serta masalah yang berkaitan
dengan proses pendidikan. Guru sangat perlu memahami dan tidak boleh buta
terhadap filsafat pendidikan sebagai tujuan dari pendidikan akan bersentuhan
langsung dengan tujuan dari kehidupan itu sendiri. Rumusan filsafat
pendidikan nasional bersifat perenialisme yang berpusat pada pelestarian dan
pengembangan budaya dan sifat pendidikan yang progresif yang berpusat
pada pengembagan subjek didik perlu disempurnakan. Filsafat pendidikan
perenialisme yang progresif melihat subjek didik sebagai bagian dari warga
dunia, dan mengingatkan warga negara agar tidak didikte oleh perubahan dan
tetap mempertahankan akar budaya nasional
Kajian filsafat terhadap Pancasila berangkat dari pemahaman tentang
lapangan filsafat yang mencakup metafisika, epistemologi, dan aksiologi.
Metafisika berkenaan dengan sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa
merupakan asas dan sumber dari segala eksistensi kehidupan, sila
Kemanusiaan, yang mana bangsa Indonesia memiliki ciri yang khas, yakni adil
dan beradab. Adil dan berdab ditunjukkan dalam perilaku yang tidak hanya
mementingkan kepentingan jasmani saja, akan tetapi juga mengutamakan
kepentingan rohani. Berikutnya adalah sila Persatuan Indonesia, pada
hakikatnya bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, adat, tradisi, budaya,
agama, kepercayaan dan yang lainnya, akan tetapi semuanya itu adalah satu
kesatuan. Sila keempat, yaitu Kerakyatan menunjukkan kebersamaan dalam
memecahkan persoalan atas dasar musyawarah dan mufakat. Sila terakhir
adalah Keadilan Sosial, esensinya adalah adil, dalam artian menyeimbangkan
antara hak dan kewajiban.
DAFTAR PUSTAKA
Fadli. 2013. Landasan Filsafat Dalam Pendidikan. Jogjakarta : Pustaka Pelajar.
Muhmidayeli. 2011. Filsafat Pendidikan. Bandung : Refika Aditama.
Noor Syam, Moh, 1986. Filsafat Pendidikan dan dasar filsafat Kependidikan
Pancasila. Surabaya : Usaha Nasional.
Rika, Wulandari. 2012. Landasan Filsafat Pendidikan Di Indonesia. Jakarta :
Rajawali Prees.
Semadi, Yoga Putra. 2019. Artikel “Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di
Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2
No. 2 Tahun 2019.
Sadulloh, Uyoh. 2012. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
122 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
Sudarsono. 2001. Ilmu Filsafat, Suatu Pengantar. Jakarta: Rineka Cipta.
Sukardjo, Muhamad dan Komarudin, Ukim. 2012. Landasan Pendidikan Konsep
dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali Prees.
Watra I Wayan. 2007. Pengantar Filsafat. Surabaya : Paramita.
Wasmana. 2018. Modul Pengantar Filsafat Pendidikan. Cimahi: IKIP Siliwangi.
http://gusfumi.wordpress.com/2010/10/20/pancasila-sebagai-landasan-filosofis-sistem-
pendidikan-nasional/ diakses tanggal 20 Desember 2020
http://forumsejawat.wordpress.com/2010/10/28/filsafat-pancasila-landasan-filsafat-
pendidikan-indonesia/, diakses tanggal 20 Desember 2020
http://fadlibae.wordpress.com/2010/03/24/landasan-filsafat-dalam-pendidikan/, diakses
tanggal 20 Desember 2020
123 | SANJIWANI: Jurnal Filsafat Vol. 12 No. 1, Maret 2021
Anda mungkin juga menyukai
- Pembentukan Karakter Dalam PerananDokumen8 halamanPembentukan Karakter Dalam PerananMaharany Octary SetyowatyBelum ada peringkat
- Nota 3 - PentadbiranDokumen6 halamanNota 3 - PentadbiranRusyda AbdullahBelum ada peringkat
- Filsafat Pancasila DindaDokumen13 halamanFilsafat Pancasila Dindaslanker88Belum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Di IndonesiaDokumen13 halamanFilsafat Pendidikan Di IndonesiaRika IndahBelum ada peringkat
- Pentinganya Pancasila Dalam PendidikanDokumen3 halamanPentinganya Pancasila Dalam PendidikanOPPAIBelum ada peringkat
- Artikel - Anggun Destiana Safiti 2163053006 - Peran Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Pendidikan Diera MilenialDokumen7 halamanArtikel - Anggun Destiana Safiti 2163053006 - Peran Filsafat Pancasila Dalam Perkembangan Pendidikan Diera MilenialAnggun Destiana SafitriBelum ada peringkat
- Filsafat PancasilaDokumen26 halamanFilsafat PancasilaIsmail ThalibBelum ada peringkat
- Journal Randi DKKDokumen14 halamanJournal Randi DKKPramudita AzisBelum ada peringkat
- Filsafat Pancasila Dan Pendidikan PDFDokumen13 halamanFilsafat Pancasila Dan Pendidikan PDFHadi rizalBelum ada peringkat
- Sintya Nurfitria Putri - Kelompok 1 - PSM 22 - Pendidikan PancasilaDokumen6 halamanSintya Nurfitria Putri - Kelompok 1 - PSM 22 - Pendidikan PancasilaSINTYA NPP SENI MUSIKFBSBelum ada peringkat
- KTI Filsafat PendidikanDokumen12 halamanKTI Filsafat PendidikanTri Wahyuni PurwaningsihBelum ada peringkat
- Dampak Pembelajaran Filsafat Bagi Pendidikan Dan Pembelajaran Di IndonesiaDokumen16 halamanDampak Pembelajaran Filsafat Bagi Pendidikan Dan Pembelajaran Di Indonesiat3r33 nBelum ada peringkat
- Pertemuan 2 3Dokumen10 halamanPertemuan 2 3Dion pratama ManihurukBelum ada peringkat
- FilsafatDokumen4 halamanFilsafatKhalishatun ZahraBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen6 halamanBab IiIwan Martua SimbolonBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila SipDokumen9 halamanFilsafat Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila SipWidya Nur EvianyBelum ada peringkat
- Filsafat Pancasila FixDokumen26 halamanFilsafat Pancasila Fixsung sungBelum ada peringkat
- 4889-Article Text-13050-1-10-20240103Dokumen13 halaman4889-Article Text-13050-1-10-20240103Faridah AiniBelum ada peringkat
- Filsafat PancasilaDokumen18 halamanFilsafat PancasilaLisa arianiBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen11 halamanFilsafat Pendidikan PancasilaNurhamdin PutraBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat Kel2Dokumen18 halamanMakalah Filsafat Kel2Reyhan kusumaBelum ada peringkat
- Resume Ddip Landasan PendidikanDokumen9 halamanResume Ddip Landasan PendidikanFadhilla HidayatiBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat PendidikanDokumen16 halamanMakalah Filsafat PendidikanPrasetyo LaksonoBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Sebagai Sistem, Subtansi Dan HubuganDokumen14 halamanFilsafat Pendidikan Sebagai Sistem, Subtansi Dan HubuganHarry NugrahaBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat PendidikanDokumen8 halamanMakalah Filsafat PendidikantiwiBelum ada peringkat
- Melisa Bella Kurnia (206190033) Uas Filsafat PendidikanDokumen5 halamanMelisa Bella Kurnia (206190033) Uas Filsafat PendidikanBella KurniaBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen16 halamanFilsafat Pendidikan PancasilaT. HABIBUDDINBelum ada peringkat
- Landasan Filosofis Pendidikan Fix.Dokumen17 halamanLandasan Filosofis Pendidikan Fix.kesyaBelum ada peringkat
- FILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA Dalam TINJAUAN ONTOLOGIDokumen6 halamanFILSAFAT PENDIDIKAN PANCASILA Dalam TINJAUAN ONTOLOGIAjenk HawaBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen9 halamanFilsafat Pendidikan PancasilaLia F. AmeliaBelum ada peringkat
- Essay Kel.9Dokumen4 halamanEssay Kel.9Fahrun FthBelum ada peringkat
- Intan Purnama Sari (201220083)Dokumen27 halamanIntan Purnama Sari (201220083)Tiara 934Belum ada peringkat
- 9 - Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Pendidikan Dan IdeologiDokumen12 halaman9 - Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Pendidikan Dan IdeologiYeni AdtnBelum ada peringkat
- Tugas Rutin Filsafat PendidikanDokumen2 halamanTugas Rutin Filsafat PendidikanNelsy SigalinggingBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanDokumen3 halamanFilsafat Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanSugianorBelum ada peringkat
- Tugas LandasanDokumen26 halamanTugas Landasangustania ritaBelum ada peringkat
- Modul 11 MIFTHA HULJANNAH 2202060010Dokumen6 halamanModul 11 MIFTHA HULJANNAH 2202060010dew4m4sterBelum ada peringkat
- PancasilaSebagaiSistemFilsafat K011211265Dokumen5 halamanPancasilaSebagaiSistemFilsafat K011211265WulanPutri AnantaBelum ada peringkat
- Makalah Kel. 4 (Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Indonesia)Dokumen9 halamanMakalah Kel. 4 (Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Indonesia)Wardina ZahraBelum ada peringkat
- Makalah Pendidikan Pancasila Klompok 7Dokumen10 halamanMakalah Pendidikan Pancasila Klompok 7suttrisugaBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen8 halamanFilsafat Pendidikan PancasilafebriyantoBelum ada peringkat
- Akbar Jati Laksono - 2115013006 - Artikel PancasilaDokumen3 halamanAkbar Jati Laksono - 2115013006 - Artikel Pancasila06Akbar Jati LaksonoBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat Kel 11Dokumen12 halamanMakalah Filsafat Kel 11Ajah NurikaBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen16 halamanFilsafat Pendidikan PancasilaT. HABIBUDDINBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Pancasila (Eka Bila)Dokumen16 halamanFilsafat Pendidikan Pancasila (Eka Bila)Eka Arif FirmansyahBelum ada peringkat
- Landasan & Asas-Asas PendidikanDokumen26 halamanLandasan & Asas-Asas PendidikanCici HernawatiBelum ada peringkat
- Makalah Pendidikan PancasilaDokumen9 halamanMakalah Pendidikan PancasilaNirma LasariBelum ada peringkat
- Filsafat PancasilaDokumen31 halamanFilsafat PancasilaArif Sofarul AnwarBelum ada peringkat
- Resume 14 Filsafat Pendidikan Ratih SabrinaDokumen10 halamanResume 14 Filsafat Pendidikan Ratih Sabrinaratih sabrinaBelum ada peringkat
- Critical JournalDokumen44 halamanCritical JournalMulia DalimunteBelum ada peringkat
- Peran Filsafat Pancasila Terhadap Pendidikan Di Indonesia KelompokDokumen6 halamanPeran Filsafat Pancasila Terhadap Pendidikan Di Indonesia KelompokFredion WisudanaBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Di IndonesiaDokumen15 halamanFilsafat Pendidikan Di IndonesiakranalanpagaBelum ada peringkat
- Tugas ResumeDokumen19 halamanTugas Resumeenggar distaBelum ada peringkat
- Kelompok 4 Asumsi Asumsi Filosofis Pendidikan (II)Dokumen5 halamanKelompok 4 Asumsi Asumsi Filosofis Pendidikan (II)FazarBelum ada peringkat
- Tugas Rutin 10Dokumen4 halamanTugas Rutin 10graceputrisigalingging01Belum ada peringkat
- Filsafat PendidikanDokumen12 halamanFilsafat PendidikanSiti NurhanaBelum ada peringkat
- Laporan Critical Journal Review Lidia Lavenia Filsafat PendidikanDokumen9 halamanLaporan Critical Journal Review Lidia Lavenia Filsafat Pendidikanlidia laveniaBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen16 halamanFilsafat Pendidikan PancasilaT. HABIBUDDINBelum ada peringkat
- Adoc - Pub - Filsafat Pendidikan PancasilaDokumen8 halamanAdoc - Pub - Filsafat Pendidikan PancasilaNur asditaBelum ada peringkat
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- 2021 Panduan Pelaksanaan PBD Secara Dalam TalianDokumen12 halaman2021 Panduan Pelaksanaan PBD Secara Dalam TaliansirBelum ada peringkat
- 2021 Panduan Pelaksanaan PBD Secara Dalam TalianDokumen12 halaman2021 Panduan Pelaksanaan PBD Secara Dalam TaliansirBelum ada peringkat
- 115 Templat Pelaporan PBD Pislam Tahun 1Dokumen7 halaman115 Templat Pelaporan PBD Pislam Tahun 1sirBelum ada peringkat
- Panduan Ringkas Pengisian Data Modul Pengurusan Guru (E-Operasi)Dokumen8 halamanPanduan Ringkas Pengisian Data Modul Pengurusan Guru (E-Operasi)sirBelum ada peringkat
- Fariza Nurbaya Binti MuhammadDokumen1 halamanFariza Nurbaya Binti MuhammadsirBelum ada peringkat
- 5 Model Pedagogi AsasDokumen5 halaman5 Model Pedagogi AsassirBelum ada peringkat
- Rancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 6 SJK Edisi KSSR 2021Dokumen22 halamanRancangan Pengajaran Tahunan Bahasa Melayu Tahun 6 SJK Edisi KSSR 2021sirBelum ada peringkat
- Penanda WacanaDokumen10 halamanPenanda WacanasirBelum ada peringkat
- 3.pergerakan LokomotorDokumen4 halaman3.pergerakan LokomotorNorziah IsmailBelum ada peringkat