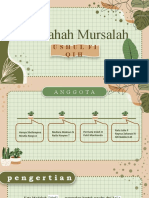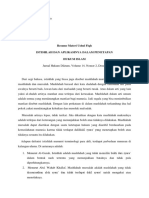Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Hukum
Diunggah oleh
Nurlaila0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan2 halamanAda tiga syarat utama yang harus dipenuhi ketika berhujjah dengan maslahah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu kemashalatan harus nyata dan umum, bukan pribadi, serta tidak bertentangan dengan nash atau ijma. Beberapa ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena syariat telah melindungi kemashalatan umat manusia, dan menggunakannya dapat memb
Deskripsi Asli:
Judul Asli
Syarat2 Dan Keraguan
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniAda tiga syarat utama yang harus dipenuhi ketika berhujjah dengan maslahah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu kemashalatan harus nyata dan umum, bukan pribadi, serta tidak bertentangan dengan nash atau ijma. Beberapa ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena syariat telah melindungi kemashalatan umat manusia, dan menggunakannya dapat memb
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
7 tayangan2 halamanMaslahah Mursalah Sebagai Dasar Hukum
Diunggah oleh
NurlailaAda tiga syarat utama yang harus dipenuhi ketika berhujjah dengan maslahah mursalah sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu kemashalatan harus nyata dan umum, bukan pribadi, serta tidak bertentangan dengan nash atau ijma. Beberapa ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena syariat telah melindungi kemashalatan umat manusia, dan menggunakannya dapat memb
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
C.
Syarat-syarat berhujjah dengang Mashalah Mursalah
Ulama yang berhujjah dengan mashlahah mursalah, mereka bersikap sangat berhati-
hati sehinga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan
keinginan tertentu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada mashalah
mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:
1) Harus merupakan kemashalatan yang hakiki, bukan yang bersifat dugaan. Maksudnya
untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat
mendatangkan kemanfaatan dan penolakan bahaya. Jika sekedar dugaan bahwa
pembentukan hukum dapat menarik manfaat, tanpa mempertimbangkannya dengan
bahaya yang datang, maka kemashalatan ini bersifat dugaan semata (mashlahah
wahmiyyah).
Contohnya pencabutan hak suami untuk mentalak istrinya dan menjadikan hak talak
tersebut sebagai hak hakim dalam segala sesuatu dan kondisi.
2) Kemashalatan itu bersifat umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan
bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi
mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk
kemashalatan individu atau beberapa orang.
Hukum tidak boleh disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan-kemashalatan
khusus bagi penguasa atau pembesar, dan memalingkan perhatian dan kemashalatan
mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemashalatan harus memberikan manfaat.
3) Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemashalatan, tidak nertentangan dengan
hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma, oleh karena itu, tideak benar
mengakui kemashalatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan
dalam bagian warisan. Sebab maslahat yang demikian itu batal, karena bertentangan
dengan nash Al-Qur’an.
Dalam hal ini, fatwa Yahya bin Yahya Al-Litsi Al-Maliki, ulama fiqih Andalusia dan
murid imam Maliki bin Anas, adalah salah, yaitu tentang seseorang raja Andalusia
berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan., kemudian imam
Yahya memberikan fatwa, bahwa tidak perlu membayar kafarat namum berpuasa dua
bulan berturut-turut. Dia mendasarkan fatwanya, bahwa kemashalatan menghendaki
demikian, karena maksud kafarat adalah mencegah orang yang berbuat dosa dan
menahannya sehingga tidak mengulangi dosa serupa, dan cara inilah yang biasA
menahan raja agar tidak mengulang perbuatannya lagi. Adapun kemerdekaan seorang
budak, maka hal ini sangat mudah bagi sang raja dan tidak ada unsur prevensi di
dalamnnya.
Fatwa diatas didasarkan pada kemaslahatan, tetapi kemaslahatan yang diambil
bertentangan dengan nash, karena di dalam nash telah jelas disebutkan bahwa kafarat
orang yang berbuka puasa dengan sengaja pada siang hari di bulan Ramadhan adalah
memerdekakan seorang budak. Jika tidak mendapatkannya, maka berpuasa dua bulan
berturut-turut, jika tidak sanggup, memberi makanan kepada 60 orang miskin., tanpa
membedakkan apakah raja atau fakir yang berbuka puasa, dengan demikian,
kemaslahatan olkeh mufti dalam menetapkan kafarat bagi raja dengan berpuasa dua
bulan berturut-turut secara khusus nerupakan kemaslahatan yang keliru.
Dari uraian tersebut jelaslah, bahwa kemaslahatan atau sifat yang munasib, harus
terdapat salah satu bukti syara’ yang mengakui atau membenarkan. Sifat munasib ini
adakalanya munasib muttasir dan adakalanya munasib mualim. Dan bila tidak ada
bukti syara yang menunjukan batalnya pengakuan tersebut, maka sifat itu adalah
munasih al-mulgha (yang dibatalkan)., dan apabila tidak ada bukti syara yang
menunjukan terhadap pengkuan syar’i yang membenarkan (mengakui) atau
membatalkannya, maka sifat tersebuat adalah munasib, mursal, dengan kata lain
disebut maslahah mursalah.
D. Keraguan Orang Yang Tidak Menggunakan Maslahah Mursalah
Sebagian ualama kaum muslimin berpendapat bahwa maslahah mursalah yang tidak
terdapat bukti syari’ mengenai pengakuan dan pembatalan terhadapnya, tidak bisa
dijadikan sebagai dasar pembentukan hukum. Alasan mereka ialah:
1) Bahwa syariat telah memelihara segala kemaslahatan manusia dengan nash-nash dan
petunjuk qiyas. Sebab syari’ tidak akan menyia-nyiakan umat manusia, maksudnya
tidak akan membiarkan kemaslahatan apapun tanpa suatu bukti dari syari’ yang
mengakuinya. Sedangkan jika tidak ada bukti dari syari, maka pada hakikatnya bukan
kemaslahatan. Namun merupakan maslahah wahmiyah (kemaslahatan yang bersifat
dugaan) dan tidak sah mendasar hukum atas kemaslahatan tersebut.
2) Bahwa pembentukan hukum atas dasar kemutlakan maslahat berarti membuka pintu
hawa nafsu bagi orang yang menurutinya, baik dari kalangan penguasa, amir, dan
para mufti. Sebagian dari mereka kadangkala kalah oleh hawa nafsu dan keinginannya
sebagai akibatnya mereka bisa menghalalkan mufsadah (kerusakan) untuk
kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan merupakan suatu hal yang bersifat pemikiran
yang berbeda berdasarkan pendapat dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu,
membentuk hukum berdasarkan mutlaknya kemaslahatan berarti membuka pintu
kejahatan.
Anda mungkin juga menyukai
- Masalih Al-Mursalah dan Peranannya dalam MasyarakatDokumen10 halamanMasalih Al-Mursalah dan Peranannya dalam Masyarakatnur syafiqahBelum ada peringkat
- Maslahah MursalahDokumen18 halamanMaslahah MursalahSiti NuraienaBelum ada peringkat
- Ushul Maslahah MursalahDokumen12 halamanUshul Maslahah MursalahMutiara MumutBelum ada peringkat
- Maslahah Mursalah Menurut Pandangan para MadzahibDokumen8 halamanMaslahah Mursalah Menurut Pandangan para MadzahibmusallasBelum ada peringkat
- Definisi MaslahahDokumen2 halamanDefinisi MaslahahBayu AhmadaBelum ada peringkat
- HUKUM ISLAMDokumen12 halamanHUKUM ISLAMkamtib lapas cibinongBelum ada peringkat
- Resume Maslahah MursalahDokumen4 halamanResume Maslahah MursalahNailu rohmanBelum ada peringkat
- Mashalih MursalahDokumen15 halamanMashalih MursalahadsolahBelum ada peringkat
- UFDokumen5 halamanUFFitria RasmiatiBelum ada peringkat
- Mashalih MursalahDokumen15 halamanMashalih MursalahNurul FatymahBelum ada peringkat
- Fiqih KontemporerDokumen16 halamanFiqih KontemporerRokhisamaliaBelum ada peringkat
- Uts, Fiqih Muamalah, Ilham Fikri, 1219088, Hes'cDokumen7 halamanUts, Fiqih Muamalah, Ilham Fikri, 1219088, Hes'cNurul HudaBelum ada peringkat
- Maqasid SyariahDokumen5 halamanMaqasid SyariahM Ridwan YahyaBelum ada peringkat
- Maslahah MursalahDokumen8 halamanMaslahah MursalahRagil BasuniBelum ada peringkat
- Tugas Maslahah MursalahDokumen4 halamanTugas Maslahah MursalahDina NaBelum ada peringkat
- Akad Wakalah Dalam FiqhDokumen14 halamanAkad Wakalah Dalam Fiqhqdw_shBelum ada peringkat
- Bab4Dokumen16 halamanBab4Oktarisanti Syahda PutriBelum ada peringkat
- Metode IjtihadDokumen2 halamanMetode IjtihadDicky HerlambangBelum ada peringkat
- Hukum Wadh'i dan Penerapannya dalam IslamDokumen5 halamanHukum Wadh'i dan Penerapannya dalam Islamidhaseunghyun100% (1)
- Syubhat Dan Hal-Hal Yang Mempengaruhinya (Kelompok 10)Dokumen4 halamanSyubhat Dan Hal-Hal Yang Mempengaruhinya (Kelompok 10)PerdinansyahBelum ada peringkat
- Qawaid Fiqiyah KelompokDokumen12 halamanQawaid Fiqiyah KelompokAbdul YahyaBelum ada peringkat
- Resume Ushul FiqhDokumen5 halamanResume Ushul FiqhIhda AyukBelum ada peringkat
- JUAL BELIDokumen15 halamanJUAL BELIZahira Ula azkiaBelum ada peringkat
- EKOMOMI SYARIAH - Zulfa Raodotul Jannah 23110015Dokumen7 halamanEKOMOMI SYARIAH - Zulfa Raodotul Jannah 23110015Ringga AnugrahBelum ada peringkat
- Maslahah Al MursalahDokumen13 halamanMaslahah Al MursalahDilaBelum ada peringkat
- Artikel PK PausDokumen4 halamanArtikel PK PausSuci RohmawatiBelum ada peringkat
- MASLAHAH MURSAALAH DALAM EKONOMI ISLAMDokumen18 halamanMASLAHAH MURSAALAH DALAM EKONOMI ISLAMIkha RikaBelum ada peringkat
- Usul Fikih MTDokumen63 halamanUsul Fikih MTAbdulloh Khoirul AzamBelum ada peringkat
- TUGAS Mashlahah MurasalahDokumen8 halamanTUGAS Mashlahah MurasalahAbi ArsyBelum ada peringkat
- Reseume MaslahatDokumen3 halamanReseume MaslahatHanafiah KahlilBelum ada peringkat
- Buletin PDM Jembarana No5Dokumen5 halamanBuletin PDM Jembarana No5Edi SusiloBelum ada peringkat
- Maslahah dan PerlaksanaannyaDokumen20 halamanMaslahah dan PerlaksanaannyaAfiqah GahamatBelum ada peringkat
- UFK7Dokumen27 halamanUFK7Gita DamanikBelum ada peringkat
- Muamalah Dalam IslamDokumen8 halamanMuamalah Dalam IslamAbi PhotographBelum ada peringkat
- Makalah Fiqih Kelas 12Dokumen9 halamanMakalah Fiqih Kelas 12Achmad FatoniBelum ada peringkat
- Al Maslahah Al MursalahDokumen6 halamanAl Maslahah Al MursalahNovery AdyBelum ada peringkat
- Kisi-Kisi UpDokumen9 halamanKisi-Kisi UpErna FatimahBelum ada peringkat
- Keagungan Peradilan IslamDokumen10 halamanKeagungan Peradilan IslamKua TenjolayaBelum ada peringkat
- MAKALAH Fiqih Muamalah Syirkah MudharabahDokumen15 halamanMAKALAH Fiqih Muamalah Syirkah MudharabahBybe AshwinBelum ada peringkat
- Penyelesaian Hukum Perempuan Hamil Di Luar Nikah Di Kota SamarindaDokumen6 halamanPenyelesaian Hukum Perempuan Hamil Di Luar Nikah Di Kota Samarindamuhamad yusufhidayatBelum ada peringkat
- Mahkum FihDokumen11 halamanMahkum FihAHMAD BIN CHE YAACOB FTI ABelum ada peringkat
- Prinsip Prinsip Dasar MuamalahDokumen3 halamanPrinsip Prinsip Dasar MuamalahReza FerdiansyahBelum ada peringkat
- Kaidah Fiqh Dalam MuamalahDokumen6 halamanKaidah Fiqh Dalam MuamalahNic Edin100% (1)
- Akad Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah 452e5de8Dokumen27 halamanAkad Mudharabah Musyarakah Dan Murabahah 452e5de8Heru KurniawanBelum ada peringkat
- Jarimah PemberontakanDokumen18 halamanJarimah PemberontakanJihan RamaditaBelum ada peringkat
- Sejarah Takaful Di Zaman RasulullahDokumen13 halamanSejarah Takaful Di Zaman RasulullahHidayah ZainalBelum ada peringkat
- MakalahDokumen15 halamanMakalahPutune Mbah017Belum ada peringkat
- 1432 3267 1 SMDokumen14 halaman1432 3267 1 SMroseidhamayanuraini15Belum ada peringkat
- MUAMALAHDokumen11 halamanMUAMALAHalvoy1Belum ada peringkat
- MENENTUKAN ILLATDokumen9 halamanMENENTUKAN ILLATalrahmabkoBelum ada peringkat
- Ijma Qiyas Urf MaslahahDokumen7 halamanIjma Qiyas Urf MaslahahSony MurayaBelum ada peringkat
- Isi Makalah MuamalahDokumen4 halamanIsi Makalah MuamalahmarinanananaBelum ada peringkat
- UTS Legal MaximDokumen3 halamanUTS Legal MaximJJ HidayatBelum ada peringkat
- MASLAH AL-MURSALAHDokumen15 halamanMASLAH AL-MURSALAHMohd AmirBelum ada peringkat
- METODE IJTIHAD DALAM FIQHDokumen71 halamanMETODE IJTIHAD DALAM FIQHAmal1a Putr1Belum ada peringkat
- Siyasah MaliyahDokumen17 halamanSiyasah MaliyahDheriez OlalaBelum ada peringkat
- FIQH (Soalan Tropikal 7)Dokumen3 halamanFIQH (Soalan Tropikal 7)officialmp3 popBelum ada peringkat
- Jawaban Uts Ushul Fiqih Sari Maharani Arfianti (0501203211) EkiDokumen5 halamanJawaban Uts Ushul Fiqih Sari Maharani Arfianti (0501203211) EkiSarimaharani Arifianti100% (1)
- Perang Melawan Okultisme, Sihir Dan Agama PalsuDari EverandPerang Melawan Okultisme, Sihir Dan Agama PalsuPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Maslahah Mursalah Sebagai Dasar HukumDokumen2 halamanMaslahah Mursalah Sebagai Dasar HukumNurlailaBelum ada peringkat
- Barisan Dan DeretDokumen18 halamanBarisan Dan DeretMattBelum ada peringkat
- Latihan MTKDokumen1 halamanLatihan MTKNurlailaBelum ada peringkat
- AKHLAK TASAWUFDokumen14 halamanAKHLAK TASAWUFNurlailaBelum ada peringkat
- Maslahah Mursalah Sebagai Dasar HukumDokumen2 halamanMaslahah Mursalah Sebagai Dasar HukumNurlailaBelum ada peringkat
- Gerak RotasiDokumen2 halamanGerak RotasiNurlailaBelum ada peringkat
- B. Dasar Hukum MudharabahDokumen2 halamanB. Dasar Hukum MudharabahNurlailaBelum ada peringkat
- Soal Gerak Rotasi 2020Dokumen2 halamanSoal Gerak Rotasi 2020NurlailaBelum ada peringkat