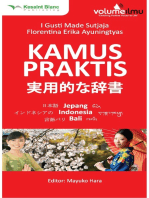Natasha Stacey - Bajo Settlement Historyen Terjemah Id
Natasha Stacey - Bajo Settlement Historyen Terjemah Id
Diunggah oleh
Helmi MujtabaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Natasha Stacey - Bajo Settlement Historyen Terjemah Id
Natasha Stacey - Bajo Settlement Historyen Terjemah Id
Diunggah oleh
Helmi MujtabaHak Cipta:
Format Tersedia
Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.
com
Judul Bab: Sejarah Permukiman Bajo
Judul Buku: Perahu untuk Dibakar
Subjudul Buku: Penangkapan Ikan Bajo di Zona Perikanan Australia
Penulis Buku: Natasha Stacey
Diterbitkan oleh: ANU Press
URL Stabil: https://www.jstor.org/stable/j.ctt24h9b6.7
JSTOR adalah layanan nirlaba yang membantu para sarjana, peneliti, dan mahasiswa menemukan, menggunakan, dan membangun
berbagai konten dalam arsip digital tepercaya. Kami menggunakan teknologi dan alat informasi untuk meningkatkan produktivitas dan
memfasilitasi bentuk beasiswa baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang JSTOR, silakan hubungi support@jstor.org.
Penggunaan Anda atas arsip JSTOR menunjukkan persetujuan Anda terhadap Syarat & Ketentuan Penggunaan, tersedia di
https://about.jstor.org/terms
Konten ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0). Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Pers ANUberkolaborasi dengan JSTOR untuk mendigitalkan, melestarikan, dan memperluas akses kePerahu untuk Dibakar
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Tersebar di seluruh daratan dan pulau Asia Tenggara tiga kelompok orang
umumnya disebut dalam literatur sebagai 'pengembara laut', 'orang laut' atau
'gipsi laut' (Sopher 1977). Ketiga kelompok etno-linguistik yang luas ini adalah
Moken, Orang Laut, dan Sama-Bajau. Setiap kelompok berbeda secara geografis,
bahasa dan budaya dan telah beradaptasi dengan lingkungan laut yang kaya dan
ekosistem pulau di Asia Tenggara (Sather 1997: 320–8).
Suku Bajo di Indonesia bagian timur adalah sub-kelompok dari kelompok terbesar,
Sama-Bajau. Selain menjadi penghuni perahu nomaden atau mantan pengembara
perahu, Sama-Bajau juga masyarakat pesisir dan darat:
Penutur Sama-Bajau terdiri dari kelompok etnolinguistik yang tersebar
paling luas yang berasal dari Asia Tenggara kepulauan. Pengembara
laut dan jauh lebih banyak penutur Sama yang terdampar dan
menetap hidup tersebar, dan di sebagian besar wilayah diselingi satu
sama lain, di atas zona maritim yang luas seluas 3,25 juta kilometer
persegi, membentang dari Palawan timur, Samar, dan pantai
Mindanao di utara, melalui Kepulauan Sulu Filipina, ke pantai utara dan
timur Kalimantan, ke selatan melalui Selat Makassar ke Sulawesi, dan
dari sana tersebar luas di wilayah timur Indonesia (Sather 1997: 2).
Diperkirakan ada antara 750.000 dan 900.000 penutur bahasa Sama-Bajau
di Asia Tenggara (ibid.) (lihat Peta 2-1). Meskipun survei komprehensif
belum pernah dilakukan di Indonesia, diperkirakan jumlah penutur Sama-
Bajau antara 150.000 dan 230.000 (ibid.: 3).
Bahasa Sama-Bajau merupakan subkelompok bahasa Austronesia yang
berlainan dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia Barat. Ada sepuluh bahasa
Sama-Bajau dan banyak dialek (Pallesen 1985). Bahasa Sama yang dituturkan
di Indonesia tampaknya terkait erat dengan bahasa Sama Selatan yang
dituturkan di sepanjang pantai Sabah, di pulau-pulau lepas pantainya, dan di
Kepulauan Sulu di Filipina selatan (Sather 1997: 9–10). Di Indonesia, hanya ada
'perbedaan kecil pada tingkat dialek' (Verheijen 1986: 26–7) dan bahasa
Indonesia Sama 'hanya satu bahasa' (Noorduyn 1991: 6).
Istilah Sama-Bajau, yang digunakan sebagai label gabungan untuk mencakup semua
bahasa yang digunakan oleh anggota kelompok ini, tidak hanya mencakup sebagian besar
eksonim yang biasa digunakan oleh orang luar, tetapi juga mencakup istilah penunjukan diri
yang digunakan oleh penutur Sama-Bajau itu sendiri (Pallesen 1985 : 43). Kebanyakan
penutur Sama-Bajau menyebut diri mereka sebagai Sama atau A'a Sama (Orang Sama)
(Sather 1997: 5). Di Filipina, Malaysia, dan Indonesia, sejumlah nama digunakan oleh orang
luar, termasuk Bajau (dan banyak kerabatnya) dan Bajau Laut (Laut Bajau). Selain ini,
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
nama Samal digunakan oleh penutur Tagalog di Filipina untuk merujuk pada penutur bahasa Sama-
Bajau yang berbasis di darat (ibid.).
Peta 2-1: Area tempat penutur Sama-Bajau ditemukan di Asia Tenggara.
Di Indonesia, sejumlah istilah telah digunakan secara teratur dalam periode
sejarah. Nama Bugis untuk orang-orang laut ini adalah Bajo, dan menurut Velthoen
(1997: 2), para pengamat kolonial Belanda cenderung mengikuti pemakaian lokal.
Jadi, istilah serumpun Bajo dan Bajau, dan variasi seperti Bajo atau Badjoo, muncul
dalam catatan sejarah Belanda awal dan kemudian Inggris dari akhir abad ke-17
dan awal abad ke-18 (lihat Fox 1977a; Sopher 1977: 143–56; 158–61; 296 –307; Reid
1983: 126). Nama Bajau kemudian ditetapkan sebagai nama generik bagi penutur
Sama-Bajau di kalangan pengamat Inggris (Sather 1997: 6–7).
Dalam bahasa Indonesia, Bajau adalah sebutan resmi sekaligus label etnik
umum bagi penutur Sama-Bajau (Acciaioli 1996: 25). Alhasil, nama ini digunakan
oleh orang Sama-Bajau baik di Indonesia maupun di Malaysia (Pallesen 1985: 43;
Acciaioli 1996: 25; Sather 1997: 5).
Dalam penelitian ini, nama Bajo lebih disukai daripada Bajau atau Sama karena beberapa alasan:
masih merupakan eksonim yang lebih umum digunakan untuk orang-orang berbahasa Sama di Indonesia
bagian timur, dan khususnya di Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur; itu adalah nama yang paling sering
digunakan oleh para sarjana yang menulis tentang Indonesia bagian timur;
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
dan hal ini akrab di kalangan pejabat pemerintah Australia dan dalam literatur mengenai
penangkapan ikan Indonesia di Zona Perikanan Australia. Nama Sama digunakan untuk
menyebut bahasa yang digunakan oleh suku Bajo di Indonesia bagian timur.
Asal dan Penyebaran Sama-Bajau
Karya paling komprehensif mengenai asal usul dan persebaran kelompok
bahasa Sama-Bajau adalahKontak Budaya dan Konvergensi Bahasa(Pallesen
1985). Berdasarkan bukti linguistik, Pallesen menyarankan titik asal di tempat
yang sekarang menjadi Filipina selatan. Sekitar awal abad ke-9, penutur dialek
Proto-Sama-Bajau tinggal di wilayah Selat Basilan antara wilayah Zamboanga
di Mindanao Selatan dan Pulau Basilan di bagian tenggara Laut Sulu (Pallesen
1985: 117). Sejumlah kelompok berpisah selama periode awal ini. Pada abad
kesebelas penyebaran lebih lanjut dimulai dengan kelompok besar bergerak
ke barat daya melalui Kepulauan Sulu dan kemudian sepanjang wilayah pesisir
timur laut Kalimantan (Kalimantan). Di sini masyarakat kembali terpecah
menjadi kelompok Kalimantan Utara dan Jama Mapun dengan 'gelombang
maju' Bajau Indonesia yang bergerak lebih jauh ke pesisir timur Kalimantan
melalui Tawau dan Tarakan (ibid.: 121). Pergerakan penutur Sama ke arah
selatan ke wilayah Sulu dan Kalimantan selatan 'dipercepat' oleh perluasan
perdagangan maritim setelah berdirinya Kesultanan Sulu pada abad ke-15
(Sather 1993a: 218). Dari pantai timur Kalimantan, atau mungkin langsung dari
Sulu selatan, penutur Sama menyebar ke selatan ke Selat Makassar, tiba di
sepanjang pantai Sulawesi dan menyebar ke bagian lain Indonesia timur
beberapa waktu sebelum awal abad keenam belas dan ketujuh belas ( Pallesen
1985: 121; Sather 1997: 15).
Mitos asal, cerita dan legenda yang ditemukan di antara suku Bajo di Sulawesi (dan
di antara Sama-Bajau lainnya di Sabah dan Sulu) menyebut Johor di Semenanjung
Malaysia sebagai tanah air asli tempat orang Bajo tersebar, membawa mereka ke
Sulawesi Selatan dan karenanya menjalin hubungan dengan kerajaan Luwu, Gowa dan
Bone (Pelras 1972: 157; Sopher 1977: 141; Zacot 1978: 26; Reid 1983: 125; Pallesen 1985:
5; Sather 1993b: 31, 1997: 17). Tukang Besi Bajo punya versi cerita yang mirip. Salah
satunya menyangkut seorang putri Bajo, atau gadis surgawi, dari Johor, yang setelah
dipisahkan dari keluarganya, terdampar di Sulawesi Selatan dan kemudian menikah
dengan Pangeran Makassar. Dia melahirkan empat putra yang memerintah wilayah
Gowa, Bone, Luwu dan Soppeng. Dengan menghubungkan asal-usul mereka dengan
pusat kekuasaan, Johor, 'yang paling bergengsi dari semua kerajaan Melayu', dan yang
mendahului Kesultanan Sulu yang kuat, ini memberikan legitimasi kepada kerajaan
Luwu, Gowa dan Bone. Mitos-mitos ini, menurut Sather, 'lebih berkaitan dengan
ideologi politik dan subordinasi masyarakat maritim dalam suksesi negara-negara
perdagangan berorientasi laut daripada dengan migrasi aktual atau asal usul
literal' (Sather 1997: 17–18).
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
Bukti paling awal tentang keberadaan suku Bajo di Sulawesi adalah
penyebutan suku Bajo Sereng (Bajo Maluku) dalam cerita epik besar dari
Sulawesi Selatan—siklus La Galigo (Pelras 1996: 74). Referensi ini rupanya
berkaitan dengan peran yang mungkin dimainkan Bajo dalam hubungan
antara kekuatan maritim Sulawesi Selatan dan Maluku (ibid.: 74). Menurut
Pelras (ibid.: 56), teks ini kemungkinan berasal dari abad ke-14, pada masa
kerajaan Luwu yang dominan.
Catatan sejarah Eropa mendokumentasikan keberadaan Bajo di Sulawesi Selatan dari
abad XVI dan XVII. Dalam catatan awal tahun 1511, orang Portugis, Tomé Pires,
mendokumentasikan kemungkinan kehadiran orang Bajo di kerajaan Gowa di sekitar kota
Makassar (Pires 1944 dalam Reid 1983: 127; Pelras 1996: 17). Laksamana Belanda Speelman,
'penakluk Makassar' (1666–67) mengatakan bahwa orang Bajo tinggal di pulau-pulau kecil di
lepas pantai Makassar dan di sana mereka mengumpulkan tempurung penyu yang mereka
berikan sebagai penghormatan kepada Raja Makassar dan 'harus selalu demikian. siap untuk
pergi dengan kapal mereka ke arah mana pun mereka dikirim' (Speelman 1670, dikutip dalam
Reid 1983: 126). Menjelang akhir 1670-an, suku Bajo dilaporkan berada di timur laut Sulawesi
di wilayah Manado (Valentijn 1724–26, dikutip dalam Sopher 1977: 300).
Sebagai pelaut yang terampil dan spesialis maritim, orang Bajo memainkan peran
penting dalam kebangkitan Negara Gowa menjadi kekuatan politik dan ekonomi di
Indonesia bagian timur selama abad ke-16 dan awal abad ke-17, dan kemudian dengan
kerajaan Bugis Bone yang kuat di timur. Makassar. Di negara-negara maritim yang
dominan ini, suku Bajo berguna sebagai penjelajah, pembawa pesan, pelaut, dan
pemanen hasil laut yang diperdagangkan ke pusat-pusat lain di Asia Timur dan
Tenggara (Reid 1983: 124–9; Collins 1995: 14).
Penyebaran pengembara perahu berbahasa Sama ke arah timur dan selatan dari
wilayah selatan Sulawesi selama tiga abad terakhir tampaknya terkait erat dengan
ekspansi dan migrasi politik dan komersial Bugis dan Makassar di wilayah tersebut, dan
dengan perkembangan negara kepulauan- jaringan perdagangan hasil laut yang luas —
khususnya teripang dan cangkang penyu — yang tersebar hingga pantai utara Australia
(Fox 1977a; Sopher 1977: 144; Sather 1993a: 218; Velthoen and Acciaioli 1993). Meskipun
tempat tinggal perahu menurun setelah abad ke-19, setelah digantikan oleh
keberadaan yang lebih berbasis pantai, perdagangan teripang dan cangkang penyu di
Indonesia bagian timur merupakan faktor penting dalam distribusi suku Bajo melalui
wilayah tersebut (Sopher 1977: 144).
Penutur sama sekarang tersebar dari Kalimantan Timur dan Sulawesi menyeberang ke
Maluku dan ke selatan di sepanjang Kepulauan Sunda Kecil. Mayoritas masyarakat penutur
bahasa Sama ditemukan di pemukiman yang tersebar di sepanjang pantai Sulawesi dan di
pulau-pulau lepas pantainya. Di Sulawesi Selatan, permukiman ditemukan di sekitar Ujung
Pandang (Makassar) dan di Kepulauan Spermonde, sepanjang pantai Teluk Bone dan lepas
pantai di Kepulauan Sembilan (Pelras 1972), seperti
10
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
serta di pulau-pulau kecil di Laut Flores seperti Selayar, Tanah Jampea, Bonerate dan Karompa. Di Sulawesi Tenggara, pemukiman terdapat di Pulau Kabaena, Muna,
Buton dan Tukang Besi, di pulau-pulau di Selat Tiworo, di sepanjang pantai Teluk Kendari, di Pulau Wowonii dan di utara di La Solo. Di Sulawesi Tengah, permukiman
suku Bajo terdapat di sepanjang pantai timur dan di Kepulauan Salabanka (Tomascik et al. 1997: 1221), serta di pulau kepulauan Banggai dan Togian. Di Sulawesi
Utara, masyarakat tersebar di sekitar Teluk Tomini dan di kabupaten Gorontalo dan Manado (Zacot 1978). Dilaporkan juga bahwa ada komunitas penutur Sama di
dekat Balikpapan di Kalimantan Timur dan di pulau-pulau lepas pantai timur Kalimantan (Sather 1997: 4; Tomascik et al. 1997: 1219). Di Maluku Utara, Masyarakat Bajo
ada di pulau Sula Taliabo, Senana dan Sular, di pulau Halmahera selatan, di Gala dan di pulau Jo Ronga, Kubi, Katinawe dan Dowora (Teljeur 1990: 204), serta di
Kepulauan Bacam, di Obit Pulau dan Kepulauan Kayoa (Collins 1995: 16). Di Nusa Tenggara Timur dan Barat, masyarakat dapat ditemukan di pulau Lombok,
Sumbawa, Flores, Adonara, Lomblem, Pantar, Timor, dan Roti, dan di pulau-pulau kecil lepas pantai yang terletak di dekat pulau-pulau besar tersebut (Verheijen 1986).
Komunitas-komunitas ini dihubungkan oleh ikatan kekerabatan, pernikahan, dan bahasa yang kuat. Komunitas penutur bahasa Sama-Bajau tersebar luas secara
geografis, tetapi suku Bajo merupakan kesatuan etnis minoritas di Indonesia bagian timur. Pulau Katinawe dan Dowora (Teljeur 1990: 204), serta di Kepulauan Bacam,
di Pulau Obit dan Kepulauan Kayoa (Collins 1995: 16). Di Nusa Tenggara Timur dan Barat, masyarakat dapat ditemukan di pulau Lombok, Sumbawa, Flores, Adonara,
Lomblem, Pantar, Timor, dan Roti, dan di pulau-pulau kecil lepas pantai yang terletak di dekat pulau-pulau besar tersebut (Verheijen 1986). Komunitas-komunitas ini
dihubungkan oleh ikatan kekerabatan, pernikahan, dan bahasa yang kuat. Komunitas penutur bahasa Sama-Bajau tersebar luas secara geografis, tetapi suku Bajo
merupakan kesatuan etnis minoritas di Indonesia bagian timur. Pulau Katinawe dan Dowora (Teljeur 1990: 204), serta di Kepulauan Bacam, di Pulau Obit dan
Kepulauan Kayoa (Collins 1995: 16). Di Nusa Tenggara Timur dan Barat, masyarakat dapat ditemukan di pulau Lombok, Sumbawa, Flores, Adonara, Lomblem, Pantar,
Timor, dan Roti, dan di pulau-pulau kecil lepas pantai yang terletak di dekat pulau-pulau besar tersebut (Verheijen 1986). Komunitas-komunitas ini dihubungkan oleh
ikatan kekerabatan, pernikahan, dan bahasa yang kuat. Komunitas penutur bahasa Sama-Bajau tersebar luas secara geografis, tetapi suku Bajo merupakan kesatuan
etnis minoritas di Indonesia bagian timur. dan Roti, dan di pulau-pulau lepas pantai kecil yang terletak di dekat pulau-pulau besar ini (Verheijen 1986). Komunitas-
komunitas ini dihubungkan oleh ikatan kekerabatan, pernikahan, dan bahasa yang kuat. Komunitas penutur bahasa Sama-Bajau tersebar luas secara geografis, tetapi
suku Bajo merupakan kesatuan etnis minoritas di Indonesia bagian timur. dan Roti, dan di pulau-pulau lepas pantai kecil yang terletak di dekat pulau-pulau besar ini (Verheijen 1986). Komunitas-komunitas
Mayoritas penutur Sama di Indonesia bagian timur ini sekarang tinggal di
pemukiman rumah tiang yang dibangun di atas air di daerah pesisir, zona
pesisir, dan di darat. Hanya sedikit penghuni perahu yang tersisa di sepanjang
pesisir timur Sulawesi, terutama di sebelah utara Kendari di La Solo dan di
sekitar kelompok pulau di Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk nomaden
perahu di Indonesia tidak diketahui, tetapi diperkirakan hanya tersisa
beberapa ratus keluarga (komunikasi pribadi, Alimaturahim, 1994). Meskipun
meninggalkan tempat tinggal perahu permanen dan gaya hidup yang lebih
menetap, beberapa orang Bajo masih menghabiskan waktu singkat atau lama
di laut, tinggal di perahu sambil terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan.
Tingkat keterlibatan dalam gaya hidup dan pengejaran maritim bervariasi
antara komunitas Bajo. Selain perikanan dan budidaya,
Sementara bahasa Sama adalah bahasa utama yang digunakan oleh Tukang Besi Pulau
Bajo di antara mereka sendiri, banyak juga yang berbicara Bahasa Indonesia dengan
berbagai tingkat kompetensi. Membaca dan menulis bahasa Indonesia merupakan
keterampilan penting bagi seorang nakhoda, yang harus mampu menyelesaikan surat-surat
administrasi sepertisurat jalan(tiket perjalanan) dan surat-surat berlayar lainnya untuk dirinya
dan krunya. Banyak orang Bajo berbicara bahasa Tukang Besi setempat (di mana transaksi
pasar lokal biasanya dilakukan) dan beberapa berbicara bahasa Muna-Buton, Bugis,
Makassar, dan bahasa perdagangan-Melayu lainnya. Multibahasa ini mencerminkan
11
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
berbagai macam orang dengan siapa mereka berhubungan melalui kegiatan maritim dan
perdagangan, dan juga sejauh mana hubungan kekerabatan mereka.
Kepulauan Tukang Besi
Kepulauan Tukang Besi terletak di bagian timur laut Laut Flores, tenggara
pulau Buton. Terdapat lima pulau utama yang berpenghuni —Wanci,
Kambode, Kaledupa, Tomia dan Binongko — dan beberapa pulau kecil yang
sebagian besar tidak berpenghuni. Pulau-pulau tersebut sebelumnya
merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Buton, namun sejak tahun 1964
menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara). Ibu kota
provinsi ini adalah kota Kendari yang luas, terletak di tepi Teluk Kendari.
Hingga saat ini, Kepulauan Tukang Besi merupakan bagian dari Kabupaten
Buton, dengan pusat pemerintahan di Baubau, dan wilayah tersebut terbagi
menjadi empat kecamatan (kecamatan): Wangi Wangi, Kaledupa, Tomia dan
Binongko (Peta 2-2).
Gugusan pulau ini berdekatan dengan salah satu sistem terumbu karang terbesar
dan paling beragam secara biologis di Indonesia (Tomascik et al. 1997: 754). Pada bulan
Juli 1996 Kepulauan Tukang Besi dinyatakan sebagai Taman Nasional Laut oleh
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Alam. Taman Nasional Laut Wakatobi 1
mencakup semua terumbu karang dan pulau-pulau di nusantara dan mencakup 1,39
juta hektar (13.900 km2).2), yang membuatnya menjadi kawasan perlindungan laut
terbesar kedua di Indonesia (Stanzel dan Newman 1997).
Orang-orang Tukang Besi terkenal di seluruh Indonesia dan sekitarnya sebagai
'pelaut, pembuat kapal, dan pedagang maritim yang pemberani' (Evers 1991: 147).
Ekonomi maritim di Kepulauan Tukang Besi berkembang karena pulau-pulau yang
relatif tidak subur ini hanya dapat mendukung pertanian skala kecil dalam jumlah
terbatas, terutama pada periode musim barat. Selama musim kemarau atau musim
timur, ekonomi berfokus pada kegiatan maritim, termasuk pengumpulan, penangkapan
ikan, dan perdagangan. Rute perdagangan dapat berkisar hingga Singapura, Malaysia,
Jawa, dan Papua Barat, dan perdagangan melibatkan berbagai kargo termasuk kayu,
garam, umbi-umbian, pakaian bekas, kopra, dan rempah-rempah. Ini sebagian besar
berasal dari daerah lain di Indonesia, khususnya dari Maluku dan Jawa.
1 Pada tahun 2004, Wangi Wangi dimekarkan menjadi dua, dan kelima kecamatan tersebut digabungkan menjadi satu
kabupaten atau kabupaten baru bernama Wakatobi. Wakatobi merupakan akronim yang diambil dari nama empat nama
aslinya kecamatan.
12
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Peta 2-2: Pemukiman di Kepulauan Tukang Besi, Provinsi Sulawesi
Tenggara.
13
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
Makanan utama yang tumbuh di pulau-pulau termasuk singkong, ubi jalar, jagung, kakao,
kacang mete, kacang tanah, sayur-sayuran, kelapa dan buah-buahan. Beras dan makanan
musiman lainnya diimpor ke pulau-pulau dari bagian lain Sulawesi Tenggara. Ikan adalah
bagian pokok dari makanan dan ekonomi lokal. Penduduk Pulau Tukang Besi terlibat dalam
kegiatan penangkapan ikan lokal untuk konsumsi dan penjualan.
Sensus pemerintah tahun 1994 menghitung total populasi 73.251 di
Kepulauan Tukang Besi. ItukecamatanWangi Wangi memiliki populasi terbesar
dengan 34.081 jiwa (lihat Tabel 2-1). Ini menggabungkan pulau Wanci dan
Kambode (lihat Peta 2-2), dan pulau-pulau kecil tak berpenghuni di sisi timur
dan selatan Pulau Wanci. 2 Ada 16 desa (desa) dalamkecamatan. Pulau
Kambode memiliki tiga komunitas: duadesa, Kapota dan Kabita, dandusun(
dusun) Kolo, dengan jumlah penduduk sekitar 3000 jiwa. Jumlah penduduk
terbesar terkonsentrasi di bagian barat dan tengah Pulau Wanci.
Tabel 2.1: Penduduk Kepulauan Tukang Besi, 1994.
Kecamatan Wangi Wangi Kaledupa Tomia Binongko
Populasi 34 081 14 379 12 948 11 843
Sumber: Kabupaten Buton 1994a: 8; 1994b: 1; 1994c: 1; 1994d: 17.
Kota utama Wanci terletak di wilayah metropolitan Wanse-Pongo. dinas dan dinas
pemerintah, sekolah menengah pertama dan atas, dan a losmen(guest house)
semuanya terletak di Pongo. Pasar induknya ada di Pongo, namun beberapa tahun lalu
digeser ke Desa Mandati I yang merupakan desa darat terdekat dengan Mola Utara. 3
Wanci dapat dicapai dengan beberapa rute, semuanya melibatkan perjalanan panjang
dan sulit. Dari Baubau, ibu kota Buton, bus menuju desa Lasalimu di pesisir timur Buton,
yang biasanya ditempuh dalam waktu tiga jam perjalanan. Dari sini feri berbasis Wanci,
dan baru-baru ini speedboat penumpang, melakukan perjalanan setiap hari antar
pulau, yang biasanya memakan waktu dua hingga tiga jam perjalanan. Feri juga
melakukan perjalanan 16 jam langsung dari Kendari ke Wanci, biasanya sekali atau dua
kali seminggu.
Ibu kota lama negara bawahan Kaledupa adalah Buranga, tetapi sekarang Ambeua
adalah ibu kota resmi negara bagian Kaledupa.kecamatanyang meliputi Pulau Kaledupa,
pulau terdekat Hoga, dan dua pulau tak berpenghuni Lintea dan Tiwolu. Ada sepuluhdesadi
Kaledupa. Transportasi harian beroperasi antara Wanse dan Ambeua dengan kapal motor
kecil — perjalanan yang memakan waktu 2–3 jam. Pulau Hoga dulunya tidak berpenghuni
karena kekurangan pasokan air bersih, namun pada tahun 1992 pemerintah setempat
membangun rumah bergaya tradisional Buton di pulau tersebut untuk menarik wisatawan
mancanegara. Usaha ini tidak berhasil, tetapi pada tahun 1995
2 Pemakaman Bajo terletak di pulau karang kecil Otoue yang terletak di selatan Mola.
3 Bahasa Wanci, dialek lokal dari bahasa Tukang Besi, adalah lingua franca yang digunakan di pasar oleh
orang Wanci dan Bajo.
14
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
bangunan diambil alih oleh Operasi Wallacea, sebuah organisasi non-pemerintah yang mengundang
sukarelawan atau siswa yang membayar biaya untuk bergabung dalam ekspedisi survei terumbu karang
selama dua hingga enam minggu (Stanzel dan Newman 1997). Organisasi ini juga telah bekerja sama
dengan pemerintah Indonesia untuk merancang dan mengimplementasikan rencana pengelolaan Taman
Laut dengan menggunakan data yang telah dikumpulkannya. 4
ItukecamatanTomia meliputi pulau Tomia, Tolandono, Lintea dan Sawah. Ibu kota
Tomia adalah Waha dan ada delapan desa di pulau itu serta komunitas kecil di
Tolandono. Pada tahun 1996, Wakatobi Dive Resort didirikan oleh orang asing di Pulau
Tolandono (juga disebut Onemobaa), yang terletak di barat daya pulau utama Tomia
(Peta 2-2). Pada awal tahun 2001, resor membuka lapangan terbang sepanjang 1506 m
di Tomia untuk membawa wisatawan melalui udara langsung dari Bali.
Pulau (dankecamatan) Binongko jauh lebih kering dan terpencil dibandingkan pulau
lainnya (Burningham 1996). Selain perdagangan laut, masyarakat Binongko juga
bergerak di bidang pengerjaan logam, khususnya pembuatanparangpisau (mirip
parang) yang dianggap sebagai salah satu yang terbaik di wilayah Sulawesi. 'Tukang
Besi' sebenarnya adalah istilah Melayu untuk tukang logam atau pandai besi.
Pemukiman Bajo di Kepulauan Tukang Besi
Ada lima komunitas Bajo di Kepulauan Tukang Besi. Yang terbesar adalah
pemukiman Mola di Pulau Wanci, yang terbagi antara dua desa yang disebut
Mola Utara (Mola Utara) dan Mola Selatan (Mola Selatan). Ada tiga desa di
pulau Kaledupa — Mantigola, Sampela dan La Hoa. Desa La Manggau terletak
di pulau Tolandono dekat Tomia. Para nelayan Bajo dari desa Mola Selatan,
Mola Utara, dan Mantigola-lah yang melakukan pelayaran musiman ke wilayah
Australia bagian utara. Studi ini terutama berkaitan dengan penduduk desa ini,
dan khususnya laki-laki dari Mola Utara dan Mola Selatan, di mana sebagian
besar pekerjaan lapangan dilakukan.
Suku Bajo adalah kelompok minoritas di Kepulauan Tukang Besi, hanya sekitar
10 persen dari total populasi. Kelompok etnis mayoritas adalah Penduduk Pulau
Tukang Besi, terkadang disebut 'orang Buton', yang berbicara dengan bahasa lokal
yang khas. 5 Seperti tetangga darat mereka, orang Bajo sering mengidentifikasi
diri mereka atau diidentifikasi oleh orang lain sebagai Orang Buton atau Buton.
Label ini bisa agak menyesatkan, memberi kesan bahwa orang atau orang yang
dimaksud sebenarnya berasal dari pulau Buton, bukan salah satu pulau di
rangkaian Tukang Besi. Praktik identifikasi dengan 'kesetiaan sejarah' ini
4 Operasi Wallacea sekarang memiliki program ilmu kelautan selama empat tahun (2004–08) untuk memandu penelitian
sosial dan biologi di Kaledupa, dengan dua pusat penelitian lain untuk mendukung kegiatannya di kecamatan tersebut.
Dampak dari sejumlah besar peneliti terhadap masyarakat setempat tidak diketahui tetapi Operasi Wallacea membanggakan
bahwa mendukung masyarakat melalui pengelolaan lingkungan laut yang lebih baik memiliki manfaat langsung bagi suku
Bajo yang sangat bergantung pada sumber daya laut (www.opwall.com).
5 Penjelasan rinci tentang bahasa Tukang Besi dapat ditemukan di Donohue (1999).
15
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
bukan identitas etnis' sejak masa Kesultanan Buton yang pernah mengklaim Kepulauan
Tukang Besi dan penduduknya sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya (Fox 1995b:
5). Istilah generik 'Buton' dengan demikian dapat mencakup sejumlah sub-etnis dari
Buton dan pulau-pulau tetangga di Sulawesi Tenggara.
Desa Mola Utara dan Mola Selatan
Pemukiman yang terdiri dari dua desa yang bersebelahan yaitu Mola Utara dan Mola
Selatan terletak di perairan pantai dangkal di pantai barat daya Pulau Wanci, kira-kira 2
km dari Wanse (Gambar 2-1). Membentang sejajar dengan pantai, pemukiman Mola
memanjang sekitar 800 m dan hingga 400 m dari garis pantai. Ini adalah pemukiman
Bajo terbesar di Kepulauan Tukang Besi, dan mungkin salah satu yang terbesar di
Indonesia. Awalnya satu desa, tetapi ditetapkan sebagai dua desa pada tahun 1981
karena populasinya yang terus bertambah. Setiap desa dibagi menjadi dua dusun. Pada
tahun 1994 Mola Utara memiliki jumlah penduduk 1963 yang tinggal di 338 rumah,
sedangkan Mola Selatan sedikit lebih besar dengan jumlah penduduk 2315 yang tinggal
di 388 rumah (lihat Tabel 2-2). Dalam beberapa kasus ada lebih dari satu keluarga yang
tinggal di sebuah rumah, jadi jumlah rumah tidak mencerminkan jumlah keluarga. Mola
Utara luasnya jauh lebih kecil daripada Mola Selatan (2,3 km2dibandingkan dengan 6 km
2 ), sehingga memiliki kepadatan populasi yang lebih tinggi. Tingkat migrasi musiman
yang tinggi berarti bahwa jumlah populasi berfluktuasi dari waktu ke waktu, terutama
selama musim timur antara bulan Juli dan Desember, ketika pejantan melakukan
pelayaran dan keluarga serta kerabat jauh bermukim kembali di Pepela selama musim
penangkapan ikan. Selain itu, karena orang Bajo sering menghabiskan waktu jauh dari
Mola untuk melakukan kegiatan lain, sulit untuk mendapatkan jumlah populasi yang
pasti.
Tabel 2-2: Populasi dan jumlah rumah di Mola, 1994.
Pria Perempuan Total Jumlah rumah
Mol Utara 981 982 1963 338
Mol Selatan 1158 1157 2315 388
Sumber:Kapubaten Buton (1994a: 9) dan data survei lapangan 1994.
Penduduk Mola sebagian besar adalah suku Bajo, tetapi beberapa perkawinan silang
telah terjadi dengan orang Tukang Besi lainnya dan dengan orang Buton, Bugis, Makassar
dan Maluku lainnya, serta dengan orang Bajo dari daerah lain di Indonesia. Banyak orang
Bajo yang tinggal di Mola Utara berasal langsung dari masyarakat lain atau tempat berlabuh
kapal di Buton, sedangkan sebagian besar penduduk paruh baya Mola Selatan lahir atau
berasal dari Mantigola pada akhir tahun 1950-an. Beberapa orang tua Bajo melaporkan
mereka lahir di laut di atas perahu kecil yang disebutsoppe. Generasi tua ini memiliki orang
tua yang lahir di tempat-tempat seperti Klingsusu, Pasar Wajo, La Goro, atau Bisaya di Buton
atau di pulau Kabaena, sebelah barat Buton. Yang lain memiliki orang tua
16
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
yang lahir di Oenggai (di Pulau Roti) atau di Kabir (di Pulau Pantar).
Sebagian besar generasi muda Bajo lahir di Mola.
Permukiman Mola terdiri dari deretan rumah yang dibangun langsung di atas fondasi
batu karang atau di atas tumpukan kayu di atas air, dengan setiap baris umumnya dipisahkan
oleh saluran air atau kanal dengan lebar yang berbeda-beda. Rumah-rumah individu dan
bagian desa dihubungkan dengan papan kayu yang ditempatkan secara renggang atau
bambu panjang di atas air atau jembatan yang ditinggikan di antara fondasi karang.
Beberapa bagian desa yang lebih tua memiliki pondasi batu karang yang lebih luas di depan
rumah. Pemukiman ini dapat diakses dari darat melalui dua jalur arteri batu karang utama,
satu di dekat kantor desa (kantor desa) dan satu di dekat masjid. Ada juga jalan setapak arteri
yang sejajar dengan saluran air utama. Setiap rumah di pemukiman memiliki akses langsung
ke laut. Penduduk yang lebih tua mengklaim bahwa Mola awalnya dibangun di atas air dan
cukup jauh dari daratan, sebelum jalan setapak permanen dibangun pada tahun 1960-an,
sehingga sebagai anak-anak mereka harus berenang atau bepergian dengan kano untuk
bersekolah. Saat ini, orang Bajo berkeliling pemukiman dengan berjalan kaki atau kano,
tetapi beberapa rumah yang baru dibangun di utara dan selatan hanya dapat diakses dengan
kano. Perjalanan dengan kano seringkali merupakan metode tercepat dan termudah untuk
berkeliling pemukiman dan dilakukan secara kompeten oleh orang Bajo yang terampil dari
segala usia (Gambar 2-2, 2-3 dan 2-4).
Pergerakan pasang surut berkisar hingga 2,5 m, secara berkala membuang sampah
rumah tangga dan limbah pribadi, tetapi selama air surut, terutama air pasang perbani,
bau busuk menyengat pemukiman. Pada saat air pasang sangat tinggi dan cuaca badai,
fondasi batuan dapat terendam di beberapa lokasi.
17
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
Gambar 2-1: Desa Mola Utara dan Mola Selatan, Pulau Wanci.
Gambar 2-2: Masjid dan rumah-rumah di sepanjang kanal utama di Mola Selatan.
18
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Gambar 2-3: Rumah-rumah yang berjejer di kanal sempit di Mola Utara bagian tengah.
Gambar 2-4: Rumah yang baru dibangun di ujung utara Mola Utara.
19
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
Suku Mola Bajo tidak memiliki hak teritorial atau klaim atas badan air tempat mereka
membangun rumah. Hanya fondasi batu karang dan rumah-rumah yang diberi hak milik
pribadi. Rumah-rumah dibangun dari berbagai bahan — kayu, batu bata atau panel daun
lontar, dengan atap asbes, timah dan rumbia. Banyak rumah kayu yang sebenarnya dibangun
dari bahan yang dibeli dari orang Tukang Besi, terutama dari Kaledupa. Gubuk beratapkan
rumbia, dengan lantai bilah kayu atau bambu, biasanya dibangun di bagian belakang rumah
untuk digunakan sebagai tempat memasak. Karena sering kali merupakan bagian rumah
yang paling keren, ini digunakan sebagai ruang tamu serba guna, tetapi di rumah yang lebih
kecil, ruang tidur dan area memasak terdapat dalam satu struktur. Beberapa rumah memiliki
gubuk toilet kecil yang dibangun di atas tumpukan di atas air, dan satu jamban sering
digunakan oleh beberapa keluarga. Mandi paling sering dilakukan di luar ruangan,
menggunakan air tawar yang disimpan dalam toples keramik atau jerigen. Beberapa rumah
memiliki gubuk terpisah untuk digunakan sebagai tempat mencuci, sedangkan rumah bata
yang lebih baru memiliki kamar mandi.
Sejak tahun 1989 air tawar telah dipompa dari tangki-tangki di daratan melalui pipa-pipa ke
sejumlah tangki penampungan satelit. Beberapa rumah di bagian tengah pemukiman memiliki air
yang dipompa langsung ke rumah mereka. Yang lebih umum, perempuan dan anak-anak harus
mengambil air dari sumur yang terletak di Mandati I, atau membeli air dari orang lain, atau pergi
dengan kano ke desa Kapota di Pulau Kambode untuk mendapatkan air minum yang berkualitas
baik. Perempuan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengumpulkan air dalam
wadah plastik dan kemudian mengangkutnya dengan kano ke rumah mereka.
Meskipun banyak bagian pemukiman memiliki listrik, listrik hanya tersedia dari
sore hingga sekitar pukul 6 pagi dan pada hari Minggu sore. Tidak setiap rumah
tangga memiliki televisi sendiri tetapi menonton TV komunal adalah hobi yang
populer, dan sekitar empat rumah, terutama milik Haji, memiliki satelit pada tahun
1995 dan dapat mengakses saluran televisi internasional.
Ada sebuah Sekolah Dasar (Sekolah Dasar Mola Utara) yang terletak di tanah di Mandati I.
Kehadiran anak-anak Bajo di sekolah tidak teratur sehingga tingkat buta huruf di masyarakat
tinggi. Hanya sedikit yang tamat SMP dan SMA, bahkan lebih sedikit lagi yang melanjutkan ke
perguruan tinggi. Orang tua yang menjunjung tinggi pendidikan dan memiliki sarana
keuangan yang diperlukan atau kontak keluarga sering menyekolahkan anaknya di Baubau
atau Kendari untuk mendapatkan standar pendidikan yang lebih tinggi. 6 Pada tahun 1995,
sekitar 20 orang dewasa muda Mola Bajo telah menyelesaikan beberapa bentuk pendidikan
tinggi di universitas di Baubau, Kendari dan Ujung Pandang, tetapi bahkan orang-orang
muda ini sulit mendapatkan pekerjaan formal.
6 Orang-orang Tukang Besi dari Kaledupa memiliki tradisi mengirim anak-anak mereka untuk tujuan pendidikan ke
daerah lain di Indonesia selama berabad-abad (Donohue 1999).
20
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Pemukiman Bajo lainnya
Itudusunof Mantigola dibangun di atas gumuk pasir dan rataan terumbu karang di
perairan dangkal di sisi barat pulau Kaledupa, sekitar 400–500 m dari area untaian
pohon bakau di Desa Horuo dan hanya dapat diakses dengan perahu. Desa Horuo
berjarak sekitar 1 jam berjalan kaki dari Ambeua. Mantigola, dengan populasi sekitar
600–700 orang, secara resmi merupakan bagian dari Desa Horuo, yang memiliki total
populasi 1342 pada tahun 1994. Seperti Mola, pemukiman ini mengalami fluktuasi
populasi dengan pejantan berlayar dalam pelayaran musiman perdagangan dan
penangkapan ikan selama pelayaran timur. musim.
Bukti populasi yang lebih besar yang tinggal di Mantigola di masa lalu dapat
disimpulkan dari serangkaian fondasi karang yang lebih jauh ke laut dan dari fakta
bahwa rumah-rumah sekarang ditempatkan agak jauh satu sama lain. Mantigola disukai
oleh orang Bajo karena laguna besar yang terletak di tengah desa berfungsi sebagai
tempat berlabuh di air yang dalam. Namun, tidak seperti Mola, hanya ada sedikit jalan
setapak di sekitar Mantigola dan perlu berkeliling desa dengan kano saat air pasang.
Rumah-rumah serupa dengan yang ada di Mola, dibangun dari berbagai bahan seperti
bambu, nipah, kayu dan besi beratap, dan dibangun di atas tiang kayu langsung di atas
air atau di atas pondasi batu karang (lihat Gambar 2-5). Tidak ada listrik. Air harus
dikumpulkan dari sumur di tanah di Horuo dan diangkut dengan jerigen dengan kano.
Terisolasinya Mantigola membuat sulitnya mendapatkan makanan segar dan
perlengkapan rumah tangga, dan perempuan biasanya membeli makanan dari Horuo
atau berjalan kaki ke area pasar utama di Ambeua. Mantigola Bajo menguburkan
jenazah mereka di tanah di sebelah kanan Horuo.
Dusun Sampela terletak kurang lebih 400 m dari daratan di sisi timur laut Pulau
Kaledupa. Secara administratif merupakan bagian dari Desa Lau Lua. Populasi Sampela
(sekitar 1200 orang) tinggal di sekitar 210 rumah yang dibangun dari material
sementara (komunikasi pribadi, Chris Majors, 1998). Sebagian besar desa dapat diakses
dengan berjalan kaki melalui jalan setapak dan jembatan. Tidak ada listrik atau pasokan
air tawar setempat, sehingga harus diambil dari sumur dan diangkut dengan kano dari
Kaledupa. Tingkat imigrasi dan emigrasi di Sampela lebih rendah daripada desa-desa
Bajo lainnya. Sampela dilaporkan sangat miskin dibandingkan dengan Mola dan
Mantigola, tetapi merupakan salah satu penerima manfaat dari proyek pengembangan
masyarakat yang didanai oleh Operasi Wallacea.
21
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
Gambar 2-5: Pasang surut di Mantigola.
Dusun La Hoa terletak di sisi timur Kaledupa dan secara administratif
merupakan bagian dari Desa Langge, yang memiliki jumlah penduduk 1771 pada
tahun 1994. La Hoa adalah komunitas Bajo terkecil di Kaledupa, yang terdiri dari
sekitar 15 rumah (komunikasi pribadi, Chris Jurusan, 1996).
Dusun La Manggau terletak di ujung utara Pulau Tolandono, tidak jauh dari
Waha, ibu kota Pulau Tomia, dan berpenduduk 500–600 jiwa. Pemukiman tersebut
secara administratif merupakan bagian dari Desa Waiti. Dusun ini terdiri dari
sejumlah kecil keluarga Bajo serta beberapa orang Tomia. Ada 10–15 rumah Bajo
yang dibangun di atas air di sisi pemukiman yang menghadap ke laut. Rumah
mereka dapat diakses dari tanah tempat tinggal orang Tomia.
Sejarah Permukiman Suku Bajo di Kepulauan Tukang Besi
Tetua desa dari masyarakat Bajo di Mantigola dan Mola menceritakan kisah
kedatangan nenek moyang mereka di Kepulauan Tukang Besi melalui pulau Buton
pada abad ke-19. Dua tetua desa yang dihormati, Si Bilaning dan Si Mbaga, 7
keduanya melaporkan bahwa pemukiman atau tempat berkumpul pertama bagi
orang Bajo yang tinggal di perahu di Kepulauan Tukang Besi adalah di Kaledupa di
Lembonga. Lembonga terletak di dekat pemukiman La Hoa saat ini di sisi utara
pulau, tidak jauh dari Buranga, ibu kota lama Pulau Kaledupa. Belakangan, banyak
orang Bajo pindah ke sisi lain pulau, ke tempat yang sekarang disebut Mantigola
7 Si Bilaning, salah satu laki-laki Bajo tertua di Mantigola, meninggal pada akhir 1994, dan Si Mbaga, salah satu laki-laki Bajo
tertua di Mola Selatan (dan sezaman dengan Si Bilaning) meninggal pada Mei 1996.
22
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
ikan pada musim timur. Mereka kemudian akan kembali ke Lembonga pada awal
musim barat. Pendirian Mantigola terjadi ketika orang Bajo meminta izin kepada Sultan
Buton untuk membangun rumah di sana karena letaknya lebih dekat ke karang lepas
pantai daripada Lembonga.
Seorang pria Bajo dari Mantigola menyatakan bahwa nama 'Mantigola' berasal dari
frase tersebutmenunggu gula, yang berarti 'menunggu gula' dalam bahasa Indonesia.
Kisah di balik namanya menarik mengingat hubungan Tukang Besi-Pulau Roti. Rupanya,
para pedagang Binongko akan berlayar ke Roti untuk membeligula air(gula dari lontar
kelapa sawit) yang kemudian dibawa kembali ke Kepulauan Tukang Besi dan dijual ke
Bajo dan orang-orang darat di lokasi Mantigola sekarang. Pedagang Binongko telah
lama menjalin hubungan dagang dengan Pepela dan penduduk lokal Roti. Beberapa
pemukim maritim pertama di Pepela adalah laki-laki Binongko.
Catatan lisan yang diberikan oleh Si Bilaning dan Si Mbaga tentang kedatangan dan
pemukiman orang Bajo di Kaledupa dapat dibandingkan dengan catatan yang dibuat oleh
Pak Kasmin, seorang Bajo dari Mola Utara, yang lulus pada tahun 1993 dari Universitas
Haluoleo dengan kualifikasi mengajar. Pak Kasmin mendokumentasikan kisah kedatangan
orang Bajo di Kaledupa berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua di Mola dan
Mantigola, antara lain Si Bilaning dan Si Mbaga:
Sebelum orang Bajo datang ke Kepulauan Tukang Besi mereka tinggal di Pasar
Wajo [pantai selatan Buton]. Suatu saat di tahun 1850-an, beberapaperahubidu
[perahu kayu besar] danperahusoppe[perahu kayu kecil] berangkat untuk
mensurvei kondisi Kepulauan Tukang Besi. Mereka menemukan pulau-pulau itu
berada di lokasi yang sangat strategis dan dengan laut yang kaya
memungkinkan untuk dikembangkan. Setelah itu, mereka kembali ke Pasar
Wajo untuk meminta izin kepada Sultan Buton; mereka diberi izin pindah untuk
tinggal di Kepulauan Tukang Besi. Orang Bajo yang pindah ke Kepulauan
Tukang Besi dipimpin oleh dua orangpunggawa[pemimpin], Puah Kandora dan
Puah Doba. Mereka berlayar berkelompok dalam beberapaperahu[perahu
kayu] dengan beberapa kepala keluarga di masing-masingnyaperahu. Mereka
pertama kali singgah di Lia di Pulau Wanci. Tidak lama kemudian mereka
pindah ke Lembonga di bagian timur laut Kaledupa, dan disanalah mereka
tinggalperahubiduatausoppedan menangkap ikan serta mengumpulkan hasil
laut lainnya, dan pada saat itu mereka masih hidup berpindah-pindah. Pada
musim timur laut mereka pindah ke bagian barat daya Kaledupa yang dikenal
dengan nama Kampung Mantigola, dan mereka kembali ke Lembonga pada
musim barat. Kedatangan orang Bajo di Kepulauan Tukang Besi disambut baik
oleh Pemerintah dan masyarakat setempat dan mereka meminta izin untuk
membangun rumah di Mantigola pada tahun 1850-an (Kasmin 1993: 32–3).
Menurut Sopher (1977: 151, 268), pada abad ke-19 kepala suku dari
setiap suku Bajo bergelarpunggawa—gelar adat kepala suku
23
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
atau pemimpin di kalangan suku Bajo-Bugis, atau Bajo yang setia kepada pangeran Bugis atau
Makassar. Orang Bugis menggunakan istilah itu untuk memaksudkan panglima militer atau kapten
kapal (Pelras 1996: 332). Menurut Mola Bajo, Puah Doba, tokoh Bugis yang disebutkan dalam cerita
di atas, juga disebut Daeng Nyirrang. Dia menikah dengan wanita Bajo dan karena itu ada
hubungan kekerabatan yang erat antara kedua kelompok tersebut. Bajo sering mengatakan 'orang
Bugis saudara kita' ('Bugis adalah saudara kami').
Selama abad ke-19, ibu kota asli Pulau Wanci berada di Lia Togo, terletak di atas
punggung bukit dengan pemandangan laut dan pulau-pulau di sekitarnya,
khususnya Kaledupa. Lokasi tersebut dipilih untuk keamanan dari perampok budak
dan bajak laut Taosug. Sebagian besar penduduk Wanci tinggal di daerah yang
lebih tinggi di pulau itu, dan pemukiman di sepanjang pantai relatif baru. Pasar
sentral dan area komersial sebelumnya beroperasi dari Lia Mawi di pesisir pantai.
Menyusul pengamanan wilayah tersebut oleh kekuatan kolonial Belanda, sebuah
komunitas kecil Bajo didirikan di Lia Mawi tetapi ibu kota dipindahkan ke wilayah
Wanse-Pongo (Donohue 1994: 4). Tidak jelas apakah pemukiman Bajo lama di Mola
Utara sekarang didirikan saat ini, namun Si Juda dari Mantigola menyatakan bahwa
penduduk asli Mola berasal dari desa Lagoro dan Lasalimu di pantai timur Buton.
Hingga tahun 1950-an, Mantigola merupakan pemukiman Bajo terbesar di
Kepulauan Tukang Besi. Setelah itu, Bajo dari Mantigola melakukan migrasi besar-
besaran ke Mola. Bajo juga diusir oleh pemberontakan dan konflik antar
komunitas.
Pemberontakan Kahar Muzakkar dan Migrasi Bajo
Antara tahun 1950 dan 1965, Kahar Muzakkar memimpin pemberontakan (
gerombolan) melawan pemerintah nasional yang membuat Sulawesi Selatan dan
Tenggara dalam keadaan kerusuhan sipil. Ini terkait dengan faksi politik Darul
Islam (Negara Islam) dan terkait denganTentara Islam Indonesia(Tentara Islam
Indonesia) pemberontakan di Jawa Barat dan Aceh. Selama periode ini, Sulawesi
terbagi antara pengikut Kahar Muzakkar danTentara Nasional Indonesia (TNI), dan
sebagian besar Sulawesi Tenggara berada di bawah kendali para pemberontak
(Harvey 1974: 1437). Pemberontakan Kahar Muzakkar, biasa disebut hanya sebagai
gerombolanoleh orang Bajo, mengakibatkan pergolakan besar bagi Mantigola Bajo
dan bertanggung jawab atas banyaknya pemukiman di Mola dan pemukiman
lainnya di Kepulauan Tukang Besi. Dari situ banyak tersebar di sekitar Indonesia
bagian timur.
Mola Mola dan Mantigola Bajo generasi tua mengingat kekacauan dalam hidup
mereka, terutama selama tahun 1956 dan 1957. Beberapa anggota masyarakat Bajo
adalah pendukung aktif darigerombolan, namun tindakan mereka ditentang oleh
masyarakat Kaledupa dan pemerintah daerahnya. Pembalasan dan serangan kekerasan
berikutnya oleh penduduk darat memaksa Mantigola Bajo pindah ke Sampela.
Serangan-serangan ini terjadi atas dorongan unit-unit lokal dariTentara Nasional
Indonesiaberbasis di Kaledupa yang ingin memiliki kontrol yang lebih ketat di Bajo.
24
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Namun, dukungan untuk pemberontakan terus berlanjut, dan sekitar setahun
kemudian, dengan ancaman lebih lanjut dari pemerintah Kaledupa, Mantigola Bajo
melarikan diri dengan perahu dan kano mereka ke Mola. Ini dilakukan atas izin
pemerintah Wanci yang mendukung pemberontakan tersebut (komunikasi pribadi,
Si Pallu, 1995). Saat itu, komunitas kecil Bajo sekitar 30 rumah sudah ada di Mola
Utara bagian tengah.
Selama periode kerusuhan dan pergolakan ini, mayoritas Mantigola Bajo pindah ke
Sampela. Beberapa saat kemudian beberapa lagi melarikan diri dari Mantigola dan
Sampela ke daerah lain di Sulawesi bagian timur. Beberapa orang Bajo pindah ke desa
Langara di Pulau Wowonii, dekat Kendari. Komunitas ini kemudian terpaksa mengungsi
ke Kendari sendiri namun akhirnya kembali. Beberapa orang melarikan diri ke desa
Matanga di Kepulauan Banggai dan ke Limbo di Pulau Kukkusang di Sulawesi Tengah.
Yang lainnya langsung pindah dari Mantigola dan Mola ke Sulamu di Teluk Kupang, dan
juga ke desa Bajo Kabir di Pulau Pantar. 8 Masyarakat Wuring di pantai utara Flores
dekat Maumere juga dihuni oleh Bajo dari Mantigola selama pemberontakan
(Burningham 1993: 209). Namun, Si Pallu dan lainnya dari Mola mengklaim mayoritas
orang Bajo yang menetap di Wuring berasal dari Pulau Kabaena, sebelah timur Buton,
dan dari Pasar Wajo di pantai selatan Buton. Menderita masalah serupa, mereka juga
mengungsi ke daerah yang lebih aman di pulau terluar.
Menurut orang Bajo,kampung(desa) La Manggau di Pulau Tolandono didirikan
setelah berakhirnya pemberontakan. Pada saat itu, sebagian besar orang Bajo yang
tinggal di Mola tetap tinggal di sana, meskipun beberapa kembali ke Sampela dan yang
lainnya kembali ke Mantigola karena kedekatannya dengan terumbu karang lepas
pantai. Namun, sejak akhir 1980-an, migrasi suku Bajo yang paling signifikan dari Mola
dan Mantigola – tidak hanya anggota masyarakat laki-laki tetapi juga perempuan dan
anak-anak – adalah dari dan ke desa Pepela di pulau Roti.
Desa Pepela, Pulau Roti
Pulau Roti terletak di Laut Timor, sebelah barat daya Kupang, ibu kota Timor
Barat. Ini adalah pulau berpenghuni paling selatan di Indonesia. Secara
administratif merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (Nusa
Tenggara Timur). Ibu kota Roti adalah Ba'a yang terletak di sisi barat pulau.
Desa Pepela terletak di ujung timur laut Roti dan di sisi selatan sebuah teluk
besar yang terlindung (lihat Peta 2-3). Teluk ini dibatasi oleh pantai berpasir
dan hutan bakau, sedangkan terumbu karang terletak di tengahnya. Di
pemukiman Pepela, pantai berpasir menurun tajam memberikan a
8 Salah satunya, Si Saddong, adalahkepala kampung(kepala desa) pada saat itu; dia adalah keturunan
bangsawan Bajo dan merupakan penjaga naskah Lontar langka dan berharga yang mendokumentasikan
sejarah Bajo.
25
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
jangkar laut dalam dekat pantai. Teluk ini sangat menarik dan memberikan
perlindungan sepanjang tahun dari angin muson timur dan barat yang kuat.
Peta 2-3: Pulau Roti, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dusun Pepela secara resmi merupakan bagian dari Desa Londalusi, di Kecamatan
Rote Timur, yang beribukota di Eahun (sekitar 9 km ke pedalaman dari Pepela). Pada
tahun 1994, jumlah penduduk Londalusi adalah 2.765 jiwa dan jumlah penduduk Pepela
kurang lebih 800 jiwa. Komposisi etnis Pepela adalah campuran, terdiri dari penduduk
asli Rote Kristen, keturunan imigran Muslim Buton dari pulau lain (Fox 1998: 127), Bugis
dari Tenggara. Sulawesi, dan Bajo dari Kepulauan Tukang Besi. Perekonomian
penduduk Pepela didasarkan pada penangkapan ikan di Laut Timor dan perdagangan
hasil laut terkait. Sebagian besar tanah dimiliki oleh penduduk asli Roti, sehingga
penduduk Muslim bergantung pada laut untuk pendapatan mereka.
Penduduk asli Kristen terlibat dalam kegiatan pertanian, pengumpulan untaian lokal, dan
penangkapan ikan di pantai dengan perahu kecil. Mereka 'tidak terkenal karena tradisi
berlayar di laut terbuka' (Fox 1998: 126). Sejarah pemukiman masyarakat maritim Muslim di
Pepela belum terdokumentasi, tetapi Pepela secara tradisional merupakan pelabuhan bagi
bagian timur Roti (ibid.: 127). Roti penting dalam jaringan perdagangan maritim pada abad
ke-19 karena orang Roti memproduksi layar kain yang terbuat dari bahan tersebutgewang
daun palem kipas (Corypha elata) untuk perahu kecil mereka sendiri dan untuk dijual (ibid.:
126). Sketsa orang Makassarperahudari Raffles Bay di
26
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Australia utara yang digambar oleh Le Breton pada tahun 1839 mengilustrasikan layar
tradisional yang diproduksi dan diperdagangkan oleh orang Roti (lihat Macknight 1976,
Gambar 33). Orang Roti juga terkenal dengan kue gula mengkristal yang terbuat dari
sari buahlontartelapak (Borassussp.) (Fox 1977b). Warga Bajo dan Pepela menuturkan,
dulu para pelaut Binongko dari Kepulauan Tukang Besi rutin berkunjung ke Pepela
untuk membelilontargula aren, yang kemudian diperdagangkan di seluruh kepulauan
Indonesia. Perdagangan ini berlanjut hingga saat ini, namun kapal dari Roti juga
berlayar ke Kepulauan Tukang Besi untuk menjual gula aren langsung ke Bajo.
Kegiatan perdagangan laut semacam ini akan menjelaskan beberapa pemukiman
Muslim di Pepela, kemungkinan dimulai pada awal abad ke-20 tetapi kemungkinan
besar setelah tahun 1920-an. Penyelesaian selanjutnya oleh kelompok Muslim lainnya
tampaknya merupakan hasil dari aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan di Laut
Timor. Saat ini populasi nelayan Pepela sebagian besar terdiri dari pendatang dari pulau
lain atau keturunan mereka, meskipun banyak yang telah menikah dengan penduduk
lokal Roti. Pulau asal yang paling sering disebut oleh warga Pepela adalah Sulawesi,
Buton, Binongko, Alor, Pantar, Flores dan Jawa. 9
Pemukiman Pepela membentang ke pedalaman dari pantai sekitar satu
kilometer. Sebuah dermaga mendominasi pelabuhan dan dari sini jalan
menuju pusat desa ke atas bukit. Sebagian besar pemukiman berada di sisi
barat, namun di sebelah timur pemukiman utama terdapat kawasan yang
disebut Kampung Baru (New Village), yang merupakan gugusan rumah orang
Bajo. Lebih jauh ke timur, dan terletak di dasar punggung bukit, terdapat
perkebunan kelapa dan kuburan. Pemukiman utama Bajo terletak jauh dari
bagian utama desa di Tanjung Pasir (Sand Spit/Point), disingkat Tanjung. Ada
beberapa toko kecil di sepanjang jalan utama. Ada satu atau dua sumur di
desa tersebut, tetapi sebagian besar air dikumpulkan dalam jerigen dari
sebuah danau kecil dan sumur di sebelah barat (sekitar 1 km dari dermaga)
dan kemudian diangkut dengan gerobak kayu.
Di sisi lain teluk adalah pemukiman Kristen Suoi (Dusun Suoi, Desa Dai Ama). Dalam
beberapa tahun terakhir beberapa laki-laki dari Suoi telah bergabung dengan Pepela
perahudalam kegiatan penangkapan ikan di Laut Timor. Di sebelah timur Pepela adalah
pemukiman kecil orang Rote, Dusun Haroe (Desa Hundi Hopo), titik terakhir yang dilalui
kapal sebelum berlayar ke Laut Timor.
Sebuah feri penumpang beroperasi setiap hari antara Kupang dan Pantai Baru, sebuah teluk
kecil berpohon bakau di sisi barat laut Roti. Sebuah perahu motor juga melakukan perjalanan
9 Misalnya, dua warga, Hassan La Musa dan Haji Saman La Duma, kini keduanya berusia 60-an, datang dari desa
Popalia di Binongko ketika masih muda saat mereka melakukan pelayaran dagang. Mereka menikah dengan
wanita lokal Rote dan menetap di Pepela, membawa serta merekaperahuteknologi. Kedua ayah mereka
sebelumnya telah berlayar ke Pepela dan berdagang dengan penduduk setempat.
27
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
seminggu dua kali antara Pepela dan desa Namosain di Kupang. Perjalanan
memakan waktu sekitar enam jam tergantung pada kondisi cuaca.
Pemukiman Bajo di Pepela
Di masa lalu, orang Bajo dari Mola dan Mantigola berlayar dari desa asalnya ke Pepela dan
menggunakannya sebagai basis pelayaran nelayan ke Laut Timor. Sementara di Pepela menunggu
kondisi cuaca yang cocok, para lelaki tinggal di rumah mereka sendiriperahu dan disediakan
kembali dengan kayu bakar dan air tawar. Seorang warga desa Mantigola, Si Suleyman, adalah
orang Bajo pertama yang menetap di Pepela, setelah menikah dengan perempuan lokal Pepela
pada tahun 1950-an. Periode utama pemukiman orang Bajo baru dimulai pada akhir tahun 1980-an,
ketika beberapa dari mereka pindah secara permanen dari desa Mola, Mantigola dan La Manggau
dan membangun atau menyewa rumah di Pepela. Migrasi ini merupakan akibat dari perubahan
ekonomi, politik dan budaya dalam praktik penangkapan ikan hiu.
Pada akhir tahun 1994 terdapat 42 rumah masyarakat Bajo di Tanjung. Dari jumlah
tersebut, tiga tidak ditempati dan satu digunakan sebagai awarung(warung kecil). Selain
itu, ada tujuh rumah Bajo di Kampung Baru, dan lima di bagian utama Pepela. Secara
total, suku Bajo menempati 50 rumah di Pepela dengan jumlah penduduk sekitar 292
jiwa (134 dewasa dan 158 anak). Dari seluruh rumah tangga yang disurvei, mayoritas
orang Bajo yang tinggal di Pepela berasal dari Mola Selatan (28 rumah tangga), dengan
jumlah yang lebih sedikit berasal dari Mola Utara (8 rumah tangga), Mantigola (10
rumah tangga) dan La Manggau (2 rumah tangga). 10 Desa asal dua rumah tidak
diketahui. Sebagian besar keluarga yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah
tinggal di Pepela selama 1–3 tahun, dengan sebagian kecil telah tinggal di sana selama
4–5 tahun.
Pemukiman Bajo di Tanjung terdiri dari dua deret utama rumah yang menghadap ke
laut (Gambar 2-6). Rumah-rumah ini sangat mendasar dalam konstruksi, kebanyakan
dari mereka terangkat dari pasir dan terbuat dari panel rumbia. Beberapa bangunan
berjumlah sedikit lebih dari satu gubuk kamar. Ini mencerminkan fungsi sementara
yang mereka layani untuk orang Bajo. Beberapa rumah di Kampung Baru tidak
terangkat dari tanah dan berlantai tanah. Beberapa rumah Bajo di bagian utama desa
umumnya dibangun lebih baik dan terdiri dari rumah panggung kayu yang lebih besar.
10 Data ini hanya boleh dianggap sebagai perkiraan karena jumlah orang yang tinggal di rumah berubah dari hari
ke hari. Populasinya sangat berpindah-pindah, dan pada minggu berikutnya survei lebih banyak pria, wanita dan
anak-anak datang dari Mola dan Mantigola. Beberapa pemilik kapal sementara, kapten dan awak kapal tidur dan
makan di rumah anggota keluarga besar, sementara yang lain mungkin tinggal di rumah mereka sendiri.perahu
saat berada di Pepela di antara pelayaran mencari ikan.
28
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Bab 2: Sejarah Permukiman Bajo
Gambar 2-6: Pemukiman Bajo di Tanjung Pasir.
Pada saat air pasang, Tanjung sebagian dipisahkan dari bagian utama desa oleh
saluran yang membelah pantai berpasir dan berkelok-kelok di belakang pemukiman
Bajo. Kanal ini memungkinkan perahu kecil masuk ke belakang desa dan memberikan
perlindungan tambahan dari kondisi cuaca selama musim barat. Sebuah jalan setapak
kecil telah ditempatkan di atas saluran ini untuk memungkinkan akses pejalan kaki ke
Tanjung saat air pasang, tetapi ini pun berada di bawah air saat air pasang sangat
tinggi, dan kemudian perlu menempuh jarak pendek dengan kano untuk mencapai desa
utama. .
Tidak ada pasokan air tawar di Tanjung, dan ini merupakan masalah besar bagi suku
Bajo. Kantor setempatcamat(Kelurahan) ragu-ragu untuk memberikan layanan apa pun
karena tidak ada jaminan bahwa Bajo akan tinggal secara permanen. Alasannya, orang
Bajo bisa dengan mudah meninggalkan Pepela jika situasi melaut berubah.
Konsekuensinya, orang Bajo yang melapor ke lokaldesakantor hanya diberi status
pengunjung, dan hanya beberapa orang Bajo yang memutuskan untuk menjadi
penduduk tetap.
Perempuan dan anak-anak Bajo mengalami kesulitan hidup di Tanjung, dan meskipun
kondisinya mirip dengan yang ada di Kepulauan Tukang Besi, lingkungan umumnya buruk.
Tidak ada toilet, air tawar harus dibeli dari pedagang lokal, dan para perempuan biasanya
harus berjalan sekitar satu kilometer bahkan untuk mencuci pakaian. Hanya beberapa anak
yang bersekolah di sekolah dasar setempat. Para perempuan melaporkan bahwa ikan dan
hasil laut lebih langka di sekitar Pepela daripada di Kepulauan Tukang Besi, dan secara umum
ada kekurangan makanan di Pepela pada
29
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Perahu untuk Dibakar
berbeda dengan Mola dan Mantigola, terutama pada musim kemarau, yang merupakan
musim penangkapan ikan utama dan karenanya merupakan periode ketika populasinya
paling tinggi. Pasar terdekat berjarak 20 menit naik bus. Sayur-sayuran dijual oleh
masyarakat lokal Roti dari rumah ke rumah dan ikan hasil tangkapan lokal dijual langsung di
pantai. Seringkali ada persaingan di antara para wanita untuk membeli hasil tangkapan.
Selama musim timur, daging hiu kering dan ikan karang kering yang dibawa kembali dari
perjalanan memancing di Laut Timor menjadi makanan pokok orang Bajo (dan Pepelan
setempat).
30
Konten ini diunduh dari
182.255.0.242 pada Rab, 03 Mei 2023 03:48:07 +00:00
Semua penggunaan tunduk pada https://about.jstor.org/terms
Anda mungkin juga menyukai
- Asal Usul Bahasa MelayUDokumen21 halamanAsal Usul Bahasa MelayUSolehah RoslanBelum ada peringkat
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Intro Ass DR JunaDokumen3 halamanIntro Ass DR JunaHaniffah Fathini IIBelum ada peringkat
- Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila-K3Dokumen17 halamanProyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila-K3aurumsalsabila98Belum ada peringkat
- Sulawesi SelatanDokumen7 halamanSulawesi SelatanAbyan FarhandhityaBelum ada peringkat
- SUKU Dan BUDAYA DI SULAWESIDokumen31 halamanSUKU Dan BUDAYA DI SULAWESIMega Fitria CarnosBelum ada peringkat
- Austronesia Awal Di IndonesiaDokumen16 halamanAustronesia Awal Di IndonesiaSimanjuntakt50% (2)
- Pembahasan Pengertian Budaya, Makna Adat Dan Literature GayoDokumen11 halamanPembahasan Pengertian Budaya, Makna Adat Dan Literature GayoAl BurujBelum ada peringkat
- Aspek Biologi Ikan BaungDokumen23 halamanAspek Biologi Ikan BaungKaisar Lamunan100% (3)
- Mengenal Pusat Kebudayaan Maritim Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Buton, Suku Mandar Di Segitiga Emas NusantaraDokumen21 halamanMengenal Pusat Kebudayaan Maritim Suku Bajo, Suku Bugis, Suku Buton, Suku Mandar Di Segitiga Emas NusantarahasanBelum ada peringkat
- Kelompok-Kelompok Etnik (Suku Bangsa) Sebagai Cikal Bakal Masyarakat Maritim Di IndonesiaDokumen5 halamanKelompok-Kelompok Etnik (Suku Bangsa) Sebagai Cikal Bakal Masyarakat Maritim Di IndonesiaMuthiaBelum ada peringkat
- Revisi Makalah Asia Tenggara 2Dokumen12 halamanRevisi Makalah Asia Tenggara 2ppanca238Belum ada peringkat
- Bangsa AustronesiaDokumen7 halamanBangsa AustronesiaFemi TaniaBelum ada peringkat
- Aspek Biologi Ikan BaungDokumen23 halamanAspek Biologi Ikan BaungAhmad ZaynieBelum ada peringkat
- BellwoodDokumen4 halamanBellwoodstrawartBelum ada peringkat
- WSBM 9Dokumen5 halamanWSBM 9Masrinda OktaviaBelum ada peringkat
- The Biodiversity of Flora in IndonesiaDokumen14 halamanThe Biodiversity of Flora in IndonesiahebriantiBelum ada peringkat
- Konsep Sama-BajauDokumen6 halamanKonsep Sama-BajauNazeka KanasidenaBelum ada peringkat
- Tokwan Part 2Dokumen104 halamanTokwan Part 2Firdaus AbdullahBelum ada peringkat
- Keberagaman Suku Bangsa Di Pulau SumateraDokumen24 halamanKeberagaman Suku Bangsa Di Pulau SumateraIsma CahyaBelum ada peringkat
- Klamer 2019 Langand Ling Compass Sejarahdankeanekaragamanbahasa Austronesiadi IndonesiaDokumen36 halamanKlamer 2019 Langand Ling Compass Sejarahdankeanekaragamanbahasa Austronesiadi IndonesiaRio F 47Belum ada peringkat
- Sofwan Awal-PendaratanDokumen13 halamanSofwan Awal-PendaratanNuur Aini RazaliBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen16 halaman1 PBNi Putu Setita Praena WidiantiniBelum ada peringkat
- Disusun Oleh Kelompok 1Dokumen17 halamanDisusun Oleh Kelompok 1Rasyid HasibuanBelum ada peringkat
- Asal Usul Bahasa MelayuDokumen78 halamanAsal Usul Bahasa Melayuibuk bagasBelum ada peringkat
- Assignment BMDokumen20 halamanAssignment BMtirasyada100% (1)
- Kebudayaan BugisDokumen13 halamanKebudayaan BugisydeargodBelum ada peringkat
- Pengembaraan Pelayaran Nelayan, Rutedantempat TujuanDokumen5 halamanPengembaraan Pelayaran Nelayan, Rutedantempat TujuanRosita AzzahraBelum ada peringkat
- Makalah FLORA DAN FAUNADokumen22 halamanMakalah FLORA DAN FAUNANur RahmanBelum ada peringkat
- Makalah Suku BugisDokumen11 halamanMakalah Suku BugisNadia ayuBelum ada peringkat
- Flores Dalam Lintas Budaya Prasejarah Di Indonesia TimurDokumen130 halamanFlores Dalam Lintas Budaya Prasejarah Di Indonesia TimurAlexander Ara KianBelum ada peringkat
- PepelingDokumen36 halamanPepelingHerman LukmanBelum ada peringkat
- Migrasi Austronesia Dan Implikasinya TerDokumen11 halamanMigrasi Austronesia Dan Implikasinya Tersela febriyantiBelum ada peringkat
- Pengantar Morfologi Bahasa BaweanDokumen96 halamanPengantar Morfologi Bahasa BaweanaurahidayatuliestariBelum ada peringkat
- 873 51 1 SMDokumen12 halaman873 51 1 SMmaulanahasan28Belum ada peringkat
- Makalah Perilaku Satwa Liar-Muh Hariyanto H-A0218306Dokumen11 halamanMakalah Perilaku Satwa Liar-Muh Hariyanto H-A0218306Agus SalimBelum ada peringkat
- MAKALAH Kerajaan BugisDokumen14 halamanMAKALAH Kerajaan BugisMochamad Dudy WijayaBelum ada peringkat
- All MakalahDokumen5 halamanAll MakalahMaskia KatmasBelum ada peringkat
- KKP BM1Dokumen32 halamanKKP BM1Na Wanie NaBelum ada peringkat
- Rumpun Bahasa AustronesiaDokumen7 halamanRumpun Bahasa AustronesiaOdyman MasyhuriBelum ada peringkat
- Jurnal Antropologi PapuaDokumen46 halamanJurnal Antropologi PapuaShofiyudin AlbadriBelum ada peringkat
- Tugas Akhir MK Pak DLM Masyarakat MajemukDokumen15 halamanTugas Akhir MK Pak DLM Masyarakat Majemukhermawati SitepuBelum ada peringkat
- Kelompok2 Etnik Suku Bangsa PDFDokumen5 halamanKelompok2 Etnik Suku Bangsa PDFFitriahBelum ada peringkat
- Makalah Muhammad Rasyid Hidayat 23311058Dokumen10 halamanMakalah Muhammad Rasyid Hidayat 23311058Paskel GintingBelum ada peringkat
- Kebudayaan Suku GayoDokumen16 halamanKebudayaan Suku GayoHafizus SabriBelum ada peringkat
- GEOGRAFIDokumen8 halamanGEOGRAFIKarenhapukh yedija TaraBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen14 halaman1 PBgorontaloveBelum ada peringkat
- 7 Unsur KebudayaanDokumen12 halaman7 Unsur KebudayaanBidenk Aza75% (4)
- MAKALAHDokumen11 halamanMAKALAHindryani wabangBelum ada peringkat
- Masyarakat Kesenian Sulawesi: Disusun OlehDokumen18 halamanMasyarakat Kesenian Sulawesi: Disusun OlehRizal RenaldyBelum ada peringkat
- Presentasi Kewarganegaraan Bab 8Dokumen24 halamanPresentasi Kewarganegaraan Bab 8Taif AzfarBelum ada peringkat
- Makalah Geografi Budaya: Geografi Budaya IndonesiaDokumen10 halamanMakalah Geografi Budaya: Geografi Budaya Indonesianisaririz67% (3)
- FaunaIndonesiaJuni2016 CryptoblepharusDokumen5 halamanFaunaIndonesiaJuni2016 Cryptoblepharusdaffaxtkr3Belum ada peringkat
- CITRADokumen9 halamanCITRACitra PutBelum ada peringkat
- Flora FaunaDokumen25 halamanFlora FaunaDewi LarasatiBelum ada peringkat
- Budaya BlajaDokumen27 halamanBudaya BlajaIkhwan SyukriBelum ada peringkat
- Suku GayoDokumen15 halamanSuku GayoI'm just normalBelum ada peringkat
- Kamus Praktis Jepang-Indonesia-BaliDari EverandKamus Praktis Jepang-Indonesia-BaliPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (3)