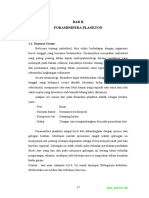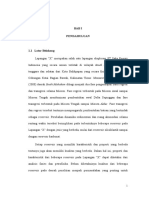Lap 3 Mikropaleontologi Lia Marnatal BR Sianturi
Lap 3 Mikropaleontologi Lia Marnatal BR Sianturi
Diunggah oleh
Johan Albert Sembiring0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2 tayangan9 halamanJudul Asli
Lap 3 Mikropaleontologi Lia Marnatal Br Sianturi
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2 tayangan9 halamanLap 3 Mikropaleontologi Lia Marnatal BR Sianturi
Lap 3 Mikropaleontologi Lia Marnatal BR Sianturi
Diunggah oleh
Johan Albert SembiringHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 9
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI
FORAMINIFERA PLANKTONIK
(GLOBOROTALIA, HANTKENINA, DAN
CRIBOHANTKENINA)
Disusun Oleh:
LIA MARNATAL BR SIANTURI
F1D219054
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
JURUSAN TEKNIK KEBUMIAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mikropaleontologi adalah cabang dari ilmu pada ilmu paleontologi yang
khusus mempelajari semua sisa-sisa yang berukuran kecil sehingga pada
pelaksanaannya harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Umumnya
fosil ukurannya lebih dari 5 mm namun ada juga yang berukuran sampai 19 mm
seperti hewan foraminifera, embrio dari fosil-fosil makro serta bagian-bagian
tubuh dari fosil makro mengamatinya harus dengan menggunakan alat bantu
tambahan berupa mikroskop serta sayatan tipis dari fosil-fosil yang akan diamati.
Secara definisi foraminifera adalah organisme bersel tunggal yang hidup
secara aquatik, mempunyai satu atau lebih kamar-kamar yang terpisah satu
dengan yang lainnya oleh sekat-sekat (septa) yang ditembusi oleh lubang-lubang
halus (foramen). Mikrofosil dapat digunakan dalam menentukan kondisi geologi
suatu daerah serta dapat menentukan umur batuan suatu daerah projek.
Fosil adalah sisa kehidupan purba yang terawetkan secara alamiah dan
terekam pada bahan-bahan dari kerak bumi. Fosil berguna mengenal kehidupan
masa lampau, mempelajari ilmu tentang fosil dan hubungannya tentang
penentuan umur suatu lingkungan yang ada di sekitarnya terlebih dahulu kita
harus mengetahui bagaimana proses terbentuknya fosil tersebut, unsur apa yang
terkandung di dalam fosil tersebut dan dimana lingkungan hidup dari fosil itu
sebelumnya.
Ada fosil yang dilakukan megaskopi, yang artinya penelitian dilakukan
dengan mata telanjang atau dengan pertolongan lensa pembesar. Oleh karena itu
dalam laporan ini akan membahas fosil yang tentunya untuk memahami tentang
mikrofosil pada filum foraminifera dengan genus Globorotalia, Hantkenina, dan
Cribohantkenina.
1.2 Tujuan
1. Mengetahui ciri-ciri Globorotalia, Hantkenina, dan Cribohantkenina
2. Mengetahui perbedaan Globorotalia (T) dengan Globorotalia (G)
3. Mengetahui perbedaan Hantkenina dengan Cribohantkenina
1.3 Alat dan Bahan
1. Alat tulis lengkap
2. Clipboard
3. Modul mikropaleontologi
4. Laptop
5. HVS
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 1
Planktonik
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Berdasarkan asal katanya, fosil berasal dari bahasa latin yaitu “fossa” yang
berarti "galian", adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi
batu atau mineral. Untuk menjadi fosil, sisa-sisa hewan atau tanaman ini harus
segera tertutup sedimen. Hewan atau tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi
ternyata masih ada disebut fosil hidup dan ilmu yang mempelajari fosil adalah
paleontologi. Dalam geologi, tujuan mempelajari fosil adalah untuk mempelajari
perkembangan kehidupan yang pernah ada di muka bumi sepanjang sejarah
bumi, mengetahui kondisi geografi dan iklim pada zaman saat fosil tersebut
hidup, menentukan umur relatif batuan yang terdapat di alam didasarkan atas
kandungan fosilnya, untuk menentukan lingkungan pengendapan batuan
didasarkan atas sifat dan ekologi kehidupan fosil yang dikandung dalam batuan
tersebut, korelasi antar batuan batuan yang terdapat di alam (biostratigrafi) yaitu
dengan dasar kandungan fosil yang sejenis/seumur (Noor, 2009).
Foraminifera merupakan makhluk hidup yang secara taksonomi ia berada di
bawah salah satu Kingdom Protista, Filum Sarcomastigophora, Subfilum
Sarcodina, Superkelas Rhizopoda dan Kelas Granuloreticulosea serta Ordo
Foraminiferida. Foraminifera berdasarkan cara hidupnya dibagi menjadi dua
kelompok, yaitu yang pertama foraminifera yang hidup di dasar laut (benthonic
foraminifera) dan yang kedua foraminifera yang hidupnya mengambang
mengikuti arus (planktonic foraminifera). Foraminifera bentonik pertama mulai
hidup sejak Zaman Kambrium sampai saat ini, sedangkan foraminifera
planktonik hidup dari Zaman Jura sampai saat ini. Foraminifer sekalipun tetap
merupakan protozoa bersel satu yang merupakan suatu kelompok organisme-
organisme sangat komplek (Culver Dan Buzas, 1983).
Teluk Ambon bagian dalam memiliki bentuk membulat. Kegiatan geologi
berupa plutonik dan vulkanik yang diikuti oleh naiknya magma granetik pada
fase pengangkatan geoantiklin di teluk tersebut masih aktif sehingga dapat
mempengaruhi pembentukan sedimen serta kondisi foraminifera di Teluk Ambon.
Lapisan lumpur hanya didapatkan pada bagian dalam teluk yaitu pada stasiun
44 dan 47 (kedalaman 20 – 30 m) dengan kadar lumpur 75% sampai 90%.
Menurut Suwartana (1986), Teluk Ambon bagian dalam memiliki bentuk
membulat. Morfologi seperti ini dapat berpengaruh terhadap kondisi daerah
tersebut. Massa air yang berasal dari Teluk Ambon bagian luar akan menyebar
ke segala penjuru teluk dalam dan semakin jauh ke tengah energi yang
ditimbulkan semakin melemah. Gelombang yang ditimbulkan oleh angin jarang
terjadi di tempat ini, kecuali di musim timur dengan frekuensi rendah. Kondisi
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 2
Planktonik
oseanografi semacam ini mengakibatkan daerah Teluk Ambon bagian dalam
relatif tenang sehingga mudah terjadi proses sedimentasi (Stoddart and Steers,
1977; Kennet, l982). Rata-rata kelimpahan foraminifera maupun jumlah spesies
yang ditemukan pada bagian dalam teluk relatif lebih rendah dibandingkan pada
bagian luar teluk. Kondisi substrat dasar yang didominasi oleh lumpur tersebut
kurang sesuai untuk kehidupan foraminifera.
Hasil identifikasi foraminifera dari 50 sampel sedimen yang diambil dari
Teluk ambon pada tahun 2007 menunjukkan terdapat 29 sampel mengandung
foraminifera. Foraminifera pada sedimen permukaan di Teluk Ambon mencapai
86 spesies yang terdiri dari 61 spesies bentonik dan 25 spesies planktonik.
Foraminifera spesies bentonik yang mendominasi sedimen permukaan perairan
Teluk Ambon adalah Amphistegina lessonii, Ammonia beccarii, Elphidium
craticulatum, Operculina ammonoides dan Quinqueloculina parkery. Foraminifera
planktonik yang sering dijumpai adalah Globorotalia tumida, Globoquadrina
pseudofoliata, Globigerinoides pseudofoliata, Globigerinoides cyclostomus dan
Pulleniatina finalis. Pada umumnya foraminifera spesies tersebut ditemukan
melimpah pada sedimen pasir, sedangkan pada sedimen lumpur tidak ditemukan
baik foraminifera bentonik maupun planktonik (Natsir, 2010).
Berdasarkan analisis spesies foraminifera plankton, daerah penelitian, pada
bor inti MD 52 dan MD 55 ini termasuk ke dalam Zona Globorotalia
truncatulinoides- truncatulinoides dari Blow (1969). Di lokasi MD 52, zona ini
dapat dibagi lagi ke dalam dua subzona, yakni Subzona Globorotalia crassaformis
hessi dan Globigerinella calida calida. Di lokasi MD 55, zona tersebut dapat dibagi
lagi ke dalam tiga subzona yaitu Subzona Globorotalia crassaformis hessi,
Globigerinella calida calida dan Beella digitata. Pada kedalaman 39 m, mulai
dijumpai Globorotalia truncatulinoides dan Globorotalia cf. fimbriata, meskipun
pada kedalaman tersebut bukan merupakan pemunculan awal dari kedua
spesies ini, karena Globigerinoides cyclostomus yang sama-sama muncul pada
kala Plistosen sudah dijumpai pada dasar bor inti yang lebih dalam lagi. Pada
kedalaman ini, kedua spesies tersebut berasosiasi dengan spesies-spesies yang
sama dengan yang dijumpai pada dasar inti bor. Spesies Globorotalia crassaformis
hessi berakhir pada kedalaman 15,00 m dan pemunculan akhir dari Globorotalia
flexuosa adalah pada kedalaman 3 m. Dia membagi N.23 ke dalam dua bagian
seperti subzona Globigerina bermudezi di bagian bawah, dan subzona Globorotalia
fimbriata di bagian atas, sedangkan Globigerinella calida calida ditempatkan di
bagian paling atas dari N.22 (bagian paling atas dari Plistosen). Tetapi,
Chaproniere (1991) membagi Zona N. 23 ke dalam tiga subzona, yakni, subzona
Globigerinella calida calida di bagian paling bawah, subzona Pulleniatina finalis di
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 3
Planktonik
bagian tengah, dan subzona Bolliella adamsi di bagian paling atas dari N. 23
(bagian paling atas dari Holosen). Tetapi bagian paling atas dari N.22 dinamakan
subzona Globigerinella calida praecalida. (Adisaputra dan Yuniarto, 2013).
Berdasarkan analisis dari spesies foraminifera plankton, kedua bor inti (MD
52 dan MD 55) termasuk ke dalam Zona Globorotalia truncatulinoides dari zonasi
Blow (1969) Zona Globorotalia truncatulinoides pada bor inti MD 52 bisa dibagi ke
dalam 2 subzona, yakni Subzona Globorotalia crassaformis crassaformis hessi dan
Subzona Globigerinella calida calida. Beda halnya dengan pada bor inti MD 55
zona tersebut bisa dibagi ke dalam 3 subzona, yakni, Subzona Globorotalia
crassaformis hessi, Globigerinella calida calida dan Beella digitata. Spesies
Globigerinella calida calida ini di daerah penelitian berada atau muncul pertama
kali di dalam Plistosen Akhir atau di bagian paling atas dari N.22, karena di kedua
sumur bor daerah penelitian sudah berasosiasi dengan Globorotalia
truncatulinoides. Ke arah yang lebih dalam sedimen tersebut menebal pada umur
ini, demikian pula sedimen yang diendapkan pada umur yang lebih muda dari
Plistosen Akhir. Tetapi pada bagian bawahnya, sedimen yang tersingkap pada MD
52 lebih tebal dari pada pada MD 55 (Pandita dkk, 2010).
Berdasarkan pada analisis dari spesies foraminifera plankton, kedua bor inti
(MD 52 dan MD 55) daerah penelitian termasuk ke dalam Zona Globorotalia
truncatulinoides dari zonasi Blow (1969) Zona Globorotalia truncatulinoides pada
bor inti MD 52 bisa dibagi ke dalam 2 subzona, yakni Subzona Globorotalia
crassaformis crassaformis hessi dan Subzona Globigerinella calida calida. Beda
halnya dengan pada bor inti MD 55 zona tersebut bisa dibagi ke dalam 3 subzona,
yakni, Subzona Globorotalia crassaformis hessi, Globigerinella calida calida dan
Beella digitata. Spesies Globigerinella calida calida ini di daerah penelitian berada
atau muncul pertama kali di dalam Plistosen Akhir atau di bagian paling atas dari
N.22, karena di kedua sumur bor daerah penelitian sudah berasosiasi dengan
Globorotalia truncatulinoides. Ke arah yang lebih dalam sedimen tersebut menebal
pada umur ini, demikian pula sedimen yang diendapkan pada umur yang lebih
muda dari Plistosen Akhir. Tetapi pada bagian bawahnya, sedimen yang
tersingkap pada MD 52 lebih tebal dari pada pada MD 55 (Sanjoto, 2010).
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 4
Planktonik
3.2 Pembahasan
Pada praktikum kali ini membahas mikropaleontologi tentang foraminifera
planktonik. Foraminifera adalah organisme bersel tunggal yang mempunyai
cangkang atau test. Foraminifera ditemukan melimpah sebagai fosil, setidaknya
dalam kurun waktu ±540 juta tahun yang lalu. Foraminifera planktonik jumlah
genusnya sedikit, tetapi jumlah spesiesnya banyak. Jumlah genusnya berjumlah
13 genus.
Ciri-ciri dari Grobotalia adalah morfologi dengan test hyaline, bentuk test
biconvex, bentuk kamar sub-globular, aperture nya memanjang umbilicus ke
pinggir test. Perbedaan antara Hantkenina dengan Cribohantkenina adalah
terdapat pada kamarnya, kamar dari Hantkenina memiliki bentuk kamar yang
tabular spine dan tiap kamarnya terdapat spine-spine yang panjang, sedangkan
Cribohantkenina memiliki kamar akhir yang sangat gemuk. Cara menghitung
putaran pada foraminifera planktonic adalah dengan melihat dari arah
putarannya, searah jarum jam atau pun sebaliknya. Kemudian dilihat dari kamar
terkecil hingga yang terbesar lalu ditarik garis yang memotong kamar satu, dua,
hingga terakhir, kemudian hitung jumlah putarannya.
Genus foraminifera Planktonik yang dibahas yaitu genus Globorotalia,
Hantkenina, dan Cribohantkenina. Genus Globorotalia dengan spesies
Globorotalia siakensis (T), dengan susunan kamar trochospiral, bentuk test-nya
sub-globular, bentuk kamarnya Globular. Suture ventral dan suture dorsal nya
tertekan kuat dengan komposisi Gamping Hyalin. Jumlah kamar ventral
berjumlah 5 kamar dan jumlah kamar dorsal berjumlah 6 kamar. Aperture
primary nya, yaitu P. A. I Umbilicus, hiasan pada permukaan test berbentuk
punctate. Genus Globorotalia dengan spesies Globorotalia tosaensis (G), dengan
susunan kamar trochospiral rendah, bentuk test-nya biconvex, bentuk kamarnya
Angular rhomboid. Suture ventral dan suture dorsal nya tertekan kuat dengan
komposisi Gamping Hyalin. Jumlah kamar ventral berjumlah 6 kamar dan
jumlah kamar dorsal berjumlah 7 kamar. Aperture primary nya, yaitu P. A. I
Umbilicus, hiasan pada aperture berbentuk punctate, hiasan pada peri-peri
berbentuk keel. Genus Globorotalia dengan spesies Globorotalia tosaensis, dengan
susunan kamar trochospiral, bentuk test-nya biumbilicate, bentuk kamarnya
Globular. Suture ventral dan suture dorsal nya tertekan kuat dengan komposisi
Gamping Hyalin. Jumlah kamar ventral berjumlah 13 kamar dan jumlah kamar
dorsal berjumlah 5 kamar. Aperture primary nya, yaitu P. A. I Umbilicus, hiasan
pada permukaan test berbentuk punctate, pada aperture berbentuk bridge. Lagi-
lagi genus Globorotalia dengan spesies Globorotalia archeomenardii (G), dengan
susunan kamar trochospiral, bentuk test-nya biconvex, bentuk kamarnya
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 5
Planktonik
Angular rhomboid. Suture ventral tertekan kuat dan suture dorsal nya tertekan
lemah dengan komposisi Gamping Hyalin. Jumlah kamar ventral berjumlah 5
kamar dan jumlah kamar dorsal berjumlah 10 kamar. Aperture primary nya,
yaitu Interiomarginal umbilical extra, hiasan pada permukaan test berbentuk
smooth, pada suture bridge dan pada umbilicus deeply umbilicus.
Genus Hantkenina dengan spesies Hantkenina dumblei, dengan susunan
kamar planispiral, bentuk tes-nya biumbilicate, bentuk kamarnya Tubulospinate.
Suture ventral tertekan kuat dan suture dorsal nya tertekan sedang dengan
komposisi Gamping Hyalin. Jumlah kamar ventral berjumlah 5 kamar dan
jumlah kamar dorsal berjumlah 5 kamar. Aperture primary nya, yaitu P. A. I
Umbilicus, hiasan pada permukaan test berbentuk punctate, pada aperture nya
berbentuk lip/rim, dan peri-peri berbentuk spine. Genus Hantkenina dengan
spesies Hantkenina alabamensis, dengan susunan kamar planispiral, bentuk tes-
nya biumbilicate, bentuk kamarnya Tubulospinate. Suture ventral tertekan
lemah dan suture dorsal nya tertekan kuat dengan komposisi Gamping Hyalin.
Jumlah kamar ventral berjumlah 4 kamar dan jumlah kamar dorsal berjumlah 5
kamar. Aperture primary nya, yaitu Interiomarginal umbilical extra, hiasan pada
peri-peri berbentuk spine. Genus Hantkenina dengan spesies Hantkenina
danvilensis, dengan susunan kamar planispiral, bentuk tes-nya biumbilicate,
bentuk kamarnya Tubulospinate. Suture ventral tertekan lemah dan suture
dorsal nya tertekan lemah dengan komposisi Gamping Hyalin. Jumlah kamar
ventral berjumlah 5 kamar dan jumlah kamar dorsal berjumlah 6 kamar.
Aperture primary nya, yaitu P. A. I Umbilicus, hiasan pada permukaan test
berbentuk punctate, pada aperture nya berbentuk lip/rim, dan peri-peri
berbentuk spine.
Yang terakhir genus Cribohantkenina dengan spesies Cribohantkenina
bermudezi, dengan susunan kamar planispiral, bentuk test-nya biumbilical,
bentuk kamarnya Tubulospinate. Suture ventral dan suture dorsal nya tertekan
lemah dengan komposisi Gamping Hyalin. Jumlah kamar ventral berjumlah 5
kamar dan jumlah kamar dorsal berjumlah 5 kamar. Aperture primary nya, yaitu
P. A. I Umbilicus dan aperture secondary nya Cribate, hiasan pada permukaan
test berbentuk punctate dan pada aperture berbentuk lip/rim.
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 6
Planktonik
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Ciri-ciri dari Globorotalia adalah memiliki morfologi dengan test Hyaline,
bentuk test biconvex, bentuk kamar sub-globular atau angular conical,
aperture memanjang dari umbilicus ke pinggir test, dan pinggir test ada
yang kecil da nada yang tidak. Ciri-ciri dari Hantkenina adalah Morfologi
bentuk test nya biubilicate, bentuk kamar tabular spinate dan susunan
kamar planispiral involute, tiap-tiap kamar terdapat spine-spine panjang.
Dan ciri-ciri Cribohantkenina adalah bentuk test biumbilicate, bentuk
kamar tabulate spinate, susunan kamar planispiral involute, dan kamar
akhir yang sangat gemuk dan mempunyai cribate.
2. Perbedaan dari Globorotalia (T) dengan Globorotalia (G), yaitu : Globorotalia
(T) mencakup seluruh Globorotalia yang tidak mempunyai keel, sedangkan
Globorotalia (G) mencakup seluruh Globorotalia yang mempunyai keel.
3. Perbedaan Hantkenina dengan Cribohantkenina, yaitu: terdapat pada
kamarnya, dimana kamar Hantkenina mempunyai bentuk kamar tabular
spine dan tiap kamarnya terdapat spine-spine yang panjang. Sedangkan
Cribohantkenina memiliki kamar akhir yang sangat gemuk.
4.2 Saran
Adapun saran pada praktikum kali ini yang dilakukan secara online,
sebaiknya praktikan lebih serius dan dapat masuk lebih tepat waktu pada room
zoom.
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 7
Planktonik
DAFTAR PUSTAKA
Adisaputra, M. K. dan H. Yuniarto. 2013. Biostratigrafi Foraminifera Kuarter Pada
Bor Inti Md 982152 Dan 982155 Dari Samudra Hindia. Jurnal Geologi
Kelautan. Vol 11(2):55-66.
Culver, S.J., And Buzas, M.A. 1983. Benthic foraminifera at the shelfbreak: North
American Atlantic and Gulf margins: in Stanley, D.J., and Moore, G.T., eds.,
The Shelfbreak: Critical Interface on Continental Margins.
Kennet, J.P. 1982. Marine geology. Prentice Hal, Inc. Englewood Cliffs, 822p.
Natsir, S. M. 2010. Kelimpahan Foraminifera Resen Pada Sedimen Permukaan Di
Teluk Ambon. E-Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Vol 2(1): 9-
18.
Noor, D. 2009. Pengantar Geologi. Bogor: CV. Graha Ilmu.
Pandita, H., S. Pambudi, dan Winarti. 2010. Kajian Biostratigrafi Dan Fasies
Formasi Sentolo di Daerah Guluhrejo dan Ngaran Kabupaten Bantul
Untuk Mengidentifikasi Keberadaan Sesar Progo. Oral Presentation.
Sanjoto, S. 2010. Zonasi Foraminifera Planktonik Daerah Gunung Kinjeng dan
Gunung Gede Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Daerah
Istimewa Yogyakarta. Jurnal Teknologi Technoscientia. Vol 2(2):239-247.
Stoddart, D.R. dan J.A. Streers. 1977. The natural and origin of coral reef islands.
Dalam “Biology and Geology of Coral Reef'” (O. Ajones dan R. Endean,
eds). Academic Press, New York, San Francisco, London: 60–102.
Laporan Praktikum Mikropaleontologi Foraminifera 8
Planktonik
Anda mungkin juga menyukai
- Borang PaleontologiDokumen24 halamanBorang PaleontologiKevin TjoengBelum ada peringkat
- Laporan Paleontologi Acara 1Dokumen16 halamanLaporan Paleontologi Acara 1Angel TottongBelum ada peringkat
- Acara 1 Mikropaleotologi Anggit Kurnia Universitas HasanuddinDokumen22 halamanAcara 1 Mikropaleotologi Anggit Kurnia Universitas HasanuddinAnggit KurniaBelum ada peringkat
- Mikropal Acara1Dokumen19 halamanMikropal Acara1Sunrise HomeBelum ada peringkat
- Tugas 1 Orbulina UniversaDokumen4 halamanTugas 1 Orbulina UniversaGeraldinoKrisnaAkbarBelum ada peringkat
- Laporan Akhir MikropalDokumen48 halamanLaporan Akhir Mikropalfuad ivanBelum ada peringkat
- MIKROPALEONTOLOGIDokumen54 halamanMIKROPALEONTOLOGIresty2pm100% (1)
- Buku Panduan Praktikum Mikro-2012 Ok Edit FinishDokumen58 halamanBuku Panduan Praktikum Mikro-2012 Ok Edit FinishchaterineBelum ada peringkat
- Artikel Prosedur Preparasi Foram KecilDokumen4 halamanArtikel Prosedur Preparasi Foram KecilarsarcanumBelum ada peringkat
- Laporan Acara 2 Paleontologi. (Repaired)Dokumen31 halamanLaporan Acara 2 Paleontologi. (Repaired)Dicky AndriantoBelum ada peringkat
- Pengantar Paleontologi - 2013Dokumen199 halamanPengantar Paleontologi - 2013Qoddriyyah Andela SaputriBelum ada peringkat
- KriptoDokumen11 halamanKriptoMichelle Azista Nabila CasandraBelum ada peringkat
- Lampiran Mikropal Acara 3 Preparat BentonikDokumen18 halamanLampiran Mikropal Acara 3 Preparat BentonikNurafni AinunBelum ada peringkat
- Foraminifera PlanktonDokumen16 halamanForaminifera PlanktonHeriober Taruk AlloBelum ada peringkat
- Filum BrachiopodaDokumen6 halamanFilum Brachiopodafitri setiawatiBelum ada peringkat
- ForaminiferaDokumen3 halamanForaminiferaHananiAdiWiraBelum ada peringkat
- Batas KonvergenDokumen4 halamanBatas KonvergenAgus TokBelum ada peringkat
- Teori Dasar BiostratigrafiDokumen15 halamanTeori Dasar Biostratigrafilindamahadita100% (1)
- Foraminifera Bentos BesarDokumen4 halamanForaminifera Bentos BesarVickiNurGihantoroBelum ada peringkat
- Paleontologi - Balanus ConcavusDokumen12 halamanPaleontologi - Balanus ConcavusDevito PradiptaBelum ada peringkat
- BiostratigrafiDokumen18 halamanBiostratigrafiBerliana AyuBelum ada peringkat
- Pulleniatina Obliquiloculata-Kelompok 2Dokumen1 halamanPulleniatina Obliquiloculata-Kelompok 2andiBelum ada peringkat
- Buku Panduan Pemetaan TopografiDokumen25 halamanBuku Panduan Pemetaan Topografisuwono radukBelum ada peringkat
- Ekologi ForaminiferaDokumen4 halamanEkologi ForaminiferaMuhammad Lukman BaihaqiBelum ada peringkat
- Zonasi Postuma, 1971 (Kelompok 4)Dokumen15 halamanZonasi Postuma, 1971 (Kelompok 4)Ryan AvirsaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Mikropal Acara 2Dokumen17 halamanLaporan Praktikum Mikropal Acara 2agung nur ihsanBelum ada peringkat
- Fosil Sebagai Indikator Lingkungan PengendapanDokumen2 halamanFosil Sebagai Indikator Lingkungan Pengendapanvandarmawann100% (1)
- 8PRAKTIKUM PETROGRAFI, PiroklastikDokumen14 halaman8PRAKTIKUM PETROGRAFI, PiroklastikGorbyansyah HarahapBelum ada peringkat
- Klasifikasi Huruf Van Der Vlerk Dan Umbgrove (Dokumen9 halamanKlasifikasi Huruf Van Der Vlerk Dan Umbgrove (ghifarisyahfriBelum ada peringkat
- Acara 5 Penampang Stratigrafi Dan Analisis ProfilDokumen26 halamanAcara 5 Penampang Stratigrafi Dan Analisis ProfilgaizkaBelum ada peringkat
- Range Hidup Dan Kelebihan Kekurangan NanofosilDokumen3 halamanRange Hidup Dan Kelebihan Kekurangan NanofosilHans So Purba0% (1)
- FosilDokumen3 halamanFosilMuhammad Lukman BaihaqiBelum ada peringkat
- Ammonite Sebagai Fosil Index Pada Zaman CretaceousDokumen7 halamanAmmonite Sebagai Fosil Index Pada Zaman CretaceousRama Diyan LesmanaBelum ada peringkat
- MIKROPALEONTOLOGI Untuk GeologiDokumen12 halamanMIKROPALEONTOLOGI Untuk GeologidafieldBelum ada peringkat
- Foraminifera PlanktonDokumen24 halamanForaminifera PlanktonGABelum ada peringkat
- Acara 5 Filum BrachiopodaDokumen14 halamanAcara 5 Filum Brachiopodamuhammad sofyanBelum ada peringkat
- ZOINDokumen15 halamanZOINAprilia Ramadayani YanitBelum ada peringkat
- Bab 3Dokumen10 halamanBab 3Sabar Itu AgusBelum ada peringkat
- Laporan Geologi Paleontologi Sangiran PDFDokumen67 halamanLaporan Geologi Paleontologi Sangiran PDFAngga PradiptaBelum ada peringkat
- MikropaleontologiDokumen25 halamanMikropaleontologiYusuf AnugerahBelum ada peringkat
- Tety Laporan Acara 8 Protozoa Dan BryozoaDokumen26 halamanTety Laporan Acara 8 Protozoa Dan BryozoaTety NurbaetyBelum ada peringkat
- Proses PemfosilanDokumen36 halamanProses PemfosilanAulia Tribhuwana Kusuma Wardhani50% (2)
- Pal Acara 4 PembahasanDokumen14 halamanPal Acara 4 PembahasanSarni Jhe Sarni JheBelum ada peringkat
- Resume Deskripsi MakropaleontologiDokumen23 halamanResume Deskripsi MakropaleontologiFaisal SalmanBelum ada peringkat
- Metode Seismik Dan GravitasiDokumen17 halamanMetode Seismik Dan GravitasiRizqi NarendraBelum ada peringkat
- Micropal Foram Planktonik 13-16Dokumen6 halamanMicropal Foram Planktonik 13-16Putri AlikaBelum ada peringkat
- Album ForaminiferaDokumen21 halamanAlbum ForaminiferaGalung TumanggorBelum ada peringkat
- Lembar Deskripsi Makropaleontologi - Pelecypoda 2Dokumen1 halamanLembar Deskripsi Makropaleontologi - Pelecypoda 2Rifki Aufa FirmanBelum ada peringkat
- Foraminifera BentosDokumen8 halamanForaminifera BentosJulpines EndriBelum ada peringkat
- Analisis Mikropaleontologi Kelompok 2Dokumen3 halamanAnalisis Mikropaleontologi Kelompok 2raihanBelum ada peringkat
- Zonasi Foraminifera PlanktonikDokumen5 halamanZonasi Foraminifera PlanktonikMuhammad Ary IsmoehartoBelum ada peringkat
- Acara 5 BrachiopodaDokumen9 halamanAcara 5 BrachiopodaVinolia GranetsyaBelum ada peringkat
- LAPORAN Dimas Paleontos 2Dokumen28 halamanLAPORAN Dimas Paleontos 2Ahmad SyahputraBelum ada peringkat
- Louise - F1D219012 - Mikropaleontologi 2Dokumen7 halamanLouise - F1D219012 - Mikropaleontologi 2Agustinus SitanggangBelum ada peringkat
- L. Mikropal 3 Atep BenyDokumen13 halamanL. Mikropal 3 Atep BenyGian GustianaBelum ada peringkat
- Laporan Mikropaleontologi 1Dokumen9 halamanLaporan Mikropaleontologi 1Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- LP 3 Mikropal Ridhoo (2) RevisiiDokumen7 halamanLP 3 Mikropal Ridhoo (2) RevisiiRidho syah PahleviBelum ada peringkat
- Mikropal Acara PlanktonikDokumen32 halamanMikropal Acara PlanktonikNirwanaBelum ada peringkat
- Nur Afni Ainun Acara 2 MikropalDokumen43 halamanNur Afni Ainun Acara 2 MikropalniarBelum ada peringkat
- Mikropal 4Dokumen7 halamanMikropal 4shazkya AnnuraBelum ada peringkat
- Laporan Mikropaleontologi 2Dokumen7 halamanLaporan Mikropaleontologi 2Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Laporan 1 Mikropaleontologi - Septika Liza Alena - F1D219007Dokumen7 halamanLaporan 1 Mikropaleontologi - Septika Liza Alena - F1D219007Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- 2017 Ta GL 072001400025 Bab-2Dokumen13 halaman2017 Ta GL 072001400025 Bab-2Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- HW Petrologi 4&5Dokumen20 halamanHW Petrologi 4&5Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Fasies Dan Struktur SedimenDokumen42 halamanFasies Dan Struktur SedimenJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- HW Petrologi 3Dokumen20 halamanHW Petrologi 3Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Cover PpetrologiDokumen1 halamanCover PpetrologiJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Skripsi - Gita Putri Handayani (F1D218004)Dokumen83 halamanSkripsi - Gita Putri Handayani (F1D218004)Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Surat Tugas Permohonan Dispensasi Kuliah MektanDokumen3 halamanSurat Tugas Permohonan Dispensasi Kuliah MektanJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Skripsi GeofisikaDokumen102 halamanSkripsi GeofisikaJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Konsep PIT 2024Dokumen3 halamanKonsep PIT 2024Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- BAB II - Laporan Tesis Fatma 30000516410007 Magister Energi UNDIPDokumen17 halamanBAB II - Laporan Tesis Fatma 30000516410007 Magister Energi UNDIPJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- BAB I - Laporan Tesis Fatma 30000516410007 Magister Energi UNDIPDokumen9 halamanBAB I - Laporan Tesis Fatma 30000516410007 Magister Energi UNDIPJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- COVER - Laporan Tesis Fatma 30000516410007 Magister Energi UNDIPDokumen13 halamanCOVER - Laporan Tesis Fatma 30000516410007 Magister Energi UNDIPJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- 988 3452 1 PBDokumen7 halaman988 3452 1 PBJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen10 halamanBab I PendahuluanJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen7 halamanBab I PendahuluanJohan Albert SembiringBelum ada peringkat
- 8274 13622 1 SMDokumen7 halaman8274 13622 1 SMJohan Albert SembiringBelum ada peringkat