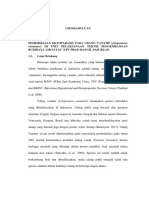Laporan Coraogy
Laporan Coraogy
Diunggah oleh
Sukron Alfi ERHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Laporan Coraogy
Laporan Coraogy
Diunggah oleh
Sukron Alfi ERHak Cipta:
Format Tersedia
LAPORAN RESMI PRAKTIKUM
KORALOGI
HISTOLOGI, MORFOLOGI, DAN ANATOMI KARANG
Sukron Alfi R.
26020112120006
PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
JURUSAN ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014
LEMBAR PENGESAHAN
NO KETERANGAN NILAI
1. Pendahuluan
2. Tinjauan Pustaka
3. Materi dan Metode
4. Hasil dan Pembahasan
5. Kesimpulan
6. Daftar Pustaka
JUMLAH
Semarang, 23 Mei 2014
Koordinator Asisten
Editta Hapsari Dianastuty
26020111140107
Praktikan
Sukron Alfi R.
26020112120006
Mengetahui,
Koordinator Dosen
Dr.Ir. Diah Permata Wijayanti, M.Sc
NIP. 19690116 199303 2 001
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat,
Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan
laporan ini
Harapan saya semoga laporan ini membantu menambah pengetahuan dan nilai bagi
para penyusun, sehingga saya dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan ini
sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Laporan ini saya akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang saya miliki
sangat kurang. Oleh kerena itu saya harapkan kepada para pembaca untuk
memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan
laporan ini.
Semarang, Mei 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
Bab I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan
1.3. Manfaat
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Biologi Karang
2.2. Karakteristik Morfologi Karang
2.3. Bentuk Pertumbuhan karang
2.4. Struktur koralit Karang
2.5. Histologi Karang
2.5.1. Jaringan Karang
2.5.2. Dekalsifikasi
2.5.3. Penghilangan Kadar Air (Dehidrasi)
2.5.4. Embedding
2.5.5. Perekatan Preparat (Mounting)
Bab III. MATERI DAN METODE
3.1. Waktu dan Tempat Praktikum
3.2. Materi Praktikum
3.2.1. Alat dan Bahan
3.2.2. Materi Praktikum Laboratorium
3.3. Metode Praktikum
3.3.1. Histologi Karang
3.3.2. Morfologi dan Anatomi Karang (Struktur Koralit Karang)
Bab IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
4.1.1. Histologi karang
4.1.2. Struktur Koralit Karang
4.2. Pembahasan
4.2.1. Histologi Karang
4.2.2. Morfologi dan Anatomi Karang (Struktur Koralit Karang)
Bab V. KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan
5.2. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Alat praktikum koralogi
Tabel 2. Bahan praktikum koralogi
Tabel 3. Hasil pengamatan histologi karang
Tabel 4. Hasil pengamatan struktur koralit karang
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Anatomi polip karang
Gambar 2. Lapisan tubuh karang
Gambar 3. Morfologi karang
Gambar 4. Karang branching
Gambar 5. Karang massive
Gambar 6. Karang encrusting
Gambar 7. Karang foliose
Gambar 8. Karang mushroom
Gambar 9. Karang submassive
Gambar 10. Karang milepora
Gambar 11. Karang Heliopora
Gambar 12. Acropora branching
Gambar 13. Acropora tabulate
Gambar 14. Acropora encrusting
Gambar 15. Acropora submassive
Gambar 16. Acropora digitata
Gambar 17. Tipe Koralit
Gambar 18. Histologi Karang H-416-2
Gambar 19. Histologi Karang H-45-3
Gambar 20. Histologi Karang H-49-1
Gambar 19. Phaceloid
Gambar 20. Cerioid
Gambar 21. Plocoid
Gambar 22. Falbello meandroid
Gambar 23. Meandroid
Gambar 24. Solitary
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Terumbu karang merupakan ekosistem perairan tropis yang begitu banyak perannya
bagi kehidupan diperairan. Ekosistem ini merupakan habitat berbagai biota laut untuk tumbuh
dan berkembang biak dalam kehidupan yang seimbang. Salah satu kekhasan dari terumbu
karang adalah produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi, pada ekosistem ini terdapat
sejumlah spesies biota yang sangat banyak. Pada umumnya terumbu karang hidudan
berkebang biak di daerah pantai dengan kedalaman tidak lebih dari 40 m dari permukaan air
laut.
Ekosistem ini memiliki banyak fungsi dan nilai ekonominya sangat penting terutama bagi sektor
perikanan. Namun ekosistem ini mudah sekali mengalami kerusakan karena letaknya yang
berdekatan dengan peisir, dimana paling mudah dipengaruhi oleh aktifitas manusia.
Terumbu karang tergolong ekosistem yang sangat produktif, secara taksonomi sangat beragam
pada perairan laut dangkal. Stuktur fisiknya terdiri dari kerangka kalsium karbonat yang
membentuk bahan padatan yang keras dalam jangka waktu yang relatif lama.
Pertumbuhan karang memerlukan kejernihan air ang tinggi dan ketersedian unsur hara yang
renah. Dengan peran Zoozantthellae maka hewan karang ini dapat tumbuh dan berkembang
dengan baik. Suhu kehidupannya berada pada batas antara 16 sampai 34 derajat Celcius,
kondisi ini mencerminkan kehidupan pada daerah tropis dan sub tropis.Dari pernyataan-
pernyataan diatas menurut para ahli bahwa terumbu karang merupakan ekosistem
yang sangat penting di lautan. Untuk itu perlu dipelajari atau dikaji lagi ilmu-ilmu yang
membahas mengenai terumbu karang. Ilmu yang mengkaji tentang terumbu karang dan
sekitarnya dinamakan koralogi. Ilmu koralogi ini penting agar kita dapat mengetahui
seluk-beluk mengenai terumbu karang. Dengan kita mengetahui seluk-beluk terumbu
karang maka kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menjaga
kelestarian terumbu karang.
Ekosistem terumbu karang tersusun atas beberapa karang dan biota-biota lain
yang hidup di dalamnya. Karang adalah binatang yang mempunyai sengat atau lebih
dikenal sebagai cnida (cnida=jelata) yang dapat menghasilkan kerangka kapur didalam
jaringan tubuhnya (Suharsono, 1996). Menurut Nybakken (1992) Karang hidup
berkoloni atau sendiri, tetapi hampir semua karang hermatipik hidup berkoloni dengan
berbagai individu hewan karang atau polyp.
1.2 Tujuan
Tujuan dari praktikum ini adalah diantaranya sebagai berikut :
Mengenali jenis-jenis karang keras (scleractinia)
Mampu menerapkan kunci identifikasi karang keras melalui bentuk koloni (life
form) dan struktur koloni
1.3 Manfaat
Manfaat dari praktikum koralogi ini diantaranya sebagai berikut :
Lebih mengetahui jenis jenis karang keras
Lebih mengetahui bentuk koloni dan struktur koloni karang
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Biologi Karang
Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang dibentuk dari endapan padat
kalsium karbonat (CaCO
3
), yang dihasilkan oleh karang dengan sedikit tambahan dari
alga berkapur (calcareous algae) dan organisme lainnya yang mensekresikan kalsium
karbonat (Nybakken 1997). Menurut Odum (1971) terumbu karang sebagai bagian
ekosistem yang dibangun oleh sejumlah biota, baik hewan maupun tumbuhan secara
terus menerus mengikat ion kalsium dan karbonat dari air laut yang menghasilkan
rangka kapur yang selanjutnya membentuk terumbu.
Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang agak dangkal,
seperti paparan benua dan gugusan pulau-pulau di perairan tropis. Untuk mencapai
pertumbuhan maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan
suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar dan sirkulasi air yang
lancar serta terhindar dari proses sedimentasi. Ekosistem terumbu karang memiliki
kemampuan yang baik dalam memperbaiki bagian yang rusak, bila karakteristik habitat
dari berbagai macam formasi terumbu karang dan faktor lingkungan yang
mempengaruhinya terpelihara dengan baik. Seperti ekosistem lainnya, terumbu karang
tidak memerlukan campur tangan atau manipulasi langsung manusia untuk
kelangsungan hidupnya (Dahuri et al, 2004).
Terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di
laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Terumbu karang terutama disusun
oleh karang-karang jenis anthozoa dari klas Scleractinia (Nybakken, 1992). Struktur
bangunan batuan kapur (CaCO
3
) tersebut cukup kuat, sehingga koloni karang mampu
menahan gaya gelombang air laut. Asosiasi organisme-organisme yang dominan hidup
disini disamping scleractinian coral adalah alga yang juga mengandung kapur
(Dawes,1981).
Gambar 1. Polip Karang
Ada dua tipe karang, yaitu karang yang membentuk bangunan kapur (hermatypic
coral) dan yang tidak dapat membentuk bangunan karang (ahermatypic coral). Karena
dapat membentuk bangunan karang hermatypic coral sering dikenal pula sebagai reef-
building coral seperti pada jenis Scleractinia. Kemampuan hermatypic coral
membentuk bangunan kapur tidak lepas dari proses hidup binatang ini. Binatang karang
ini dalam hidupnya bersimbiose dengan sejenis alga berfotosintesis (zooxanthellae)
yang hidup di jaringan-jaringan polyp karang tersebut. Hasil samping dari aktivitas
fotosintesis ini adalah endapan kapur kalsium karbonat (CaCO
3
) yang membentuk
struktur dan bangunan yang khas. Ciri ini yang digunakan untuk menentukan jenis dan
spesies binatang karang. (Romimohtarto dan Juwana, 2001)
Berdasarkan proses pembentukannya, terumbu karang dibagi dalam 3 (tiga)
jenis yaitu :
1. Terumbu karang cincin (Atol), biasanya terdapat di pulau-pulau kecil yang
terpisah jauh dari daratan. Pembentukan karang tipe ini memerlukan waktu
beratus-ratus tahun. Contoh terumbu karang cincin dapat ditemui di
Takabonerate, Sulawesi Selatan.
2. Terumbu karang penghalang (Barrier reefs), Terumbu karang penghalang yang
terbesar terdapat di Australia yang dikenal dengan The Great Barrier Reef.
3. Terumbu karang tepi (Fringing reefs) merupakan jenis yang paling banyak
ditemukan di perairan Indonesia. Terumbu karang ini berada di pesisir pantai
yang jaraknya mencapai 100 meter ke arah laut.
Gambar 2. Tiga tipe terumbu karang dan proses evolusi geologinya
Terumbu karang (coral reef) merupakan organisme yang hidup di dasar perairan
dan berupa bentukan batuan kapur (CaCO3) yang cukup kuat menahan gaya
gelombang laut. Sedangkang organism-organisme yang dominan hidup disini adalah
binatang karang yang memiliki kerangka kapur, algae yang banyak diantaranya juga
mengandung kapur (Dawes, 1981).
Terumbu terbentuk dari endapan massif terutama kalsium karbonat yang
dihasilkan oleh hewan karang (filum Cnidaria, kelas Anthozoa, bangsa Scleractina),
alga berkapur dan organism-organisme lain yang mengeluarkan kalsium karbonat
(Nybakken, 1992).
Pembentukan karang merupakan proses yang lama dan kompleks. Berkaitan
dengan pembentukan terumbu karang terbagai atas dua kelompok yaitu karang yang
membentuk terumbu atau disebut hermatypic coral dan karang yang tidak dapat
membentuk terumbu atau ahermatypic coral. Kelompok hermatypic coral dalam
prosesnya bersembiosis dengan zooxentellae dan membutuhkan sinar matahari untuk
membentuk bangunan dari kapur yang dikenal dengan reef building corals, sedangkan
kelompok kedua tidak dapat membentuk bangunan kapur sehingga dikenal dengan
non-reef building corals yang secara normal hidupnya tidak tergantung pada sinar
matahari (Veron, 1986).
2.2 Karakteristik Morfologi Karang
Morfologi terumbu karang tersusun atas kalsium karbonat (CaCO3) dan terdiri
atas lempeng dasar, merupakan lempeng yang berfungsi sebagai pondasi dari septa yang
muncul membentuk struktur tegak dan melekat pada dinding yang disebut epiteka. Keseluruhan
skeleton yang terbentuk dari satu polip disebut koralit, sedangkan keseluruhan skeleton
yang terbentuk dari banyak polipdari satu individu atau koloni disebut koralum.
Permukaan koralit yang terbukadisebut kalik. Septa dibedakan menjadi septa pertama,
kedua, ketiga, danseterusnya, tergantung dari besar-kecil dan posisinya. Septa yang
tumbuhhingga mencapai dinding luar dari koralit disebut kosta. Pada dasar
sebelahdalam dari septa tertentu umumnya dilanjutkan oleh suatu struktur yang
disebutpali. Struktur yang berada di dasar dan tengah koralit sering
merupakankelanjutan dari septa yang disebut kolumela (IPB, 2008).
Sedangkan menurut Manuputty (1998), Karang lunak sesuai dengannamanya
memiliki tubuh yang lunak tapi lentur. Jaringan tubuhnya disokong olehkumpulan duri-
duri kecil yang kokoh, tersusun sedemikian rupa sehinggatubuhnya lentur dan tidak
mudah putus atau sobek. Duri-duri tersebut disebutspikula, mengandung karbonat
kalsium. Secara sepintas karang lunak tampakseperti tumbuhan karena bentuk
koloninya bercabang seperti pohon, memilikitangkai yang identik dengan batang dan
tumbuh melekat pada substrat dasar yang keras.
Gambar 3. Morfologi Karang
2.3 Bentuk Pertumbuhan Karang
Kategori bentuk pertumbuhan karang (koloni karang) ini berdasarkan pada English dkk.
(1998).
Pertumbuhan Non-Acropora :
1. Bentuk Bercabang (branching), kode CB, memiliki cabang lebih panjang daripada
diameter. Model percabangan sambung-menyambung dan ujung cabang yang runcing.
Gambar 4. Karang Brancing
2. Bentuk Padat (massive), kode CM, umumnya memilik bentuk seperti bongkahan
batu. Permukaan karang ini halus dan padat, biasanya ditemukan di sepanjang tepi
terumbu karang dan bagian atas lereng terumbu.
3. Bentuk kerak (encrusting), kode CE, tumbuh mengikuti bentuk substrat tempat ia
menempel dengan permukaan yang kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil.
banyak terdapat pada lokasi yang terbuka dan berbatu-batu, terutama mendominasi
sepanjang tepi lereng terumbu. Koloni karang yang baru tumbuh umumnya berbentuk
kerak.
4. Bentuk lembaran (foliose), kode CF, merupakan lembaran-lembaran yang menonjol,
berukuran kecil dan membentuk lipatan atau melingkar. Ditemukan terutama pada
lereng terumbu dan daerah-daerah yang terlindung. Bersifat memberikan perlindungan
bagi ikan dan hewan lain.
5. Bentuk Jamur (mushroom), berbentuk oval dan tampak seperti jamur,kode CMR,
memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit beralur dari tepi hingga pusat
mulut. Khusus karang jamur, ia tidak berkoloni, sehingga bila menemukan karang
jamur maka ia merupakan satu individu.
6. Bentuk submasif (submassive), kode CS, bentuk kokoh dengan tonjolan-tonjolan
atau kolom-kolom kecil.
7. Karang api (Millepora), kode CML, semua jenis karang api yang dapat dikenali
dengan adanya warna kuning di ujung koloni dan rasa panas seperti terbakar bila
disentuh.
8. Karang biru (Heliopora), kode CHL, dicirikan dengan warna biru pada rangka
kapurnya.
Bentuk pertumbuhan Acropora sebagai berikut :
1. Acropora bentuk cabang (Branching Acropora), kode ACB, bentuknya bercabang
seperti ranting pohon.
2. Acropora meja (Tabulate Acropora), kode ACT, bentuknya bercabang dengan arah
mendatar menyerupai meja. Karang ini ditopang dengan batang yang berpusat atau
bertumpu pada satu sisi membentuk sudut atau datar. Bersifat memberi perlindungan
pada ikan-ikan yang dapat bersembunyi di balik meja nya.
3. Acropora mengerak (Encursting Acropora), kode ACE, bentuknya seperti kerak,
namun koralitnya menonjol (ada axial corallite). Biasanya dijumpai pada Acropora yang
baru tumbuh membentuk koloni.
4. Acropora Submasif (Submassive Acropora), kode ACS, percabangannya berbentuk
gada/lempeng dan kokoh.
5. Acropora berjari (Digitate Acropora), kode ACD, bentuk percabangannya rapat
dengan cabang seperti jari-jari tangan.
2.4 Struktur Koralit Karang
Gambar 19. Tipe Koralit
Suatu koralit karang baru dapat terbentuk dari proses budding (percabangan)
dari karang. Selain bentuk koralit yang berbeda-beda, ukuran koralit juga berbeda-
beda. Perbedaan bentuk dan ukuran tersebut memberi dugaan tentang habitat serta
cara menyesuaikan diri terhadap lingkungan, namun faktor dominan yang
menyebabkan perbedaan koralit adalah karena jenis hewan karang (polip) yang
berbeda-beda.
Pembagian Bentuk koralit:
1. Placoid , masing-masing koralit memiliki dindingnya masing-masing dan dipisahkan
olehkonesteum.
2. Cerioid , apabila dinding koralit saling menyatu dan membentuk permukaan yang
datar.
3. Phaceloid , apabila koralit memanjang membentuk tabung dan juga mempunyai
koralit dengan dinding masing-masing .
4. Meandroid apabila koloni mempunyai koralit yang membentuk lembah dan koralit
disatukan oleh dinding-dinding yang saling menyatu dan membentuk alur-alur seperti
sungai.5.Flabello-meandroid , seperti meandroid , membentuk lembah-lembah
memanjang,namun koralit tidak memiliki dinding bersama.
6.Dendroid , yaitu bentuk pertumbuhan dimana koloni hampir menyerupai pohon yang
dijumpai cabang-cabang dan di ujung cabang biasanya dijumpai kalik utama.
7.Hydnophoroid , koralit terbentuk seperti bukit tersebar pada seluruh permukaan
sehingga sangat mudah untuk dikenal.
2.5 Histologi Karang
1.1. Histologi Karang
Menurut Bevelander et all (1988) histologi berasal dari bahasa yunani (histos =
jaringan), adalah suatu ilmu yang menguraikan struktur dari hewan serta tumbuhan
secara terinci, dan hubungan antara struktur pengorganisasian sel dan jaringan dan
fungsi-fungsi yang mereka lakukan. Dan menurut Cha (2004) histologi mempelajari
anatomi secara mikroskopik, di dalamnya dipelajari sel, jaringan, organ dan sistem
organ baik pada hewan maupun tumbuhan. Studi pendukung dalam histologi adalah
ekologi, fisiologi, reproduksi, biokimia, immunologi, embriologi dan sistematika.
Histologi mengenai karang berguna dalam konservasi terutama dalam
mendiagnosis penyakit yang dialami oleh polip karang, sehingga sebagai mahasiswa
Ilmu Kelautan yang tidak menutup kemungkinan untuk bergelut pada bidang
konservasi khususnya konservasi karang, maka dianggap perlu untuk mempelajari
histologi karang. Histologi dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian jaringan
polip pada karang melalui proses histologi (Suharsono, 1984).
1.1.1. Jaringan Karang
Jaringan karang terdiri dari ektoderm, mesoglea, dan endoderm.
Ektoderm merupakan jaringan terluar dan di dalam jaringan ini dapat dijumpai
adanya cilia (bulu halus), kantong mucus (lendir) dan sejumlah nematocyst.
Mesoglea adalah jaringan yang mendekati homogen seperti jelly, terletak di
antara ektoderm dan endoderm. Endoderm adalah jaringan yang terletak pada
bagian yang paling dalam. Sebagian besar terisi oleh zooxanthella. Zooxanthella
ini merupakan algae uniseluler, berwarna kuning coklat, dan hidup sebagai
simbion karang (Suharsono, 1984).
Bagian yang keras berupa kerangka kapur, terdiri dari lempeng dasar
yang tipis, dan disebut "basal plate". Dari lempeng dasar muncul lempeng-
lempeng yang berdiri tegak secara radial dan disebut septa. Masing-masing
septa dihubungkan oleh lempengan yang melingkar yang disebut theca atau
dinding. Penyusun kerangka ini terdiri dari serat kristalin atau butir-butir aragonit
CaCO
3
yang mempunyai diameter dua mikron. Secara umum bentuk dasar
kerangka kapur semua jenis karang adalah sama. Perbedaan pengendapan
CaCO
3
dan adanya faktor genetik memberikan bentuk-bentuk yang karakteristik
pada masing-masing jenis karang (Suharsono, 1984).
1.1.2. Dekalsifikasi
Menanamkan spesimen decalcification sebelum menggunakan 1 -1,5%
dengan titik leleh rendah atau agarosa HistoGel. Decalcifying larutan asam
klorida dengan agen Chelating, etilen diamina tetraacetic acid (EDTA) (Cha,
2004).
1.1.3. Penghilangan Kadar Air (Dehidrasi)
Mengganti alkohol 70% yang dipakai pada proses washing, dengan
alkohol 70% yang baru kedalam botol sampel sehingga potongan sampel
terendam seluruhnya. Selanjutnya secara bertahap alkohol 70% diganti dengan
alkohol 80%, dan 96%. Pada masing-masing tahapan dehidrasi, direndam
dengan durasi masing-masing 2X15 menit (Cha, 2004).
1.1.4. Embedding
Agar dapat memperoleh potongan tipis dengan mikrotom, setelah fiksasi
jaringan harus diinfiltrasi dengan suatu zat yang dapat memberi suatu
konsistensi kuat yang diperlukan untuk pemotongan. Ini dapat berupa gelatin,
seloidin, parafin, atau bahkan liat lainnya. Parafin umum digunakan untuk
mikroskop cahaya (Junqueira et all, 1980).
Sedangkan Menurut Cha (2004) adalah :
Dehidrasi untuk menghapus semua jejak-jejak air
Infiltrasi dengan cairan yang dapat mengeras cukup untuk memungkinkan
pemotongan bagian tipis
Clear dengan reagen yang bercampur dengan larutan dehidrasi dan
menengah embedding
Menanamkan media: Parafin untuk cahaya mikroskop & Glycol metakrilat
atau epoksi untuk mikroskopi elektron
Topologi jaringan
1.1.5. Perekatan Preparat (Mounting)
Proses terakhir ini yakni jaringan ini dicelupkan ke dalam xylene dan
ditiriskan, lalu objek glass diberi entelan dan ditutup dengan deglass, kemudian
diamati dibawah mikroskop (Cha, 2004).
BAB III. MATERI DAN METODE
3.1. Waktu dan Tempat Praktikum
Hari / Tanggal : Jumat, 16 Mei 2014
Pukul : 07.30 10.00 WIB
Tempat : Lab. Biologi Laut Ilmu Kelautan UNDIP
3.2. Materi Praktikum
3.2.1. Alat dan Bahan
Tabel 1. Alat praktikum koralogi
NO ALAT GAMBAR FUNGSI
1 Preparat
Sebagai tempat
ditempelkannya
sayatan jaringan
karang
2 Mikroskop
elektrik
Sebagai alat
untuk melihat
sampel
mikroskopis
3 Alat tulis
Alat untuk
mencatat
4 Kamera
Alat untuk
merekam
gambar (foto)
Tabel 2. Bahan praktikum koralogi
NO BAHAN GAMBAR FUNGSI
1 Jaringan Karang
Sebagai bahan
untuk diamati
2 Karang
(Sclerectania)
mati
Sebagai bahan
untuk diamati
3.2.2. Materi Praktikum Laboratorium
1. Tahapan Histologi Karang
2. Morfologi dan Anantomi Karang (struktur koralit karang)
3.3. Metode Praktikum
3.3.1. Histologi Karang
Pemotongan sampel karang
Dekalsifikasi
Pemotongan jaringan
Dehidrasi (penghilangan kadar air)
Embedding
Pemotongan Jaringan (specimen)
Pewarnaan
Perekatan preparat (mounting)
Pengamatan di bawah mikroskop
3.3.2. Morfologi dan Anantomi Karang (struktur koralit)
Menyiapkan sampel karang yang akan diamati
Mengamati struktur koralit dari sampel karang
(dengan cara melihat langsung dengan mata/ tanpa alat
bantu)
Mencatat hasil (nama struktur koralit) dan
menggambar bentuk struktur koralit
dari sampel karang
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
4.1.1. Histologi Karang
Tabel 3. Hasil pengamatan histologi karang
NO GAMBAR KAMERA KETERANGAN GAMBAR KODE PREPARAT
1 - Oosit
- Mesentri
- Mesoglea
- Zooxznthella
H-416-2
2 - Oosit
- Mesentri
- Mesoglea
- Zooxanthella
H-45-3
3 - Mesentri
- Mesoglea
- Zooxanthella
H-49-1
4.1.2. Struktur Koralit Karang
Tabel 4. Hasil pengamatan struktur koralit karang
NO
GAMBAR KAMERA
NAMA
STRUKTUR
KORALIT
CIRI-CIRI
1 Phaceloid - Koralit menonjol
- Memiliki conesteum /
conesteum terlihat
- Tonjolat dari koralit
bercabang
2 Cerioid - Tidak ada conesteum
- Tidak beralur / ber-
seri-seri
- Antara koralit
terpisahkan oleh
dinding
3 Plocoid - Koralit menonjol
- Memiliki conesteum /
conesteum terlihat
- Koralit tunggal / tidak
bercabang
4
Flabello
meandroid
- Koralit menonjol
- Memiliki conesteum /
conesteum terlihat
- Membentuk alur
seperti sungai
meander (berkelok)
5 Meandroid - Membentuk alur
seperti sungai
meander (berkelok)
- Tidak ada conesteum
- Anatara koralit
terpisahkan oleh
dinding
6 Solitary - Bukan koloni koral
- Septa teralur jelas
- Hanya satu koralit
4.2 Pembahasan
4.2.1 Histologi Karang
Hasil dari pengamatan histologi yang telah dilakukan terhadap beberapa sampel
sayatan jaringan dari karang menunjukan beberapa bagian-bagian dari histologi karang
tersebut berupa mesentary (ms), mesoglea (mg), zooxanthella (z). Setiap bagian
memiliki ciri-ciri tersendiri, mesoglea (mg) memiliki ciri berupa saluran panjang dan
terdapat bintik-bintik hitam, mesentary berupa kumpulan dari bintik-bintik hitam yang
membentuk kelompok, dan zooxanthella berbentuk bulat agak besar.
4.2.2 Morfologi dan Anatomi Karang
Hal yang dilakukan saat pengamatan anatomi berupa pengamatan lifeform,
morfologi, dan jenis coralite pada karang tersebut. Hasil pengamatan menunjukan
terdapat beberapa lifeform pada jenis karang berupa massive dan mushroom. Setiap
karang memiliki jenis coralite yang berbeda walaupun dalam lifeform yang sama.
Bebrapa bentuk massive memiliki coralite ceroid, meandroid dan phaceloid. Sedangkan
untuk mushroom termasuk kedalam karang yang soliter. Setiap coralite memiliki ciri
khas tersendiri, ceroid memiliki satu wall atau dinding sehingga karang tersebut tidak
memiliki conesteum, placoid memiliki wall yang berbeda seingga karang ini memiliki
conesteum atau pemisah antar wall, placeloid memiliki tegakan sendiri dan tidak
memiliki kosta hanya memiliki wall dan memiliki conesteum, meandroid memiliki satu
wall dan terdiri dari beberapa columela.
V. KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Dari praktikum yang sudah dilakukan kita dapat mengerti beberapa hal yaitu:
1. Dalam praktikum kali ini kita dapat memahami dan mengerti tentang
morfologi dan anatomi karang khusus nya bentuk koloni dan struktur koralit
dari karang yang kita identifikasi.
2. Dan juga dapat mengetahui proses histologi karang yang melalui 6 tahap
yaitu pemotongan jaringan, dekalsifikasi, dehidrasi, embedding, pewarnaan
preparat dan juga perekatan preparat.
5.2 Saran
1. Diharapkan praktikan lebih teliti dalam mengidentifikasi struktur anatomi
karang
2. Diharapkan sebelum melakukan praktikum praktikan mempelajari modul
sebelumnya
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2012 dalam http://repository.ipb.ac.id diakses pada Tanggal 22 November 2012 Pukul
21.40 WIB.
Cha, Ha-Rim. 2004. Understanding Coral Histology - How & Why -
http://www.nhm.ku.edu/inverts/presentations2004/harim_museumlunch_april2004.ppt
Dahuri Rokhmin. 2004. Pedoman Sumber daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT
Pradnya paramita. Jakarata.
Dawes, C. J. 1981. Marine Botany. Jhon Wiley & Sons, Inc. 229 hal
IPB, 2008. Bab II 2008rer. Bogor Agricultural University. Bogor.
Junqueira, Luis C; Carneiro, Jose. 1980. Hisrologi Dasar (Basic Histology).Jakarta: EGC.
Nybakken. J. W. 1988. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologis. PT Gramedia. Jakarta
Nybakken,J,W. 1992. Biologi Laut satu Pendekatan Ekologis. (Terjemahan. Alih
bahasa oleh H.M Eidman). PT. Gramedia.Jakarta )
Nybakken, J.W. 1994. Marine Biology : An Ecologycal Approach. PT Gramedia. Jakarta.
Manuputty, Anne W.E., 1998. Beberapa Karang Lunak (Alcyonaria) Penghasil Substansi
Bioaktif. Puslitbang Oseanologi LIPI. Jakarta.
Odum, E. P., 1971. Dasar-dasar Ekology. Cetakan ke-3. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta.
Romimohtarto,K. dan S. Juwana. 2001. Biologi Laut: Ilmu Pengetahuan tentang Biota
Laut.Puslitbang Oseanologi LlPI. Jakarta. 527 h.
Romimohtarto, K. dan S. Juwana. 2001. Biologi Laut, Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut.
Jakarta: Djambatan. Hal. 190, 422.
Suharsono. 1998. Condition of coral reef resources in Indonesia. J Pes Laut 1:42-52.
Veron JEN. 1986. Coral of Australia and The Indopasific. Angus & Robertos. Australia
Wibisono, 2005. Pengantar Ilmu Kelautan. Penerbit Grasindo. Jakarta.
Anda mungkin juga menyukai
- Praktek Lapangan OceanDokumen23 halamanPraktek Lapangan OceanAslanBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum KoralogiDokumen22 halamanLaporan Praktikum KoralogiSyamsu RizalBelum ada peringkat
- Laporan KoralogiDokumen15 halamanLaporan KoralogiDesmaini DesBelum ada peringkat
- Laporan-Koralogi - 1 - PDFDokumen32 halamanLaporan-Koralogi - 1 - PDFWahyuBagio100% (1)
- Paper IndividuDokumen7 halamanPaper IndividuLeonny MustikaBelum ada peringkat
- Laporan KoralogiDokumen12 halamanLaporan KoralogiMaruf Kurniawan0% (1)
- Laporan Terumbu KarangDokumen4 halamanLaporan Terumbu KarangMuhammad Fahmi Djunaid AshariBelum ada peringkat
- CephalopodaDokumen5 halamanCephalopodaX IceBelum ada peringkat
- Pengenalan Bentuk Pertumbuhan KarangDokumen9 halamanPengenalan Bentuk Pertumbuhan KarangRadinalBelum ada peringkat
- Laporan Akhir PRAKTIKUM Koralogi (FINAL) PDFDokumen29 halamanLaporan Akhir PRAKTIKUM Koralogi (FINAL) PDFsakti bhujnggaBelum ada peringkat
- Kelompok 6 Pertumbuhan KarangDokumen29 halamanKelompok 6 Pertumbuhan KarangFathul DewaBelum ada peringkat
- Laporan Lengkap Fisbiola - RafsanjaniDokumen24 halamanLaporan Lengkap Fisbiola - RafsanjaniRafsanjaniArBelum ada peringkat
- Skripsi 1Dokumen116 halamanSkripsi 1Muhammad MunirBelum ada peringkat
- Anemon LautDokumen9 halamanAnemon LautUlfi FaizahBelum ada peringkat
- Laporan Pelatihan Transplantasi KarangDokumen7 halamanLaporan Pelatihan Transplantasi Karangawang_8375Belum ada peringkat
- Jurnal Filum Moluska Ninaa - Ilmu Kelautan. Laporan LengkapDokumen12 halamanJurnal Filum Moluska Ninaa - Ilmu Kelautan. Laporan LengkapAriyantiBelum ada peringkat
- Ekosistempantai PasirDokumen27 halamanEkosistempantai PasirZuchdiawati Luthfi UtamiBelum ada peringkat
- Laporan Lengkap AkustikDokumen15 halamanLaporan Lengkap AkustikRati ErwinBelum ada peringkat
- Laporan Limnologi Acara MorfometriDokumen7 halamanLaporan Limnologi Acara MorfometriQurrotu Aini PutriBelum ada peringkat
- MakrozoobenthosDokumen11 halamanMakrozoobenthosDwi Kus PardiantoBelum ada peringkat
- Laporan Avetebrata EchinodermataDokumen12 halamanLaporan Avetebrata Echinodermataira septilianaBelum ada peringkat
- Jurnal Bentik-OseanoDokumen9 halamanJurnal Bentik-OseanoNur ShabrinaBelum ada peringkat
- Laporan Akustik KelautanDokumen22 halamanLaporan Akustik KelautanSay CheseBelum ada peringkat
- Sri Dianty Isvandari - 26020114140116 - Profil Kecepatan Bunyi Di LautDokumen15 halamanSri Dianty Isvandari - 26020114140116 - Profil Kecepatan Bunyi Di LautErik Wijaya KusumaBelum ada peringkat
- MIGRASI VERTIKAL HARIAN Ceriodaphnia Sp. DI DANAU BATUR, BALI-INDONESIADokumen7 halamanMIGRASI VERTIKAL HARIAN Ceriodaphnia Sp. DI DANAU BATUR, BALI-INDONESIAbenyamin7Belum ada peringkat
- Montipora StellataDokumen6 halamanMontipora StellataNurul AiniBelum ada peringkat
- PlanktonDokumen43 halamanPlanktonRenaldy BelidaBelum ada peringkat
- Jurnal Organik Dalam LautDokumen5 halamanJurnal Organik Dalam LautErshy PennaBelum ada peringkat
- Keberagaman BryozoaDokumen11 halamanKeberagaman Bryozoadidin_burhanudin3626100% (1)
- MAKALAH Botani LautDokumen23 halamanMAKALAH Botani LautBob AnggaraBelum ada peringkat
- 2019smy PDFDokumen49 halaman2019smy PDFrachmad hidayatBelum ada peringkat
- Avertebrata AirDokumen13 halamanAvertebrata AirAdinda Kurnia Putri100% (1)
- Ektoparasit Pada Udang Vannamei PKLDokumen22 halamanEktoparasit Pada Udang Vannamei PKLIzzudin Syaifullah100% (1)
- Panduan Praktikum Akustik Kelautan UndipDokumen15 halamanPanduan Praktikum Akustik Kelautan UndipMuhammad Jeckha100% (1)
- Jurnal Avertebrata SpongeDokumen7 halamanJurnal Avertebrata SpongeRukman awan syamBelum ada peringkat
- Makalah Pencernaan TeripangDokumen14 halamanMakalah Pencernaan TeripangRenaldy LosongBelum ada peringkat
- Tugas OseanografiDokumen28 halamanTugas Oseanografikhairunmutia100% (1)
- DESAIN WADAH PERBENIHAN DENGAN SISTEM RESIRKULASI - Kelompok 4Dokumen17 halamanDESAIN WADAH PERBENIHAN DENGAN SISTEM RESIRKULASI - Kelompok 4YunitaBelum ada peringkat
- Ekosistem Terumbu KarangDokumen185 halamanEkosistem Terumbu KarangRaptorzsBelum ada peringkat
- Acropora CervicornisDokumen20 halamanAcropora CervicornisFajar SetiawanBelum ada peringkat
- Identifikasi Plankton IDokumen12 halamanIdentifikasi Plankton IReamure GokilBelum ada peringkat
- Nugraha Ali Dimyati - Morfologi Anatomi, Dan Lapisan PolipDokumen5 halamanNugraha Ali Dimyati - Morfologi Anatomi, Dan Lapisan PolipNugrahaBelum ada peringkat
- Modul INVERTEBRATA AKUATIKDokumen38 halamanModul INVERTEBRATA AKUATIKZULFADLIBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum OseanografiDokumen8 halamanLaporan Praktikum OseanografiIndri NurwahidahBelum ada peringkat
- Paper Ekologi Laut TropisDokumen7 halamanPaper Ekologi Laut TropisRefwina CapricaBelum ada peringkat
- ACC 3 - Jecly Paembonan - PerbaikanDokumen16 halamanACC 3 - Jecly Paembonan - PerbaikanJIMMY PAEMBONANBelum ada peringkat
- Modul Praktikum Avertebrata AirDokumen72 halamanModul Praktikum Avertebrata AirAskin100% (1)
- Anemon LautDokumen5 halamanAnemon LautNanda Al FarisiBelum ada peringkat
- REPRODUKSI FITOPLANKTON HayaDokumen4 halamanREPRODUKSI FITOPLANKTON HayafikaBelum ada peringkat
- Kuliah 3Dokumen43 halamanKuliah 3Nadia SaputriBelum ada peringkat
- Lita SkripsiDokumen77 halamanLita SkripsiYulita solemedeBelum ada peringkat
- Laporan PraktikumDokumen32 halamanLaporan PraktikumHujan TurunBelum ada peringkat
- Filum CnidariaDokumen7 halamanFilum CnidariaIrlosianaBelum ada peringkat
- Kuliah LapanganDokumen61 halamanKuliah LapanganBintangManurungBelum ada peringkat
- Tugas LobsterDokumen10 halamanTugas LobsterMuhammad IksanBelum ada peringkat
- Laporan Biologi LautDokumen28 halamanLaporan Biologi LautRajis AdityaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Ekologi LautDokumen19 halamanLaporan Praktikum Ekologi LautAtim FebryBelum ada peringkat
- Makalah Ekosistem Terumbu KarangDokumen22 halamanMakalah Ekosistem Terumbu KarangSalwa NurafifahBelum ada peringkat
- Tugas Geografi Bu NurhayatiDokumen11 halamanTugas Geografi Bu NurhayatiRaihan HilmyBelum ada peringkat
- Bab I Biologi Laut Ekosistem Terumbu KarangDokumen15 halamanBab I Biologi Laut Ekosistem Terumbu KarangNurhidayat Alverio100% (1)
- Laporan CoraogyDokumen30 halamanLaporan CoraogySukron Alfi ER100% (2)
- Acropora SubmassiveDokumen2 halamanAcropora SubmassiveSukron Alfi ERBelum ada peringkat
- Sejarah FotogrameteriDokumen28 halamanSejarah FotogrameteriSukron Alfi ERBelum ada peringkat
- Osfis Modul IDokumen35 halamanOsfis Modul ISukron Alfi ERBelum ada peringkat
- Botani LautDokumen40 halamanBotani LautSukron Alfi ER100% (1)