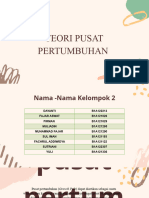Strategi Desa Pusat Pertumbuhan
Strategi Desa Pusat Pertumbuhan
Diunggah oleh
RiyantoJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Strategi Desa Pusat Pertumbuhan
Strategi Desa Pusat Pertumbuhan
Diunggah oleh
RiyantoHak Cipta:
Format Tersedia
Strategi pertumbuhan
Pertumbuhan (Growth Pole)
Pengembangan wilayah yang dijalankan melalui pendekatan
strategi pusat pertumbuhan sccara teoritis dilandasi olch konsep
kutub pertumbuhan yaitu, ditandai dengan adanya lokasi kutub-
kutub pertumbuhan ckonomi dalam suatu k.cteraturan ruang. Growth
pole atau kutub pertumbuhan pertama kali dikemukakan oleh
Francois Perroux (dalam Muta'ali 2014: 156) dengan tesisnya
sebagai herikut:
Pertumbuhan lidak akan terjadi di sembarang tempat dan
juga tidak terjadi sccara serentak, telapi pertumbuhan terjadi pada
titik-titik ataus kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang
berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menycbar sepanjang saluran
sini untuk mencarí yang baranekn ragam dan dengan penganuh yang dinamis terhadap
perekonomian wilayah.
Pengertian growth pole yang terkait dengan ruang sebagai
SAIatu kumpulan kekuntan ekonomi, yang didefinisikan oleh PerroOux
memiliki gaya tarik dan gaya tolak dalam suatu medan daya tarik
dan gaya dorong bersama dengan pusal-pusat lainnya. Pengertian ini
bermakana bahwa growth pole berperan memacu (menarik dan
mendorong) perkembangan ekonomi di wilayahnya. Perroux
menyatakan bahwa yang menjadi medan magnet merupakan
kegiatan industri yang manpu menjadi leading sectar
Pengembangan wilayah seperti ini secara nyata akan terlihat
dari perkembangan kota-kota schagai kutub pertumbuhan di suatu
wilayah yang membentuk suatu hierarki kota. Melalui hirarki kota
ini diharapkan dapat terjadi proses penycbaran kemajuan antar kota
di wilayah terscbut yang berlangsung dalam beberapa cara (Munir
dalam Lutfi 2014: 159) yaitu scbagai berikut:
1) Pcrluasan kegiatan ckonomi ke wilayah pasar yan baru yaitu
dari pusat terbesar kepada yang kecil.
2) Perpindahan kegiatan herupah rendah dari pusat yang hesar ke
pusal yang lebih kecil karcna meningkatnya upah di kota (pusat) yang lebih besar
3) Memberlkan alternatlf lokasi ynng lebih baik unnuk keglatan
Industri yang mempunyal wilayah pasac dan kebutuhan
prisarana yang berbeda sehingga operasinya lebih efisien.
4) Dorongan investasi dari wirausahawan yang disebarkan melaluli hirarki
Friedman (dalam Muta'ali, 2014: 159) memperkuat konsep
pusat pertumbuhan dengan mengemukakan konsep Center-
Periphery (pusar-pinggiran). Hubungan antara pusat dan pingiran
digambarkan dengan dua efek yaitu efek sebar (spread effect) dan
efek serap (backwash effect). Spread effect terjadi apabila ekspansi
kegiatan ekonomi pada Core (pusat) membutuhkan input bahan baku
dani daerah sekitarnya (mekanisme input-output). Sebaliknya
Backwash Effect terjadi jika industri populsif tertentu cenderung
hanya kan menarik modal dari dacrah sekitarmya sehingga output
kan Icbih tinggi.
Pusat pertumbuhan (growth pole) itu scndiri dapat diartikan
dalam dua cara yaitu sccarn fungsional dan gcografis. Pusat
pertumbuhan secara fungsional adalah sutu lokasi konsentris
kelompok usaha atau cabang cabang industri yang dinamis sehíngga
mampu menstimulasi kehidupan ckonomi baik ke dalam maupun ke
Juar (wilayah belakangnya). Pusat pertumbuhan seeara geografis
adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan
schingga menjadi pusat daya tank (pole of attraction), (Tarigan,2007: 162). Rasilitas yang dimnksaud
berlulnungan dengn daya tarik
austu wilayah merupakaun ketersedinan berbangni macam fasilitas
pelaynnan publik, haik pelayanan sosial muaupun ckonanni
Kemudahan sebagai daya tarik suatu wilayah erat knitannya dengan
aksesibilitas suatu wilayah.
b. Strategi Desentralisasi Teritorial
Pendekatan desentralisasi terotorial merupakan strategi
pembangunan dari bawah (developed from below) Pembangunan
dari bawah memperluas pengertian pembangunan tidak hanya
kemajuan ekonomi (pertumbuhan ekonomi semata) yang sentralistik
tetapi memberikan kesempatan bagi individu-individu, kelompok-
kelompok sosial dan organisasi masyarakat untuk memobilisasi
kemampuan dan sumberdaya lokal bagi kemajuannya. Pendekatan
ini menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi
pembangunan dinamis di wilayah-wilayah (perdesaan) yang relatif
terbelakang (Muta ali. 2014: 161)
c Strategi Agropolitan
Agropolitan merupakan pendekatan pengembangan wilayah
yang menitikberatkan pada upaya untuk menciptakan dorongan bagi
pembangunan dinamis di wilayah-wilayah perdesaan dan wilayah
yang relatil terhelakang. Dalam pendekatan agropolitan upaya untuk
mempercepat pembangunán di perdesaan dilakukan dengan memasukkan kegiatan non primer seperti
industri, perdagangan, jasa dan lain-lain yang menunjang sektor pertanian. Hal ini berrti bahwa
gropolitan adalah suatu wilayah yang struktur parekonomiannya
tidak hanya bertumpu poda sektoc pertanian. Setor pertanian yang
dikembangkan yakni sektor industri yang meminki inkages sccara
Iangsung, yaitu menghasilkan alat pertanian dan mengolah hasil
pertanian sccara agroindustri, (Muta'ali, 2014: 163-164)
d.
Strairgi Integrasi Spasial (Functional Spatial Integration)
Startegi integrasi spasial merupakan jalan tengah antara
pendekatan sentralisasi yang menckankan pertumbuhan pada
wilayah perkotaan dan desentralisasi yang menckankan penyebaran
investasi dan sumberdaya pembangunan pada kota-kota kecil dan
pedesaan. Pendekatannya adalah memacu perkembangan sektor
pertanian yang diintegrasikan dengan sektor industri pendukungnya
Berdasarkan asumsi tersebut, sasaran dari strategi mi adalah
meningkatkan produksi pertanian. memperluas lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan bagi scbagian besar penduduk terutama
penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dengan titik
perhatiannya aadalah pada wilayah pedesaan.
Rondinelli (dalam Mula ali. 2014
1651. mengkategorikan 7
(tujuh) keterkitan (spatial linkages), yaitu:
1.Keterkailan tisik (jaringan transortasi)
2.Keterkaitan ekonomi: kekrkaitan produksi kedepan ( forward linkages) dan ke belakang ( backward
linkages)
Keterkaitan pergerakan penduduk (inigrasi) dan tenaga kerja
4. Keterkaitan teknologi
5. Keterkaitan sosial
6.Keterkaitan pelayanan sosial
7.Keterkaitan administrasi, politik dan kelermbagam
c. Teori Lokasi
Lokasi menggambarkan posisi pada runag terscbut mengenai
keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan
Inin di lokasi lain Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau
jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan menganalisis
dampak atas kegiatan karena lokasi yang berdckatan/herjauhan
tersebut (Tarigan, 2006: 78)
Tcori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata runag (spatial
order) terhadap berbagai kegiatan baik ckonomi maupun sosial
berdasarkan karakieristik potensi wilayah dan aspek geografis. Salah
satu hal yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh
jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi
lainnya. Faktor penarik adanya intensitas interkasi terhadap suatu
wilayah ialah data tarik wilayah meliputi ketersediaan sarana
prasarana baik ckonomi maupun sosial serta tingkat aksesibilitas
wilayah (Tarigan, 2006:79)
Teori lokasi yang digunakan untuk pendistribusian ruang
dalam penelitian berdasarkan teori lokasi Von Thunen
1. Model Von Thunen
Johan Heinrich Von Thunen mengupas perbedaan lokasi
dari berbagai kegiatan perbedaan pertanian atas dasar perbedaan
sewa tanah (pertimbangan ckonomi). Von Thunen membuat
asumsi (Tarigan, 2006:93) scbagai berikut:
a)
Wilayah analisis bersifat terisolir (isolated statc) schingga
tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain.
b) Tipe permukiman adalah padat di
sat wilayah (pusat
pasar) dan kurang padat apabila menjauh dari pusat
wilayah.
c) Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah, topografi
d) Fasilitas pengangkutan adalah primitit (sesuai pada
zamannya) dan relatif seraga oim. Ongkos ditentukan leh
berat barang yang dibawa.
(a
Kecuali perbedaan jarak ke pasar. semua faktor alamiah
yang meimpengaruhi penggunaan lanah adalah seragam dan
konstan
Eerdasarkan sunsi di atas, Von Thunen menyinipulkan
ketertnubungan sewa tansh dengan jarak ke pasar. Sewa tanah
akan semakin mahal apabila tanah itu berada dekat dengan pusat
pasar dan akan semakin murah apabila berada jauh dari pusat
pasar. Pola keruangan yang dihasilkan oleh Model Von Thunen
sebagai berikut:
6 5 4 3 2 1P
Gambar 1. Pola Keruangan Model Von Thunen
Keterangan:
P : Pasar
Cincin 1 Pusat Industri/Kerajinan
Cincin 2 Pertanian intensif (produksi susu dan sayur mayur)
Cincin 3 : Wilayah hutan
Cincin 4 Pertanian ekstensif (dengan rotasi 6 atau 7 tahun)
Cincin 5 Wilayah peternakan
Cincin 6 Wilayah pembuangan sampah
Konsep Von Thunen bahwa sewa tanah sangat
mempengaruhi jenis kegiatan yang mengambil tempat pada
lokasi tertentu sampai saat ini masih herlaku dan hal ini
mendorong terjadinya konsentrasi kegiatan tertentu pada lokasi
tertentu. Model Von Thunen menggunakan asumsi sewa tanah
untuk produksi pertanian tetapi menurut beberapa ahli teori ini
masih sangat relevan untuk sewa tanah perkotaan saat ini
dengan menambah aspek tertentu, semisal kemudahan akses dan daya tarik suatu wilayah terhadap
yang lain (tarigan, 2006:95)
Anda mungkin juga menyukai
- Pusat PertumbuhanDokumen5 halamanPusat PertumbuhanYona PelawiBelum ada peringkat
- Geo PerkotaanDokumen8 halamanGeo PerkotaanSun SyamsunBelum ada peringkat
- Konsep Pusat Pertumbuhan Dilandasi Oleh Konsep Ruang EkonomiDokumen4 halamanKonsep Pusat Pertumbuhan Dilandasi Oleh Konsep Ruang EkonomiSabikha AnisaBelum ada peringkat
- Strategi Pengembangan WilayahDokumen13 halamanStrategi Pengembangan WilayahOne Piece100% (1)
- TEORI Pertumbuhan WilayahDokumen10 halamanTEORI Pertumbuhan WilayahGhaziyah GhandyBelum ada peringkat
- Teori Pusat PertumbuhanDokumen8 halamanTeori Pusat PertumbuhanYuwono Ario100% (2)
- Pengertian Growth PoleDokumen7 halamanPengertian Growth PolebmanuhuaBelum ada peringkat
- Teori Kerucut PermintaanDokumen14 halamanTeori Kerucut PermintaanAndikaRosyadi100% (1)
- Bab 2 Draft AkhirDokumen61 halamanBab 2 Draft AkhirBoyke P SiraitBelum ada peringkat
- Laporan Teori Pertumbuhan WilayahDokumen11 halamanLaporan Teori Pertumbuhan Wilayahadek dessy kBelum ada peringkat
- Pusat Pertumbuhan (Growth Pole)Dokumen39 halamanPusat Pertumbuhan (Growth Pole)Halimayul LopindaBelum ada peringkat
- Perencanaan Pembangunan Dengan Teori PolarisasiDokumen5 halamanPerencanaan Pembangunan Dengan Teori PolarisasiRirin Trisdayanti100% (1)
- Paper Ilmu WilayahDokumen212 halamanPaper Ilmu WilayahAriq 1999Belum ada peringkat
- Teori Perencanaan WilayahDokumen18 halamanTeori Perencanaan Wilayahindy farahBelum ada peringkat
- Model Pengembangan Wilayah Dari Atas Dan Dari BawahDokumen3 halamanModel Pengembangan Wilayah Dari Atas Dan Dari BawahIndriyana Igirisa100% (1)
- B. Pusat Pertumbuhan EditDokumen24 halamanB. Pusat Pertumbuhan EditMartha HasibuanBelum ada peringkat
- 4 PERENC Kota Dan Desa UNPAR MPWK 2023@SH PDFDokumen35 halaman4 PERENC Kota Dan Desa UNPAR MPWK 2023@SH PDFRiza NuansyahBelum ada peringkat
- E RegionalDokumen6 halamanE RegionalHadiBelum ada peringkat
- Strategi Pengemabangan WilayahDokumen7 halamanStrategi Pengemabangan WilayahDewi L. PasaribuBelum ada peringkat
- Teori RuangDokumen12 halamanTeori RuangherdiansyahBelum ada peringkat
- Pembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah 3.1Dokumen4 halamanPembangunan Dan Pertumbuhan Wilayah 3.1Laela HimmahBelum ada peringkat
- Pembangunan Kawasan Dan Tata Ruang Oleh Rahardjo AdisasmitaDokumen4 halamanPembangunan Kawasan Dan Tata Ruang Oleh Rahardjo AdisasmitaShallima Nada PuspaBelum ada peringkat
- Materi Geografi Kelompok 2Dokumen15 halamanMateri Geografi Kelompok 2Syaiba KiandaBelum ada peringkat
- 3.1 Pembangunan Wilayah Dan Pusat PertumbuhanDokumen9 halaman3.1 Pembangunan Wilayah Dan Pusat PertumbuhanNia RahmadaniBelum ada peringkat
- Polarisasi Ekonomi DuniaDokumen10 halamanPolarisasi Ekonomi DuniaAnisha Widowati100% (1)
- Model Dan Strategi PengembanganDokumen15 halamanModel Dan Strategi PengembanganjuneryBelum ada peringkat
- PWK UnhasDokumen16 halamanPWK UnhasMark Margh UmargnaBelum ada peringkat
- Integrasi SpasialDokumen5 halamanIntegrasi SpasialOne PieceBelum ada peringkat
- Aglomerasi Dalam Ekonomi RegionalDokumen5 halamanAglomerasi Dalam Ekonomi RegionalUli Uly100% (1)
- PAPER (Teori Wilayah Kutub Pertumbuhan)Dokumen6 halamanPAPER (Teori Wilayah Kutub Pertumbuhan)DonnchandBelum ada peringkat
- Tugas I Ekonomi Regional Vs Geografi Ekonomi Arief Prasetyo NPM 1306361192Dokumen11 halamanTugas I Ekonomi Regional Vs Geografi Ekonomi Arief Prasetyo NPM 1306361192vicki_lusiagustin100% (1)
- Teori Kutub PertumbuhanDokumen5 halamanTeori Kutub PertumbuhanChikara 1734Belum ada peringkat
- Ringkasan Ekonomi RegionalDokumen4 halamanRingkasan Ekonomi RegionalDEO FEBRIANTOBelum ada peringkat
- Teori Pembangunan AldoDokumen9 halamanTeori Pembangunan AldoWinda PajriantiBelum ada peringkat
- Teori Pusat PertumbuhanDokumen13 halamanTeori Pusat PertumbuhanSYUKUR ABDULLAHBelum ada peringkat
- Pusat PertumbuhanDokumen14 halamanPusat PertumbuhanSakamaki IzayoiBelum ada peringkat
- Bahanajar 1630732035Dokumen16 halamanBahanajar 1630732035sarip keduaBelum ada peringkat
- Growth PoleDokumen19 halamanGrowth PoleseldiesBelum ada peringkat
- Pusat PertumbuhanDokumen8 halamanPusat PertumbuhanwiwikjuiartiBelum ada peringkat
- Pusat PertumbuhanDokumen7 halamanPusat PertumbuhanOfaridaBelum ada peringkat
- Ekonomi Regional Dan Geografi EkonomiDokumen15 halamanEkonomi Regional Dan Geografi Ekonomivicki_lusiagustinBelum ada peringkat
- Teori Lokasi Dan Analisis Spasial PDFDokumen20 halamanTeori Lokasi Dan Analisis Spasial PDFسري حميدهBelum ada peringkat
- Kelompok 2 Teori Pusat PertumbuhanDokumen15 halamanKelompok 2 Teori Pusat PertumbuhanFajar AswatBelum ada peringkat
- Lokasi Pola RuangDokumen5 halamanLokasi Pola RuangSae SunggawaBelum ada peringkat
- Reza Ekapri Hartino 4Dokumen1 halamanReza Ekapri Hartino 4Reza AlvinBelum ada peringkat
- Teori Aktivitas Industri& Pengembangan DesaDokumen15 halamanTeori Aktivitas Industri& Pengembangan Desanoor_puspitoBelum ada peringkat
- Ekonomi Regional Pusat PertumbuhanDokumen20 halamanEkonomi Regional Pusat PertumbuhanPaparazzy •Belum ada peringkat
- Ordo KotaDokumen11 halamanOrdo KotaNoviie AriiyaniiBelum ada peringkat
- Uas Prencanaan Wilayah, Anfred YeiimoDokumen5 halamanUas Prencanaan Wilayah, Anfred YeiimoAnfred JeimoBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen6 halamanBab IiiSelvi PohanBelum ada peringkat
- Teori Pusat PertumbuhanDokumen15 halamanTeori Pusat PertumbuhanSafri NugrohoBelum ada peringkat
- 1.teori Pengembangan WilayahDokumen6 halaman1.teori Pengembangan WilayahPetrus Damiani Sugi BalaBelum ada peringkat
- TR2 - Teori LokasiDokumen6 halamanTR2 - Teori LokasimariefmuntheBelum ada peringkat
- Bab Ii RevisiDokumen22 halamanBab Ii RevisiIkalmyBelum ada peringkat
- Teori Von ThunenDokumen11 halamanTeori Von ThunenTri FebriawanBelum ada peringkat