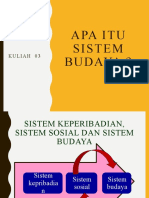Kesukubangsaan Dan Primordialitas
Diunggah oleh
ArigatouHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kesukubangsaan Dan Primordialitas
Diunggah oleh
ArigatouHak Cipta:
Format Tersedia
Kesukubangsaan dan Primordialitas:
Program Ayam di Desa Mwapi, Timika,
Irian Jaya1
Parsudi Suparlan
(Universitas Indonesia)
Abstract
In this article, Suparlan uses both concept's of ethnicity and primordialism
in explaining the failure of Poultry Farming Assistance Program carried out
by the local office of the general of Animal Housebandry in Mwapi Villlage,
Irian Jaya. Among the Komoro's who live in this village are devided into two
clans: Muare and Pigapu. Their culture is called Ndaitita which mainly
based on egalitarianism. They do not have a formal social stratification.
Each person percieved as atomistic individual. Concepts of state and larger
societies do not exist in Komoro's culture. Their social relation base on
family and clan. When the head of Mwapi villages had task to coordinate
the chicken program, he only recruited the persons from his clan: Muare.
According to Suparlan, the heads start his ethnicity in forming make this
group. But the programs started to ruin when the group had to work
together. Komoro' peoples are very individualistic. So, the programs had
failure. To cover up this problems. Chief starts his primordialism as the core
beliefs.
1
Naskah aslinya disampaikan dalam Widyakarya Nasional Antropologi 1997, Jakarta 25-
28 Agustus 1997.
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 1
Kesukubangsaan sebagai sebuah konsep ilmiah telah bergeser
pengertiannya dari mengenai isi kebudayaan menjadi mengenai jatidiri atau
identitas yang muncul dalam interaksi sosial, dan yang karena itu kajian
mengenai kesukubangsaan menjadi terfokus pada batas-batas sukubangsa di
mana artibut-atribut kesukubangsaan yang mencakup simbol-simbol kebudayaan
sebagaimana didefinisikan oleh para pelakunya menentukan corak
kesukubangsaan yang bersangkutan. Pergeseran tersebut dimulai oleh Frederik
Barth (1969:9-38) yang menunjukkan bahwa kajian mengenai sukubangsa
bukanlah kajian mengenai kolektiva dengan isi atau taksonomi kebudayaannya,
tetapi kajian mengenai organisasi sosial yang askriptif berkenaan dengan asal
muasalnya yang mendasar dan umum dari para pelakunya; sebab, jika kajiannya
mengenai kolektiva dan isi kebudayaannya yang dilakukan secara taksonomi
maka yang dihasilkan adalah kajian-kajian mengenai taksonomi kebudayaan,
pola-pola kebudayaan, akulturasi budaya, atau perubahan kebudayaan; dan
bukan kajian mengenai kesukubangsaan adalah (?) kajian yang memusatkan
perhatian pada antar hubungan di antara para pelaku, dengan jati diri
sukubangsanya sebagai atribut-atribut yang digunakan dalam interaksi-interaksi
sosial. Karena itu Barth dalam tulisannya tersebut mengemukakan
pentingnya perhatian kajian mengenai sukubangsa pada batas-batas sukubangsa,
yang terwujud dalam hubungan antarsukubangsa, karena dalam interaksi tersebut
perbedaan-perbedaan jati diri dari para pelaku nampak jelas ditunjukkan; yang
terwujud baik dengan sengaja maupun dilakukan secara spontan, maupun
yang terwujud sebagai atribut-atribut fisik, simbol-simbol yang tersurat maupun
yang tersirat, serta yang rasit (?). Berbagai tulisan mengenai kesukubangasaan
setelah tulisan Frederik Barth tersebut telah memenuhi khasanah kepustakaan
antropologi, dan tulisan yang paling terakhir mengenai masalah kesukubangsaan
adalah hasil karya Jenkins (1997).
Jenkins (1997) tertarik untuk mendalami konsep kesukubangsaan dengan
memusatkan perhatiannya pada permasalahan jati diri, yang dikajinya secara
akademik dan intelektual, dengan melihatnya dari sejarah perkembangan
penggunaan konsep ini yang dimulai oleh Max Weber, memperbandingkannya
dengan konsep ras, dan bahkan melihat konsep kesukubangsaan secara
taksonomik untuk kemudahan analisis (sic!). Dalam upaya untuk
mengoperasionalkan konsep kesukubangsaannya secara membumi, dia
menggunakan kasus-kasus masyarakat negara di Eropa, yang dilihatnya secara
makro. Apa yang terabaikan dalam kajian Jenkins seperti tersebut di atas
adalah batas-batas sukubangsa yang ditekankan pentingnya oleh Frederik
Barth. Batas-batas sukubangsa yang terwujud sebagai arena-arena interaksi
2 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
yang terwujud dalam birokrasi, dalam tempat-tempat umum-lokal serta pasar,
yang mewujudkan adanya macam kebudayaan dominan atau bukan dominan
pada tingkat makro (Bruner 1974: 251-280), yang mempengaruhi dan bahkan
dalam beberapa hal menentukan corak jati diri dari para pelakunya (Suparlan
1995).
Permasalahan lainnya yang juga tercakup dalam kajian Jenkins (1997)
tersebut di atas adalah sorotannya mengenai primor- dialitas yang dikemukakan
oleh Clifford Geertz (1973b: 268, 306), yang dilihat oleh Jenkins (1997:13,41)
sebagai sama dengan kesukubangsaan. Padahal, dalam tulisannya tersebut
Clifford Geertz sama sekali tidak berbicara mengenai kesukubangsaan, walaupun
dia memang menyinggung masalah etnosentrisme di dalam pembahasannya
mengenai teori kebudayaan (1973a: 4), tetapi etnosentrisme berbeda atau tidak
sama pengertiannya dari pengertian kesukubangsaan atau ethnicity. Yang
dibicarakan oleh Geertz (1973b: 250) adalah primordialitas atau ikatan-ikatan
primordial, yang didefinisikannya sebagai 'sesuatu yang berakar pada sesuatu
yang 'sudah takdirnya' (given) atau....di mana seseorang terikat secara moral
oleh berbagai rasa tanggungjawab yang timbal balik pada anggota-anggota
kerabatnya, tetangganya, sesama penganut agamanya, .... setidak-tidaknya
primordialitas tersebut sebagian terbesar terwujud oleh adanya kesadaran moral
atas sesuatu kemutlakan yang penting atau utama yang dapat diperhitungkan
secara untung rugi semata-mata, yang diatributkan pada ikatan dirinya
sendiri'. Dengan kata-kata yang lebih sederhana, Geertz (1973b: 268)
mengartikan primordialitas sebagai 'sebuah dunia jati diri perorangan atau pribadi,
yang secara kolektif diratifikasi dan secara publik diungkapkan, yang merupakan
sebuah keteraturan dunia'. Primordalitas adalah sesuatu yang utama, atau
primordial, yaitu perasaan yang dipunyai orang perorang, berkenaan dengan
keha- dirannya dengan kehidupannya di dunia ini sebagai suatu takdir bahwa
dia dilahirkan dan dibesarkan dalam suatu lingkungan keluarga dan kerabat,
keyakinan keagamaan, bahasa, berbagai adat serta sistem-sistem makna yang
ada dalam kebudayaannya, yang dirasakan sebagai dunia kehidupannya yang
utama karena tidak dapat terpisahkan dari dirinya, bukan hanya dalam hal-hal
yang rasional tetapi juga mencakup keseluruhan rasa yang dipunyainya. Konsep
primordialitas ini oleh Geertz 1973b: 256-310) digunakan untuk memahami
proses-peoses integrasi nasional yang terjadi di negara-negara yang sedang
terbentuk atau berkembang pada beberapa dekade yang lalu, di mana negara
yang dibangun berdasarkan prinsip -prinsip ideologi atau keyakinan nasionalisme
serta negara secara utuh, karena adanya ikatan-ikatan atau sentimen-sentimen
primordial yang dipunyai oleh warganya secara orang perorang yang terungkap
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 3
secara kolektif dan sosial.
Apa yang menarik dari interpretasi Jenkins (1997: 47-79) yang melihat
primordialitas sama dengan kesukubangsaan, adalah penolakannya terhadap
konsep primordialitas, yang mengikuti pendapat berbagai ahli lainnya sebagai
sebuah konsep yang obsolete, karena dia melihat bahwa primordialitas
sebenarnya tidaklah primordial (utama) tetapi primer (pertama), sebagai hasil
dari sosialisasi pada tahap-tahap pertama (primary socialization) dari kehidupan
seseorang. Karena itu, menurut pendapatnya tersebut, konsep primordialitas
dapat dilupakan begitu saja. Apa yang dikemukakan oleh Jenkins tersebut
harus dilihat dalam perspektif metodologi atau pendekatan yang digunakannya.
Kalau permasalahan kesukubangsaan hanya akan dilihat dalam kaitannya
taksonomi jati diri serta dilihat dengan kaitannya dengan berbagai permasalahan
jati diri, termasuk ras, seperti yang telah dilakukan oleh Jenkins, maka
primordilitas memang menjadi sesuatu yang obsolete. Tetapi bila
kesukubangsaan dan primordilitas dilihat dari perspektif para pelakunya di
dalam melihat dan menginterpretasi dunia atau lingkungan yang dihadapinya, di
mana perasaan-perasaan yang mendasar dan umum yang dianggap para pelaku
tersebut adalah sebagai yang utama, yang digunakannya sebagai sistem-sistem
acuan (reference systemm) yang selektif penggunaannya dalam mewujudkan jati
diri atau kesukubangsaan dalam interaksi bagi mempertahankan sesuatu
kehormatan ataupun memenangkan sesuatu dalam persaingan sumberdaya,
maka primordialitas bukanlah sesuatu yang obsolete, dan utama atau primordial
karena tidak dilihat sebagai proses primer dari sosialisasi, tetapi menjadi bagian
dari proses-proses terwujudnya jati diri dan batas-batas sukubangsa.
Saya akan menggunakan konsep kesukubangsaan dan primordialitas untuk
menjelaskan kasus ketidakberhasilan Program Ayam dari Dinas Peternakan
Propinsi Irian Jaya yang diselenggarakan di desa Mwapi, Kelurahan Wania,
Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Irian Jaya. Apa yang ingin saya
tunjukkan adalah bahwa konsep kesukubangsaan dan konsep primordialitas
adalah dua buah konsep yang sebenarnya berbicara mengenai sebuah
permasalahan yang sama, dan selalu ada dalam setiap gejala sosial dalam
kehidupan sebuah masyarakat yang tidak mengenal atau memahami makna-
makna dari konsep-konsep masyarakat dan negara serta berbagai konsep lainnya
yang berkaitan dengan itu. Walaupun kesukubangsaan dan primordialitas tersebut
berbicara mengenai masalah yang sama, tetapi, masing-masing mempunyai
penekanan dan implikasi ruang lingkup permasalahan yang berbeda dan yang
karena itu pendekatan taksonomik yang digunakan oleh Jenkins seperti tersebut di
atas menjadi tidak relevan.
4 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
Latar belakang
Warga desa Mwapi adalah Orang Kamoro yang dalam kepustakaan
antropologi dikenal dengan nama Orang Mimika (Pouwer 1955). Kebudayaan
Orang Kamoro yang dideskripsikan oleh Pouwer lebih dari 40 tahun yang lalu,
pada dasarnya masih berlaku bagi umumnya Orang Kamoro di Kabupaten
Mimika (Trenkenschuh 1970; Widjojo 1997), dan bagi Orang Kamoro yang
tinggal di desa Mwapi (Suparlan 1996a, 1996b, 1997a, 1997b, dan juga 1997c).
Desa Mwapi terletak di sebelah timur kota Timika, termasuk kelurahan Wania,
Kecamatan Mimika Timur. Desa ini dibangun oleh Dinas Sosial Propinsi pada
tahun 1982, di sebidang tanah hak adat Orang Kaugapu yang telah diserahkan
kepada Dinas Sosial Propinsi Irja. Di sebelah utara desa Mwapi terdapat
sungai Kauga, di sebelah selatan dibatasi oleh jalan raya yang menghubungkan
kota Timika dengan Mapura Jaya yang menjadi ibu kota kecamatan Timika
Timur. Warga desa Mwapi berasal dari warga masyarakat desa Muare Lama
dan Pigapu Pantai yang tinggal tersebar di tepi-tepi pantai dan rawa-rawa di
muara sungai Kamaro. Penduduk desa Mwapi, jika dilihat asal muasalnya
adalah keluarga-keluarga yang tergolong dalam salah satu dari dua taparu yang
ada di desa Mwapi, yaitu: Muare dan Pigapu. Bahkan nama Mwapi
sebenarnya adalah gabungan dari singkatan nama Mua (Mwa) dan Pi singkatan
dari Pigapu.
Walaupun kebudayaan Orang Kamoro di desa Mwapi dan di Timika pada
umumnya memperlihatkan pola-pola yang sama dengan yang dipunyainya
kira-kira empat puluh tahun yang lampau, seperti dinyatakan di atas, tetapi
sesungguhnya kebudayaan mereka ini telah mengalami perubahan yang tidak
kecil. Perubahan ini terutama disebabkan oleh PT Freeport-Indonesia (PTFI)
yang melakukan penambangan tembaga dan emas di daerah pegunungan
Grassberg dan dibangunnya kota serta pelabuhan pertambangan di Timika.
Penambangan yang dimulai pada tahun 1973 dan mulai berkembang pesat sejak
akhir tahun 1980an membawa dampak masuknya pendatang-pendatang
spontan dari luar Timika dan dari luar Irian Jaya. Bersamaan dengan ini
masuk dan mantapnya sistem ekonomi uang ke dalam kehidupan Orang
Kamoro, meningkatnya kebutuhan-kebutuhan konsumsi serta kebutuhan-
kebutuhan kehidupan lainnya yang harus dipenuhi sementara kemampuan
produktif mereka untuk dapat dipasarkan secara relatif adalah tetap sama
dengan kemampuan produktif mereka sebelumnya. Kondisi yang mereka
punyai ini telah menyebabkan mereka di satu pihak ingin mengejar
kemampuan dan kemakmuran yang berada di depan mereka serta mereka
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 5
hadapi sehari-hari tetapi di lain pihak mereka itu menjadi putus asa karena
ketidak mampuan untuk meraihnya dan karena itu hidup dengan mengikuti
pola-pola kebudayaan secara tradisional berlaku dalam kehidupan mereka.
Semakin besar dan berkembangnya PTFI dan semakin mantapnya kekuasaan
pemerintah Republik Indonesia di Timika berdampak pada semakin sadarnya
Orang Kamoro, termasuk warga desa Mwapi, akan ketergantungan
kehidupan mereka pada pemerintah. Bagi mereka PTFI dan pemerintah adalah
memberi rezeki atau kemakmuran dan tempat menggantungnya nasib kehidupan
mereka. Bagi mereka pemerintah adalah kekuasaan yang dapat menghancurkan
mereka tetapi juga pemberi hadiah-hadiah yang murah hati, pemaaf, dan yang
harus disenangkan hatinya.
Jumlah penduduk Kamoro di Mwapi pada tahun 1996 ada 608 orang,
yang terdiri atas 95 keluarga. Di antara penduduk Kamoro di desa Mwapi
terdapat 29 keluarga, atau 155 orang, yang tinggal di permukiman sementara di
dekat peternakan sapi "Pangan Sari", yang terletak di sebelah barat dari kota
Timika. Mereka ini, yaitu orang dewasa dan kepala keluarga bekerja di
perusahaan peternakan tersebut. Di samping Orang Kamoro yang menjadi
penduduk desa Mwapi, juga terdapat warga desa tersebut yang berasal dari
luar Kamoro. Jumlah mereka ada 4 keluarga atau 29 orang, yang berasal dari
Kei yang hidup di desa tersebut sebagai guru SD setempat atau ikut keluarga
guru tersebut. Jumlah warga taparu Muare dibandingkan dengan jumlah warga
taparu Pigapu yang tinggal di desa tersebut kira-kira sama dengan 70%
dibanding 30%. Masing-masing anggota atau keluarga hidup mengelompok
dalam lingkungan taparunya sendiri. Sehingga, bila kita berkunjung ke desa
Mwapi, terdapat kesan bahwa desa tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
di bagian sebelah barat desa Mwapi adalah rumah-rumah dan pekarangannya
yang dihuni oleh keluarga taparu Muare dan di bagian sebelah timurnya
adalah hunian dari para warga taparu Pigapu. Kepala desa Mwapi berasal dari
taparu Muare, yang terpilih sebagai kepala desa karena jumlah pemilih asal
taparu Muare lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih dari taparu
Pigapu.
Mata pencaharian utama mereka adalah memangkur sagu, menangkap
ikan dan kerang serta kepiting di sungai, rawa-rawa, dan di tepi pantai, meramu
hasil hutan, berburu dan menjerat babi hutan serta burung, dan berkebun.
Bercocok tanam bukanlah mata pencaharian utama mereka tetapi mereka itu
membuat kebun atau ladang juga walaupun tidak baik perawatannya. Hutan
yang telah ditebangi atau bekas kebun lama yang telah ditebang dan ditebasi
6 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
semak belukarnya, ditanami pohon pisang, ubi kayu, ubi manis, keladi, pepaya,
dan tembakau. Mereka tidak mengenal konsep tebas-bakar dalam pembuatan
ladang atau kebun. Ta naman-tanaman tersebut setelah tumbuh lalu
ditinggalkan, dan pada waktu menurut perki- raan mereka telah ada tanaman
yang pantas dipanen maka mereka datang ke kebun. Rumah-rumah mereka
biasanya dibangun di tepi sungai tidak jauh dari kebun-kebun mereka atau di
tepi pantai, begitu juga kebun-kebun mereka itu biasanya dibuat di tepi-tepi
sungai, di daerah-daerah yang kering atau tidak berpaya.
Secara tradisional mereka itu hidup mengelompok dalam satuan
kekerabatan yang dinamakan taparu atau klen, yang pada dasarnya mengikuti
prinsip matri-bilateral, yang juga merupakan sebuah kesatuan hidup teritorial,
yang terdiri atas beberapa keluarga atau fam, yang merupakan sebuah
perkampungan atau desa. Menurut keterangan kepala desa Mwapi, Orang
Muara berasal dari desa Muare Lama, yang dibangun oleh pemerintah penjajahan
Belanda pada tahun 1953 untuk memukimkan keluarga-keluarga yang
tergolong dalam taparu-taparu yang termasuk suku Mauripi. Keberadaan dan
kelestarian sebuah taparu tidak langgeng. Sesuai dengan konteksnya, sebuah
keluarga atau fam atau sebuah kampung dapat berubah menjadi sebuah taparu,
tergantung pada pentingnya fam atau keluarga tersebut bagi pengorganisasian
kehidupan sosial untuk terwujudnya pengelompokan teritorial atau perkampungan
dapat mensejahterakan kehidupan mereka. Di kampung Muare Lama, sebagai
contohnya, yang terletak di tepi pantai di muara sungai Kamora terdapat
empat buah taparu (Pouwer 1955: 283), yang taparu-taparu tersebut di desa
Mwapi berubah menjadi fam atau hilang diganti dengan nama fam yang lain.
Bahkan, taparu Muare di desa Mwapi sebenarnya adalah nama kampung
Muare Lama yang merupakan tempat hunian teritorial dari pengelompokan
empat taparu, seperti tersebut di atas. Pemerintah jajahan Belanda di Irian
Jaya dan pemerintah Indonesia, mengupayakan supaya kelompok-kelompok
taparu yang kecil jumlah warganya itu dapat bermukim dalam sebuah
'kampung' (jaman pemerintah Belanda) atau dalam sebuah 'desa' (jaman peme-
rintahan Indonesia) secara bersama-sama. Hasil dari kebijaksanaan tersebut,
sebagaimana yang telah kita lihat pada masa sekarang, adalah adanya desa-
desa Orang Kamoro yang dihuni oleh setidak-tidaknya dua taparu, seperti yang
berlaku dalam desa Mwapi.
Hidup dari sagu sebagai makanan pokok dan ikan sebagai lauk utama,
dan sekali-kali menyantap hasil kebun (pisang,singkong, ubu manis, atau
lainnya), nasi dan/atau supermie telah menyebabkan bahwa mereka itu secara
tetap dan terus menerus melakukan perpindahan dari hulu sungai (tempat
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 7
dusun-dusun sagu tempat mereka memangkur sagu), ke muara sungai (tempat
menangkap ikan, kerang, dan kepiting) dan kebun-kebun mereka (antara hulu
dan muara sungai). Sampai sekarang pola kehidupan seperti ini masih mereka
ikuti, termasuk mereka yang telah menjadi warga permukiman transmigrasi
setempat di kabupaten Mimika. Sehingga desa-desa Orang Kamoro hanya
pada waktu-waktu tertentu saja warganya lengkap, termasuk desa Mwapi.
Dalam kehidupan Orang desa Mwapi, dan ini juga berlaku dalam kehidupan
Orang Kamoro pada umumnya, corak keluarga adalah keluarga batih; dan
rumah tangga atau dapur adalah yang utama. Kewajiban terhadap sesama
anggota keluarga adalah dalam tolong menolong bila ada kesusahan, dan
hubungan antara keponakan dengan saudara laki-laki ibu serta hubungan
antara menantu laki-laki dengan mertua adalah lebih penting dari hubungan-
hubungan kekerabatan lainnya. Kasih sayang di antara sesama anggota
keluarga batih serta di antara mereka yang sekerabat adalah yang mengikat
hubungan-hubungan di antara mereka yang sekerabat.
Walaupun demikian posisi seorang individu sebagai perorangan dalam
keluarga adalah unik atau atomistik, yang terwujud dalam berbagai bentuk
kepemilikan individual atas benda-benda berharga untuk sumber-sumber
kehidupan mereka maupun dalam bentuk atribut-atribut untuk jati diri. Masing-
masing anggota keluarga, anak-anak mempunyai kebebasan individual yang
relatif besar dalam mengemukakan pendapat dan dalam kebebasan
melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, termasuk adalam hal kebiasaan
makan. Masing-masing anggota keluarga bila ingin makan, secara bersama-
sama maupun secara sendiri-sendiri dalam waktu yang bersamaan maupun
dalam waktu yang berbeda-beda, mengambil sagu dari tumong atau tempat sagu
mentah yang terbuat dari anyaman daun sagu yang tersimpan di dapur, untuk
membuat sagu bakar sendiri untuk dimakannya sendiri. Hanya anak-anak balita
yang dipersiapkan makanan dan minumannya oleh orang tuanya, terutama oleh
ibunya masing-masing.
Pada masa sekarang, di mana anak-anak harus tinggal di desa untuk
bersekolah sementara orang tua harus pergi memangkur sagu atau mencari ikan,
menjadikan kemandirian anak-anak tetap bagian utama dari sosialisasi. Oleh
orang tua mereka, masing-masing anak diberi satu atau beberapa batang pohon
kelapa untuk mereka ambil buahnya bagi makanan mereka selama orang tua
mereka harus pergi untuk memangkur sagu di dusun sagu 'milik' fam mereka,
fam kerabat mereka, atau milik taparu mereka di hulu sungai, atau pergi
menangkap ikan di pantai selama dua atau tiga minggu. Dalam keadaan
8 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
demikian anak-anak tersebut ikut dengan orang tua mereka, atau bila anak-
anak tersebut harus tetap tinggal di desa untuk bersekolah mereka itu dititipkan
pengawasannya kepada kerabat dekat, sementara sejumlah sagu mentah juga
dititipkan pada kerabat tersebut untuk makanan anak-anak, yang harus mereka
makan dengan cara memasaknya sendiri.
Kemandirian dari orang perorang, mencakup juga kemandirian dalam hal
kerja dan hasil kerja yang menjadi miliknya sendiri, dan tidak perlu dibagikan
sebagian hasilnya kepada orang lainnya. Bahkan dalam kegiatan kerja sama,
prinsip hak kepemilikan perorangan ini tetap berlaku. Banyak contoh-contoh
mengenai hal ini dalam kehidupan Orang Kamoro di desa Mwapi, untuk itu saya
akan mengambil sebuah contoh dalam kegiatan memangkur sagu di hulu sungai
Pika, yang terletak di bagian sebelah utara timur laut dari desa Mwapi.
Sepanjang sungai Pika adalah daerah rawa-rawa yang ditumbuhi oleh
pohon-pohon sagu yang hidup dalam kelompok-kelompok dusun sagu. Masing-
masing dusun sagu ini secara tradisional merupakan milik dari taparu-taparu
dan fam-fam yang pada masa sekarang hidup di desa Mwapi. Perjalanan dari
desa Mwapi ke dusun-dusun sagu tersebut bisa memakan waktu 2-3 hari
dengan menyusuri sungai Kauga ke arah hilir dan kemudian berbelok ke arah
kanan di pertemuan sungai Kauga dengan sungai Pika, lalu terus menyusuri
sungai tersebut ke arah hulu. Rombongan peramu sagu ini biasanya terdiri atas
tiga sampai dengan lima keluarga. Sesampai di daerah sagu yang menjadi hak
adat mereka, masing-masing membersihkan atau memperbaiki gubuk-gubuk
yang sudah ada, yang telah dibangun masa lampau oleh orang-orang tua mereka
masing-masing, untuk tempat menginap. Selama kira-kira dua minggu mereka
tinggal di gubuk-gubuk tersebut, dan masing-masing keluarga (suami isteri
dengan dibantu oleh anak mereka yang sudah remaja, bila ada) berpencar ke
dusun-dusun sagu yang secara adat adalah milik keluarga atau famnya untuk
memangkur sagu, menjerat babi dan burung, dan menangkap ikan untuk lauk
makan mereka. Setelah waktu yang mereka setujui untuk memangkur sagu itu
habis, mereka kembali lagi ke desa Mwapi secara bersama-sama. Masing-
masing dengan perolehan jumlah tumang sagu yang berbeda. Ada yang bisa
mengumpulkan sampai dua puluh lima tumang sagu dan ada yang hanya
mampu mengumpulkan sepuluh tumang sagu saja. Perolehan ini tergantung
pada waktu kerja yang telah mereka curahkan untuk memangkur sagu, atau
untuk kegiatan-kegiatan lainnya, selama mereka berada di dusun sagu
tersebut. Apa yang telah mereka peroleh adalah hak milik mereka masing-
masing, dan tidak ada konsep untuk memberikan sedikit sagu pun bagi mereka
yang sedikit perolehannya. Dengan kata lain, tidak ada konsep gotong royong
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 9
atau bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ada dalam konsep
kebudayaan mereka adalah, bekerja bersama-sama tetapi perolehannya untuk
mereka masing-masing yang mengerjakannya.
Prinsip lain yang mendasar yang ada dalam kebudayaan mereka, sebagai
sesuatu yang teradatkan dan utama dalam kehidupan mereka, yang mereka
namakan ndaitita , atau pedoman bagi kehidupan yang ditentukan oleh dan
diwarisi dari nenek moyangnya yang mereka anggap sebagai yang sakral serta
bersanksi gaib. Prinsip yang utama dalam ndaitita adalah prinsip timbal balik
atau reciprocity, yang mereka namakan aopao. Prinsip timbal balik ini terwujud
di hampir keseluruhan aspek kehidupan mereka, baik dalam hu- bungannya
dengan sesama di dunia yang nyata, maupun dalam hu- bungannya dengan
dunia gaib. Di antara prinsip timbal balik yang menonjol, yang relevan dengan
tulisan ini adalah yang dinamakan nawarapoka yang artinya pembayaran
kembali atas segala sesuatu yang telah diterima dari pemberian oleh pihak
lainnya, yang menghasilkan adanya kegiatan balas membalas pemberian baik
berupa materi maupun berupa jasa-jasa atau pujian. Di samping itu ada prinsip
paiti, yang arti harafiahnya adalah malu. Konsep paiti ini merupakan
pendukung atau pendorong bagi dilaksanakannya aopao atau nawarapoka oleh
para pelaku yang bersangkutan; karena, kalau hanya mau menerima pemberian
saja itu maka hal itu sangat memalukan bagi si penerima di mata para pelaku
lainnya.
Prinsip timbal balik beserta keseluruhan konsep-konsep budaya
pendukung yang mendorong perwujudannya dalam berbagai bentuk tindakan
sehari-hari maupun dalam upacara-upacara, terutama berlaku dalam lingkungan
kerabat dan taparu, atau orang-orang luar kerabat dan taparu yang dianggap
sebagai teman dekat. Contoh tadi dilaksanakannya prinsip aopao yang terwujud
sebagai nawarapoka yang melibatkan paiti adalah kewajiban pengabdian
menantu laki-laki kepada mertua dan keluarganya. Menantu laki-laki diperlakukan
sebagai sapi perah yang harus menghidupi mertua dan keluarganya, karena
dia telah diberi anak perempuan oleh sang mertua untuk dikawininya, atau untuk
menjadi isterinya. Apa yang menarik dari prinsip aopao, yang juga berlaku di
hampir semua kebudayaan sukubangsa di Irian Jaya, adalah bahwa imbalan
atau pembayaran tersebut harus dituntut, yaitu dengan cara mengingatkan
bahwa kalau tidak dilakukan pembayaran nawarapoka maka hal itu
memalukan (paiti), dan kalau tidak juga dilakukan nawarapoka atau imbalam
pembayaran oleh orang yang menerima pemberian walaupun sudah
dipermalukan, maka si pemberi merasa dipermalukan dan untuk menghapus rasa
malu tersebut maka si pemberi akan mengimbanginya dengan cara melakukan
10 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
pembalasan, dengan menggunakan berbagai cara tenung atau sihir.
Dari uraian tersebut di atas corak masyarakat desa Mwapi serta Orang
Kamoro pada umumnya adalah egalitarian. Yaitu sebuah masyarakat yang
relatif tidak mempunyai sistem penjenjangan secara formal (Fried, 1967), dan
karena itu secara relatif terdapat kesamaan dalam hak dan kewajiban dari
individu-individu warga masyarakatnya. Individu-individu mempunyai ciri-ciri yang
atomistik. Hubungan-hubungan di antara sesamanya terikat melalui berbagai
sistem kekerabatan yang berdasarkan atas pilihan-pilihan pribadi dan diatur
berdasarkan atas prinsip timbal balik. Kemunculan tokoh atau orang yang
berprestasi (we ayku) mulai ada dalam sejarah kebudayaan Orang Kamoro,
tetapi konsep we ayku ini punah bersama dengan mantapnya kekuasaan
penjajahan Belanda di Timika yang menekankan kekuasaan administrasi desa
dengan kepala desa yang ditunjuk. Pada masa sekarang seorang kepala
desa, yang dipilih oleh warga desa, bukanlah seorang we ayku. Kepala desa
dipilih oleh warga desa karena dia adalah anggota taparunya atau karena dia
kerabat dari anggota taparunya, dalam persaingannya dengan calon kepala
desa lainnya yang ada adalah anggota taparu lain.
Orang Mwapi dan orang-orang luar
Dalam kehidupan Orang Mwapi hanya anggota keluarga dan kerabat
yang tergolong sebagai taparu mereka yang dapat mereka percayai, mereka
mintai tolong, dan hidup dengan prinsip timbal balik atau aopao, yang mereka
golongkan sebagai orang-dalam, sebagai lawan dari kategori orang-luar. Di luar
kategori tersebut semua orang digolongkan sebagai orang-luar. Anggota-
anggota taparu lainnya, yang sama sekali tidak ada hubungan kekerabatan
malalui hubungan perkawinan, yang hidup bersama dalam satu desa, juga
digolongkan sebagai orang-luar. Konsep orang-dalam lawan orang-luar tidak
terwujud sebagai sebuah konsep tersendiri, tetapi ada dalam konsep umum we
yang artinya manusia. Tercakup dalam konsep we ini terdapat konsep yang
mendasar yang dinamakan iwoto atau manusia yang beradab yang mengenal
kasih sayang sebagai manusia yang dibedakan dari orang-luar atau juga dari
hewan. Tidak adanya konsep orang-luar sebagai sebuah konsep kebudayaan
tersendiri, dalam khazanah tradisi budaya mereka, mungkin disebabkan oleh
keberadaan orang-luar yang menurut mitologi mereka sebenarnya berasal dari
mereka sendiri yang telah mengembara meninggalkan mereka dan sekarang
kembali sebagai anak cicit nenek moyang tersebut. Orang-luar tersebut
biasanya dilihat sebagai orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 11
pengetahuan, teknologi, dan kekayaan yang membuat mereka tunduk atau
mengalah karenanya. Konsep orang-luar, sebagaimana yang sekarang ada dalam
kebudayaan mereka, secara tradisional justru mengacu pada penggolongan
berdasarkan perbedaan pengelompokan secara kekerabatan, berdasarkan atas
perbedaan asal taparu dan desa atau kampung.
Dalam sistem penggolongan masa kini yang dipunyai oleh Orang Mwapi
mengenal orang-luar, golongan yang paling luar adalah orang-orang pendatang
dari luar Irian Jaya yang mereka tandai berdasarkan atas ciri-ciri fisik dan
kebudayaannya. Selanjutnya, secara berturut-turut, sistem penggolongan orang-
luar mencakup para pendatang dari berbagai asal sukubangsa di Irian Jaya,
orang-orang Kamoro dari desa-desa lainnya, orang-orang yang berasal dari
taparu lain tetapi menjadi warga desa yang sama, orang-orang dari fam atau
keluarga luas yang matri-bilateral lain tetapi berasal dari taparu yang sama,
orang-orang dari rumah tangga atau keluarga batih lainnya tetapi masih berada
dalam satu famatau keluarga luas, dan terakhir adalah individu atau perorangan
lainnya di luar dirinya walaupun masih sesama anggota rumahtangga atau
keluarga batih. Konsep mengenai orang-luar yang tercakup dalam berbagai
golongan tersebut seringkali dikacaukan oleh pentingnya hubungan perorangan
di antara mereka dengan orang-luar. Hubungan-hubungan perorangan yang
dekat dapat meniadakan batas-batas serta jarak-jarak sosial yang jauh yang
seharusnya terwujud sesuai dengan sistem penggolongan tersebut.
Pengalaman-pengalaman menghadapi orang-luar, yang di satu pihak menguntungkan kehidupan ekonomi sehari
mereka, lain juga mereka rasakan sebagai merugikan kehidupan mereka secara menyeluruh, telah membuat merek
tidak berani untuk menentang atau mela wannya. Trenkenschuh (1970) telah membahasnya serta menyimpulkan
bahwa kebudayaan orang Kamoro telah dihancurkan sebagai akibat hubungan-hubungan mereka dengan par
penyebar agama Katolik, dengan sistem penjajahan Belanda yang menuntut pajak dan kerja rodi, dan dengan penjaja
Jepang yang lebih kejam lagi. Yang mereka punyai sekarang adalah rasa rendah diri serta tidak percaya diri dalam
menghadapi orang-luar, dan untuk membangkitkan rasa percaya diri tersebut mereka lari ke minuman beralkoho
Selama penelitian saya di lapangan, saya mengamati kebenaran pendapat Trenkenschuh tersebut dalam bentuk gejala
gejala pemabokan yang umum berlaku dalam kehidupan mereka. Tetapi saya juga melihat adanya kemampuan Orang
Kamoro, terutama di desa Mwapi untuk menyembunyikan kelemahan tersebut dengan cara berlaku sopan dalam
menghadapi orang-luar. Gejala tersebut terutama dapat diamati dalam hubungan mereka dengan para pejabat yang
biasanya datang untuk memberi hadiah-hadiah kepada mereka, berkomunikasi dengan para tamu pejabat yang datang
berkunjung dengan menggunakan idiom-idiom sesuai dengan kategori pejabat atau orang-luar yang mereka hadap
tersebut (hal ini juga dikemukakan oleh Widjojo (1997) dalam pembahasannya mengenai hubungan Orang Kamoro
dengan orang-luar). Karena itu Orang Kamoro memberikan kesan sebagai golongan sukubangsa di Kabupaten
Timika, yang dapat dibedakan dari ciri-ciri kebudayaan suku-sukubangsa lainnya, karena mereka ini berpenampila
12 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
sopan, penurut, dan indecisive atau tidak mempunyai ketegasan dalam memutuskan sesuatu masalah. D
ciri Orang Kamoro mirip dengan stereotip yang dikenakan pada Orang Jawa yang dikatakan, kalau meny
sesuatu suruhan dari atasan adalah dengan cara mengatakan inggih (ya) tetapi tidak dikerjakan, padaha
ingin menyatakan mboten (tidak). Atau menyatakan mbesuk (besok), padahal artinya bisa kapan sa
tersebut tidak pernah dikerjakan.
Berkaitan dengan performansi dalam interaksi dengan orang-luar
tersebut, kemampuan memainkan peranan sebagai pemain panggung pada
Orang Mwapi juga cukup tinggi. Apa yang dikemukakan dalam rapat-rapat atau
pertemuan-pertemuan desa dengan pejabat yang datang berkunjung biasanya
hanya basa-basi untuk memuaskan ego para pejabat yang bersangkutan. Kecuali
bila dia atau mereka itu tahu bahwa si pejabat atau si pengunjung itu
mengetahui seperti apa sebenarnya isi dari kebudayaan atau ndaitita yang
mereka punya itu. Dalam keadaan demikian itu biasanya tidak lagi dapat
menjadi pemain panggung (front stage), tetapi sebaliknya mereka itu akan
bertindak biasa sebagai Orang Kamoro yang mengungkapkan keadaan
sebenarnya mengenai kehidupan mereka (back stage), bila kita menggunakan
model interaksi dari Goffman (1959) di dalam kita memahami gejala -gejala
tersebut. Gejala lain yang saya amati dari dampak hubungan dengan orang-luar
yang menyebabkan mereka menjadi merasa rendah diri adalah, mengatasi
rasa rendah diri mereka dengan cara melarikan diri ke dalam dunia Kamoro
atau ndaitita yang mereka ciptakan atau bangun kembali, baik secara sadar
ataupun secara tidak sadar. Mereka menekankan kembali pentingnya hidup
subsistensi yang berpindah-pindah dari hulu sungai ke tepi pantai dan tepi pantai
ke kebun, yang mereka lakukan secara terus menerus dan berulang-ulang dari
waktu ke waktu, dan dari satu generasi berikutnya. Dengan cara-cara tersebut,
mereka itu merasa memperoleh kebebasan pribadi dari berbagai perasaan
tertekan secara sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi sehari-hari.
Melalui cara-cara hidup seperti tersebut di atas, mereka menciptakan
serta menghidupkan kembali ikatan-ikatan primordial yang telah dihancurkan oleh
pemerintah jajahan Belanda dan Jepang dan oleh gereja. Keluarga, kerabat, dan
taparu adalah yang utama dalam kehidupan mereka; dan, kesemuanya itu
didukung oleh serta mendorong terwujudnya kegiatan-kegiatan sosial,
ekonomi, dan politik yang menekankan pentingnya ikatan-ikatan primordial
tersebut. Dalam dunia yang primordial, yang mereka bangun kembali inilah
mereka merasa menjadi manusia kembali.
Karena itu, saya tidak menjadi kaget pada waktu saya mengamati adanya
perdebatan dan pertengkarang yang cukup sengit di antara sesama warga
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 13
taparu Muare berkaitan dengan masalah nawarapoka dan paiti berkenaan
dengan macam serta besarnya sumbangan pada kerabat untuk mas kawin salah
seorang warga yang akan kawin dengan seorang wanita asal Asmat. Saya juga
tidak heran pada waktu terjadi pertengkaran antara seorang warga taparu
Muare dengan warga taparu Pigapu berkenaan dengan sejarah nenek moyang
mereka dan hubungan-hubungan yang terjadi di masa lampau di antara
nenek moyang tersebut dalam kaitannya dengan penguasaan dan hak-hak atas
dusun-dusun sagu dan wilayah-wilayah penangkapan ikan mereka. Masalah-
masalah ini, di mata mereka sekarang ini, bukanlah masalah sepele, tetapi
sebuah masalah berkenaan dengan jatidiri dan atribut-atribut kehormatan bagi
jatidiri tersebut. Saya tertawa dan bersamaan dengan itu mengajak pastor dari
paroki Mapurujaya, yang juga menjadi pastor dari Orang Mwapi, untuk
memahaminya pada waktu dia bercerita bahwa pada suatu hari di tahun 1994,
pada waktu masa Paskah, ada sejumlah warga desa yang justru secara
sembunyi-sembunyi melakukan upacara mbi (patung nenek moyang) sebagai
patung bis pada Orang Asmat.
Program Ayam dan kelompok masyarakat
Pada suatu hari di bulan September 1996, seorang petugas dari Dinas
Peternakan Propinsi Irian Jaya menemui saya di Kantor Perwakilan
Departemen Transmigrasi dan PPH di Timika. Dari staf Kantor Perwakilan
Departemen Transmigrasi dan dari warga masyarakat desa Mwapi dia
mengetahui bahwa saya sedang mengadakan penelitian di desa Mwapi dan
Kaugapu. Petugas Dinas Peternakan Propinsi tersebut mengatakan bahwa dia
datang dari Jayapura ke Timika dengan membawa 352 ekor ayam buras yang
diangkutnya dengan pesawat Merpati. Bersamaan dengan ayam tersebut juga
dibawanya persediaan makanan-jadi berupa pelet, serta obat-obatan anti
penyakit ayam. Dia meminta pendapat saya mengenai Program Ayam ini.
Saya katakan sangat bagus sebab akan membantu meningkatkan mutu gizi
makanan warga desa Mwapi, akan menguntungkan secara ekonomi, dan akan
meningkatkan kemampuan warga desa tersebut dalam berpikir secara ekonomi
yang berorientasi ke pasar. Saya katakan, segera saja dibagikan keseluruhan
ayam tersebut kepada seluruh keluarga yang menjadi warga desa Mwapi, secara
merata dan adil, berikut pelet atau makanan-jadi ayam, serta obat-obatan. Dan,
jangan lupa untuk memberi petunjuk-petunjuk pemeliharaan ayam yang sehat
dan menguntungkan, secara terperinci dan sejelas-jelasnya kepada mereka,
petunjuk-petunjuk cara membuat pelet, dan cara pengobatannya bila ayam
14 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
diserang penyakit. Dan, mungkin untuk selama kira-kira satu bulan, sebaiknya
tinggal di desa, Mwapi, dan betul-betul mensupervisi pemeliharaan aya m
tersebut secara perorangan, dari satu keluarga ke keluarga lainnya secara
keseluruhan.
Tetapi, kemudian dia mengatakan bahwa cara pemberian atau bantuan
ayam kepada warga desa Mwapi tidaklah seperti yang saya bayangkan.
Menurut dia Program Ayam ini adalah sebuah program pembangunan ayam
yang bergulir. Artinya di desa Mwapi dibentuk sebuah kelompok masyarakat
yang akan mengelola ayam tersebut di bawah pimpinan kepala desa Mwapi.
Setelah satu atau dua tahun, yaitu setelah ayam tersebut berkembang biak
menjadi banyak, maka akan dibentuk sebuah kelompok masyarakat lainnya untuk
pemeliharaan ayam di desa Kaugapu atau desa-desa lainnya secara bergiliran,
dengan menggunakan hasil pembiakan kelompok masyarakat ayam tersebut.
Saya katakan bahwa bila cara kelompok masyarakat yang akan digunakan untuk
memelihara dan mengembang biakkan ayam, maka dia akan gagal. Terkecuali
bila dia sendiri yang memimpin pembentukan kelompok masyarakat dengan
dibantu oleh kepala desa Mwapi, sampai kelompok masyarakat untuk
pemeliharaan ayam tersebut telah betul-betul mantap mekanisme kerjanya;
setelah itu baru dia tinggalkan. Untuk itu paling tidak akan harus memerlukan
waktu selama satu tahun pembinaan dan pembimbingan yang disertai dengan
kerja keras secara mental dan fisik, baik oleh penyuluh atau pembimbingnya
maupun oleh warga setempat. Terutama bagi warga masyarakat setempat
keberadaan serta mekanisme kerja kelompok masyarakat tersebut akan berubah
keseluruhan pola-pola kebudayaan subsistensi dan berpindah-pindah secara
berkala dari hulu sungai (dusun sagu) ke pantai (menangkap ikan) atau ke rawa-
rawa, dan ke desa (menengok anaknya yang sekolah, menjual hasil perolehan,
atau menikmati waktu istirahat) serta kebunnya (memetik hasil kebun).
Alasannya adalah, karena Orang Kamoro, mencakup juga Orang Kamoro
di desa Mwapi, tidak mengenal konsep masyarakat atau negara, sebagaimana
yang seharusnya, dan karena itu tidak mempu-nyai konsep untuk bekerja
bersama -sama tetapi untuk diri sendiri masing-masing. Saya berikan contohnya
kegagalan program IDT di desa Mwapi, dan desa-desa lainnya di kabupaten
Timika yang menggunakan model kelompok masyarakat. Tetap dia
mengatakan bahwa 'itu kan IDT'. Yang jelas dia tidak mempercayai kata-kata
saya. Setelah menyerahkan ayam berikut makanan dan obat-obatan ayam
kepada kepala desa Mwapi, dia segera berangkat kembali ke Jayapura. Dia
menyerahkan seluruh permasalahan pemeliharaan ayam tersebut, dari mulai
pembentukan kelompok masyarakat sampai dengan cara-cara pembuatan
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 15
kandang serta pemeliharaan ayam dan perawatan pengobatan ayam yang sakit
tersebut kepada kepala desa Mwapi yang telah dibekalinya dengan petunjuk-
petunjuk yang cukup. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan kembali pada
akhir bulan Oktober nanti, untuk berkonsultasi lagi dengan saya.
Pada akhir bulan November 1966 dia berada kembali di Timika dengan
membawa ayam serta berbagai perlengkapan pemeliharaannya untuk Orang
Kamoro di desa Miyoko; dan pada permulaan bulan Desember dia menemui
saya. Kedatangannya di Timika juga dimaksudkan untuk menengok ayam yang
telah dibagikannya kepada warga desa Mwapi. Alangkah kagetnya bapak
petugas peternakan ini. Karena, ayam yang semula berjumlah 352 ekor pada
waktu diberikan kepada desa Mwapi sekarang hanya tinggal 116 ekor. Jawaban
yang diperoleh dari kepala desa dan anggota-anggota kelompok masyarakat
tersebut seragam, yaitu: ada yang dimakan anjing, dibawa lari ular, ada yang
mati karena saling berkela hi, dan ada yang hilang barangkali dicuri orang pada
malam hari. Bapak petugas ini mengeluhkan nasibnya kepada saya dan anggota-
anggota tim penelitian, yang pada waktu itu sedang mentabulasi data kwesioner
di wisma transmigrasi di Timika. Kami mau tertawa tetapi kami tahan,
karena kasihan membayangkan nasibnya yang harus membuat
pertanggungjawaban kepada atasannya, karena jumlah ayam yang seharusnya
menjadi banyak karena berkembang biak tetapi justru menjadi susut jumlahnya.
Sekarang dia meminta saran saya.
Saya nasehatkan untuk membuat laporan Program Ayam sebagaimana
adanya kepada pejabat yany menjadi atasannya, dan kalau dia takut disangka
berbohong saya bersedia membantunya dengan kesaksian saya. Selanjutnya,
dia harus membagikan sisa ayam yang berjumlah 116 ekor tersebut kepada
seluruh keluarga yang pada saat ini berada di desa Mwapi dengan seadil-
adilnya dan merata, sebelum hari Natal. Kalau tidak ayam tersebut akan habis
tidak ketahuan rimbanya. Sedangkan untuk desa Miyoko, sebaiknya dia
meminta kepala desa Miyoko untuk memerintahkan kepala -kepala keluarga
segera membuat kandang ayam yang baik dan kuat untuk ayam-ayam yang
akan mereka terima. Lalu, ayam-ayam yang mereka bawa tersebut dibagikan
secara adil dan merata kepada semua keluarga -keluarga yang menjadi warga
desa Miyoko. Bersama dengan itu dia juga harus juga memberikan petunjuk-
petunjuk pemberian makanan kepada ayam, pembuatan makanan ayam, dan
cara-cara pengobatan bila ayam-ayam tersebut terserang penyakit.
Sebenarnya, apa yang terjadi di desa Mwapi pada waktu ayam-ayam
tersebut akan diserahkan kepada kepala desa jauh lebih kompleks dari pada
hilangnya ayam-ayam tersebut. Pada waktu kepala desa Mwapi mendapat
16 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
berita bahwa desanya akan mendapat ayam, dan untuk itu dia diminta oleh
petugas peternakan tersebut untuk membuat kelompok masyarakat, dia merasa
senang. Kepala desa telah berpengalaman dalam membuat kelompok masyarakat
dan memberdayakannya untuk kepentingan anggota-anggotanya dalam
program IDT, walaupun program IDT itu tersendiri bangkrut. Untuk
kepentingan penerimaan ayam serta pemeliharaannya tersebut, dipanggilnya 20
kepala keluarga, yang kesemuanya adalah dari taparu Muare, yang sebagian
besar adalah kerabat-kerabat dekat istrinya dan sisanya adalah kerabat-
kerabatnya atau teman-teman dekatnya yang mempunyai hubungan-hubungan
aopao dan nawarapoka. Para anggota kelompok masyarakat tersebut
kemudian secara bersama-sama diberi tugas oleh kepala desa untuk
memperbaiki kandang-kandang ayam dan pagar bambu yang mengelilingi
kandang-kandang tersebut, bekas atau sisa peninggalan program ayam IDT,
yang letaknya di wilayah hunian taparu Muare dari desa Api. Ketika ayam
diserahkan kepada kepala desa, langsung dimasukkan ke dalam kandang
ayam. Bapak petugas merasa senang karena merasa bahwa ayam-ayam yang
diserahkannya tersebut akan menjadi ayam bergulir, karena melihat bahwa
kandang ayam telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dengan keyakinan
akan keberhasilannya, dia meninggalkan desa Mwapi dan Timika untuk kembali
ke Jayapura.
Pada waktu kepala desa Mwapi menyampaikan berita kepada
perangkat desa, yang juga anggota-anggota kerabatnya, sedangkan perangkat
desa yang bukan kerabatnya atau yang bersal dari taparu Pigapu tidak diberi
tahu mengenai program ayam ini, bahwa mereka akan menerima ayam dari
Dinas Peternakan Propinsi untuk program pembangunan ayam, ada juga
anggota-anggota dari taparu Pigapu yang mendengarnya. Beberapa orang dari
taparu Pigapu yang merasa dirinya sebagai tokoh atau pimpinan taparu
tersebut mendatangi kepala desa dan meminta agar mereka juga diberi bagian.
Kepala desa mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukannya. Dengan
mengutip kata-kata bapak petugas peternakan dia mengatakan kepada mereka
yang mewakili taparu Pigapu, bahwa ayam ini harus diberikan kepada kelompok
masyarakat yang jumlahnya 20 keluarga. Kelompok masyarakat ini akan
memeliharanya, dan kalau sudah dua tahun ayam-ayam tersebut akan
digulirkan kepada kelompok masyarakat lainnya yang akan dibentuk kemudian.
Untuk pemeliharaan yang berikutnya, kelompok masyarakat tersebut bisa terdiri
atas orang-orang Pigapu. Wakil-wakil dari taparu Pigapu bersungut-sungut
tetapi mereka meninggalkan si kepala desa karena mendengar dia mengutip
kata-kata bahasa Indonesia seolah-olah terdengar seperti kata-kata si bapak
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 17
petugas. Dari kata-kata si kepala desa mereka menyadari bahwa kata-kata dan
makna yang terkandung di dalamnya bukanlah urusan si kepala desa tetapi
urusannya si petugas. Mereka harus berbicara sendiri dengan si petugas.
Beberapa warga taparu Pigapu yang kemudian mendengar bahwa hanya
warga taparu Muare saja yang akan memperoleh ayam menjadi marah.
Menurut keterangan yang saya peroleh, ada yang mabok-mabok dan mencaci
maki kepala desa dan kerabat-kerabatnya. Ada pula yang bertengkar dengan
warga taparu Muare, dan menuduh bahwa kelompok masyarakat bergulir
hanya tipu-tipu kepala desa Mwapi saja. Ada beberapa keluarga, yang karena
merasa tidak dihargai sehubungan dengan perbuatan kepala desa yang hanya
menguntungkan kerabat-kerabatnya yang Orang Muare, lalu pergi ke bekas
desa Pigapu Lama di muara sungai Kamora untuk bermukim dan hidup di situ
dengan cara mencari ikan dan kerang di tempat tersebut yang hasilnya dijual
kepada para tengkulak asal Makassar. Pada waktu permasalahan kelompok
masyarakat yang anggota-anggotanya terseleksi tersebut telah mereda, muncul
lagi masalah baru. Yaitu, siapa sebenarnya yang harus merawat ayam-ayam
tersebut! Karena ada sejumlah anggota-anggota kelompok masyarakat yang
sama sekali tidak mau ikut mengurusi ayam-ayam tersebut, ada juga yang hanya
pura-pura mengurusi tetapi sebenarnya hanya duduk-duduk mengobrol saja
sekitar kandang ayam. Yang merasa benar-benar mengurusi ayam tersebut
menjadi kecewa. Untuk apa berlelah-lelah mengurusi ayam, sedangkan yang
tidak ikut mengurusi nantinya akan juga memperoleh bagian keuntungan dari
kegiatan pemeliharaan ayam tersebut. Lebih baik tidak akan mengurusi, demikian
kira-kira keluhan tersebut.
Sambil menggerutu mereka itu secara sembunyi-sembunyi mulai
mengambil ayam milik kelompok masyarakat tersebut, yang mereka anggap
sebagai imbalan atas jerih payah mereka. Yang melihat perbuatan tersebut
ikut-ikutan juga, karena ayam tersebut sebenarnya ayam yang tidak ketahuan
siapa sebenarnya pemiliknya; sehingga kalau ada yang hilang tidak ada yang
menuntut ganti rugi kepada mereka. Saya sendiri memergoki mereka, dalam
waktu-waktu yang berbeda, menyembunyikan ayam dalam gulungan sarung di
kendaraan umum yang melaju ke pasar Timika. Baru belakangan kepala desa
mengetahui bahwa kelompok masyarakat untuk program pengembangan ayam
ini telah berubah menjadi kelompok masyarakat untuk mengkonsumsi ayam.
Dia tidak bisa berbuat apapun. Mereka itu semua adalah kerabatnya. Dia
terikat dalam saling hubungan aopoa dan nawarapoka dengan mereka itu
semua. Cara terbaik, menurut pertimbangannya, adalah membuat sebuah
skenario yang masuk akal, untuk melindungi kerabat-kerabatnya yang anggota
18 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
kelompok masyarakat ayam tersebut, dengan cara menyalahkan anjing, ular,
penyakit, dan pencuri yang tidak diketahui siapa adanya. Dengan cara ini dia
menyelamatkan dirinya sendiri dari rasa malu dalam menghadapi anggota-
anggota taparu Pigapu. Sedangkan dalam menghadapi petugas peternakan dia
tidak merasa malu, karena menurut keyakinanya, pemerintah masih kaya dan
karena itu tidak akan rugi kalau kalau ayam yang hanya berjumlah sekian itu
hilang. Lagipula, menurut pikirannya, berdasarkan pengalamannya, tugas
pemerintah adalah memberikan hadiah-hadiah kepada rakyatnya terutama
warga desa Mwapi karena baru sedikit yang telah diterima dari pemberian
pemerintah. Bahkan kalau perlu meminta tambahan ayam lagi.
Pembahasan dan kesimpulan
Corak masyarakat desa Mwapi yang egalitarian, di mana tidak ada sistem
penjenjangan sosial yang formal dan di mana berlaku hak-hak dan kewajiban
perorangan yang sama dari semua warga masyarakat dalam kaitannya dengan
kerja, menyebabkan bahwa konsep mengenai masyarakat luas dan/atau negara
tidak ada dalam kebudayaan mereka. Dalam tradisi atau kehidupan sehari-hari
mereka yang berpindah-pindah dalam rotasi secara berkala dan tetap, dengan
mata pencaharian yang taraf ekonominya subsistensi, konsep masyarakat luas
dan negara tidak relevan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Yang lebih relevan
dalam menghadapi lingkungan alam bagi berbagai pemenuhan kebutuhan
kehidupan mereka adalah keluarga, keluarga luas, dan taparu.
Berbagai dorongan untuk pemenuhan kebutuhan bagi kehidupan mereka
atau untuk bertindak bagi mengungkapkan keinginan-keinginan mereka hanya
mungkin terwujud dalam konteks-konteks yang relevan. Konteks-konteks yang
relevan ini mencakup kondisi-kondisi pelaku dan suasana-suasana yang ada dan
yang relevan dari situasi-situasi yang mereka hadapi. Bila dua faktor ini tidak
relevan dengan keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan untuk pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan maka tindakan-tindakan yang mengungkapkan
keinginan-keinginan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut terjadi tidak
terwujud.
Acuan dan mekanisme kontrol dalam kehidupan Orang Kamoro adalah
ndaitita atau kebudayaan mereka yang mereka yakini kebe-narannya dan
kesakralannya yang berasal dari nenek moyang untuk dapat hidup sejahtera
sebagai Orang Kamoro. Sistem-sistem penggolongan, konsep-konsep, teori-teori,
dan paradigma -paradigma yang ada dalam kebudayaan tersebut pada dasarnya
menekankan kehidupan yang egalitarian, menekankan pentingnya hubungan-
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 19
hubungan keseimbangan yang berdasarkan asas timbal balik di antara orang-
perorang dengan mahkluk atau kekuatan gaib, dan dengan lingkungan alam di
mana mereka itu hidup. Segala tindakan, dalam konsep budaya mereka, dari
pengamatan sehari-hari mengenai apa yang mereka lakukan, harus selalu
berada dalam konteks-konteks yang relevan dengan tindakan-tindakan mereka
tersebut. Apa yang tidak ada dalam ndaitita adalah konsep-konsep mengenai
negara berikut kekuasaannya.
Apa yang kritikal dalam kaitannya dengan program ayam dan
pembentukan kelompok masyarakat adalah makna program ayam dan
kelompok masyarakat dalam konteksnya; yaitu, yang mereka lihat sebagai
perwujudan dari kekuasaan pemerintah. Pemerintah yang dapat dan mampu
memaksakan kehendaknya dengan cara halus dan dengan cara kekerasan
serta penghukuman bagi yang menentangnya. Tetapi di lain pihak pemerintah
juga baik hati karena memberikan hadiah-hadiah dan pemaaf kalau suruhannya
gagal karena alasan-alasan yang masuk akal. Konsep mengenai pemerintah
atau kekuasaan pemerintah seperti tersebut di atas, berkenbang dan menjadi
mantap melalui pengalaman-pengalaman orang-orang tua mereka, serta
melalui pengalaman-pengalaman yang mereka alami sendiri. Konsep mereka
mengenai pemerintah tersebut menjadi mantap karena pola-pola tindakan para
pejabat atau petugas dalam berbagai pelaksanaan program pembangunan
memperlihatkan kesamaan-kesamaan sebagaimana yang dilihat dan dialami oleh
Orang Kamoro. Pola -pola tersebut mancakup para pejabat atau petugas itu ingin
mendengarkan kata-kata persetujuan dan pujian mereka yang langsung
diungkapkan secara bertatapan muka. Semua petunjuk dan suruhan di-iya-kan.
Di belakang nanti tidak dikerjakan tidak jadi soal, karena banyak alasan untuk
menjelaskannya, tetapi yang terpenting jangan sampai menyinggung perasaan
para pejabat atau petugas.
Dalam tulisan ini telah saya tunjukkan kegagalan program
pengembangan ayam melalui kelompok masyarakat di desa Mwapi. Melalui
uraian secara sederhana mengenai apa yang terjadi dalam proses-proses
pembentukan kelompok masyarakat dan pengelolaan ayam oleh kelompok
masyarakat tersebut saya perlihatkan bahwa ikatan-ikatan primordial
merupakan acuan utama bagi mengorganisasi diri untuk menguasai sumberdaya
serta pendistribusiannya dan dalam upaya menghadapi dunia-luar yang ingin turut
campur menikmati sumberdaya yang telah berada di tangan mereka. Dalam
menghadapi dunia luar, yaitu pemerintah yang diwakili oleh petugas dan anggota-
anggota taparu Pigapu, ikatan-ikatan primordial tersebut memperkuat solidaritas
pengelompokan kerabat yang pada dasarnya telah terikat oleh saling hubungan
20 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
aopao dan kewajiban nawarapoka. Kepala desa Mwapi yang melihat
permasalahan ini dari perspektif kepentingan dirinya dan kerabatnya, dapat dilihat
sebagai:
(1) Dirinya adalah kelompok kerabatnya, dan kelompok kerabatnya
adalah dirinya. Sebuah hubungan timbal balik yang berupa saling
ketergantungan, yang disadari atau tidak disadari yang menunjukkan bahwa
tanpa dirinya kelompok kerabatnya akan hancur beran- takan, dan kalau
kelompoknya hancur berantakan maka dia juga akan hancur berantakan, karena
yang utama dan satu-satunya sistem acuan yang dikenalnya serta yang
paling dipercayainya dalam kehidupan di desa Mwapi dalam menghadapi
berbagai situasi adalah kelompok kerabatnya. Dengan demikian, gejala -gejala
yang diuraikan dan dibahas seperti tersebut di atas bukanlah sesuatu yang
'primer' yang berlaku di dalam proses-proses sosialisasi sebagaimana
dikemukakan oleh Jenkins dalam bahasannya mengenai konsep primordial dari
Geertz, tetapi sesuatu yang utama, yang berupa perasaan-perasaan serta
keyakinan-keyakinan yang utama yang dipunyai oleh masyarakat-masyarakat
yang hidup dalam suasana keterbelakangan serta tidak mempunyai konsep
masyarakat dan negara di dalam kebudayaan mereka.
(2) Primordialitas, sebagaimana telah dikemukakan oleh Geertz dalam
tulisan ini adalah gejala yang terwujud 'sebagai jati diri perorangan yang secara
kolektif diratifikasi dan secara publik diungkapkan', yang dapat diinterpretasi
bahwa primordialitas adalah gejala perorangan yang berisikan perasaan-
perasaan dan keyakinan-keyakinan mengenai dirinya dan dunianya yang
paling utama, karena mendasar dan umum berkenaan dengan takdir kela -
hirannya dan ketergantungan hidupnya dalam dunianya tersebut. Cara-cara
penanganan kepala desa dalam pembentukan kelompok masyarakat untuk
pengembangan ayam memperlihatkan ciri-ciri tindakan-tindakannya yang
primordialitas. Primordialitas ini juga terungkap dalam tindakan-tindakannya
menangani kehilangan ayam dan kegagalan kelompok masyarakat yang
dipimpinnya.
(3) Batas-batas sukubangsa antara taparu Muare dan Pigapu diperjelas,
dan tidak dapat diseberangi dalam masalah ayam di desa Mwapi, sebagaimana
diuraikan dalam tulisan ini. Siapa kami dan siapa mereka dipertegas
perbedaannya, dan kesukubangsaan atau jatidiri sukubangsa menjadi tampak
sebagai gejala perorangan yang terungkap secara individual maupun secara
kolektif dalam interaksi-interaksi yang digunakan dalam tujuan untuk
memenangkan kompetisi sumberdaya dan kehormatan atau untuk
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 21
mempertahankan sumberdaya yang telah dikuasainya berikut alokasinya.
Dari penjelasan tersebut di atas, kesukubangsaan dan primordialitas
sebenarnya adalah dua konsep yang saling tumpang tindih atau melengkapi.
Untuk itu, kesukubangsaan harus dilihat sebagai gejala perorangan, yang berupa
jati diri yang mengacu pada atri-but-atribut sukubangsa dan kebudayaan dari
pelakunya, yang terungkap dalam interaksi. Primordialitas adalah sentimen-
sentimen atau perasaan-perasaan dan keyakinan yang utama yang mengacu pada
(?) sebagaimana para pelakunya melihat dirinya dan dunianya dalam kaitannya
dengan keluarga, kerabat, sukubangsa dan kebudayaannya. Tanpa sesuatu yang
primordial maka juga kesukubangsaan tidak berarti apa-apa, karena bila
demikian maka sukubangsa adalah sama dengan sebuah kategori sosial yang
umum dan karena itu juga maka kesukubangsaan adalah sebuah jati diri sosial
yang umum. Padahal kesukubangsaan bertahan lama dan mantap dalam
kehidupan masyarakat majemuk atau masyarakat multi-ethnic seperti di
Mwapi, atau di Timika, serta di Irian Jaya dan Indonesia pada umumnya, di
mana permasalahan asal muasal merupakan acuan utama dalam interaksi-
interaksi yang berlaku.
Kepustakaan
Barth, F.
1969 'Introduction' dalam Frederik Barth (ed.) Ethnic Groups and
Boundaries. Boston: Little, Brown, hlm.8-39.
Bruner, E.M.
1974 'The Expression of Ethnicity in Indonesia', dalam Abner Cohen (ed).
Urban Ethnicity. A.S.A. Monograph (12) London: Tavistock, hlm. 251-
280.
Fried, M.
1967 The Evolution of Political Society. An Essay in Political
Antropology. New York: Random.
Geertz, C.
1973a 'Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture', The
Interpretation of Cultures. New York: Basic, hal.3-32.
22 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
1973b 'The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil
Politics in the New States', The Interpretation of Cultures. New
York: Basic, hal. 255-310.
Goffman, E.
1959 The Presentation of Self in Everyday Life. Garden City, N.Y.:
Doubleday Anchor.
Jenkins, R.
1997 Rethinking Ethnicity: Arguments and Exploration.London: Sage.
Pouwer, J.
1955 Enkele Aspecten van de Mimika-Cultuur (Nederlands Nieuw
Guinea). 's-Gravenhage: Staatsdrukerij.
Suparlan, P.
1995 The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society.
Tempe, Arizona: Program for Southeast Asian Studies, Arizona State
University.
1996a Interim Report. Tim Penelitian Sosial Budaya Transmigrasi di Desa
Mwapi dan Kaugapu, Kelurahan Waina, Kecamatan Timika Timur.
Jakarta: Departemen Transmigrasi dan PPH, R.I., 26 Oktober 1996.
1996b Model Sosial Budaya Bagi Penyelenggaraan Pembangunan
Transmigrasi Untuk Desa Mwapi dan Kaugapu. Ekspose Hasil
Penelitian untuk Departemen Transmigrasi dan PPH, R.I.Timika, 19
Desember 1996.
1997a Pembangunan Transmigrasi Model Pemugaran Bagi Orang Kamoro di
desa Mwapi dan Kaugapu, Timika Timur. Diskusi Panel Terbatas,
dengan Menteri Transmigrasi dan PPH, R.I., Ditjen Bina Masyarakat
Transmigrasi, Jakarta, 24 Januari 1997.
1997b 'Transmigrasi dalam Pembangunan Wilayah dan Kelestariannya dengan
Perspektif Sosial Budaya: Model untuk Irian Jaya', Analisis CSIS
ANTROPOLOGI INDONESIA 54, 1998 23
3(26): 219-244.
1997c Transmigrasi dalam Pembangunan Daerah Perbatasan Irian
Jaya. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI. Jakarta,
12 Agustus 1997.
Trenkenschuh, F.
1969 'Border Areas of Asmat: The Timika', An Asmat Sketchbook, (1) hal.
77-82. Agats: Museum Asmat.
Widjojo, M.S
1995 Orang Kamoro dan Perubahan Sosial Budaya di Timika Irian Jaya.
Jakarta: LIPI.
24 ANTROPOLOGI INDONESIA 54. 1998
Anda mungkin juga menyukai
- Antropologi KlasikDokumen9 halamanAntropologi KlasikAndi Muhammad Yusuf100% (3)
- Clifford Geertz, Politik MaknaDokumen16 halamanClifford Geertz, Politik MaknaRadja GorahaBelum ada peringkat
- Review Buku Roger M. Keesing, Samuel GunawanDokumen25 halamanReview Buku Roger M. Keesing, Samuel GunawanReyzilina NuryanzaBelum ada peringkat
- George Simmel, Interaksi SosialDokumen1 halamanGeorge Simmel, Interaksi SosialRana Ramadhania Wati100% (1)
- Antropologi PerkotaanDokumen14 halamanAntropologi PerkotaanAinun Mardiana Sinambela67% (3)
- Kel.9 Determinisme Masa Kanak Kanak Antro PsikologiDokumen10 halamanKel.9 Determinisme Masa Kanak Kanak Antro PsikologiSriagustina SinagaBelum ada peringkat
- MAKALAH Pierre BourdieuDokumen25 halamanMAKALAH Pierre BourdieuAkbar NoviantoBelum ada peringkat
- Hubungan Antropologi Dengan Ilmu Yang LainDokumen2 halamanHubungan Antropologi Dengan Ilmu Yang LainKhairuna Rizal100% (2)
- Feminisme Dan AntropologiDokumen8 halamanFeminisme Dan AntropologiFadhil Rahmat100% (1)
- Interaksionisme Simbolis 1Dokumen48 halamanInteraksionisme Simbolis 1Glory Kristiani HalimBelum ada peringkat
- SAP Peng AntropologiDokumen8 halamanSAP Peng Antropologi10011997Belum ada peringkat
- Pendidikan PolitikDokumen9 halamanPendidikan Politikkarina lestariBelum ada peringkat
- Review 7 - Ikhsan Nurdiansyah - 11201110000006 - Budaya PopulerDokumen3 halamanReview 7 - Ikhsan Nurdiansyah - 11201110000006 - Budaya PopulerIkhsan Nurdiansyah 2020100% (1)
- Konsep Suku BangsaDokumen18 halamanKonsep Suku BangsaVioletta SusiloBelum ada peringkat
- Antropologi in PsikologiDokumen17 halamanAntropologi in PsikologiAgustiana Malika Ilma H100% (1)
- Jean BaudrillardDokumen11 halamanJean BaudrillardAfrizal RahmanBelum ada peringkat
- Pemetaan Teori SosiologiDokumen38 halamanPemetaan Teori SosiologiRENNYBelum ada peringkat
- Materi AntropologiDokumen22 halamanMateri AntropologiBobby PatriaBelum ada peringkat
- Orientasi TeoritisDokumen4 halamanOrientasi Teoritisalid100% (1)
- Mengkaji Wewenang Negara Dalam Bidang MoralDokumen12 halamanMengkaji Wewenang Negara Dalam Bidang MoralRegina dwi putri cahyaniBelum ada peringkat
- Antropologi Sosial (System of Kinship)Dokumen12 halamanAntropologi Sosial (System of Kinship)Andi Muhammad Yusuf100% (2)
- Teori EvolusiDokumen14 halamanTeori EvolusiTariBelum ada peringkat
- ASUMSI Teori Fungisional Struktural 2Dokumen6 halamanASUMSI Teori Fungisional Struktural 2Veni Handrayani100% (5)
- Fetisisme Komoditas: Pemujaan Status Simbol Dalam Gaya Hidup MahasiswaDokumen19 halamanFetisisme Komoditas: Pemujaan Status Simbol Dalam Gaya Hidup MahasiswatintarijrBelum ada peringkat
- Sistem Kekerabatan Dan Organisasi SosialDokumen4 halamanSistem Kekerabatan Dan Organisasi SosialHeldi PrasetyaBelum ada peringkat
- Lukisan Anak-Anak Di BaliDokumen28 halamanLukisan Anak-Anak Di BaliAfina FitriaBelum ada peringkat
- Teori Interaksi SimbolikDokumen20 halamanTeori Interaksi SimbolikAyuanatul RamadhanBelum ada peringkat
- Bahan Mentah Antropologi Dan Konteks Aneka Warna ManusiaDokumen6 halamanBahan Mentah Antropologi Dan Konteks Aneka Warna ManusiaDwi Jaka PranataBelum ada peringkat
- Pemikiran Klasik Dan Modern Tentang PerkotaanDokumen5 halamanPemikiran Klasik Dan Modern Tentang PerkotaanMelky NahakBelum ada peringkat
- Paradigma Definisi Sosial NopiDokumen11 halamanParadigma Definisi Sosial NopiRaVy SelamanyaBelum ada peringkat
- Pancasila Sebagai Roh Kebudayaan Bangsa IndonesiaDokumen13 halamanPancasila Sebagai Roh Kebudayaan Bangsa IndonesiaRafi RidatullahBelum ada peringkat
- State BuildingDokumen11 halamanState Buildingad5027clBelum ada peringkat
- TR Teori DifusiDokumen5 halamanTR Teori DifusiPutri NaibahoBelum ada peringkat
- Teori Modernisasi Klasik Dan ModernDokumen7 halamanTeori Modernisasi Klasik Dan ModernMarkuso SimamoraBelum ada peringkat
- Teori Evolusi BudayaDokumen8 halamanTeori Evolusi BudayaDyta Dwi HartantiBelum ada peringkat
- Hubungan Antara Organisasi Sosial Dan Sistem Kekerabatan Di Dalam MasyarakatDokumen2 halamanHubungan Antara Organisasi Sosial Dan Sistem Kekerabatan Di Dalam MasyarakatvanesBelum ada peringkat
- Apa Itu Cultural StudiesDokumen1 halamanApa Itu Cultural StudiesSifahannisaBelum ada peringkat
- TEORI QUEER Oleh Judith Butler PDFDokumen3 halamanTEORI QUEER Oleh Judith Butler PDFmuhamkalim67Belum ada peringkat
- OkDokumen14 halamanOkGareng Jelek Dan IrengBelum ada peringkat
- Ringkasan Bab 13 - Nugroho Taufiq Yusron - 1403621058Dokumen10 halamanRingkasan Bab 13 - Nugroho Taufiq Yusron - 1403621058Nugroho Taufik YusronBelum ada peringkat
- Soal Uts AntroDokumen7 halamanSoal Uts AntroIkhwa SasmithaBelum ada peringkat
- Tiatira Isti - Resume12 - SosmodernDokumen9 halamanTiatira Isti - Resume12 - SosmodernOyangberthLoilalyMalubayaBelum ada peringkat
- Ilmu KewarganegaraanDokumen28 halamanIlmu KewarganegaraanasoizzyBelum ada peringkat
- Interaksi SimbolikDokumen11 halamanInteraksi SimbolikCintia Whinda0% (1)
- Tentang Bullying (Patologi Sosial)Dokumen12 halamanTentang Bullying (Patologi Sosial)Metty Aliya SetiyaniBelum ada peringkat
- Komunikasi Sebagai Multidisiplin 1Dokumen7 halamanKomunikasi Sebagai Multidisiplin 1DjilarAncheszBelum ada peringkat
- 10 Elemen JurnalistikDokumen11 halaman10 Elemen JurnalistikRaisa QorirahBelum ada peringkat
- Teori Struktural FungsionalDokumen12 halamanTeori Struktural FungsionalIDA ZUBAIDAHBelum ada peringkat
- Kumpulan Judul Skripsi Jurusan SosiologiDokumen11 halamanKumpulan Judul Skripsi Jurusan SosiologiIbnu HardiBelum ada peringkat
- Pengertian Antropologi Menurut para Ahli, JusmanDokumen11 halamanPengertian Antropologi Menurut para Ahli, JusmanHeryanda OnDaudBelum ada peringkat
- Pembangunan Sosial Dan Kebijakan SosialDokumen6 halamanPembangunan Sosial Dan Kebijakan Sosialkarmila_pink85Belum ada peringkat
- Keanekaragaman BudayaDokumen11 halamanKeanekaragaman BudayaLihin Bello SPBelum ada peringkat
- Sejarah Singkat Himasos Fisip UnsriDokumen2 halamanSejarah Singkat Himasos Fisip UnsriSuryati sBelum ada peringkat
- Essay Media AntopologiDokumen9 halamanEssay Media AntopologiHaulah Citra 'leyenk'Belum ada peringkat
- Review 4 - Ikhsan Nurdiansyah - 11201110000006 - Produksi BudayaDokumen2 halamanReview 4 - Ikhsan Nurdiansyah - 11201110000006 - Produksi BudayaIkhsan Nurdiansyah 2020Belum ada peringkat
- Perbandingan Asumsi Teori Struktural FungsionalDokumen8 halamanPerbandingan Asumsi Teori Struktural FungsionalErlina Fitri ArtantiBelum ada peringkat
- Fahri Firdiana Kartika Sari - 049255965 - Bju Pengantar Sosiologi Isip 4110Dokumen9 halamanFahri Firdiana Kartika Sari - 049255965 - Bju Pengantar Sosiologi Isip 4110Fahri Firdiana Kartika SariBelum ada peringkat
- Rangkuman Teori IdentitasDokumen5 halamanRangkuman Teori IdentitasIzharul FananyBelum ada peringkat
- EtnisDokumen10 halamanEtnisRhahadjeng Maristya PalupiBelum ada peringkat
- UTS Antropologi DasarDokumen3 halamanUTS Antropologi DasarMelati SekarwangiBelum ada peringkat
- Alur Pelayanan Administrasi Akademik FISIP UnandDokumen2 halamanAlur Pelayanan Administrasi Akademik FISIP UnandArigatouBelum ada peringkat
- Rumpun FisipDokumen15 halamanRumpun FisipArigatouBelum ada peringkat
- Pengertian SPIDokumen11 halamanPengertian SPIArigatouBelum ada peringkat
- Jurusan Di FISIPDokumen18 halamanJurusan Di FISIPArigatouBelum ada peringkat
- Pertemuan 3-2021Dokumen41 halamanPertemuan 3-2021ArigatouBelum ada peringkat
- Bahan Pertemuan 3Dokumen22 halamanBahan Pertemuan 3ArigatouBelum ada peringkat
- Teori Teori Klasik Pembangunan EkonomiDokumen5 halamanTeori Teori Klasik Pembangunan EkonomihiasBelum ada peringkat
- Slide PKN Landasan PKNDokumen10 halamanSlide PKN Landasan PKNArigatouBelum ada peringkat
- Bahan Pertemuan 2Dokumen17 halamanBahan Pertemuan 2ArigatouBelum ada peringkat
- Materi Tentang Sumber - Sumber HukumDokumen13 halamanMateri Tentang Sumber - Sumber HukumArigatouBelum ada peringkat
- Penyuluhan TBCDokumen3 halamanPenyuluhan TBCArigatouBelum ada peringkat