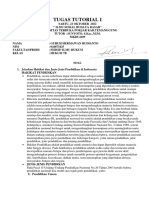1 SM 1
1 SM 1
Diunggah oleh
Angel Gladies ManihurukJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
1 SM 1
1 SM 1
Diunggah oleh
Angel Gladies ManihurukHak Cipta:
Format Tersedia
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No.
2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
MEMBANGUN KARAKTER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT
PENDIDIKAN KI HADJAR DEWANTARA
I Gusti Agung Made Gede Mudana
Jurusan Pendidikan Agama dan Bahasa Bali, STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia
E-mail: agungmudana1961@gmail.com
Abstrak
Sistem pendidikan yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara (ing ngarsa sung tuladha, ing madya
mangun karsa, dan tut wuri handayani) adalah wasiat luhur yang patut dijadikan sebagai acuan
dalam pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara haruslah
bersifat nasional. Artinya, secara nasional pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan
tidak mengabaikan budaya lokal. Bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, ras, dan
agama hendaknya memiliki kesamaan corak dalam mengembangkan karakter anak bangsanya.
Penyelenggaraan pendidikan jangan terjebak pada pencapaian target sempit yang hanya
melakukan transfer pengetahuan, tetapi perlu dengan sengaja mengupayakan terjadinya
transformasi nilai untuk pembentukan karakter anak bangsa. Pembentukan karakter peserta didik
perlu melibatkan tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) secara sinergis.
Pengembangan karakter peserta didik perlu memperhatikan perkembangan budaya bangsa
sebagai sebuah kontinuitas menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (konvergensi) dan tetap
memiliki sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (konsentris).
Kata Kunci: Membangun Karakter; Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara
Abstract
The education system put forward by Ki Hadjar Dewantara (ing ngarsa sung tuladha, ing madya
mangun karsa, and tut wuri handayani) is a noble will that should be used as a reference in the
development of character education. Education according to Ki Hadjar Dewantara must be of a
national nature. This means that nationally education must have the same style without ignoring
local culture. The Indonesian nation which consists of many tribes, races, and religions should
have a common pattern in developing the character of their nation's children. The implementation
of education should not be trapped in the achievement of narrow targets that only transfer
knowledge, but it is necessary to deliberately pursue the transformation of values for the formation
of national character. Character building of students needs to involve tri education centers (family,
school, and community) synergistically. Character development of students needs to pay
attention to the development of national culture as a continuity towards the unity of world culture
(convergence), and still have personality traits in the world humanitarian environment
(concentric).
Keyword: Character Building; Educational Philosophy Ki Hadjar Dewantara
1. Pendahuluan
Pemuda masa kini hidup dalam dunia yang serba pragmatis sebagai dampak dari
globalisasi yang memasuki budaya Indonesia melalui perkembangan teknologi dan informasi
yang sangat memikat. Globalisasi tidak selalu mendatangkan dampak negatif seperti tersebut di
atas. Akan tetapi, globalisasi di Indonesia lebih banyak mendatangkan dampak negatif, seperti
pola hidup masyarakat yang menjadi lebih konsumtif, hedonis, dan materialistik. Akibatnya,
pemuda masa kini belajar hanya untuk meraih hasil yang baik dengan mengandalkan segala cara
tidak terkecuali mencontek yang sudah menjadi budaya bagi siswa yang hanya mementingkan
nilai dari pada ilmu. Hal tersebut menunjukan akhlak generasi muda Indonesia yang bobrok.
Perilaku dan sikap bangsa Indonesia di kalangan generasi muda, khususnya anak didik perlu
terus diperkuat sehingga dapat melahirkan generasi muda yang handal dan memiliki karakter
yang kuat, salah satunya dengan menumbuhkan minat baca untuk menambah pengetahuan. Hal
Jurnal Filsafat Indonesia | 75
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
itu penting agar bangsa Indonesia dapat berkembang dan sejajar dengan bangsa-bangsa asing
dalam pergaulan internasional, tetapi tidak larut dalam arus globalisasi.
Bangsa Indonesia membutuhkan lima karakter untuk dapat menampilkan jati dirinya dan
bersaing dengan bangsa lain. Pertama, karakter bangsa yang bermoral (religius). Bangsa ini
harus sarat dengan nilai-nilai moral dan etika keagamaan sebagai sebuah pandangan dan
praktik. Kedua, karakter bangsa yang beradab. Beradab dalam arti luas, menjadi suatu bangsa
yang memiliki karakter, berbudaya, dan berperikemanusiaan. Ketiga, karakter bangsa yang
bersatu, di dalamnya termasuk menegakkan toleransi, tidak mungin Indonesia dapat bersatu
tanpa adanya toleransi, keharmonisan, dan persaudaraan. Keempat, karakter bangsa yang
berdaya, dalam arti yang luas berdaya berati menjadi bangsa yang berpengetahuan, terampil,
berdaya saing secara mental, pemikiran maupun teknis. Daya saing bukan hanya sekadar dalam
arti materi dan mekanik, melainkan dalam makna secara mental, hati, dan pikiran. Kelima,
karakter bangsa yang berpartisipasi. Partisipasi sangat diperlukan untuk menghapus sikap masa
bodoh, mau enaknya saja, dan tidak pernah peduli dengan nasib bangsa Indonesia. Karakter
partisipasi ditandai dengan penuh peduli, rasa dan sikap bertanggung jawab yang tinggi serta
komitmen yang tumbuh menjadi karakter dan watak bangsa Indonesia (Ismadi. 2014: 29).
Menurut survei yang dilakukan oleh United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization (UNESCO) pada tahun 2016 bahwa minat baca masyarakat Indonesia yang masih
sangat rendah, yakni 0,001 persen. Hal ini sangat disayangkan karena masyarakat Indonesia
tidak ada kesadaran terhadap menumbuhkan minat baca. Seharusnya Indonesia belajar dari
buku berjudul “Sekolah Taman Siswa” karangan Ki Hadjar Dewantara. Buku tersebut telah
dijadikan referensi di Finlandia, tetapi di Indonesia buku tersebut tidak dibaca. Dalam buku
tersebut, salah satunya Ki Hadjar Dewantara telah menuliskan tentang kondisi belajar yang
menyenangkan. Pemerintah Finlandia telah mengikuti pandangan Ki Hadjar Dewantara dengan
mengubah sistem belajar dan situasi di sekolah menjadi lebih nyaman dan menggembirakan.
Berbeda dengan sekolah dan instansi pendidikan di Indonesia yang peserta didiknya lebih
banyak merasa stres saat belajar (Belarminus, 2014).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memandang pentingnya pendidikan karakter
dalam diri anak didik agar dapat menjadi bekal kelak di masa depan dalam menggapai cita-cita
anak bangsa. UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, menerangkan bahwa tujuan pendidikan
nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang bermartabat.
Dalam hal ini, proses pendidikan harus ditanamkan nilai-nilai moral. Penanaman nilai moral tidak
hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan masyarakat karena
dalam proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di sekolah. Ki Hadjar Dewantara
membedakan lingkungan pendidikan menjadi tiga yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan,
yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga
jika ditinjau dari ilmu sosiologi, keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang terdiri atas
beberapa individu yang terikat oleh suatu keturunan, yakni kesatuan dari bentuk-bentuk kesatuan
masyarakat. Keluarga tempat anak diasuh dan dibesarkan, berpengaruh besar terhadap
pertumbuhan dan perkembangannya baik secara fisik maupun mental.
Lingkungan sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya
sangat besar pada jiwa anak. Jadi, di samping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun
mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Sekolah
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak,
terutama untuk kecerdasannya. Lingkungan masyarakat adalah lingkungan tempat tinggal anak,
juga meliputi teman-teman anak di luar sekolah. Kondisi orang-orang di lingkungan desa atau
kota tempat tinggal anak juga turut memengaruhi perkembangan jiwanya (Yuwono, 2015).
2. Metode
Metode yang dipergunakan di dalam artikel ini adalah study kepustakaan, yaitu menelaah
sumber pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan karakter dalam perspektif filsafat
pendidikan Ki Hajar Dewantara. Telaah penelitian sejenis juga dilakukan agar didapat simpulan
yang valid.
Jurnal Filsafat Indonesia | 76
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
3. Hasil dan Pembahasan
Ki Hadjar Dewantara
Mengangkat pemikiran seorang tokoh besar seperti Ki Hadjar Dewantara tanpa terlebih
dahulu memahami dan mempertimbangkan kondisi sosioal dan politik masa hidupnya yang
mengiringi pertumbuhan pemikirannya, tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik
karena pada dasarnya Ki Hadjar Dewantara merupakan produk sejarah masa lampau. Oleh
karena itu, situasi dan kondisi yang berkembang ikut menentukan perkembangan dan corak
pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara terlahir dari keluarga kerajaan Paku Alam
yang merupakan keturunan bangsawan, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan
nama R.M. Suwardi Suryaningrat. Ayah Ki Hadjar Dewantara bernama Kanjeng Pangeran Harjo
Surjaningrat, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Hadipati Harjo Surjosasraningrat yang bergelar
Sri Paku Alam III (Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 4. 1989). Ki Hadjar Dewantara merupakan
keturunan dari Paku Alam III, dan mendapat pendidikan agama dari ayahnya.
Beliau juga mendapat pelajaran falsafah Hindu yang tersirat dari cerita wayang dan juga
satra jawa gending. Ki Hadjar Dewantara di dalam keluarganya banyak bersentuhan dengan iklim
keluarga yang penuh dengan nuansa kerajaan yang feodal. Walaupun ayahnya seorang
keturunan dari Paku Alam III, Ki Hadjar Dewantara seorang yang sangat dekat dengan rakyat
karena pada masa kecilnya Ki Hadjar Dewantara senang bergaul dengan anak-anak kebanyakan
di kampung-kampung sekitar puri tempat tinggalnya. Ki Hadjar Dewantara menolak adat feodal
yang berkembang di lingkungan kerajaan. Hal ini dirasakan olehnya bahwa adat yang demikian
menganggu kebebasan pergaulannya (Taman Siswa, 1979). Pada masa itu, pendidikan
sangatlah langka, hanya orang-orang dari kalangan Belanda, Tiong Hoa, dan para pembesar
daerah saja yang dapat mengenyam jenjang pendidikan yang diberikan oleh pemerintahan
Belanda.
Ki Hadjar Dewantara sewaktu kecil mendapat pendidikan formal pertama kali pada tahun
1896. Akan tetapi, Ki Hadjar Dewantara merasa kecewa karena teman sepermainannya tidak
dapat bersekolah bersama sebab mereka hanya rakyat biasa. Hal ini yang kemudian mengilhami
dan memberikan kesan yang sangat mendalam di dalam hati nuraninya dalam melakukan
perjuangannya, baik dalam dunia politik maupun pendidikan. Ki Hadjar Dewantara juga
menentang kolonialisme dan foedalisme yang menurutnya sangat bertentangan dengan rasa
kemanusiaan kemerdekaan dan tidak memajukan hidup dan penghidupan manusia secara adil
dan merata (Soeratman, 1985). Kecintaan Ki Hadjar Dewantara terhadap ilmu pengetahuan dan
agama membuatnya menjadi sosok yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas
sehingga membuat beliau dihormati oleh rakyat dan disegani oleh musuh. Ki Hadjar Dewantara
melihat ketimpangan pendidikan yang dialamai oleh rakyat kecil sehingga mendorong Ki Hadjar
Dewantara untuk berusaha memperjuangkan rakyat kecil agar dapat mengenyam pendidikan
karena bagi Ki Hadjar Dewantara, pendidikan merupakan hak setiap manusia dan juga bekal bagi
masa depan.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan Karakter
Pengertian Pendidikan Karakter
Pendidikan dalam konteks sekarang kurang relevan untuk mengatasi krisis moral yang
sedang melanda di negara Indonesia. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan
bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian
remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik
orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.
Sistem pendidikan Indonesia masih jauh dari kata berhasil untuk menghasilkan generasi penerus
bangsa yang cerdas ilmu dan perilaku, dibuktikan dengan banyak munculnya kasus-kasus
korupsi dalam pemerintahan, kejahatan seksual yang merajalela, narkoba yang terus memakan
korban dsb. Berdasarkan realita tersebut perlu adanya perombakan sistem pendidikan agar
dapat menghasilkan generasi yang cerdas akal dan budi pekertinya.
Pendidikan karakter menjadi wacana yang telah lama dibicarakan oleh berbagai pihak
dalam kaitannya dengan generasi Indonesia, seperti apa yang hendak dihasilkan untuk
menggantikan generasi sebelumnya. Wacana pendidikan karakter telah ada pula sebelum
kemerdekaan atau sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Di antaranya adalah tokoh
pendidikan nasional yang turut serta memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui bidang
pendidikan yang merupakan bapak pendidikan Nasional, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Sepak
terjang Ki Hadjar Dewantara di dunia pendidikan sudah tidak diragukan lagi, peranan Ki Hadjar
Jurnal Filsafat Indonesia | 77
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
Dewantara sangat besar dalam sejarah pendidikan tanah air. Ki Hadjar Dewantara menyebutkan
bahwa pendidikan adalah “Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar
mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan
kebahagiaan yang setinggi-tingginya” (Taman Siswa, 1977).
Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan pengertian pendidikan adalah ”Pendidikan,
umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan
karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak; dalam pengertian Taman Siswa tidak boleh dipisah-
pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan
dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya” (Taman Siswa, 1977).
Definisi pendidikan yang dikembangkan Ki Hadjar Dewantara, menunjukkan bahwa Ki Hadjar
Dewantara memandang pendidikan moral sebagai suatu proses yang dinamis dan
berkesinambungan. Di sini tersirat pula wawasan kemajuan karena sebagai proses pendidikan
harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan kemajuan zaman.
Keseimbangan unsur cipta, rasa, dan karsa yang tidak dapat dipisah-pisahkan ini
memperlihatkan bahwa Ki Hadjar Dewantara tidak memandang pendidikan hanya sebagai
proses transfer ilmu pengetahuan (transfer of knowledge). Hal ini sesuai dengan kondisi yang
dihadapi oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan pada masa itu (kolonial Belanda) penuh
dengan semangat keduniawian (materialism), penalaran (intellektualism) serta individualism
(Taman Siswa, 1977). Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan ranak kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Muara ranah kognitif adalah tumbuh dan berkembangnya kecerdasan
dan kemampuan intelektual akademik, ranah afektif bermuara pada terbentuknya karakter
kepribadian, dan ranah psikomotorik akan bermuara pada keterampilan dan perilaku. Hal ini
sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa terdapat tiga aspek dalam
pembelajaran, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
Pengetahuan adalah bentuk dari prinsip dan fakta, keterampilan adalah pemerolehan
kemampuan melalui pelatihan atau pengalaman. Sikap didefinisikan sebagai suatu pendapat,
perasaan atau mental seseorang yang ditunjukkan oleh tindakan. Pendidikan sebagai upaya
untuk memajukan budi pekerti, baik itu kekuatan batin maupun karakter agar anak didik dapat
menemukan kesempurnaan hidup. Ki Hadjar Dewantara memandang pentingnya pendidikan
karakter sebagai bekal untuk meraih cita-cita karena karakter manusia menjadi modal utama
dalam menjalani kehidupan. Ki Hadjar Dewantara mendefinisikan pendidikan adalah sebagai
daya dan upaya yang dilakukan untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin,
karakter, pikiran dan tubuh anak agar dapat mencapai kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan
penghidupan anak-anak peserta didik dapat selaras dengan dunianya (Taman Siswa, 1967).
Pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara memperhatikan keseimbangan cipta,
rasa, dan karsa tidak hanya sekadar proses alih ilmu pengetahuan saja atau transfer of
knowledge, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai (transformation of
value). Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi
sebenar-benar manusia. Di sisi lain, karakter dalam istilah sederhananya adalah pendidikan budi
pekerti, kata karakter berasal dari bahasa inggris character, artinya watak. Ki Hadjar Dewantara
telah jauh berpikir dalam masalah pendidikan karakter, mengasah kecerdasan budi sungguh baik
karena dapat membangun budi pekerti yang baik dan kokoh, hingga dapat mewujudkan
kepribadian (persoonlijkhheid) dan karakter (jiwa yang berasas hukum kebatinan). Jika itu terjadi,
orang akan senantiasa dapat mengalahkan nafsu dan tabiat-tabiatnya yang asli, seperti bengis,
murka, pemarah, kikir, keras, dan lain-lain (Taman Siswa. 1977). Karakter adalah pola untuk
membentuk peserta didik yang beradab, membangun watak manusia yang berke-Tuhanan Yang
Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan memiliki ketrampilan, sehat
jasmani dan rohani sehingga bisa mewujudkan manusia yang mandiri serta bertanggung jawab
terhadap kesejahteraan bangsa, Negara, dan masyarakat pada umumnya.
Tujuan Pendidikan Karakter
Tujuan pendidikan bagi Ki Hadjar Dewantara adalah membangun anak didik menjadi
manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya serta sehat jasmaninya untuk menjadi
anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air
serta manusia pada umumnya (Suparlan, 1984). Ki Hadjar Dewantara mengungkapkan bahwa
pendidikan merupakan proses pembudayaan, yaitu suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur
kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga
dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju kearah keluhuran
Jurnal Filsafat Indonesia | 78
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
budaya manusia. Upaya kebudayaan (pendidikan) dapat ditempuh dengan sikap yang dikenal
dengan teori Trikon, yaitu sebagai berikut.
a. Kontinuitas yang berarti bahwa garis hidup kita sekarang harus merupakan lanjutan dari
kehidupan kita pada zaman lampau berikut penguasaan unsur tiruan dari kehidupan dan
kebudayaan bangsa lain.
b. Konvergensi yang berarti kita harus menghindari hidup menyendiri, terisolasi, dan mampu
menuju ke arah pertemuan antarbangsa dan komunikasi antarnegara menuju kemakmuran
bersama atas dasar saling menghormati, persamaan hak, dan kemerdekaan masing-masing.
c. Konsentris yang berarti setelah kita bersatu dan berkomunikasi dengan bangsa-bangsa lain
di dunia, kita jangan kehilangan kepribadian sendiri. Bangsa Indonesia adalah masyarakat
merdeka yang memiliki adat istiadat dan kepribadian sendiri, meskipun bertitik pusat satu,
tetapi dalam lingkaran yang konsentris masih tetap memiliki lingkaran sendiri yang khas yang
membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya (Taman Siswa, 1977).
Dasar Pendidikan
Falsafah pendidikan Ki Hadjar Dewantara bukan semata-mata sistem pendidikan
perjuangan, melainkan juga merupakan suatu pernyataan falsafah dan budaya bangsa Indonesia
sendiri. Sistem pendidikan tersebut kaya akan konsep-konsep kependidikan yang asli. Ki Hadjar
Dewantara mengembangkan sistem pendidikan melalui Perguruan Taman Siswa yang
mengartikan pendidikan sebagai upaya suatu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan
benih turunan bangsa itu. Untuk itu, Ki Hadjar Dewantara mengembangkan metode among
sebagai sistem pendidikan yang didasarkan asas kemerdekaan dan kodrat alam. Ki Hadjar
Dewantara mengartikan merdeka sebagai kesanggupan dan kemampuan untuk berdiri sendiri
guna mewujudkan hidup diri sendiri, hidup tertib, dan damai dengan kekuasaan atas diri sendiri.
Merdeka tidak hanya berarti bebas, tetapi harus diartikan sebagai kesanggupan dan
kemampuan, yaitu kekuatan dan kekuasaan untuk memerintah diri pribadi (Taman Siswa, 1977).
Sistem pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikembangkan berdasarkan lima asas pokok yang
disebut Pancadarma Taman Siswa, yang meliputi:
a. asas kemerdekaan, yang berarti disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik
hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
b. asas kodrat alam, yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makluk, yaitu
satu dengan kodrat alam. Manusia tidak dapat lepas dari kodrat alam dan akan berbahagia
apabila dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. Oleh
karena itu, setiap individu harus berkembang dengan sewajarnya (Suparlan, 1984);
c. asas kebudayaan, yang berarti bahwa pendidikan harus membawa kebudayaan kebangsaan
itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan
kepentingan hidup lahir batin rakyat pada setiap zaman dan keadaan;
d. asas kebangsaan, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malah harus
menjadi bentuk kemanusiaan yang nyata. Oleh karena itu, asas kebangsaan ini tidak
mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, tetapi mengandung rasa satu dengan
bangsa sendiri, satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju kepada
kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa; dan
e. asas kemanusiaan, yang menyatakan bahwa darma setiap manusia itu adalah perwujudan
kemanusiaan yang harus terlihat pada kesucian batin dan adanya rasa cinta kasih terhadap
sesama manusia dan terhadap makluk ciptaan Tuhan seluruhnya (Surjomihardjo, 1986).
Pokok Ajaran/ Sistem Pendidikan
Pokok ajaran Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan yang cocok untuk anak-
anak Indonesia adalah Pendidikan Nasional. Untuk menyelengarakan pendidikan nasional,
beliau mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa yang kemudian dikenal sebagai
Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa bertujuan untuk membuat rakyat pandai,
sebab Ki Hadjar Dewantara berkeyakinan bahwa perjuangan pergerakan tidak akan berhasil
tanpa kepandaian. Untuk itu, Ki Hadjar Dewantara mengemukakan konsepnya mengenai
Pendidikan Nasional yang direalisasi mulai tanggal 3 Juli 1922 dengan mendirikan Perguruan
Taman Siswa di Yogyakarta dengan tugas-tugasnya. Pertama, untuk mendidik rakyat agar
berjiwa kebangsaan dan berjiwa merdeka, serta menjadi kader-kader yang sanggup dan mampu
mengangkat derajat nusa dan bangsanya sejajar dengan bangsa lain yang merdeka. Kedua,
membantu perluasan pendidikan dan pengajaran yang pada waktu itu sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak, sedangkan sekolah yang disediakan oleh pemerintah Belanda sangat terbatas.
Jurnal Filsafat Indonesia | 79
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
Ki Hadjar Dewantara telah menciptakan sistem pendidikan yang merupakan sistem
pendidikan perjuangan. Falsafah pendidikannya adalah menentang falsafah penjajahan dalam
hal ini falsafah Belanda yang berakar pada budaya Barat. Dalam pandangan Ki Hadjar
Dewantara, kedewasaan bisa diartikan sebagai kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan
penghidupan anak-anak yang selaras dengan alamnya dan masyarakat. Ki Hadjar Dewantara
mengartikan pendidikan secara umum sebagai daya upaya untuk mewujudkan perkembangan
budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelektual) dan jasmani anak menuju ke arah masa depan
yang lebih baik. Kedewasaan akan tercapai pada akhir windu ketiga, yaitu tercapainya
kesempurnaan hidup selaras dengan alam, anak, dan masyarakat. Jadi, dapat diartikan bahwa
pendidikan terutama berlangsung sejak anak lahir hingga anak berusia sekitar 24 tahun. Dalam
pelaksanaan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara menggunakan “Sistem Among” sebagai
perwujudan konsepsi beliau dalam menempatkan anak sebagai sentral proses pendidikan.
Dalam Sistem Among, setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan
bersikap: Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tut wuri handayani (MLPTS,
1992).
a. Ing ngarsa sung tuladha
Ing ngarsa berarti di depan, atau orang yang lebih berpengalaman dan lebih
berpengatahuan. Sedangkan tuladha berarti memberi contoh, memberi teladan
(Reksohadiprodjo, 1989). Guru harus bisa menjaga tingkah lakunya supaya bisa menjadi teladan.
Dalam pembelajaran, apabila guru mengajar menggunakan metode ceramah, guru harus benar-
benar siap dan tahu bahwa yang diajarkannya itu baik dan benar.
b. Ing madya mangun karsa
Berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) ketika berada di tengah harus mampu
membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi pada anak didik. Hal ini dapat diterapkan
bila guru menggunakan metode diskusi. Sebagai narasumber dan sebagai pengarah, guru dapat
memberikan masukan-masukan dan arahan.
c. Tut wuri handayani
Berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) berada di belakang, mengikuti, dan
mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Ketika
guru berada di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan, dapat terjadi anak
didik akan berusaha bersaing, berkompetisi menunjukkan kemampuannya yang terbaik
(Soeratman, 1989).
Ki Hadjar menyetujui teori Konvergensi, yaitu perkembangan manusia itu ditentukan oleh
dasar (nature) dan ajar (nurture). Anak yang baru lahir diibaratkan kertas putih yang sudah ada
tulisannya, tetapi belum jelas. Selanjutnya Ki Hadjar juga berpendapat bahwa perkembangan
anak didik mulai dari lahir hingga dewasa dibagi atas fase-fase sebagai berikut.
1) Zaman Wiraga (0-8 th) merupakan periode yang sangat penting bagi perkembangan badan
dan pandca indra.
2) Zaman Wicipta (8-16 th) merupakan masa perkembangan untuk daya-daya jiwa terutama
pikiran anak.
3) Zaman wirama (16-24 th) merupakan masa untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat
karena anak mengambil bagian sesuai dengan cita-cita hidupnya (Taman Siswa. 1977)
4. Simpulan dan Saran
Sistem pendidikan yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara (ing ngarsa sung tuladha, ing
madya mangun karsa, dan tut wuri handayani) adalah wasiat luhur yang patut dijadikan sebagai
acuan dalam pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara
haruslah bersifat nasional. Artinya, secara nasional pendidikan harus memiliki corak yang sama
dengan tidak mengabaikan budaya lokal. Bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, ras,
dan agama hendaknya memiliki kesamaan corak dalam mengembangkan karakter anak
bangsanya. Penyelenggaraan pendidikan jangan terjebak pada pencapaian target sempit yang
hanya melakukan transfer pengetahuan, tetapi perlu dengan sengaja mengupayakan terjadinya
transformasi nilai untuk pembentukan karakter anak bangsa. Pembentukan karakter peserta didik
perlu melibatkan tri pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) secara sinergis.
Pengembangan karakter peserta didik perlu memperhatikan perkembangan budaya bangsa
sebagai sebuah kontinuitas menuju ke arah kesatuan kebudayaan dunia (konvergensi), dan tetap
memiliki sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (konsentris). Asas dan
Jurnal Filsafat Indonesia | 80
Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 2 No. 2 2019
ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
dasar pendidikan yang digagas Ki Hadjar Dewantara merupakan landasan dasar yang kokoh
untuk membangun karakter bangsa, bersendi pada budaya bangsa dengan tidak mengabaikan
budaya asing.
5. Daftar Pustaka
Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 4. 2004. Jakarta: Delta Pamungkas.
Ismadi, Hurip Danu. 2014. Pendidikan Karakter dalam Perspektif Kebudayaan. Jakarta: Gading
Inti Prima.
MLPTS. 1992. Peraturan Besar dan Piagam Persatuan Taman Siswa. Yogyakarta: MLPTS.
Reksohadiprodjo, Ki Muchammad Said. 1989. Masalah-masalah Pendidikan Nasional. Jakarta:
CV Haji Masagung.
Soeratman, Darsiti. 1989. Ki Hajar Dewantara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Nasional.
Surjomiharjo, Abdurrachman. 1986. Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah
Indonesia Modern. Jakarta: Sinar Harapan.
Jurnal Filsafat Indonesia | 81
Anda mungkin juga menyukai
- TOPIK 3 KONEKSI ANTAR MATERI Filosofi PendidikanDokumen2 halamanTOPIK 3 KONEKSI ANTAR MATERI Filosofi PendidikanChristina Hutabarat100% (1)
- Koneksi T3 FpiDokumen3 halamanKoneksi T3 FpiFatmawati ZulkarnainBelum ada peringkat
- T3 - Koneksi Antar MateriDokumen3 halamanT3 - Koneksi Antar Materiirynanoviantyedu23Belum ada peringkat
- Topik3 Filosofi Koneksi Antar Materi,.Dokumen2 halamanTopik3 Filosofi Koneksi Antar Materi,.rutnatalia1802Belum ada peringkat
- 504 987 1 SMDokumen10 halaman504 987 1 SMFalias AsmiBelum ada peringkat
- Aprilia Dwi Yustika - 6koneksi Antar Materi FPI Topik 3Dokumen3 halamanAprilia Dwi Yustika - 6koneksi Antar Materi FPI Topik 3Aprilia Dwi YustikaBelum ada peringkat
- Prosiding Semnas Pendidikan 2012-OKDokumen10 halamanProsiding Semnas Pendidikan 2012-OKDesi PasaribuBelum ada peringkat
- Koneksi Materi Topik 3Dokumen3 halamanKoneksi Materi Topik 3Nunung ErayaniBelum ada peringkat
- Topik 4 - Koneksi Antar MateriDokumen3 halamanTopik 4 - Koneksi Antar MateriRosBelum ada peringkat
- ISTIQAMADokumen25 halamanISTIQAMAIsti QamaBelum ada peringkat
- Koneksi Antar Materi TOPIK 3 FILOSOFI PEND. INDONESIADokumen4 halamanKoneksi Antar Materi TOPIK 3 FILOSOFI PEND. INDONESIAppg.ritaoktaviana00Belum ada peringkat
- T3. Koneksi Antar Materi - FilosofiDokumen2 halamanT3. Koneksi Antar Materi - FilosofiRifqy HidayatullahBelum ada peringkat
- Topik 4-Aksi Nyata-Filosofi Pendidikan Indonesia.Dokumen9 halamanTopik 4-Aksi Nyata-Filosofi Pendidikan Indonesia.Rahmad DefaBelum ada peringkat
- Topik 3 - Koneksi Antar MateriDokumen2 halamanTopik 3 - Koneksi Antar MateriRosBelum ada peringkat
- Fpi. Topik 5 Koneksi Antar MateriDokumen6 halamanFpi. Topik 5 Koneksi Antar MateriVitta Helsantri.Belum ada peringkat
- Koneksi Antar Materi Topik 4 FPI Rizqi FadlilahDokumen10 halamanKoneksi Antar Materi Topik 4 FPI Rizqi FadlilahrizkieeririsBelum ada peringkat
- Tugas Terstruktur Jdu UasDokumen27 halamanTugas Terstruktur Jdu UasHasna NurBelum ada peringkat
- Manusia Indonesia Dari Perspektif Yang BeragamDokumen3 halamanManusia Indonesia Dari Perspektif Yang BeragamMarBelum ada peringkat
- Koneksi Antar Materi - Manusia Indonesia Dari Perspektif Yang BeragamDokumen2 halamanKoneksi Antar Materi - Manusia Indonesia Dari Perspektif Yang BeragamAgung Priambodo100% (1)
- Tugas KewarganegaraanDokumen8 halamanTugas KewarganegaraanTes EmpatBelum ada peringkat
- Tugas Tuton 2 Pancasila Raihan044595986Dokumen7 halamanTugas Tuton 2 Pancasila Raihan044595986Egon EdanBelum ada peringkat
- T.3. Koneksi Antar Materi (Filosofi)Dokumen2 halamanT.3. Koneksi Antar Materi (Filosofi)ppg.andiazis01Belum ada peringkat
- Makalah PKNDokumen11 halamanMakalah PKNmithaBelum ada peringkat
- Koneksi Antar Materi Topik 3Dokumen3 halamanKoneksi Antar Materi Topik 3RahmiatiBelum ada peringkat
- Pendidikan Kewarganegaraan 1Dokumen6 halamanPendidikan Kewarganegaraan 1Windi Rahmanda FitriBelum ada peringkat
- Zakiyatul Mawaddah - Pendidikan Karakter Berbasis BudayaDokumen21 halamanZakiyatul Mawaddah - Pendidikan Karakter Berbasis BudayaZakiyatul MawaddahBelum ada peringkat
- Pendidikan Multikultural Untuk Membentuk KarakterDokumen6 halamanPendidikan Multikultural Untuk Membentuk KarakterDiniyah KhoerunnisaBelum ada peringkat
- T3. Koneksi Antar Materi-Filosofi PendidikanDokumen4 halamanT3. Koneksi Antar Materi-Filosofi Pendidikanandihafizul100799Belum ada peringkat
- FPI - Topik 3 - Koneksi Antar MateriDokumen3 halamanFPI - Topik 3 - Koneksi Antar MateriInayatul JannahBelum ada peringkat
- Topik 3 Koneksi Antar Materi Filosofi Pendidikan - 20240328 - 114543 - 0000Dokumen8 halamanTopik 3 Koneksi Antar Materi Filosofi Pendidikan - 20240328 - 114543 - 0000Nur SalmaBelum ada peringkat
- Guruh Hermawan - 7B - Ilmu Sosial Budaya Dasar - TT1Dokumen5 halamanGuruh Hermawan - 7B - Ilmu Sosial Budaya Dasar - TT1Boby MorenoBelum ada peringkat
- T3-FPI-Koneksi Antar Materi-SalsabilaDokumen3 halamanT3-FPI-Koneksi Antar Materi-Salsabilappg.salsabilaaisy08Belum ada peringkat
- Topik 3. Koneksi Antar MateriDokumen3 halamanTopik 3. Koneksi Antar Materippg.tiaagustin98830Belum ada peringkat
- 133-Article Text-348-1-10-20201026Dokumen10 halaman133-Article Text-348-1-10-20201026Didat JRBelum ada peringkat
- Ali Fahroni - 1910111310003 - A2 (2019) - ArtikelDokumen7 halamanAli Fahroni - 1910111310003 - A2 (2019) - Artikelajengmuslimah25Belum ada peringkat
- Topik 3 Koneksi Antar Materi Nirwana 239018485047Dokumen3 halamanTopik 3 Koneksi Antar Materi Nirwana 239018485047nirwanaBelum ada peringkat
- T3 - Koneksi MateriDokumen4 halamanT3 - Koneksi MateriDelia AnggraeniBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa Indonesia (Atas)Dokumen17 halamanTugas Bahasa Indonesia (Atas)StarpatrickBelum ada peringkat
- T3 - Koneksi Antar Materi - Filosofi PendidikanDokumen3 halamanT3 - Koneksi Antar Materi - Filosofi PendidikanIsniBelum ada peringkat
- Tugas - PKN - Havizh - Pert 2Dokumen4 halamanTugas - PKN - Havizh - Pert 2lianikmatulmaula02Belum ada peringkat
- Koneksi Antar Materi Fpi Topik 3Dokumen4 halamanKoneksi Antar Materi Fpi Topik 3ppg.zanityaningrum97228Belum ada peringkat
- T3 KoneksiDokumen2 halamanT3 KoneksiPutri Amalia FarhanaBelum ada peringkat
- Tugas Pendidikan Kewarganegaraan, Lesta Fadila Aulia SariDokumen8 halamanTugas Pendidikan Kewarganegaraan, Lesta Fadila Aulia Sarisindyanjasari3Belum ada peringkat
- Resume Materi Ke-4 Mufasihatul MDokumen5 halamanResume Materi Ke-4 Mufasihatul MMufasihatul MunnaffarohBelum ada peringkat
- PERAN GURU TUK MEWUJUDKAN GENERASI EMAS..... (Artikel0 PDFDokumen4 halamanPERAN GURU TUK MEWUJUDKAN GENERASI EMAS..... (Artikel0 PDFAbdul HamidBelum ada peringkat
- Jurnal Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Ips Di Sekolah DasarDokumen15 halamanJurnal Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Ips Di Sekolah DasarmeganetBelum ada peringkat
- Filosofi Topik 3Dokumen1 halamanFilosofi Topik 3Ratna sasi SuciBelum ada peringkat
- Topik 3 Koneksi Antar Materi - Filosofi PendidikanDokumen12 halamanTopik 3 Koneksi Antar Materi - Filosofi Pendidikanppg.windaputri00730Belum ada peringkat
- 716 1310 1 SMDokumen19 halaman716 1310 1 SMeddy puryantoBelum ada peringkat
- T5-7 Koneksi Antar Materi - Krisna Ari SubaktiDokumen5 halamanT5-7 Koneksi Antar Materi - Krisna Ari SubaktikrisnaBelum ada peringkat
- Alda Sein Saputri - 20230841128 - Koneksi AntarmateriDokumen3 halamanAlda Sein Saputri - 20230841128 - Koneksi AntarmateriAldaBelum ada peringkat
- Ulangan Tengah Semester Fsi Khulmi HasanahDokumen4 halamanUlangan Tengah Semester Fsi Khulmi Hasanahppg.khulmihasanah97030Belum ada peringkat
- Proposal WijiDokumen35 halamanProposal WijiZulhijri RiansyahBelum ada peringkat
- Bab IDokumen8 halamanBab Iby lyBelum ada peringkat
- Topik 3 Koneksi FilosofiDokumen2 halamanTopik 3 Koneksi Filosofinovi talitaBelum ada peringkat
- Topik 2 - Ruang KolaborasiDokumen5 halamanTopik 2 - Ruang Kolaborasiadintadarmawan.2023Belum ada peringkat
- Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Bangsa Indonesia Yang Berkarakter (Menuju Kurikulum 2013 Yang Berkarakter) Ahmad ZohdiDokumen18 halamanPeran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Bangsa Indonesia Yang Berkarakter (Menuju Kurikulum 2013 Yang Berkarakter) Ahmad ZohdiNur raodatul JannahBelum ada peringkat
- Tita Mardiana - TOPIK 4 - T4-7. Koneksi Antar Materi - Pancasila Dan Profil Pelajar Pancasila Dari Perspektif LainDokumen3 halamanTita Mardiana - TOPIK 4 - T4-7. Koneksi Antar Materi - Pancasila Dan Profil Pelajar Pancasila Dari Perspektif LainIbnul MubarokBelum ada peringkat
- Jurnal Pengantar 13Dokumen16 halamanJurnal Pengantar 13Einstein AlbertBelum ada peringkat