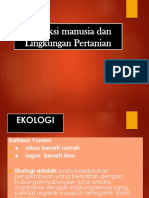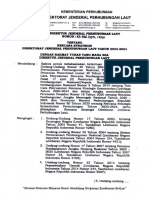Adoc - Pub Upaya Pelestarian Ekologi Tatar Sunda
Diunggah oleh
Sela RenikaDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Adoc - Pub Upaya Pelestarian Ekologi Tatar Sunda
Diunggah oleh
Sela RenikaHak Cipta:
Format Tersedia
Upaya Pelestarian Ekologi Tatar Sunda
Johan Iskandar
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 1
ABSTRAK
Pada masa silam orang Sunda pada umumnya memiliki kemampuan memanfaatkan sumber
daya alam dan mengelola lingkungan atau ekosistemnya secara lestari. Hal tersebut antara lain
dikarenakan orang Sunda memiliki pengetahuan ekologi tradisional (Traditional Ecological
Knowledge-TEK) yang mendalam dan memiliki pandangan ekologis terhadap ekosistemnya.
Pengetahuan ekologi tradisional orang Sunda tersebut biasanya diperoleh dari hasil pewarisan
dari leluhurnya secara turun temurun dan dari pengalam pribadi melalui trial and error secara
berkelanjutan sepanjang hayatnya. Selain itu, orang Sunda juga dalam kehidupannya
memiliki pandangan ekologis, bahwa mereka dalam kehidupan sehari-harinya mengganggap
dirinya tidak bebas, terlepas dari pengaruh faktor-faktor biotik dan abiotik, serta kekuatan
makrokosmos. Karena itu, dengan berbekal berbagai pengetahuan ekologi tradisional, serta
dibalut dengan pandangan ekologis, orang Sunda di masa silam memiliki berbagai kearifan
ekologi dalam mengelola lingkungannya. Misalnya, kearifan ekologi dalam pemanfaatan tata
ruang secara tradisional dengan sistem zonasi berdasarkan landasan kesakralan wilayahnya,
dan kesuaian untuk penggunaannya. Pun dalam pengelolaan sistem pertanian, orang Sunda
senantiasa berlandaskan pada sistem pengetahuan ekologi tradisional dan teknologi asli,
serta dengan mengadaptasikan dengan ekosistem lokalnya. Hal ini diwujudkan dalam
pengelolaan sistem agroforestri asli orang Sunda, seperti sistem ladang (huma), talun-kebun
dan pekarangan, dengan menanam keanekaan jenis tanaman yang sangat tinggi. Pun dalam
sistem pengelolaan sawah, orang Sunda pada umunya dengan menanam aneka ragam varietas
padi lokal, dan biasa dipadukan dengan budidaya ikan atau pun budidaya palawija. Karena
itu, sistem pertanian tradisional tersebut memiliki ketangguhan dan mampu menghadapi
berbagai perubahan lingkungan yang tidak menentu sepanjang waktu, seperti bencana
kekeringan, banjir, ledakan hama, serta pengaruh perubahan ekonomi pasar. Namun,
sayangnya kini berbagai pengetahuan ekologi tradisional dan pandangan ekologis yang
terwujud dalam rasa hormat orang Sunda terhadap ekosistem tersebut telah banyak
mengalami perubahan. Akibatnya, kini tidak dapat dihindari lagi timbulnya berbagai bencana
ekologi, seperti kerusakan hutan, banjir, kekeringan, dan ledakan hama, yang pada dasarnya
semua itu diakibatkan oleh ulah manususia yang kurang atau tidak bijaksana terhadap
lingkungannya. Karena itu, seyogianya berbagai konsep pengetahuan dan teknologi
tradisional orang Sunda yang cukup baik dalam memanfaatkan dan mengelola ekosistemnya,
jangan dipandang sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman. Tapi, seyogianya, berbagai
pengetahuan ekologi tradisional dan kearifan ekologi tersebut dapat diintegrarasikan dengan
pengetahuan ilmiah Barat, sehingga dapat berguna dalam menunjang pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya alam secara lestari untuk menopang pembangunan berkelanjutan di
Indonesia.
Pada makalah ini, penulis mendiskusikan 3 aspek utama, yaitu tentang gambaran umum
ekosistem orang Sunda, konsep interaksi orang Sunda dan lingkungan atau ekosistemnya,
beberapa contoh upaya pelestarian ekologi orang Sunda, dan kesimpulan tentang perlunya
integrasi sistem pengetahuan lokal dan teknologi tradisional orang Sunda dengan pengetahuan
ilmiah Barat untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Kata kunci: pelestarian ekologi, pengetahuan lokal,orang Sunda, Tatar Sunda.
Pendahuluan
Ekologi tatar Sunda memiliki sifat karakteristik menarik.Lingkungan di bagian utaranya
berupa dataran rendah.Sementara itu, di bagian selatannya, merupakan kawasan bergunung-
gunung dengan ditutupi hutan khas pegunungan (Lombard, 1996: 29-30).Ditilik dari sejarah
ekologi, hingga akhir abad 17 hampir seluruh wilayah di tatar Sunda masih ditutupi hutan
lebat dengan populasi jarang (Hardjono, 1987: 26).Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 2
orang Sunda di masa silam, dalam upaya mengadaptasikan dirinya terhadap lingkungan hutan
pegunungan dengan populasi jarang, guyub mengelola sistem usaha tani huma (swidden
cultivation system) (de Haan, 1910; Terra, 1958: 161; Geertz, 1963: 14; Iskandar, 1998).
Jadi, kendatipun penduduk dataran rendah di tatar Sunda semasa pra-islam, seperti masa
kerajaan Pajajaran kemungkinan telah mengenal sistem sawah.Tapi, penduduk di pedalaman
guyub berladang (ngahuma) yang dipadukan dengan budidaya tanaman lada
(Koentjaraningrat, 1972: 54).Sementara itu, sistem sawah yang aslinya berasal dari Jawa
Tengah, pertama kali dilaporkan penetrasi ke kawasan Jawa Barat dari Sumedang dan
Tasikmalaya terjadi di akhir 1750 (Terra, 1958:161; Geertz, 1963: 44).
Namun, berdasarkan perkembangan sejarah ekologi, sistem huma di tatar Sunda dari waktu ke
waktu terus terdesak, mengingat sistem tani huma dilarang pemerintah sejak masa kolonial
Belanda, ditambah pula jumlah penduduk kian padat (bandingkan Kools, 1935). Akibatnya,
kini sistem huma hampir punah di tatar Sunda, kecuali masih ditemukan di kawasan
G.Kendeng, Banten Selatan, yang dipraktikan oleh masyarakat Baduy dan di kawasan
G.Halimun yang dipraktikan oleh masyarakat Kasepuhan (Iskandar, 1998:3). Sebaliknya,
sistem sawah seiring dengan perubahan waktu, terus berkembang dan lebih mendapat
perhatian pemerintah sejak masa Kolonial Belanda hingga kini.
Namun demikian, walau pun sistem huma hampir punah, Orang Sunda dalam upaya
mengadaptasikan dirinya pada kawasan hutan pegunungan, tetap mengelola pertanian
berlandaskan hutan, yaitu mengelola sistem talun-kebun. Sistem talun-kebun ini merupakan
sistem pertanian asli orang Sunda (Terra, 1958: 160). Pada dasarnya sistem talun-kebun
adalah merupakan evolusi dari sistem huma yang telah dimodifikasi, disesuaikan dengan
penduduk yang kian padat dan ekonomi pasar makin pesat (Iskandar, 2009a: 151). Selain itu,
di sekitar rumah-rumah penduduk juga dikembangkan sistem pekarangan. Pada sistem
pekarangan itu biasa pula diintegrasikan dengan kolam pekarangan. Hal ini merupakan
adaptasi penduduk pegunungan di tatar Sunda terhadap lingkungannya yang banyak air (cur-
cor cai). Pun penduduk di tatar Sunda mengembangkan sistem sawah khas pegunungan,
berupa sistem sawah terasering (ngais gunung), untuk adaptasi terhadap erosi tanah dan
longsor.
Berdasarkan perkembangan agroforestri global, sistem huma, talun-kebun, dan pekarangan
dapat dikategorikan sebagai agroforestri tradisional (Nair, 1985; Von Maydell, 1985;
Christanty dkk, 1986). Yaitu suatu sistem pertanian asli penduduk hasil pewarisan turun
temurun yang menerapkan sistem penanaman campuran aneka ragaman tanaman semusim
dan tanaman keras pepohonan kayu. Struktur tajuk vegetasinya berlapis-lapis menyerupai
hutan alami. Karena itu, sistem huma, pekarangan dan talun-kebun miliki banyak manfaat
ekologi dan sosial ekonomi budaya, serta sangat adaptif terhadap berbagai perubahan
lingkungan, seperti gangguan hama, kekeringan, banjir dan goncangan ekonomi pasar
(Iskandar, 2009a:142).
Jadi, ditilik dari sejarah ekologi, orang Sunda di masa silam memiliki kemampuan beradaptasi
dengan baik dengan lingkungan/ekosistem lokalnya.Mereka memiliki kemampuan untuk
memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya secara lestari. Hal tersebut antara lain
dikarenakan orang Sunda di masa silam, memiliki pengetahuan ekologi tradisional
(Traditional Ecological Knowledge-TEK) yang mendalam. Pun mereka memiliki pandangan
ekologis, yaitu bahwa dalam kehidupan orang Sunda senantiasa berupaya untuk menjaga
keharmonisan dengan alam (lihat Hidding, 1948; Wessing, 1978, Iskandar 1998).
Namun sayangnya, kini pengetahuan ekologi tradisional dan pandangan ekologis orang
Sunda, banyak yang telah luntur.Akibatnya, berbagai kearifan ekologis orang Sunda juga
banyak yang telah hilang. Maka, timbul berbagai tindakan manusia yang tidak atau kurang
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 3
bijaksana terhadap alam dan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan serta bencana
ekologis, seperti banjir, kekeringan, dan ledakan hama pertanian (Iskandar, 2009a: 6).
Pada makalah ini, 3 aspek dibahas oleh penulis, yaitu gambaran umum ekologi tatar
Sunda, interaksi orang Sunda dengan lingkungannya, beberapa contoh pengelolaan
lingkungan oleh orang Sunda, dan tentang perlunya pengintegrasian pengetahuan ekologi
tradisional dengan pengetahuan ilmiah Barat, guna mendukung upaya pelestarian lingkungan,
untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Interaksi Orang Sunda dengan Ekosistemnya
Ditilik dari kajian ekologi manusia, manusia seperti halnya mahluk hidup lainnya senantiasa
terlibat dalam hubungan timbal balik yang sangat kompleks dengan lingkungannya.Namun,
berbeda dengan mahluk hidup lainnya, manusia dalam berinteraksi timbal balik dengan
lingkungannya dipengaruhi kuat oleh kebudayaan dengan sistem sosialnya (Rambo 1983;
Ingold, 1992; Marten, 2001; Iskandar 2009a).Sistem sosial dalam hal ini dartikan sebagai
segala sesuatu yang dimiliki manusia, seperti pengetahuan, nilai, kepercayaan, teknologi,
organisasi sosial dan lainnya (Marten 2001:1).Sementara itu, kebudayaan dalam hal ini
diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang dimiliki manusia sebagai mahluk
sosial.Kebudayaan manusia tersebut berisi berbagai perangkat model pengetahuan yang
secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang
dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya
(Suparlan, 2005: 114). Jadi, sistem sosial dan kebudayaan manusia dapat berperan penting
dalam proses adaptasi manusia terhadap ekosistem lokal, agar manusia dapat hidup secara
berkelanjutan (Ingold, 1992:39; Marten, 2001:2).
Di antara berbagai unsur sistem sosial budaya manusia, sistem pengetahuan ekologi lokal,
nilai dan kepercayaan, memiliki peran penting bagi manusia dalam memanfaatkan dan
mengelola sumber daya alam dan lingkungannya secara berkelanjutan.Pengetahuan lokal atau
pengetahuan asli (Indigenous Knowledge-IK) atau pun pengetahuan ekologi tradisional
(Traditional Ecological Knowledge-TEK) memiliki sifat sangat khusus. Misalnya, IK
sifatnya lokal; IK ditransmisikan secara lisan dengan bahasa ibu, secara turun temurun; dan
IK merupakan hasil pengalaman dari keterlibatan penduduk dalam praktik sehari-hari dalam
berinteraksi dengan lingkungan lokalnya dalam kurun waktu sangat panjang (diakronik), dan
dengan dikuatkan oleh berbagai pengalaman yang sangat kaya, melalui trial dan error
(Cotton, 1976: 86; Ellen dan Harris, 2002:4-5). Hal tersebut berbeda dengan pengetahuan
ilmiah Barat, yang bersifat berlandaskan rasionalisme, penyederhanaan atau
mensimplifikasian, dan disebarkan secara tertulis (Cotton, 1976; Marten, 2001: 122; Keraf,
2002: 253-261).
Pada umumnya masyarakat lokal secara lintas budaya di berbagai negara, termasuk orang
Sunda memiliki pengetahuan ekologi tradisional yang sangat mendalam.Bahkan, pengetahuan
ekologi tradisional tersebut lebih mendalam dari pengetahuan ilmiah Barat. Pun memiliki
peran sangat penting untuk pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi lingkungan secara
lestari (bandingkan Maffi, 2004: 11). Biasanya sistem nilai dan kepercayaan manusia terhadap
lingkungan, antara lain diwujudkan dalam bentuk pantangan atau tabu (pamali atau teuwasa)
dan penghormatan terhadap alam yang disakralkan (karamat), dan hal ini menjadi penting
dalam upaya konservasi alam tradisional oleh penduduk lokal secara mandiri. Dengan kata
lain, bahwa keputusan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam dan mengelola
lingkungan ditentukan sangat ditentukan antara lain oleh bagaimana sumber daya alam dan
lingkungan dipersepsikan oleh penduduk lokal (Cotton, 1996: 245; Carlson dan Maffi, 2004:
2 ).
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 4
Karena itu, tidaklah heran orang Sunda di masa silam, mampu memanfaatkan dan mengelola
lingkungan secara lestari dan mandiri, mengingat mereka mempunyai pengetahuan lokal dan
landasan kepercayaan (kosmos) yang kuat dalam mengelola ekosistemnya. Kini, walaupun
sistem pengelolaan lingkungan berbasis pengetahuan ekologi tradisional dan landasan adat
cenderung kian langka di tatar Sunda, namun sistem tersebut masih dapat dijumpai. Beberapa
contohnya diberikan di bawah ini.
Pengelolaan Tata Ruang Urang Sunda SecaraTradisional
Pada masa silam urang Sunda sangat peduli terhadap penataan ruang untuk kehidupan sehari-
hari. Hal ini, antara lain, dapat disimak dalam naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian
(Kropak 632) yang memberi wejangan, antara lain agar manusia bijaksana dalam
pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan. Berdasarka naskah Sunda tersebut, telah
dikenaal tak kurang dari 19 kategori lahan yang harus dihindari untuk dibangun manusia,
yang disebut ‘kotoran bumi’.
Lahan tersebut antara lain, lahan sarongge (tempat angker), lemah sahar (tanah sangar),
sema (kuburan), catang ronggeng (lahan dengan lereng curam), garenggengan (permukaan
tanah kering, tetapi di bawahnya berlumpur), dangdang wariyan (lahan legok yang sering
tergenang air), lemah laki (tanah tandus yang curam), kebakan badak (kubangan, termasuk
kolam besar), hunyur (bukit kecil), pitunahan celeng (tempat babi), kalomberan (comberan),
dan jarian (tempat buang sampah) (Murtiyoso, 1994: 64-65).
Kini, kendati kian pudar, pengelolaan tata ruang lokal dan usaha konservasi alam mandiri
oleh masyarakat lokal dapat ditemukan pada beberapa kelompok masyarakat Sunda, seperti
masyarakat Kampung Dukuh, Garut Selatan, misalnya, mengenal pengelolaan tata ruang
secara adat. Wilayah Kampung Dukuh menurut adat dapat dibagi atas 5 zona pemanfaatan.
Zona tersebut adalah lahan garapan untuk bertani, lahan larangan berupa lahan hutan dengan
makam karomah yang dikeramatkan, lahan titipan (awisan) berupa lahan yang dicadangkan
untuk awisan para pendatang, lahan tutupan berupa lahan hutan untuk kepentingan ekologis,
dan lahan cadangan bagi perluasan lahan pertanian (YP2AS, 2005).
Di kampung Naga,Tasikmalaya, secara adat wilayahnya dibagi menjadi tiga zona. Zona
pertama adalah kawasan suci, tempat hutan keramat yang dikonservasi secara adat.Zona
kedua adalah kawasan bersih atau daerah permukiman.Adapun zona ketiga adalah kawasan
kotor, yaitu tempat mandi, mencuci, kolam pekarangan, dan kandang ternak (Suganda, 2006).
Pada masyarakat Kasepuhan Cibedug, Sukabumi, tata ruangnya dibagi menjadi tujuh zona,
yaitu leuweung titipan (hutan titipan), leuweung kolot (hutan tua), leuweung cadangan (hutan
cadangan), kompleks keramat (situs), walungan (sungai), mata air dan lain-lain (Yogaswara,
2009: 118).
Demikian pula di Baduy, Banten Selatan, wilayahnya secara adat dibagi menjadi beberapa
zona berdasarkan kesakralannya. Kawasan leuweung gede/leuweung titipanPusaka Buana,
Cikeusik, dan Sasaka Domas di Cibeo, Baduy Dalam dianggap paling sakral serta
dimanfaatkan untuk tempat ziarah. Zona baagian luarnya juga dianggap sakral, yaitu kawasan
Baduy Dalam.Bagian luarnya, kawasan Baduy Luar, dihuni orang Baduy Luar (panamping),
dianggap kurang sakral. Sementara bagian paling luar dari kawasan Baduy merupakan zona
penyangga, yaitu Daerah Dangka, kawasan enclave di desa-desa muslim tetangga Baduy.
Pada setiap bukit Baduy juga dikelola dengan sitem zonasi, yaitu dibagi 3 zonasi.Zona
pertama, bagian lembah bukit, dijadikan permukiman dan kampung (dukuh lembur) yang
tidak boleh dibuka.Kawasan hutan di sempadan sungai juga dikonservasi orang Baduy.Zona
kedua, di atas permukiman, digunakan untuk berladang (ngahuma) serta tempat hutan
sekunder bekas ladang yang sedang diberakan (reuma). Sementara itu, zona ketiga di puncak
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 5
gunung berupa hutan tua (leuweung kolot), pantang dibuka dijadikan huma (Iskandar,
2009b:98-99).
Konsep pemanfaatan tata ruang orang Sunda ini sejalan dengan konsep ilmiah Barat,
seperti pembagian zonasi pengelolaan taman nasional maupun cagar biosfer (lihat Soedjito,
2004: 7), atau pun evaluasi pemanfaatan dan perencanaan penggunaan lahan (lihat Beets,
1990: 226).
Pengelolaan Sistem Huma
Dewasa ini, dalam kondisi iklim kian tak menentu, seperti timbulnya bencana kekeringan
dan banjir, kerap timbulnya ledakan hama, dan pengaruh ekonomi yang sering bergejolak,
sistem huma seperti yang dikelola oleh masyrakat Baduy, di Desa Kanekes, Kecamatan
Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten Selatan masih cukup dapat diandalkan dalam
mengadaptasikan terhadap berbagai perubahan lingkungannya yang kian tak menentu
tersebut. Hal tersebut antara lain, karena penduduk peladang (pahuma), Urang Baduy
memiliki strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang kian tak menentu
dan ekonomi pasar yang deras melanda desanya. Misalnya, menyusun kalender pertanian
secara mandiri, dan menanam aneka ragam tanaman pada sistem huma (Iskandar, 1998;
Iskandar, 2007).
Pada umumnya masyarakat Baduy dalam mengelola sistem huma menggunakan sistem
kalender pertanian yang disusun mereka sendiri secara mandiri.Dalam kondisi normal, tahun
baru kalender pertanian Baduy atau disebut tunggul tahun, disebut bulan Safar/Kapat
(bertepatan dengan April-Mei).Tunggul tahun biasanya ditetapkan pimpinan adat (puun),
dengan menggunakan perhitungan tradisional disertai dengan hasil pengamatan berbagai
indikator di alam, misalnya kehadiran serangga dan sarang labah-labah (lancah kidang), serta
perputaran rasi bintang, seperti bentang kidang (the belt of orion) dan bintang kartika (the
Pleiades). Misalnya, jika sarang lancah kidang di rerumputan telah terlihat bolong tengahnya,
tanam padi ladang harus segera dimulai.Sedangkan masa berbuah kanyere (Bridelia monoica)
matang mengindikasi memulai musim kemarau.Bentang kidang khususnya telah menjadi
indikator utama dalam menyusun kalender pertanian urang Baduy.Karena itu, tak heran
apabila dikenal berbagai ungkapan sehari-hari urang yang menggambarkan tentang posisi
bentang kidang di alam dan pekerjaan ngahuma yang harus dikerjakan.Contohnya tanggal
kidang turun kujang.Hal ini artinya, apabila bentang kidang tampak terlihat di ufuk timur
menjelang subuh, orang Baduy harus mulai menebang semak-semak belukar dengan kujang
(parang khusus orang Baduy Dalam).Tanggal kidang biasanya bertepatan dengan dengan
musim kemarau atau dalam bulan Baduy, mulai bulan Sapar (April-Mei) dan Kalima (Mei-
Juni).Kidang ngarangsang kudu ngahuru (posisi bintang seperti ngarangsang harus
membakar sisa tebangan sebak belukar), biasanya pada bulan Kanem (Juni-Juli) dan Kapitu
(Juli-Agustus), kidang nyuhun atawa condongka barat kudu ngaseuk (posisi kidang tepat di
atas kepala atau sudah mulai miring ke barat harus tanam padi), biasanya mulai bulan Kapitu
(Juli-Agustus), Kadalapan (Agustus-September) dan Kasalapan (September-
Oktober).Sebaliknya, apabila bentang kidang tidak menampakan lagi, biasanya bertepatan
dengan bulan Kasalapan dan Kasapuluh (Oktober-Nopember) harus segera berakhir musim
tanam padi ladang. Karena tanahnya dianggap telah panas dan banyak hama. Hal ini biasanya
diungkapkan orang Baduy, seperti kidang marem turun kungkang ulah melak pare (kidang
hialng tak boleh tanam padi banyak hama kungkang). Maka, dengan ada kalender tradisional
ini, menyebabkan pengerjaan tiap tahapan-tahapan ladang serempak dan kompak dilakukan
oleh segenap warga Baduy. Hal ini penting untuk mengadaptasikan pada kondisi iklim yang
kian tak menentu di alam, dan menanggulangi hama pertanian.
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 6
Berdasarkan pengelolaan tanaman di huma di masyarakt Baduy, biasanya bagi para
keluarga yang menggarap ladang cukup luas, 0,5 ha atau lebih, di dalam lahan ladang mereka
secara adat wajib tanam 3 varietas padi sakral, yaitu pare koneng, pare siang, dan pare ketan
langgasari. Tiga varietas pare sakral tersebut secara ada diharuskan ditanam di ladang
(huma) secara terpisah, tidak boleh bersinggungan. Karena itu, pare koneng biasanya ditanam
di tengah ladang, pare siang di bagian timur, dan pare ketan langgasari ditanam di bagian
barat. Untuk sebagai pemisah tiga varietas padi sakral tersebut, biasa dipisahkan (dipasing)
oleh beberapa varietas padi lainnya yang non-sakral. Karena itu, pada setiap petak ladang
biasanya minimal ditanami 5 varietas padi. Maka, secara total varietas padi ladang di Baduy
Dalam dan Baduy Luar, telah tercatat 89 varietas (Iskandar dan Ellen, 1999). Pemisahan
penanaman padi tersebut sangat penting sebagai upaya untuk menjaga kemurnian benih
varietas padi, mengingat tanaman padi di alam dapat melakukan penyilangan satu sama
lainnya (bandingkan Richard, 1994).
Selain tanaman padi, di ladang juga biasa ditanami aneka ragam tanaman semusim lainnya,
seperti tambahan pangan pokok, sayuran, bumbu masak, buah-buahan dan tanaman
obat.Karena itu, panen aneka ragam jenis tanaman dapat dilakukan secara waktu yang
bergiliran hampir sepanjang tahun. Hasil utama huma adalah padi huma dan tabu diperjual
belikan. Hasil padi huma biasanya disimpan di lumbung-lumbung padi hingga puluhan
tahun.Namun, berbagai hasil non padi, seperti pisang, petai, durian, dan lain-lainnya tidak
pantang dijual.Uang tunai hasil penjualannya biasanya digunakan untuk membeli beras dan
kebutuhan sehari-hari lainnya.Karena itu, ketika masih tersedia cukup uang tunai untuk
membeli beras, padi ladang jarang dikonsumsi sehari-hari, dan hanya digunakan untuk upcara
adat tiap tahapan penyelenggaraan pengerjaan ladang, dan upacara adat lainnya. Di samping
itu, adanya keanekaragaman tanaman di ladang, sistem ladang juga lebih tahan terhadap
serangan hama, dan menghindari kegagalan panen akibat berbagai gangguan lingkungan,
seperti bencana kekeringan, banjir dan serangan hama, serta menghindari harga jual yang
jatuh di pasar (bandingkan Rambo, 1984: 156; Altieri dan Vulkasin,1988: 98; Iskandar, 2007:
130;Berkes 1999: 61).
Pengelolaan Sistem Talun-Kebun
Talun adalah istilah Orang Sunda masa silam, untuk kebun buah-buahan atau kebun kayu-
kayu di sekitar mukiman atau pun di pemukiman (bandingkan Terra, 1958:161) .Istilah talun
saat ini kurang dikenal lagi oleh generasi muda, istilahnya lebih banyak dikenal sebagai kebun
tatangkalan, kebun campuran atau sebagai dudukuhan (Iskandar, 2009a).Berbeda dengan
sistem huma yang kian langka, sistem talun-kebun masih cukup banyak dipraktikan oleh
masyarakat Sunda.Sistem talun-kebun sangat bervariasi dan dipengaruhi faktor-faktor biofisik
lokal dan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.Namun, secara
umum sistem talun-kebun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu masih menggunakan
rotasi tahunan dan tidak mennggunakan rotasi tahunan.
Pada sistem talun-kebun yang menggunakan rotasi tahunan, biasanya setiap tahunan, sebagai
lahan dari satu lahan talun atau kebon tatangkalan atau kebon awi dibuka untuk dijadikan
kebun tanaman semusim.Karena itu, tak heran bahwa sistem talun tersebut disebut pula
sebagai sistem talun-kebun.
Di daerah Paseh, Majalaya, jenis tanaman semusim yang utama ditanam penduduk adalah
tembakau, serta jenis-jenis tanaman semusim lainnya, antara lain bawang merah, kacang
merah, cabai merah, leunca, terong, jagung, bonteng, laja, kunir, dan talas. Di daerah Cirata,
Purawakarta dan Cianjur, jenis tanaman semusim yang ditanam, antara lain padi gogo, dan
jenis-jenis tanaman lainnya, seperti cengek, jagung, bayam, dan singkong.
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 7
Jenis-jenis tanaman semusim dipanen secara berurutan. Di lain pihak, saat panen, jenis-jenis
tanaman semusim, yaitu beberapa tanaman tahunan, seperti sisa-sisa tebangan bambu dan
albasiah, tumbuh dan bertunas kembali di kebun, bercampur dengan tanaman semusim. Pada
fase ini, lahan tersebut bukan dinamakan kebun lagi, melainkan biasa disebut kebon
campuran.
Lantas, apabila jenis-jenis utama semusim, seperti kacang roay/kasus di Soreang, Bandung
Selatan, tembakau dan bawang merah/kasus di Majalaya, dan padi gogo/kasus di Cirata usai
dipanen, lahan kebun campuran tersebut menjadi rimbun dan didominasi tanaman tahunan,
antara lain bamboo/awi tali, ater, gombong, albasiah, petai, tisuk, dan aren. Maka, kini
tataguna lahan tersebut kini bukan dinamakan kebun campuran lagi, melainkan talun, seperti
talun awi atau talun tatangkalan.Mengingat talun itu menjadi rimbun, tahun berikutnya petani
pindah menggarap petak talun lainnya.
Apabila disimak dari sistem talun-kebun, pada hakikatnya sistem tersebut merupakan
modifikasi dari sistem huma yang telah dimodifikasi dan diadaptasi penduduk lokal,
disesuaikan dengan kondisi biofisik lokal dan sosial ekonomi masyarakat. Jadi, pada sistem
talun-kebun, (a) fase kebun beranologi dengan fase huma pada sistem huma, (b) fase kebun
campuran beranalogi dengan fase reuma ngora pada sistem huma, dan (c) fase talun
beranalogi dengan reuma kolot pada sistem huma.
Salah satu ciri khas agroforestri tradisional talun, antara lain ditanami aneka ragam
campuran jenis-jenis tumbuhan semusim dan tahunan. Berbagai jenis tumbuhan tersebut
membentuk struktur vegetasi berlapis-lapis menyerupai hutan alami.Mengingat susunan
vegetasi tradisional menyerupai struktur vegetasi hutan alami, tak heran bila agroforestri
memiliki fungsi ekologi yang lazim dimiliki hutan, selain juga mempunyai fungsi sosial,
ekonomi, dan budaya bagi masyarakat.
Contoh fungsi ekologi, antara lain perlindungan plasma nutfah, perlindungan bahaya erosi
tanah, pengatur sistem hidrologi, efek iklim mikro, penghasil oksigen, penyerap CO2, dan
habitat satwa liar. Adapun fungsi sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat, antara lain
fungsi produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga (subsisten) dan
komersil. Pengelolaan sistem agroforestri talun-kebun orang Sunda, ini sangat sejalan dengan
konsep ilmiah Barat, seperti bersifat penting pengelolaan lingkungan berlandaskan prinsip-
prinsip ekologi dan dapat mengkonservasi aneka ragam kehati dan membantu
penanggulangan sumbangan kebutuhan pangan untuk menanggulangi kemiskinan pedesaan
(bandingkan Altieri dan Vulkasin, 1988: 17; Van Noordwijk, 2010: 56)
Pengelolaan Sistem Pekarangan
Pada masa silam, orang Sunda dikenal memiliki aneka ragam pengetahuan lokal untuk
mengelola lingkungannya, yang diperoleh secara pewarisan dari leluhurnya dan dengan
melalui pengujian secara trialand error sepanjang hayatnya secara berkelanjutan. Aneka
ragam pengetahuan lokal tersebut, di antaranya dapat menghasilkan berbagai kearifan ekologi
penduduk dalam mengelola lingkungannya. Misalnya, di Tatar Sunda dikenal adanya sistem
pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan antara pertanian, peternakan dan perikanan
(integrated agriculture-aquaculture) dalam suatu sistem pekarangan dan kolam pekarangan
pedesaan. Suatu sistem agroforestri tradisional yang lebih komprenhensif dari sistem
agroforestri yang diperkenalkan sistem Barat, yang mulai dipopulerkan baru di akhir 1970-an
(bandingkan Von Maydell, 1985; Nair, 1985).
Pada dasarnya pengelolaan sistem pekarangan kolam pedesaan tersebut merupakan
kearifan ekologi orang Sunda dalam mengadaptasikan dirinya dalam lingkungan yang banyak
air (cur cor loba cai). Kolam-kolam pekarangan tersebut biasanya dibangun di depan,
samping atau belakang rumah, yang pada umumnya diintegrasikan dengan sistem pengelolaan
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 8
pekarangan yang rimbun ditanami aneka ragam campuran tanaman semusim dan tahunan
dengan bercanpur baur, termasuk dengan pemeliharaan ternak. Karena itu, fungsinya dapat
beraneka ragam, seperti fungsi ekologis, untuk perlindungan erosi, menyuburkan tanah,
mengatur sistem hidrologi, mengatur iklim mikro dan lainnya, serta fungsi sosial ekonomi
budaya, antara lain untuk produksi pemenuhan kebutuhan sehari-hari (produksi subsisten) dan
hasil surplusnya dapat dijual (produksi komersil).
Tidak hanya itu, keberadaan aneka ragam tanaman keras, seperti buah-buahan dan kayu
lainnya di pekarangan juga dapat berfungsi penting dalam menyerap karbon (CO2) di atmofer,
yaitu melalui proses fotosintesis diubah jadi karbohidrat, kemudian disebar keseluruh organ
tanaman, untuk pertumbuhan daun, batang, ranting, bunga, dan buah. Kaena itu, aneka ragam
jenis tanaman pekarangan dapat berperan penting dalam penimbunan/rosot karbon dan dapat
berperan dalam meredam pemanasan global penyebab perubahan iklim. Ditambah pula,
pepohonan di pekarangan jarang ditebangi dan dibakar, sehingga karbon yang telah diikat
tanaman tidak dikembalikan ke atmosfer. Karena itu, cadangan karbon di pekarangan cukup
tinggi. Misalnya, hasil pengukuran cadangan karbon pekarangan di Rancakalong, Sumedang,
Jawa Barat tercatat 26.3 Mg/ha, dengan didominasi dari tanaman buah-buahan (55,10 %)
(Hadikusumah 2010). Sementara itu, cadangan karbon di hutan primer rimbun di Kalimantan
Timur, tercatat 230,1 Mg/ha (Rahayu dkk, n.d: 31).
Pengelolaan Sistem Sawah
Pada umumnya ekosistem sawah di tatar Sunda sangat bervariasi, yaitu dapat dibedakan
berdasarkan sistem pengairannya, lokasi topografi sawah, kandungan air dan kesuburan tanah.
Berdasarkan sistem pengairannya, sawah dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu sawah
berigasi dan sawah non irigasi atau sawah tadah hujan atau pun disebut pula sawah guludug.
Ditilik dari topografinya, menurut masyarakat Sunda di Rancakalong, Sumedang
berdasarkan lokasi topografinya, sawah dapat dibedakan secara umum atas 2 tipe, yaitu sawah
yang terletak di bukit-bukit atau gunung (sawah gunung) dengan hamparan sawah kecil-kecil
dengan sistem terasering nyabuk (ngais) gunung dan sawah-sawah di dataran rendah (sawah
landeuh)dengan hamparan luas (sawah lega) biasanya tanpa terasering. Sementara itu, sawah
berdasarkan kandungan air dan kesuburannya, di tatar Sunda dikenal sawah berair banyak dan
berawa-rawa, serta berlumpur (sawah ledok) dan sawah kering tidak banyak mengandung air
(sawah jengkar) (Melia 2007; Warsiti 2009).
Mengingat adanya aneka ragam tipe sawah di tatar Sunda, maka para petani di tatar Sunda
biasanya membudidayakan aneka ragam varietas padi lokal yang sesuai dengan kondisi
ekologi lokalnya, seperti sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah gunung, sawah landeuh,
sawah ledok dan sawahcengkar. Misalnya, di sawah ranca biasanya ditanami petani oleh
berbagai padi lokal yang gabahnya tahan rontok (ranggeuyan), dengan memiliki karakteristik
batang tinggi (jarami jangkung), dan tahan terhadap genangan air. Demikian pula, pada sawah
gunung biasa ditanam juga berbagai varietas pare ranggeuyan yang tahan terhadap kurang
cahaya matahari. Umur panen padi biasanya agak lambat (leuir) rata-rata 6 bulan. Sementara
itu, di sawah landeuh dan lega, biasa dibudidayakan kultivar padi lokal mudah rontok
(sengon), yang beradaptasi pada cahaya tinggi, temperatur tinggi, tidak berair banyak. Umur
panen padi tersebut biasanya relatif singkat (hawara) dengan rata-rata 4-5 bulan.
Di samping itu, mengingat usaha tani sawah dipengaruhi kuat oleh juga oleh budaya
penduduk, dengan dipengaruhi oleh rasa hormat pada Dewi Padi, Nyi Pohaci. Maka, pada
beberapa tahapan tanam padi senantiasa diadakan upacara adat. Biasanya untuk upacara adat
tersebut harus dipersembahkan sesajen yang diolah dari padi lokal. Konsekuesinya, para
petani sawah senantiasa, menanam kultivar padi lokal, karena hasilnya dibutuhkan untuk
berbagai upacara tradisional.
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 9
Mengingat adanya kergamaman tipe ekosistem sawah dan kebutuhan upacara adat, para
petani di tatar Sunda biasa menanam aneka ragam kultivar padi lokal. Misalnya, di
Rancakalong, Sumedang, pada era tahun 1960-an, sebelum Revolusi Hijau, tercatat 60
kultivar padi lokal (landraces) yang biasa ditanam petani sawah. Tapi, jumlah kultivar padi
tersebut kini tinggal tersisa sekitar 22 kultivar padi (Warsiti, 2009). Demikian pula, di
masyarakat Kasepuhan, Cisolok Sukabumi, yang tidak sepenuhnya menerima program
Revolusi Hijau, hingga tahun 1970-an, masih tercatat 112 kultivar padi lokal yang ditanam
penduduk. Namun, kini jumlahnya hanya tercatat sekitar 46 kultivar padi (Soemarwoto,
2007). Selain itu, sebelum Revolusi Hijau, pola tanam padi sawah dapat berotasi, dengan
disellingi memelihara ikan (mina padi) atau pun ditanami palawija. Karena itu, dengan
adanya sistem rotasi pola tanam padi sawah, serta adanya masa tanam dan panen serempak,
serangan hama padi sawah biasanya dapat dikurangi (bandingkan Lansing, 1991).
Penutup
Pada makalah ini penulis telah mendiskusikan tentang kondisi gambaran tentang ekologi
tatar Sunda dan pengelolaan Orang Sunda terhadap sumber daya dan lingkungannya yang
khas, seperti wilayahnya bergunung-gunung ditutupi hutan, tanahnya relatif subur dan banyak
air. Mengingat kondisi lingkungan yang khas tersebut, orang Sunda di masa silam telah
mampu mengadaptasikan diri terhadap lingkungannya, dengan memanfaatkan sumber daya
dan lingkungannya secara lestari. Hal tersebut terutama karena dibekali oleh pengetahuan
ekologi tradisional, serta nilai dan kepercayaan (values and beliefs). Misalnya, walapun istilah
agroforestri, secara global di dunia baru populer sekitar akhir tahun 1970-an (Von Maydell,
1985: 84). Namun, sebelum istilah agrtoforestri itu popular, orang Sunda dengan
berlandaskan pengetahuan ekologi tradisional, telah mempraktikan macam-macam sistem
agroforestri tradisional, seperti sistem huma, talun-kebun dan pekarangan, secara turun
temurun. Ciri khas dari macam-macam sistem agroforestri tradisional tersebut, antara lain
memiliki keanekaan tanaman tinggi. Karena itu, secara umum sistem agroforestri tradisional
tersebut lebih tahan terhadap serangan hama; anomali iklim, seperti kekeringan dan banjir,
serta tahan terhadap pengaruh pasar. Sedangkan, manfaatnya secara ekologis dan sosial
ekonomi sangat banyak, seperti bahan pangan dan non pangan (Altieri dan Vulkasin, 1988:
117-119).
Berbagai manfaat ekologis, misalnya mengingat struktur vegetasinya kompleks berlapis-lapis,
maka lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti energi matahari, air, dan
unsur hara kebutuhan tanaman. Tidak hanya itu, fungsi ekologi lainnya, yaitu perlindungan
kesuburan tanah; menjaga permukaann tanah dari erosi; memelihara sistem hidrologi;
perlindungan keragaman plasma nutfah; menyediakan habitat satwa liar; memelihara iklim
mikro; menghasilkan oksigen; dan menyerap gas emisi pencemar ke udara, khususnya gas
rumah kaca CO2, yang menjadi salah satu penyebab pemenasan global.
Sementara itu, berbagai fungsi sosial ekonomi budaya agroforestri tradisional, antara lain
total produksi per unit lahan lebih efisien; produksinya dapat dipanen sepanjang tahun; dan
aneka ragam produksi dapat digunakan sebagai tambahan pangan pokok, bumbu masak,
bahan sayur, buah-buahan, bahan obat tradisional, bahan kerajinan, bahan upacara adat, dan
lainnya, untuk memenuhi kebutuhan subsisten dalam keluarga dan hasil lebihnya bisa dijual
untuk sumber pendapatan keluarga. Maka, keberadaan agroforestri tradisional, sungguh
penting untuk konservasi lingkungan dan menopang kehidupan sosial ekonomi budaya
penduduk lokal.
Selain itu, aspek nilai dan kepercayaan penduduk terhadap alam atau ekosistem dapat
berfungsi penting sebagai adaptasi manusia dengan lingkungan (Lovelace, 1984:
96).Misalnya, menghormati dan tabu mengganggu atau merusak lingkungan yang dianggap
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 10
keramat, seperti makam, hutan keramat, sumber mata air, dan lainnya dapat berfungsi untuk
adaptasi dan menghindari kepunahan sumber daya alam.Tidak hanya itu, fungsi penting dari
nilai dan kepercayaan untuk membangun ‘solidaritas sosial’ dari berbagai keragaman latar
belakang individu. Misalnya, sebelum program Revolusi Hijau, para petani sawah, sebelum
memulai tanam padi, segenap warga desa biasa menentukan waktu tanam bersama dan juga
melaksanakan upacara adat bersama secara kompak. Pengaruhnya, masa tanam dan masa
panen padi dapat serempak. Karena itu, berbagai serangan hama dapat dihandari, karena daur
hidup dapat diputus dan tidak ada kekurangan air di musim kemarau (lihat Lansing, 1991).
Namun, sayangnya kini berbagai pengetahuan ekologi tradisional, serta nilai dan
kepercayaan orang Sunda cenderung telah luntur. Akibatnya, dengan kian merasuknya sistem
ekonomi pasar dan berubahnya pandangan masyarakat tradisional yang bersifat pandangan
ekologis, dengan pandangan Barat, bersifat pandangan antroposentris, dengan perlakuan
terhadap sumber daya alam bersifat ekspoitatif, dengan dilandasi pengetahuan ilmiah yang
menekankan rasionalisme, penyederhanaan atau mensimplifikasian, serta penggunaan
teknologi yang kurang ramah lingkungan (bandingkan Marten, 2001: 122; Keraf, 2002: 253-
261).
Konsekuensinya, timbul berbagai kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan dan
timbulnya bencana ekologi, seperti timbulnya ledakan hama padi sawah, akibat homogenisasi
penanaman varietas tanaman padi unggul, punahnya musuh-musuh alami hama, karena
intensifikasi penggunaan pestisida, dan masa tanam dan panen yang tidak serempak. Pun
banjir,longsor dan kekeringan kerap terjadi, karena terganggunya sistem hidrologi akibat
rusaknya kawasan hutan dan maraknya alih fungsi talun-kebun menjadi kebun komersil,
seperti kebun sayur. Kehancuran sumber daya alam tersebut dapat melemahkan usaha tani
dan ekonomi penduduk pedesaan. Karena itu, untuk pengembangan pertanian berkelanjutan,
seyogianya berbagai pengetahuan ekologi tradisional dan praktik-praktik pengelolaan usaha
tani para petani yang sejalan dengan pengetahuan ilmiah/pengetahuan Barat, seyogianya
diintergasikan dengan pengetahuan Barat dalam upaya untuk pengembangan pertanian
berkelanjutan di Indonesia
Referensi
Altieri, M. and H.L. Vulkasin (eds), 1988. Environmentally Sound Small-Scale Agricultural
Projects: Guidelines For Planning. New York: Codel Inc.
Carlson, T.J.S and Maffi, L. 2004. Introduction: Ethnobotany and Conservation of Biocultural
Diversity. Dalam Carlson, T.J.S and Maffi, L. (eds), Ethnobotany and Conservation of
Biocultural Diversity. New York: The New York Botanical Garden Press, Pp.1-6.
De Haan, F. 1910. Priangan.De Preanger-Regentschappen Onder Het Nederlandsch Bestuur
tot 1811, deel 1. Batavia:G.Kolff&Co.
Berkes, F. 1999. Sacred Ecology: Traditional Ecological Knowledge and Resource
Management. Philadelphia: Taylor Francis.
Christanty, L., J.Iskandar, O.S. Abdoellah, and G.G. Marten, 1986. Traditional Agroforestry
in
West Java: The Pekarangan (Homegarden) and Talun-Kebun (Annual-Perennial
Rotation) Cropping Systems. Dalam G.G. Marten (ed), Traditional Agriculture in
South East Asia: A Human Ecology Perspective. Boulder: Westview Press, 132-158.
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 11
Cotton, C.M. 1996. Ethnobotany: Principles and Applications. England: John Willey
and Sons.Ltd.
Ellen, R.F and H.Harris, 2000.Introduction. Dalam R.F. Ellen, P. Parkes, A.Bicker (eds),
Indigenous Environmental Knowledge and its Transformation: Critical
Annthrophological Perspective. Amsterdam: Hardwood Academic Publishers.
Geertz, C. 1963. Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia.
Berkeley and Los Angeles: Univertsity of California Press.
Hardjono, J. 1987. Land, Labour and Livelihood in a West Java Village. Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press.
Hidding, K.A.H. 1948. Geesteestur en Cultuur.Den Haag: Uitgeverij W.Van Hoeve.
Ingold, T. 1992.Culture and the Perception of the Environment. Dalam Croll, E. and
D.Parkin (eds), Bush Base:Forest Farm Culture, Environment and Develoment.
Routledge: London and New York, Pp.39-56
Iskandar, J. 1998. Swidden Cultivation As A Form of Cultural Identity: The Baduy Case.
Unpublished Ph.D Dissertation, University of Kent, at Canterbury, United Kingdom.
Iskandar, J. 2007. Responses to Environmental Stress in the Baduy Swidden System, South
Banten, Java. Dalam Ellen, R. (ed), Modern Crises and Traditional Strategies: Local
Ecological Knowledge in Island Southeast Asia. New York-Oxford: Berghahn Books:
Pp. 112-132.
Iskandar, J. 2009a. Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Bandung: Program
Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran.
Iskandar, J. 2009b. Pelestarian Daerah Mandala dan Keragaman Hayati Oleh Orang Baduy.
Dalam H.Soedjito, Y.Purwanto, E.Sukara (eds), Situs Keramat Alami: Peran Budaya
Dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Pp.
86-110.
Iskandar, J.and R.F. Ellen, 1999. In Situ Conservation of Rice Landraces Among the
Baduy of West Java.Journal of Ethnobiology 19 (1): 97-125.
Keraf, A.S. 2002.Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Koentjaraningrat, 1972.Sundanese. Dalam Lebar, E.M. (ed), Ethnic Groups of Insular
Southeast
Asia. New Haven: Human Relations Area Files Press. Pp. 54-56.
Kools, J.F. 1935. Hoema’s Hoemablokken En Boschreserves in De Residentie Bantam
Wageningen: H.Veenman & Zonen.
Lansing, J.S. 1991. Priests and Programmers: Technologies of Power in the Engineered
Landscape of Bali. Princeston, New Jersey: Princeston University Press.
Lombard, D. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu. Jakarta: Gramedia
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 12
Pustaka Utama.
Lovelace, G.W. 1984. Cultural Beliefs and the Mangement of Agroecosystems. Dalam
Rambo,
A.T., P.E. Sajise (eds), An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural
Systems in Southeast Asia. Hawaii: East-West Center. Pp. 194-205.
Maffi, L. 2004. Maintaining and Restoring Biocultural Diversity: The Evolution of a Role for
Ethnobiology. Dalam Carlson, T.J.S and Maffi, L. (eds), Ethnobotany and
Conservation of Biocultural Diversity. New York: The New York Botanical Garden
Press, Pp.9-35.
Marten, G. G. 2001.Human Ecology: Basic Concepts for Sustainable Development.
London: Earthscan.
Malia, R. 2007. Studi Pemanfaatan dan Pengelolaan Kultivar Padi Lokal di Desa
Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.Skripsi Jurusan
Biologi, FMIPA, Universitas Padjadjaran (Tidak Dipublikasikan).
Murtiyoso, S. 1994. Klasifikasi Lahan Pada Masyarakat Sunda Kuno, Sangyang Siksakanda
ng Karesian. Dalam K.Adimihardja (ed), Sistem Pengetahuan dan Teknologi Rakyat:
Subsistensi dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Kalangan Masyarakat
Sunda di Jawa Barat. Bandung: Ilham Jaya Pp. 61-70.
Nair, P.K.R, 1985. Classification of agroforetry Systems.Agroforestry Systems 3 (2): 97-128.
Rahayu, S., B.Lusiana dan M.van Noordwijk, (tt). Pendugaan Cadangan karbon di Atas
Permukaan Tanah Pada Berbagai Sistem Penggunaan Lahan di Kabupaten Nunukan,
Kalimantan. Dalam B. Lusiana, M. van Noordwijk, S. Rahayu (eds), Cadangan
Karbon di Kabupaten Kalimantan Timur: Monitoring Secara Spasial dan
Permodelan. Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF). Pp. 23-36.
Rambo, A.T. 1984. No Free Lunch: A Reexamination of the Energetic Efficiency of Swidden
Agriculture. Dalam Rambo, A.T., and P.E. Sajise (eds), An Introduction to Human
Ecology Rresearch on Agricultural Systems in Sourheast Asia. Honolulu: East-West
Center, Pp. 154-163.
Richards, P. 1994. Local Knowledge Formation and Validation: The Case of Rice Production
in Central Sierra Leone. Dalam Scoones, I, Thompson, J. (eds), Beyond Farmer First:
Rural People’s Knowledge, Agricultural Research and Extension Practice. London:
Intermerdiate Technology Publication, Pp. 165-170.
Soemarwoto, O., L.Christanty, Henky, Y.H. Herri, Johan Iskandar, Hadyana and Priyono,
1985. The Talun-Kebun: A Man-Made Forest Fitted to Family Needs. Food and Nutrition
Bulletin 7 (3):48-51
Soemarwoto, R. 2007. Kasepuhan Rice Landrace Diversity, Risks Management and
Agricultural
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 13
Modernization. Dalam Ellen, R. (ed), Modern Crises and Traditional Strategies:
Local Ecological Knowledge in Island Southeast Asia. New York-Oxford: Berhahn
Books, Pp.84-111.
Suganda, H. 2006. Kampung Naga Mempertahankan Tradisi. Bandung: Kiblat Utama.
Suparlan, P. 2005. Kebudayaan Dalam Pembangunan. Dalam Kusairi dkk (eds), Sustainable
Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran
Surna Tjahja Djajadiningrat. Jakarta: ICSD.
Terra, G.J.A. 1958.Farm Systems in Southeast Asia. Netherlands Journal of Agricultural
Science 6 (3):157-182.
Van Noordwijk, M., 2010. Climate Change, Biodiversity, Livelihoods, and Sustainagility in
Southeast Asia. In Sajise, P.E., M. V. Ticsay, G.C. Saguiguit (eds), Moving Forwards
Southeast Asian Perspectives and Climate Change and Biodiversity. Singapore:
ISEAS Publishing, Pp. 55-83.
Von Maydell, H.J. 1985. The Contribution of Agroforestry Development.Agroforestry
Systems
3: 83-90.
Warsiti, I. 1997. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kultivar Padi Lokal dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Kelestarian Kultivar Padi Lokal. Tesis Pada Program Studi Magister
Ilmu Lingkungan Unpad (Tidak dipublikasikan).
Wessing, R. 1978. Cosmology and Social Behavior in A West Javanese Settlement. Ohio:
Ohio University Center for International Studies.
Yogaswara, H. 2009. Situs Keramat Alami Sebagai Alternatif Pengakuan Hak-Hak
Masyarakat Adat: Kasus Kasepuhan Cibeduk, Banten. Dalam H.Soedjito, Y.Purwanto,
E.Sukara (eds), Situs Keramat Alami: Peran Budaya Dalam Konservasi
Keanekaragaman Hayati. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Pp. 112-129.
Konferensi Internasional Budaya Sunda II 14
Anda mungkin juga menyukai
- Bab IDokumen21 halamanBab IJanu NestaBelum ada peringkat
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Review Buku Kampung Naga: Pengetahuan Ekologi Tradisional Dan Pelestarian Keaneragaman Hayati TanamanDokumen21 halamanReview Buku Kampung Naga: Pengetahuan Ekologi Tradisional Dan Pelestarian Keaneragaman Hayati TanamanAndika N SahputraBelum ada peringkat
- Bab I1Dokumen7 halamanBab I1yovitaladoangin italadoanginBelum ada peringkat
- Burung GagakDokumen150 halamanBurung GagakWindy AgathaBelum ada peringkat
- Bab I PDFDokumen31 halamanBab I PDFLilis LiandaBelum ada peringkat
- UntitledDokumen11 halamanUntitledCintaa Cendana DewiiBelum ada peringkat
- ARIODokumen13 halamanARIOBhyno BeatsBelum ada peringkat
- Agroforestry TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGANDokumen51 halamanAgroforestry TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGANFitri WulandariBelum ada peringkat
- Contoh ProposalDokumen31 halamanContoh ProposalNurrokhmah RizqihandariBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Di MalukuDokumen6 halamanKearifan Lokal Di Malukuaurelio hendriksz100% (1)
- Bentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat TugutilDokumen11 halamanBentuk Pengelolaan Hutan Dengan Kearifan Lokal Masyarakat Adat TugutilAgung Setiya NBelum ada peringkat
- Nps 1042Dokumen22 halamanNps 1042Beny SianturiBelum ada peringkat
- MJL 2 Manusia LingkunganDokumen21 halamanMJL 2 Manusia LingkunganEgu Jason Voorhes0% (1)
- Kearifan Lokal Dalam Mengelola Hutan RakyatDokumen5 halamanKearifan Lokal Dalam Mengelola Hutan RakyatizhomBelum ada peringkat
- MAKALAH Ekowisata Sem 1Dokumen11 halamanMAKALAH Ekowisata Sem 1julian100% (2)
- Kta Dan AgrowisataDokumen21 halamanKta Dan AgrowisataFatonah Syifa AzzahraBelum ada peringkat
- 4 Bab1Dokumen19 halaman4 Bab1Nailan SurayyaBelum ada peringkat
- Agroforestry KalimantanDokumen8 halamanAgroforestry KalimantanPetris 25Belum ada peringkat
- BAHAN AJAR Budaya Lahan KeringDokumen16 halamanBAHAN AJAR Budaya Lahan KeringNovianti Rosalia AbiBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Suku Pedalaman Di Indonesia Dalam Mitigasi BencanaDokumen12 halamanKearifan Lokal Suku Pedalaman Di Indonesia Dalam Mitigasi BencanaHalim Perdana Kusuma100% (2)
- MK - Bdyalhankering, Klautan Dan PrwstaDokumen4 halamanMK - Bdyalhankering, Klautan Dan PrwstaNadia HenukhBelum ada peringkat
- Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati DanDokumen9 halamanKeanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati Danrestiyanna100% (2)
- Dinamika Cendana Antara Masyarakat Dengan Pemerintah DaerahDokumen7 halamanDinamika Cendana Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Daerahtukuh takdir sembadaBelum ada peringkat
- Revitalisasi Adat MelayuDokumen17 halamanRevitalisasi Adat MelayuYandra WindesiaBelum ada peringkat
- Review Materi Ekologi Geografi - Fitri Wahyuni - 1813034009Dokumen25 halamanReview Materi Ekologi Geografi - Fitri Wahyuni - 1813034009Intan PermataBelum ada peringkat
- Biodiversity AmunitionDokumen2 halamanBiodiversity AmunitionMaghfira MaulidiaBelum ada peringkat
- Kearifan LokalDokumen8 halamanKearifan LokalGiska ManikasariBelum ada peringkat
- Projek KMH - Kelompok 3Dokumen19 halamanProjek KMH - Kelompok 3Laila SapniBelum ada peringkat
- Bagian I. Materi Lahan Kering: Buddhayah Buddhi BuddhiDokumen112 halamanBagian I. Materi Lahan Kering: Buddhayah Buddhi BuddhiApmida TanesibBelum ada peringkat
- Kelestarian HutanDokumen13 halamanKelestarian HutanAditya Nugie PrasetyoBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan AlamDokumen8 halamanKearifan Lokal Adat Masyarakat Sunda Dalam Hubungan Dengan Lingkungan AlamIlham MaulanaBelum ada peringkat
- Nur Indah SariDokumen12 halamanNur Indah SariAbdul RahmanBelum ada peringkat
- ManajemenhutanlestariDokumen12 halamanManajemenhutanlestariSazni NasutionBelum ada peringkat
- Masyarakat Undau MauDokumen8 halamanMasyarakat Undau MaubudimagBelum ada peringkat
- Zainudin Hasan - Hulu Tulung Pengelolaan Lingkungan Berkearifan Lokal - RevisiDokumen7 halamanZainudin Hasan - Hulu Tulung Pengelolaan Lingkungan Berkearifan Lokal - RevisiZainudin HasanBelum ada peringkat
- Antr LingkunganDokumen27 halamanAntr Lingkunganaqila maretasyaBelum ada peringkat
- Hulu TulungDokumen4 halamanHulu TulungZainudin HasanBelum ada peringkat
- Sawah DuluDokumen13 halamanSawah DuluEbit MrBelum ada peringkat
- 287065043Dokumen20 halaman287065043Tika AstariBelum ada peringkat
- Nilai Keanekaragaman HayatiDokumen7 halamanNilai Keanekaragaman HayatiHasna Dila LatifahBelum ada peringkat
- HUTAN LebatDokumen16 halamanHUTAN LebatKesdik Kusuma Arista BaktiBelum ada peringkat
- Wibowo Hari,+8 Berkala+Arkeologi+Vol+25+No+1+November+2005Dokumen8 halamanWibowo Hari,+8 Berkala+Arkeologi+Vol+25+No+1+November+2005Sahrul HabibiBelum ada peringkat
- Resume Kuliah TamuDokumen6 halamanResume Kuliah TamuClarissa ElricaBelum ada peringkat
- 108-296-1-PB Kearifan Lingkungan Gunung KidulDokumen12 halaman108-296-1-PB Kearifan Lingkungan Gunung KidulFaisol Faisol RahmanBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen4 halamanTugas 1RikaBelum ada peringkat
- Pengantar Ilmu KehutananDokumen12 halamanPengantar Ilmu Kehutananakaarab40Belum ada peringkat
- Rresume Materi Konservasi Tanah Dan Air - Ikrar Fajar Shiddiq - (G1011201268)Dokumen9 halamanRresume Materi Konservasi Tanah Dan Air - Ikrar Fajar Shiddiq - (G1011201268)Ikrar FajarBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Dan Pelestarian LingkunganDokumen15 halamanKearifan Lokal Dan Pelestarian LingkunganHedy Yunus DermawanBelum ada peringkat
- 03 Ekosistem Dan PertanianDokumen38 halaman03 Ekosistem Dan PertanianNaufal FadhlurrahmanBelum ada peringkat
- Analisis Fungsi Ekologis Masyarakat Pada Sistem Pengelolaan Produksi Getah Damar Di Krui, Lampung BaratDokumen7 halamanAnalisis Fungsi Ekologis Masyarakat Pada Sistem Pengelolaan Produksi Getah Damar Di Krui, Lampung BaratTio BaskoroBelum ada peringkat
- Jurnal PDFDokumen114 halamanJurnal PDFAdfi KhalidBelum ada peringkat
- KonservasiDokumen3 halamanKonservasianggita pusparini salsabillahBelum ada peringkat
- Literasi Lingkungan Hutan Tropis Dan Kearifan Lokal 10Dokumen7 halamanLiterasi Lingkungan Hutan Tropis Dan Kearifan Lokal 10this urlifeBelum ada peringkat
- Kuis Ekologi PembangunanDokumen4 halamanKuis Ekologi PembangunanMoch Ricky Adha BudimanBelum ada peringkat
- Mutiara Dina Aulia - 22058104 - Tugas 2 KLDokumen6 halamanMutiara Dina Aulia - 22058104 - Tugas 2 KLMegia Zaharatul jannahBelum ada peringkat
- Identifikasi Buku Hutan WanagamaDokumen8 halamanIdentifikasi Buku Hutan WanagamaElena KrisditoBelum ada peringkat
- Karya Tulis IlmiahDokumen17 halamanKarya Tulis IlmiahYuninda Tri Noor IndahsariBelum ada peringkat
- Kearifan Lokal Asy CidaunDokumen26 halamanKearifan Lokal Asy CidaunMuhammad Arief RamadhanBelum ada peringkat
- Form Jurnal Siti BudimanDokumen2 halamanForm Jurnal Siti BudimanSela RenikaBelum ada peringkat
- 37-File Utama Naskah-155-1-10-20210202Dokumen22 halaman37-File Utama Naskah-155-1-10-20210202Sela RenikaBelum ada peringkat
- Permukiman IslamiDokumen18 halamanPermukiman IslamiSela RenikaBelum ada peringkat
- Kabuyutan Cipageran Cimahi Dari Zaman Ke ZamanDokumen16 halamanKabuyutan Cipageran Cimahi Dari Zaman Ke ZamanSela RenikaBelum ada peringkat
- 6928 14718 2 PBDokumen14 halaman6928 14718 2 PBSela RenikaBelum ada peringkat
- 20210709005225.dokumen Renstra Ditjen Hubla Tahun 2020 - 2024Dokumen167 halaman20210709005225.dokumen Renstra Ditjen Hubla Tahun 2020 - 2024Sela RenikaBelum ada peringkat
- Arsitektur Tropis Pada Tata Ruang Dan Permukiman DDokumen9 halamanArsitektur Tropis Pada Tata Ruang Dan Permukiman DSela RenikaBelum ada peringkat
- Pola Tata Ruang Kawasan Permukiman Kampung Naga Tasik Malaya - 2Dokumen117 halamanPola Tata Ruang Kawasan Permukiman Kampung Naga Tasik Malaya - 2Sela RenikaBelum ada peringkat
- Morfologi Dan Situs KerajaanDokumen138 halamanMorfologi Dan Situs KerajaanSela RenikaBelum ada peringkat