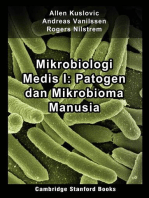VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUMANISME
Diunggah oleh
Patricia Mega Sri Yulianty TaeJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUMANISME
Diunggah oleh
Patricia Mega Sri Yulianty TaeHak Cipta:
Format Tersedia
Covid-19 bisa menimbulkan komplikasi yang serius dan mengancam jiwa, dan tidak
ada yang sepenuhnya aman dari penularan virus tersebut. Dari satu saja orang yang terinfeksi
Covid-19, terdapat potensi penularan terhadap puluhan orang lain, bahkan lebih. Vaksin
Covid-19 berfungsi menekan potensi itu. Ketika seseorang terinfeksi virus corona, sistem
imun alias antibodinya telah dapat mengenali virus itu sehingga kemungkinan tertular lagi
lebih kecil. Artinya, dia lebih kebal atau imun terhadap Covid-19 ketimbang orang lain yang
belum pernah terinfeksi. Vaksin Covid-19 menawarkan perlindungan berupa kekebalan
tersebut tanpa perlu sakit Covid dulu. Orang yang positif Covid harus menghadapi
kemungkinan terburuk berupa kehilangan nyawa. Yang bergejala ringan atau tanpa gejala
pun tetap mesti melakukan isolasi mandiri dan mengikuti prosedur perawatan yang rumit.
Bila mendapatkan vaksin Covid-19, kita tak perlu mengalami masa-masa sulit dan berisiko
itu untuk memperoleh kekebalan terhadap virus corona. Namun tidak dapat kita pungkiri
masih banyak masyarakat yang masih menolak akan pemberian vaksin.
Hal tersebut merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian pemerintah dari tahun
2018 adalah masalah penolakan masyarakat terhadap vaksinasi baik secara global maupun
nasional.Menurut sejarah, vaksin pertama kali ditemukan oleh Edward Jenner. Namun
sebenarnya teknik inokulasi (memasukkan kuman ke dalam tubuh manusia untuk mendapat
kekebalan) pertama kali dilakukan di Cina dan Turki. Pada tahun 1717, seorang istri dari duta
besar Inggris di Turki, Lady Mary Wortley Montagu, sering melihat kebiasaan orang Turki
mengambil nanah dari luka penderita Smallpox dan ditanamkan pada sayatan di tubuh anak
yang sehat lalu dibalut. Beberapa hari kemudian anak tersebut mengalami demam, namun
menjadi kebal terhadap Smallpox (Harjaningrum, 2011). Fenomena penolakan terhadap
vaksinasi bukan merupakan hal yang baru. Tidak lama sejak ditemukan vaksin campak pada
pada akhir abad ke 18, kelompok anti vaksin sudah ada dan berlanjut hingga sekarang(Succi,
2018). Disamping itu juga pemerintah Indonesia melakukan kewajiban dalam pemberian
vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dalam artikel Hukumonline berjudul Polemik
Jerat Pidana bagi Penolak Vaksinasi Covid-19, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Oemar Sharif Hiariej menganggap ada sanksi bagi
warga yang menolak vaksinasi Covid-19. Sebab, vaksinasi Covid-19 merupakan kewajiban di
tengah situasi wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19. Sanksi yang dimaksud
merujuk pada Pasal 9 jo Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
(Baca: Sosialisasi Masif dan Pentingnya Vaksinasi Covid-19). Banyak polemic yang masih
terjadi tentang sanksi dan kewajiban menjalankan vaksin. Beberapa orang berpendapat bahwa
mewajibkan vaksin merupakan salah satu tindakan mengabaikan hak manusia untuk memilih.
Sehingga bahwasanya sanksi bagi penolak vaksin masih perlu dikaji ulang, namun bagi pihak
yang menghasut dan mengajak untuk menolak vaksin maka harus ada sanksi tegas. Lalu
bagaimanakah perspektif ontology dalam VAKSINISASI DALAM NILAI
HUMANISME ?
Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap Orang wajib mematuhi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan”. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan
menyebutkan, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
Dia menilai Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan merupakan pasal “sapujagat” yang
bersifat karet dan pasal keranjang sampah. Menurutnya, Pasal 93 UU Kekarantinaan
Kesehatan dapat dikatakan sebagai pidana administratif. Bagi siapapun yang tidak mematuhi
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai Pasal 9 ayat (1) dapat dijerat dengan Pasal
93 UU Kekarantinaan Kesehatan.
Menurutnya, Pasal 9 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan berkaitan dengan penerapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Karena itu, terdapat kewajiban bagi setiap warga
negara untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan terkait kekarantinaan
kesehatan. “Ketika kita menyatakan vaksin itu kewajiban, secara mutatis mutandis jika ada
warga yang tidak mau divaksin bisa dikenakan sanksi pidana, bisa didenda atau penjara, atau
bisa dua-duanya. Jadi bahasa (penafsirannya, red) amat sangat luas, itu kita istilahkan pasal
karet,” ujarnya dalam sebuah webinar, Sabtu (9/1/2021) kemarin.
Meski rumusan norma tersebut sedemikian mudah menjerat pelanggaran kekarantinaan
kesehatan, namun hukum pidana itu bersifat ultimum remedium (upaya terakhir). Artinya
hukum pidana digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir (setelah upaya lain
sudah dilakukan). “Jelas ada sanksi. Tapi sedapat mungkin pidana itu jalan (upaya, red)
terakhir,” katanya.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai
tafsir Wamenkumham sangat berlebihan. Dia beralasan penerapan sanksi pidana dalam UU
6/2018 bila memenuhi dalam kondisi. Pertama, bila pilihan keputusan pemerintah
menyatakan karantina wilayah, bukan PSBB. Kedua, tindakan yang dapat dikriminalisasi
atau dipidana antara lain keluar masuknya wilayah karantina tanpa izin. Ketiga, subjeknya
adalah para supir, nahkoda dan pilot.
Dengan begitu, menurutnya tafsir Wamenkumham bagi yang menolak disuntiik vaksin
Covid-19 bisa dijerat Pasal 93 UU 6/2018 berlebihan dan keliru. “Itu tafsir lebay. Ini menurut
saya tidak relevan. Karena kita hanya (penetapan, red) PSBB. Demikian pula kedaruratan itu
terjadi bukan karena satu dua orang, melainkan situasi pandemi kedaruratan yang
menyeluruh,” ujarnya.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (FH UAI) Suparji
Achmad punya pandangan senada. Dia menilai tindakan yang dilarang dalam Pasal 93 UU
6/2018 yakni perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
menghalang-halangi kekarantinaan kesehatan yang menimbulkan dampak kedaruratan
kesehatan.
“Yang menjadi kewajiban adalah mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sesuai
Pasal 9 ayat (1) UU 6/2018,” kata Suparji.
Dia menilai tafsir Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dapat menjerat pidana bagi warga
negara yang menolak vaksin menggunakan tafsir meluas (ekstensif) yang tidak tepat dan
tidak memenuhi asas legalitas. Dia merujuk Pasal 1 angka 1 UU 6/2018 yang
menyebutkan, “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar
atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.”
Dengan begitu, menurut Suparji, vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai oleh pemerintah
bersifat sukarela. Sebab, bila menggunakan UU 6/2018 yang menjadi kewajiban setiap warga
negara adalah mematuhi kegiatan kekarantinaan kesehatan, bukan kewajiban vaksinasi
Covid-19.
“Dalam UU 6/2018 tidak terdapat norma yang mengatur vaksin. Karenanya, vaksin menjadi
sukarela bagi masyarakat untuk pencegahan virus. Sedangkan vaksinasi tidak ada norma UU
yang mewajibkan,” tegasnya.
Lalu seperti apakah sikap masyarakat terhadap vaksinasi, baik yang menolak maupun yang
menerima?
Kewajiban vaksinasi ini memunculkan kontroversi. Ada kekhawatiran terhadap keamanan
dan kesehatan tubuh, baik untuk jangka pendek maupun panjang, sehingga menimbulkan
penolakan. Padahal, Presiden Jokowi sudah memberikan contoh dengan divaksinasi kali
pertama (13 Januari 2021). Namun, masih ada juga tenaga kesehatan yang secara terang-
terangan menolak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun mengeluarkan maklumat (11 Januari
2021) agar seluruh dokter anggota IDI mengikuti program vaksinasi dan menghentikan
polemiknya. Penolakan terang-terangan juga datang dari politisi, anggota dewan, dan tokoh
agama
Ontology ilmu terdiri dari suku kata,yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuat yang
berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontology dapat diartikan sebagai ilmu,
Filsafat ilmu merupakan kajian atau telaah secara mendalamsecara mendalam terhadap
hakikat ilmu
Sejak tahun 1976, vaksin diakui terbukti bisa mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus
atau bakteri tertentu. Vaksin sendiri zat aktif pada virus yang apabila disuntikkan dapat
meningkatkan kekebalan tubuh," jelas Mimi dalam keterangan tertulis yang diterima
Kompas.com, Selasa (12/1/2021).
Eksistensialisme yang berkembang pada abad ke 20 di Perancis dan
Jerman, bukan sebagai akibat langsung dari suatu keadaan tertentu, tetapi
lebih disebabkan oleh respon yang dialami secara mendalam atas
runtuhnya berbagai tatanan di dunia Barat yang sebelumnya dianggap
stabil. Meletusnya perang dunia pertama telah menghancurkan keyakinan
atas keberlanjutan kemajuan peradaban menuju kebenaran dan kebebasan.
Kemudian dengan melemahnya banyak struktur eksternal kekuasaan,
seperti struktur ekonomi, politik serta kekuasaan pada saat itu yang sudah
kehilangan legetimasinya, dan kuasa atas individu jadi terasa sudah tidak
lagi ditolerir karena ditentang dan dianggap tidak memiliki peran yang
berarti, dan pada saat itu manusia perorangan hanya bisa tunduk pada
kekuasaan internal atas dirinya sendiri. Kondisi seperti itu telah
mengantarkan para eksistensialis kembali pada diri manusia sebagai pusat
filsafat yang sejati dan sebagai satu-satunya kekuasaan yang
berlegitimasi.1Dalam sejarah perkembangannya, eksistensialisme jelas
mengacu pada fenomena kemanusiaan kongkret yang tengah terjadi.
Sebagaimana diketahui, filsafat eksistensialisme berkembang pesat pasca
perang dunia kedua, yang seolah membenarkan permenungan filosofis
pada kenyataan (kemanusiaan) yang kongkret tersebut. Oleh karena itu,
permenungan rasionalitas Descartes yang menegaskan Cogito Ergo Sum
”Saya berpikir maka saya ada”, dibalik secara ekstrem oleh eksistensialis
dengan pernyataan: “Saya ada, maka saya berpikir”.2 Aliran ini lebih
menekankan perhatiannya pada subyek, bukan pada obyek, hal ini tentu
saja berbeda dengan fenomenologi yang lebih menekankan hubungan
subyek dan obyek pengetahuan dengan intensionalitasnya, maupun dengan
filsafat bahasa yang lebih menyoroti obyek. Eksistensialisme tidaklah
sekedar menunjukkan suatu sistem filsafat secara khusus, karena setelah
melalui berbagai perkembangan, stilah ini telah meresapi banyak bidang di
luar filsafat, seperti psikologi, seni, sastra, drama, dan sebagainya.
Terdapat perbedaan-perbedaan yang besar antara bermacam-macam
filsafat yang biasa diklasifikasikan sebagai filsafat eksistensialis, tetapi
meskipun demikian terdapat tema-tema yang sama yang memberi ciri
kepada gerakan-gerakan eksistensialis, antara lain misalnya.
Pertama,eksistensialis merupakan suatu tantangan yang kuat terhadap
filsafat tradisional dengan segala bentuknya, sebab filsafat tradisional
mengarahkan perhatiannya pada wujud dan pengenalannya kepada sebab-
sebab yang jauh bagi wujud tersebut serta dasar-dasar prinsip
pertama,3kedua, eksistensialisme adalah suatu protes atas nama
individualis terhadap konsep-konsep ‘akal’ dan ‘alam’ yang ditekankan
pada periode pencerahan abad ke 18. “Penolakan untuk mengikuti suatu
aliran, penolakan terhadap kemampuan sesuatu kumpulan keyakinan,
khususnya kemampuan sistem, rasa tidak puas terhadap filsafat tradisional
yang bersifat dangkal, akademik dan jauh dari kehidupan, semua itu
adalah pokok dari eksistensialisme”.4Ketiga, Eksistensialisme juga
merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal (tanpa
kepribadian) dari zaman industri modern atau zaman teknologi, serta
pemberontakan massa pada zaman sekarang. Dan keempat,
eksistensialisme juga merupakan suatu protes terhadap gerakan-gerakan
totaliter, baik gerakan fasis, komunis, dan lain-lain yang cenderung
menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa.5Pengakuan
atas ‘keberadaan’ manusia sebagai subyek yang bereksistensi terletak pada
kesadaran yang langsung dan subyektif, yang tidak dapat dimuat dalam
sistem atau dalam suatu abstraksi. Tidak ada pengetahuan yang terpisah
dari subyek yang mengetahui. Itulah sebabnya, kaum eksistensialis sangat
percaya bahwa kebenaran adalah pengalaman subyektif tentang hidup,
yang konsekuensi logisnya menentang segala bentuk obyektivitas dan
impersonalitas mengenai manusia. Tidak berlebihan bila kelompok
eksistensialis membedakan antara eksistensi dan esensi, sesuatu yang
selalu menjadi perbincangan menarik para filsuf. Eksistensi berarti
keadaan yang aktual, yang terjadi dalam ruang dan waktu; dan
bereksistensi yaitu menciptakan dirinya secara aktif, berbuat menjadi dan
merencanakan.6 Sedangkan esensi merupakan sesuatu yang membedakan
antara suatu benda dan corak-corak benda lainnya. Esensi adalah yang
menjadikan benda itu seperti apa adanya, atau suatu yang dimiliki secara
umum oleh bermacam-macam benda. Yang pertama adalah esensi baru
kemudian muncul eksistensi. Asumsi ini ditolak oleh kaum eksistensialis,
utamanya Sartre yang justru mengatakan bahwa ‘eksistensi sebelum
esensi’ atau eksistensi mendahului esensi. Kaum eksistensial berusaha
menemukan kebebasan dengan menunjukkan suatu fakta, betapa benda-
benda (obyek) tidak mempunyai makna tanpa keterlibatan pengalaman
manusia. Manusia merupakan suatu titik sentrum dari segala relasi,
sebagai subyek dengan pengalamannya. Justru dengan kesadaran
‘keberadaannya’, eksistensi manusia diakui, yang oleh Sartre, cara berada
manusia melalui dua cara yaitu l’ᆗ etre-en-soi(berada pada dirinya ) dan
l’ᆗ etre-pour-soi(berada untuk dirinya).
B. Makna Kebebasan Manusia Sartre mengatakan ”aku dikutuk bebas,
ini berarti bahwa tidak ada batasan atas kebebasanku, kecuali kebebasan
itu sendiri, atau jika mau, kita tidak bebas untuk berhenti bebas”.7Melihat
pernyataan di atas bahwa kebebasan menjadi tema sangat penting dalam
bangunan filsafat Sartre. Dalam bukunya Being and Nothingness, Sartre
banyak menganalisis kebebasan dan cara berada manusia untuk
menemukan kebebasan.8 Menurut Sartre ada dua “’ᆗ etre” (berada) yaitu
l’ᆗ etre-en-soi(berada pada dirinya ) dan l’ᆗ etre-pour-soi(berada untuk
dirinya). Dalam bahasa Inggris en-soi dapat diterjemahkan thingness
sementara pour-soiyaitu no-thingness.9 Maksud l’ᆗ etre-en-soi atau
‘berada pada dirinya’ adalah semacam berada an sich. Ada banyak yang
berada, pohon, binatang, manusia, benda-benda, dan sebagainya,
semuanya itu berbeda-beda “berada” mewujudkan ciri segala benda
jasmani. Semua benda ada dalam dirinya-sendiri, tidak ada alasan
mengapa benda-benda berada begitu. Segala yang berada dalam diri ini
tidak aktif, akan tetapi juga tidak pasif, tidak meng-ia-kan dan tidak
menyangkal. ’ᆗ Etre-en-soimentaati prinsip identitas, jika di dalam
sesuatu yang ada itu terdapat perkembangan, maka perkembangan itu
terjadi karena sebab-sebab yang telah ditentukan. Oleh karenanya
perubahan-perubahan itu adalah perubahan yang kaku. Menurut Sartre
segala yang “berada dalam dirinya” (l’ᆗ etre-en-soi) memuakkan,10 yang
ada begitu saja, tanpa kesadaran, tanpa makna. Adanya pour-soi membuat
manusia begitu istimewa, karena seakan-akan meninggalkan suatu
‘lubang’ dalam dunia benda, dunia objek-objek. Lubang tersebut
merupakan kebebasan manusia. Hal inilah yang dapat melepaskan diri dari
adanya en-soi. Sementara yang dimaksud dengan l’ᆗ etre-pour-soi
(berada untuk dirinya) yaitu berada dengan sadar akan dirinya, yaitu cara
berada manusia. l’ᆗ etre-pour-soi tidak mentaati prinsip identitas seperti
halnya ’ᆗ etre-en-soi. Manusia mempunyai hubungan dengan
keberadaannya. Ia bertanggung jawab atas fakta, berbeda dengan benda-
benda. Sebab benda hanyalah benda, tetapi tidak demikian dengan
manusia, karena manusia memiliki kesadaran, yaitu kesadaran yang
reflektif dan kesadaran yang pra reflektif.
.
Anda mungkin juga menyukai
- Pengenaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di IndonesiaDokumen15 halamanPengenaan Sanksi Pidana Penolakan Vaksinasi Covid-19 Di IndonesiaseptiBelum ada peringkat
- Tugas 1 Hukum FilsafatDokumen5 halamanTugas 1 Hukum FilsafatPutri AlfitriBelum ada peringkat
- Makalah Sesi 5Dokumen14 halamanMakalah Sesi 5nasyaBelum ada peringkat
- Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen4 halamanFilsafat Hukum Dan Etika Profesigarethbarry2001Belum ada peringkat
- Filsafat HukumDokumen17 halamanFilsafat Hukumiwang saudjiBelum ada peringkat
- HUKUM COVID-19 DAN HAK KESEHATANDokumen9 halamanHUKUM COVID-19 DAN HAK KESEHATANLulilu LalapanBelum ada peringkat
- KEWAJIBAN MELAKSANAKAN VAKSIN COVID 19-DikonversiDokumen4 halamanKEWAJIBAN MELAKSANAKAN VAKSIN COVID 19-DikonversiKevinBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa IndonesiaDokumen3 halamanTugas Bahasa IndonesiaSafa Angelia Maryala GizaBelum ada peringkat
- SEMINAR NASIONAL 2021Dokumen6 halamanSEMINAR NASIONAL 2021Winatta SariiBelum ada peringkat
- Filsafat Ilmu - PBLDokumen57 halamanFilsafat Ilmu - PBLPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- (Makalah Kelompok) Dwi Andini Sukma Wijaya - Kewajiban Melaksanakan Vaksin Covid-19Dokumen8 halaman(Makalah Kelompok) Dwi Andini Sukma Wijaya - Kewajiban Melaksanakan Vaksin Covid-19Dwi AndiniBelum ada peringkat
- 8661-Article Text-8397-1-10-20210728Dokumen3 halaman8661-Article Text-8397-1-10-20210728Puspi JnhwnBelum ada peringkat
- Anton Hidayat Tugas 1filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen3 halamanAnton Hidayat Tugas 1filsafat Hukum Dan Etika ProfesiSyahry AqlyBelum ada peringkat
- Qurrota A'yun NurhasanahDokumen4 halamanQurrota A'yun NurhasanahQurrota A'yun NBelum ada peringkat
- Skripsi WidyaDokumen70 halamanSkripsi WidyaBayu NawawiBelum ada peringkat
- KELOMPOK 1 - KELAS A - LAPORAN PROJECT CITIZEN (1) Docx-Converted - Gusti Ayu Pradiipta Devi SuastinaDokumen10 halamanKELOMPOK 1 - KELAS A - LAPORAN PROJECT CITIZEN (1) Docx-Converted - Gusti Ayu Pradiipta Devi SuastinaAnnisa ZubaidiBelum ada peringkat
- ILMU PENGNTAR POLITIK ISIP4212Dokumen8 halamanILMU PENGNTAR POLITIK ISIP4212Shagika KanishaBelum ada peringkat
- Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen3 halamanFilsafat Hukum Dan Etika Profesiintun trianiBelum ada peringkat
- Upaya Pemerintah Dalam Meredam Dampak Covid-19 Ditinjau Dari Aspek HukumDokumen12 halamanUpaya Pemerintah Dalam Meredam Dampak Covid-19 Ditinjau Dari Aspek HukumBELLA ROFIKA LISTYABelum ada peringkat
- 3732-Article Text-15147-1-10-20211230Dokumen24 halaman3732-Article Text-15147-1-10-20211230MustikaBelum ada peringkat
- FILSAFAT HUKUM DAN ETIKA PROFESI TUGAS 1Dokumen2 halamanFILSAFAT HUKUM DAN ETIKA PROFESI TUGAS 1MS SinabangBelum ada peringkat
- ArtikelDokumen5 halamanArtikelGrace Evelyn PardedeBelum ada peringkat
- Hubungan Presepsi dan Motivasi Vaksinasi Covid-19Dokumen8 halamanHubungan Presepsi dan Motivasi Vaksinasi Covid-19Dho DhoBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen6 halaman1 PBRizki Wahyudi YudiBelum ada peringkat
- Menjaga Sistem Imun Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan SenamDokumen7 halamanMenjaga Sistem Imun Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan SenamRosyida OktavianiBelum ada peringkat
- Regulatory Inconsistency Guidelines For The Protection of Health Personnel in Facing Covid-19 Perlindungan Hak Tenaga Kesehatan Di Tengan Pandemi Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2020Dokumen7 halamanRegulatory Inconsistency Guidelines For The Protection of Health Personnel in Facing Covid-19 Perlindungan Hak Tenaga Kesehatan Di Tengan Pandemi Berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2020FajriBelum ada peringkat
- Kti Kelompok 17 - Pemberlakuan Kebijakan Vaksin CovidDokumen14 halamanKti Kelompok 17 - Pemberlakuan Kebijakan Vaksin Covidahmad mukhollifBelum ada peringkat
- Ghina - Komunikasi EfektifDokumen5 halamanGhina - Komunikasi EfektifGina KhalaidaBelum ada peringkat
- Opini CovidDokumen4 halamanOpini CovidAmeilia AngelaBelum ada peringkat
- Pai 2024 - d3 Rmik - 30523008 - Ahmad Syifaa AzzuhriDokumen19 halamanPai 2024 - d3 Rmik - 30523008 - Ahmad Syifaa AzzuhriAhmad Syifaa AzzuhriBelum ada peringkat
- Essay Covid 19Dokumen3 halamanEssay Covid 19aulyaBelum ada peringkat
- Contoh Kasus Dan Bab 3Dokumen3 halamanContoh Kasus Dan Bab 3Nophi NonerBelum ada peringkat
- Syifa Anindya - 2033004106045 - TUGAS 2Dokumen3 halamanSyifa Anindya - 2033004106045 - TUGAS 2Syifa AnindyaBelum ada peringkat
- Bahan Presentasi MPPHDokumen7 halamanBahan Presentasi MPPHCucuBelum ada peringkat
- Vaksinasi CovidDokumen4 halamanVaksinasi CovidAulia AradiaBelum ada peringkat
- Implementasi CovidDokumen32 halamanImplementasi CovidAkbar MedikaBelum ada peringkat
- Vaksinasi CovidDokumen4 halamanVaksinasi CovidHaji SukatmanBelum ada peringkat
- Hak & Kewajiban VaksinDokumen13 halamanHak & Kewajiban VaksinRangga Bagus PratamaBelum ada peringkat
- VaksinUU4Dokumen5 halamanVaksinUU4Sri dewiBelum ada peringkat
- Perspektif Antropologis 2Dokumen4 halamanPerspektif Antropologis 2Liana MardianaBelum ada peringkat
- Mpu23052 E-Folio - Group 4 - Pengambilan Vaksin Menurut IslamDokumen15 halamanMpu23052 E-Folio - Group 4 - Pengambilan Vaksin Menurut Islamsyamilafiq19Belum ada peringkat
- Esensi FaizurDokumen5 halamanEsensi Faizuresensi. idBelum ada peringkat
- Soal Kuis 1 Agenda 3Dokumen2 halamanSoal Kuis 1 Agenda 3M.sawal LudinillahBelum ada peringkat
- Pemicu 1 - Blok 1 - Shadrina - 200600238Dokumen9 halamanPemicu 1 - Blok 1 - Shadrina - 200600238ShadrinaBelum ada peringkat
- BJT - HKUM4103 Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen3 halamanBJT - HKUM4103 Filsafat Hukum Dan Etika Profesiandi eka sarmila100% (2)
- BJT - Tugas2 Pengantar Sosiologi PDFDokumen6 halamanBJT - Tugas2 Pengantar Sosiologi PDFSalahudin HafidzBelum ada peringkat
- HKUM4103Dokumen9 halamanHKUM4103bona iboBelum ada peringkat
- Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Vaksin Covid 19Dokumen12 halamanPandangan Masyarakat Indonesia Terkait Vaksin Covid 19Haurgeulis City100% (1)
- GLOBAL HEALTH ISSUESDokumen5 halamanGLOBAL HEALTH ISSUESAayuliiiBelum ada peringkat
- Fadhel Ally - UTS HAMDokumen16 halamanFadhel Ally - UTS HAMNikeu KusnantiniBelum ada peringkat
- Faktor Psikologi yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19Dokumen9 halamanFaktor Psikologi yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat terhadap Vaksinasi Covid-19putrianjuBelum ada peringkat
- JM lexcrimen,+Monica+Shahnaz+TudaDokumen11 halamanJM lexcrimen,+Monica+Shahnaz+TudaLia Laelatul FaridaBelum ada peringkat
- Pandangan Islam Terhadap VaksinDokumen5 halamanPandangan Islam Terhadap VaksinWan Amir IslamBelum ada peringkat
- Vaksinasi Dalam Pandangan Islam Dari Perspektif Sejarah Dan KontemporerDokumen18 halamanVaksinasi Dalam Pandangan Islam Dari Perspektif Sejarah Dan Kontemporerorang di duniaBelum ada peringkat
- BJU - Umum - TMK1 - HKUM4103 Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen2 halamanBJU - Umum - TMK1 - HKUM4103 Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiGilang JRBelum ada peringkat
- BJU - Umum - TMK1 - HKUM4103 Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen2 halamanBJU - Umum - TMK1 - HKUM4103 Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiGilang JRBelum ada peringkat
- Tugas Terstruktur I TS 2 Filsafat Manusia - Kelas C - Santi LIntani Gunawan - 7103022120Dokumen8 halamanTugas Terstruktur I TS 2 Filsafat Manusia - Kelas C - Santi LIntani Gunawan - 7103022120Santi Lintani GunawanBelum ada peringkat
- Kebijakan LockdownDokumen24 halamanKebijakan LockdownZakaria N WandaBelum ada peringkat
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Functional ConsequencesDokumen19 halamanFunctional ConsequencesPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Pengukuran Epid 2021Dokumen40 halamanPengukuran Epid 2021Patricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Surveilans Epidemiologi dalam Pemantauan Masalah KesehatanDokumen44 halamanSurveilans Epidemiologi dalam Pemantauan Masalah KesehatanPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Pola Penyakit m14 2021Dokumen54 halamanPola Penyakit m14 2021Patricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Pola Penyakit m14 2021Dokumen54 halamanPola Penyakit m14 2021Patricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Yunidar DP 19079 Analisis JurnalDokumen5 halamanYunidar DP 19079 Analisis JurnalPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Critical ApraisalDokumen28 halamanCritical ApraisalPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Bab 1 PTSDDokumen3 halamanBab 1 PTSDPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- KONSEP PENYAKITDokumen73 halamanKONSEP PENYAKITPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- EPIDEMI EPIDEMIOLOGIDokumen45 halamanEPIDEMI EPIDEMIOLOGIPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Pengukuran Epid 2021Dokumen40 halamanPengukuran Epid 2021Patricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- JUDULDokumen46 halamanJUDULPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- EPIDEMI EPIDEMIOLOGIDokumen45 halamanEPIDEMI EPIDEMIOLOGIPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Askep Pengkajian KomunitasDokumen48 halamanAskep Pengkajian KomunitasPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- KLB & Wabah AnyarDokumen31 halamanKLB & Wabah AnyartaliaadiantiBelum ada peringkat
- K3UNTUKSEMUADokumen39 halamanK3UNTUKSEMUAPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- CAMAMAEDokumen13 halamanCAMAMAEPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- JUDULDokumen10 halamanJUDULPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- PENGEMBANGAN POSKESTRENDokumen26 halamanPENGEMBANGAN POSKESTRENBagus LutfiBelum ada peringkat
- ASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT RESIKO TINGGI PADA ANAK SEKOLAHDokumen19 halamanASUHAN KEPERAWATAN KOMUNITAS PADA AGREGAT RESIKO TINGGI PADA ANAK SEKOLAHPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Laporan Kesehatan Komunitas RambipujiDokumen112 halamanLaporan Kesehatan Komunitas RambipujiPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- LK Mastektomi MammaeDokumen20 halamanLK Mastektomi MammaePatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- JUDULDokumen46 halamanJUDULPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Komunitas Agregat Rawan BencanaDokumen99 halamanAsuhan Keperawatan Komunitas Agregat Rawan BencanaPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Penyuluhan KB Jangka PanjangDokumen5 halamanPenyuluhan KB Jangka PanjangPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Pendidikan Kesehatan Imunisasi dan ASI EksklusifDokumen5 halamanPendidikan Kesehatan Imunisasi dan ASI EksklusifPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Askep Keluarga DGN HipertensiDokumen35 halamanAskep Keluarga DGN HipertensiPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- ASUHAN KEPERAWATAN KOMPREHENSIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN SISWA SDN SUKORAMEDokumen23 halamanASUHAN KEPERAWATAN KOMPREHENSIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN SISWA SDN SUKORAMEPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat
- Pre Planning FGD Bumil RestiDokumen4 halamanPre Planning FGD Bumil RestiPatricia Mega Sri Yulianty TaeBelum ada peringkat