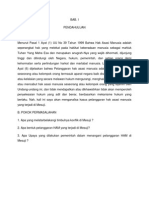Analisis Kasus
Analisis Kasus
Diunggah oleh
Kevin Kurniawan Wijaya0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
64 tayangan3 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
64 tayangan3 halamanAnalisis Kasus
Analisis Kasus
Diunggah oleh
Kevin Kurniawan WijayaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
Kasus Rempang
Dalam kasus Rempang, terdapat konflik agraria yang terjadi antara
masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha terkait pembangunan
kawasan industri Pulau Rempang. Konflik ini terjadi karena tidak adanya
perlindungan hukum atas tanah yang kemudian dicap sebagai warga liar karena
tidak memiliki sertifikat tanah. Dalam kasus Rempang, tidak ada kejelasan perihal
ganti rugi, hunian baru dan tempat relokasi, karena warga Rempang dianggap
sebagai warga liar karena tidak memiliki sertifikat tanah. Guru Besar Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Dr. Ibnu Sina
Chandranegara, MH., menjelaskan konteks permasalahan yang terjadi dalam
kasus Rempang. Ia menyoroti perlakuan Pemerintah yang melabeli warga
Rempang sebagai warga liar karena tidak mempunyai sertifikat. Pakar hukum
pidana Universitas Pelita Harapan (UPH) Agus Surono menilai tak ada unsur
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat dalam konflik agraria di Pulau
Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Subyek hukum dalam kasus Rempang adalah masyarakat adat Rempang
yang terdiri dari Suku Melayu, Suku Laut, dan Suku Jawa. Masyarakat adat
Rempang dianggap sebagai subyek hukum karena mereka adalah pemilik tanah
yang telah dihuni secara turun temurun dan memiliki hak atas tanah tersebut.
Sedangkan obyek hukum dalam kasus Rempang adalah tanah di Pulau Rempang
yang menjadi subyek perdebatan hukum yang rumit. Obyek hukum ini menjadi
objek konflik agraria antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha
terkait pembangunan kawasan industri Pulau Rempang.
Dalam kasus Rempang, terdapat beberapa pendekatan teori hukum yang
dapat digunakan untuk menganalisis konflik agraria yang terjadi. Berikut adalah
beberapa pendekatan teori hukum yang relevan dalam kasus Rempang:
1. Perspektif Keadilan: Teori keadilan yang relevan dalam kasus ini adalah
teori utilitarianisme. Teori ini berpendapat bahwa suatu tindakan dianggap adil
jika memberikan kebahagiaan dan keuntungan yang maksimal bagi sebanyak
mungkin orang.
2. Filsafat Hukum: Filsafat hukum menjadi salah satu cabang ilmu yang
berperan penting dalam mengkaji aspek-aspek hukum secara lebih mendalam.
Dalam kasus Rempang, dapat digunakan pendekatan filsafat hukum untuk
menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan.
3. Hukum Responsif: Pendekatan hukum responsif merupakan pendekatan
yang menekankan pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan
hukum maupun cara untuk mencapainya. Tipe hukum responsif mempunyai ciri
yang menonjol, yakni pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip
dan tujuan.
Dalam kasus Rempang, pendekatan teori hukum yang paling relevan
adalah pendekatan hukum responsif. Hal ini dikarenakan pendekatan ini
menekankan pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum
maupun cara untuk mencapainya. Selain itu, tipe hukum responsif mempunyai ciri
yang menonjol, yakni pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip
dan tujuan, yang dapat membantu dalam menyelesaikan konflik agraria yang
terjadi di Rempang.
Dasar atau sumber hukum yang digunakan dalam kasus Rempang adalah
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-undang ini menjadi dasar
hukum pengadaan tanah untuk pembangunan Rempang Eco City. Selain itu,
dalam kasus ini juga digunakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar
1945, seperti Pasal 24 ayat 1, Pasal 28A, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 3, Pasal
28H ayat 4, dan Pasal 28J ayat 2. Selain itu, dalam menyelesaikan konflik agraria
yang terjadi di Rempang, dapat digunakan pendekatan hukum responsif yang
menekankan pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum
maupun cara untuk mencapainya.
Kasus Sianida Jesica
Jessica Kumala Wongso dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang
pembunuhan berencana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di PN Jakarta
Pusat. Pasal tersebut berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun" Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara
karena dinilai terbukti membunuh Mirna dengan memasukkan racun sianida ke
dalam es kopi yang dia minum. Jessica juga telah melakukan beberapa upaya
hukum, termasuk peninjauan kembali (PK), namun semuanya ditolak.
Subyek hukum dalam kasus pembunuhan sianida Jessica adalah Jessica
Kumala Wongso, sedangkan obyek hukumnya adalah Wayan Mirna Salihin,
korban yang meninggal setelah meminum kopi yang dicampur dengan sianida
yang diberikan oleh Jessica.
Dalam kasus pembunuhan sianida Jessica Kumala Wongso, penelitian
yang dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan ini
memfokuskan pada aturan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan aspek
subtantif dan prosedural dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam kasus ini juga
digunakan alat bukti berupa rekaman CCTV sebagai petunjuk dalam tindak
pidana pembunuhan.
Dasar atau sumber hukum yang digunakan dalam kasus pembunuhan
sianida Jessica Kumala Wongso adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Selain itu, dalam kasus ini
juga digunakan alat bukti berupa rekaman CCTV sebagai petunjuk dalam tindak
pidana pembunuhan. Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman 20 tahun
penjara kepada Jessica Kumala Wongso juga menjadi dasar hukum dalam kasus
ini.
Anda mungkin juga menyukai
- Tugas 3 Hukum AlvinDokumen6 halamanTugas 3 Hukum AlvinAlvin HakimBelum ada peringkat
- Tugas Tuton 3 Pthi - Nira Indriani048895937Dokumen3 halamanTugas Tuton 3 Pthi - Nira Indriani048895937Nira IndrianiBelum ada peringkat
- Politik Hukum Pertanahan PrismatikDokumen22 halamanPolitik Hukum Pertanahan PrismatikDanang AdiBelum ada peringkat
- Tugas 3 Pengantar Ilmu HukumDokumen4 halamanTugas 3 Pengantar Ilmu Hukumrima jumaliaBelum ada peringkat
- Tugas 3 Roza Suci Daningsih PthiDokumen4 halamanTugas 3 Roza Suci Daningsih PthiRoza CeBelum ada peringkat
- Hukum Dan MasyarakatDokumen6 halamanHukum Dan MasyarakatYellis AndiniBelum ada peringkat
- Pengantar Ilmu Hukum PDFDokumen4 halamanPengantar Ilmu Hukum PDFdika alarifBelum ada peringkat
- PTHI Hukum UTDokumen5 halamanPTHI Hukum UTruby.gzhangBelum ada peringkat
- Tugas 3 - Pengantar Ilmu Hukum (Aprilia Widiana)Dokumen4 halamanTugas 3 - Pengantar Ilmu Hukum (Aprilia Widiana)aping12.pingBelum ada peringkat
- Jurnal (I Kadek Wira Picha Pramandika.0175010101)Dokumen14 halamanJurnal (I Kadek Wira Picha Pramandika.0175010101)Wulan SwandewiBelum ada peringkat
- m2kb4 ProfesionalDokumen6 halamanm2kb4 ProfesionalRifa RamadaniBelum ada peringkat
- TUGAS TUTORIAL ONLINE 3 (Pthi)Dokumen3 halamanTUGAS TUTORIAL ONLINE 3 (Pthi)annisatrieshilla12Belum ada peringkat
- Tugas HukumDokumen8 halamanTugas HukumErliy manoppoBelum ada peringkat
- 1614101025-Desak Paramita Brata-Pencurian Mayat (Ori)Dokumen16 halaman1614101025-Desak Paramita Brata-Pencurian Mayat (Ori)MitaBelum ada peringkat
- Analisis Kasu Pelanggaran Ham LokalDokumen6 halamanAnalisis Kasu Pelanggaran Ham LokalFauzan HidayatBelum ada peringkat
- Artikel AdekDokumen15 halamanArtikel AdekWBelum ada peringkat
- Kasus KerangkengDokumen3 halamanKasus KerangkengEen Monika100% (1)
- Kasus Perselisihan Di Indonesia Yang Berkaitan Dengan Antropologi HukumDokumen6 halamanKasus Perselisihan Di Indonesia Yang Berkaitan Dengan Antropologi HukumJabalrhBelum ada peringkat
- AkbarDokumen47 halamanAkbarakbarm0441Belum ada peringkat
- Jurnal Besman Rev.1Dokumen14 halamanJurnal Besman Rev.1kepatuhanbrilifeBelum ada peringkat
- Artikel Ilmiah Sengketa Lahan Pancoran Buntu II Dari Sudut Pandang Hukum Pidana IndonesiaDokumen3 halamanArtikel Ilmiah Sengketa Lahan Pancoran Buntu II Dari Sudut Pandang Hukum Pidana IndonesiaMagdalena Yossi Dian MadaniBelum ada peringkat
- Makalah Pelanggaran HAM Di MesujiDokumen6 halamanMakalah Pelanggaran HAM Di MesujiFaisal AkhmadBelum ada peringkat
- Lexetsocietatis dk28,+1.+Ronald+Varit+SabajaDokumen9 halamanLexetsocietatis dk28,+1.+Ronald+Varit+SabajaZahra AryantiBelum ada peringkat
- Isi Tugas HKM FilsafatDokumen9 halamanIsi Tugas HKM FilsafatHattamul NotarisBelum ada peringkat
- T1-Pengantar Ilmu HukumDokumen2 halamanT1-Pengantar Ilmu HukumPingki NovianaBelum ada peringkat
- Tugas 1 Pengantar Ilmu HukumDokumen6 halamanTugas 1 Pengantar Ilmu HukumJoshBelum ada peringkat
- TMK 2 - Fisalfat Hukum Dan Etika Profesi - 043509549Dokumen4 halamanTMK 2 - Fisalfat Hukum Dan Etika Profesi - 043509549Melly AgestyBelum ada peringkat
- Contoh Kasus Hukum Perdata InternasionalDokumen4 halamanContoh Kasus Hukum Perdata InternasionalRizky D'shisuiBelum ada peringkat
- 445 2967 1 PBDokumen18 halaman445 2967 1 PBJulia SusantiBelum ada peringkat
- BINDO Tanggapan Kritis ProyekDokumen14 halamanBINDO Tanggapan Kritis ProyekAndi Afifah Khairunnisa100% (1)
- Laporan Penegakan Hukum Kelompok 4Dokumen6 halamanLaporan Penegakan Hukum Kelompok 4Asri SubiartiBelum ada peringkat
- Paper HukumDokumen6 halamanPaper HukumLioBelum ada peringkat
- Antropologi HukumDokumen11 halamanAntropologi HukumAnita SBelum ada peringkat
- Analisis Kasus Pelanggaran Ham Di IndonesiaDokumen16 halamanAnalisis Kasus Pelanggaran Ham Di IndonesiaWULAN MULYABelum ada peringkat
- Tugas 1 PTHIDokumen3 halamanTugas 1 PTHIGladiola VictoryBelum ada peringkat
- 156 - I Made Pawitra Witata Adhiyaksa - 2206063600 - RegDokumen5 halaman156 - I Made Pawitra Witata Adhiyaksa - 2206063600 - RegelleBelum ada peringkat
- Makalah ForensikDokumen10 halamanMakalah ForensikRizki SahputraBelum ada peringkat
- AdiwijayaDokumen5 halamanAdiwijayarobbyBelum ada peringkat
- Tugas 2 - Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiDokumen6 halamanTugas 2 - Filsafat Hukum Dan Etika ProfesiTamimiBelum ada peringkat
- Tugas 3 ISBD Alexander Satrio WibowoDokumen3 halamanTugas 3 ISBD Alexander Satrio WibowoAlexander SatrioBelum ada peringkat
- TUGAS 3 Pengantar Ilmu HukumDokumen8 halamanTUGAS 3 Pengantar Ilmu HukumAulia RahmiBelum ada peringkat
- Lembar Tugas 3 - PihDokumen8 halamanLembar Tugas 3 - Pihpanwascamblk2024Belum ada peringkat
- Tugas Iii Ilmu Hukum PolitikDokumen8 halamanTugas Iii Ilmu Hukum PolitikrizalzesarBelum ada peringkat
- Korban Dalam Sudut ViktimologiDokumen21 halamanKorban Dalam Sudut ViktimologiBaruna BagaskaraBelum ada peringkat
- Tugas 1 - PTHIDokumen3 halamanTugas 1 - PTHIacoba602Belum ada peringkat
- Tugas 1 PTHI 044638967Dokumen5 halamanTugas 1 PTHI 044638967SonikBelum ada peringkat
- Tugas 3 PthiDokumen5 halamanTugas 3 PthimyselfoamBelum ada peringkat
- Tugas 1 - Ersya Elin Aneke Putri - 047859637Dokumen6 halamanTugas 1 - Ersya Elin Aneke Putri - 047859637ERSYA ELIN ANEKE PUTRIBelum ada peringkat
- PKM Ai-Ristantia P 2023 JadiDokumen23 halamanPKM Ai-Ristantia P 2023 Jadidelironinsp9Belum ada peringkat
- Tugas Filsafat Hukum, Sylvia Meylindawati, 20200620020Dokumen16 halamanTugas Filsafat Hukum, Sylvia Meylindawati, 20200620020Akbar MedikaBelum ada peringkat
- Mahkamah KonstitusiDokumen18 halamanMahkamah KonstitusiToean ItjhanBelum ada peringkat
- Jawaban Responsi Pengantar Ilmu HukumDokumen3 halamanJawaban Responsi Pengantar Ilmu HukumMaulidhina MahardikaBelum ada peringkat
- Tugas 1 Agry Leofanny Pengantar Ilmu HukumDokumen5 halamanTugas 1 Agry Leofanny Pengantar Ilmu HukumagryleoBelum ada peringkat
- Penyimpangan KonstitusiDokumen6 halamanPenyimpangan KonstitusiMuhammad Nur AlfieBelum ada peringkat
- Kasus Pelanggaran HAM Di IndonesiaDokumen7 halamanKasus Pelanggaran HAM Di IndonesiaatikarahmayeniBelum ada peringkat
- R 8 PCND 1593225212Dokumen16 halamanR 8 PCND 1593225212Rizky AuliaBelum ada peringkat
- Sosiologi HukumDokumen5 halamanSosiologi HukumHidayat YogiBelum ada peringkat
- IndentasiDokumen2 halamanIndentasiKevin Kurniawan WijayaBelum ada peringkat
- Isu Kewarganegaraan GandaDokumen4 halamanIsu Kewarganegaraan GandaKevin Kurniawan WijayaBelum ada peringkat
- Soal Dan JawabanDokumen3 halamanSoal Dan JawabanKevin Kurniawan WijayaBelum ada peringkat
- Perencanaan Kampanye MPRDokumen3 halamanPerencanaan Kampanye MPRKevin Kurniawan WijayaBelum ada peringkat