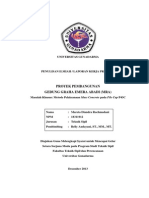MENCARI CINTA DI BALIK TOPENG
Diunggah oleh
Mareta Diandra RachmadaniJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
MENCARI CINTA DI BALIK TOPENG
Diunggah oleh
Mareta Diandra RachmadaniHak Cipta:
Format Tersedia
1
Dari Balik Topeng Kelana
Desember 2003. Di bawah pohon rindang, halaman rumah seorang abdi dalem Keraton Kasepuhan, Cirebon. Lantunan nada Gonjing dan Sarung Ilang(1) berkumandang dari sebuah radio tape butut milik mimi(2). Iramanya yang khas dan sudah tidak asing lagi di telingaku ini, menggiringku untuk mulai menggerakkan tubuh. Berlenggak-lenggok sebagaimana yang mimi ajarkan padaku sejak usiaku menginjak 5 tahun. Syahdu. Aku menikmatinya. Termasuk menikmati sepasang mata yang lekat menatap lenggokan tubuhku ini sejak tadi. Aku terus menari. Mengingat setiap gerakan yang mimi contohkan kepadaku saat kami berlatih tari topeng bersama. Menikmati setiap denting nada tarling khas kampung halamanku ini. Membiarkan tangan dan kakiku ini bergerak dengan lihainya, seolah dirasuki roh di bawah sadarku. Aku terus menari. Menari dalam tatapan itu. Hingga usai musik terhenti. Ia bertepuk tangan, saat aku dengan eloknya membungkukkan tubuhku di hadapannya. Bak seorang putri raja mempesona pangerannya. Bagus Sri, bagus. Kamu sudah pandai ya. Kalau begini, Aang(3) akan belikan es krim, mau toh ? Bener ya, Ang ? Asri mau es krim, Ang. Mau, mau. jawabku tak sabar. Aku memang selalu manja padanya. Ayo, ayo kita beli es krim ya. Aang merangkulku. Kami berjalan keluar halaman rumah. Menuju toko es krim tak jauh dari rumahku. Aang. Itu panggilanku padanya. Nama aslinya Fatah. Ia selalu bangga dengan nama itu. Orang tuanya mengambil nama itu dari salah satu nama Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon, Fatahillah, atau dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Aku hafal betul cerita itu. Sejak dulu, ia selalu berceloteh tentang hal itu. Usianya 3 tahun di atasku. Kami kenal sejak kecil sekali. Ayahnya dan ayahku merupakan abdi dalem Keraton Kasepuhan, Cirebon. Rumah kami berdekatan. Hanya dipisahkan oleh sepetak lapangan bola kecil, tempat bocah-bocah kampung kami biasa bermain. Aku menghormatinya, sebagai kakakku. Karena aku terlahir sebagai anak tunggal. Begitu pun dengannya. Keakraban orang tua kami menular kepada kami berdua. Sejak kecil, kami selalu bermain bersama. Dari pagi hingga petang. Namun kini sedikit berkurang, karena sudah setahun ini Aang Fatah harus bersekolah di sebuah sekolah menengah pertama yang letaknya cukup jauh dari rumah kami. Waktunya untukku tersita oleh waktu perjalanannya dari sekolah sampai ke rumah. Aku sempat protes tentang hal ini. Tapi, dengan lembut Aang Fatah memberikan penjelasan padaku. Ia begitu dewasa di mataku. Tenang dong, Sri. Aang kan gak pergi lama-lama. Sepulang sekolah, Aang pasti akan main ke rumahmu. Kita akan bermain bersama sampai magrib. Seperti biasa. senyumnya menjuntai.
(1)
(2)Mimi adalah sebutan ibu dalam bahasa Cirebon. (3)Aang adalah panggilan untuk kakak laki-laki dalam bahasa Cirebon.
Gonjing dan Sarung Ilang adalah lagu pengiring tari topeng Kelana.
Aku ingat betul kejadian itu. Saat Aang Fatah menjabarkan padaku bahwa waktu bermain kami tak akan berkurang hanya karena ia harus pergi bersekolah ke tempat yang cukup jauh. Saat Aang Fatah berjanji padaku untuk tidak akan pernah melupakanku. Sekali pun ia mempunyai banyak teman baru. Tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, yang aku ingat, aku begitu mempercayainya. Tak mengerti apa yang sebenarnya ada di hati ini, yang aku tahu, aku menyayanginya. Iya, menyayanginya. Sejak kecil. ** Desember 2012. Di sebuah sanggar tari terbuka, kompleks Keraton Kasepuhan, Cirebon. Hey ! Hayo, lagi ngelamunin apa sih, Nok(4), sore-sore begini ? Dewi mengejutkanku. Eh. Duh. Apa sih, Wi. Aku gak lagi ngelamunin apa-apa kok. aku mengelak. Aku tahu Dewi tidak akan percaya, karena jelas-jelas aku memang sedang melamun. Tapi aku tak perduli. Duh, mau bohong nih sama aku ? Ada apa sih sama Aang-mu itu ? kali ini Dewi menggodaku. Tawa dan senyumnya yang manis menghujaniku. Matanya melirik nakal ke arah seorang pria yang sedang mengajarkan tari topeng kepada beberapa muridnya, di tengah sanggar ini. Hah ? Apa ? Nggg, engga kok, Wi. Apa sih kamu ini. aku semakin terkejut. Berusaha mengelak lagi, tapi aku tahu usahaku tidak berhasil sepenuhnya. Duh, aku ini. Kenapa Dewi bisa sampai tahu sih aku sedang melamun memperhatikan Aang Fatah. Dewi memang berhasil menyadarkanku. Menyadarkanku dari lamunan panjang. Menyadarkanku dari wisata pikiran entah ke beberapa tahun yang lalu. Menyadarkanku tentang Aang Fatah. Entah mengapa, sore ini rasa itu muncul kembali. Rasa yang aku sendiri tak paham maksud dan artinya. Rasa yang aku sendiri tak sadar sejak kapan ia hadir dalam hati ini. Rasa yang aku sendiri tak tahu akan aku apakan nasibnya. Melihat Aang Fatah dari balik pilar sanggar ini, irama hatiku mengalun dengan sendirinya. Melantunkan irama yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Menadakan bait-bait yang tak pernah kukenal. Mengsyairkan tanda-tanda yang jujur saja, aku takut untuk mengakuinya. Sebenarnya, hal seperti ini bukanlah yang pertama kalinya aku rasakan. Entah apa yang sebenarnya semesta inginkan dariku. Kepala ini selalu dibayang-bayangi wajah Aang Fatah yang teduh, senyumnya yang ramah, dan tatapannya yang menjadi candu bagiku. Dulu, saat rasa ini belum hadir, berbincang dengan Aang Fatah adalah hal yang biasa kulakukan. Tak ada bedanya dengan perbincangan yang kulakukan dengan orang-orang lainnya. Tapi sekarang, entah sejak kapan, jangankan untuk berbincang, melihatnya tersenyum padaku saja, jantung ini sudah berlomba tidak karuan. Dulu, aku begitu manja padanya. Bersandar di bahunya, merengek menggenggam lengannya, hingga tertidur di punggungnya adalah hal yang biasa. Tapi sekarang, saat tangan halusnya mengusap rambutku dengan ramah, seperti ada gempa berskala richter tinggi menggoncang hatiku.
(4) Nok adalah panggilan untuk anak perempuan dalam bahasa Cirebon.
Terkadang aku berpikir, jika aku mampu menggambarkan rasa hatiku sedemikian hebatnya, apakah ini pertanda, kalau rasa yang kupunya untuk Aang Fatah, juga telah berubah, dari sayang kepada kakak, menjadi sayang kepada pria dewasa ? Jika jawabannya iya, lantas apakah ini benar ? Entahlah. Sungguh. Entahlah. Tuhkan ! Kamu ngelamun lagi ! Hahaha. Kamu mau bohongi aku ya ? Gak akan bisa, Nok ayu(5), gak akan bisa... lagi-lagi Dewi menepuk pundakku, menyadarkanku dari alam bawah sadarku. Ah, Dewi benar. Aku memang tak akan bisa berbohong padanya. Dewi adalah sahabat baikku. Kami bersekolah bersama. Dari SD hingga SMA. Kami pun memiliki hobi yang sama, menari. Berbohong di depan Dewi adalah hal yang sia-sia untuk kulakukan. Aku hanya tersenyum menjawab pertanyaan Dewi. Aku tak tahu harus berkata apa. Dewi yang sadar akan diriku yang sudah tidak bisa berbohong lagi pun tahu apa yang harus ia lakukan. Dewi mendekat padaku. Ia duduk di sampingku. Sama-sama bersandar pada sebuah pilar di salah satu sudut sanggar tari ini. Sudahlah, jangan terus-terusan membohongi perasaanmu, Sri. Kalau kamu memang menaruh hati pada Aang Fatah, katakan saja padanya. Ah, apa sih kamu ini, Wi. Mana mungkin aku suka sama Aang Fatah. Dia itu kan sudah seperti kakakku sendiri. Sejak kecil, kami sudah bersama-sama, mana mungkin aku bisa suka padanya. Kamu ini, Wi, bisa saja. Hahaha. aku tahu tawaku terakhir itu akan terdengar aneh. Biarlah, aku tak tahu lagi harus berkata apa pada Dewi. Loh, bersahabat sejak kecil kan bukan larangan untuk saling suka toh ? Perasaan suka itu datang dengan sendirinya, Sri. Gak ada yang minta dan gak ada yang melarang juga. Kamu gak perlu takut, perasaan kamu ini bukan sesuatu yang harus kamu buang. Rasa suka itu anugerah, Sri. Aku tertegun. Berusaha mengulang dan mencerna kalimat Dewi barusan. Iyo wis iyo. Aku nyerah, Wi. Kamu emang sahabat baikku, mana bisa aku bohong di depan kamu, ya ? Hahaha. aku mengacak-ngacak rambut Dewi. Kami tertawa bersama. ** Langit membalutku dengan jingganya. Anggun sekali. Matahari yang sudah hampir mengakhiri masa tugasnya hari ini, menyisakan bayangan tubuhku di tanah. Dan sekelompok burung gereja yang setia menemaniku dari atas dahan pohon di hadapanku ini. Aku masih berada di sanggar. Duduk di bangku-bangku halamannya. Menikmati senja. Menikmati langit sore hari. Aku sedang menunggu mimi. Ibuku itu juga salah satu guru tari topeng di sanggar ini. Ia mengajar kelas dewasa, berbeda dengan Aang Fatah yang mengajar kelas anak-anak. Banyak orang bilang, bakat tari yang kumiliki ini berasal dari ibuku itu. Dulu, mimi adalah salah seorang penari topeng terbaik di kota ini. Keelokannya di atas panggung sudah menghipnotis banyak pasang mata. Maka tak heran, mimi begitu bersemangat mengajariku tari topeng. Katanya, mencintai budaya daerah itu bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga harus benar-benar dilestarikan. Beruntungnya diriku, karena mimi tidak hanya mengajariku bagaimana caranya menari yang baik, tapi juga bagaimana mencintai budaya daerah, tulus dari dalam hati. Dan mimi berhasil. Aku mencintai budayaku ini.
(5) Nok ayu = gadis cantik
Aku hanya seorang diri. Dewi sudah pulang ke rumahnya sedari tadi. Katanya, ia harus membantu ibunya di rumah, jadi ia tidak bisa menemaniku menunggu mimi. Tak apa. Aku cukup senang sendiri. Bagiku, langit jingga dan burung gereja adalah paduan yang pas untuk mengusir sepi. Ah iya, satu lagi. Aku mengeluarkan buku agendaku dari dalam tas. Dan sebuah pena bertinta biru. Aku mulai membuka agendaku. Merobek secarik kertas di dalamnya, dan mulai berpikir. Aku ingin menulis sebuah puisi. Puisi adalah teman setiaku selain tari. Saat aku tidak bisa menggambarkan isi hati dengan gerakan tubuh di atas panggung, aku memilih untuk menuangkannya dalam barisan kata-kata. Tak terhitung berapa banyak puisi yang sudah kubuat. Sama seperti tak terhitungnya berapa banyak aku menghabisi waktuku untuk berlatih tari topeng. Jemariku mulai menari. Bersama pena. Di atas secarik kertas ini. Saat senja menyelimutiku Kau tak akan tahu betapa bayangmu tak luput dari kepalaku Saat jingga membalutku Kau tak akan tahu betapa namamu selalu hadir di memoriku Janganlah kau ganggu senja yang teduh ini Karena kau tak akan mengulangnya kembali Jangan pula kau renggut jingga darinya Karena kau tak akan tahu apa yang akan terjadi lagi Seperti jingga yang tak pernah tahu mengapa ia harus hadir saat senja Mungkin, seperti itulah aku Yang tak pernah tahu mengapa aku harus hadir padamu Biarkan jingga selalu berada pada senja Biarkan pula aku selalu ada untukmu Karena seabadi jingga di kala senja Mungkin, seabadi itu pula rasa ini di hatiku Kurasa, tak ada yang pernah salah. Saat rasa dalam hati ini menuntut untuk dicurahkan dalam sepotong kata-kata. Tak ada yang salah, saat jingga dan senja kala ini ternyata mampu membawa lantunan kata demi kata dari lubuk hatiku terdalam. Juga tak akan pernah salah, saat ternyata lagi-lagi Aang Fatah-lah yang muncul di benakku, untuk kutujukan sebait kata-kata ini. Aku memandangi secarik kertas ini. Tinta biru dalam pena yang kugunakan memenuhi lebih dari setengah permukaan kertas. Aku membuka kembali tutup penaku. Kububuhkan tanda tanganku di pojok kanan bawah kertas ini. Dan sepotong kalimat lagi di bawahnya. Desember 2012 Di kala senja. Di saat jingga menghujaniku. Untukmu, F. Aku baru saja ingin membaca ulang karyaku itu. Tapi, tiba-tiba saja. Hayo, apaan nih ? Ciyeee, puisi toh, Nok ayu ? Hahahaha. Ya ampun ! Pria ini ! Ah, bagaimana bisa ?!
Eh, Aang ! Kertasku jangan diambil, Ang ! Ayo sini balikin, Ang ! aku merengek. Aang Fatah. Iya. Ternyata dia juga masih ada di sanggar ini. Di datang menghampiriku tiba-tiba. Secepat kilat ia merebut kertas yang sedang kugenggam. Saking asiknya menulis, aku sampai tidak sadar kehadirannya mendekatiku. Ah, bodohnya dirimu, Sri ! Aku terus berusaha menggapai tangan kiri Aang Fatah. Ia duduk di samping kiriku, dan kertas itu berada di tangan kirinya. Jauh menggapai awang-awang. Tubuhnya yang tegap menghalangiku. Aku menarik-narik kerah baju bagian belakangnya. Tapi usahaku tetap siasia. Aang Fatah begitu gagah. Berada di balik punggungnya seperti ini justru membuat hatiku semakin tak karuan. Ditambah lagi wangi parfum khas miliknya. Salah satu alasanku menaruh hati padanya. Kamu lagi suka sama cowok ya, Sri. Hayo, gak usah bohong sama Aang. Hahahaha. Siapa cowoknya toh, Sri ? Eh, ini ada namanya ya.. Ya ampun ! Tidak ! Jangan ! F ? Entah mengapa, Aang Fatah berhenti tertawa. Ia menoleh ke arahku. Wajahnya begitu dekat dengan wajahku. Hingga aku mampu mendengar desah napasnya. Guratan halus wajahnya mampu kulihat dengan jelas. Hidungnya yang mancung hampir bertabrakan dengan hidungku yang tak kalah mancung. Matanya lurus menatapku. Begitu dalam. Rupanya ia tak tahu, betapa wanita di hadapannya ini sanggup benar-benar meleleh jika ia terus menatapku seperti ini. Alisnya bertemu menjadi satu. Dahinya berlipat. Ia benar-benar berpikir. Dan mungkin, mencium sesuatu dari goresan huruf F yang aku tulis di akhir puisiku itu. Jangan. Jangan untuk saat ini. Aku belum siap. F itu.... Fa.... Aang Fatah mulai menebak. Jangan ! Kumohon, Tuhan. Jangan kali ini. Aku belum siap jika Aang Fatah tahu bahwa aku menyukainya. Janganlah. Kumohon. Fadli, ya ? Iya kan ? Hayo, ciyeee. Asri ternyata sudah luluh juga ya.. Apa ? Apa yang baru saja Aang Fatah katakan ? Ah, terima kasih, Tuhan. Ia salah besar. Fadli adalah nama salah satu temanku di sanggar tari ini. Ia juga salah satu teman SDku. Sudah sejak lama orang-orang disini membicarakan kami. Kata orang, Fadli menyukaiku. Ia kerap tertangkap basah sedang mengambil gambarku dari telepon genggamnya secara diam-diam. Ia jugalah yang ternyata selalu menaruhkan bunga mawar di loker tempatku menyimpan peralatan tari. Dan, mungkin ia juga alasan setiap pagi telepon genggamku berdering, karena ada pesan selamat pagi yang masuk ke dalam kotak pesanku. Sebenarnya, aku juga sudah mengetahui hal itu. Bagaimana tidak, Fadli bukanlah orang yang pandai menyembunyikan perasaannya. Setiap kami berbicara, matanya selalu berkata lain. Tapi aku tak bisa berbuat banyak. Entah karena apa, hati ini tidak pernah terbuka untuknya. Namanya tak pernah ada dalam ingatanku setiap aku membuka mata. Bagiku, Fadli hanya teman yang baik. Tidak lebih. Mendengar tebakan Aang Fatah yang salah, aku menghembuskan napas panjang.
Duh, Aang ini. Berhenti menggodaku, Ang. aku sengaja tidak membantah tebakannya. Aku membiarkannya. Aku membiarkan Aang Fatah mengira bahwa huruf F itu untuk Fadli. Padahal, semesta beserta seluruh peri-peri yang hadir di sore hari ini juga tahu, F itu untuk nama yang selalu kau banggakan, Ang. Namamu. Fatah. Aku merebut kertas yang ada di genggaman Aang Fatah. Kali ini berhasil. Ia tidak lagi menggenggamnya dengan erat. Sekarang ia fokus menggodaku dengan menyebutkan nama Fadli berkali-kali di hadapanku. Sungguh, pria ini tak sadar. Bahwa aku ingin sekali menghentaknya, dan berkata di depan wajahnya, bahwa huruf F di puisi ini adalah namanya. Tapi. Aku tidak bisa. Tidak saat ini. Aang Fatah terus menggodaku. Sesekali aku membuang muka darinya, tanda tak setuju. Ia terus saja menggodaku. Menggelitik tubuhku dengan jemarinya, karena ia hafal betul aku tak akan sanggup menahan gelinya. Aku balas memukul tubuhnya yang tegap. Menghentakan kepalan tanganku pada bahunya, tak keras, hanya gurauan. Begitulah cara kami bercanda. Dari dulu, tak pernah berubah. Begitulah cara kami tertawa bersama. Membiarkan burung-burung iri karena tak bisa sebebas ini. Sampai, telepon genggam milik Aang Fatah berbunyi. Hahaha. Eh, eh, sebentar Sri. Kayanya handphone-ku bunyi. Sebentar ya. ia merogoh sakunya. Ia membaca nama yang tertera pada layar telepon genggamnya yang berkedapkedip. Sekilas, kulihat wajahnya seketika sumringah. Matanya berbinar. Ada rona lain yang kutangkap dari wajahnya setelah menatap layar telepon genggamnya itu. Tunggu dulu... Apakah ini..... ? Aang Fatah berjalan sedikit menjauh dariku. Ia menerima telepon dari seseorang disana. Entah siapa. Aku tak tahu. Pembicaraan mereka terlihat sangat akrab. Sesekali Aang Fatah tertawa. Sesekali ia memelankan volume bicaranya, terlihat begitu lembut. Tak berkurang sedikit pun binar di matanya. Tak menyusut sedikit pun senyum yang mengembang di wajahnya sedari tadi, setelah ia menerima telepon itu. Beribu satu pertanyaan menghinggapi pikiranku. Berjuta perasaan muncul seketika dalam hatiku. Aku bertanya. Dalam diam. Siapakah orang di ujung sana ? Apakah mungkin ia adalah......... ? Ah, sudahlah. Mungkin itu hanya telepon urusan pekerjaan yang memang sudah dinantikan oleh Aang Fatah. Iya. Mungkin, begitu. ** Terik matahari siang ini mungkin adalah yang terpanas sepanjang bulan. Ditambah posisi kota Cirebon-ku tercinta ini yang berada di pinggir laut Jawa, menambah ganasnya matahari yang senatiasa mengawasi. Bagiku, dan mungkin bagi seluruh masyarakat Cirebon, panasnya kota ini sudah menjadi makanan sehari-hari sejak dulu kala. Akan ada yang kurindukan jika kumeninggalkan kota ini. Dan teriknya kota yang tak ada duanya inilah salah satu jawabannya. Hari ini adalah hari dimana 2 hari lagi akan diadakan sebuah pementasan tari topeng. Waktu sudah berjalan sekitar 1 minggu setelah kejadian di suatu senja tempo itu. Tapi, aku masih ingat semuanya. Hafal betul. Setiap detiknya. Terutama saat kami bercanda. Iya. Kami. Aku dan Aang Fatah. Ah, sudahlah. Selalu saja namanya kusebut di setiap pikiranku berbicara.
Aku ingin fokus pada pementasanku 2 hari lagi. Karena pementasan ini adalah agenda tahunan bagi para budayawan Cirebon, khususnya kaum seperti kami, penari. Pementasan ini akan menjadi pementasan besar yang mungkin akan dihadiri oleh banyak orang, termasuk pelancong dari luar kota. Aku tidak ingin gagal. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri, dan juga kota tercintaku ini, hanya karena gagal dalam pementasannya nanti. Aku sungguh-sungguh. Mimi juga sangat berharap besar padaku. Dan aku tak ingin mengecewakannya. Pada pementasan tari topeng nanti, aku akan membawakan tari topeng Kelana. Tari topeng Kelana adalah gambaran seseorang yang bertabiat buruk, serakah, penuh amarah dan tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, namun tarinya justru yang paling banyak disenangi oleh penonton. Sebagian dari gerak tarinya menggambarkan seseorang yang tengah marah, mabuk, gandrung, tertawa terbahak-bahak, dan sebagainya. Bentuk topengnya menggambarkan karakter angkuh atau sosok manusia sombong. Pada ukiran topengnya tampak hiasan kepala memakai siger jambang, mata lebih nampak bengis berkumis tebal serta bibir gigi gereget kesan marah yang tidak puas-puas, warna mukanya merah tua. Entah mengapa, dari sekian banyak tari topeng khas Cirebon, tari topeng Kelana adalah favoritku. Wataknya yang gagah dan garang selalu menarik di mataku. Inilah salah satu alasan mengapa aku tak ingin main-main pada pementasan nanti. Lek, Fatah dateng ora ?(6) aku tak sengaja mendengar mimi bertanya pada salah satu kru sanggar tari kami. Kayae sih bli, Mi. Fatah ijin arepan ke umah calone iku, Mi.(7) Jadi, Aang Fatah tidak datang hari ini ? Ah, tunggu, calon apa ? Entah mengapa, mendengarnya secara tak sengaja menyulut turun semangatku. Aku menghela napas panjang. Sedikit bergumam pelan, tanda tak suka. Hilang kemana semangatku yang tadi membara ? Aku tak tahu. Aku seperti kehilangan salah satu motivasiku. Hari ini mungkin bukan hari pementasannya. Tapi, berlatih di hadapan Aang Fatah mampu menambah kepercayaan diriku. Entah bagaimana bisa hal itu terjadi. Sejak dulu, menari dalam tatapannya yang lekat adalah kesukaanku. Hari ini, aku tak akan mendapatkannya. Aku mulai bisa berdamai dengan diriku sendiri. Ada atau tak ada Aang Fatah hari ini, aku harus tetap berlatih dengan maksimal. Dan tentang calon yang dibicarakan tadi, aku tak mau ambil pusing penasaran memikirkannya. Biarkan saja. Tapi. Aku tersentak. Seperti teringat sesuatu. Entahlah. Aku tak tahu. Tiba-tiba saja aku ingat akan hal itu. Telepon itu. ** Ramai riuh penonton terdengar sampai ke belakang panggung. Banyaknya penonton yang hadir dalam audiotorium ini menghangatkan suasana panggung. Mereka menantikan acara pementasan yang akan dimulai sesaat lagi. Dari balik tirai ini, aku mampu melihat semuanya. Dari area belakang panggung ini, aku mampu menangkap puluhan pasang mata yang sudah tidak sabar untuk kehadiran kami, para pementas.
(6) Dek, Fatah datang tidak ? (7) Sepertinya tidak, Bu. Fatah ijin akan ke rumah calonnya itu, Bu.
Hari ini adalah hari pementasan tariku diselenggarakan. Sudah sejak pagi aku bersiap di tempat ini. Berlatih sebentar, mengulang gerakan dan menyempurnakannya dengan bantuan mimi. Menunggu giliran untuk dirias. Dan kini, aku sudah hampir siap. Wajahku merona dibalut tata rias yang cantik. Tidak sedikit orang-orang di sini berkata padaku, bahwa aku terlihat begitu mempesona. Dengan pakaian tari topeng Kelana berwarna merah yang gagah. Dengan segala atribut yang siap membantuku saat tampil nanti. Tinggal menunggu pembawa acara naik ke atas panggung, dan membuka acara. Aku didaulat untuk menjadi penari pembuka dalam acara ini. Suatu kehormatan. Aku hampir siap. Iya, hampir. Karena masih ada yang kunanti. Sejak tadi pagi, aku belum menemukan sosok Aang Fatahh. Ia tak terlihat disini. Padahal seharusnya, ia cukup sibuk hari ini, karena beberapa murid tarinya juga akan pentas. Tapi, entahlah. Aku sendiri tak berani untuk menanyakan keberadaannya pada orang lain. Aku terus mencari. Menyapu setiap bangku yang sudah lumayan penuh dari balik panggung ini dengan mataku. Memperhatikan dengan lihai satu per satu wajah, berharap akan kudapatkan wajah Aang Fatah yang teduh itu. Tapi nihil. Aku tak melihatnya. Kehadiran Aang Fatah dalam pementasanku merupakan salah satu modalku untuk tampil maksimal. Apalagi pada acara pementasan sebesar ini. Tak munafik, rasa deg-degan jantungku tak pernah bisa berkurang. Memikirkan apa yang akan terjadi nanti, saat aku menari di atas panggung di hadapan puluhan pasang mata itu. Dengan kehadiran Aang Fatah, aku yakin aku mampu meredam rasa deg-degan itu. Mungkin, aku terdengar berlebihan. Tapi entahlah, aku begitu menyukai tatapannya. Tatapannya yang lekat padaku saat aku berlenggok di atas panggung. Ada sebuah energi yang ku tak tahu dari mana asalnya. Sebuah energi dari sorot matanya, yang seolah berkata Menarilah dengan indah, Sri. Semua akan baik-baik saja. Percayalah. Dan untuk pementasan sebesar ini, aku butuh ia hadir di sini. Suasana di belakang panggung yang ramai mulai berkurang, saat ketua acara pementasan tari ini meminta perhatian. Rupanya, acara akan segera dimulai. Ia meminta kami, para pementas, untuk membuat lingkaran, bergandengan tangan, dan berdoa dalam diam untuk kelancaran pementasan nanti. Aku salah satu di antara mereka. Namun aku gagal berdoa dengan fokus. Doa yang kuucapkan dalam hati, tidak lain dan tidak bukan, adalah pengharapanku untuk bisa menemukan Aang Fatah di antara banyaknya penonton di hadapanku, saat aku sudah di atas panggung nanti. Itu saja. Pembawa acara mulai menaiki panggung. Ia membuka acara dengan cukup menawan, membuat para penonton semakin tidak sabar untuk menyaksikan para pementas. Dan, marilah kita sambut. Penampilan tari topeng Kelana, yang akan dibawakan oleh Asri Sekar. Beri tepuk tangan ! pembawa acara itu menyebutkan namaku. Baiklah. Inilah saatnya. Aku berjalan dari balik panggung, membawa topeng Kelana di genggamanku. Aku berjalan dengan anggunya. Berdiri di tengah panggung dan menghadapi hujan tatapan dari penonton di dalam audiotorium ini. Senyumku mengembang dengan manisnya. Tapi diamdiam, mataku terus mencari sesosok pria yang kunanti di antara puluhan penonton di hadapanku ini. Hasilnya masih nihil. Ia belum terlihat.
Musik mulai terdengar. Aku sudah siap di posisi awalku. Aku mulai menggerakkan tanganku dengan gemulai. Aku berusaha sekuat tenaga untuk bisa konsentrasi pada tarianku. Berusaha memasuki nada-nada yang mengalun, mengiringinya dengan gerakan tangan dan kaki yang lentur. Kuhentakkan setiap gerakan tangan dan kakiku dengan tegas. Gagah dan perkasa. Aku harus terlihat seperti itu, sesuai karakter tari topeng Kelana yang kubawakan. Seperti biasa, tarianku dimulai tanpa topeng. Lantunan irama tarling terus merasukiku. Menuntun tubuh ini bergerak sesuai dengan apa yang sudah kupersiapkan. Hingga tiba saat bagian ngedok(8). Aku memutar tubuhku membelakangi penonton. Aku memakai topeng Kelana yang sudah kusiapkan dengan sigapnya. Kugigit dengan kencang bagian dalam topeng, agar terpasang dengan sempurna di wajahku. Untuk beberapa saat, aku membiarkan musik mengalun tanpa gerakan tubuhku. Saat ini, aku benar-benar berharap, aku dapat menemukan sosok Aang Fatah dari balik topeng Kelana-ku ini. Aku memutar tubuhku lagi. Aku mulai berlenggak-lenggok dengan elok. Dari balik topeng Kelana ini, aku berusaha mencari sosok itu. Satu per satu. Perlahan-lahan, sambil terus menggerakkan tubuhku. Konsentrasiku terbagi dua. Tapi aku tetap berusaha tenang. Sampai pada akhirnya. Aku menemukannya. Tapi, saat sosok itu tertangkap oleh mataku. Hatiku bergetar seketika. Gemuruh muncul di dalamnya. Pikiranku semakin tak karuan, tapi aku tetap berusaha menggerakkan tubuhku. Yang kulihat bukan hanya sekedar Aang Fatah. Tapi sesosok wanita yang ada di sampingnya. Sesosok wanita yang tangannya sejak tadi bertautan di lengan Aang Fatah. Entah pikiran dari mana, tapi mereka terlihat begitu serasi di mataku. Mereka terus tersenyum, sambil sesekali bertatapan dan menggumamkan beberapa kalimat yang tak jelas dari pandanganku. Aku semakin tak karuan. Tiba-tiba aku ingat kejadian senja itu. Telepon itu. Pikiranku lari kesana kemari. Jantungku berdetak semakin cepat. Napasku tersenggal. Gigiku beradu semakin kuat, menggigit bagian dalam topeng hingga mampu kurasakan kayunya. Gerakanku sedikit berantakan. Tapi aku tetap terus menari. Napasku semakin tercekat, kala aku ingat percakapan mimi dengan salah satu kru tempo hari. Calon ? Calon apa maksudnya sebenarnya ? Apakah itu...., calon, istri ? Apakah wanita itu orangnya ? Astaga. Aku tak dapat mengelak lagi. Gerakanku semakin tak karuan. Irama tarling yang terus berputar tak lagi seirama dengan gerakan tubuhku. Aku lunglai. Entah kemana kekuatanku saat menghentakkan kaki dan tangan ini. Tapi aku terus bergerak. Aku tak tahu lagi akan terlihat seperti apa aku di mata para penonton ini. Aku tak bisa berpikir. Aku gagal berkonsentrasi. Aku berusaha mengaitkan semua kejadian yang terus berputar di kepalaku. Telepon itu. Calon itu. Dan aku semakin yakin pada satu titik. Titik yang tak pernah ku tahu sebelumnya. Titik yang sesungguhnya tak kuharapkan kebenarannya. Semakin ku memikirkannya, semakin aku yakin pada titik itu. Mereka terlihat semakin mesra. Aang Fatah kerap mendekatkan wajahnya pada wajah wanita di sampingnya itu. Ia membisikkan sesuatu yang tak mungkin dapat kudengar ucapannya. Wanita itu membalasnya dengan senyumnya yang begitu cantik. Atau sesekali mencubit manja lengan pria yang semakin erat dalam dekapannya itu.
(8) Ngedok adalah bagian saat penari memakai topengnya (kedok).
10
Aku kacau. Topeng Kelana-ku basah. Aku tak kuasa membendung air mataku. Aku tak kuasa menahan pilunya dalam hati. Aku tahu, penonton di hadapanku ini mulai dapat mencium sesuatu yang tidak beres terjadi padaku. Terlihat dari ujung mata di balik topengku ini, ada mimi yang menatapku dari samping panggung tempatku berdiri. Ia terlihat cemas. Sambil terus menggigit bibir bagian bawahnya, ia berusaha menyemangatiku dari jauh. Maafkan aku, Mi. Aku gagal. Aku terus menari walau ku tahu hasilnya tak akan sempurna. Aku terus menari dan membiarkan topeng ini terus membasah. Aku terus menari hingga napasku kerap tersenggal, berusaha mengatur tempo jantung ini. Dari balik topeng Kelana ini, aku menemukan satu hal. Hal yang bahkan tak kusadari dan kuduga keberadaannya. Dari balik topeng Kelana ini, aku belajar satu hal. Bahwa tidak semua cinta tercipta untuk menjadi sepasang kekasih. Dari balik topeng Kelana ini, aku menangis. Dan kau tak akan tahu itu, Ang. ***
Anda mungkin juga menyukai
- KisahCintaSantriDokumen7 halamanKisahCintaSantrielvinaBelum ada peringkat
- Kumpulan Cerpen AbsurdDokumen66 halamanKumpulan Cerpen AbsurdHendra Bangkit PramanaBelum ada peringkat
- Cerpen SingkatDokumen27 halamanCerpen Singkatdwi noviantiBelum ada peringkat
- Cerpen BellaDokumen15 halamanCerpen BellaAgustina SyaputriBelum ada peringkat
- Novel Sejarah KelamDokumen67 halamanNovel Sejarah KelammarianiBelum ada peringkat
- Diari Seorang BuayaDokumen7 halamanDiari Seorang BuayaHelmi EffendyBelum ada peringkat
- NOVELDokumen37 halamanNOVELFlinteria RantungBelum ada peringkat
- Puisi Itu CintaDokumen31 halamanPuisi Itu CintaRio Andika AbdullahBelum ada peringkat
- Angel Daun Datu - Dari Insecure Menjadi Lebih BersyukurDokumen6 halamanAngel Daun Datu - Dari Insecure Menjadi Lebih BersyukurVirgilia AnnaBelum ada peringkat
- Kenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu - W.S RendraDokumen6 halamanKenang-Kenangan Seorang Wanita Pemalu - W.S Rendradidizoneunila100% (5)
- Berdansa Di Bawah Cahaya RembulanDokumen11 halamanBerdansa Di Bawah Cahaya RembulanIdris Nearby каляBelum ada peringkat
- LUKA-WPS OfficeDokumen14 halamanLUKA-WPS OfficeKomalamala malaaBelum ada peringkat
- Kenang Kenangan Seorang Wanita Pemalu W S RendraDokumen6 halamanKenang Kenangan Seorang Wanita Pemalu W S RendraMASYITOH DIN CAHYANI100% (1)
- DIRIKUDokumen10 halamanDIRIKUReski aulia Ash sahraBelum ada peringkat
- Cinta yang TulusDokumen8 halamanCinta yang TulusJuned PersBelum ada peringkat
- 4Dokumen9 halaman4CintaQitaBelum ada peringkat
- Kaus Kaki BolongDokumen10 halamanKaus Kaki BolongAghanidanurBelum ada peringkat
- Surat JiwaDokumen42 halamanSurat JiwakhairunnisakamaruddiBelum ada peringkat
- Novel Always Love YouDokumen51 halamanNovel Always Love Youwahyuni permataBelum ada peringkat
- Bentuk Catatan KronologiDokumen156 halamanBentuk Catatan KronologiFatkhur RohmanBelum ada peringkat
- Pelangi Di Langit SenjaDokumen5 halamanPelangi Di Langit SenjaAhmad RopikBelum ada peringkat
- MIMPI MENUNTUNDokumen43 halamanMIMPI MENUNTUNUlvi IsnainiBelum ada peringkat
- Cerpen PendekDokumen32 halamanCerpen PendekwayangunabelokBelum ada peringkat
- BERMALAM TANPA MANFAATKAN FASILITASDokumen5 halamanBERMALAM TANPA MANFAATKAN FASILITAStio_seezue67% (3)
- Di Atas Bumi, Di Bawah Langit Finished)Dokumen159 halamanDi Atas Bumi, Di Bawah Langit Finished)Gilang FirmandaBelum ada peringkat
- Cerpen 1Dokumen6 halamanCerpen 1YELZA YURISQABelum ada peringkat
- Kumpulan PuisiDokumen11 halamanKumpulan PuisisaifullahBelum ada peringkat
- CERPEN TENTANG CINTA DAN PENYESALANDokumen6 halamanCERPEN TENTANG CINTA DAN PENYESALANYudho KerenzBelum ada peringkat
- Who Are YouDokumen8 halamanWho Are YouMarolinaSetyaRahayuBelum ada peringkat
- CerpenDokumen6 halamanCerpenLuffyBelum ada peringkat
- SinopsisDokumen6 halamanSinopsisBalqis AzharBelum ada peringkat
- IlpoverelloDokumen7 halamanIlpoverellovalentino elvisBelum ada peringkat
- DIAMNYADokumen43 halamanDIAMNYAGamingNoob CrackBelum ada peringkat
- Bisik Pohon PinusDokumen9 halamanBisik Pohon PinusJamesBelum ada peringkat
- Aku Suka Melihat Kemesraan KawanDokumen3 halamanAku Suka Melihat Kemesraan KawanAlloy AzzalyBelum ada peringkat
- Cerpen KusutDokumen5 halamanCerpen KusutMustika RahmawatiBelum ada peringkat
- Hanya Mimpi...Dokumen5 halamanHanya Mimpi...power5293Belum ada peringkat
- Cerpen Mengalir Bagai AirDokumen12 halamanCerpen Mengalir Bagai AirHalimatus Sa'diyahBelum ada peringkat
- CINTA DALAM DRA-WPS OfficeDokumen15 halamanCINTA DALAM DRA-WPS OfficeSembarang SembarangBelum ada peringkat
- SOAL TKMDokumen35 halamanSOAL TKMFariskanur ZamanmulyanaBelum ada peringkat
- Kelas X-7.Dokumen3 halamanKelas X-7.MUHAMMAD KRISNA AJI KURNIAWANBelum ada peringkat
- Novel Pendek: Luka SemalamDokumen35 halamanNovel Pendek: Luka Semalamshinahariah70% (33)
- Senandung Rindu Bintang KecilkuDokumen10 halamanSenandung Rindu Bintang KecilkuIstin Nana Robi'ahBelum ada peringkat
- Cinta Segi EmpatDokumen6 halamanCinta Segi EmpatYovitaBelum ada peringkat
- Novel Ipi TamatDokumen32 halamanNovel Ipi Tamattia0% (1)
- Analisis CerpenDokumen10 halamanAnalisis CerpenJoko NugrohoBelum ada peringkat
- Cerpen Rahadiani Bulan BahasaDokumen18 halamanCerpen Rahadiani Bulan Bahasarahadiani ningrumBelum ada peringkat
- Laut Dan LangitDokumen3 halamanLaut Dan LangitPrameshwari PutriBelum ada peringkat
- Cerpen Kelompok 3Dokumen10 halamanCerpen Kelompok 3Muhammad NurBelum ada peringkat
- Rinduku Ke SyurgaDokumen6 halamanRinduku Ke SyurgaaryBelum ada peringkat
- Wa0011.Dokumen3 halamanWa0011.Assyifa PutriBelum ada peringkat
- Surga Yang DekatDokumen5 halamanSurga Yang DekatNatasha HadiwinataBelum ada peringkat
- SEXUALDokumen10 halamanSEXUALYoutube Premium0% (1)
- Novel - Jaka & DaraDokumen219 halamanNovel - Jaka & DaraEiichiro FhajaruBelum ada peringkat
- Cerpen 12unexpected Ali PrillyDokumen15 halamanCerpen 12unexpected Ali PrillyMurti NingsihBelum ada peringkat
- Gadis Pemimpi 1Dokumen10 halamanGadis Pemimpi 1Ayu LestariBelum ada peringkat
- Cerpen Nazwa.k 1Dokumen6 halamanCerpen Nazwa.k 1Diki Denta PermanaBelum ada peringkat
- Cerpen Kelompok FharilDokumen16 halamanCerpen Kelompok FharilachmadfharilalradjabBelum ada peringkat
- CerpennkuuuuDokumen9 halamanCerpennkuuuuFarhan NasrullahBelum ada peringkat
- Modul AutocadDokumen21 halamanModul AutocadDadan YupiBelum ada peringkat
- Batrimetri Laut JawaDokumen1 halamanBatrimetri Laut JawaMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- Daftar PustakaDokumen1 halamanDaftar PustakaMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- Kata PengantarDokumen2 halamanKata PengantarMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- Presentasi KP - Mareta Diandra R (18311912)Dokumen31 halamanPresentasi KP - Mareta Diandra R (18311912)Mareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- JURNAL Metode Pelaksanaan Mass Concrete Pada Pile Cap P43CDokumen13 halamanJURNAL Metode Pelaksanaan Mass Concrete Pada Pile Cap P43CMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- CoverDokumen1 halamanCoverMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- Curiculum Vitae Mareta Diandra R 2014Dokumen2 halamanCuriculum Vitae Mareta Diandra R 2014Mareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- Daftar IsiDokumen5 halamanDaftar IsiMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- CoverDokumen1 halamanCoverMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- ABSTRAK Metode Pelaksanaan Mass ConcreteDokumen2 halamanABSTRAK Metode Pelaksanaan Mass ConcreteMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat
- Soal TP HidrolikaDokumen1 halamanSoal TP HidrolikaMareta Diandra RachmadaniBelum ada peringkat