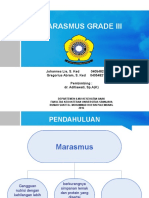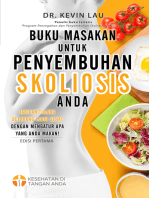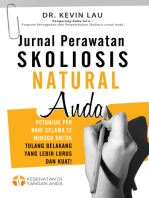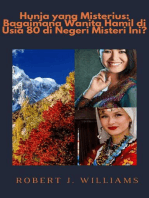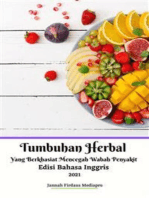Case G6PD
Case G6PD
Diunggah oleh
Dinar Kartika HapsariJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Case G6PD
Case G6PD
Diunggah oleh
Dinar Kartika HapsariHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB I
LAPORAN KASUS
I. IDENTIFIKASI
Nama : Ahmad Handika
Umur : 9 tahun
Jenis kelamin : laki - laki
Berat badan : kg
Panjang badan : 125 cm
Agama : Islam
Alamat : OKU Selatan
Dikirim Oleh : Datang sendiri
MRS : 2013
II ANAMNESIS
Alloanamnesis (ibu dan ayah pasien) dan autoanamnesis tanggal 8 Nopember
2013
Keluhan utama : Sakit perut
Keluhan tambahan : Demam tinggi, pilek.
Sejak 6 hari SMRS penderita mengeuh demam tinggi. Demam hilang timbul,
demam lebih tinggi pada malam hari (-), menggigil (-), berkeringat (+), meracau
(+), kejang (-), sesak (-), perdarahan di gusi (-), mimisan (-), nyeri sendi (+),nafsu
makan menurun (+), mual (+), muntah (+), muntah tidak menyemprot, frekuensi
3-4 kali per hari, banyaknya 3-4 sendok, muntah isi apa yang dimakan. BAB cair
(-), Frekuensi BAK 3-4 kali sehari, jumlah seperti biasa, masih bisa menahan
kencing, nyeri saat BAK (+). Penderita lalu berobat ke bidan dan dikatakan
menderita malaria, kemudian diberi 5 macam obat, yaitu obat penurun panas, 2
obat mual yang diminum sebelum dan sesudah makan, dan 2 obat malaria, tapi
ibu penderita lupa bentuk dan nama obatnya. Setelah minum obat, keluhan
berkurang.
2
Sejak 3 hari SMRS, demam muncul kembali. Demam tinggi, demam hilang
timbul, demam lebih tinggi pada malam hari (-), menggigil (-), berkeringat (+),
meracau (+), kejang (-), sesak (+), perdarahan di gusi (-), mimisan (-), nyeri sendi
(+), nafsu makan menurun (+), mual (+), muntah (+), muntah tidak menyemprot,
muntah semakin sering, frekuensi 4-6 kali per hari, banyaknya 1-3 sendok,
muntah isi apa yang dimakan. BAB cair (-), BAB hitam (+), frekuensi 1 x..
Frekuensi BAK 3-4 kali sehari, jumlah seperti biasa, masih bisa menahan kencing,
nyeri saat BAK (+) bertambah parah. Penderita lalu berobat ke bidan dan
dikatakan menderita demam tifoid, kemudian diberi 4 macam obat, yaitu 2 macam
sirup, dan 2 tablet, yaitu obat penurun panas, obat sakit maag, dan obat tifoid.
Sejak 1 hari SMRS penderita merasa keluhan tidak berkurang, sesak (+)
bertambah parah, lemas (+), pucat(+), nyeri saat BAK (+), kemudian penderita
dibawa berobat ke RSUD Ibnu Sutowo Baturaja.
Riwayat penyakit dahulu
Riwayat menderita penyakit dengan keluhan dan gejala yang sama sebelumnya
disangkal
Riwayat keluarga
40 Thn 35 thn
9 thn 6 thn 9 bulan
Tidak ada kelurga yang menderita penyakit yang sama.
Riwayat sosial Ekonomi
Penderita merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, Ayah penderita bekerja
sebagai petani jagung. Ibu penderita bekerja sebagai ibu rumah tangga, dengan
3
penghasilan keluarga Rp. 1.000.000 per bulan. Kesan sosial ekonomi menengah
ke bawah.
Riwayat Higienitas Rumah dan keluarga
Penderita sekeluarga tinggal di rumah yang terdiri dari tiga kamar dan 1
WC, masing masing kamar ada jendela satu, dan di ruang tamu ada 2 jendela.
Lantai rumah terbuat dari semen. Rumah mendapatkan cahaya matahari. Aktivitas
mencuci, masak, mandi serta minum menggunakan air sumur.Jarak antara rumah
dan tetangga tidak terlalu dekat. Air tergenang (-), menguras bak mandi 1 minggu
sekali (+), pembungan sampah dengan cara dibakar, menggantung baju (-)
Kesan : Ventilasi, pencahayaan, sanitasi lingkungan rumah baik.
Riwayat Kehamilan dan Kelahiran
Masa kehamilan : cukup bulan
Partus : spontan
Ditolong oleh : bidan
BBL : 3500 gram
PBL : tidak diketahui
Keadaan saat lahir : Langsung menangis
Riwayat Perkembangan
Berbalik : 3 bulan
Tengkurap : 3 bulan
Merangkak : 6 bulan
Duduk : 8 bulan
Berdiri : 9 bulan
Berjalan : 12 bulan
Berbicara : 13 bulan
Kesan : Riwayat perkembangan sesuai dengan tahap perkembangan usia.
Riwayat Makanan
4
ASI : sejak lahir sampai 2 tahun, pemberian ASI 8 kali sehari , pagi,
siang, maupun malam. ASI eksklusif 0-6 bulan.
Susu formula : Sejak usia 7 bulan sampai 4 tahun.
Bubur promina : Sejak usia 6 bulan sampai 7 bulan penderita mendapat bubur
promina, 3 x perhari, jumlahnya 4-6 sendok makan.
Bubur saring : 7 bulan sampai 9 bulan, diberikan sebanyak 4-5 sdm dengan
frekuensi 3x sehari. Biasanya bubur saring ditambah ikan 1
potong disuir, telur rebus 1 buah, sayur ikat.
Nasi biasa : sejak usia 9 bulan mulai diberikan nasi biasa sebanyak - 1
centong nasi dengan frekuensi 3x sehari. Nasi biasanya ditambah
ati ayam, ikan 1 potong, telur 1 buah.
Riwayat makan saat ini : Rata-rata anak makan 3x/hari, makan pagi, siang dan
makan malam. Sekali makan banyaknya 1 centong nasi, lauk ikan 1
potong, telur 1 buah, ayam 1 potong, tempe 1 potong, makanan
habis. Penderita suka jajan bakso hampir setiap sore, setiap 1
minggu sekali makan mie instan.
Kesan : kualitas dan kuantitas makan cukup.
Riwayat Imunisasi
BCG = 1x
Hepatitis B = 3 x
DPT = 3 x
Polio = 4 x
Campak = 3 x
Kesan : Imunisasi dasar lengkap
III. PEMERIKSAAN FISIK
Keadaan umum : Tampak sakit sedang
Kesadaran : Compos mentis
Nadi : 112 x/m
5
Tekanan Darah : 110/60 mmHg
Pernapasan : 42 x/m
Temperatur : 37,4
0
c
Keadaan gizi : BB : 20 kg TB 125 cm
Berdasarkan kurva CDC:
BB/U = 20 /29 x 100 % = 68,9 % moderate wasting
TB/U = 125/134 x 100% = 93,28 % mild stunting
BB/TB = 20 / 25 x 100% = 80 % gizi kurang
Kesan status gizi : Gizi kurang
Keadaan Spesifik :
Kepala : Lingkar Kepala cm (di antara 0SD dan -2SD) normocephali
Rambut : Distribusi normal, warna hitam, tidak mudah dicabut
Mata : Mata cekung (-), konjungtiva anemis (+)/(+), sklera ikterik
(+)/(+), pupil bulat, isokor, ukuran 3 mm/3mm, refleks cahaya
(+)/(+)
Hidung : Deformitas (-), nafas cuping hidung (-), deviasi septum (-),
mukosa hiperemis (-), sekret (-), hipertrofi konka (-)
Telinga : Deformitas(-), nyeri tarik aurikula (-), mukosa hiperemis(-),
sekret (-), serumen plak (+), kanalis aurikula eksterna lapang,
nyeri tekan tragus dan mastoid (-)
Mulut : Rhagaden(-), cheilitis(-), coated tongue(+), papil atrofi(+)
Tenggorokan : Uvula tenang, tonsil T2-T2, dinding faring posterior
hiperemis (-)
Leher : pembesaran kelenjar getah bening (-).
Thorak
Pulmo
6
Inspeksi :statis paru kanan-paru kiri simetris, dinamis paru kanan-paru kiri
simetris, retraksi (-)
Palpasi :stem fremitus paru kanan = paru kiri
Perkusi :sonor di kedua lapangan paru, batas paru hati ICS V linea
midklavikularis dekstra, peranjakan hati 1 sela iga
Auskultasi: vesikuler (+) normal, wheezing (-), ekspirasi memanjang (-),
rhonki(-)
Cor
Inspeksi : iktus kordis terlihat di ICS V linea midklavikularis sinistra
Palpasi : iktus kordis teraba di ICS V linea midklavikularis sinistra
Perkusi : batas atas jantung ICS II linea midklavikularis sinistra
batas kanan jantung ICS IV linea parasternalis sinistra
batas kiri jantung ICS IV linea aksilaris anterior
Auskultasi : HR 112x/menit, bunyi jantung I-II normal, reguler, pulsus
defisit (-), murmur (-), gallop (-)
Abdomen
Inspeksi : datar
Palpasi : sedikit tegang, nyeri tekan (-), hati dan limpa tidak teraba
Perkusi : timpani, nyeri ketok (-) di seluruh kuadran abdomen
Auskultasi : bising usus (+) normal
Genitalia : tidak ada kelainan
Ekstremitas : akral hangat, pucat (+), capillary refill time kurang dari 2 detik.
Hasil Pemeriksaan Laboratorium :
( 8 oktober 2013)
Hb : 7,4 g/dl
RBC : 3.000.000 /ul
Leukosit : 22.700 /ul
Golongan darah rhesus: A +
LED 139 mm/jam
Hitung jenis leukosit :
7
- Segmen : 69 %
- Limfosit 31 %
( 10 Oktober 2013)
Hb : 7,2 g/dl
Eritrosit : 3.100.000 /ul
Leukosit : 16.400/ul
Trombosit : 766.000 /ul
Hematokrit : 22 %
LED : 110mm/jam
Hitung Jenis Leukosit
- Segmen : 73 %
- Limfosit : 23 %
Kesan : terdapat anemia, leukositosis, trombositosis, peningkatan LED
V. DIAGNOSIS BANDING
Anemia + jaundice e.c G6PD dd/ Malaria, AIHA + susp. ISK + gizi kurang.
VI. DIAGNOSIS
Anemia + jaundice e.c. susp. G6PD + ISK + gizi kurang.
VII. PEMERIKSAAN PENUNJANG
- BCG test
VIII. PENATALAKSANAAN
- IVFD KAEN IB gtt XII/menit
- Inj.Vitamin K 2x1 amp
- Inj.Ampicilin 3x700 mg
- Inj. Furosemide1amp post transfusi
- Transfusi WB 200 cc gtt XX/menit
8
- O
2
dower
- Diet bubur biasa
IX. PROGNOSIS
Quo ad vitam : dubia ad bonam
Quo ad functionam : dubia ad bonam
FOLLOW UP
Tanggal Follow Up
7 Nopember 2013
Usia: 9 tahun
Perawatan hari ke-1
BB: 20 kg
D
S
O
Anemia e.c susp. defisiensi G6PD + susp. ISK
+ gizi kurang
Pucat (+), kuning(+), BAK hitam (+), BAB
hitam (+)
KU : Tampak sakit sedang
Sens : Compos mentis
TD : 100/60 mmHg
Nadi : 101 x/ menit isi dan tegangan kurang
RR : 46 x /menit
T: 37,7 C
Keadaan spesifik
Kepala : NCH (-/-), CA (+/+), SI (+/+),
refleks cahaya (+/+) N, pupil bulat,
isokor, diameter 3mm/3mm, uvula
tenang, tonsil T1-T1, dinding faring
posterior hiperemis (-)
Leher :Tidak ada kelainan, perbesaran KGB
(-), kaku kuduk (-)
Thoraks : Bentuk simetris, pergerakan statis
dan dinamis simetris, retraksi (-)
Paru-paru : statis, dinamis simetris, stem
fremitus kanan=kiri, sonor pada kedua
lapangan paru, vesikuler (+) Normal,
ronki (-), wheezing(-)
Jantung :ictus tidak teraba, HR 101 x/menit,
irama reguler, BJ I-II normal, murmur
(-), gallop (-)
Abdomen :datar, lemas, hepar tidak teraba dan
lien tidak teraba, cubitan kulit kembali
cepat (+), bising usus (+) normal
Ekstremitas : Akral hangat (-), pucat, edema
9
P
tidak ada, CRT < 2 detik
Lipat paha dan genitalia:Pembesaran KGB tidak
ada, genitalia tidak ada kelainan
IVFD NS gtt XII/menit
Inj.Vitamin K 2x1 amp
Inj.Ampicilin 3x700 mg
Inj. Furosemide1amp post transfusi
Transfusi WB 200 cc gtt XX/menit (I)
O
2
dower
Diet bubur biasa
8 Nopember 2013
Usia: 9 tahun
Perawatan hari ke-2
BB: 20 kg
D
S
O
Anemia e.c susp. defisiensi G6PD + susp. ISK
+ gizi kurang
Pucat (+), kuning(+), sesak (+), BAK kecoklatan
(+)
KU : Tampak sakit sedang
Sens : Compos mentis
TD : 110/60 mmHg
Nadi : 112 x/ menit isi dan tegangan kurang
RR : 42 x /menit
T: 37,4 C
Keadaan spesifik
Kepala : NCH (-/-), CA (+/+), SI (+/+),
refleks cahaya (+/+) N, pupil bulat,
isokor, diameter 3mm/3mm, uvula
tenang, tonsil T1-T1, dinding faring
posterior hiperemis (-), coated tongue
(+)
Leher :Tidak ada kelainan, perbesaran KGB
(-), kaku kuduk (-)
Thoraks : Bentuk simetris, pergerakan statis
dan dinamis simetris, retraksi (-)
Paru-paru : statis, dinamis simetris, stem
fremitus kanan=kiri, sonor pada kedua
lapangan paru, vesikuler (+) Normal,
ronki (-), wheezing(-)
Jantung :ictus tidak teraba, HR 112 x/menit,
irama reguler, BJ I-II normal, murmur
(-), gallop (-)
Abdomen :datar, lemas, hepar tidak teraba dan
lien tidak teraba, cubitan kulit kembali
cepat (+), bising usus (+) normal
Ekstremitas : Akral hangat (-), pucat, edema
tidak ada, CRT < 2 detik
Lipat paha dan genitalia:Pembesaran KGB tidak
10
ada, genitalia tidak ada kelainan
IVFD KAEN 1B gtt XII/menit
Inj.Vitamin K 2x1 amp
Inj.Ampicilin 3x700 mg
Transfusi WB 200 cc gtt XX/menit (II)
Oral vitamin B complex 3x1 tab
O
2
dower
Diet bubur biasa
9 Nopember 2013
Usia: 9 tahun
Perawatan hari ke-3
BB: 20 kg
D
S
O
P
Anemia e.c susp. defisiensi G6PD + susp. ISK
+ gizi kurang
Pucat (+), kuning(+), sesak (-), BAK kuning (+)
KU : Tampak sakit sedang
Sens : Compos mentis
TD : 110/60 mmHg
Nadi : 90 x/ menit isi dan tegangan cukup
RR : 30 x /menit
T: 37,1 C
Keadaan spesifik
Kepala : NCH (-/-), CA (+/+), SI (+/+),
refleks cahaya (+/+) N, pupil bulat,
isokor, diameter 3mm/3mm, uvula
tenang, tonsil T1-T1, dinding faring
posterior hiperemis (-), coated tongue
(+)
Leher :Tidak ada kelainan, perbesaran KGB
(-), kaku kuduk (-)
Thoraks : Bentuk simetris, pergerakan statis
dan dinamis simetris, retraksi (-)
Paru-paru : statis, dinamis simetris, stem
fremitus kanan=kiri, sonor pada kedua
lapangan paru, vesikuler (+) Normal,
ronki (-), wheezing(-)
Jantung :ictus tidak teraba, HR 90 x/menit,
irama reguler, BJ I-II normal, murmur
(-), gallop (-)
Abdomen :datar, lemas, hepar tidak teraba dan
lien tidak teraba, cubitan kulit kembali
cepat (+), bising usus (+) normal
Ekstremitas : Akral hangat (-), pucat, edema
tidak ada, CRT < 2 detik
Lipat paha dan genitalia:Pembesaran KGB tidak
ada, genitalia tidak ada kelainan
IVFD KAEN 1B gtt XII/menit
Oral vitamin B complex 3x1 tab
11
Diet bubur biasa
11 Nopember 2013
Usia: 9 tahun
Perawatan hari ke-5
BB: 20 kg
D
S
O
P
Anemia e.c susp. defisiensi G6PD + susp. ISK
+ gizi kurang
Pucat (+), kuning(-), sesak (-), BAK kuning (+)
KU : Tampak sakit sedang
Sens : Compos mentis
TD : 90/60 mmHg
Nadi : 94 x/ menit isi dan tegangan cukup
RR : 26 x /menit
T: 37,0 C
Keadaan spesifik
Kepala : NCH (-/-), CA (+/+), SI (-/-), refleks
cahaya (+/+) N, pupil bulat, isokor,
diameter 3mm/3mm, uvula tenang,
tonsil T1-T1, dinding faring posterior
hiperemis (-), coated tongue (+)
Leher :Tidak ada kelainan, perbesaran KGB
(-), kaku kuduk (-)
Thoraks : Bentuk simetris, pergerakan statis
dan dinamis simetris, retraksi (-)
Paru-paru : statis, dinamis simetris, stem
fremitus kanan=kiri, sonor pada kedua
lapangan paru, vesikuler (+) Normal,
ronki (-), wheezing(-)
Jantung :ictus tidak teraba, HR 90 x/menit,
irama reguler, BJ I-II normal, murmur
(-), gallop (-)
Abdomen :datar, lemas, hepar tidak teraba dan
lien tidak teraba, cubitan kulit kembali
cepat (+), bising usus (+) normal
Ekstremitas : Akral hangat (-), pucat, edema
tidak ada, CRT < 2 detik
Lipat paha dan genitalia:Pembesaran KGB tidak
ada, genitalia tidak ada kelainan
IVFD KAEN 1B gtt XII/menit
Oral vitamin B complex 3x1 tab
Transfusi WB 200 cc gtt XX/menit (III)
Diet bubur biasa
12 Nopember 2013
Usia: 9 tahun
Perawatan hari ke-6
BB: 20 kg
D
S
O
Anemia e.c susp. defisiensi G6PD + susp. ISK
+ gizi kurang
Pucat (-), kuning(-), sesak (-), BAK kuning (+)
KU : Tampak sakit sedang
12
P
Sens : Compos mentis
TD : 100/60 mmHg
Nadi : 94 x/ menit isi dan tegangan cukup
RR : 24 x /menit
T: 36,5 C
Keadaan spesifik
Kepala : NCH (-/-), CA (-/-), SI (-/-), refleks
cahaya (+/+) N, pupil bulat, isokor,
diameter 3mm/3mm, uvula tenang,
tonsil T1-T1, dinding faring posterior
hiperemis (-), coated tongue (-)
Leher :Tidak ada kelainan, perbesaran KGB
(-), kaku kuduk (-)
Thoraks : Bentuk simetris, pergerakan statis
dan dinamis simetris, retraksi (-)
Paru-paru : statis, dinamis simetris, stem
fremitus kanan=kiri, sonor pada kedua
lapangan paru, vesikuler (+) Normal,
ronki (-), wheezing(-)
Jantung :ictus tidak teraba, HR 90 x/menit,
irama reguler, BJ I-II normal, murmur
(-), gallop (-)
Abdomen :datar, lemas, hepar tidak teraba dan
lien tidak teraba, cubitan kulit kembali
cepat (+), bising usus (+) normal
Ekstremitas : Akral hangat (-), pucat, edema
tidak ada, CRT < 2 detik
Lipat paha dan genitalia:Pembesaran KGB tidak
ada, genitalia tidak ada kelainan
IVFD KAEN 1B gtt XII/menit
Oral vitamin B complex 3x1 tab
Transfusi WB 200 cc gtt XX/menit (IV)
Diet bubur biasa
13
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
I. DEFISIENSI G6PD
a. Definisi
Defisiensi G6PD adalah suatu kelainan enzim yang terkait kromosom sex
(x-linked), yang diwariskan, dimana aktifitas atau stabilitas enzim G6PD
menurun, sehingga menyebabkan pemecahan sel darah merah pada saat seorang
individu terpapar oleh bahan eksogen yang potensial menyebabkan kerusakan
oksidatif.
b. Epidemiologi
Defisiensi G6PD merupakan penyakit defisiensi enzim tersering pada
manusia, sekitar 2-3% dari seluruh populasi di dunia diperkirakan sekitar 400
juta manusia di seluruh dunia. Frekuensi tertinggi didapatkan daerah tropis,
ditemukan dengan frekuensi yang bervariasi pada berbagai ras Timur tengah,
India, Cina, Melayu, Thailand, Filipina dan Melanesia. Defisiensi G6PD menjadi
penyebab tersering kejadian ikterus dan anemia hemolitik akut di kawasan Asia
Tenggara 14. Di Indonesia insidennya diperkirakan 1-14% 17,18, prevalensi
defisiensi G6PD di Jawa Tengah sebesar 15% 19, di pulau-pulau kecil yang
terisolir di Indonesia bagian Timur (pulau Babar, Tanimbar, Kur dan Romang di
Propinsi Maluku), disebutkan bahwa insiden defisiensi G6PD adalah 1,6 - 6,7%.
c. Biokimia Molekuler dan Metabolisme Fisiologis Enzim G6PD
Enzim G6PD merupakan polipeptida yang terdiri atas 515 asam amino
dengan berat molekul 59,265 kilodalton 15. Enzim G6PD merupakan enzim
pertama jalur pentosa phoshat, yang mengubah glukosa-6-phosphat menjadi 6-
fosfogluconat pada proses glikosis. Perubahan ini menghasilkan
NicotinamideAdenine Dinucleotide Phosphate (NADPH), yang akan mereduksi
14
glutationteroksidasi (GSSG) menjadi glutation tereduksi (GSH). GSH berfungsi
sebagai pemecah peroksida dan oksidan radikal H2O2 (Gambar 1) 10- 16.Dalam
keadaan normal peroksida dan radikal bebas dibuang olehkatalase dan gluthatione
peroxidase, selanjutnya meningkatkan produksi GSSG. GSH dibentuk dari GSSG
dengan bantuan enzim gluthatione reductase yang keberadaannya tergantung pada
NADPH. Pada defisiensi G6PD, pembentukkan NADPH berkurang sehingga
berpengaruh pada regenerasi GSH dari GSSG,
akibatnya mempengaruhi kemampuan untuk menghilangkan peroksida dan
radikal bebas.
Gen G6PD terdiri 13 ekson dan 12 intron yang tersebar pada daerah seluas
lebih 100 kb pada ujung terminal lengan panjang kromosom X. Defisiensi G6PD
terjadi akibat mutasi gen G6PD, suatu penyakit sex-linked. Laki-laki hanya
mempunyai 1 kromosom X, sehingga jika terjadi mutasi maka defisiensi G6PD
akan muncul atau bermanifes. Wanita mempunyai 2 kromosom X, sehingga jika
terdapat 1 gen yang abnormal karena mutasi, pasangan atau
allele-nya dapat menutupi kekurangannya tersebut, sehingga defisiensi G6PD
bisa bermanifes namun dapat pula tidak.
Defisiensi G6PD meliputi berbagai mutasi gen G6PD yang berbeda-beda
dan tidak bereaksi sama, hal ini menjelaskan mengapa individu defisiensi G6PD
menunjukkan reaksi berbeda dengan faktor pencetus yang sama. Gen G6PD yang
berlokasi pada kromosom Xq28 dengan panjang 18 Kb, terdiri atas 13 exon
merupakan DNA dan 12 intron merupakan sekuen pengganggu, merupakan
sampah DNA yang tidak berperan dalam fungsi enzim. Fungsi enzim ditentukan
oleh sekuens dan ukuran gen G6PD dan mRNA yang menjadi ciri gen.
Pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) dapat membantu mengidentifikasi
adanya mutasi. Saat ini telah diketahui lebih 40 mutasi yang tersebar sepanjang
pada seluruh pengkode gen, masing-masing berbeda-beda dan mempunyai ciri
khas tersendiri. Telah dilaporkan lebih 400 varian G6PD, dengan disertai
penampilan klinis dan atau fenotif yang beragam. Varian tersebut dibedakan
berdasar aktifitas enzim residual, mobilisasi elektroforetik, afinitas dan analog
subtrat, stabilisasi terhadap panas dan pH optimum.
15
WHO membuat klasifikasi berdasarkan varian yang ditemukan di setiap
negara, subtitusi nukleotid dan subtitusi asam amino yaitu
Kelas I : Anemia hemolitik non sferositosis (aktifitas residual G6PD, <20).
Merupakan jenis defisiensi enzim G6PD yang jarang ditemukan.
Kelompok ini mempunyai kelainan fungsional yang berat (varian
Harilaou). Sel darah merah tidak mampu mempertahankan diri dari
oksidan endogen, sehingga terjadi hemolisis kronik. Adanya pemaparan
dengan faktor pencetus akan menyebabkan terjadinya eksaserbasi
anemia hemolitik akut.
Kelas II : defisiensi berat (aktifitas residual G6PD, <10). Kelompok defisiensi
enzim G6PD berat (varian G6PD Mediteranian). Pemaparan dengan
faktor pencetus (eksogen) akan menimbulkan hemolisis akut dan proses
tersebut akan terus berlanjut selama masih terdapat pemaparan dengan
faktor pencetus. Hal ini disebabkan rendahnya aktivitas enzim G6PD
baik pada sel darah merah yang tua maupun muda.
Kelas III : defisiensi sedang (aktifitas residual G6PD, 10-60). Kelompok defisensi
enzim G6PD ringan (varian G6PD A). Pada kelompok ini, hemolisis
yang timbul akibat pemaparan dengan faktor pencetus akan berhenti
dengan sendirinya walaupun pemaparan masih terus berlanjut. Hal ini
disebabkan aktivitas enzim G6PD pada sel darah merah yang muda
masih cukup tinggi untuk menahan oksidan, dan hanya sel darah merah
yang tua saja yang mengalami hemolisis.
Kelas IV : non defisiensi (aktifitas residual G6PD, 100). Kelompok yang tidak
mengalami gejala-gejala defisiensi G6PD.
Kelas V : non defisiensi (aktifitas residual G6PD, >100)
d. Peranan Enzim G6PD Pada Sel Darah Merah
Sel darah merah membutuhkan suplai energi secara terus menerus untuk
mempertahankan bentuk, volume, kelenturan (fleksibilitas), dan regulasi
pompanatrium-kaliumnya. Energi ini diperoleh dari glukosa melalui dua jalur
16
metabolisme yaitu, 80% dari proses glikolisis anaerobik (jalur Emden-Meyerhof)
dan 20% proses glikolisis aerobik (jalur Pentosa Fosfat).
Peran enzim G6PD dalam mempertahankan keutuhan sel darah merah serta
menghindarkan kejadian hemolitik, terletak pada fungsinya dalam jalur pentosa
fosfat. Di dalam sel darah merah terdapat suatu senyawa glutation tereduksi
(GSH) yang mampu menjaga keutuhan gugus sulfidril (SH) pada hemoglobin dan
sel darah merah. Fungsi GSH adalah mempertahankan residu sistein pada
hemoglobin dan protein-protein lain pada membran eritrosit agar tetap dalam
bentuk tereduksi dan aktif, mempertahankan hemoglobin dalam bentuk fero,
mempertahankan struktur normal sel darah merah, serta berperan dalam proses
detoksifikasi, dimana GSH merupakan substrat kedua bagi enzim gluthation
peroksidase dalam menetralkan hidrogen peroksida yang merupakan suatu
oksidan yang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan oksidatif pada sel darah
merah.
Senyawa GSH pada awalnya dalah suatu glutation bentuk disulfida
(glutation teroksidasi, GSSG) yang direduksi menjadi glutation bentuk sulfhidril
(glutation tereduksi, GSH). Reduksi GSSG menjadi GSH dilakukan oleh NADPH,
pada jalur pentosa fosfat, dimana pada jalur metabolisme ini NADPH dibentuk
bila glucose-6-phosphate dioksidasi menjadi 6-fosfogluconat dengan bantuan
enzim G6PD (Gambar 2) 10-16,25. .Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa
fungsi enzim G6PD adalah menyediakan NADPH yang diperlukan untuk
membentuk kembali GSH.
17
Pada defisiensi G6PD kadar NADPH berkurang, sehingga adanya paparan
terhadap stress oksidan akan mempengaruhi pembentukan ikatan disulfide,
mengakibatkan hemoglobin mengalami denaturasi dan membentuk partikel kental
(Heinz bodies). Heinz bodies akan berikatan dengan membran sel, menyebabkan
perubahan isi, elastisitas, dan permeabilitas sel. Sel darah merah pada kondisi
tersebut dikenali sebagai sel darah merah yang rusak dan akan dihancurkan oleh
sistem retikulo-endotelial (lien, hepar dan sumsum tulang) proses hemolitik.
Meskipun gen G6PD terdapat pada semua jaringan tubuh, tetapi efek defisiensi
dalam eritrosit pengaruhnya sangat besar karena enzim G6PD diperlukan dalam
menghasilkan energi untuk mempertahan umur eritrosit, membawa oksigen,
regulasi transport ion dan air kedalam dan keluar sel, membantu pembuangan
karbondioksida dan proton yang terbentuk pada metabolisme jaringan. Karena
tidak ada mitokondria di dalam eritrosit maka oksidasi G6PD hanya bersumber
dari NADPH, bila kadar enzim G6PD menurun, eritrosit mengalami kekurangan
energi dan perubahan bentuk yang memudahkan mengalami lisis bila ada stres
oksidan.
18
e. Manifestasi Klinis dan Laboratoris
1. Manifestasi Klinis
Pada umumnya, individu dengan defisiensi enzim G6PD yang diturunkan,
tidak mengalami hemolisis dan sering tanpa anemia (serta tanpa gejala), namun
hal tersebut dapat timbul bila penderita terpapar bahan eksogen yang potensial
menimbulkan kerusakan oksidatif. Beberapa penyakit yang diketahui
berhubungan dengan defisiensi G6PD adalah : hiperbilirubinemia (Kern
Ikterik), hemolisis intravaskuler, favism, sindroma hepatitis hemolisis, anemia
hemolisis kronik.
Gejala klinik timbul 1-3 hari setelah terpapar faktor pencetus, berupa
anemia hemolitik akut dengan gambaran khas berupa rewel, iritabel/tampak
rewel, letargi, suhu meningkat > 380 C, mual, nyeri abdominal, diare, anemia,
ikterik dan kelainan pada urine (hemoglobinuria). Pada pemeriksaan fisik
didapat kepucatan yang bervariasi dan takikardi, lien dan hepar biasanya
membesar. Pada kasus berat terjadi syok hipovolemik dan gagal jantung.
2. Gambaran Laboratoris
Gambaran laboratorium didapatkan anemia normositik normokromik
bervariasi dari ringan sampai berat, gambaran menyolok anisositosis,
poikilositosis dan jumlah retikulosit meningkat > 30%. Dengan pewarnaan
metil violet tampak Heinz bodies. Jumlah lekosit biasanya meningkat dengan
dominan granulosit, bilirubin indirek meningkat tetapi enzim hepar dalam batas
normal.
Anemia hemolitik umumnya dicetuskan oleh paparan berupa obat-obatan
(seperti sulfonamide, primakuin, kloramfenikol, kloroquin, asam nalidiksat,
quinakrin, nitrofurantorin, salisilat, dapson, fenasetin, asitanisid, dan antipirin),
diet kacang coklat (victa fava), bahan kimia (Naphthalene), infeksi
pneumokokus, hepatitis dan penyakit ketoasidosis, yang pada prinsipnya
menyebabkan penurunan kadar glutation, dimana kadar tersebut sudah rendah
akibat defisiensi G6PD itu sendiri. Di daerah endemis malaria di Afrika dan
Asia Tenggara hemolisis sering diinduksi pemberian primakuin.
19
Saat ini penunjang diagnostik yang banyak digunakan dalam membantu
menegakkan diagnosis defisiensi G6PD adalah tes Heinz Body dan tesstabilitas
GSH. Uji tapis dapat dilakukan dengan test methylene-blue dengan perubahan
warna saat reduksi methemoglobin atau dengan flouresensi NADPH. Tes
diagnostik defisiensi G6PD berdasarkan aktifitas enzim dapat dideteksi dengan
pemeriksaan laboratorium sederhana. melakukan skrining dengan metode the
formazan-ring/Hironos methode.
f. Bahan-bahan Kimia Eksogen Yang Dapat Berperan Sebagai Pencetus
Bahan-bahan yang dilaporkan pernah menginduksi terjadinya Anemia
Hemolitik pada subyek dengan defisiensi G6PD antara lain (tabel 1):
20
II. ANEMIA
Anemia adalah berkurangnya hingga di bawah nilai normal jumlah SDM,
kuantitas hemoglobin, dan volume packed red blood cells (hematokrit) per
100 ml darah. Anemia menyebabkan berkurangnya jumlah sel darah merah
atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga darah tidak dapat
mengangkut oksigen dalam jumlah sesuai yang diperlukan tubuh. Anemia
bukan merupakan diagnosa akhir dari suatu penyakit akan tetapi selalu
merupakan salah satu gejala dari sesuatu penyakit dasar.
Klasifikasi anemia berdasarkan morfologi yaitu :
1. Anemia normositik normokrom, di mana ukuran dan bentuk sel-
sel darah merah normal serta mengandung hemoglobin dalam
jumlah normal (MCV dan MCHC normal atau normal rendah)
tetapi individu menderita anemia. Penyebab anemia jenis ini adalah
kehilangan darah akut, hemolisis, penyakit kronik termasuk
infeksi, gangguan endokrin, gangguan ginjal, kegagalan sumsum
dan penyakit-penyakit infiltratif metastatik pada sumsum tulang.
2. Anemia makrositik normokrom, ukuran sel-sel darah merah
lebih besar dari normal tetapi normokrom karena konsentrasi
hemoglobinnya normal (MCV meningkat; MCHC normal). Hal ini
diakibatkan oleh gangguan atau terhentinya sintesis asam nukleat
DNA seperti yang ditemukan pada defisiensi B12 dan atau asam
folat.
3. Anemia mikrositik hipokrom, Mikrositik berarti kecil, hipokrom
berarti mengandung hemoglobin dalam jumlah yang kurang dari
normal (MCV rendah; MCHC rendah). Hal ini umumnya
menggambarkan insufisiensi sintesis hem (besi), seperti pada
anemia defisiensi besi, keadaan sideroblastik dan kehilangan darah
kronik, atau gangguan sintesis globin, seperti pada talasemia
(penyakit hemoglobin abnormal congenital).
Klasifikasi anemia berdasarkan etiologinya adalah :
21
1. Anemia pasca perdarahan, akibat perdarahan massif seperti
kecelakaan, luka operasi persalinan dan sebagainya.
2. Anemia hemolitik, akibat penghancuran eritrosit yang berlebihan.
Dibedakan menjadi 2 faktor :
1) Faktor intrasel, Misal talassemia, hemoglobinopatia
(talassemia HbE, sickle cell anemia), sferositos congenital,
defisiensi enzim eritrosit (G-6PD, piruvat kinase, glutation
reduktase).
2) Faktor ekstrasel, misal intoksikasi, infeksi (malaria),
imunologis (inkompabilitas golongan darah, reaksi
hemolitik pada transfusi darah).
3. Anemia defisiensi, karena kekurangan faktor pematangan eritrosit
(besi, asam folat, vitamin B12, protein, piridoksin, eritropoetin, dan
sebagainya).
4. Anemia aplastik, disebabkan terhentinya pembuatan sel darah
oleh sumsum tulang.
III. INFEKSI SALURAN KEMIH
a. Definisi
Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di sepanjang jalan saluran
kemih, termasuk ginjal itu sendiri akibat proliferasi suatu mikroorganisme.
Untuk menyatakan adanya infeksi saluran kemih harus ditemukan bakteri di
dalam urin. Suatu infeksi dapat dikatakan jika terdapat 100.000 atau lebih
bakteri/ml urin, namun jika hanya terdapat 10.000 atau kurang bakteri/ml urin,
hal itu menunjukkan bahwa adanya kontaminasi bakteri.Bakteriuria bermakna
yang disertai gejala pada saluran kemih disebut bakteriuria bergejala. Sedangkan
yang tanpa gejala disebut bakteriuria tanpa gejala.
b. Epidemiologi
Infeksi saluran kemih dapat terjadi pada 5% anak perempuan dan 1-2% anak
laki-laki. Kejadian infeksi saluran kemih pada bayi baru lahir dengan berat lahir
22
rendah mencapai 10-100 kali lebih besar disbanding bayi dengan berat lahir
normal (0,1-1%). Sebelum usia 1 tahun, infeksi saluran kemih lebih banyak
terjadi pada anak laki-laki. Sedangkan setelahnya, sebagian besar infeksi saluran
kemih terjadi pada anak perempuan. Misalnya pada anak usia pra sekolah di mana
infeksi saluran kemih pada perempuan mencapai 0,8%, sementara pada laki-laki
hanya 0,2% dan rasio ini terus meningkat sehingga di usia sekolah, kejadian
infeksi saluran kemih pada anak perempuan 30 kali lebih besar dibanding pada
anak laki-laki. Pada anak laki-laki yang disunat, risiko infeksi saluran kemih
menurun hingga menjadi 1/5-1/20 dari anak laki-laki yang tidak disunat. Pada usia
2 bulan 2 tahun, 5% anak dengan infeksi saluran kemih mengalami demam
tanpa sumber infeksi dari riwayat dan pemeriksaan fisik. Sebagian besar infeksi
saluran kemih dengan gejala tunggal demam ini terjadi pada anak perempuan.
Faktor resiko yang berpengaruh terhadap infeksi saluran kemih:
- Panjang urethra. Wanita mempunyai urethra yang lebih pendek
dibandingkan pria sehingga lebih mudah
- Faktor usia. Orang tua lebih mudah terkena dibanndingkan dengan usia
yang lebih muda.
- Wanita hamil lebih mudah terkena oenyakit ini karena penaruh hormonal
ketika kehamilan yang menyebabkan perubahan pada fungsi ginjal
dibandingkan sebelum kehamilan.
- Faktor hormonal seperti menopause. Wanita pada masa menopause lebih
rentan terkena karena selaput mukosa yang tergantung pada esterogen
yang dapat berfungsi sebagai pelindung.
- Gangguan pada anatomi dan fisiologis urin. Sifat urin yang asam dapat
menjadi antibakteri alami tetapi apabila terjadi gangguan dapat
menyebabkan menurunnya pertahanan terhadap kontaminasi bakteri.
- Penderita diabetes, orang yang menderita cedera korda spinalis, atau
menggunakan kateter dapat mengalami peningkatan resiko infeksi.
Sebagian besar infeksi saluran kemih tidak dihubungkan dengan faktor risiko
tertentu. Namun pada infeksi saluran kemih berulang, perlu dipikirkan
kemungkinan faktor risiko seperti :
23
Kelainan fungsi atau kelainan anatomi saluran kemih
Gangguan pengosongan kandung kemih (incomplete bladder emptying)
Konstipasi
Operasi saluran kemih atau instrumentasi lainnya terhadap saluran kemih
sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kontaminasi dari luar.
Kekebalan tubuh yang rendah
c. Etiologi
Bakteri yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih adalah jenis
bakteri aerob. Pada kondisi normal, saluran kemih tidak dihuni oleh bakteri atau
mikroba lain, tetapi uretra bagian bawah terutama pada wanita dapat dihuni oleh
bakteri yang jumlahnya makin berkurang pada bagian yang mendekati kandung
kemih. Infeksi saluran kemih sebagian disebabkan oleh bakteri, namun tidak
tertutup kemungkinan infeksi dapat terjadi karena jamur dan virus. Infeksi oleh
bakteri gram positif lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan infeksi gram
negatif.
Lemahnya pertahanan tubuh telah menyebabkan bakteri dari vagina,
perineum (daerah sekitar vagina), rektum (dubur) atau dari pasangan (akibat
hubungan seksual), masuk ke dalam saluran kemih. Bakteri itu kemudian
berkembang biak di saluran kemih sampai ke kandung kemih, bahkan bisa sampai
ke ginjal.
Bakteri infeksi saluran kemih dapat disebabkan oleh bakteri-bakteri di
bawah ini :
A. Kelompok anterobacteriaceae seperti :
1. Escherichia coli
2. Klebsiella pneumoniae
3. Enterobacter aerogenes
4. Proteus
5. Providencia
6. Citrobacter
B. Pseudomonas aeruginosa
24
C. Acinetobacter
D. Enterokokus faecalis
E. Stafilokokus sarophyticus
d. Gambaran Klinis
Gejala gejala dari infeksi saluran kemih sering meliputi:
Gejala yang terlihat, sering timbulnya dorongan untuk berkemih
Rasa terbakar dan perih pada saat berkemih
Seringnya berkemih, namun urinnya dalam jumlah sedikit (oliguria)
Adanya sel darah merah pada urin (hematuria)
Urin berwarna gelap dan keruh, serta adanya bau yang menyengat dari
urin
Ketidaknyamanan pada daerah pelvis renalis
Rasa sakit pada daerah di atas pubis
Perasaan tertekan pada perut bagian bawah
Demam
Anak anak yang berusia di bawah lima tahun menunjukkan gejala yang
nyata, seperti lemah, susah makan, muntah, dan adanya rasa sakit pada
saat berkemih.
Pada wanita yang lebih tua juga menunjukkan gejala yang serupa, yaiu
kelelahan, hilangnya kekuatan, demam
Sering berkemih pada malam hari
Pada anak anak, mengompol juga menandakan gejala adanya infeksi saluran
kemih.
Gejala- gejala dari cystitis di atas disebabkan karena beberapa kondisi:
Penyakit seksual menular, misalnya gonorrhoea dan chlamydia
Terinfeksi bakteri, seperti E-coli
Jamur (Candida)
Terjadinya inflamasi pada uretra (uretritis)
Wanita atau gadis yang tidak menjaga kebersihan bagian kewanitaannya
25
Wanita hamil
Inflamasi pada kelerjar prostat, tau dikenal dengan prostatitis
Seseorang yang menggunakan cateter
Anak muda yang melakukan hubungan seks bebas
Jika infeksi dibiarkan saja, infeksi akan meluas dari kandung kemih hingga ginjal.
Gejala gejala dari adanya infeksi pada ginjal berkaitan dengan gejala pada
cystitis, yaitu demam, kedinginan, rasa nyeri pada punggung, mual, dan muntah.
Cystitis dan infeksi ginjal termasuk dalam infeksi saluran kemih.
Tidak setiap orang dengan infeksi saluran kemih dapat dilihat tanda tanda
dan gejalanya, namun umumnya terlihat beberapa gejala, meliputi:
Desakan yang kuat untuk berkemih
Rasa terbakar pada saat berkemih
Frekuensi berkemih yang sering dengan jumlah urin yang sedikit (oliguria)
Adanya darah pada urin (hematuria)
Setiap tipe dari infeksi saluran kemih memilki tanda tanda dan gejala yang
spesifik, tergantung bagian saluran kemih yang terkena infeksi:
1. Pyelonephritis akut. Pada tipe ini, infeksi pada ginjal mungkin terjadi
setelah meluasnya infeksi yang terjadi pada kandung kemih. Infeksi pada
ginjal dapat menyebabkan rasa salit pada punggung atas dan panggul,
demam tinggi, gemetar akibat kedinginan, serta mual atau muntah.
2. Cystitis. Inflamasi atau infeksi pada kandung kemih dapat dapat
menyebabkan rasa tertekan pada pelvis, ketidaknyamanan pada perut
bagian bawah, rasa sakit pada saat urinasi, dan bau yang mnyengat dari
urin.
3. Uretritis. Inflamasi atau infeksi pada uretra menimbulkan rasa terbakar
pada saat urinasi. Pada pria, uretritis dapat menyebabkan gangguan pada
penis.
Gejala infeksi saluran kemih pada anak anak, meliputi:
1. Diarrhea
26
2. Menangis tanpa henti yang tidak dapat dihentikan dengan usaha tertentu
(misalnya: pemberian makan, dan menggendong)
3. Kehilangan nafsu makan
4. Demam
5. Mual dan muntah
Untuk anak anak yang lebih dewasa, gejala yang ditunjukkan berupa:
1. rasa sakit pada panggul dan punggung bagian bawah (dengan infeksi pada
ginjal)
2. seringnya berkemih
3. ketidakmampuan memprodukasi urin dalam jumlah yang normal, dengan
kata lain, urin berjumlah sedikit (oliguria)
4. tidak dapat mengontrol pengeluaran kandung kemih dan isi perut
5. rasa sakit pada perut dan daerah pelvis
6. rasa sakit pada saat berkemih (dysuria)
7. urin berwarna keruh dan memilki bau menyengat
Gejala pada infeksi saluran kemih ringan (misalnya: cystitis, uretritis) pada orang
dewasa, meliputi:
1. rasa sakit pada punggung
2. adanya darah pada urin (hematuria)
3. adanya protein pada urin (proteinuria)
4. urin yang keruh
5. ketidakmampuan berkemih meskipun tidak atau adanya urin yang keluar
6. demam
7. dorongan untuk berkemih pada malam hari (nokturia)
8. tidak nafsu makan
9. lemah dan lesu (malaise)
10. rasa sakit pada saat berkemih (dysuria)
11. rasa sakit di atas bagian daerah pubis (pada wanita)
12. rasa tidak nyaman pada daerah rectum (pada pria)
Gejala yang mengindikasikan infeksi saluran kemih lebih berat (misalnya:
pyelonephritis) pada orang dewasa, meliputi:
27
1. kedinginan
2. demam tinggi dan gemetar
3. mual
4. muntah (emesis)
5. rasa sakit di bawah rusuk
6. rasa sakit pada daerah sekitar abdomen
Merokok, ansietas, minum kopi terlalu banyak, alergi makanan atau sindrom
pramenstruasi bisa menyebabkan gejala mirip infeksi saluran kemih. Gejala
infeksi saluran kemih pada bayi dan anak kecil. Infeksi saluran kemih pada bayi
dan anak usia belum sekolah memilki kecendrungan lebih serius dibandingkan
apabila terjadi pada wanita muda, hal ini disebabkan karena memiliki ginjal dan
saluran kemih yang lebih rentan terhadap infeksi.
Gejala pada bayi dan anak kecil yang sering terjadi, meliputi:
1. Kecendrungan terjadi demam tinggi yang tidak diketahui sebabnya,
khususnya jika dikaitkan dengan tanda tanda bayi yang lapar dan sakit,
misalnya: letih dan lesu.
2. Rasa sakit dan bau urin yang tidak enak. ( orang tua umumnya tidak dapat
mengidentifikasikan infeksi saluran kemih hanya dengan mencium urin
bayinya. Oleh karena itu pemeriksaan medis diperlukan).
3. Urin yang keruh. (jika urinnya jernih, hal ini hanya mirip dengan penyakit,
walaupun tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa bayi tersebut bebas
dari Infeksi saluran kemih).
4. rasa sakit pada bagian abdomen dan punggung.
5. muntah dan sakit pada daerah abdomen (pada bayi)
6. jaundice (kulit yang kuning dan mata yang putih) pada bayi, khususnya
bayi yang berusia setlah delapan hari.
28
BAB III
ANALISIS KASUS
Seorang anak laki -laki berusia 12 tahun datang dengan keluhan utama
batuk lama. Sejak 1 bulan SMRS anak mengalami batuk, batuk berdahak,
dahak berwarna putih encer. Selain batuk penderita juga mengalami demam,
demam hilang timbul dan dan biasanya lebih tinggi pada malam hari, berkeringat
dimalam hari (+), Penderita juga mengalami nafsu makan menurun. Terkadang
penderita mengalami mual dan muntah isi apa yang dimakan banyaknya gelas
belimbing tiap muntah.
2 minggu SMRS penderita masih batuk. Penderita masih tidak bisa berjalan,
demam (+) hilang timbul. Penderita lalu dibawa berobat ke rumah sakit DKT, dan
dilakukan pemeriksaan rontgen paru, dikatakan oleh dokter sakit paru- paru kotor.
Dari pemeriksaan fisik didapat status gizi anak gizi kurang, conjungtiva
anemis, adanya pembesaran KGB di regio coli dextra dan sinistra multiple, dan
akral tampak pucat. Dari pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya
leukositosis, peningkatan LED, dan, anemia, sedangkan dari hasil ronsen paru
tampak adanya infiltrate.
Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang
diatas maka dilakukan sistem scoring TB, didapatkan hasil scoring anak yaitu 5 (
6). Anak tersebut masih meragukan untuk memenuhi criteria positif TB
sehingga tidak diberikan OAT terlebih dahulu. Pada penderita ini diberikan
pereda batuk untuk sementara yaitu glyseryl guaiacolate (GG) yang bertujuan
untuk meningkatkan pengeluaran secret di traktus respiratorius dengan
menurunkan perlekatan dan tegangan permukaannya, maka dari itu GG dapat
menghilangkan mucus yang kental dan menurunkan frekuensinya.
Selain batuk, pasien juga mengalami demam lebih dari dua minggu
(demam lama), kemungkinan penyebab demam lama pada penderita ini adalah TB
paru karena berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik menyokong ke arah TB
paru. Penegakan diagnosis pasti TB pada kasus ini menunggu hasil reaksi local
dari tes BCG, sehingga dapat dilakukkan evaluasi ulang system scoring TB, jika
hasil BCG tes 5 mm dan evaluasi system scoring menunjukkan hasil 6, maka
29
penderita ini diberikan terapi OAT. Prinsip dasar terapi TB minimal 3 macam
obat dan diberikan dalam waktu 6 bulan, OAT pada anak diberikan setiap hari,
baik pada tahap intensif maupun tahap lanjutan.
Pada penderita ini diberikan terapi antibiotic berupa Ampisilin dan gentamisin
sampai hasil BCG tes menunjukkan anak positif TB. dosis ampisilin 3 x 600 mg,
dan gentamisin 2 x 40 mg. Status gizi anak ini tergolong gizi kurang, prinsip diet
untuk anak dengan berat badan kurang adalah tinggi kalori dan protein. Pemberian
makanan sesuai kebutuhan untuk mengejar kekurangan berat badan dan tinggi
badan, untuk mencegah kerusakan jaringan lebih kanjut dan meningkatkan daya
tahan tubuh. Selain batuk dan demam, sejak 1 bulan SMRS penderita jatuh
terduduk dari tembok sekolah setinggi 2 meter, dan sekarang pasien tidak bisa
berjalan. Dari hasil rontgen pada tanggal 6 september 2013 di RS DKT ditemukan
adanya fraktur os Coxae dextra. Penatalaksanaan fraktur os coxae perlu tindakan
bedah maka dari itu pasien di konsulkan ke bedah orthopedi.
.
30
DAFTAR PUSTAKA
1. Fisher RG, Boyce TG. A problem-oriented approach. Dalam: Moffets
Pediatric infectious diseases. Edisi ke-4. New York: Lippincott William &
Wilkins;2005.
2. Behrman, R. E., Kliegman, R.M., Jenson, H. B.Nelson Textbook of
Pediatrics 17
th
Edition. Philadelphia: Saunders, 2004.
3. Soedarmo, Sumarmo P. Poorwo. Herry Garna, dkk.Demam.Dalam: Buku
Ajar Infeksi & Pediatri Tropis. Edisi Kedua. Bagian Ilmu Kesehatan Anak
FKUI. Badan Penerbit IDAI, Jakarta. 2010; Hal 21 44
4. Andriole VT (editor) : Lyme disease and other sperochetal disease, Rev
Infect Dis 1989; (Suppl 6) : S1433.
5. Britigan BE et al : Gonococal infection: A model molecular pathogenesis,
N Engl J. Med 1985 ; 312 :1682.
6. Hook EW III, Holmes KK: Gonococal infection, An Intern Med, 1985;
102; 229.
7. Jawetz E et al (eds) : Medical MIcrobiology, 19
th
ed , Appleton and Lange,
Norwalk, Connecticut/San Mateo Californiam 1991.
8. Jawetz. E , Melnick & Adelberg : Mikrobiologi Kedokteran, edisi 20 EGC
Jakarta 1996
9. Joklik W.K et.al (eds) : Zinserr Microbiology, 19
th
ed, Appleton Century-
Crofts, New York, 1988
10. Gupte S : Mikrobiologi dasar. Edisi ketiga, Binarupa aksara Jakarta, 1990.
11. Morse SA: Chancroid and Haemophylus ducreyi, Clin Micribiol Rev
1989; 2; 137.
12. Pelzar Michael: Dasar-dasar Mikrobiologi, jilid 2 UI-Press Jakarta 1988.
Anda mungkin juga menyukai
- Case Diare KronikDokumen30 halamanCase Diare KronikAnggita Nur AzizaBelum ada peringkat
- Case 1 Diare Cair Akut Dehidrasi R-SDokumen48 halamanCase 1 Diare Cair Akut Dehidrasi R-SsteBelum ada peringkat
- Laporan Kasus 1 Morbili - Dr. Hj. Roito Elmina G.H, Sp. ADokumen26 halamanLaporan Kasus 1 Morbili - Dr. Hj. Roito Elmina G.H, Sp. AFikar AxlrosesBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Sindrom NefrotikDokumen26 halamanLaporan Kasus Sindrom NefrotikFikar Axlroses50% (8)
- CRS Meningitis TuberkulosisDokumen50 halamanCRS Meningitis TuberkulosisRiriBelum ada peringkat
- Laporan KasusDokumen35 halamanLaporan KasusNingsih ArdiningsihBelum ada peringkat
- BAB IIDokumen23 halamanBAB IIIsma LiaBelum ada peringkat
- Laporan Jaga Dr. Fajar, Sp.a - Sarah Gustia - FixDokumen20 halamanLaporan Jaga Dr. Fajar, Sp.a - Sarah Gustia - FixSarahGustiaWoromboniBelum ada peringkat
- LAPJAG Tia 4 - Dr. Jumnalis, SPDokumen28 halamanLAPJAG Tia 4 - Dr. Jumnalis, SPsilvikatnBelum ada peringkat
- Koas Anak CaseDokumen37 halamanKoas Anak CaseDhinie NovianiBelum ada peringkat
- Lapkas 1 Disentri AmubaDokumen38 halamanLapkas 1 Disentri AmubaFarah Sonya AnastasyaBelum ada peringkat
- Case GEA DG Dehidrasi Ringan-SedangDokumen17 halamanCase GEA DG Dehidrasi Ringan-SedangMila DamayantiBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Glomerulonefritis AkutDokumen17 halamanLaporan Kasus Glomerulonefritis Akutyessi apriance100% (3)
- Lapsus Isip DCADokumen60 halamanLapsus Isip DCAYennySuryaniBelum ada peringkat
- Kejang Demam KompleksDokumen81 halamanKejang Demam KomplekstianurulhBelum ada peringkat
- 5260 - Case Report MalindaDokumen82 halaman5260 - Case Report MalindalailchodriyahBelum ada peringkat
- Lapkas - Diare AkutDokumen44 halamanLapkas - Diare AkutAsyha KantifaBelum ada peringkat
- CBD HSPDokumen58 halamanCBD HSPdimdimdimaaar100% (1)
- Status Ujian FachryDokumen6 halamanStatus Ujian FachryFachry RahmanBelum ada peringkat
- Refka DiareDokumen43 halamanRefka DiareStephani PanggaloBelum ada peringkat
- Case KDK FixDokumen37 halamanCase KDK FixdiditamariBelum ada peringkat
- Diare Akut AnakDokumen48 halamanDiare Akut AnakmelisaarendraBelum ada peringkat
- 999Dokumen54 halaman999Pervinder SinghBelum ada peringkat
- Rhesus TBDokumen44 halamanRhesus TBSisca Dwi AgustinaBelum ada peringkat
- Spondilitis TBDokumen46 halamanSpondilitis TBdr_dinoBelum ada peringkat
- Laporan Kasus MarasmusDokumen23 halamanLaporan Kasus MarasmusmynaBelum ada peringkat
- ThifoidDokumen17 halamanThifoidNurul AzizahBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Besar Rio N. PratamaDokumen48 halamanLaporan Kasus Besar Rio N. PratamaHielmy Auliya HasyimBelum ada peringkat
- Presentasi Kasus AnakDokumen25 halamanPresentasi Kasus AnaktsruliantyBelum ada peringkat
- Borang PKM Ukrio RajinDokumen72 halamanBorang PKM Ukrio RajinVebi AdriasBelum ada peringkat
- Makalah Lapsus DiareDokumen29 halamanMakalah Lapsus DiareFery Rahmatussafri GranatBelum ada peringkat
- Refkas Anis Zakky ISKDokumen44 halamanRefkas Anis Zakky ISKRaymond Andre MuzettaBelum ada peringkat
- Diare Dengan Dehidrasi Ringan SedangDokumen21 halamanDiare Dengan Dehidrasi Ringan SedangAprilia JamadiBelum ada peringkat
- Disentri Presentasi FixDokumen38 halamanDisentri Presentasi FixDeffa Trisetia JulianBelum ada peringkat
- Case Report 1 Nimas CPSADokumen48 halamanCase Report 1 Nimas CPSAdhityarzBelum ada peringkat
- Refkas CitraDokumen42 halamanRefkas CitraGalang Setia AdiBelum ada peringkat
- MarasmusDokumen35 halamanMarasmusGregorius AbramBelum ada peringkat
- Dias DadrsDokumen32 halamanDias DadrsMaylinda PutriBelum ada peringkat
- DADRSDokumen52 halamanDADRSannisankhBelum ada peringkat
- Lapsus Disentri AmoebaDokumen22 halamanLapsus Disentri AmoebaDiphda SatriaBelum ada peringkat
- Morning Report Dokter Muda Unmul Stase Ilmu Kesehatan AnakDokumen36 halamanMorning Report Dokter Muda Unmul Stase Ilmu Kesehatan AnakunmuldoctorBelum ada peringkat
- Refleksi Kasus Sindrom NefrotikDokumen19 halamanRefleksi Kasus Sindrom NefrotikAnonymous xtDUXVyJBelum ada peringkat
- Presentasi Demam TifoidDokumen73 halamanPresentasi Demam TifoidKesuma Larasati100% (1)
- Lapkas TFDokumen22 halamanLapkas TFafridaaynBelum ada peringkat
- LPORAN KASUS DB Victoria Goretty FixDokumen25 halamanLPORAN KASUS DB Victoria Goretty FixEka SetiyaniBelum ada peringkat
- Kasus Sindrom NefrotikDokumen44 halamanKasus Sindrom Nefrotikmiracle_shop_2Belum ada peringkat
- Responsi Demam Berdarah Dengue VIVIANDokumen32 halamanResponsi Demam Berdarah Dengue VIVIANVivian O VashtiBelum ada peringkat
- Mini Cex-Asma BronkialDokumen15 halamanMini Cex-Asma Bronkialcty_luphdearBelum ada peringkat
- Ny Ew, CKD, Cap HT RDokumen43 halamanNy Ew, CKD, Cap HT RRahmanindya DPBelum ada peringkat
- Kasus Igd VomitusDokumen9 halamanKasus Igd VomitusVania OktavianiBelum ada peringkat
- CBD AnemiaDokumen33 halamanCBD AnemiaMasayu Intan ElfianiBelum ada peringkat
- Laporan Kasus BPDokumen55 halamanLaporan Kasus BPMuchammad Karunia Fadillah100% (1)
- Laporan Kasus CMLDokumen35 halamanLaporan Kasus CMLFahrenheit FaqodBelum ada peringkat
- Askep M2 Neti AstariDokumen14 halamanAskep M2 Neti AstariNETI ASTARIBelum ada peringkat
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatDari EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Buku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Dari EverandBuku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (4)
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Program Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaDari EverandProgram Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9)
- Hunja yang Misterius: Bagaimana Wanita Hamil di Usia 80 di Negeri Misteri Ini?Dari EverandHunja yang Misterius: Bagaimana Wanita Hamil di Usia 80 di Negeri Misteri Ini?Belum ada peringkat
- Tumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Dari EverandTumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Belum ada peringkat
- Surat Pernyataan Untuk SIPDokumen2 halamanSurat Pernyataan Untuk SIPDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Brachial Palsy & Trigger FingerDokumen22 halamanBrachial Palsy & Trigger FingerDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Anatomi Thorax FebriDokumen27 halamanAnatomi Thorax FebriDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Surat Perintah TugasDokumen3 halamanSurat Perintah TugasDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Penyuluhan Asam UratDokumen8 halamanPenyuluhan Asam UratDinar Kartika Hapsari50% (2)
- Laporan Kasus Gizi BurukDokumen30 halamanLaporan Kasus Gizi BurukDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- PneumomikosisDokumen19 halamanPneumomikosisDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Kejang Demam KompleksDokumen28 halamanKejang Demam KompleksDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Puasa SehatDokumen17 halamanPuasa SehatDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Dermatomikosis SuperfisialisDokumen13 halamanDermatomikosis SuperfisialisDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat
- Konsensus IDAI Kejang Demam 2016Dokumen23 halamanKonsensus IDAI Kejang Demam 2016Valencia JaneBelum ada peringkat
- Hub g6pd DGN MalariaDokumen85 halamanHub g6pd DGN MalariaDinar Kartika HapsariBelum ada peringkat