AD Pirous
Diunggah oleh
roufchasbullahHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
AD Pirous
Diunggah oleh
roufchasbullahHak Cipta:
Format Tersedia
A. D.
PIROUS
This isnt dawah. Im not campaigning for religion. I am making art. What you see here, all these paintings, these are my spiritual notes. (A. D. Pirous)
Di sebuah ruang kerja yang besar dan bersih, dari arah samping dan dengan sudut pandang menjauh, tampak Abdul Djalil Pirous menekuri meja di hadapannya. Sementara di belakangnya berdiri rak kayu bercat putih serta rak kaca berwarna cokelat. Ke-dua rak dengan ukuran-ukuran kolom yang lebar ini sanggup menampung penuh buku-buku, katalog-katalog pameran, piringan hitam dan arsip-arsip kerja. Semuanya saling berhimpitan secara teratur dan rapih. Suasana di ruang itu terasa hening dan khusyuk. Pirous sendirian di ruang itu. Mengenakan kemeja putih dan bretel yang selalu menjadi tampilan khasnya, ia seperti membaca, merenung atau mungkin sedang menuliskan catatan. Ia seakan-akan mengasingkan diri atau berada dalam keadaan keberantaraan (inbetweeness). Pengasingan mungkin merupakan syarat yang mengkarakterisasikan intelektual sebagai seseorang yang berdiri sebagai figur marjinal di luar hak istimewa, menjauh dari kekuasaan. Intelektual atau cendekiawan di pengasingan tidak menanggapi logika konvensional, tapi lebih menyikapi keberanian dan perubahan. Karena itu, ketimbang seniman, sosok Pirous dalam foto yang diambil pada 2001 di dalam ruangan itu cenderung mengesankan seorang cendekiawan yang tengah berada di puncak kematangan berpikir, bersikap dan memberi pengaruh. Gestur, suasana maupun isi ruang, komposisi dan sudut pandang yang direkam oleh foto itu memberi kesan tersendiri. Foto tersebut menginspirasi saya untuk merepresentasikan profil Pirous dalam pameran Jau Timu: 80 Tahun A. D. Pirous ini.
Mazhab Pirousi yang Bersegi-segi Semenjak pertengahan 1950-an, sebagai pribadi yang mengalami, mengetahui dan mendalami setiap peristiwa seni, Pirous tidak hanya terlibat di dalam gerak sejarah seni rupa. Ia bahkan menyumbang satu watak yang turut memperkaya identitas sejarah seni rupa Indonesia. Sumbangan itu berupa kecenderungan estetik yang khas, yang kemudian dikenal dengan nama seni lukis kaligrafi Indonesia. Pengaruhnya di ranah ini membuatnya memiliki banyak pengikut. Sebenarnya lukisan kaligrafi Pirous menyimpang dari tradisi kaligrafi murni. Ia membebaskan aksara Arab dari kaidah khattiyah-nya (misalnya tsulutsi, kufi, diwani, naskhi, farisi, dan sebagainya), meskipun dalam beberapa hal, masih memperlihatkan akar bentuknya. Pakar kaligrafi Islam Indonesia Sirodjuddin A.R. (2003) mengatakan bahwa kaligrafi Pirous bergerak seakan-akan tanpa mazhab. Menuruti teladan penamaan mazhab seperti khat Yaquti hasil kreasi Yaqut al Mustasini, khat Rayhani dari Ali ibnu Ubaidillah Al-Rayhan, khat Abbasi oleh Shah Abbas, khat Ismaili dari Ismail al Syajari, khat Gazlani oleh Gazlan Bek dan khat Nasiri dari Nasiruddin, Sirodjuddin pun menamakan langgam kaligrafi dalam lukisan Pirous dengan istilah menarik: mazhab Pirousi atau mazhab Djalili dari kata Pirous atau Djalil. Tak hanya menyimpang dari kaidah atau ihwal keberhasilan Pirous dalam menegakkan mazhabnya sendiri. Beberapa waktu belakangan ini bahkan Pirous menyerukan dan terang-terangan melakukan desakralisasi terhadap seni lukis kaligrafi. Pirous keluar dari jebakan dogmatis yang hanya akan menggelincirkan seorang pelukis kaligrafi melulu berkutat pada persoalan khattiyah. Dalam pengamatan Pirous kemudian, secara psikologis para pelukis kaligrafi Indonesia masih terbelenggu, sehingga mengakibatkan terjadinya sakralisasi khat-khat yang dipetik dari Al-Quran ke atas kanvas. Pelukis kaligrafi, saran Pirous,harus bisa keluar dari persoalan tersebut untuk tidak lagi semata-mata menyajikan sesuatu yang sakral, tetapi mampu menjawab dan menelaah problematika sosial melalui lukisan kaligrafinya. Di mata Pirous, setiap jenis huruf, baik itu roman atau hijaiyah arab, melalui penanganan khusus dari sang pelukis, tetap berpeluang luas memunculkan persoalan baru.
Tidak sedikit kaligrafi dalam karya-karya awal Pirous yang sulit dibaca secara eksplisit. Khat-khat kaligrafi, efek bongkahan, retakan, tekstur, warna yang terdapat di dalam lukisan membangun kesan estetik. Dalam rentang proses yang cukup lama, akhirnya Pirous sampai pada kesadaran bahwa apabila huruf-huruf itu adalah media komunikasi, maka aspek keterbacaan, kelugasan makna dan pesan, harus tersampaikan. Estetika hanyalah satu aspek saja dari lukisan kaligrafi, ujar Pirous pada masa ini, adapun pesan yang diterima oleh manusia merupakan aspek yang jauh lebih penting. Kendati demikian, Pirous mengamini bahwa pesan yang disisipkan melalui khatkhat tersebut tidak dimaksudkan untuk mendahului makna pewahyuan yang sudah ada sebelumnya. Artinya, ketika Pirous mengutip sepenggal ayat Al-Quran di atas kanvas, ia tidak semata-mata mengerjakannya untuk kepentingan khutbah maupun dakwah Islam. Pada sebuah peristiwa penting yang ia alami atau ketika Pirous sedang menghayati suatu gejolak kehidupan sosial di sekitarnya, responsinya terhadap peristiwa sering ia nyatakan melalui ayat-ayat suci, syairsyair sufistik, pepatah bijak leluhur hingga puisi modern. Semua itu, yang kemudian ia lukiskan ke atas kanvas, adalah catatan-catatan spiritual (berkerohanian) yang pertama-tama ditujukan untuk pribadinya sebelum kemudian ia siarkan ke publik umum (pameran seni, misalnya). Sesungguhnya Pirous tidak pernah menginginkan munculnya persepsi dihadapan khalayak bahwa lukisannya adalah instrumen penginsyafan atau propaganda kebenaran Ilahi yang klise. Bagi Pirous, lukisan adalah ruang dialognya dengan Sang Khalik dan ciptaan-Nya, karena itu bersifat personal. Seperti yang ia sudah nyatakan sendiri melalui kutipan di atas bahwa alih-alih berdakwah, lukisan di mata Pirous adalah catatan spiritual. Indeks perjalanan spiritual inilah yang antara lain hendak ditularkan oleh Pirous kepada khalayak. Berbekal sikap ini, Pirous leluasa melakukan eksperimen dan eksplorasi estetik. Walapun begitu, tidak berarti bahwa aspek dakwah dalam lukisan Pirous kemudian lenyap. Pada momen pertemuan yang khusus dan optimal, lukisanlukisan kaligrafi kiranya sanggup memancing kehadiran tentang hal-hal yang teologis dan spiritual. Pada titik ini, setiap orang akan menerima pengalaman
tersebut secara berbeda-beda. Barangkali penting mencermati lukisan-lukisan kaligrafi Pirous bukan pada soal beragama (religious), berkerohaniannya (spiritual). melainkan soal
Menampilkan Sosok Pirous Seutuhnya Pada hari ini, Pirous dan wacana seni lukis kaligrafi mustahil dipisahkan. Akan tetapi, kita tidak bisa menilai Pirous secara parsial. Kontribusinya tidak hanya dapat dilihat dari kepeloporannya mengembangkan seni lukis kaligrafi di Indonesia. Pemikiran-pemikirannya yang ditujukan kepada perbaikan dan perubahan sosial dan budaya Aceh mudah kita jumpai. Lalu perhatian maupun aksi nyata yang dilakukannya guna memajukan keilmuan di dunia pendidikan seni rupa. Belum lagi peran sentralnya dalam melahirkan studi desain grafis di Indonesia. Sementara gagasannya tentang identitas budaya Islam dan juga identitas seni rupa Indonesia, belum lagi keluwesan pergaulannya dalam melakukan diplomasi budaya, baik secara nasional maupun internasional; wawasannya tentang seni rupa Asia, menempatkan Pirous sebagai pribadi yang bersegi banyak. Berdasarkan asumsi itu, saya tidak pernah membayangkan pameran ini hanya memuat karya-karya seni lukis, gambar dan grafis dari masa ke masa sebagaimana lazimnya sebuah pameran retrospektif. Saya memutuskan untuk menampilkan sejumlah koleksi arsip, fotografi, hasil rekaman audio, visual maupun catatan-catatan renungan, materi perkuliahan, guntingan koran. Semua materi itu diandaikan mampu menghadirkan dimensi sejarah. Dengan demikian, pameran ini diharapkan tidak berhenti sebagai pameran retrospektif biasa. Karena itu, isu utama yang disorongkan oleh pameran ini bukan lagi sebuah pembahasan atas pencapaian-pencapaian artistik Pirous secara periodikal. Wacana yang hendak diusung melalui pameran ini pun diharapkan tidak lagi terjebak hanya pada soal seni rupa maupun kesenimanan. Pameran Jau Timu: 80 Tahun A.D. Pirous memang lebih ditujukan untuk menghadirkan beliau seutuhnya di hadapan khalayak sebagai manusia yang
sudah memberi arti pada kemajuan agama, budaya, seni, pendidikan untuk bangsanya sendiri. Titik tolak saya dalam mengkurasi pameran ini adalah semangat yang terkandung di dalam pernyataan Pirous sendiri. Ia menyatakan: Di usia 80, hemat saya, masalah seni rupa dan sebagainya bukan lagi prioritas. Hal terpenting yang ingin saya bagi ke masyarakat saat ini adalah refleksi pembelajaran terhadap permasalahan tersebut. Dalam mengamati sosok Pirous secara lebih luas, profesor antropologi Amerika Kenneth M. George dalam Picturing Islam: Art and Ethics in a Muslim Lifeworld (2010), sudah melangkah lebih jauh. Buku setebal 164 halaman yang bahan utamanya pernah diterbitkan sebelumnya sebagai A.D. Pirous: Vision, Faith and Journey in Indonesia Art, 1955-2002 (2002) ini menyajikan dunia Islam dengan mengeksplorasi isu-isu agama, nasionalisme, etnisitas, dan globalisasi melalui kehidupan dan karya Pirous. Dengan menggabungkan pendekatan antropologi seni dan agama, buku ini berhasil menunjukkan dampak Islam, etnis, nasionalisme, dan globalisasi pada pekerjaan dan kehidupan seorang seniman pascakolonial yang diakui secara internasional. Para komentator Picturing Islam juga mengatakan betapa perspektif buku ini berhasil memberikan potret menarik dan kaya yang sumbernya digali dari seorang seniman. Karena itu, buku ini turut memberikan kontribusi untuk membangun pengertian mendalam tentang politik, budaya dunia seni pascakolonial Asia serta mengungkap perasaan kreatif dan etnis seorang seniman Muslim. Kenneth, dalam hal ini, membuka jalan baru untuk melihat profil Pirous. Dan tentu saja, di sisi yang bersamaan, Picturing Islam sesungguhnya menyarankan sebuah metode alternatif keilmuan seni yang akan meneladani peminat sejarah seni di tanah air untuk menganalisis profil seniman-seniman Indonesia lainnya. Di luar itu, lukisan-lukisan, pemikiran dan biografi Pirous yang dielaborasi oleh Kenneth dalam Picturing Islam sesungguhnya membuka jalan alternatif untuk studi Islam di Indonesia. Buku ini menyimpang dari tradisi penulisan sejarah Islam Indonesia yang selama ini cenderung mengkajinya melalui jalur sejarah sosial, keorganisasian maupun politik.
Dari Retro ke Perspektif Pameran pertama retrospektif A.D. Pirous berlangsung selama satu minggu pada 22 27 Oktober 1985 di Taman Ismail Marzuki - Jakarta. Menampilkan lukisan, etsa dan cetak saring, pameran ini merupakan rekaman perkembangan semenjak 1960-1985. Buku A.D. Pirous: Lukisan, Etsa dan Cetak Saring Retrospektif 19601985 yang diluncurkan mengiringi pameran retrospektif 1985 ini ditulis oleh Machmud Buchari dan Sanento Yuliman. Selain memuat latar biografis oleh Buchari, buku setebal lebih dari 100 halaman ini mengupas hampir satu-persatu karya A.D. Pirous secara formal dan tajam oleh Sanento. Antara tahun 19561965, Sanento misalnya mencatat, bukanlah masa yang tenang dan gampang bagi Pirous. Pekerjaannya masa itu memperlihatkan pergantian corak yang cepat, kadang-kadang kembali untuk waktu yang singkat kepada corak yang sudah ditinggalkan, dan juga nampak percobaan-percobaan dengan berbagai unsur lukis dan dengan bahan dan teknik, tulis Sanento. Dengan kekuatan telaah setiap penulisnya, buku ini memberikan pijakan awal kepada siapa saja untuk memahami Pirous dan karya-karyanya pada satu masa tertentu. Masih bertempat di Jakarta, pameran retrospektif ke-dua dilakukan di Galeri Nasional pada 2002. Ini merupakan pameran besar untuk memperingati 70 tahun usia Pirous. Menandai usia panjang ini, pada tahun itu pula, diterbitkan buku karangan Kenneth M. George dan Mamannoor. Selain membahas ketokohan Pirous secara pribadi dan kontribusinya di dunia seni rupa serta memuat analisa karya-karyanya secara mendalam, buku A.D. Pirous: Vision, Faith and Journey in Indonesia Art, 1955-2002 juga merupakan cerita mengenai manusia Indonesia dan bagaimana tokoh di dalamnya memaknai akan ke-Indonesia-annya. Lebih dari 250 halaman, buku ini menyajikan dokumentasi komprehensif. Di masa depan depan, buku ini berpeluang menjadi salah satu buku yang paling otoritatif tentang Pirous. Pada 2003, sebanyak 38 esai Pirous yang ia tulis dalam rentang 40 tahun (1963-2003) dikumpulkan dan diterbitkan. Bunga rampai yang diberi judul Melukis itu Menulis yang mengulas ragam topik mulai soal pendidikan, kritik seni, sejarah seni rupa, budaya hingga pengalaman pribadi sampai obituari ini
memperlihatkan kecakapan menulis dan kejelian Pirous mengurai topik dan permasalahan. Dalam Saseo Ono dan Perkembangan Seni Lukis Indonesia di Zaman Jepang (1942-1946), esai yang bersumber dari tesis 1964, Pirous misalnya mengatakan bahwa pengaruh Jepang dalam praktik seni terasa lebih luas, lebih sensitif dan terbuka. Pirous tidak mengingkari kontribusi Jepang, baik secara kelembagaan melalui Keimin Bunka Shidosho maupun perorangan seperti pelukis Saseo Ono yang ditunjukkan oleh Pirous di dalam esai tersebut. Penting untuk dicermati bagaimana sikap dan pandangan Pirous yang tegas ini cukup berseberangan dengan sejumlah sejarawan seni rupa lainnya yang menganggap sepele periode kependudukan Jepang bagi kemajuan seni rupa Indonesia. Pada 1964, saat baru menginjak usia 32 tahun, Pirous menyelesaikan tesis berjudul Seni Pariwara sebagai Alat Propaganda Perjuangan. Kedudukan tesis ini penting karena mengupas perjalanan pariwara sebagai instrumen dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia pascakemerdekaan, dan dipaparkan pula bagaimana seniman-seniman terlibat secara aktif di dalamnya. Kata seni dalam rangkaian istilah seni pariwara yang digunakan Pirous, pada hari ini bisa kita pahami sebagai desain, yang pada dekade 1960-an memang belum populer di masyarakat Indonesia (dipahami secara luas, makna pariwara adalah iklan, periklanan atau bisa kita setarakan dengan advertising). Tesis tersebut menyumbang jalan bagi penulisan sejarah sosial desain Indonesia. Selain memuat repro contoh-contoh pariwara pada masa revolusi hingga dekade 1960-an, tesis ini menunjukkan fungsi dan pengaruh seni pariwara guna menegakkan kemerdekaan, membangun serta membina kesadaran berbangsa. Mengutip ucapan S. Sudjojono, di dalam tesis itu Pirous turut menekankan arti pentingnya peran seniman pada masa revolusi dalam mengobarkan nasionalisme, mendidik jiwa rakyat di samping menanam rasa keindahan (estetika). Pariwara perjuangan, tegas S. Sudjojono, tidak hanya berfungsi pengobar semangat, tetapi juga bertugas mendidik jiwa rakyat di samping menanam rasa keindahan. Dengan menekankan estetika, kemunculan masyarakat baru yang baru saja melepaskan diri dari kolonialisme akan mencapai nilai adab kemanusiaan yang
hakiki. Bertalian dengan pokok itulah, tesis setebal lebih dari 150 halaman itu menyorongkan bukti-bukti yang kuat. Tesis sejarah sosial desain Indonesia ini sesungguhnya turut merintis pembentukan wacana budaya visual (visual culture) di Indonesia. Buku Melukis itu Menulis semakin menarik karena memuat esai Komputer Art: Jalan Berliku Pelukis Djoni Djuhari (1988). Djoni Djuhari, pelukis sekaligus dosen di lingkungan Seni Rupa-ITB, ketika itu sedang memamerkan karya-karya hasil olahan komputer yang kemudian dicetak di atas kertas kertas. Mengantar pameran tersebut, Pirous menulis: Sebagai seorang pelukis yang peka terhadap unsur-unsur estetika seperti garis, bentuk, warna, irama, komposisi dan sebagainya, dan juga mendalami bidang percetakan serta penguasaan yang baik dalam ilmu fotografi, di samping aktif dan akran dengan boneka dan perancangan pola tekstil-tekstil lewat teknik cetak saringnya dan semua ini telah mengantarkan Djoni ke pelataran ungkapan seni. Dia termasuk seorang perintis citra baru, kemungkinan baru, dan tanggapan baru dalam perjalanan seni rupa kita: seni rupa komputer, computer art atau lart dinateur. Sumbangsih esai ini penting untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana seni media baru (new media art) di Indonesia bermula, terutama di Bandung.
Identitas: Pirous Menemukan Pirous Soal identitas seni rupa merupakan salah satu isu sentral yang kerap dibicarakan oleh Pirous. Kita akan memaklumi keadaan ini mengingat Pirous mengalami dekade di mana wacana identitas dalam seni dan budaya pernah memanasi atmosfir dunia cendekiawan. Selama di Bandung, semenjak pertengahan 1950-an, melalui pendidikan seni, Pirous meresapi arti kemodernan dari guru-guru Belandanya, terutama Ries Mulder. Proses ini tidak berlangsung mulus. Pada akhir 1950-an, Mulder dan guru-guru Belanda lainnya pulang kembali ke Eropa. Lukisan-lukisan awal saya pernah dikritik Ries Mulder karena dinilai tidak berhasil menunjukkan prinsipprinsip yang ia ajarkan, ungkap Pirous. Semasa Mulder, Pirous mengakui
bagaimana ia berusaha sungguh-sungguh mengikuti kemodernan dalam seni lukis. Menjadi pelukis modern pada masa itu, demikian Pirous, tersimpan di dalam bawah sadar pelukis-pelukis Indonesia. Hanya saja, implementasinya sangat beraneka ragam karena memang disesuaikan dengan naluri masingmasing pelukis. Dari pernyataan ini terbayang oleh kita bagaimana dislokasi kejiwaan yang melanda pelukis-pelukis Indonesia pada masa itu. Dislokasi bertalian dengan identitas. Inti dari persoalan ini adalah kenyataan bahwa tidak sedikit seniman Indonesia pada dekade 1950-an menempatkan diri mereka sebagai ahli waris dunia yang sah. Mereka merasa bahwa melukis dengan cara modern, berpikir layaknya pelukis modern dengan sendirinya sudah menjadi bagian dari emansipasi yang dijanjikan universalitas. Sebagai pelukis muda, Pirous mengalami gelora ini. Puncak dari tegangan identitas dirasakan Pirous ketika melawat ke Amerika pada awal 1970-an. Di negeri Abang Sam itu, Pirous sering mempertanyakan dirinya maupun keabsahan nilai-nilai universal seni modern yang ia resapi sebelumnya. Saat itu dari museum-museum dan galeri-galeri New York, saya mencari dan mempertanyakan kehadiran karya-karya pelukis Indonesia. Ternyata memang tidak ada, kenang Pirous. Pirous terpukul dengan kenyataan ini. Filsuf dan pengamat seni rupa Arthur C. Danto pernah menyatakan: Modernisme disusun di Paris dan New York. Hasilnya bisa membingungkan dunia. Ia menolak semua tradisi estetik kecuali dari wilayah Eropa dan Amerika Serikat. Modernisme merupakan kisah mengenai budaya Barat dan tentu saja tidak menempatkan seniman maupun karya seni di luar dari itu. Pirous pun sampai pada kesimpulan: kalau pedoman seni modern Barat itu memang benar, namun tidak mampu menjawab kegelisahan senimannya (baca: seniman non-Barat), lalu bagaimana membuktikan kebenaran pedoman itu? Kepada Helena Spanjaard (1989), Pirous mengakui: Di Bandung saya tidak memiliki banyak pemikiran tentang menjadi pelukis Indonesia. Saya terlalu sibuk belajar melukis menuruti pedoman-pedoman Barat. Hanya setelah saya menguasai tekniknya, saya mulai merenungkan isinya. Hal ini terjadi ketika saya di luar negeri pada saat adanya jarak antara saya dan Indonesia. Ketika itulah saya
bertanya pada diri sendiri: Baiklah Pirous, siapakah anda ini sesungguhnya? Dan saya simpulkan bahwa saya seorang pelukis Indonesia karena lingkungan Indonesia menjadi bahan-bahan persoalan untuk saya. Bagaimanapun juga, sikap Pirous dalam menghayati identitas, dalam beberapa hal, tidak bisa dilepaskan dari atmosfir kemodernan kota Bandung, terutama pada masa-masa ketika seni rupa di kota ini dijuluki Laboratorium Barat. Harus diakui, sebagian besar pedoman melukis di Bandung diselenggarakan dengan tradisi akademik Barat. Hasil didikan Barat ini berhasil mengkonstruksi cara pandang serta cara menilai seni yang baru dan berbeda. Pendekatan ilmiah, formalisme, selalu bersandar pada perkembangan sejarah seni universal dan menjadi bagian dari situ, adalah komponen-komponen utama yang ditekankan di dalam laboratorium ini. Tak banyak orang luar yang mengerti apa yang sesungguhnya tengah berlangsung dan pengetahuan semacam apa yang diajarkan di sana. Dalam hal ini, nasib kota-kota besar lain di Indonesia tidak seberuntung Bandung. Sekitar 10 tahun setelah Trisno Sumardjo memberi cap Laboratorium Barat, pada akhir Januari 1964, Pirous beserta sejumlah kolega di lingkungan Seni Rupa-ITB dan seniman-seniman Bandung lainnya menyiarkan dukungan ke Manifes Kebudayaan seteru ideologi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Surat dukungan ini bersifat terbuka yang memudahkan lawan membidik sasaran tembaknya. Resiko ini disadari oleh Pirous dan kolega lainnya. Masih tebal dalam ingatannya ketika pada masa-masa itu infiltrasi komunis ke kampus ITB berlangsung kuat dan berhasil membangun suasana saling penuh curiga. Kendati berada di tengah situasi politik yang tidak menentu, sekalipun tidak ringan, seniman-seniman ITB tetap konsisten menjalankan tugas mereka: menyelenggarakan pendidikan berdasarkan keilmuan seni rupa Barat serta mengeksplorasi buah seninya. Cap Laboratorium Barat yang diberikan sebelumnya serta merta menajamkan persepsi khalayak terhadap senimanseniman ITB. Sebab di mata kaum komunis, istilah Barat pada masa-masa itu identik dengan nekolim dan kontra revolusioner: dua istilah yang mengerikan dan sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang.
10
Pirous sangat mencintai kota Bandung. Di kota ini pula ia mempersunting Erna Garnasih, seorang wanita priangan lulusan Seni Rupa-ITB pada 1968. Mereka dikarunia tiga orang anak: Mida, Iwan, Rihan. Pirous sangat menghayati pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ketika merantau dari Aceh ke Bandung pada September 1955, di usia 23 tahun, Pirous tidak pernah membayangkan bahwa ia akan ditakdirkan menjadi salah seorang yang turut memajukan identitas seni rupa kota ini. Pada 1992, misalnya, melalui The 7th Asian Internasional Art Exhibition, sebuah pameran internasional yang diadakan di Gedung Merdeka, Pirous berhasil mengedepankan kota Bandung ke arena seni rupa yang lebih luas dan bergengsi. Kiprah selanjutnya membuktikan komitmen dan konsistensi Pirous bagi kemajuan seni kota Bandung secara nyata. Di kota ini pula, pada pertengahan 1970-an, bersama G. Sidharta dan Adri Palar, Pirous menggagas Decenta (Design Center Association) suatu perkumpulan seniman/desainer yang memadukan kaidah-kaidah antara pengetahuan seni dan desain. Pirous membangun ruang budaya lain yang dikenal sebagai Serambi Pirous di kawasan Sangkuriang.
Jau Timu Ungkapan Aceh Jau Timu (Mengarahlah ke Timur) yang mendasari pameran ini mengandung falsafah yang dalam. Dia mengurai makna tentang sebuah visi, etos, spirit kepada siapa saja untuk berani berkata ya kepada hidup; untuk mengarah ke penjuru kehidupan yang lebih baik. Ungkapan yang bertalian dengan semangat Pirous merantau ke tanah Timur ini, sesungguhnya berhubungan erat dengan sunnah Rasulullah SAW tentang pentingnya menuntut ilmu sekalipun dia terletak di ujung China). Makna Jau Timu akan mengenai sasaran apabila diterapkan dalam menggali kembali khazanah Timur agar tidak senantiasa menoleh Barat sebagai satusatunya tata nilai yang paling absah dalam memandang masalah sosial, ekonomi, politik hingga seni-budaya. Ungkapan yang disarankan oleh sang ayah ketika Pirous masih berusia muda ini sebenarnya bisa ditempatkan sebagai sumber dunia sekalipun (tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri
11
inspirasi, spirit, afirmasi dan legitimasi ihwal perlunya mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis ulayat (indigenous) yang berpusat di Asia guna memahami realitas Asia secara lebih baik lagi. Barangkali orang perlu ke Barat dahulu untuk memahami Timur, ungkap Pirous,atau mungkin juga orang bisa terlebih dahulu menghayati hakikat Timur dan menemukan Barat di dalamnya. Apa dan siapakah Timur dan Barat itu? Bagaimana hakikat pertentangan antar keduanya bisa kita pahami? Dalam Orientalisme Edward Said memprovokasi dasar-dasar pengertian yang bertalian dengan pertentangan antara Timur dan Barat. Ia menyatakan bahwa pengertian orientalisme dapat didiskusikan dan dianalisis sebagai institusi yang berbadan hukum untuk menghadapi Timur, yang berkepentingan membuat pernyataan tentang Timur, membenarkan pandangan-pandangan tentang Timur, mendeskripsikannya dengan mengajarkannya, memposisikannya, menguasainya. Pendeknya, kata Said, orientalisme adalah cara Barat untuk mendominasi, merestrukturisasi dan menguasai Timur. Selain itu, Said juga menengarai bahwa seorang orientalis adalah orang yang mengajarkan, menulis tentang atau meneliti Timur, terlepas apakah dia seorang antropolog, seniman, sosiolog, sejarawan, atau filolog, dengan kata lain, adalah orang yang mendaku memiliki pengetahuan atau memahami kebudayaankebudayaan Timur. Cara pandang Said ini bagaimanapun memiliki pengaruh yang luas. Istilah orientalisme kini seringkali digunakan sebagai makna pejoratif yang bisa berarti manipulasi kolonial terhadap Timur. Pirous sendiri sangat menyadari perihal yang dilematis tersebut dan bagaimana relevansinya dalam wacana kebudayaan pada hari ini.
Guru Besar Pirous adalah guru besar dalam arti yang sebenarnya. Di usia 80 tahun, ia masih melukis. Ia juga masih menghadiri maupun membuka acara pameran seni;
12
menjalani rapat berkala sebagai anggota Akademi Jakarta maupun kapasitasnya sebagai dewan penasihat Galeri Nasional Jakarta. Pameran ini dipersembahkan untuk dedikasinya yang luar biasa kepada seni rupa Indonesia, untuk segenap spirit yang pernah ia salurkan ke dunia pendidikan, kepada wawasan serta visi-visinya yang melampaui zaman dan terutama sumbangsihnya pada kemanusiaan juga kehidupan.
Bandung, Januari 2012 Aminudin TH Siregar
Pustaka Dudy Wiyancoko (ed.), A. D. Pirous: Melukis itu Menulis, (Bandung: Penerbit ITB, 2003). Joseph Ficher (ed.), Modern Indonesia Art, (Berkeley, 1990). Kenneth M. George dan Mamannoor, A. D. Pirous: Vision, Faith and Journey in Indonesia Art, 1955-2002, (Bandung: Serambi Pirous, 2002). Kenneth M. George, Picturing Islam: Art and Ethics in a Muslim Lifeworld, (UK: Blackwell Publishing, 2010). Machmud Buchari & Sanento Yuliman, A. D. Pirous: Lukisan, Etsa dan Cetak Saring Retrospektif 1960-1985, (Bandung: Galeri Decenta, 1985). Edward Said, Orientalism, (New York: Vintage Book, 1979). Web-site http://www.lemka.net/2011/01/ad-pirous-dan-kaligrafi-kontemporer.html.
13
Anda mungkin juga menyukai
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Kaligrafi Kontemporer AD PirousDokumen18 halamanKaligrafi Kontemporer AD PirousAgung PirsadaBelum ada peringkat
- Aliran SENI LUKIS MODERNDokumen17 halamanAliran SENI LUKIS MODERNLia Hanisa RahmawatiBelum ada peringkat
- Bab IDokumen20 halamanBab Ibismillah masyaallahBelum ada peringkat
- Seni Instalasi LengkapDokumen6 halamanSeni Instalasi LengkapTaufiq Wyra HadieBelum ada peringkat
- 08 Tajuk 4Dokumen17 halaman08 Tajuk 4WaniRoslyBelum ada peringkat
- Sejarah Seni BaratDokumen38 halamanSejarah Seni BaratBasirah AsriBelum ada peringkat
- Apa Itu Seni TampakDokumen4 halamanApa Itu Seni TampakCikgu AngahComelBelum ada peringkat
- Kuratorial Pameran Tunggal Seni Visual Susilawati SusmonoDokumen9 halamanKuratorial Pameran Tunggal Seni Visual Susilawati Susmono6042101014Belum ada peringkat
- Isolasionisme Dan Kontekstualisme DalamDokumen7 halamanIsolasionisme Dan Kontekstualisme DalamArief SatriyoBelum ada peringkat
- B-Perkembangan Makna Simbolik Motif Medalion-Jurnal ImajiDokumen28 halamanB-Perkembangan Makna Simbolik Motif Medalion-Jurnal ImajiEvolution exBelum ada peringkat
- Perjuangan PersagiDokumen4 halamanPerjuangan PersagiPutri100% (1)
- Periode PersagiDokumen6 halamanPeriode PersagiMuhammad Fariz IXBelum ada peringkat
- Perjalanan Seni Rupa Baru Di IndonesiaDokumen4 halamanPerjalanan Seni Rupa Baru Di IndonesiaFaiz SetiawanBelum ada peringkat
- Cakaran Jurnal Entang WiharsoDokumen3 halamanCakaran Jurnal Entang WiharsoIftikhar Ahmad RajwieBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen11 halaman1 PBchar gameBelum ada peringkat
- 9159 25748 1 SMDokumen20 halaman9159 25748 1 SMDae AshBelum ada peringkat
- Laporan Seminar Seni RupaDokumen7 halamanLaporan Seminar Seni RupaLinda LangitshabrinaBelum ada peringkat
- Sastra Dan PemikiranDokumen5 halamanSastra Dan PemikiranClaudia Larassati100% (1)
- Apresiasi Dan Kritikan SeniDokumen12 halamanApresiasi Dan Kritikan SeniArnold JunilBelum ada peringkat
- Materi Seni RupaDokumen15 halamanMateri Seni RupaYemima ApriliaBelum ada peringkat
- Kuratorial Jim Supangkatarief Ash ShiddiqDokumen11 halamanKuratorial Jim Supangkatarief Ash ShiddiqRum TaoBelum ada peringkat
- Makalah Lukis SurealisDokumen10 halamanMakalah Lukis Surealisfadlali100% (1)
- Seni BudyaDokumen10 halamanSeni BudyaAnonymous hvwCrABelum ada peringkat
- SULUK 4.inddDokumen76 halamanSULUK 4.inddKedokteran Unisma MalangBelum ada peringkat
- Pandangan Sumbangan Tokoh Terhadap Pendidikan Seni VisualDokumen55 halamanPandangan Sumbangan Tokoh Terhadap Pendidikan Seni VisualPyqa Nor100% (2)
- Ass Pengenalan SeniDokumen12 halamanAss Pengenalan Seninorizanar9453Belum ada peringkat
- Perbandingan Seni Lukisan Antara TamadunDokumen10 halamanPerbandingan Seni Lukisan Antara TamadunNor Adilah Ali100% (1)
- Seni OrientalDokumen5 halamanSeni OrientalFirdaus AdhaBelum ada peringkat
- Sejarah Dan ApresiasiDokumen19 halamanSejarah Dan ApresiasisuuushhheeeBelum ada peringkat
- Transidentalisme Seni Dan Budaya Kajian ApresiasiDokumen20 halamanTransidentalisme Seni Dan Budaya Kajian ApresiasiSaparudinBelum ada peringkat
- Definisi Seni LukisDokumen7 halamanDefinisi Seni LukisAbdurahman Cahyadiputra100% (1)
- Bicara Seni 1Dokumen20 halamanBicara Seni 1azman bin hilmiBelum ada peringkat
- Pengertian Aliran Seni lukis-WPS OfficeDokumen5 halamanPengertian Aliran Seni lukis-WPS Officewarnet mufidnetBelum ada peringkat
- Seni Dalam Pandangan Islam-1Dokumen9 halamanSeni Dalam Pandangan Islam-1arif rahmatullahBelum ada peringkat
- Estetika Seni Rupa Indonesia Sebuah Jalan Putar20190729-74236-1f1tf7i-With-Cover-Page-V2Dokumen17 halamanEstetika Seni Rupa Indonesia Sebuah Jalan Putar20190729-74236-1f1tf7i-With-Cover-Page-V2Pradhia IkbarBelum ada peringkat
- IPTEKS Konsep Seni Dan KeindahanDokumen7 halamanIPTEKS Konsep Seni Dan Keindahanaliah bachmidBelum ada peringkat
- Apa Itu Seni Menurut Prespektif Jakob SumardjoDokumen8 halamanApa Itu Seni Menurut Prespektif Jakob Sumardjopuddingchu069Belum ada peringkat
- ESTETIKAISLAMDokumen4 halamanESTETIKAISLAMHamdan AkromullahBelum ada peringkat
- KK Penulisan Sejarah SeniDokumen4 halamanKK Penulisan Sejarah SeniSiti Nur AisahBelum ada peringkat
- Perbezaan Seni Barat Dan Seni IslamDokumen4 halamanPerbezaan Seni Barat Dan Seni IslamSiti Nur Aisah0% (1)
- Tugas Seni Budaya Dan KeterampilanDokumen12 halamanTugas Seni Budaya Dan KeterampilanZabran Ryfi100% (1)
- Kliping Reproduksi Karya Seni LukisDokumen10 halamanKliping Reproduksi Karya Seni LukisNur AuliaBelum ada peringkat
- Popo Iskandar Seniman Budayawan Dan Pendidik - Yabu M PDFDokumen11 halamanPopo Iskandar Seniman Budayawan Dan Pendidik - Yabu M PDFYabu Mallabasa100% (1)
- Latar Belakang Sastra Angkatan 45Dokumen6 halamanLatar Belakang Sastra Angkatan 45Lutfia LilaBelum ada peringkat
- SENI VISUALDokumen26 halamanSENI VISUALP.h. KhengBelum ada peringkat
- CCU 艺术Dokumen7 halamanCCU 艺术Abel AgripinaBelum ada peringkat
- Seni Rupa ModernDokumen45 halamanSeni Rupa ModernDwinita Ayuni LarasatiBelum ada peringkat
- Materi 3.7Dokumen7 halamanMateri 3.7Dwi wahyu setyaningsihBelum ada peringkat
- Pandangan Politik S. SudjojonoDokumen13 halamanPandangan Politik S. SudjojonoKamuBelum ada peringkat
- HADISDokumen36 halamanHADISRiakhairiah SinambelaBelum ada peringkat
- SEJARAH SENI RUPA ASIADokumen3 halamanSEJARAH SENI RUPA ASIAAicha JunikaBelum ada peringkat
- Bismillah FAZA AGHNIA BRILIANNABILA 17206241044Dokumen14 halamanBismillah FAZA AGHNIA BRILIANNABILA 17206241044Ong Faza29Belum ada peringkat
- MakalahDokumen211 halamanMakalahNeli Annisa SeptianiBelum ada peringkat
- SEJARAH MODERNDokumen213 halamanSEJARAH MODERNIman Prakoso100% (1)
- Pandangan & Sumbangan Tokoh Terhadap Pendidikan Seni VisualDokumen55 halamanPandangan & Sumbangan Tokoh Terhadap Pendidikan Seni VisualEswary Vijaen67% (6)
- 572-Article Text-1403-1-10-20211007Dokumen11 halaman572-Article Text-1403-1-10-20211007Nizma FaizaBelum ada peringkat
- Angkatan 45-1Dokumen8 halamanAngkatan 45-1Rangu't Turang'kBelum ada peringkat
- 45] Sastra Angkatan 45Dokumen12 halaman45] Sastra Angkatan 45Rino Dwiagus SetyawanBelum ada peringkat
- AmourDokumen4 halamanAmourroufchasbullahBelum ada peringkat
- Ibnu MuqlahDokumen6 halamanIbnu MuqlahroufchasbullahBelum ada peringkat
- Tugas Pengurus KelasDokumen2 halamanTugas Pengurus KelasroufchasbullahBelum ada peringkat
- ManajemenpendidikanDokumen7 halamanManajemenpendidikanroufchasbullahBelum ada peringkat
- Pengumuman Bidikmisi 2012Dokumen3 halamanPengumuman Bidikmisi 2012roufchasbullahBelum ada peringkat


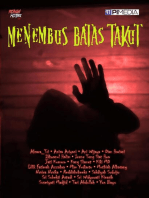

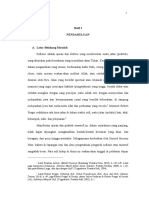


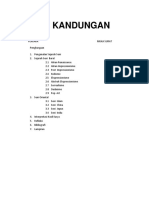



















































![45] Sastra Angkatan 45](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78404682/149x198/9c1028758c/1368721711?v=1)




