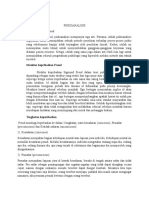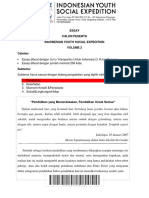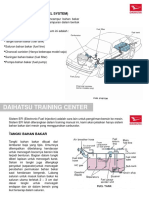Wacana Vol. 1
Diunggah oleh
Mhd AdityaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Wacana Vol. 1
Diunggah oleh
Mhd AdityaHak Cipta:
Format Tersedia
WACANA VOL.
1
“OSPEK: PENDIDIKAN ATAU PENINDASAN(?)”
KUMPULAN ESAI KEPADA MAHASISWA BARU
Penulis:
John Heryanto
Pavel Ivanovsky Alamsyah
Naufal Waly
Taufik Nurhidayat
Komite Pelajar Menolak Perploncoan
Organisasi Bumi Rakyat
Pranadipta Putra
Tata Letak:
Naufal Waly & John Heryanto
Desain Sampul:
John Heryanto
Penanggung Jawab Produksi:
Ridwan Kamaludin
Noor Sidiq
Pahrul Gunawan
Nadia Finsuri
Lintang Sulistyo Anggoro
Fahadpa Alfadj
Seri Buletin LPM Daunjati
Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung
Jalan Buah Batu No. 212, Kota Bandung, Jawa Barat
Web: daunjationline.com
Email: ukm.daun.jati@gmail.com
Instagram: /lpmdaunjati
Cetakan pertama (edisi revisi) Agustus 2019.
WACANA VOL. 1
OSPEK: PENDIDIKAN ATAU PENINDASAN(?)
KUMPULAN ESAI KEPADA MAHASISWA BARU
Wacana merupakan seri buletin yang diterbitkan LPM Daunjati,
sebagai sarana meluaskan gagasan terkait kebudayaan dan
untuk merawat ruang-ruang demokrasi dalam berkehidupan.
Editorial
oleh: Redaksi LPM Daunjati
Institusi pendidikan, semestinya menjadi tempat untuk
membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, ruang bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan bangkitnya nalar kritis
setiap individu akan kenyataan yang ada di dunianya.
Celakanya, segala kemestian di atas tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada. Perploncoan, budaya yang pertama kali
dikenalkan pada masyarakat Hindia Belanda oleh para siswa
yang kebanyakan bangsa Belanda kepada siswa baru yang
pribumi, dalam rangka memperkuat struktur sosial yang ada
kala itu: yang penjajah (kolonial) harus terus berada satu kasta
di atas dari yang terjajah (pribumi), sampai hari ini masih saja
diwariskan. Bahkan setelah 74 tahun kolonialisme itu pergi
dari Indonesia.
Pewarisan itu tidak terjadi begitu saja, namun sebuah
konsekuensi logis dari rezim yang masih memiliki kepentingan
dan mendapat keuntungan dari adanya budaya tersebut:
menciptakan pelajar dan mahasiswa yang gampang diatur,
tidak mudah melawan, tidak gampang protes dan lain
sebagainya. Belakangan, pasca mulai terpublikasinya kasus-
kasus perploncoan yang menelan banyak korban, pemerintah
mulai memperlihatkan upayanya untuk menghilangkan budaya
plonco. Alih-alih memberi solusi konkrit, budaya plonco hanya
diganti bajunya tanpa dihilangkan substansinya: bekerja sama
dengan tentara dalam ospek. Plonco langsung oleh senior di
beberapa sekolah dan kampus memang langsung lenyap dalam
sekejap. Tapi efeknya tetap sama, bahkan lebih parah:
melibatkan tentara mengospek adalah membayangkan pelajar
dan mahasiswa harus serba seragam dan serba sigap untuk
bilang “siap!”, sebuah upaya pematian nalar kritis dan kreatif.
Pelibatan tentara ke dalam institusi pendidikan menjadi bukti,
bahwa upaya penghapusan budaya plonco yang dilakukan
pemerintah bukan upaya yang tulus, melainkan basa-basi
belaka. Tapi di sisi lain juga, dalam beberapa tahun terakhir
masih banyak kampus yang mahasiswanya menolak cara yang
dilakukan pemerintah ini. Alasannya “Pemerintah tidak tau apa
kebutuhan internal organisasi kita!” sambil tetap
mempertahankan budaya memelonco mahasiswa baru atas
nama kedisiplinan dan penyiapan mental. Padahal tidak jelas
juga apakah dua alasan yang populer dan berkembang di
kalangan mahasiswa yang masih mempertahankan budaya
plonco itu punya konteksnya dengan pendidikan atau tidak.
Misal kedisiplinan, bukan kah semestinya kedisiplinan orang
terdidik ada dalam konteks disiplin keilmuan yang ilmiah, yang
mensyaratkan demokratisasi ilmu pengetahuan? Bukan
kedisiplinan ala meneer terhadap pribumi, dalam proses kerja
paksa era kolonial; budaya yang menguatkan struktur sosial
bahwa yang penjajah (senior) harus terus berada satu kasta di
atas dari yang terjajah (junior). Kenyataan yang semestinya tak
perlu ada di open rekruitmen sebuah organisasi mahasiswa,
tapi itu lah kenyataannya, budaya plonco memang masih ada.
Bahkan setelah 74 tahun merdeka dari kolonialisme.
Dan pada akhirnya, organisasi mahasiswa intra kampus akan
terus konsisten menjadi kapal yang rombeng seperti sekarang.
Terombang-ambing dalam lautan persoalan nyata dunia
pendidikan: biaya mahal, misalnya, yang selamanya tak akan
bisa dilihat selama kabut lingkaran setan senioritas masih
menutupi pandangan mata para mahasiswa baru setiap
tahunnya.
OSPEK: PENDIDIKAN ATAU PENINDASAN(?)
Oleh: John Heryanto
Bagaimana sebetulnya OSPEK itu berlangsung saat memasuki
perguruan tinggi seni seperti ISBI Bandung? Sehingga
mahasiswa semester atas maupun alumni seringkali
mengeluarkan kata-kata seperti ini: “Sia hayang di-ospek deui,
kitu?” (Kamu mau di-ospek lagi?), “Tuh! Jiga kitu jelema anu teu
ngasaan ospek mah!” (Tuh, kayak begitu kalau orang yang
nggak ikut ospek!), “Ayeunamah teu sabaraha, baheulamah
urang hulu teh nepi ka ditincak ku Tatib” (Hari ini gak seberapa,
dulu kita sampai diinjak kepalanya sama Tatib* (*salah satu
divisi yang biasanya ada di Ospek)) dan berbagai kata-kata
lainnya.
Seorang mahasiswa bermana Braung M. Irsyad menulis di
kolom “Celotehan Pojok Kampus” atas pengalaman mengikuti
OSPEK, dalam buletin Daunjati edisi ke 3 tahun 2006: “Saya
tidak ingin bertanya, mengapa saya ikut dalam kegiatan BSM
atau Peka Seni, sebab jawabannya adalah karena saya
mahasiswa baru. Namun, kalau pertanyaannya diubah,
mengapa saya harus mengikuti kegiatan tersebut. Saya tidak
bisa menjawabnya, peserta yang lain juga merasakan hal yang
sama.”.
Kebisuan, tak menemukan jawaban maupun alasan mengikuti
sebuah kegiatan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus
seringkali muncul hingga kini sebagai sebuah pertanyaan yang
tanpa jawaban. Hingga pertanyaan lebih jauhnya: Apakah yang
telah terjadi dalam pendidikan selama ini? Bukan kah
pendidikan bertujuan agar siswa/mahasiswa memiliki
kemampuan untuk meningkatkan aspek kognitif (nalar), afektif
(rasa), psikomotorik (karsa), dan lain-lain. Selain itu
sekolah/kampus juga mesti hadir sebagai tempat
berlangsungnya perkembangan pribadi (personal development)
saat kanak-kanak dan remaja, menguasai pola prilaku yang
khas dan pengembangan pemahaman diri (self-understanding)
dan lain-lain.
Sedangkan penyelenggaraan OSPEK pada dasarnya bertujuan
untuk membiasakan mahasiswa baru mengadapi perkuliahan
lewat bimbingan belajar singkat. Memiliki tujuan yang sama
yaitu untuk mengenal kondisi kampus secara menyeluruh
tidak hanya akademik, menjaga solidaritas dan kekompakan
angkatan, menyatukan mahasiswa agar saling mengenal dan
menghormati, baik ke satu angkatan maupun ke angkatan
yang lain. Loyalitas dan militansi terhadap cita-cita dan
perjuangan mahasiswa dan organisasi yang diatur dalam
AD/ART-nya masing-masing organisasi mahasiswa di tingkat
jurusan hingga universitas. Kegiatan Orientasi atau Bimbingan
Studi untuk mahasiswa baru ini mengacu pada peraturan
Kemendikbud No.0125/U/1979 dan Keputusan Dirjen Dikti No.
38/DIKTI/Kep/2000. Pada tahun 70-an itulah Kata OSPEK
digunakan untuk acara menyambut mahasiswa baru. Pada
praktiknya OSPEK malah melahirkan generasi bisu, generasi
yang dibungkam. Hal ini seperti sebuah spanduk yang
terpasang di samping Gedung Sunan Ambu, menjelang daftar
ulang mahasiswa baru 2019 (terpasang selama sepekan di awal
bulan Agustus) yang bertuliskan: “Hancurkan Senioritas di
sekolah & kampus. Buka Ruang Demokrasi Seluas Luasnya!”.
Kebisuan sekelompok mahasiswa bagi Paulo Freire muncul dari
persentasi dan adanya ‘situasi penindasan’, sehingga
melahirkan kebudayaan bisu. Kebisuan tersebut bisa menimpa
mahasiswa baru tidak hanya dalam OSPEK tapi bisa juga di
dalam kelas saat proses perkuliahan berlangsung. Ketika
mahasiswa tingkat atas atau dosen memiliki legalitas dan
otoritas lebih dan tanpa dialog, mahasiswa baru mengalami
‘situasi-situasi yang menindas di luar kehendaknya’. Tidak
memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Hal ini seperti puisi “Surat
Cinta”-nya Semi Ikra Anggara pada tahun 2006 setahun setelah
dia menjadi mahasiswa di STSI/ISBI Bandung:
“Antara Lembaga dan Mahasiswa
Mana yang bisa kupercaya.”
Bila melihat petikan puisi di atas terkait mahasiswa, OSPEK
bukan hanya melahirkan budaya bisu semata, tapi juga telah
menghilangkan kepercayaan mahasiswa baru pada mahasiswa
lama atau senior karena berbagai kekerasan yang dialami,
seperti larik puisi Semi selanjutnya:
“Ketika Mahasiswa senior
Menampar mahasiswa baru seenaknya
Dalam acara inisiasi
Di mana kah hati direktur lembaga?
Di dalam kulkaskah?”
Bahkan dalam sebuah pertunjukan yang dilakukan mahasiswa
teater angkatan 2015, yang saat itu masih mahasiswa baru, di
acara Makrab himpunan mahasiswa jurusan teater, seorang
aktor berujar, dengan iringan musik, dengan dada yang
terengap-engap seperti kehilangan napas, dan mata yang sayup:
“Aku takut menjadi senior, dua atau tiga tahun lagi, kalau
syaratnya harus lupa cara bikin kopi, harus lupa cara pergi ke
warung, harus lupa jalan ke kantin, harus lupa cara bergerak,
dan harus lupa jadi manusia.”
Teks-teks tersebut begitu saja muntah dari sekumpulan
mahasiswa yang beberapa bulan sebelumnya menjadi peserta
Peka Seni dan BSM. Teks tersebut bertolak dari pengalaman
dan pertemuan dengan mahasiswa lama selama OSPEK.
Otoritas senior yang berlangsung, seperti banyak guyonan para
mahasiswa lama atau alumni ketika reuni, yang sering
terdengar di ruang-ruang pertemuan: “Senior tidak pernah
salah dan jika senior salah maka kembali pada pasal satu”.
Kisah–kisah mengikuti kegitaan OSPEK juga hadir dalam
nuansa yang akrab antara para senior, lebih dari sekadar
mengingat masa lalu, pengalaman di-OSPEK dan meng-OSPEK
bahkan menjadi sesuatu yang dogmatis, bahwa tindakan-
tindakan perploncoan merupakan tradisi yang harus terus
dipelihara. Adapun beberapa di antara: 1) “Mahasiswa baru
yang laki-laki harus botak/cepak/gundul karena dari dulu juga
botak, begitu juga ketika saya ikutan OSPEK”, 2) “Mahasiswa
baru tidak boleh berkeliaran di area kampus, maksimal jarak
terdekat 500 meter dari kampus, dan kalau ingin ke kampus
harus jalan kaki dengan maksimal jarak 1 KM selama kegiatan
OSPEK berlangsung”; Hal-hal tersebut secara otomatis
membatasi aktivitas mahasiswa baru untuk mengenal lebih
dekat kampusnya secara alamiah, serta menutup kemungkinan
untuk belajar berdasarkan jam yang diinginkan oleh dirinya
sendiri; 3) Peserta seringkali tidak diberitahu konten dan jadwal
per hari kegiatan OSPEK, dan jika ingin tahu agenda OSPEK
mesti datang ke acara; Hal ini dapat membawa kemungkinan
pada ketidak-percayaan mahasiswa baru pada kegiatan OSPEK,
dengan menumbuhkan rasa was-was jika sewaktu-waktu ada
tindakan atau kegiatan yang membahayakan keselamatan; 4)
Mahasiswa baru ketika di rangkaian OSPEK alam (rangkaian
yang dilakukan di luar kampus, biasanya di lokasi perkemahan)
harus merasakan masuk lumpur untuk menguji mental, 5)
Mahasiswa baru diberikan tugas-tugas yang tidak jelas, semisal
disuruh membawa makanan dengan teka-teki, diintrogasi tiba-
tiba serta digeledah selayaknya penjahat, ketika panitia OSPEK
memeriksa tugas peserta, disuruh membuat papan nama dyang
kemudian digantung di leher dan lain sebagainya.
Pengalaman mengikuti OSPEK dan diplonco tidak hanya
menimpa mahasiswa ISBI Bandung. Tapi juga dialami oleh Soe
Hok Gie pada tahun 1961 ketika menjadi mahasiswa baru di
Universitas Indonesia. Sebagaimana tulisannya dalam “Catatan
Seorang Demonstran”:
“Ketika baru diplonco kami dibentak-bentak, ditendang tas kami
dan dimaki-maki. Baru-baru terpikir olehku, apa guna semua ini?
Di mana kadang – kadang manusia disuruh menjadi binatang.”.
Deretan angka kematian mahasiswa baru pun kemudian
membayangi setiap pelaksanaan OSPEK. Terutama sejak tahun
1999 hingga 2014 tercatat lebih sebanyak 80 orang mahasiswa
baru meninggal akibat plonco di Perguruan Tinggi di Indonesia.
Hal ini kemudian mendorong terbitnya surat Keputusan
Direktur Jendral Pemebelajaran dan Kemahasiswaan
Kemenristekdikti RI No. 09/B1/SK/2016 Tentang Pengenalan
Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKK-BM) dan Surat
Edaran Kemenag No. 3032.A/Di.I/PP.00.9/07/2016 Tentang
Pengenalan Budaya Akademik bagi Mahasiswa Baru.
Selain itu OSPEK telah melahirkan sistem patronase (pola dan
hubungan atasan dan bawahan) dalam hal ini tentunya yang
memiliki kuasa adalah atasan maka atasan memerlukan
pembenaran sebagai bentuk dari pada kuasa (hegemoni). Maka
terjadilah senioritas dan inilah yang diwariskan turun temurun
sampai hari ini. Atau yang Soe Hok Gie sebut dengan:
“Terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa.
Memerintah kalau ditekan, tapi menindas kalau berkuasa.
Setiap tahun datang adik-adik saya dari sekolah menengah.
Mereka akan menjadi korban-korban baru untuk ditipu oleh
tokoh mahasiswa semacam tadi.”
Sudah saatnya hari ini mempertanyakan kembali OSPEK.
Apalagi jika hal itu sebagai rekruitmen keanggotaan organisasi
mahasiswa tingkat jurusan dan universitas. Maka OSPEK
mestilah menjawab persoalan terkini, yang lebih
mengedepankan pendidkan dan keilmuan. Terutama
memperkenalkan Tri Darma Perguruan Tinggi: pendidikan,
penelitian, dan pengabdian. Mahasiswa baru dengan itu akan
dapat gambaran kehidupan kampus yang diisi dengan
perkuliahan, diskusi, riset, kerja social, serta khusus di ISBI
Bandung, kerja seni dan kebudayan. Selain itu mahasiswa baru
juga dihadapkan pada kenyataan carut marutnya sistem
pendidikan dan biaya kuliah yang terus melangit yang tak
sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bahwa:
“Pendidikan adalah hak semua warga negara, yang
pelaksanaannya ditanggung sepenuhnya atau dijamin oleh
negara”. Maka organisasi mahasiswa mestilah mampu
menempa mental dan kepekaan sosial mahasiswa atas realitas
sosial politik maupun ekonomi-politik.
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
“Jihad yang paling utama adalah kalimat yang haq di hadapan
penguasa zalim”, (HR. At-Tirmidzi no. 22329, disahihkan oleh
Senioritas Itu Sampah Zaman!*
Oleh: Pavel Ivanovsky Alamsyah
*tulisan ini terbit pertama kali di qureta.com
Gegap gempita perayaan kelulusan siswa SMA telah usai.
Saatnya mereka, sebagian dari yang mencoret-coret seragam
sekolah di jalanan beberapa waktu lalu menggunakan pilox dan
spidol, akan kembali disibukan dengan gegap gempita yang
lainnya. Apalagi kalau bukan soal kuliah? Jadi mahasiswa
tentu jadi kebanggaan bagi setiap orang yang memiliki
keberuntungan bisa membayar uang kuliah. Lain halnya
dengan mereka yang terpaksa harus membuang mimpi
merasakan bangku kuliah karena dipaksa miskin oleh negara
yang hanya sibuk mengeruk keuntungan dari si miskin dan
menambah pundi-pundi keuntungan si kaya. Jangankan bayar
uang kuliah, buat makan saja harus lebih berhemat.
Beruntung kalau diberi beasiswa.
Sebagai mantan mahasiswa baru yang pernah malang
melintang di tiga program studi dan dua universitas berbeda
selama 6 tahun, tentu saya, juga segerombolan manusia yang
lebih dulu menginjakkan kaki di kampus, pernah merasakan
apa yang dirasakan oleh calon-calon mahasiswa baru saat ini.
Dari mulai teman baru, pelajaran baru, suasana baru, bahkan
sampai pacar baru pernah ada di benak mahasiswa baru nan
jomblo seperti saya saat pertama kali menyerahkan berkas-
berkas pendaftaran mahasiswa di bagian registrasi (tata usaha)
kampus tujuan saya.
Hari-hari seolah terasa lama berlalu. Rasanya tak sabar bagi
saya untuk segera memulai petualangan baru bersama teman-
teman baru. Saya rasa demikian juga yang sedang dirasakan
oleh teman-teman calon mahasiswa baru saat ini. Yang terjadi
justru sebaliknya, bukan perubahan kebijakan kampus yang
berhasil kita lakukan, melainkan antara sesama mahasiswa,
karena sejak OSPEK dipertontonkan dengan budaya saling
mendominasi antar mahasiswa, terkadang mengakibatkan adu
jotos akibat hal-hal yang remeh-temeh atau rebutan proyek
kegiatan event organizer yang dibumbui program unit kegiatan
mahasiswa (UKM) antar mahasiswa. Anehnya, bahkan ada
senior yang dengan gagahnya mengatakan di depan mahasiswa
baru bahwa "sebelum melawan penindasan, kalian harus
merasakan bagaimana ditindas" sebagai dalih agar mahasiswa
baru mau mendengarkan perintah-perintah senior.
Sungguh senioritas telah mendarah daging dalam diri
mahasiswa seperti ini. Padahal tanpa kita atur-atur atau
arahkan bak kerbau sekalipun, mahasiswa-mahasiswa baru ini
akan tetap mampu menyesuaikan dengan lingkungan barunya.
Darwin bahkan Engels sudah pernah menguraikan bahwa
manusia, sejak mulai memisahkan diri dari binatang, mampu
melewati fase penyusuaian dengan lingkungannya yang
senantiasa berubah (lihat Engels, Peranan yang Dimainkan
Kerja dalam Peralihan Kera Jadi Manusia). Bagi saya, yang
pernah terlibat dan menyesal sepenuhnya pernah menjalankan
praktik senioritas saat penyelenggaraan OSPEK, praktik-
praktik semacam ini lebih merupakan sebagai budaya balas
dendam dan sampah sejarah yang semestinya sudah lama
membusuk di tempat pembuangan sampah. Tidak ada alasan
kuat untuk terus mempertahankannya.
Lalu Apa yang Harus Kita Lakukan?
Mahasiswa baru, jika masih saja kalian temui praktik-praktik
dan tipikal senior yang seperti saya sampaikan di atas,
alangkah baiknya kamu mulai berpikir lagi untuk
mendengarkan setiap ocehannya yang penuh omong kosong
dan hasrat untuk mendominasi tersebut.
Masih banyak yang harus aku, kamu, dan teman-teman lain
lakukan untuk mengubah kampus yang kian hari kian sulit
diakses oleh masyarakat luas. Negara, yang katanya melalui
undang-undang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa, justru berbalik 180° dan menjadikan
kampus tempat yang sulit diakses oleh masyarakat luas dan
menjadikannya lumbung memperoleh keuntungan sebanyak-
banyaknya.
Liberalisasi pendidikan, skema pembayaran Uang Kuliah
Tunggal, hingga kontrol terhadap organisasi mahasiswa (UKM)
adalah paket lengkap yang menjadikan kampus sebagai salah
satu instrumen penindasan mahasiswa dan masyarakat secara
luas. Kalian mahasiswa baru, tidak perlu takut jika harus
berhadapan dengan tipikal-tipikal senior di atas. Sebab ada
banyak mahasiswa yang bisa kamu temui di sudut-sudut
kampus, di kantin-kantin, di klub-klub diskusi taman kampus,
sampai di depan gedung rektorat yang bisa bergandengan
tangan denganmu, berdiri bersamamu, dan bersuara lantang
untuk menyudahi praktik-praktik sampah itu.
Hanya dengan berkumpul dan bertukar pikiran dengan orang-
orang seperti itu, setidaknya kalian punya peluang terbebas
dari doktrin-doktrin senioritas. Dan untuk kalian, yang pernah
sama-sama jadi panitia OSPEK, bahkan yang sampai sekarang
masih jadi panitia OSPEK dan melanggengkan praktik-praktik
senioritas, apa kalian tidak bosan menyaksikan bahwa hampir
setiap tahun, senioritas yang dipraktikkan selama OSPEK itu
sama sekali tidak ada gunanya?
Ada banyak hal yang perlu kita lakukan bersama-sama tanpa
harus mendominasi satu sama lain. Ada banyak teori-teori yang
mestinya kita baca lalu kita uji bersama dalam praktik untuk
mengubah kampus agar menjadi tempat yang lebih mudah
diakses oleh masyarakat luas, bukan jadi tempat meraup
pundi-pundi keuntungan bagi negara dan segelintir orang yang
mengendalikan negara.
Tidak perlu menungulur-ngulur waktu lagi. Ayo, ubah kampus
demi kebahagianku, kebahagianmu, dan kebahagiaan kita!
Terakhir, saya ingin mengutip kata-kata Jenny Von Westphalen
untuk kalian, mahasiswa baru: "Kebahagiaan membutuhkan
pemberontakan."
Selamat datang, kawan baru. Sampai bertemu di medan juang.
Semoga kita dapat berkawan untuk bahu-membahu
menghapus senioritas dan mengubah kampus.
PT SENI: MENGKRITIK KOMERSIALISASI
KAMPUS ATAU TRADISI YANG BERULANG?*
Oleh: Naufal Waly
*tulisan ini terbit pertama kali di daunjationline.com, saat
momen Peka Seni tahun 2019
Hari itu kampus ISBI Bandung halaman depan lumayan ramai,
dengan hadirnya meja-meja himpunan yang membuka stan
pendaftaran masuk himpunan untuk mahasiswa baru. Selain
himpunan yang membuka meja, ada juga stan pendaftaran PT
Seni atau Peka Seni (Pengenalan Kampus Seni), program
rekrutmen berbasis orientasi kampus yang diselenggarakan
BEM.
Tentu berbeda dengan program rekrutmen himpunan, Peka
Seni cakupan dan targetnya lebih banyak, yaitu mahasiswa
baru dari seluruh jurusan. Hari ini memang hari pertama bagi
mahasiswa baru jalur Mandiri untuk mendaftar ulang ke pihak
kampus, yang dibuka dari tanggal 6 hingga 17 Agustus 2018.
Setelah sebelumnya mahasiswa baru jalur SNMPTN dan
SBMPTN sejumlah 310 orang (daya tampung,sbi.ac.id) telah
melakukan daftar ulang lebih dulu, hingga tanggal 17 Agustus
bagian administrasi Peka Seni tinggal menunggu 363
mahasiswa baru lagi untuk mendaftar Peka Seni. Itu pun jika
seluruhnya daftar ulang menjadi mahasiswa dan, jika
seluruhnya mendaftar Peka Seni
Dalam sejarahnya, ospek level universitas memang selalu
mendapat antusiasme keikutsertaan yang besar, baik di ISBI
Bandung maupun kampus-kampus pada umumnya. Berbagai
daya tarik dan yang menjadi tuntutan mahasiswa baru agar
ikut serta, antara lain: sertifikat ospek berguna untuk beasiswa,
sudah kepalang bayar saat pendaftaran awal, sampai
penasaran dengan tradisi yang ada.
Di sisi lain, terkadang informasi seputar hal negatif yang ada
dalam ospek sudah diketahui mahasiswa baru, tetap saja
antusiasme untuk ikut serta selalu besar tiap tahunnya. Maka
tidak heran jika dari tahun ke tahun Peka Seni selalu berhasil
menjaring lebih dari 60% dari seluruh jumlah mahasiswa baru,
setidaknya untuk mendaftar (tidak semua yang mendaftar lolos
menjadi anggota BEM atau lulus dari Peka Seni).
Peka Seni tahun 2018 memakai PT Seni sebagai judul acara.
Judul tersebut merujuk pada ‘analogi konsep perusahaan’,
seperti bisa dilihat dalam spanduk publikasi yang terpasang di
beberapa tempat di kampus. Dari mulai gambar pabrik, orang-
orang dengan baju proyek, orang-orang yang digambarkan dari
kelas pekerja, sampai mesin produksi.
Publikasi tersebut paling banyak digantung di “gedung
mangkrak” yang dalam formulir pendaftaran mahasiswa baru
digambarkan desain plannya, alias khayalan (tidak sesuai
kenyataannya). Kaitan antara PT Seni yang salah satu
tujuannya sebagai orientasi kampus, dengan ‘analogi konsep
perusahaan’ dengan latar belakangnya seolah memberi makna
kampus bekerja seperti perusahaan: “mengambil untung
sebanyak-banyaknya”, bisa dilihat pada realita kampus saat ini
yang makin komersial.
Komersialisasi, memang konsekuensi logis dari negara yang
menganut sistem ekonomi kapitalisme, alih-alih sistem tersebut
hanya berpengaruh pada harga ‘pasar sungguhan’, dunia
pendidikan pun kena imbasnya. Hari ini, dunia pendidikan pun
akhirnya bagian dari pasar itu sendiri, yakni, mengelola
akumulasi modal (dari anggaran subsidi pemerintah, dari biaya
yang dibayarkan mahasiswa, sampai penghasilan dari
penyewaan infrastruktur kampus), menghasilkan nilai lebih
(surplus), dan menghisap hasil tenaga kerja (lulusan sebagai
calon buruh-buruh).
Sistem pembayaran UKT yang konon menyesuaikan
kemampuan ekonomi mahasiswa adalah bukti kampus
memang telah komersil. Tapi ‘kan menyesuaikan kemampuan.
Benarkah? Ternyata tidak juga. Sistem UKT masih terus
bermasalah, bahkan pada hal substansialnya: menyesuaikan
kemampuan.
Seperti misalnya banyak kasus mahasiswa yang mendapatkan
golongan pembayaran yang tidak sesuai kondisi ekonominya,
sehingga penentuan golongan banyak dipertanyakan:
semenyesuaikan apa sistem UKT terhadap kemampuan
mahasiswa?
Daunjati mencatat sepanjang tahun 2017 hingga awal 2018
ada 3 mahasiswa dari Fakultas Seni Pertunjukan yang putus
kuliah karena alasan biaya. Padahal, mereka termasuk
mahasiswa dengan UKT golongan kedua terendah. Jika
memakai perspektif PT atau perusahaan atau kapitalisme,
fenomena putus kuliah karena alasan ekonomi adalah sebuah
hal yang biasa, salah sorangan teu boga duit.
Tapi jika masih mengamini instrumen “Pendidikan adalah hak
setiap warga negara”, masih bisa kah diterima kenyataannya:
ada mahasiswa, seorang warga negara Indonesia, memiliki
keinginan mengenyam pendidikan, namun mereka tak miliki
uang untuk membayar biaya kuliah (yang diasumsikan oleh
Sistem UKT sudah menyesuaikan kemampuan mahasiswa),
sehingga berhenti kuliah adalah pilihan satu-satunya? Tidak
akan. Kecuali, jika instrumen itu hanya slogan omong kosong
di kertas Undang-undang, yang pada kenyataannya kampus
telah tidak ada bedanya dengan PT atau perusahaan atau
kapitalisme; mengambil untung sebanyak-banyaknya.
Dalam setahun ke belakang, terhitung sejak Peka Seni 2017
(jaraknya setahun, karena saat berita ini ditulis Peka Seni 2018
sudah dalam proses pendaftaran peserta) isu sistem UKT tidak
menjadi wacana utama dalam kampus, dan organisasi
mahasiswa. Upaya pengumpulan kuesioner yang dihimpun
Daunjati, konsolidasi Ormawa tahun lalu (2017) akhirnya tidak
berdampak banyak, selain dampak kecil yaitu beberapa
mahasiswa berhasil mendapat perbaikan golongan UKT.
Prosesnya ada yang datang bersama orangtua memprotes
penentuan golongan yang tidak sesuai, ada yang pada akhirnya
didata dan diurus melalui himpunan masing-masing. Namun,
dampak tersebut tentu cuma dampak kecil bagi sistem UKT
yang jangka panjang, yang akan “turun-temurun”, dan makin
menguatkan eksistensi pendidikan yang komersil jika terus
didiamkan. Dampak yang konkret seharusnya bisa dihasilkan
dari gerakan yang kolektif, atau populer dikenal sebagai
gerakan massa. Bukan gerakan protes yang sendiri-sendiri
seperti upaya perbaikan golongan UKT yang dampaknya hanya
untuk per-orangan saja. Gerakan massa yang secara ilmiah,
sebenarnya mampu muncul dari Peka Seni, misalnya. Momen
pengumpulan mahasiswa secara besar dan kolektif dalam satu
event. Tapi pada kenyataannya tidak terjadi apa yang
diharapkan di atas. Setelah Peka Seni selesai, masing-masing
mahasiswa mengurus masalah UKT-nya sendiri. Bukti
pendulangan banyak orang di Peka Seni (tahun 2017), tidak
mencapai kesadaran kolektif untuk melawan penindasan
kampus dalam hal ekonomi.
Fakta di atas menjadi PR sekaligus beban yang dipikul Peka
Seni tahun ini, yang kadung memilih PT Seni sebagai judul.
Judul yang terlalu vulgar, jika tujuannya untuk mengkritik
komersialisasi pendidikan. Tapi jika tujuannya bukan
mengkritik, PT Seni mungkin hanya akan mengulang sejarah
Peka Seni tahun 2017, atau Peka Seni dari masa ke masa, yang
selalu menyia-nyiakan massa mahasiswa baru dan
membiarkan 'tradisi' yang terus berulang, lebih buruknya,
mengamini wacana kampus yang makin hari makin komersial.
GALAK KEPADA ADIK MABA
TAPI TAKUT BIROKRAT KAMPUS*
Oleh: Taufik Nurhidayat
*tulisan ini terbit pertama kali di siksakampus.com
Menghayati dramaturgi-sosial, ospek ibarat panggung bagi
senior-senior tertindas. Sesekali mereka ingin terpaksa terhormat.
Siapa lagi kalau bukan adik-adik maba sebagai sasarannya.
(Redaksi LPM Daunjati)
Sebenarnya sudah bukan lagi kewenangan saya selaku senior
di atas senior-senior aktivis kampus untuk mengomentari
senioritas. Sudah saatnya saya beranjak memikirkan hal luar
kampus secara serius; misal memikirkan pengorganisiran fans
club yang reaksioneris sebagai massa pembaca artikel saya
supaya saya bisa dengan mudah meniti tangga popularitas.
Tapi jahanamnya, saya tidak punya ans club. Ow, sungguh
kejamnya dunia netizen yang latah berantah ini!
Tak apalah, toh popularitas itu fana belaka. Yang awet adanya
ialah penindasan, dalam wujud senioritas sekalipun. Bila
musim ospek tiba, pemandangan nyata tersebut lumrah
dibuat-buat. Maba seakan kerbau yang sepatutnya dibebani,
diatur-atur, disuruh-suruh, diarahkan atasnama pengenalan
kampus. Senior yang mewujud jadi panitia ospek merasa
dirinya berwenang mendidik adik maba ihwal kelakuan
mahasiswa yang baik nan benar. Prek!
Bahkan, di tempat saya bermain tapi belajar, yakni Universitas
Negeri Yogyakarta, kerap dipertontonkan sandiwara angker
senioritas kepada adik-adik maba. Tentunya, ketika saya masih
menjelma maba pun pernah berpura-pura takut kepada kakak-
kakak galak yang sengaja dipersiapkan untuk menertibkan
adik-adik maba dalam momen ospek.
Ciri khasnya, kakak-kakak galak itu ber-dresscode serba hitam,
pasang muka tanpa senyum, berlagak kaku (bukan tegas), dan
seenaknya mereka membentak tanpa malu-malu walau belum
kenal. Mereka memang sekumpulan tim khusus berlagak galak
dan membentak-bentak ria. Adik-adik maba yang ketahuan
melanggar peraturan, nantinya akan berurusan dengan orang-
orang macam mereka. Hukuman pun menanti bagi adik-adik
maba pelanggar aturan; lagi-lagi atasnama pengenalan kampus.
“Mana tugasnya?!”, “Kenapa telat?!”, “Cepaaaat, jangan
lambat!”, “Kamu dihukum….”, dan lontaran bernada bentak
lainnya kerap terdengar berisik tiada arti di telinga adik-adik
maba. Mungkin saja, adik-adik maba tahu bahwa kakak-kakak
galak itu cuma berpura-pura. Atau juga, adik-adik maba
banyak yang maklum bahwa kakak-kakak galak itu butuh
pengakuan hormat dari para juniornya setahun sekali.
Yaelaaah…kapan lagi coba bisa dihormati para junior kalau
tidak pas momen ospek? Karena di hari-hari berikutnya, bisa
jadi kakak-kakak galak itu menjelma para penurut di hadapan
dosen atau malah merupa kerbau bebal di hadapan bebalnya
birokrat kampus. Payah pisan euy….!
Namun sebagai orang yang diakui senior di atas senior-senior
aktivis kampus, saya menganggap bahwa mazhab galak yang
dianut kakak-kakak panitia tersebut merupakan euforia konyol
atau tontonan drama kebodohan yang sepatutnya ditiadakan
saja. Galak-galak ria adalah pemaksaan hormat kepada senior.
Sepengalaman saya sebagai senior, kehormatan yang diperoleh
dari para junior itu datang karena sumbangsih kesabaran para
senior dalam membimbing, memberi ilmu bermanfaat,
mengorbankan waktu untuk mbribik, apalagi meneladankan
sifat berani melawan penindasan dalam kampus dan membela
golongan mustadh’afin. Tentunya, ya, seperti saya ini. Bukan
saya bermaksud sombong, setidaknya yang saya sampaikan
tersebut memang valid. Kalau nggak percaya, tanyakan saja
kepada junior-junior saya di kampus.
Berlagak angker menakut-nakuti maba hanyalah pelarian diri
dari realita penindasan yang dialami mahasiswa. Sekuat-
kuatnya iman, senior juga punya keterbatasan kuasa dalam
menghadapi pihak-pihak yang mendominasinya. Ini rentan
dialami mahasiswa. Banyak contoh kasus membuktikan
ketidakberdayaan mahasiswa seperti: mengkritik dosen tapi
takut dapat nilai jelek, memimpin massa berdemo tapi takut di-
drop out, menolak biaya kuliah mahal tapi sungkan bersuara,
melawan kesewenangan tapi sedih dibenci senior, dan
parahnya, ingin selingkuh dengan teman satu kelompok KKN
tapi takut dilaporkan pacar kepada rektor, otoritas kecamatan
setempat, dan ormas keagamaan. Pahit sekali, bukan?
Kebetulan, ospek digiatkan setahun sekali. Di situ ada ruang
untuk memperoleh kehormatan dari para junior—walau
memaksa, sekadar mengalihkan diri dari jenuhnya
penghormatan kepada pihak dominan di kampus. Senior-senior
galak dalam ospek cenderung suka memandang adik-adik
maba terlalu polos untuk dibikin takut. Selama ada
kesempatan, maka diraihlah kehormatan atas ketakutan adik-
adik maba dalam tempo sesingkat-singkatnya ospek. Ibarat
kata pepatah brengsek ciptaan saya, “menjadi serigala sepekan,
kemudian menjadi kerbau berbulan-bulan”. Pepatah ini
memang cocok bagi panitia ospek berlagak galak tapi takut
birokrat kampus.
Kalau begitu, saya selaku senior di atas senior-senior hendak
unjuk wacana mengenai teori dramaturgi sosial dalam mengkaji
peran keangkeran senior-senior panitia ospek. Menilik
pemikiran Erving Goffman, si sosiolog, manusia dalam
berinteraksi sosial membutuhkan panggung sandiwara agar
kesan ideal akan dirinya bisa tersampaikan kepada lawan
interaksinya. Untuk mencapai kesan ideal tersebut, manusia
selalu mengenakan atribut-atribut bersandiwara ketika sedang
memainkan perannya di panggung sosial. Atribut yang
dikenakan bisa berupa verbal atau non-verbal, dan
sandiwaranya pun harus benar-benar ekspresif supaya
meyakinkan. Adapun di balik panggung, sebenarnya manusia
sedang menyembunyikan kekurangan-kekurangan pada dirinya
sendiri.
Analisa di atas sejalan dengan apa yang dilakukan kakak-
kakak galak panitia ospek. Mereka harus memperoleh kesan
ideal sebagai senior bahwa mereka adalah orang-orang yang
patut dihormati maba (juniornya). Ekspresi kegalakan disertai
gerik dan ujaran-ujaran bernada membentak adalah atribut
yang meyakinkan. Kegalakan ditontonkan supaya maba
terpaksa percaya bahwa dengan menjadi tertib dan patuh
adalah potret mahasiswa ideal. Penugasan-penugasan ospek
yang harus dipatuhi diseolahkan sebagai simulasi tugas-tugas
akademik (bukan intelektual) yang akan di hadapi maba
mendatang. Dan, kakak-kakak galak memaksa agar adik-adik
maba patuh dan tertib supaya bisa menjadi mahasiswa ideal
seperti mereka; senior memaksa jadi teladan. Namun di
baliknya, mereka memang benar-benar mahasiswa yang patuh
aturan birokrat kampus karena lebih memilih sebagai
pecundang supaya selamat karir akademiknya.
Apa, mahasiswa ideal? Matamu njepat, senior…!!!
Menghayati dramaturgi sosial, ospek ibarat panggung bagi
senior-senior tertindas. Sesekali mereka ingin terpaksa
terhormat. Siapa lagi kalau bukan adik-adik maba sebagai
sasarannya. Piciknya, birokrat-birokrat kampus pun
mengizinkan praktik penindasan dan kepura-puraan demikian
atasnama kedisiplinan akademik. Saling tipu mah sudah
biasa.Yang perlu adik-adik maba sadari, tidak usah takut akan
galak-galak ria senior kalian kala ospek berlangsung. Tapi
jangan juga tuh senior-senior galak buru-buru kamu skakmat
pada agenda akbar penyambutan maba. Tolong, jangan dulu
kamu permalukan. Aktingnya benar-benar susah, dik. Jiwa
pemberontaknya disimpan dulu ya, dik…. Setelah ospek, kalian
bisa ambil sikap menolak tunduk.
Tapi kalau adik-adik maba sudah tidak tahan akan tontonan
goblok yang galak-galak itu, yaaah… Mau gimana lagi, di–
skakmat aja juga gak apa-apa! Kami yang pernah dikejar-kejar
aparat siap jadi partner-mu. Mereka mah ingusan, dik,
dibentrok dosen saja, nangis-nangis kok.
Akhirnya, saya selaku senior di atas senior-senior, menitip
pesan kepada kakak-kakak galak panitia ospek. Ospek nggak
perlu yang galak-galak gitu deh, please… Saya bosan lihat yang
begituan. Tolonglah berikan saya tontonan yang agak
menghibur hati yang bergundah cita ini. Saya bisa
menghormati kamu sekalian selaku senior-senior di bawah
saya jika bisa menjadikan ospek sebagai wahana menduduki
rektorat selama sepekan; pagi-siang-sore-malam tanpa pulang,
untuk menagih janji rektor serta kabinetnya dalam menghapus
biaya pendidikan mahal dan penjaminan kebebasan hak-hak
intelektual kampus. Berani? Atau takut?
Fiyuuuhhh…semoga tontonan berlagak galak kepada adik-adik
maba bisa berganti menjadi ajang kegalakan menghadap
birokrat kampus. Selama bertahun-tahun, saya berharap
demikian. Tapi laknatnya, senior-senior di bawah saya itu
gobloknya minta ampun! Dari tahun ke tahun ketika ospek
terselenggara, saya sempatkan mampir ke kampus; menikmati
kelakuan adik-adik maba yang memang masih perlu dibimbing
untuk tahu bahwa menjadi anak kuliahan itu tiada
istimewanya samasekali. Terlebih, menghormati kakak-kakak
panitia yang galak itu hanya percuma. Di masa mendatang,
mereka macam segerombolan pecundang ketika adik-adik
maba terbebani biaya kuliah mahal, terhalang mengakses
ruang belajar, diremehkan ilmunya, atau menghadapi dosen
bebal yang gila hormat. Kegalakan senioritas sama halnya
dengan popularitas; yakni fana dan belum tentu seawet
kharisma saya. Adik-adik maba harus tahu itu!
Pernyataan Sikap*
Oleh: Komite Pelajar Menolak Perploncoan
*tulisan ini terbit pertama kali dalam aksi turun ke jalan
Parade Pelajar Menolak Perploncoan yang diikuti sekitar 100
orang siswa dari berbagai sekolah dan beberapa mahasiswa,
tanggal 3 Agustus 2019 di Jalan Asia-Afrika Bandung
Berbicara soal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),
maka kita akan menemui masalah kekerasan yang sudah
menahun. Kekerasan ini disebabkan oleh tradisi perpeloncoan
yang melekat di dalamnya. Perpeloncoan sendiri merupakan
salah satu kekerasan paling tua dalam dunia pendidikan di
Indonesia yang diwariskan dari masa kolonialisme Hindia
Belanda ketika menjalankan politik etis. Dan sampai saat ini,
perploncoan masih dipertahankan dalam Masa Pengenalan
Lingkungan Sekolah. Maka tak heran jika para siswa baru
selalu mendapat kekerasan fisik maupun verbal dari para siswa
senior ketika Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
berlangsung. Kekerasan ini terus terjadi, meski pada tahun
ajaran baru tahun 2016/2017 Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan sempat mengeluarkan Permendikbud Nomor 18
yang mengatur bahwa sekolah dilarang mewajibkan para
siswanya untuk memakai atribut yang melecehkan dan
merendahkan para siswanya seperti nametag besar, kaos kaki
warna-warni, ataupun atribut aneh-aneh lainnya.
Namun faktanya aturan tersebut tidak sanggup untuk
meredam segala macam bentuk perploncoan. Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada rentang
tahun 2016-2017 secara akumulatif terdapat 249 korban
tindak perpeloncoan dalam Masa Pengenalan Lingkungan
Sekolah. Salah satu kasus yang terbaru terjadi di Palembang,
pada bulan Juli lalu, ketika dua siswa Sekolah Taruna
meninggal saat mengikuti kegiatan masa pengenalan di
sekolahnya. Mereka dipukuli para senior hingga tak bernyawa.
Pada mayat salah satu siswa ditemukan luka legam di
tubuhnya, dan yang terakhir mengalami koma selama enam
hari hingga akhirnya meninggal. Alih-alih memperbaiki kondisi
ini, Kemendikbud justru semakin memundurkan dan
mengokohkan tradisi perpeloncoan dalam MPLS melalui
pelibatan kembali tentara di tahun ajaran baru 2019-2020. Di
masa Orde Baru, pelibatan tentara di lingkup pendidikan
bertujuan menanamkan budaya takut, budaya bungkam,
budaya tunduk, agar siswa tidak kritis, serta tidak melawan
bobroknya sistem kekuasaan Orde Baru. Oleh karena itu,
dalam melihat aturan Kemendikbud yang melibatkan kembali
tentara di lingkungan sekolah, kita tidak akan bisa melepaskan
kepentingan ekonomi-politik di belakangnya. Bukan barang
baru bahwa pendidikan di Indonesia adalah komoditas.
Pendidikan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang.
Pengukuhan ini terus diamini dengan liberalisasi, privatisasi,
dan komersialisasi di bidang pendidikan. Selain menjadikan
pendidikan sebagai lahan bisnis, hal tersebut juga dilakukan
untuk kepentingan penciptaan buruh-buruh terampil yang
murah sesuai kebutuhan industri. Perpeloncoan yang hadir di
sekolah merupakan bagian dari pengkondisian sejak dini agar
para murid tunduk dan patuh di bawah industrialisasi
pendidikan dan pasar.
Pendidikan seharusnya hadir untuk membebaskan manusia,
mendorong kapasitas individu manusia untuk berpikir kritis
akan dunianya sendiri maupun sekitarnya. Bukan membangun
budaya diam atau pola parkir yang patuh pada struktur dan
hierarki layaknya korporat. Menolak perpeloncoan artinya
berjuang secara sadar untuk mendorong iklim demokratis dan
mengembalikan sebagaimana pendidikan seharusnya, menjadi
pembebas manusia.
Maka dari itu, kami dari Komite Pelajar Menolak Perploncoan
menyerukan: 1) Tarik militer dari sekolah, 2) Hentikan tradisi
perploncoan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, 3)
Hapuskan sistem Full Day School, 4) Wujudkan pendidikan
gratis, 5) Usir guru cabul dari sekolah, 4) Angkat guru honorer
menjadi guru tetap, 6) Lawan senioritas, 7) Buka ruang
demokrasi di sekolah dengan melibatkan semua elemen sekolah
untuk menentukan kebijakan sekolah.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas dukungannya
kami ucapkan terimakasih.
PERPLONCOAN: PENINDASAN SISTEMATIS
PENINGGALAN KOLONIAL*
Oleh: Organisasi Bumi Rakyat
*tulisan ini terbit pertama kali di siksakampus.com
Penggojlokan atau perponcloan merupakan salah satu bentuk
kekerasan paling tua dalam dunia pendidikan Indonesia.
Muasalnya bisa ditelusuri mulai dari rezim pemerintah kolonial
Hindia Belanda yang mulai menjalankan politik etis. STOVIA,
Geneeskundinge Hooge School (GHS), Technische Hooge School
(THS), merupakan beberapa perguruan tinggi rezim kolonial
Belanda di Indonesia yang menjalankan perploncoan terhadap
mahasiswa baru. Mahasiswa-mahasiswa senior (mayoritas
adalah kaum Belanda totok) dengan bentakan dan teriakan
rasis serta mewajibkan mahasiswa baru untuk memakai
atribut yang memalukan serta melakukan permainan -
permainan untuk menghina kaum pribumi.
Pascarevolusi nasional dan pengakuan kemerdekaan Republik
Indonesia. Tradisi perploncoan ini masih diteruskan meskipun
nama institusi sudah diubah menjadi Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia (FK UI) dan Institut Teknologi Bandung.
Sejak rezim demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, banyak
organisasi/gerakan mahasiswa menentang tradisi penindasan
dalam kampus ini dan menuntut agar perploncoan dihapuskan.
Beberapa organisasi/gerakan mahasiswa seperti Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Centrale Gerakan
Mahasiswa Indonesia (CGMI), Gema 45 (Gerakan Mahasiswa 45)
tidak hanya aktif berdemonstrasi dan menggelar mimbar
massal anti perploncoan, mereka juga beberapa kali
membubarkan perploncoan secara langsung. Sayangnya
perjuangan ini gagal seiring pecahnya peristiwa G30S dan
jatuhnya Soekarno beserta rezim demokrasi terpimpin. Begitu
Soeharto dan rezim fasis Orde Baru-nya berkuasa, tradisi
perploncoan ini dikembalikan lagi. Bahkan militerisme Orde
Baru yang merasuk ke segala bidang, termasuk bidang
pendidikan, malah memperkokoh perploncoan di pendidikan
tinggi secara militeristik. Ignatius Mahendra menyatakan,
“Bagaimana pedagogi (atau pendidikan) militer tersebut? Orang
yang berpendidikan selalu dikonotasikan dengan kepatuhan
dan ketertundukan, yang buta sebenarnya. Perbedaan adalah
sesuatu yang terlarang, demikian juga dengan kecerdasan
(kritis) ataupun kreativitas.”. Bagaimana membentuk manusia
seperti itu? “Pendeknya, digunakan disiplin dan kontrol yang
mengekang prajurit dalam suatu ikatan baja dalam hal apapun
yang ia lakukan atau pikirkan, saat bertugas maupun tak
bertugas. Tiap individu dengan kejam dibengkokan, ditarik dan
dipelintir hingga tulang belakang yang terkuat pun terancam
patah, dan memang pada akhirnya hanya ada dua
kemungkinan: bengkok atau patah. Rezim Orde Baru
berkepentingan menyelenggarakan perploncoan untuk
menanamkan budaya takut, budaya bungkam, budaya tunduk,
agar mahasiswa tidak berani menghadapi penindasan, diam
tidak bersuara, tidak memprotes, serta tidak melawan
kesewenangan tirani penguasa. Perploncoan juga terus
menerus menanamkan senioritas agar tidak tercipta kesetaraan.
Mahasiswa terus menerus dibenturkan dengan mahasiswa agar
tidak bisa bersatu melawan biang keladi komersialisasi
pendidikan yaitu tirani penguasa. Lantas mengapa setelah
rezim fasis Orde Baru tumbang, perploncoan masih terus
bertahan? Sebab hanya pucuk penguasa saja yang berganti
namun sistem penindasan Imperialisme-Kapitalisme masih
terus bertahan. Komersialisasi pendidikan berkepentingan
mencetak buruh - buruh terampil untuk kepentingan Industri.
Perploncoan dipertahankan untuk terus membentuk
kepatuhan dan ketertundukan.
Perploncoan juga berakibat menguatnya sauvinisme akademik
(sikap mengagung-agungkan bidang pendidikan / studi
masing-masing serta menjelek-jelekkan bidang pendidikan /
studi pihak lain). Bukan rahasia lagi bahwa dalam setiap
perploncoan selalu ada kegiatan pawai atau arak-arakan
dengan dipenuhi teriakan-teriakan slogan atau yel-yel bahkan
lagu yang memuja-muja bidang studi masing-masing (bahkan
beberapa secara implisit menjelekkan bidang pendidikan/studi
pihak lain). Sebagai contoh Fakultas Peternakan (Fapet) di
suatu perguruan tinggi di Malang pada perploncoan tahun
2008 mewajibkan gestur tangan telunjuk diacungkan ke depan
atas dengan menyebut nama-nama hewan ternak serta diakhiri
dengan telunjuk diarahkan ke dada dengan menyebut Fapet.
Suatu ungkapan implisit yang mencap kelompok lain sebagai
ternak dan diri sendiri sebagai mahasiswa. Sauvinisme
akademik ini bahkan menular ke SMA (bersamaan dengan
menularnya perploncoan ke tingkat Sekolah Menengah Atas),
dimana banyak guru dan murid dengan latar belakang IPA
menjelekkan bidang studi IPS, dan begitu pula sebaliknya.
Sauvinisme akademik ini adalah ciri khas kapitalisme yang
dicangkokkan ke negara-negara dunia ketiga oleh Imperialisme,
dimana pendidikan semakin dispesialisasi (digolong-golongkan)
sesuai kebutuhan industri dan dalam ekonomi pasar yang
memberlakukan kompetisi pasar bebas memaksa setiap orang
untuk menjatuhkan satu sama lain.
Kembali ke permasalahan perploncoan di kampus, birokrat
kampus seringkali mengelak dan berdalih bahwa perploncoan
merupakan kegiatan wewenang mahasiswa yang tidak
dicampuri birokrat. Ini adalah sikap yang bias. Karena pada
kenyataannya yang ditolerir dan dipelihara birokrat kampus
adalah kegiatan-kegiatan perploncoan yang menanamkan
budaya takut, bungkam, tunduk, dan menjunjung tinggi
senioritas sedangkan kegiatan-kegiatan yang kritis seringkali
dipersulit, dihalang-halangi, dilarang, bahkan dibubarkan, dan
diancam dengan cap subversif. Bukan sekali atau dua kali saja
pemutaran film tentang Pembantaian 65, The Act of Killing, dan
semacamnya dilarang. Bahkan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA)
Universitas Brawijaya (UB) pun pernah melarang bedah buku
Dosa-Dosa Nurdin Halid (bekas pimpinan PSSI) sementara di
sisi lain melestarikan perploncoan serta paksaan agar rambut
mahasiswa dipotong cepak, wajib pakai jaket almamater, dan
name tag sebesar dada, selama satu semester, suatu kebijakan
yang sebenarnya tidak ilmiah. Ini menunjukkan bahwa Sistem
Pendidikan Nasional masih tidak ilmiah, tidak demokratis,
serta tidak mengabdi ke rakyat. Karena itu perjuangan
mahasiswa untuk mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional
yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat harus
menyertakan perjuangan menghapuskan perploncoan agar
budaya takut, bungkam, dan tunduk bisa diubah menjadi
budaya berani, budaya vokal-kritis, dan berlawan dalam
perjuangan melawan penindasan.
Bukan Senioritas,
Mengubah Kampus Butuh Solidaritas!*
Oleh: Pranadipa Putra
*tulisan ini terbit pertama kali di solidaritas.net
Akhir-akhir ini, seiring dengan semakin dekatnya
penyelenggaraan pengenalan kehidupan kampus bagi
mahasiswa baru (baca: ospek), senioritas kembali mendapat
tempat penting dalam obrolan-obrolan/diskusi di kalangan
mahasiswa. Sebagian mahasiswa, dengan berbagai alasan
pembenarannya menganggap bahwa senioritas di kalangan
mahasiswa masih perlu untuk terus dijaga. Sebagian lainnya
menganggap bahwa senioritas adalah sampah zaman yang
semestinya sudah lama membusuk di tempat sampah.
Para pembela senioritas menganggap (dari segi moralitas)
bahwa baik buruknya praktek-praktek senioritas di kampus
tergantung siapa yang menjalankannya. Selagi yang
menjalankan adalah orang yang tepat, maka senioritas akan
berdampak baik, begitu sebaliknya. Singkatnya: senior yang
baik akan mampu mengarahkan junior ke jalan yang benar;
junior yang baik adalah junior yang harus menghormati
seniornya karena usianya lebih tua; kira-kira demikianlah
harapan idealnya.
Pada kenyatannya, alih-alih berdampak baik, di kampus
praktek-praktek senioritas justru menjadi alat bagi senior
untuk melegitimasi dominasinya atas junior. Hanya karena
merasa lebih tua, senior seringkali menganggap remeh junior.
Pada penerimaan mahasiswa baru misalnya, mahasiswa baru
dipaksa harus tunduk, patuh dan bungkam terhadap setiap
perintah senior.
Relasi senior-junior ini juga acap kali dimanfaatkan oleh rektor
dan birokrasi kampus untuk mengamankan kekuasaannya dari
gelombang protes mahasiswa. Beberapa kali bisa kita temui di
kampus-kampus, yang karena kedekatannya dengan rektor,
mahasiswa senior (juga ada alumni) dimanfaatkan untuk
meredam kemarahan mahasiswa junior atas bobroknya
kampus. Alhasil mahasiswa-mahasiswa yang sudah dijejali
sejak awal bahwa junior harus menghargai senior ini terkadang
tanpa pikir panjang langsung mengiyakan saja dan memilih
meredam kemarahan mereka.
Berkaca dari pengalaman-pengalam yang sering kita temui di
kampus tersebut, senioritas sangat berpotensi untuk
menumpulkan nalar kritis mahasiswa karena menanamkan
budaya patuh, bungkam, tunduk, yang pada akhirnya
menyebabkan mahasiswa tidak berani menghadapi penindasan,
tidak memprotes, serta tidak melawan kesewenangan, seperti
yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru untuk
mengamankan kekuasaannya dari gelombang protes
mahasiswa. Selain itu, senioritas juga menghambat terciptanya
kesetaraan di kalangan mahasiswa, sehingga antar mahasiswa
terus menerus dibenturkan agar tidak bisa bersatu melawan
penindasan.
Mengubah Kampus dan Kebutuhan Solidaritas
Adalah kapitalisme lah yang menjadi akar dari masalah yang
dihadapi mahasiswa di kampus saat ini. Biaya kuliah yang
semakin mahal, tidak adanya ruang demokrasi, regulasi
pendidikan yang pro modal, hanyalah sedikit dari berbagai
gejala rusaknya esensi pendidikan oleh sistem yang menindas
ini.
Kenapa kapitalisme? Bukankah kebijakan-kebijakan di kampus
lebih banyak di atur oleh negara melalui tangan rektor dan
birokrasi kampus?
Menyalahkan rektor dan birokrasi kampus pada dasarnya
bukanlah tindakan yang salah, namun hal itu dapat menggeser
akar masalah yang sebenarnya, yakni sistem yang sekarang
dianut oleh kampus secara khusus, umumnya oleh sistem
pendidikan di Indonesia saat ini.
Dalam Program of the Democratic Socialist Party, Doug Lorimer
menjelaskan, “Peran negara dalam masyarakat kapitalis adalah
untuk membela kepentingan kelas yang memiliki alat-alat
produksi (kelas berkuasa) dengan menekan segala ancaman
terhadap dominasinya dan mengintegrasikan secara ideologis
kelas-kelas yang dieksploitasi”. Kepentingan dari kelas yang
berkuasa hari ini adalah menghasilkan profit yang pada
akhirnya sistem pendidikan pun, melalui regulasi yang dibuat
negara diarahkan untuk memenuhi kepentingan tersebut.
Namun rektor dan birokrasi kampus bukan berarti seperti
boneka yang tak berdaya dan tak perlu dipersalahkan atas
kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Keputusan mereka
memilih untuk menjadi perpanjangan tangan dan berdidiri di
sisi kelas berkuasa, dengan demikian telah menjadikan mereka
bagian dari kelas berkuasa. Oleh karenanya perlawanan
terhadap mereka adalah ekspresi dari perlawanan terhadap
kelas berkuasa dan sistem yang ada di belakangnya.
Masalah-masalah yang menumpuk di lingkungan kampus
inilah yang menuntut perlunya persatuan perjuangan
mahasiswa untuk melakukan gerakan perlawanan demi
mengubah kampus dan menggilas sistem yang menindas ini
sampai ke akar-akarnya. Sekat-sekat yang dibangun oleh
senioritas (senior-junior) sudah semestinya kita buang jauh-
jauh, terlebih ketika mahasiswa seluruh dunia menghadapi
sebuah ancaman universal, yaitu kapitalisme.
Tidak cukup sampai di situ saja, karena kepentingan
kapitalisme untuk meraup keuntungan sebesar-sebesarnya dan
kontrol kapitalis atas alat-alat produksi memungkinkan mereka
untuk tidak hanya mendominasi di satu sektor kehidupan saja,
melainkan semua sektor kehidupan rakyat (sektor buruh, tani,
mahasiswa dan rakyat miskin lainnya), maka gerakan
perlawanan mahasiswa sudah seharusnya tidak hanya di
konsentrasikan di dalam kampus saja. Gerkan mahasiswa
harus terlibat aktif bersolidaritas dengan kekuatan sektor
gerakan rakyat lainnya guna menumbangkan sistem
kapitalisme.
Solidaritas yang dibangun ini haruslah solidaritas yang bersifat
horizontal, yang membagi resiko kepada seluruh orang yang
terlibat dalam gerakan, dan tidak hanya dengan menjadi
komentator yang duduk di belakang panggung yang hanya bisa
menanyakan macam-macam tapi tidak pernah membela
sesuatu apapun. Sejarah telah banyak memberikan pelajaran
kepada kita, hanya dengan cara seperti itulah tujuan untuk
menggilas tatanan masyarakat kapitalis akan terbuka lebar.
Untuk mengakhiri tulisan ini, saya ingin mengutip kata-kata
Trotsky tentang gerakan mahasiswa:
“Kaum borjuis menghargai gerakan mahasiswa dengan setengah
setuju, setengah memperingatkan; kalau para pemuda
mengadakan sedikit guncangan terhadap birokrasi monarkis,
hal itu tidak terlalu jelek, selama ‘anak-anak itu’ tidak bergerak
terlalu jauh dan tidak membangkitkan perjuangan keras dari
massa.” (Trotsky, Revolusi Spanyol 1931-39).
Selamat datang mahasiswa baru!
Panjang umur persatuan rakyat!
Panjang umur solidaritas!
Lawan senioritas!
[boleh dicetak dan diperbanyak tanpa izin.]
LPM DAUNJATI
Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung,
Jalan Buah Batu No. 212, Kota Bandung, Jawa Barat
Anda mungkin juga menyukai
- Parenting JepangDokumen6 halamanParenting JepangBlog TravelingBelum ada peringkat
- TEORI BIROKRASI LENINDokumen14 halamanTEORI BIROKRASI LENINvina HermawatiBelum ada peringkat
- ProfilDokumen10 halamanProfilAnonymous u9SDgyihGBelum ada peringkat
- SEHAT_KERJADokumen59 halamanSEHAT_KERJAAnggi Setiawan100% (1)
- Rundown Acara Akad Nikah and Resepsi FebryDokumen5 halamanRundown Acara Akad Nikah and Resepsi FebryRahmatulloh STBelum ada peringkat
- Tugas Kemitraan - Kel. 4 KIMIA FARMA RevDokumen37 halamanTugas Kemitraan - Kel. 4 KIMIA FARMA Revlucia rosdiana damanikBelum ada peringkat
- Laporan Kegiatan Field StudyDokumen4 halamanLaporan Kegiatan Field Studywina widiawatiBelum ada peringkat
- Resensi Cerita Negara CentengDokumen2 halamanResensi Cerita Negara CentengRaffi SanjayaBelum ada peringkat
- Gerakan Sosial Dan Perubahan Sosial Oleh Mustain Mashud PDFDokumen20 halamanGerakan Sosial Dan Perubahan Sosial Oleh Mustain Mashud PDFAhmad SyarifudinBelum ada peringkat
- Metodologi Feminis untuk Penelitian SosialDokumen179 halamanMetodologi Feminis untuk Penelitian SosialAyudiah UprianingsihBelum ada peringkat
- Dampak Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Kuba Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Amerika Serikat Dengan Negaranegara Amerika LatinDokumen109 halamanDampak Embargo Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Kuba Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Amerika Serikat Dengan Negaranegara Amerika LatinekopaputunganBelum ada peringkat
- MARXISME DASARDokumen25 halamanMARXISME DASARdinanty hayuningratBelum ada peringkat
- Kritik Teori Sebagai Masalah Ilmu SosialDokumen8 halamanKritik Teori Sebagai Masalah Ilmu SosialAhmad Subhan100% (1)
- P3K TersedakDokumen21 halamanP3K TersedakyoeliaBelum ada peringkat
- Dasar-RJPDokumen12 halamanDasar-RJPherri herriansyahBelum ada peringkat
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)Dokumen7 halamanRencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)sri coxBelum ada peringkat
- Materialisme Dialektika HistorisDokumen41 halamanMaterialisme Dialektika HistorisNosyrf AjiBelum ada peringkat
- P R O P O S A L ApotekDokumen18 halamanP R O P O S A L ApotekSandyOctavianusLBelum ada peringkat
- MDH Pengantar Materialisme DialektikaDokumen22 halamanMDH Pengantar Materialisme DialektikaRamdani la InduBelum ada peringkat
- Teori Pergerakan Sosial by Robert MirselDokumen278 halamanTeori Pergerakan Sosial by Robert MirselsandiBelum ada peringkat
- Pengantar MarxismeDokumen37 halamanPengantar MarxismeZaiNuddin JheeinBelum ada peringkat
- PKWTDokumen16 halamanPKWTunggul bimaBelum ada peringkat
- PERUBAHAN SOSIALDokumen6 halamanPERUBAHAN SOSIALAteng ScoutBelum ada peringkat
- MAO TENTANG KONTRADIKSIDokumen34 halamanMAO TENTANG KONTRADIKSISurachMan MamanBelum ada peringkat
- Tugas Tutorial 1 SPMDokumen8 halamanTugas Tutorial 1 SPMwidiastamaBelum ada peringkat
- MeningkatkanHasilBelajarDokumen34 halamanMeningkatkanHasilBelajarAmaliyahnurul 30Belum ada peringkat
- Buku Ekonomi Pembangunan 2020 v02Dokumen122 halamanBuku Ekonomi Pembangunan 2020 v02cepi juniarBelum ada peringkat
- TRAUMATIK SERVIKALDokumen10 halamanTRAUMATIK SERVIKALErnaBelum ada peringkat
- Bagian Inti Teknik Penulisan SkripsiDokumen68 halamanBagian Inti Teknik Penulisan SkripsiKuliner Ning FiaBelum ada peringkat
- Teori & Filsafat PolitikDokumen3 halamanTeori & Filsafat PolitikMuhammad Iqbal Saputra50% (2)
- 3154 - Filsafat HukumDokumen268 halaman3154 - Filsafat Hukumrafida fajar ayuBelum ada peringkat
- Bersatu Untuk Menyelesaikan Tuntutan Revolusi Agustus 1945 - Aidit (1956)Dokumen53 halamanBersatu Untuk Menyelesaikan Tuntutan Revolusi Agustus 1945 - Aidit (1956)Amorfati Munggaran100% (2)
- Business PlanDokumen10 halamanBusiness PlanClaudia WinataBelum ada peringkat
- MEMBENTUK LIGA KOMUNISDokumen16 halamanMEMBENTUK LIGA KOMUNISIrsyad MahmudBelum ada peringkat
- Teori Kelas Atas dan BawahDokumen6 halamanTeori Kelas Atas dan BawahMuhammad rohmadinBelum ada peringkat
- Modul Cara Menulis OpiniDokumen5 halamanModul Cara Menulis OpiniFirmansyah MohammadBelum ada peringkat
- Kelayakan BisnisDokumen40 halamanKelayakan BisnisImprovindo MajuBelum ada peringkat
- Rangkuman Kepribadian IIDokumen15 halamanRangkuman Kepribadian IIMeilistianaBelum ada peringkat
- Pengertian BelajarDokumen31 halamanPengertian BelajarRizky Lega pratamaBelum ada peringkat
- Kasus BBLRDokumen24 halamanKasus BBLRmirellagresyalliBelum ada peringkat
- Djalan Keluar Dari Krisis Ekonomi - Ir. Sakirman (1953)Dokumen19 halamanDjalan Keluar Dari Krisis Ekonomi - Ir. Sakirman (1953)Amorfati MunggaranBelum ada peringkat
- Tugas 2 - PPN Dan PPNBM - Glorio Theodore - 041306848Dokumen2 halamanTugas 2 - PPN Dan PPNBM - Glorio Theodore - 041306848gloryo theodoreBelum ada peringkat
- Ernest Mandel Teori Negara Marxis (1969)Dokumen27 halamanErnest Mandel Teori Negara Marxis (1969)Satrio Putra PrasetyoBelum ada peringkat
- Hikayat Kadiroen - Semaoen (1920)Dokumen99 halamanHikayat Kadiroen - Semaoen (1920)Amorfati Munggaran100% (1)
- Analisis Saham ICBP Menggunakan Pendekatan Nilai Relatif dan IntrinsikDokumen31 halamanAnalisis Saham ICBP Menggunakan Pendekatan Nilai Relatif dan IntrinsikYour FlixBelum ada peringkat
- GRI G4 Materialitas Prinsip dan Penentuan Aspek Penting Laporan KeberlanjutanDokumen9 halamanGRI G4 Materialitas Prinsip dan Penentuan Aspek Penting Laporan Keberlanjutanemail daringBelum ada peringkat
- Menulis Opini yang BerdampakDokumen11 halamanMenulis Opini yang BerdampakAhmad YaniBelum ada peringkat
- 5 6125177427762085917Dokumen544 halaman5 6125177427762085917lukmanul hakimBelum ada peringkat
- Sejarah Filsafat IlmuDokumen62 halamanSejarah Filsafat IlmuNafila AzmiBelum ada peringkat
- OPTIMASI SKRIPSIDokumen17 halamanOPTIMASI SKRIPSIMuhammad Gilang BhaskoroBelum ada peringkat
- Awalil Rizky & Nasyith Majidi - Bank Bersubsidi Yang MembebaniDokumen298 halamanAwalil Rizky & Nasyith Majidi - Bank Bersubsidi Yang Membebaniخير الأنام الحبشى100% (7)
- Otoritas Kampus Dan Tumpulnya Budaya Kritis MahasiswaDokumen4 halamanOtoritas Kampus Dan Tumpulnya Budaya Kritis MahasiswaMudawis SolemanBelum ada peringkat
- Pendidikan Yang MemerdekakanDokumen4 halamanPendidikan Yang MemerdekakanAndi Febryan RamadhaniBelum ada peringkat
- Peran Pemuda Dalam Pembangunan NasionalDokumen16 halamanPeran Pemuda Dalam Pembangunan NasionalMbah Cendana Seneng Mendem80% (10)
- Peranan Mahasiswa Dalam Mempertahankan PancasilaDokumen0 halamanPeranan Mahasiswa Dalam Mempertahankan PancasilaHusnul UmamBelum ada peringkat
- Literasi Masa KiniDokumen24 halamanLiterasi Masa KinihumaidhalfarisiBelum ada peringkat
- Essay PancasilaDokumen2 halamanEssay PancasilaMUHAMMAD AZIZ FIKRI 097Belum ada peringkat
- OspekDokumen13 halamanOspekArif Joko WicaksonoBelum ada peringkat
- Gerakan Mahasiswa Masa LaluDokumen7 halamanGerakan Mahasiswa Masa Laluanita diyanahBelum ada peringkat
- KEMAHASISWAANDokumen12 halamanKEMAHASISWAANCannabis SativaBelum ada peringkat
- 03 Perawatan Sistem Bahan Bakar KonvensionalDokumen57 halaman03 Perawatan Sistem Bahan Bakar KonvensionalMhd AdityaBelum ada peringkat
- Korosipadamobil Bhramantya UploadDokumen30 halamanKorosipadamobil Bhramantya UploadIkhwan DarmabaktiBelum ada peringkat
- Korosipadamobil Bhramantya UploadDokumen30 halamanKorosipadamobil Bhramantya UploadIkhwan DarmabaktiBelum ada peringkat
- 001 Definisi Tune Up Perawatan Berkala ServiceDokumen8 halaman001 Definisi Tune Up Perawatan Berkala ServiceRahmat Desman KotoBelum ada peringkat
- 04 Perawatan Timing BeltDokumen16 halaman04 Perawatan Timing BeltMhd AdityaBelum ada peringkat
- Tugas 5 AktuariaDokumen3 halamanTugas 5 AktuariaMhd AdityaBelum ada peringkat
- IGNITION SYSTEMDokumen41 halamanIGNITION SYSTEMMhd AdityaBelum ada peringkat
- Solusi Auto Id Untuk Car Service 443 PDFDokumen6 halamanSolusi Auto Id Untuk Car Service 443 PDFMuhammad SugariBelum ada peringkat
- Tugas 4 AktuariaDokumen2 halamanTugas 4 AktuariaMhd AdityaBelum ada peringkat
- IGNITION SYSTEMDokumen41 halamanIGNITION SYSTEMMhd AdityaBelum ada peringkat
- ID Analisa Pengaruh Bahan Dasar Pelumas TerDokumen8 halamanID Analisa Pengaruh Bahan Dasar Pelumas TerMhd AdityaBelum ada peringkat
- Materi KB 2Dokumen5 halamanMateri KB 2Iwan MagLiaBelum ada peringkat
- Tugas 3 AktuariaDokumen3 halamanTugas 3 AktuariaMhd AdityaBelum ada peringkat
- Bahan Ajar 7 Transmisi Otomatis Dengan Kontrol ElektronikDokumen24 halamanBahan Ajar 7 Transmisi Otomatis Dengan Kontrol ElektronikMhd AdityaBelum ada peringkat
- MI - 3 - Konsep ProdukDokumen15 halamanMI - 3 - Konsep ProdukMhd AdityaBelum ada peringkat
- RPP AbsDokumen5 halamanRPP AbsMhd AdityaBelum ada peringkat
- Makalah 123Dokumen21 halamanMakalah 123PADMAWATIBelum ada peringkat
- RPP Sistem KemudiDokumen13 halamanRPP Sistem KemudiMhd AdityaBelum ada peringkat
- Perbaikan Sistem KendaraanDokumen47 halamanPerbaikan Sistem KendaraanMhd AdityaBelum ada peringkat
- Spesifikasi XeniaDokumen23 halamanSpesifikasi XeniaMhd AdityaBelum ada peringkat
- Laporan Pembuatan Tools BoxDokumen3 halamanLaporan Pembuatan Tools BoxErwan EsteBelum ada peringkat
- RPP Kelas XI KD. 3.1 1 PertemuanDokumen29 halamanRPP Kelas XI KD. 3.1 1 PertemuanMhd AdityaBelum ada peringkat
- Modul 1 KB 1 PDFDokumen23 halamanModul 1 KB 1 PDFPandu PandawaBelum ada peringkat
- RPP Sistem KemudiDokumen13 halamanRPP Sistem KemudiMhd AdityaBelum ada peringkat
- RPP Kelas XI KD. 3.1 1 PertemuanDokumen29 halamanRPP Kelas XI KD. 3.1 1 PertemuanMhd AdityaBelum ada peringkat