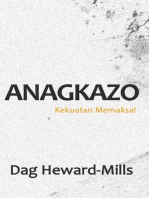Rasa Malu
Diunggah oleh
Arif YudistiraHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Rasa Malu
Diunggah oleh
Arif YudistiraHak Cipta:
Format Tersedia
Rasa Malu
Luqman Al-Hakim pernah ditanya oleh seseorang.
“Apa satu hal baik dalam diri manusia?.
“Agama,” jawab Luqman.
“Kalau dua?” tanya orang itu.
“Agama dan Harta.”
“Kalau tiga?”
“Agama, Harta, dan Rasa Malu.”
Runtuh apa yang disebut “manusia” saat ia kehilangan rasa “malu”nya. Harkat serta
martabat manusia menjadi tanggal bila ia menghilangkan satu sifat ini. Dalam kebudayaan
timur, rasa malu amat dijunjung tinggi. Malu bila berkata tidak sopan, malu bila tidak hormat
kepada yang tua, malu bila berperilaku seenaknya di muka umum. Agama mengajarkan malu
sebagai nilai yang berharga dari manusia. Dalam hadist Bukhari, “Nabi adalah yang lebih
pemalu dari gadis perawan yang dipingit di kamarnya.” Seorang manusia teladan, panglima
perang, manusia paling agung memiliki sifat keras pemberani, tetapi juga amat pemalu.”
Ada semacam “batas”. Malu, adalah batas. Bila ia diterabas, maka benarlah apa yang
disabdakan Nabi dalam hadit Bukhari yang lain yang berbunyi : “Jika kamu tidak malu,
berbuatlah sesukamu.” Tuhan sendiri sangat malu melihat hamba-Nya yang memohon ampun
kepadanya. Ia amat malu untuk menyiksa hamba-Nya.
Danarto di bukunya Cahaya Rasul (1999) mengutip hadist Nabi : “Sesungguhnya Allah
selalu melihat orangtua renta, tiap pagi dan sore, dan berkata, “Wahai hamba-Ku, telah tua
usiamu, Makinkusut kulitmu. Makin rapuh tulangmu. Makin dekat ajalmu. Makin dekat
kedatanganmu kehadirat-Ku. Malulah pada-Ku, maka Aku akan malu oleh ketuaanmu untuk
menyiksamu di neraka.”
Dalam hadist Qudsi, Tuhan berfirman : “Kasih-Ku, mendahului murka-Ku.” Tuhan amat
sangat sayang kepada hamba-Nya bila ia memiliki rasa “malu”. Panggung peradaban manusia
tumbuh dan kuat karena memiliki rasa “malu”. Semakin beradab suatu bangsa, semakin ia
memiliki tata susila yang baik. Semakin tinggi adab manusia, semakin ia pemalu untuk
berbuat jahat dan dosa. Ibnu Qayyim Al Jauziyah menjelaskan bahwa kata malu berasal dari
kata al-hayah (hidup), siapa yang tidak memiliki hayah, berarti ia mayat di dunia. Dan di
akhirat dia akan sengsara.
Dalam dunia yang Maha luas ini, rasa malulah yang membuat kita menjadi besar
sekaligus kecil. Di tengah jagat raya yang luas ini, kita adalah setitik noktah. Untuk itulah,
rasanya tak pantas kita untuk menyombongkan diri lagi angkuh. Tetapi rasa malu untuk
berbuat salah dan dosa kepada Tuhan yang mengangkat kita menjadi mulia bersama-Nya.
Saat “rasa malu” tanggal, bukan cuma baju yang sobek, tetapi juga hati menjadi
terkoyak-koyak karena tidak lagi bisa membedakan antara yang haq dan yang batil. Antara
yang benar dengan yang “sepertinya benar”. Malu membuat hamba merasa rela untuk
menjalankan perintah serta menjauhi larangan. Hamba yang merasa dikasihi Tuhan tahu,
Tuhan amat dekat dengan-Nya.
Di jaman yang runyam seperti sekarang ini, “rasa malu” kian tanggal. Orang Jawa
menyebut “Satrio ilang wirange” (Kesatria hilang rasa malunya). Pejabat tidak lagi merasa
malu menyalahgunakan wewenangnya. Anak tidak lagi memiliki “rasa malu” kepada
orangtuanya. Kejahatan dan angkaramurka seolah dengan tanpa rasa malu dipertontonkan di
hadapan kita.
Orang semakin berilmu, semakin menanggalkan “rasa malu”nya. Kejahatan dan nafsu
seolah diumbar tanpa batas. Orang tidak malu lagi melakukan perselingkuhan, melakukan
skandal, dan kemaksiatan. Gelar Profesor, gelar doktor tidak membuat seorang semakin
menajamkan “malu” untuk berbuat serong.
Dalam zaman yang linglung itulah kita seperti hendak memperbaiki. Bahwa
kecerdasan, intelektual, dan segala gelar yang kita peroleh tiada memiliki arti saat “malu”
telah kita tanggalkan. Namun kita melihat kejahatan dan juga korupsi semakin menjadi.
Orang tidak lagi risih memegang uang yang bukan milik sendiri. Orang tidak lagi merasa
malu, saat aib menjadi tontonan di setiap harinya.
Ada kisah menarik tentang “rasa malu” dari Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas
kedatangan pencuri di malam hari, ia mengendap-endap dan masuk ke rumahnya. Abu
Nawas mengetahui kejadian itu, namun apa yang dilakukan Abu Nawas?. Ia malah sembunyi
di sudut rumahnya. Pencuri itu fokus kesana-kemari dan tidak ada barang yang berharga
yang dimiliki Abu Nawas. Lalu pencuri itu melihat Abu Nawas. “Hei, mengapa kamu malah
sembunyi disitu?”. Abu Nawas menjawab : “Aku malu, karena tidak ada barang berharga satu
pun yang bisa kuberikan padamu.” Pencuri itu pun justru kecewa dan pergi, namun ia lega
Abu Nawas tidak berteriak padanya sehingga warga tidak memukulinya.
Saat orang memiliki “malu”, maka ia akan semakin berhati-hati dalam hidupnya. Ia
tahu apa yang harus disembunyikan dan tampakkan. Ia semakin mengerti apa yang sejatinya
perlu dilihat oleh orang dengan apa yang tidak. Ia sadar betul, kapan ia akan menunjukkan
kepada liyan mana yang harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mana yang harus
terang-terangan. Sifat malu membawa kita pada sifat arif, penuh pertimbangan dan tidak
tergesa-gesa.
Para Nabi, para Rasul, serta para sufi adalah seorang pemalu. Hari-harinya nampak
dijalani dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Mereka malu, saat Tuhan tidak berkenan
terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka malu, apa yang mereka lakukan tidak sesuai
dengan perkenan Tuhan. Rasa malu membawa mulut mereka basah dengan dzikir. Zuhud
dan sikapnya yang tidak tamak hadir karena “malu” kepada Tuhan-Nya.
Saat kita melihat orang gila di tengah-tengah kita, kita tersentak, terperangah,
sembari menggumam, “ora due isin” (tidak tahu malu)!. Dan kita tahu, itu pula yang akan kita
ucapkan pada koruptor, dan siapapun yang berbuat nista ketahuan boroknya. Dalam dunia
mereka dipermalukan, dihukum dengan aneka rupa hukuman. Dan siapakah penghukum yang
adil dari dosa-dosa kita?. Semoga Tuhan mengampuni kita dan menabur kasih-Nya. Tentu
saat kita masih menyimpan “rasa malu” kepada-Nya.
Anda mungkin juga menyukai
- SombongDokumen9 halamanSombongNanda Hanyfa MaulidaBelum ada peringkat
- Jadilah Manusia Yang Memiliki Rasa Malu Kepada AllahDokumen4 halamanJadilah Manusia Yang Memiliki Rasa Malu Kepada AllahSaputra AndiBelum ada peringkat
- Resep Menjadi WaliyullohDokumen19 halamanResep Menjadi WaliyullohLATIFBelum ada peringkat
- Budaya Malu Dalam Perspektif IslamDokumen15 halamanBudaya Malu Dalam Perspektif IslamT. KURNIA IROHIMBelum ada peringkat
- MaluDokumen9 halamanMaluHeriyantoalamsyahBelum ada peringkat
- MAKALAHDokumen4 halamanMAKALAHJailani YacobBelum ada peringkat
- MaluDokumen18 halamanMaluHAMZAH SULTHANBelum ada peringkat
- Melihat Allah Dengan Tawadhu'Dokumen3 halamanMelihat Allah Dengan Tawadhu'Safarudin AhmadBelum ada peringkat
- KesombonganDokumen4 halamanKesombonganBagja GumelarBelum ada peringkat
- Al KibruDokumen4 halamanAl KibruShofwil Widad AliBelum ada peringkat
- Makalah AanDokumen22 halamanMakalah AanAs-syahrul Al-RamadhanBelum ada peringkat
- Makalah Hadist Kelompok 3Dokumen7 halamanMakalah Hadist Kelompok 3MartinaBelum ada peringkat
- Sifat MaluDokumen2 halamanSifat MaluZicky AchmadBelum ada peringkat
- AkhlakDokumen21 halamanAkhlakIndahSyafriAnnisaBelum ada peringkat
- TazkirahDokumen39 halamanTazkirahRaja SolahudinBelum ada peringkat
- Makalah Akidah Akhlak (Malu)Dokumen6 halamanMakalah Akidah Akhlak (Malu)ARSALAM 01Belum ada peringkat
- Qiraatul Kutub Kel 1Dokumen4 halamanQiraatul Kutub Kel 1Muhammad Fawas Ihsan Ramadhani RamadhaniBelum ada peringkat
- Takut Kepada AllahDokumen4 halamanTakut Kepada AllahfitrianiBelum ada peringkat
- Malu Dalam AlquranDokumen1 halamanMalu Dalam Alquranadhan ditBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen10 halamanBab I Pendahuluannan saputra saputraBelum ada peringkat
- Sifat UjubDokumen7 halamanSifat UjubnsBelum ada peringkat
- BAHAGIA Dan Mencintai Diri SendiriDokumen5 halamanBAHAGIA Dan Mencintai Diri SendiriLamiasih LamiasihBelum ada peringkat
- ZALIMDokumen30 halamanZALIMmegareksa100% (1)
- Sifat Malu Dalam Pandangan IslamDokumen6 halamanSifat Malu Dalam Pandangan IslamMEKKAHBelum ada peringkat
- Ceramah KebodohanDokumen6 halamanCeramah Kebodohanade NugrahaBelum ada peringkat
- Anda Bisa Baynagkan Bagaimana Jahatnya Kedua Anak Gadis Nabi Lot Yang Dengan Sengaja Membuat Bapak Mereka Mabuk Agar Bapak Mereka Mau Meniduri Mereka BerduaDokumen5 halamanAnda Bisa Baynagkan Bagaimana Jahatnya Kedua Anak Gadis Nabi Lot Yang Dengan Sengaja Membuat Bapak Mereka Mabuk Agar Bapak Mereka Mau Meniduri Mereka BerduateukuBelum ada peringkat
- MixDokumen39 halamanMixAhmadBelum ada peringkat
- Bedah Buku Pemimpin Yang TuhanDokumen11 halamanBedah Buku Pemimpin Yang TuhanViqi alBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen10 halamanBab IiAbi Taufiq MatangkuliBelum ada peringkat
- Menjinakkan KesombonganDokumen7 halamanMenjinakkan KesombonganFendi IrawanBelum ada peringkat
- PERBUATAN DOSA DAN AIB HARUS DIRAHASIAKAN 04 Nov 2022Dokumen3 halamanPERBUATAN DOSA DAN AIB HARUS DIRAHASIAKAN 04 Nov 2022kuakabawetan6Belum ada peringkat
- Empat Mutiara Pada Diri ManusiaDokumen6 halamanEmpat Mutiara Pada Diri ManusiaIzzuddin SiregarBelum ada peringkat
- Malu Dalam IslamDokumen2 halamanMalu Dalam IslamShucy Larasati100% (1)
- Bokep HaramDokumen1 halamanBokep HaramMuhammad JunaidiBelum ada peringkat
- 76 Dosa Besar Yang Sering Dianggap BiasaDokumen14 halaman76 Dosa Besar Yang Sering Dianggap BiasamarwaBelum ada peringkat
- Mari Berkongsi (Siri 20)Dokumen105 halamanMari Berkongsi (Siri 20)Wang LingBelum ada peringkat
- Muru'Ah Wanita MuslimahDokumen55 halamanMuru'Ah Wanita MuslimahNur fajrina TamimiBelum ada peringkat
- Materi HIZBUSY SYAITHONDokumen14 halamanMateri HIZBUSY SYAITHONAchmad Hidayat100% (1)
- 2 Malu Berbuat DosaDokumen17 halaman2 Malu Berbuat DosaShabrina SATER KEB REGBelum ada peringkat
- BAB 18 Keasyikan Yang Menghancurkan KeluargaDokumen36 halamanBAB 18 Keasyikan Yang Menghancurkan KeluargaDanang Sulistyo100% (1)
- AL-HAYA Malu PemaluDokumen17 halamanAL-HAYA Malu PemaluGudang Skripsi, KTI Dan MakalahBelum ada peringkat
- Makalah Sifat SombongDokumen8 halamanMakalah Sifat Sombongmuslim_hur45100% (2)
- DunguDokumen7 halamanDunguMochamad Reza NudiansyahBelum ada peringkat
- TazkirahDokumen8 halamanTazkirahSyifaRosli100% (5)
- Makalah Hadist Tentang Malu Sebagian Dari ImanDokumen8 halamanMakalah Hadist Tentang Malu Sebagian Dari ImanRachmadNeoddyen100% (1)
- Sombong Atau Dalam Istilah ArabnyaDokumen3 halamanSombong Atau Dalam Istilah ArabnyafachruddinyaBelum ada peringkat
- Teks Pidato AgamaDokumen12 halamanTeks Pidato AgamaAnjun TiaBelum ada peringkat
- Jumat 9 September 2022 Sifat MaluDokumen5 halamanJumat 9 September 2022 Sifat MaluAhmed AkifBelum ada peringkat
- Khutbah 23 - Jelmaan Amal ManuasiaDokumen3 halamanKhutbah 23 - Jelmaan Amal ManuasiaMunzili MahmunBelum ada peringkat
- Hilangnya Budaya MaluDokumen25 halamanHilangnya Budaya MaluSlamet MunawarBelum ada peringkat
- Ya Allah Kenalkan Aku Dengan DirikuDokumen3 halamanYa Allah Kenalkan Aku Dengan DirikuHusni Fansury NasutioneBelum ada peringkat
- Bab 10 Perilaku TercelaDokumen15 halamanBab 10 Perilaku TercelaAllen ReynaldiBelum ada peringkat
- Kata Kata Hikmah 1Dokumen22 halamanKata Kata Hikmah 1Norrashidah MokhtarBelum ada peringkat
- Membersihkan Hati Dari Berprasangka Buruk Kepada AllahDokumen28 halamanMembersihkan Hati Dari Berprasangka Buruk Kepada AllahAyuCaturWardaniBelum ada peringkat
- Cinta Dunia Dan Takut MatiDokumen17 halamanCinta Dunia Dan Takut MatiHannani YunusBelum ada peringkat
- Membangun Generasi Masa Depan Yang Intelek Dan Qur'AniDokumen11 halamanMembangun Generasi Masa Depan Yang Intelek Dan Qur'Anisalmanalfatah100% (4)
- Kumpulan Artikel Motivasi dan SpiritualitasDari EverandKumpulan Artikel Motivasi dan SpiritualitasPenilaian: 2 dari 5 bintang2/5 (1)
- Apa Artinya Menjadi Cerdik Seperti UlarDari EverandApa Artinya Menjadi Cerdik Seperti UlarPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (15)
- Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di IndonesiaDokumen350 halamanIdeologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di IndonesiaEndry AbidinBelum ada peringkat
- Merayakan Indonesia RayaDokumen86 halamanMerayakan Indonesia RayaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Kerja Seorang IlmuwanDokumen5 halamanKerja Seorang IlmuwanArif YudistiraBelum ada peringkat
- Kewajiban Perempuan Dalam IslamDokumen4 halamanKewajiban Perempuan Dalam IslamArif YudistiraBelum ada peringkat
- Berbaik Sangka Kepada AllahDokumen8 halamanBerbaik Sangka Kepada AllahArif YudistiraBelum ada peringkat
- Nabi Perempuan Dalam IslamDokumen5 halamanNabi Perempuan Dalam IslamArif YudistiraBelum ada peringkat
- Target Dan Positioning SekolahDokumen6 halamanTarget Dan Positioning SekolahArif YudistiraBelum ada peringkat
- Duka Dan Nestapa para PencintaDokumen2 halamanDuka Dan Nestapa para PencintaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Presiden Perempuan, Mimpi Di Siang BolongDokumen2 halamanPresiden Perempuan, Mimpi Di Siang BolongArif YudistiraBelum ada peringkat
- Buku Itu SimbolikDokumen3 halamanBuku Itu SimbolikArif YudistiraBelum ada peringkat
- Anak Dan Peranan KitaDokumen3 halamanAnak Dan Peranan KitaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Zizek Menertawakan KitaDokumen3 halamanZizek Menertawakan KitaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Kerja Seorang SenimanDokumen3 halamanKerja Seorang SenimanArif YudistiraBelum ada peringkat
- Respon Islam Terhadap BencanaDokumen3 halamanRespon Islam Terhadap BencanaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Pentingnya Pendidikan Keluarga. JoglosemarDokumen5 halamanPentingnya Pendidikan Keluarga. JoglosemarArif YudistiraBelum ada peringkat
- Politik Dan KeadabanDokumen3 halamanPolitik Dan KeadabanArif YudistiraBelum ada peringkat
- Akar Masalah Pendidikan IslamDokumen3 halamanAkar Masalah Pendidikan IslamArif YudistiraBelum ada peringkat
- Ajak Anak Belajar Qur'an Sedini MungkinDokumen2 halamanAjak Anak Belajar Qur'an Sedini MungkinArif YudistiraBelum ada peringkat
- Filsafat Itu Mkan KrupukDokumen4 halamanFilsafat Itu Mkan KrupukArif YudistiraBelum ada peringkat
- Buku Bacaan Anak Dan Pembentukan KarakterDokumen5 halamanBuku Bacaan Anak Dan Pembentukan KarakterArif YudistiraBelum ada peringkat
- Bencana Alam Dan AnakDokumen11 halamanBencana Alam Dan AnakArif YudistiraBelum ada peringkat
- Nasib Sastra Di Sekolah KitaDokumen6 halamanNasib Sastra Di Sekolah KitaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Problem Pendidikan Dasar Kita. JoglosemarDokumen4 halamanProblem Pendidikan Dasar Kita. JoglosemarArif YudistiraBelum ada peringkat
- Dongeng Dan MimesisDokumen3 halamanDongeng Dan MimesisArif YudistiraBelum ada peringkat
- Anak Dan Obsesi Pendidikan KitaDokumen4 halamanAnak Dan Obsesi Pendidikan KitaArif YudistiraBelum ada peringkat
- Ajak Anak Belajar Qur'an Sedini MungkinDokumen2 halamanAjak Anak Belajar Qur'an Sedini MungkinArif YudistiraBelum ada peringkat
- Ekstrakurikuler Jurnalistik Dan PeningkatanDokumen10 halamanEkstrakurikuler Jurnalistik Dan PeningkatanArif YudistiraBelum ada peringkat
- Ihwal Pendidikan Budi PekertiDokumen3 halamanIhwal Pendidikan Budi PekertiArif YudistiraBelum ada peringkat
- Sekolah Dan AnakDokumen4 halamanSekolah Dan AnakArif YudistiraBelum ada peringkat