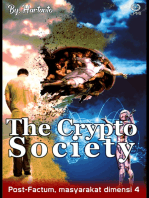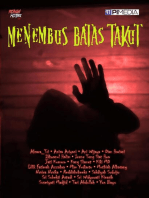Subaltern dan Historiografi
Diunggah oleh
Dhika PutraJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Subaltern dan Historiografi
Diunggah oleh
Dhika PutraHak Cipta:
Format Tersedia
Dhika Purnama Putra
Representation of the Subaltern: Spivak and Historiography
Y. T. Vinayaraj
Resensi
Subaltern merupakan kata yang digunakan oleh Gramsci sebagai penunjuk terhadap kelompok kelas
bawah. Subaltern diartikan sebagai kelompok dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni dari
kelas-kelas yang berkuasa. Kelas-kelas yang berkuasa tersebut melakukan eksploitasi dan penindasan
terhadap kelompok yang termarjinalkan. Makna “subaltern” yang dimaksud oleh Spivak adalah
mereka yang bukan elite dan kaum yang tidak bisa bicara dalam wacana kolonialisme.
Kaum subaltern adalah mereka yang selalu dalam posisi direpresentasikan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, seperti pemerintah, politisi, birokrat, dan aktivis kemasyarakatan. Mereka tidak
pernah bisa merepresentasikan dirinya karena kurang memiliki akses bicara di arena publik.
Kaum subaltern adalah kelompok yang selama ini selalu dalam posisi tidak
berdaya (disempowered), tidak pernah bisa berbicara di media publik (disenfranchised), dan bersifat
marjinal. Golongan ini dapat meliputi kelompok pekerja, petani, perempuan, difabel, rakyat, wong
cilik. “jika subaltern berbicara, dan itu didengar; maka dia bukan subaltern. "Subaltern berbicara,
tetapi, dia berpendapat," itu tidak terdengar "dan tentu saja" itu tidak bisa didengar ". Maka dalam
kajian ini mempertanyakan keterwakilan suara masyarakat kelas bawah oleh kelas-kelas yang
berkuasa.
Spivak menyebutkan, subaltern merupakan kelompok-kelompok yang mengalami penindasan oleh
kelas penguasa. Spivak menekankan bahwa eksploitasi terhadap kaum tertindas disebabkan adanya
dominasi struktural. Dominasi struktural tersebut muncul dari suatu sistem pembagian kerja
internasional. Dalam sistem pembagian kerja internasional, segala bentuk representasi harus datang
dari posisi istimewa atau kekuasaan. Posisi istimewa atau kekuasaan tersebut muncul karena adanya
kesempatan, pendidikan, kewarganegaraan, kelas, ras, gender dan lokasi. Dalam praktik kolonialisme,
suara masyarakat terjajah dalam menunjukkan eksistensinya sering terbendung oleh kelas penguasa
yang diciptakan rezim penjajah. Posisi subaltern kemudian selalu tersisih karena proyek penjajahan
akan dilanjutkan oleh masyarakat terjajah lainnya yang mewarisi pola pikir kolonial. Oleh sebab itu,
posisi subaltern akan terus ditekan dengan berbagai praktik penjajahan gaya baru yang terus
direproduksi.
Gayatri Spivak mempertanyakan peran intelektual pasca kolonial yang dianggap mewakili masyarakat
yang mengalami penindasan ataupun ketidakadilan. Spivak mengecam dan memperingatkan kepada
intelektual pasca kolonial tentang bahaya klaim mereka atas suara-suara dari kelompok yang
tertindas. Menurut Spivak, seorang yang intelek tidak mungkin dapat mengklaim dan meromantisir
kemapuan intelektual mereka untuk mencari perhatian dari kelompok kelas bawah demi suatu tujuan
pragmatis. Tindakan-tindakan intelektual tersebut bagi Gayatri Spivak justru bersifat kolonial. Seperti
yang dilakukuan oleh para politikus yang berbicara mengenai kesejahtraan untuk rakyat dalam setiap
kontestasi politik. Menurut Spivak, hal tersebut menyamaratakan atau dalam istilah Gramsci
menghegemoni keberagaman kelompok-kelompok yang tertindas.
Spivak menjawab pertanyaan 'worlding' dan 'othering' dalam historiografi untuk mengungkap
hubungan kekuasaan yang tidak setara yang terkandung dalam representasi Barat Lainnya - 'Dunia
Ketiga' dan Dunia Ketiga Lainnya. Mengkritik keterlibatan postkolonial dan poststruktural untuk
mewakili subaltern, Spivak berpendapat bahwa tidak ada subaltern 'esensialis' yang tidak terwakili
yang dapat mengetahui, berbicara, dan mewakili diri mereka sendiri dalam sejarah, budaya dan
politik. Untuk menyuarakan subaltern dalam penulisan kembali sejarah, Spivakian berada di batas
tengah antara yang subjektif dan objektif.
Suara dari para kaum tertindas atau subaltern tidak akan dapat dicari karena para kaum tertindas
tidak bisa bicara. Oleh karena itu, Spivak mengatakan bahwa kaum intelektual harus hadir sebagai
pendamping atau orang yang mewakili kelompok-kelompok yang tertindas tersebut. Peranan kaum
intelektual sangat penting untuk memperjuangkan kelompok-kelompok subaltern dan seharusnya
bertindak secara nyata tanpa harus merasa mewakili mereka. Spivak menolak segala jenis ide
esensialis tentang subjektivitas subaltern dan menegaskan bahwa tidak ada subjek postkolonial
esensialis yang dapat berbicara dan mengetahui kondisi mereka sendiri.
Pertanyaan tentang 'ketidakterwakilan' dari subaltern selanjutnya diperluas ke pertanyaan gender.
Dengan memfokuskan, perempuan sebagai subaltern, Spivak menegaskan, “dalam rencana
perjalanan subaltern yang dihilangkan ini, jejak perbedaan seksual dilipatgandakan. ”Spivak
memperingatkan feminisme dekonstruksionis Barat agar tidak menjadi 'terlibat dengan feminisme
borjuis esensialis.' Spivak mendesak para feminis 'dunia pertama' untuk belajar berhenti merasa
istimewa sebagai seorang wanita. Apa yang ingin dia lakukan dengan feminisme adalah untuk
menemukan kembali subaltern gender / wanita Dunia Ketiga / wanita marginal dan untuk
menekankan lokasi wanita yang berbeda, tersebar, dan heterogen. Wanita di negara dunia ketiga
adalah sebagai subaltern yang direpresi oleh gender mereka sebagai gender kedua dari sistem
patriarki, dan juga oleh rezim penguasa atau penjajah. Seperti cantoh kasus Satī atau terkenal dengan
istilah Pati Obong adalah praktik pemakaman religius di India. Perempuan yang baru saja menjadi
janda secara sukarela, atau dipaksa, untuk membakar dirinya di atas tumpukan kayu api upacara
kremasi suaminya.
Essai
Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu
pada ketentuan hukum pidana Islam. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Aceh No.
6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap
diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dapat menerapkan beberapa peraturan tambahan yang
bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi
untuk menerapkan peraturan daerah, tetapi Aceh mendapatkan otonomi khusus dengan tambahan
izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Contohnya,
salah satu peraturan daerah (Perda) Aceh lainnya mewajibkan semua umat Muslim di Aceh
mengenakan busana Islami, yang didefinisikan sebagai pakaian yang menutupi aurat yang tidak
tembus pandang, dan tidak menunjukkan bentuk tubuh. Meski bentuk Qanun tersebut berlaku pada
laki-laki dan perempuan, pada praktiknya, pengaturan atas berpakaian terhadap perempuan lebih
represif.
Dalam kasus ini perempuan seperti diposisikan sebagai pondasi negara yang harus dikontrol dalam
setiap kegiatannya, termasuk dalam hal berpakaian. Razia-razia yang dilakukan oleh petugas syariat
yang disebut dengan Wilayatul Hisbah (WH) nyatanya lebih banyak menyasar perempuan ketimbang
lelaki. Perempuan Aceh merupakan bentuk struktur kekuasaan patriarki. Perempuan tidak pernah
menjadi agen mereka sendiri. Mereka adalah semacam kepentingan yang dibungkam kebebasan
mereka dan secara seksual dikontrol oleh orang lain. Perempuan Aceh bisa disebut sebagai subaltern
dalam wacana dominasi patriarki yang terjadi di Indonesia sebagai negara dunia ketiga. Kritik yang
dilakukan oleh Spivak dengan pendekatan melalui postkolonialisme adalah upaya dekonstruksi dari
representasi perempuan sebagai subaltern untuk disuarakan.
Anda mungkin juga menyukai
- SubalternDokumen13 halamanSubalternMoch Zainul ArifinBelum ada peringkat
- Perempuan SpivakDokumen15 halamanPerempuan SpivakMartina Rosmaulina MarbunBelum ada peringkat
- Kekerasan Simbolis Dalam Novel BekisarMerahDokumen8 halamanKekerasan Simbolis Dalam Novel BekisarMerahArumNgestiPalupiBelum ada peringkat
- Pemikiran Gayatri Spivak Tentang Subaltern Dan Refleksinya Pada Kasus Diskriminasi Terhadap Bangsa Moro Di FilipinaDokumen3 halamanPemikiran Gayatri Spivak Tentang Subaltern Dan Refleksinya Pada Kasus Diskriminasi Terhadap Bangsa Moro Di Filipinajacksennainggolan100% (2)
- Essay: 1. Nyoman Kutha Ratna, "Poskolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 205Dokumen7 halamanEssay: 1. Nyoman Kutha Ratna, "Poskolonialisme Indonesia: Relevansi Sastra" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 205DiasBelum ada peringkat
- Esai Dasar Dasar Ilmu SosialDokumen4 halamanEsai Dasar Dasar Ilmu Sosialjian aynBelum ada peringkat
- Poskolonialisme Dan PDokumen6 halamanPoskolonialisme Dan PIchsan HatibBelum ada peringkat
- BAK UMPAN: KELIHATANNYA LEMAH, PADAHAL KUATDokumen20 halamanBAK UMPAN: KELIHATANNYA LEMAH, PADAHAL KUATKowalski D Abdee100% (1)
- Tokoh POSKOLONIALISDokumen4 halamanTokoh POSKOLONIALISFathia Az-ZahraBelum ada peringkat
- MEMPERJUANGKAN HAKDokumen5 halamanMEMPERJUANGKAN HAKMahlisa OktavianaBelum ada peringkat
- Postkolonialisme: Definisi, Sejarah, Dan Kajian SastraDokumen10 halamanPostkolonialisme: Definisi, Sejarah, Dan Kajian SastraJanoval RizkiBelum ada peringkat
- A31119088 Mohamad Ayub Mewengkang - Review - Sejarah Ketatanegaraan - Kelas BDokumen5 halamanA31119088 Mohamad Ayub Mewengkang - Review - Sejarah Ketatanegaraan - Kelas BWinda YantiBelum ada peringkat
- Jejaring KebijakanDokumen11 halamanJejaring Kebijakanahmad dhaniBelum ada peringkat
- Prof. - Parsudi - Suparlan With Cover Page v2Dokumen15 halamanProf. - Parsudi - Suparlan With Cover Page v2Hafida SudirmanBelum ada peringkat
- Dinita Ayu Novela - Perempuan Dan Feminisme-Menyelami Pemikiran Dan Gerakan RA Kartini-Dikonversi PDFDokumen7 halamanDinita Ayu Novela - Perempuan Dan Feminisme-Menyelami Pemikiran Dan Gerakan RA Kartini-Dikonversi PDFhab ibBelum ada peringkat
- Tugas FeminismeDokumen5 halamanTugas FeminismeFesilia MarzukiBelum ada peringkat
- Kenapasii en IdDokumen22 halamanKenapasii en IdSyakira Isyraf QasamahBelum ada peringkat
- Feminisme LiberalDokumen2 halamanFeminisme LiberalCalvin AdityaBelum ada peringkat
- HakMinoritasDokumen17 halamanHakMinoritasDendy FaozanBelum ada peringkat
- Masyarakat Multikultural - 0 PDFDokumen13 halamanMasyarakat Multikultural - 0 PDFmohfarisarfandhyfBelum ada peringkat
- Masyarakat MajemukDokumen7 halamanMasyarakat MajemukIbink RergaBelum ada peringkat
- TEORI POSKOLONIALDokumen23 halamanTEORI POSKOLONIALFauziah sri karmala0% (1)
- 23-Article Text-305-1-10-20181212Dokumen13 halaman23-Article Text-305-1-10-20181212Kurniawatin KurniawatinBelum ada peringkat
- Gayatri Spivak - Kel 10Dokumen14 halamanGayatri Spivak - Kel 10Sigit AdjiBelum ada peringkat
- Mampukah Kaum Pinggiran BersuaraDokumen5 halamanMampukah Kaum Pinggiran BersuaraImamBelum ada peringkat
- Perempuan Dalam Gerakan Kebangsaan PDFDokumen345 halamanPerempuan Dalam Gerakan Kebangsaan PDFVUEnessa Vanessa Untuk EdukasiBelum ada peringkat
- Analisis Feminisme Cerpen Catatan Seorang PelacurDokumen9 halamanAnalisis Feminisme Cerpen Catatan Seorang Pelacurchefa foreverBelum ada peringkat
- Raja Priyayi KawulaDokumen10 halamanRaja Priyayi KawulaAditya PrawiraBelum ada peringkat
- Perempuan Dan Kekerasan Pada Masa Orde B 047082d9Dokumen12 halamanPerempuan Dan Kekerasan Pada Masa Orde B 047082d9Wilson ChannelBelum ada peringkat
- Ardi 257-276Dokumen20 halamanArdi 257-276fahrezi hBelum ada peringkat
- Makalah UIN Penyiar IslamDokumen34 halamanMakalah UIN Penyiar IslamBadrul Amin AN NsiBelum ada peringkat
- Be RandaDokumen18 halamanBe Randaipul lohBelum ada peringkat
- ANARKISMEDokumen12 halamanANARKISMETegarBelum ada peringkat
- Interseksi GenderDokumen13 halamanInterseksi GenderMTs N 1 SlemanBelum ada peringkat
- Kajian Prosa FiksiDokumen32 halamanKajian Prosa FiksiIna NryBelum ada peringkat
- Pesan Moral Dalam Kearifan Lokal Jawa Melalui Cerpen "Jenengku: " Karya Krishna MiharjaDokumen9 halamanPesan Moral Dalam Kearifan Lokal Jawa Melalui Cerpen "Jenengku: " Karya Krishna MiharjaPemulaBelum ada peringkat
- Resistensi Dari Objektifikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah MunawirDokumen10 halamanResistensi Dari Objektifikasi Terhadap Perempuan Dalam Novel The Sinden Karya Halimah MunawirNadia Bella OktaviaBelum ada peringkat
- Pengaruh Kemajemukan Di IndonesiaDokumen7 halamanPengaruh Kemajemukan Di IndonesiaPutra BungsuBelum ada peringkat
- Poskolonial Sebuah PembahasanDokumen19 halamanPoskolonial Sebuah PembahasanTika Fitri100% (1)
- FerdianLihardoHarahap GagasanManusiaIndonesiaDokumen2 halamanFerdianLihardoHarahap GagasanManusiaIndonesiaFerdian HarahapBelum ada peringkat
- DILIMA KAJIAN GENDERDokumen23 halamanDILIMA KAJIAN GENDERAlii BabaBelum ada peringkat
- POSTKOLONIALISMEDokumen13 halamanPOSTKOLONIALISMEDino 6969100% (1)
- NEGARA DAN KEKUASAANDokumen12 halamanNEGARA DAN KEKUASAANrangga agungBelum ada peringkat
- Feminisme Dalam NovelDokumen12 halamanFeminisme Dalam NovelFebi Putri UtamiBelum ada peringkat
- KETIDAKADILAN GENDERDokumen10 halamanKETIDAKADILAN GENDERKey AzkayraBelum ada peringkat
- 5736-Article Text-8103-9806-10-20160727Dokumen9 halaman5736-Article Text-8103-9806-10-20160727Batlayeri RBelum ada peringkat
- 010 - Resume PAUDDokumen5 halaman010 - Resume PAUDFera Nur Farida010Belum ada peringkat
- ProposalDokumen25 halamanProposalNur AzizahBelum ada peringkat
- Krisis Identitas dan Inferioritas dalam Polemik KebudayaanDokumen2 halamanKrisis Identitas dan Inferioritas dalam Polemik KebudayaanNovita RahmahBelum ada peringkat
- Kelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)Dokumen23 halamanKelompok VII (Tipe-Tipe Sistem Politik)Gama Muazzam80% (5)
- Ambivalensi Kehidupan Tokoh Larasati Dal Be609384Dokumen12 halamanAmbivalensi Kehidupan Tokoh Larasati Dal Be609384Eric ClarkBelum ada peringkat
- Feminisme Kultural StudiDokumen20 halamanFeminisme Kultural StudiSahrul0% (1)
- Kajianpuisi Dinasarihardiyantilf 1800003130 DDokumen6 halamanKajianpuisi Dinasarihardiyantilf 1800003130 DDinasari HardiyantiBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Kebudayaan Amilia R-2Dokumen12 halamanProposal Penelitian Kebudayaan Amilia R-2Amilia RachmawatiBelum ada peringkat
- NEGARA DAN MASYARAKAT SIPILDokumen9 halamanNEGARA DAN MASYARAKAT SIPILsandi maulidinBelum ada peringkat
- Teori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaDari EverandTeori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Politik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal KontemporerDari EverandPolitik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal KontemporerPenilaian: 3 dari 5 bintang3/5 (2)
- Design Thinking 3Dokumen17 halamanDesign Thinking 3Dhika PutraBelum ada peringkat
- Design Thinking 1Dokumen27 halamanDesign Thinking 1Dhika PutraBelum ada peringkat
- CINEMATIC LIGHTING TECHNIQUESDokumen16 halamanCINEMATIC LIGHTING TECHNIQUESDhika PutraBelum ada peringkat
- Cinematic LightingDokumen16 halamanCinematic LightingDhika PutraBelum ada peringkat
- Narasi Dongeng Oleh Dhika Purnama PutraDokumen3 halamanNarasi Dongeng Oleh Dhika Purnama PutraDhika PutraBelum ada peringkat
- Bluesky Collapse Case SolvedDokumen5 halamanBluesky Collapse Case SolvedDhika Purnama PutraBelum ada peringkat
- Kritik Seni - Geliat Zine Cetak Di Era Disruptif Oleh Dhika Purnama PutraDokumen5 halamanKritik Seni - Geliat Zine Cetak Di Era Disruptif Oleh Dhika Purnama PutraDhika PutraBelum ada peringkat
- KuantitatifDokumen17 halamanKuantitatifDhika PutraBelum ada peringkat
- Pengertian HTMLDokumen5 halamanPengertian HTMLDhika PutraBelum ada peringkat
- Bacaan Shalat Fardu Dan ArtinyaDokumen6 halamanBacaan Shalat Fardu Dan ArtinyaRahmat PrihartonoBelum ada peringkat