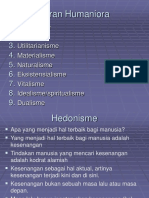Jiwa Manusia
Diunggah oleh
Andri Al-abqohJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Jiwa Manusia
Diunggah oleh
Andri Al-abqohHak Cipta:
Format Tersedia
JIWA MANUSIA
Plotinus mengatakan, jiwa tidak bergantung pada materi. Materi seratus persen pasif,
sedangkan jiwa seratus persen aktif. Karena itu, jiwa merupakan esensi tubuh material. Tubuh
itu materi yang berisi prinsip-prinsip ketiadaan, penuh dengan kejahatan dan keterbatasan
yang berjarak jauh dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti tubuh lantas boleh diabaikan. Dunia
tidak boleh disangka sebagai sumber ketidakbahagiaan, karena Tuhan sebenarnya telah
menciptakan yang ada ini dengan ketelitian, keteraturan dan keindahannya.
Agustinus menyatakan bahwa menurut naturnya (demikian seharusnya) jiwa memang ada
(bertempat) pada badan (tidak melalui proses emanasi seperti prasangka Plotinus). Tetapi
jiwa tidak bergantung pada badan karena sifatnya immortal (abadi), sehingga ia tidak ikut
binasa jika badan hancur. Dari sini, jiwa itu lebih tinggi dan lebih hakikat (esensial) daripada
badan.
Menurut Thomas Aquinas, karena jiwa lebih tinggi dari raga, maka jiwa harus menjadi
pembimbing. Jiwa tertinggi adalah jiwa rasional yang merupakan manifestasi kehidupan
tertinggi yang menyajikan supremasi intelek di atas benda, tetumbuhan (jiwa vegetatif) dan
hewan (jiwa sensitif). Sekalipun jiwa itu satu, tetapi dapat dibagi dalam kemampuannya yang
meliputi: daya mengindera (sensation), berfikir (reason), dan nafsu (appetite) yang mencakup
kemauan. Sebagaimana Agustinus, Aquinas meyakini jiwa bersifat immaterial karena mampu
memikirkan obyek-obyek yang bersifat immaterial dan universal. Jiwa juga bersifat abadi
karena ia pemberi hidup (bagi badan). Pemberi hidup harus selalu hidup. Baginya, jiwa adalah
form. Matter (dalam hal ini badan) memperoleh form dari jiwa, lantas mengaktual. Begitu
jasad rusak, jiwa memisahkan dirinya.
Kelak, menurutnya, jiwa akan dipersatukan kembali dengan tubuhnya dalam kehidupan
mendatang.Tentang interaksi tubuh dan jiwa menarik disimak pemikiran Cartesian berikut
ini: Melalui analisisnya, Rene Descartes sampai pada suatu simpulan bahwa tidak ada ruang
kosong di alam semesta ini. Semuanya penuh dengan aneka partikel yang memiliki sifat-sifat
dasar sederhana (simple natures) yaitu keluasan (ekstensi) dan gerak (motion). Tiga partikel
dasar yang ada di alam ini adalah: api, udara, dan tanah. Tubuh manusia juga terdiri dari
partikel-partikel tersebut dengan 10 fungsi fisiologis yang bergerak secara mekanis: (1)
pencernaan makanan, (2) sirkulasi darah, (3) daya tahan dan pertumbuhan, (4) respirasi, (5)
tidur dan terjaga, (6) sensasi pada dunia eksternal, (7) imajinasi, (8) memori, (9) nafsu dan
gairah, (10) pergerakan tubuh. Kesemuanya itu dikontrol oleh aktivitas otak dan sistem syaraf.
Adapun variasi respon spesifik (individual) adalah hasil dari interaksi respon eksternal dan
kesiapan “emosional” internal “roh-roh hewani”.
Descartes percaya bahwa memahami manusia tak cukup hanya dengan penjelasan secara
mekanistis karena adanya “kesadaran dan kehendak”, “keinginan dan pertimbangan-
pertimbangan rasional” dalam tindakannya. Disini ia mempercayai entitas immaterial yang
disebut sebagai jiwa, yang sama sekali berbeda dengan tubuh. Sekalipun tidak pernah nampak
secara langsung atau dialami dalam totalitasnya, jiwa dapat dikenali dengan melacak ide-ide
bawaan (innate ideas). Jiwa dikatakan bersifat padu, rasional dan konsisten. Jiwa dapat
berperan menjadikan perilaku disadari (atas pertimbangan rasional). Dalam bahasanya,
“Cogito ergo sum” (aku berfikir, maka aku ada). Tetapi, sekalipun jiwa dapat mempengaruhi
perilaku, ia tidak selalu dapat mengendalikannya. Descartes mengatakan, “Tak cukup
mempunyai pikiran yang baik. Hal yang utama ialah menerapkannya dengan baik.”
Blaise Pascal juga pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rumit dan
kaya dengan variasi serta mudah berubah. Maka dari itu, matematika dan demikian pula
halnya dengan logika dan metafisika tidak mungkin dapat memahami manusia secara utuh.
Disiplin-disiplin pemikiran itu hanya alat-alat yang dapat digunakan untuk memahami obyek-
obyek yang konsisten dan bebas kontradiksi. Sedangkan manusia itu makhluk yang penuh
dengan kontradiksi, sehingga satu-satunya jalan untuk memahami manusia adalah melalui
agama. Jadi, tatkala akal tidak mampu menjangkau sesuatu maka hati dapat menyingkap hal
itu. Kata Pascal, “Hati mempunyai alasan-alasannya yang tidak dapat diketahui akal budi.”
Baginya, lebih rasional percaya kepada Tuhan daripada tidak,sebab, jika memang Tuhan ada
maka akibatnya sangat besar, tetapi jika memang Dia tidak ada maka tidak ada yang perlu
merasa kehilangan.
Sutejo ibnu Pakar FILSAFAT MANUSIA IAIN SNJ CRBN
Berbeda dengan John Locke yang memandang jiwa manusia itu seperti kertas kosong yang
baru berisi pengetahuan atau idea-idea melalui pengalaman empiris (a-posteriori), Immanuel
Kant justru memandang bahwa jiwa manusia itu bersifat aktif, mengkoordinasikan sensasi-
sensasi empiri yang masuk melalui indera untuk kemudian menjadi disadari atau dapat
dipersepsi keberadaannya dengan idea-idea kategoris yang a-priori. Sebelumnya Kant
membedakan antara akal-murni (pure-reason) yaitu yang bekerja secara logis (atau akal yang
di kepala) dan akal-praktis (practical-reason) yaitu kesadaran moral (yang berada di hati).
Menurutnya, indera dan akal manusia hanya mampu mengetahui dunia luar sebatas pada
penampakannya (fenomena) saja. Sedangkan tentang noumena (thing-in-itself) atau obyek-
obyek keyakinan dan berbagai hal yang bersifat ghaib lainnya, indera dan akal manusia sama
sekali tidak mampu menembus untuk mengetahuinya. Termasuk tentang Tuhan atau
pembalasan di hari akhirat, maka akal teoritis tidak akan dapat membuktikan hakikatnya.
Sekalipun demikian, akal teoritis tidak melarang manusia untuk bisa mempercayai adanya
noumena itu. Kesadaran moral (akal praktis) manusialah yang kemudian memerintahkan
seseorang untuk mempercayai atau meyakininya.
Jadi, kebenaran tidak seluruhnya bisa diperoleh melalui indera dan akal. Ada juga
kebenaran yang hanya mungkin bisa diperoleh dengan kata hati (inilah yang disebut moral
oleh Kant) atau iman. Kata hati itu suatu perintah tanpa syarat yang ada dalam kesadaran
manusia. Suatu perasaan yang tidak dapat dielakkan yang memerintah untuk berbuat sesuatu
yang sesuai dengan keinginan universal, yakni hukum kewajaran yang universal. Manusia
mengetahuinya tidak dengan memikirkannya, melainkan perasaan itu muncul tiba-tiba yang
mendorong kesadaran untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memang
seharusnya demikian diperbuatnya untuk suatu kepentingan kehidupan/ kemanusiaan.
Moralitas dengan demikian bukanlah doktrin tentang bagaimana manusia mencapai
kebahagiaan, tetapi bagaimana seseorang dapat membuat dirinya layak berbahagia atas
kebahagiaan yang diterima orang lain.
Jika kesadaran dan kehendak adalah kualitas jiwa yang melulu rasional dalam pemikiran
Descartes, Arthur Schopenhauer justru menegaskan bahwa kesadaran dan intelek hanyalah
fenomena bahkan alat dari kehendak yang sering bersifat buta atau tidak tersadari. Jadi, unsur
sejati yang tak pernah letih dan tak pernah mati dari manusia tidak lain adalah kehendak
dengan keinginan kuatnya dan bukannya rasio. Segala gerakan tubuh tidak lain dari
obyektivikasi dari tindakan kehendak. Seluruh sistem syaraf dalam otak dan tubuh manusia
tak ubahnya antena bagi kepentingan kehendak. Dan kehendak terkuat manusia adalah
kehendak untuk hidup dan memaksimumkan hidup, atau untuk mengalahkan kematian.
Tetapi kehendak yang senantiasa mengisyaratkan keinginan tersebut pada kenyataannya
selalu saja lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang bisa diperoleh untuk
memuaskannya dalam hidup ini. Maka dunia tidak lain adalah penderitaan. Penyakit
kehidupan (derita) ini kemudian hanya bisa diatasi jika kehendak manusia telah ditundukkan
oleh pengetahuan dan intelegensi. Jadi, sekalipun berpengetahuannya intelek pada awalnya
lahir karena dorongan kehendak, tetapi dalam perkembangannya intelek dapat menolak
untuk patuh kepada kehendak. Bahkan jika intelek terus diasah dan dilatih, dengan
pengetahuannya tersebut intelek mampu mengendalikan dan mengarahkan keinginan-
keinginan. Dalam bahasanya, “Si vis tibi omnia subjicere, subjicete ratione” (kalau kamu
hendak membuat apa saja tunduk kepadamu, maka tunduklah kamu pada rasiomu).
Ternyata, penaklukan yang paling mengagumkan dalam hidup ini tidak lain adalah
penaklukan atas diri sendiri. Jalannya dilalui melalui renungan dan kontemplasi yang cerdas
tentang kehidupan. Maka amatilah segala obyek kehidupan ini tidak melulu sebagai obyek
keinginan (karena hanya akan berujung kesengsaraan), tetapi amatilah sebagai obyek-obyek
pemahaman (sehingga kebijaksanaan dan kebahagiaan hidup yang dicapai).
Mengenai kehendak, Friedrich Nietzsche juga menegaskan esensialitasnya pada organisme
yang disebut manusia. Tetapi kehendak dalam filsafatnya bukannya sebagai sumber derita
melainkan kebajikan utama. Menurut Nietzsche, kehendak yang paling kuat dan paling tinggi
dari manusia adalah kehendak untuk berperang, untuk berkuasa dan bukan sebaliknya untuk
kalah atau menderita. Hidup ini pada dasarnya adalah perjuangan untuk bereksistensi dimana
organisme yang paling kuatlah yang pantas dan berhak untuk terus melangsungkan
kehidupannya. Jadi, kebajikan utama tidak lain adalah kekuatan atau kekuasaan, sedangkan
kelemahan tidak berarti lain kecuali keburukan yang tercela. Maka, fungsi kehidupan
sebenarnya bukanlah untuk memperbaiki mayoritas yang kebanyakan berisi manusia tidak
layak, tetapi untuk menciptakan jenius, manusia yang superior (ubermensch).
Sutejo ibnu Pakar FILSAFAT MANUSIA IAIN SNJ CRBN
Manusia yang unggul itu adalah manusia yang sanggup membuat (menghadapi) tragedi
menjadi (seolah) komedi karena (secara personalitas) tubuhnya telah terlatih untuk
menderita dalam keheningan yang diam dan kehendaknya pun terlatih untuk memerintah dan
mematuhi perintah. Suasana hati dari manusia kuat dan hebat itu digambarkan tak jauh dari
suatu “optimisme tragis”, yakni keberanian untuk mencari intensitas dan peningkatan
pengalaman (meski dengan menambah kesengsaraan) dan sanggup bahagia menemukan
kekerasan sebagai hukum dari kehidupan. Katanya, “Hanya dengan menjadikan penderitaan
sebagai gejala estetik (obyek perenungan dan rekonstruksi artistik), maka eksistensi
(manusia) dan dunia tampak saling membenarkan.” Pemikirannya ini diilhami seni mitologis
Yunani Kuno yang mampu memadukan 2 (dua) cita sekaligus, yaitu: maskulinitas Dyonysius
(dewa anggur dan pesta-pora, petualangan dan naluri, serta dewa musik, tarian dan drama)
dengan feminitas Apollo (dewa kedamaian dan harmoni, kontemplasi intelektual dan
keteraturan logis, serta dewa lukisan, patung dan puisi epik). Nietzsche berkata,
“Kesengsaraan bagi para pemikir ibarat tanah subur bagi tanaman.”
Lebih lanjut tentang kehendak berkuasa, Nietzsche mula-mulamelihat ada dua penilaian
atau titik pandang dan kriteria etik tentang tingkah laku manusia, yaitu: herren moral (moral
tuan) dan heerden moral (moral budak). Semisal tentang konsep “baik”, maka bagi golongan
aristokrat (para tuan) itu bisa berarti kuat, berani, berkuasa, suka perang, seperti dewa.
Sedangkan bagi rakyat jelata (para budak), “baik” berarti keramahan, kedamaian, jinak, manis.
Ironisnya menurut Nietzsche, justru moral budak (yang inferior) inilah yang diterima
sebagai etika hampir secara universal. Nietzsche menuduh bahwa berkat kefasihan lidah para
nabilah “dunia” dan “daging” seolah sinonim dengan kejahatan, sementara “kemiskinan”
malah menjadi bukti kebajikan. Tetapi jika ditelisik lebih dalam, Nietzsche meyakinkan bahwa
ternyata yang ada di balik semua moralitas tersebut (baik herren maupun heerden moral)
tidak lain adalah kehendak rahasia untuk berkuasa. Semisal saja “belas-kasihan” yang
ditunjukkan dengan mengunjungi orang sakit, sejatinya hal itu tidak lain adalah puncak
kenikmatan superioritas dalam memandang ketidakberdayaan tetangganya. Demikian pula
misalnya dengan “cinta” yang sejatinya adalah keinginan untuk memiliki (menguasai). Dalam
bahasanya, “L’amour est de tous les sentiments le plas egoiste, et par consequent, lorsqu’il est
blesse, le moling genereux” (cinta adalah segenap perasaan yang sangat egoistis, dan
konsekuensinya, kala sedang berselisih ia sangat tidak bermurah hati). Jadi, rasio dan
moralitas tidak berdaya melawan nafsu untuk berkuasa. Keduanya hanya menjadi senjata atau
barang mainan yang digenggam oleh nafsu. Dyonysius akhirnya menaklukkan Apollo.
Midas bertanya, “Apakah nasib merupakan sesuatu yang terbaik bagi manusia?” Milenus
menjawab, “Oh, anak-anak dari kemalangan dan penderitaan,mengapa kau memaksaku untuk
mengatakan apa yang terbaik dari apa yang sebetulnya tak pernah terdengar? Yang terbaik
dari semuanya tidak akan pernah mungkin tergapai (yaitu) tidak pernah lahir dan tidak
pernah ada. (Adapun) yang kedua terbaik (yaitu) mati muda.”
Sutejo ibnu Pakar FILSAFAT MANUSIA IAIN SNJ CRBN
Sutejo ibnu Pakar FILSAFAT MANUSIA IAIN SNJ CRBN
Anda mungkin juga menyukai
- Pengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Sejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniDari EverandSejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniBelum ada peringkat
- tahapAN KESADARANDokumen106 halamantahapAN KESADARANBambang Triatmoko100% (1)
- Pengertian IdealismeDokumen14 halamanPengertian IdealismeLisanaAliyyaHumaida100% (1)
- Kel 10Dokumen17 halamanKel 10Erlinda Dian ApriliaBelum ada peringkat
- BAB X FilsafatDokumen15 halamanBAB X FilsafatANNISA EFIKA YUSTAFIDABelum ada peringkat
- Bab XDokumen7 halamanBab XANNISA EFIKA YUSTAFIDABelum ada peringkat
- Paper Lengkap Pu Kelompok 3Dokumen22 halamanPaper Lengkap Pu Kelompok 3miskah machmoedBelum ada peringkat
- Jiwa & TubuhDokumen21 halamanJiwa & TubuhMuhammad AuliaBelum ada peringkat
- Filsafat Manusia Dualisme CartesianDokumen5 halamanFilsafat Manusia Dualisme CartesianAhmad Akbar SyarifudinBelum ada peringkat
- Membangun Kesadaran RasaDokumen18 halamanMembangun Kesadaran RasaImam MuharrorBelum ada peringkat
- BAB 7 MakalahDokumen9 halamanBAB 7 Makalahaprilia chairunnisaBelum ada peringkat
- Soal DualismeDokumen4 halamanSoal DualismeTeresna SainseillahBelum ada peringkat
- Filsafat 2Dokumen3 halamanFilsafat 2Abdul MalikBelum ada peringkat
- Tugas Filsafat Ilmu Pengetahuan 2Dokumen10 halamanTugas Filsafat Ilmu Pengetahuan 2sanry komsaryBelum ada peringkat
- RESUME FilsafatDokumen11 halamanRESUME FilsafatNami KazeBelum ada peringkat
- Jiwa Manusia Menurut para FilosofDokumen15 halamanJiwa Manusia Menurut para FilosofastiiBelum ada peringkat
- DUALISMEDokumen6 halamanDUALISMEirfan achmadiBelum ada peringkat
- Wa Amanu Wa Hajaru Wa JahaduDokumen27 halamanWa Amanu Wa Hajaru Wa JahaduAbd Cholik Sholeh100% (1)
- Bab 1 Manusia Dan Alam SemestaDokumen6 halamanBab 1 Manusia Dan Alam SemestaAu Batilmurik RefraBelum ada peringkat
- Kehendak ButaDokumen24 halamanKehendak ButaDevi TrianurBelum ada peringkat
- Tahapan-Kesadaran PDFDokumen106 halamanTahapan-Kesadaran PDFBainahhumaydiBelum ada peringkat
- Tahapan-Kesadaran PDFDokumen106 halamanTahapan-Kesadaran PDFBainahhumaydiBelum ada peringkat
- Analisis Swot Konsep Dasar Filsafat Idealisme Implikasi Dan Aplikasi Dalam PendidikanDokumen7 halamanAnalisis Swot Konsep Dasar Filsafat Idealisme Implikasi Dan Aplikasi Dalam Pendidikant3r33 nBelum ada peringkat
- Gagasan Henry BergsonDokumen4 halamanGagasan Henry BergsonSalvatoris DuarmasBelum ada peringkat
- Idealisme Transendental KantDokumen190 halamanIdealisme Transendental KantNaufal IhsanBelum ada peringkat
- Pertemuan Kelima Fil ManusiaDokumen26 halamanPertemuan Kelima Fil Manusiaragil sernandaBelum ada peringkat
- PK 5Dokumen6 halamanPK 5yendi andikaBelum ada peringkat
- Aliran Filsafat Intuisionisme Dan KritismeDokumen7 halamanAliran Filsafat Intuisionisme Dan KritismeOktaviani A. NtBelum ada peringkat
- Filsafat VitalismeDokumen3 halamanFilsafat Vitalismesalma syifaBelum ada peringkat
- Modul 5 Aliran IdealismeDokumen16 halamanModul 5 Aliran IdealismeAnnisa MaharaniiBelum ada peringkat
- Manusia Adalah Makhluk Pencari KebenaranDokumen6 halamanManusia Adalah Makhluk Pencari KebenaranNu'man Latief100% (1)
- IntuisiDokumen7 halamanIntuisiBinjai MusikBelum ada peringkat
- Manusia Kajian Filsafat - En.idDokumen9 halamanManusia Kajian Filsafat - En.idIyoksBelum ada peringkat
- 1399 2693 1 SMDokumen7 halaman1399 2693 1 SMArvinoBelum ada peringkat
- Jiwa Dan Tubuh Menurut Pandangan Ibnu MiskawaihDokumen15 halamanJiwa Dan Tubuh Menurut Pandangan Ibnu MiskawaihRisMariskaBelum ada peringkat
- Aliran Humaniora-1Dokumen12 halamanAliran Humaniora-1Gita SJBelum ada peringkat
- 1) Ermansyah R. Hindi (KA2I) - RevisiDokumen35 halaman1) Ermansyah R. Hindi (KA2I) - RevisiIank cha'EmBelum ada peringkat
- 2B - Jatmika Aji Santika - 1195010070 Tugas FilsafatDokumen14 halaman2B - Jatmika Aji Santika - 1195010070 Tugas FilsafatJatmika AjiBelum ada peringkat
- Aliran IntuisiDokumen8 halamanAliran IntuisiArif GunawanBelum ada peringkat
- 2892-Article Text-6767-1-10-20180511Dokumen33 halaman2892-Article Text-6767-1-10-20180511Kristama AritonangBelum ada peringkat
- ManusiaDokumen8 halamanManusianurul hidayatiBelum ada peringkat
- Empat Potensi Dan Kecerdasan Manusia Yang MengagumkanDokumen3 halamanEmpat Potensi Dan Kecerdasan Manusia Yang MengagumkanIwan KurniawanBelum ada peringkat
- Cogito Ergo Sum VS Credo Ergo SumDokumen25 halamanCogito Ergo Sum VS Credo Ergo SumRighit_Permana_599Belum ada peringkat
- Filsafat ManusiaDokumen4 halamanFilsafat ManusiaAbdallah Ibnu MBelum ada peringkat
- Dinamika Perkembangan Ilmu Ilmiah ModernDokumen16 halamanDinamika Perkembangan Ilmu Ilmiah ModernImam MuharrorBelum ada peringkat
- Chapter Report Kelompok 3 Arthur ShcopenhauerDokumen6 halamanChapter Report Kelompok 3 Arthur ShcopenhauerNadia andrianiBelum ada peringkat
- A.M.FARHAN RIFQI - 210701502102 - FILSAFAT MANUSIA - KELAS A-DikonversiDokumen4 halamanA.M.FARHAN RIFQI - 210701502102 - FILSAFAT MANUSIA - KELAS A-DikonversiFarhan RifqiBelum ada peringkat
- Sementara ItuDokumen3 halamanSementara Itutheogive palandengBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat ManusiaDokumen18 halamanMakalah Filsafat ManusiaImadul AuwalinBelum ada peringkat
- Kekuatan JiwaDokumen5 halamanKekuatan JiwaIbnu Risalah Al-ayubiBelum ada peringkat
- Filsafat KomunikasiDokumen22 halamanFilsafat KomunikasiAnju PratamaBelum ada peringkat
- Referensi Filsafat ManusiaDokumen5 halamanReferensi Filsafat Manusiaandi ulfatBelum ada peringkat
- Pandangan para Filosof Tentang Konsep TuhanDokumen17 halamanPandangan para Filosof Tentang Konsep TuhanniaBelum ada peringkat
- Artikel 1 Manusia Dan Pendidikan.Dokumen10 halamanArtikel 1 Manusia Dan Pendidikan.Ghea KhaqBelum ada peringkat
- Fungsi Fungsi Ilmu JiwaDokumen11 halamanFungsi Fungsi Ilmu JiwaBambangSubahriBelum ada peringkat
- Laporan Bacaan MMI Kel 7Dokumen7 halamanLaporan Bacaan MMI Kel 7Rifqi AyuuuBelum ada peringkat
- Konsep Dasar Psikologi 2022 RevisiDokumen34 halamanKonsep Dasar Psikologi 2022 RevisiInstagram CemimiwBelum ada peringkat
- PsikologiDokumen6 halamanPsikologidicky arfaniBelum ada peringkat
- Bab 7 JIWA DAN TUBUHDokumen10 halamanBab 7 JIWA DAN TUBUHVika Anggari Putri0% (1)
- Penelitian FilsafatDokumen55 halamanPenelitian FilsafatAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Uas Perencanaan Pendidikan Andri KoharDokumen8 halamanUas Perencanaan Pendidikan Andri KoharAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Tugas Penelitian Filsafat FidaDokumen14 halamanTugas Penelitian Filsafat FidaAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Resume BukuDokumen11 halamanResume BukuAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Semester 2021-2022-2Dokumen10 halamanSemester 2021-2022-2Andri Al-abqohBelum ada peringkat
- Nur Iban F - Jurnal Analisis Kebijakan PendidikanDokumen13 halamanNur Iban F - Jurnal Analisis Kebijakan PendidikanAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Manajemen Mutu PendidikanDokumen19 halamanManajemen Mutu PendidikanAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- 40 Wasiat Gusti SinuhunDokumen6 halaman40 Wasiat Gusti SinuhunAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Tendik Dalam Mengelola Sarana PrasaranaDokumen14 halamanTendik Dalam Mengelola Sarana PrasaranaAndri Al-abqohBelum ada peringkat
- Tugas Uas - Malisatul Mar'Ah (Mpi - A)Dokumen23 halamanTugas Uas - Malisatul Mar'Ah (Mpi - A)Andri Al-abqohBelum ada peringkat
- Ruh Vs Hawa NafsuDokumen12 halamanRuh Vs Hawa NafsuAndri Al-abqoh100% (1)
- Presentasi Nur Iban Faturohman-1Dokumen13 halamanPresentasi Nur Iban Faturohman-1Andri Al-abqohBelum ada peringkat