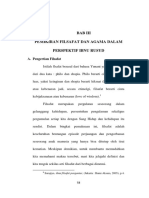Tugas Filsafat Islam Khusus Kelas C Dan D
Diunggah oleh
Minanur RochmanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tugas Filsafat Islam Khusus Kelas C Dan D
Diunggah oleh
Minanur RochmanHak Cipta:
Format Tersedia
Tugas Mandiri sebagai syarat Mengikuti Ujian Akhir (UAS)
Semeter Genap TA. 2022/2023
Mata Kuliah : Filsafat Islam Semester/Kelas : IV / C dan D
Ketentuan Tugas
a. Mahasiswa mempelajari buku (terjemah) ‘Tahafut al-Falasifah’ dan
‘Tahafut at-Tahafut’ dan pokok-pokok pikiran Al-Ghazali dan Ibn Rusyd
tentang ‘Hukum Sebab Akibat (Kausalitas) dan Mukjizat’ sebagaimana
tersebut di bagian bawah lembar tugas ini.
b. Tugas ditulis tangan dalam lembar kertas HVS ukuran A4 dengan identias
lengkap.
c. Mahasiswa menyerahkan hasil tugas dan menandatangani daftar hadir /
bukti penerimaan tugas sebelum mengerjkan UAS.
Uraikan gambaran pemahaman Anda dengan menjawab pertanyaan tersebut
dibawah ini.
1. Lengkapilah tabel perbandingan pemikiran dengan kata kunci/konsep
Hubungan
No Al-Ghazali Ibn Rusyd
sebab-akibat
1. Mu’jizat
2. Akal
3. Kebiasaan (al-‘adat)
4. Keniscayaan
2. Tulislah pokok-pokok pemahaman Anda pikiran al-Gazali tentang
a. Hubungan antara sebab-akibat dengan keniscayaan
b. Hubungan sebab-akibat dengan kebiasaan (al-‘adat)
c. Sebab akibat dengan akal
d. Sebab akibat dengan mu’jizat
3. Tulislah pokok-pokok pikiran Ibn Rusyd tentang
a. Hubungan antara sebab-akibat dengan keniscayaan
b. Hubungan sebab-akibat dengan kebiasaan (al-‘adat)
c. Sebab akibat dengan akal
d. Sebab akibat dengan mu’jizat
4. Gambarkan pemahaman Anda dan gunakan argumentasi ala “ Al-Ghazali
dan Ibn Rusyd ”, untuk menjelaskan antara kebiasaaan (al-‘adat) atau
menyalahi kebiasaan (khariq al-'dat) atas fenomena tersebut dibawah ini:
a. Kebiasaan kucing yang menjadikan tikus hampir menjadi makanan
utama kucing!
b. Menyalahi kebiasaan, ternyata benar-benar terjadi seorang nenek
melahirkan cucunya kandungnya sendiri!
5. Setelah anda membaca, memahami dan membandingkan pemikiran Al-
Ghazali dalam buku dan Ibn Rusyd
PEMIKIRAN IBNU RUSYD
Tentang
Hukum Sebab Akibat (Kausalitas) dan Mukjizat
Dalam karyanya Tahâfut al-Tahâfut, Ibnu Rusyd mengkritik apa yang telah
dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang hubungan sebab-akibat serta
kaitannya dengan perkara yang menyimpang dari kebiasaan dan mukjizat
nabi. Berikut ini dikemukakan bantahan Ibnu Rusyd tersebut.
1. Terdapat hubungan yang dharuriy (pasti) antara sebab dan akibat
Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa antara sebab
dan akibat atau kausalitas terdapat hubungan keniscayaan. Pengingkaran
akan adanya sebab, yang melahirkan adanya musabab atau akibat,
merupakan pernyataan yang tidak logis. Karena itu, menurut Ibnu Rusyd,
para mutakalimin termasuk Al-Ghazali sebenarnya mengatakan sesuatu
yang berlawanan dengan hati nurani mereka. Adapun pernyataan bahwa
sebab itu berpengaruh secara efektif dengan sendirinya terhadap lahirnya
suatu akibat atau efektivitas, pengaruh tersebut disebabkan hal lain, baik
secara langsung maupun tidak langsung, merupakan permasalahan yang
memerlukan kajian mendalam.
Selanjutnya, Ibnu Rusyd menyatakan bahwa pada suatu benda atau segala
sesuatu yang ada di alam ini memiliki sifat dan ciri tertentu, yang disebut
dengan sifat zâtiyah. Dalam arti bahwa untuk terwujudnya sesuatu keadaan
mesti ada daya atau kekuatan yang telah ada sebelumnya. Bagaimana
seseorang, kata Ibnu Rusyd, bisa mengingkari adanya sebab terhadap
musabab, padahal segala yang mawjũd ini tidak bisa dipahami, kecuali
dengan mengenali sebab-sebab zâtiyat. Tanpa sebab-sebab zâtiyat ini tidak
bisa dibedakan antara satu mawjũd dengan mawjũd yang lain. Seperti api
memiliki sifat zatiyat, yakni membakar. Air memiliki pula sifat zâtiyat-nya,
yakni membasahi. Sifat membakar dan membasahi inilah yang
membedakan antara api dan air. Jika tidak ada sifat tertentu bagi tiap-tiap
mawjũd, maka tentu api dan air menjadi sama saja. Sudah barang tentu, kata
Ibnu Rusyd, hal ini adalah suatu kemustahilan.
2. Hubungan sebab akibat dengan adat atau kebiasaan
Telah disebutkan bahwa Al-Ghazali memandang hubungan sebab-akibat
sebagai adat atau kebiasaan. Ternyata Ibnu Rusyd mempertanyakan apa
sebenarnya yang dimaksud Al-Ghazali sebagai adat tersebut. Apakah adat
fâ'il (Allah SWT), atau adat mawjũd, atau adat bagi kita dalam menetapkan
sesuatu sifat atau predikat terhadap mawjũd ini. Kalau yang dimaksud adat
bagi Allah SWT, hal ini mustahil karena apa yang disebut sebagai adat
adalah suatu kemampuan atau potensi yang diusahakan fâ'il yang
mengakibatkan berulang-ulangnya perhatian fâ'il. Hal ini tentu
bertentangan dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa
sunatullah itu tidak akan berganti dan tidak akan berubah (QS Al-Isra' [17]:
77). Jika yang dimaksud adalah adat bagi mawjũd, maka hal ini hanya akan
berlaku bagi yang memiliki roh atau nyawa karena bagi yang selain itu,
bukanlah adat namanya, tetapi tabiat. Dan apabila yang dimaksud adalah
adat bagi kita dalam menentukan sesuatu sifat atau predikat terhadap
mawjũd ini, seperti si Fulan biasa (adat)-nya melakukan ini dan melakukan
itu, maka berarti yang mawjũd ini semuanya terlepas daripada nisbat
(hubungan)-nya kepada fâ'il (Allah SWT).
3. Hubungan sebab akibat dengan akal
Ibnu Rusyd juga membantah pendapat Al-Ghazali tentang hubungan sebab
akibat ini dengan pandangannya yang bertitik tolak dari akal sehat, yang
menurutnya merupakan dasar yang menentukan. Kata Ibnu Rusyd,
menyangkal keberadaan sebab efisien yang tampak pada hal-hal yang
terasa adalah menyesatkan. Orang yang mengingkari hal tersebut berarti
mengingkari apa yang ada dalam pikiran dan lidahnya atau terbawa oleh
keraguan yang menyesatkan. Lebih dari itu, Ibnu Rusyd memandang bahwa
filsafat tidak hanya berdiri di atas akal sehat, tetapi juga atas ilmu
pengetahuan. Empirisme itu bermanfaat untuk tujuan praktis, bukan untuk
ilmu-ilmu pasti. Empirisme praktis didasarkan pada akal sehat.
Pengetahuan ilmiah mempercayai hukum sebab akibat, yang dipandang
sangat meyakinkan. Bersifat ilmiah berarti mampu meramalkan apa yang
akan terjadi di kemudian hari, apabila suatu sebab telah diketahui.
Mempercayai ilmu dan kekuatannya disebabkan oleh kemampuan kita
untuk meramal atas dasar menguatkan keimanan kita menyangkut alam
semesta ini, dan menyatakan bahwa segala sesuatu di alam ini terjadi
menurut keteraturan sempurna, yang dapat dipahami sebagai hukum sebab
akibat. Karena itu, secara tegas Ibnu Rusyd menyatakan bahwa
pengetahuan akal tidak lebih daripada pengetahuan tentang segala yang
mawjũd beserta sebab akibat yang menyertainya. Pengingkaran akan sebab
berarti pengingkaran terhadap akal dan ilmu pengetahuan.
Pengakuan akan adanya ikatan yang kuat antara sebab dengan akal
melahirkan pernyataan akan adanya hubungan yarg pasti antara sebab
dengan akibat, yang pada gilirannya akan melahirkan pula suatu pengakuan
bahwa segala yang mawjũd di alam ini penuh dengan hikmah karena
hikmah berarti mengetahui sebab-sebab berdasarkan pertimbangan akal.
Pengingkaran akan adanya hubungan yang pasti antara sebab dan akibat,
berarti pengingkaran akan hikmah-hikmah yang terdapat dalam segala
yang mawjũd di alam ini. Lebih lanjut Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa
adanya akibat atau musabab yang lahir dari sebab hanya terjadi dalam tiga
bentuk.
Pertama, karena keterpaksaan, seperti seseorang makan karena lapar.
Kedua, agar musabab dalam keadaan lebih baik dan lebih sempurna, seperti
adanya dua mata bagi manusia.
Ketiga, tidak karena keterpaksaan dan juga tidak karena adanya maksud
untuk kebaikan atau kesempurnaan, hal ini berarti bahwa terjadinya
musabab dari sebab itu karena kebetulan. Konsekuensi logis dari bentuk
yang terakhir ini adalah terjadinya musabab tidak tergambarkan di
dalamnya adanya pembuat sebab, apalagi adanya hikmah karena musabab
tersebut hanya terjadi karena kebetulan.
Kelihatannya Ibnu Rusyd menempatkan Al-Ghazali khususnya dan Al-
Asy'ary umumnya pada golongan yang memilih bentuk terakhir dari ketiga
bentuk hubungan sebab akibat di atas. Mereka memandang segala yang
mawjũd di alam ini tidak memiliki esensi dan sifat yang menentukan fungsi-
fungsi khusus dari masing-masing mawjũd. Keberadaan esensi serta sifat-
sifat tersebut pada segala yang mawjũd ini hanyalah bersifat jâ'iz menurut
akal. Pandangan yang demikian, menurut Ibnu Rusyd, menunjukkan tidak
terdapatnya hikmah keserasian antara manusia dengan alam ini, hal ini
adalah tidak benar.
Dari kritik Al-Ghazali tentang ini terkesan bahwa ia mengkhawatirkan akan
meredusir kehendak mutlak Allah SWT dan memberikan kekuasaan pada
alam. Sebenarnya kekhawatiran Al-Ghazali seperti ini tidak perlu terjadi
karena sebab akibat atau sunatullah sebagai suatu keniscayaan pada
dasarnya diciptakan Allah SWT. sesuai dengan kehendak mutlak-Nya, yang
pada hakikatnya Allah SWT juga yang menentukan.
4. Hubungan sebab akibat dengan mukjizat
Telah disebutkan bahwa menurut Al-Ghazali pengakuan akan adanya
hubungan keniscayaan antara sebab akibat (kausalitas) akan
mengakibatkan orang tidak percaya terhadap adanya mukjizat nabi.
Sehubungan dengan itu, Ibnu Rusyd membedakan antara dua mukjizat,
yaitu mukjizat al-Barrâniy dan mukjizat al-Jawwâniy. Mukjizat yang disebut
pertama (al-Barrâniy), ialah mukjizat yang diberikan kepada seorang nabi,
tetapi tidak sesuai dengan risalah kenabiannya, seperti tongkat Nabi Musa
menjadi ular, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, dan lainnya.
Mukjizat jenis ini saat itu dipandang sebagai mukjizat atau perbuatan di
luar kebiasaan dan boleh jadi satu waktu akan dapat diungkapkan oleh ilmu
pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan telah dapat mengungkapkannya, ia
tidak lagi dipandang sebagai mukjizat atau perbuatan di luar kebiasaan.
Sementara itu, mukjizat yang kedua (al-Jawwâniy), ialah mukjizat yang
diberikan kepada seorang nabi yang sesuai dengan risalah kenabiannya,
seperti mukjizat Al-Qur’an bagi Nabi Muhammad Saw. Mukjizat inilah
dipandang sebagai mukjizat yang sesungguhnya, karena mukjizat jenis ini
tidak akan dapat diungkapkan oleh ilmu pengetahuan (sains) di manapun
dan kapan pun.
Ternyata Ibnu Rusyd menentang adanya mukjizat al-Barrâniy, sebagai yang
dipahami Al-Ghazali sesuatu yang terjadi penyimpangan dari adat atau
kebiasaan (khariq al-'adat). Karena itu, Nabi Isa dapat menghidupkan orang
mati, menurut Ibnu Rusyd, harus ditakwilkan dalam pengertian
menghidupkan hati orang yang tidak beriman menjadi beriman. Sedangkan
mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api, mungkin saja waktu
itu pada diri Nabi Ibrahim diberikan sifat yang tidak bisa dibakar api,
seperti sifat asbestos umpamanya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Allah
SWT mencabut sifat membakar dari api karena sifat membakar adalah sifat
zatiyah dari api. Apabila sifat ini dihilangkan pada api, ia tidak dapat lagi
disebut dengan api. Atas dasar inilah, para filosof Muslim tidak ada seorang
pun yang mengingkari kemungkinan adanya perubahan dari satu materi ke
materi lain, apabila masih dalam satu jenis materi yang memiliki unsur-
unsur yang sama, seperti api, air, udara, dan tanah. Akan tetapi, yang
diingkari filosof Muslim ialah perubahan dari satu materi ke materi lain
yang tidak memiliki unsur-unsur yang sama karena jenisnya memang
berbeda.
Tentang tuduhan Al-Ghazali bahwa para filosof Muslim menjadi kafir
lantaran tidak percaya terhadap mukjizat para nabi, dibantah Ibnu Rusyd
dengan mengatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut tidak boleh
dipermasalahkan atau diteliti para filosof. Bagaimanapun keajaiban yang
terjadi dalam Islam tidak terletak pada keajaiban seperti mengubah seutas
tali menjadi seekor ular, melainkan pada Al-Qur’an, yang keajaibannya
diakui oleh setiap manusia lewat persepsi dan pemikirannya, dan keajaiban
Al-Qur’an jauh lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Menurut Ibnu
Rusyd tidak seorang pun di antara para filosof Muslim yang
mempermasalahkan mukjizat karena hal ini termasuk soal prinsip yang
terdapat dalam syariat. Kalau ada di antara para filosof Muslim yang
membahasnya, pelakunya patut dihukum.
PEMIKIRAN AL GHAZALI
Tentang
Hukum Sebab Akibat (Kausalitas) dan Mukjizat
Dalam bukunya Tahafut al-Faldsifat, Al-Ghazali mempersoalkan masalah
khariq al-'dat (menyalahi kebiasaan) yang erat kaitannya dengan masalah
hukum kuasalitas, dalam pengertian, apakah hubungan antara sebab dan
akibat merupakan hubungan yang pasti. Hal ini, menurutnya, dapat
menyebabkan seseorang mempercayai atau tidak mempercayai adanya
mukjizat para nabi, yang olehnya, mukjizat ia artikan sebagai hal yang
menyimpang dari kebiasaan alam.
Telah disebutkan bahwa Al-Ghazali sebenarnya tidak mengingkari adanya
hukum kausalitas. Namun yang ia ingkari adalah pendapat para filosof
Muslim yang mengatakan bahwa hubungan sebab akibat merupakan
hubungan kepastian atau keniscayaan. Sikap Al-Ghazali ini didasari oleh
konsep bahwa Allah adalah Pencipta segala yang ada termasuk peristiwa
yang berada di luar kebiasaan. Pada sisi lain, untuk menjaga jangan sampai
terjadi adanya anggapan di kalangan kaum Muslimin bahwa apa yang
terjadi di alam ini hanya disebabkan kekuatan kebendaan semata. Padahal,
ada sebab lain di balik kebendaan itu yang merupakan rahasia tersembunyi,
yang justru inilah yang merupakan sebab hakiki, yakni Allah. Pendapat Al-
Ghazali selengkapnya tentang ini terdapat dalam kitabnya Tahafut al-
Falasifat, yang secara garis besarnya dapat dipaparkan sebagai berikut.
Menurut Al-Ghazali, hubungan antara sebab dan akibat tidak bersifat
dharuriy (kepastian), dalam pengertian keduanya tidak merupakan
hubungan yang mesti berlaku, tetapi keduanya masing-masing memiliki
individualitasnya sendiri. Sebagai contoh, antara makan dan kenyang tidak
terdapat hubungan yang bersifat keniscayaan. Artinya, orang makan tidak
niscaya merasa kenyang karena makan tidak mesti menyebabkan orang
kenyang. Begitu pula kertas tidak mesti terbakar oleh api, air tidak mesti
membasahi kertas atau kain. Semua ini hanya merupakan adat atau
kebiasaan alam, bukan suatu kemestian. Terjadinya segala sesuatu di dunia
ini karena kekuasaan dan kehendak Allah semata. Karena itu, kalau kertas
yang terbakar terkena api, orang makan menjadi kenyang, dan kain basah
terkena air, itu semua semata-mata hanya karena kekuasaan dan iradah
Allah. Lebih lanjut ia katakan bahwa seorang ayah bukan pembuat (fa'il)
terhadap anaknya. la tidak bisa mengadakan anaknya dengan menaburkan
benih (nuthfah) kepada rahim istrinya. la juga tidak mampu menjadikan
anaknya laki-laki atau perempuan, lengkap anggota badannya sesuai
dengan keinginannya. Anak itu ada dan lahir ke dunia karena Sebab
Pertama, yakni Allah Swt.
Dengan demikian, tidak benar anggapan bahwa api itu pembuat terbakar,
obat itu pembuat sembuh, roti itu pembuat kenyang, dan lain sebagainya.
Kata Al-Ghazali, para filosof Muslim mengingkari kasus tidak terbakarnya
Nabi Ibrahim ketika dibakar dengan api. Mereka menganggap hal itu tidak
mungkin, kecuali dengan menghilangkan sifat membakar dari api atau
mengubah diri (zat) Nabi Ibrahim menjadi suatu materi yang tidak bisa
terbakar oleh api.
Menurut pandangan Al-Ghazali bahwa api itu tidak membakar Nabi Ibrahim
karena memang api bukan pembuat terbakar. Akan tetapi, hal itu adalah
perbuatan Allah dengan kudrat dan iradat-Nya, baik karena api berubah
sifatnya menjadi tidak membakar atau Nabi Ibrahim berubah materinya
menjadi materi lain sehingga ia menjadi tidak terbakar oleh api. Begitu pula
seseorang yang bepergian, di rumahnya ditinggalkannya seekor kambing
dan ketika ia pulang, kambing telah berubah menjadi seekor harimau. Batu
bisa menjadi emas atas izin Allah. Karena itu, kata Al-Ghazali, kejadian-
kejadian yang menyimpang dari kebiasaan di alam bisa saja terjadi atas ke-
hendak dan iradat Allah.
Demikian juga halnya kasus Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati,
tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, bisa terjadi karena menyangkut
materi yang sifatnya menerima perubahan. Tanah berubah menjadi
tanaman, tanaman dimakan oleh binatang lalu berubah menjadi darah,
darah berubah menjadi air mani binatang jantan dan kalau bertemu dengan
sel telur dalam rahim binatang betina akan berubah menjadi janin, dan
seterusnya akan melahirkan hewan sejenisnya. Rentetan kejadian di atas
berlaku berdasarkan kebiasaan yang berlangsung dalam masa yang relatif
panjang. Akan tetapi, tidak-lah mustahil apabila dengan kehendak dan
kekuasaan Allah proses panjang tersebut berubah menjadi lebih singkat
sebagaimana proses yang berlaku pada mukjizat pada nabi.
Kalau dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada para nabi yang
menyimpang dari kebiasaan, apakah hal ini terjadi karena kekuatan diri
nabi sendiri atau disebabkan hal lain? Dalam hal ini baik para filosof Muslim
maupun Al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, sebagaimana para
filosof bisa menerima terjadinya hujan, petir, gempa bumi atas kekuatan
diri nabi atau karena hal lain. Namun yang lebih penting, kata Al-Ghazali,
harus mengakui bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah, baik secara
langsung maupun melalui perantaraan malaikat sebagai mukjizat untuk
menguatkan bukti kenabian mereka.
Dalam masalah perubahan jenis, seperti hitam berubah menjadi putih, batu
berubah menjadi emas, benda berubah menjadi binatang, dengan kehendak
dan kekuasaan-Nya, Allah bisa saja melakukan hal yang demikian karena ia
tidak tergolong padu hal yang mustahil. Sebab hal yang mustahil adalah
menetapkan sesuatu dan meniadakannya sekaligus pada waktu yang
bersamaan, atau menetapkan dua hal yang berlawanan sekaligus. Contoh,
menetapkan hitam dan putih terhadap suatu benda pada waktu yang
bersamaan, termasuk perkara yang mustahil. Kalau kita menetapkan hitam
pada suatu benda, berarti kita meniadakan putih daripadanya. Begitu pula
sebaliknya, jika kita menetapkan putih padanya, berarti kita meniadakan
hitam padanya. Menetapkan putih dan hitam pada suatu benda dalam
waktu yang bersamaan, itulah yang mustahil. Dengan demikian, kalau
dikatakan bahwa Allah mampu mengubah batu menjadi emas, atau
mengubah tongkat menjadi ular, tidaklah termasuk perkara yang mustahil.
Selanjutnya, Al-Ghazali berkata jika dikatakan tanah berubah menjadi
hewan, dan antara 'aradl atau accident dengan jauhar (atom) bukanlah
materi yang berserikat (seperti darah dan nuthfah, air dan udara), dan
bukan materi yang berserikat pula semua jenis, dari segi ini, hal tersebut
adalah mustahil. Apabila Allah menggerakkan tangan orang mati, lalu
duduk, kemudian menulis sehingga menghasilkan tulisan yang teratur, hal
ini tidaklah mustahil, jika kita membolehkan terjadinya hal-hal baru pada
iradat bebas Allah. Hanya saja hal ini diingkari karena terjadinya sesuatu
yang berlawanan dengan adat atau kebiasaan. Sementara itu, Al-Ghazali
mengembalikan semua itu kepada kehendak dan kekuasaan mutlak Allah.
Atas kehendak dan kekuasaan-Nya semuanya bisa terjadi meskipun
berlawanan dengan kebiasaan. Dari segi inilah terjadinya mukjizat para
nabi.
Anda mungkin juga menyukai
- Menyingkap Sandi Al-Qur'an: Tafsir Sufi yang UnikDari EverandMenyingkap Sandi Al-Qur'an: Tafsir Sufi yang UnikPenilaian: 2 dari 5 bintang2/5 (2)
- Pernyataan Keaslian Skripsi DKKDokumen21 halamanPernyataan Keaslian Skripsi DKK2250161138anggiBelum ada peringkat
- Filsafat Islam Kel, 7Dokumen12 halamanFilsafat Islam Kel, 7Richlatul QurbaBelum ada peringkat
- Fasl Maqal Ibn Rushd Persoalan Ilmu Allah Itu Juz - Atau KulliDokumen2 halamanFasl Maqal Ibn Rushd Persoalan Ilmu Allah Itu Juz - Atau KulliMuhammad AkmalBelum ada peringkat
- Filsafat IslamDokumen6 halamanFilsafat Islamريدا حديبيهBelum ada peringkat
- Makalah Al-Ghazal Ibnu Rusyd Serta Averoisme Dan Analisis Perbandingan Pemikiran Serta Pengaruhnya Terhadap RenaisanceDokumen19 halamanMakalah Al-Ghazal Ibnu Rusyd Serta Averoisme Dan Analisis Perbandingan Pemikiran Serta Pengaruhnya Terhadap RenaisanceNiramustanirah100% (1)
- Konsep AlamDokumen17 halamanKonsep AlamAli KhaidarBelum ada peringkat
- Hukum Kausalitas (Ghazali Vs Ibn Rusyd)Dokumen3 halamanHukum Kausalitas (Ghazali Vs Ibn Rusyd)Amar UdinBelum ada peringkat
- Iman Takdir Hidup Dalam KetaraturanDokumen10 halamanIman Takdir Hidup Dalam KetaraturanMuhammad AseffudinBelum ada peringkat
- Pembuktian Adanya Tuhan Oleh para Filsuf Barat Klasik Dan Imam AlDokumen4 halamanPembuktian Adanya Tuhan Oleh para Filsuf Barat Klasik Dan Imam AlS HafidzBelum ada peringkat
- Tuhan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan IslamDokumen3 halamanTuhan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan IslamDream Theatre100% (1)
- Jalan Menuju KeimananDokumen31 halamanJalan Menuju KeimananAisy FitriyaniBelum ada peringkat
- HAKIKAT ALAM SEMESTA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Meihesa Khairul Maknun)Dokumen15 halamanHAKIKAT ALAM SEMESTA DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM (Meihesa Khairul Maknun)Andi Saputra siraitBelum ada peringkat
- Buku Kaidah Kausalitas Memahami Hubungan Sebab Akibat Dalam Realitas Kehidupan MuslimDokumen31 halamanBuku Kaidah Kausalitas Memahami Hubungan Sebab Akibat Dalam Realitas Kehidupan MuslimAlfa siryBelum ada peringkat
- Filsafat Ibnu RusydDokumen5 halamanFilsafat Ibnu RusydRifqi Ridha Bin GusharyaBelum ada peringkat
- Filsafat Islam Ibnu RusydDokumen12 halamanFilsafat Islam Ibnu RusydAndhika BgskraBelum ada peringkat
- Makalah Agama P1 INDIVIDUDokumen19 halamanMakalah Agama P1 INDIVIDUAlfin komaru zamanBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen15 halamanBab IiiOppai ChanBelum ada peringkat
- Middle Filsafat AzizahDokumen2 halamanMiddle Filsafat AzizahAzzahofficialBelum ada peringkat
- Filsafat IslamDokumen3 halamanFilsafat IslamfardinaningsihBelum ada peringkat
- Fitrah Beragama Bagi ManusiaDokumen11 halamanFitrah Beragama Bagi Manusiaerick 0928Belum ada peringkat
- Kliping Peristiwa Yang Menggambarkan Takdir Allah Berlaku Bagi Semua MakhluknyaDokumen10 halamanKliping Peristiwa Yang Menggambarkan Takdir Allah Berlaku Bagi Semua MakhluknyaRahmatHidayatBelum ada peringkat
- Hukum Kausalitas Menurut Pemikiran ReligioDokumen6 halamanHukum Kausalitas Menurut Pemikiran Religionurindah sariBelum ada peringkat
- Studi Integrasi Islam Dan SainsDokumen25 halamanStudi Integrasi Islam Dan SainsZam SalavyBelum ada peringkat
- Assignment Ijaz Al-QuranDokumen24 halamanAssignment Ijaz Al-QuranMuhammad RilwanBelum ada peringkat
- Hakikat Manusia (Aismuh) SeepDokumen18 halamanHakikat Manusia (Aismuh) SeepEry AngreyniBelum ada peringkat
- Polemik Pemikiran Filsafat Al-Ghazali Dan Ibnu RusydDokumen5 halamanPolemik Pemikiran Filsafat Al-Ghazali Dan Ibnu RusydDaniel JochiBelum ada peringkat
- Soal Filsafat UasDokumen4 halamanSoal Filsafat Uasatik nuryantiBelum ada peringkat
- MAKALAH FIKIH MUNAKAHAT KELOMPOK Empat-1Dokumen18 halamanMAKALAH FIKIH MUNAKAHAT KELOMPOK Empat-1Nurma ZigarBelum ada peringkat
- Fitrah Dan IslamDokumen9 halamanFitrah Dan Islamverchat bellaBelum ada peringkat
- Hadist Fitrah Kel 1Dokumen15 halamanHadist Fitrah Kel 1veniBelum ada peringkat
- Makalah - Pendidikan - Agama - Islam-Kelompok 1Dokumen17 halamanMakalah - Pendidikan - Agama - Islam-Kelompok 1Dika NuryansahBelum ada peringkat
- Konsep Takdir Dalam Peningkatan SDMDokumen10 halamanKonsep Takdir Dalam Peningkatan SDMDwi Susanti PutriBelum ada peringkat
- Tugas Ulangan Tengah SemesterDokumen12 halamanTugas Ulangan Tengah Semesterjamil boneBelum ada peringkat
- Filsafat Al-GhazaliDokumen9 halamanFilsafat Al-GhazaliZackiBelum ada peringkat
- Hubungan Ilmu Fiqhi Dengan Ilmu LainnyaDokumen14 halamanHubungan Ilmu Fiqhi Dengan Ilmu LainnyaAksan 2023Belum ada peringkat
- ISLAMICDokumen15 halamanISLAMICAnnisa Ayu ShalihaBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 4 - FITRAH MANUSIA DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKANDokumen13 halamanMakalah Kelompok 4 - FITRAH MANUSIA DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKANFitri WinartiBelum ada peringkat
- Tugas Ipi Pgmi 4 ElviraDokumen14 halamanTugas Ipi Pgmi 4 ElviraElviraBelum ada peringkat
- Makalah Kel.7Dokumen13 halamanMakalah Kel.7Viola LastaniaBelum ada peringkat
- Pandangan AlghazaliDokumen7 halamanPandangan AlghazaliFieza AqillaBelum ada peringkat
- Irfan Nurhadi (Ulumul Quran)Dokumen15 halamanIrfan Nurhadi (Ulumul Quran)Irfan NurhadiBelum ada peringkat
- Asep Biografi Al KindiDokumen56 halamanAsep Biografi Al KindiAdin Ahsan El-SiradzBelum ada peringkat
- Makalah IpiDokumen14 halamanMakalah IpiElviraBelum ada peringkat
- Tugas Uas Filsafat ThosimahDokumen21 halamanTugas Uas Filsafat ThosimahthosimahBelum ada peringkat
- Tugas Filsafat AL GHAZALIDokumen5 halamanTugas Filsafat AL GHAZALIalpatBelum ada peringkat
- Makalah Metodologi Studi Islam Kelompok 2Dokumen38 halamanMakalah Metodologi Studi Islam Kelompok 2onyour faBelum ada peringkat
- Kel.9 Filsafat IslamDokumen9 halamanKel.9 Filsafat IslamBagus Adnan1704Belum ada peringkat
- Ibn RusydDokumen14 halamanIbn RusydZaenul AbidinBelum ada peringkat
- Hakikat Manusia Keimanan Dan Ibadah Dalam IslamDokumen16 halamanHakikat Manusia Keimanan Dan Ibadah Dalam IslamSandi SendiBelum ada peringkat
- Artikel Berpasangan Paling FinalDokumen9 halamanArtikel Berpasangan Paling FinalSkip IklanBelum ada peringkat
- MAKALAH I'Jazul Quran - AfnanDokumen18 halamanMAKALAH I'Jazul Quran - AfnanKhoirul AnamBelum ada peringkat
- 4821 10279 1 SMDokumen7 halaman4821 10279 1 SMIbnu AprizalBelum ada peringkat
- Hakikat Manusia Keimanan Dan Ibadah Dalam Islam PDFDokumen16 halamanHakikat Manusia Keimanan Dan Ibadah Dalam Islam PDFSandi SendiBelum ada peringkat
- Makalah Ayat Ayat Kauniyyah Dalam Al QurDokumen22 halamanMakalah Ayat Ayat Kauniyyah Dalam Al QurArifin FauziBelum ada peringkat
- Asbabun NuzulDokumen10 halamanAsbabun NuzulfathnuchusainBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen22 halamanBab IiiWafa KhildaBelum ada peringkat
- Mukjizat Al-Qur'an 11Dokumen16 halamanMukjizat Al-Qur'an 11muhammad tahirBelum ada peringkat
- Makalah Prespektif Islam Tentang AlamDokumen16 halamanMakalah Prespektif Islam Tentang AlamAriani Al GhomaishaBelum ada peringkat
- Sumber KausalitasDokumen16 halamanSumber KausalitasABDUL AZIZ UNPAMBelum ada peringkat
- Mar'Atus Sholihah (Pai SD)Dokumen3 halamanMar'Atus Sholihah (Pai SD)Minanur RochmanBelum ada peringkat
- Makalah MBM LatifDokumen15 halamanMakalah MBM LatifMinanur RochmanBelum ada peringkat
- SPI Lulu'Il Ma'Nun PDFDokumen15 halamanSPI Lulu'Il Ma'Nun PDFMinanur RochmanBelum ada peringkat
- 1 - Ontologi Islam - OkDokumen11 halaman1 - Ontologi Islam - OkMinanur RochmanBelum ada peringkat
- Manajemen Isa Pai DDokumen11 halamanManajemen Isa Pai DMinanur RochmanBelum ada peringkat
- Makalah MPI Tema 3 - Kurnia NF PDFDokumen18 halamanMakalah MPI Tema 3 - Kurnia NF PDFMinanur RochmanBelum ada peringkat
- Makalah FilsafatDokumen11 halamanMakalah FilsafatMinanur RochmanBelum ada peringkat