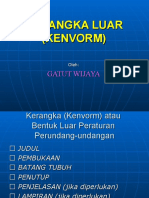Sifat Pemberat Pidana
Diunggah oleh
Ockee KecillDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Sifat Pemberat Pidana
Diunggah oleh
Ockee KecillHak Cipta:
Format Tersedia
SIFAT PEMBERAT PIDANA
Pemberat
Pidana
yang
Bersifat
Primer
Pemberat pidana yang bersifat primer adalah dasar pemberatan pidana utama yang mengacu pada KUHP dan undang-undang pidana khusus (hukum pidana materiil) untuk dijadikan pedoman pemberatan pidana pada tahap penyidikan, penuntutan dan mengadili. Dengan demikian, penerapan prinsip pemberat pidana primer ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penyusunan surat dakwaan oleh kejaksaan, penyusunan surat tuntutan, maupun ketika akan menjatuhkan pidana. Seorang Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tentunya harus memperhatikan hitungan pidana terberat yang dapat diberikan pada terdakwa dalam hal adanya alasan pemberat pidana. Hitungan pidana terberat tersebut tidak boleh diabaikan. Oleh karena, apabila pidana yang dituntut atau dijatuhkan lebih diperberat lagi dari pidana maksimum (khusus) yang telah diperberat maka hal ini merupakan penyimpangan dari sistem pemidanaan maksimum (khusus). Akibat hukumnya tidak ditegaskan dengan pasti baik dalam KUHP maupun KUHAP. Akan tetapi, dilihat dari sisi praktik, kelalaian ini merupakan eelah hukum bagi pelaku atau lawyer-nya untuk melakukan perlawanan hukum. Misalnya saja, mengajukan pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan/atau mengajukan upaya hukum atas ada putusan pemidanaan. Lebih jauh, putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (vanreehtsweenietig) oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sekalipun dalam pemidanaan mengacu pada prinsip kebebasan hakim namum titik tolak penjatuhan pidana tetap harus mengacu pada aneaman maksimum dalam pasal yang didakwakan. Sejalan dengan ini, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa: "Memang benar, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang dianeamkan dalam pasal yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, harus didasarkan pada aneaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan". Senada dengan itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pada dasamya kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana bukanlah kebebasan yang tanpa batasan. Hakim memang bebas memilih bentuk pidana pokok dan menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Namun demikian, telah ditentukan adanya pola pemidanaan dengan batas maksimum dan minimum. Lebih lanjut dinyatakan bahwa batas maksimum adalah maksimum umum dan maksimum khusus. Maksimum umum bagi pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut,
pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun, sementara pidana denda tidak ada maksimum umumnya. Apabila ada alasan pemberatan maka pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 (dua puluh) tahun, pidana kurungan menjadi maksimum l (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 (delapan) bulan. Sementara maksimum khusus dieantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik. Dengan kata lain, maksimum khusus adalah maksimum pidana yang telah dirumuskan dalam delik-delik tertentu saja. Pentingnya perhitungan atas pemberatan pidana harus sudah diperhatikan sejak pelaku disidik (apakah ada alasan pemberat), dituntut (berapakah maksimum lamanya tuntutan pidana), dan dipidana (berapakah lamanya pidana yang dapat dijatuhkan). Seorang penyidik hams mampu menilai apakah dalam fakta hukum ditemukan adanya alasan yang dapat memberatkan tersangka. Apabila ada, maka hal tersebut akan dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Kemudian diteruskan sebagai dasar lamanya tuntutan pidana dalam surat tuntutan serta sebagai dasar lamanya pemidanaan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, seorang penyidik hams mampu mengidentifikasi ada atau tidaknya alasan pemberat pidana dalam suatu tindak pidana tertentu. Seorang jaksa dan hakim harus mampu menghitung aneaman dan penjatuhan pidana maksimal yang dapat diberikan pada terdakwa. Sementara itu, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjabarkan ada 6 alasan untuk pemberat pemidanaan, yaitu: 1. Seorang pejabat melanggaar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 2. Waktu melakukan kejahatan, menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, 3. Karena Pengulangan (reeidive), 4. Karena Gabungan (samenloop), 5. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang seeara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana 6. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas ummn bagi ketentuan hukum pidana khusus. Dari 6 (enam) hal yang dikemukakan E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi di atas tampaknya sama dengan 5 (lima) hal yang telah penulis kemukakan sebelumnya. Hanya hal nomor 6 yang menunjukkan perbedaan dengan 5 (lima) alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut mereka, adanya point ke-6 merujuk pada pengaturan dalam undang-undang pidana khusus bagi militer (KUHPM). Lebih lanjut dikatakan: "Dalam KUHPM ditemukan pula dasar-dasar umum
tentang penambahan (pemberatan. Pen) pidana yang berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diatur dalam buku ke II KUHPM, seperti misalnya keadaan-keadaan: 1. Dilakukan pada waktu perang oleh seseorang yang tunduk pada Mahkamah Militer (Pasal 2 jo Pasal 35 KUHPM); 2. Melanggar kewajiban jabatan dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 52 KUHP (Pasal 36 KUHPM); 3. Seorang atasan yang bersama-sama dengan bawahannya melalukan suatu kejahatan bersenjata (Pasal 38 KUHPM). Demikian pula terdapat beberapa dasar penambahan (pemberatan. Pen) pidana dalam pasal tindak pidana KUHPM, yang seeara khusus ditentukan antara lain keadaan: (1) dilakukan dalam dinas, dan (2) apabila petindak (pelaku. Pen) adalah perwira yang memegang komando dan lain sebagainya." Namun demikian, masalah point nomor 6 tersebut tidak akan dibahas lebih jauh dalam tulisan ini. Hanya saja memang perlu untuk diketahui bahwa dalam KUHPM juga mengatur adanya masalah pemberatan pidana sebagaimnana yang diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, penjelasan selanjutnya akan mengacu pada 5 (lima) alasan saja sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Berikut ini akan dijelaskan satu-persatu tentang (lima) hal yang rnerupakan dasar peringan pidana yang bersifat primer tersebut.
A. Dasar Pemberat Pidana Karena Jabatan Dasar pemberatan pidana karena jabatan ini diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan bahwa: "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Seorang pejabat yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah seorang pegawai negeri sipil. Di samping itu, ketentuan tersebut juga menggariskan adanya beberapa unsur yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat pemidanaan (ditambah sepertiga) bagi seorang pegawai negeri sipil, yaitu: 1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; 2. Memakai kekuasaan jabatannya; 3. Menggunakan kesempatan karena jabatannya; dan 4. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.
Dari 4 (empat) unsur pegawai negeri sipil berdasarkan Pasal 52 tersebut sebenamya masih dapat disederhanakan lagi hanya menjadi 2 (dua) unsur yaitu: 1. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; dan 2. Memakai kekuasaan, mengunakan kesempatan, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Menurut A. Zainal Abidin Farid," alasan pemberat pidana karena jabatan ini jarang sekali digunakan dalam praktik oleh penuntut umum dan hakim. Bahkan menurut beliau pemberat pidana karena jabatan seolah-olah tidak dikenal dalam praktik oleh karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52. Misalnya, seorang dosen yang memukul mahasiswanya tidak memenuhi syarat nomor 1, sekalipun ia adalah pegawai negeri sipil. Syarat nomor 1 juga tidak terpenuhi dalam kasus seorang polisi yang seharusnya bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman umum justru melakukam peneurian. Barulah anggota polisi tersebut melanggar kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang ditugaskan khusus untuk menjaga uang suatu bank negara, lalu ia sendiri meneuri uang ini. Syarat nomor 2 juga sering tidak dipenuhi oleh seorang pegawai negeri sipil. Misalnya seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor kepolisian sebagai juru ketik tidak dapat dikenakan pemberatan dalam Pasal 52 kalau ia menahan seseorang di tahanan kepolisian. Sebaliknya, apabila yang merampas A kemerdekaan seseorang adalah seorang penyidik perkara pidana maka barulah dapat dikatakan memenuhi syarat nomor 2. Demikian juga apabila seorang anggota kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan senjata dinasnya maka disini telah memenuhi syarat nomor 2. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dikemukakan di sini adalah: apakah pemberatan pidana karena jabatan dalam Pasal 52 ini berlaku juga untuk "Kejahatan Jabatan" dan "Pe1anggaran Jabatan" sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII Buku Kedua dan Bab VIII Buku Ketiga KUHP? Menurut doktrin, ketentuan dalam Pasal 52 tidak dapat diberlakukan sebagai alasan pemberat pidana untuk "Kejahatan Jabatan" dan "Pelanggaran Jabatan" sebagaimana diatur dalam Bab XXVIII Buku Kedua dan Bab VIII Buku Ketiga KUHP. B. Dasar Pemberat Pidana Karena Menggunakan Bendera Kebangsaan Dasar pemberatan pidana karena menggunakan bendera kebangsaan ini diatur dalam Pasal 52a KUHP yang menyatakan bahwa: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah
sepertiga (garis bawah dari penulis)". Merujuk pada Pasal 52a di atas tampak bahwa tidak disebutkan dengan tegas tentang penggunaan bendera kebangsaan dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pemberatan pidana karena penggunaan bendera kebangsaan dalam suatu tindak pidana dapat dinilai sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim. Mereka dapat menguji seeara kasuistis tentang penggunaan bendera kebangsaan dalam suatu tindak pidana. Kuneinya adalah adanya keterkaiatan erat antara tindak pidana dengan penggunaan bendera kebangsaan. Paling tidak ada 2 (dua) hal yang dapat dijadikan pedoman. Pertama, penggunaan bendera kebangsaan dengan tujuan untuk memudahkan si-pelaku melakukan aksinya. Kedua, penggunaan bendera kebangsaan dalam suatu tindak pidana sehingga menimbulkan penodaan terhadap martabat bangsa. Pada dasarya, kedua hal di atas jelas dapat menimbulkan penodaan terhadap bangsa. Bendera kebangsaan adalah lambang kebesaran dari masyarakat suatu negara. Apabila seseorang melakukan tindak pidana dengan menggunakan bendera kebangsaan maka akan ada kemungkinan negatif yang ikut timbul. Seperti, adanya beban psikologis bagi orang-orang yang sangat hormat dengan bendera kebangsaan. Atau, merupakan penghinaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Adami Ehazawi, alasan pemberatan pidana dalam penggunaan bendera kebangsaan ini dapat ditinjau seeara obyektif, yaitu akan mengelabui orang-orang untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang dilakukan si pembuat itu adalah suatu perbuatan yang resmi guna mempermudah si pelaku dalam melakukan aksinya. Patut juga dikemukakan di sini bahwa masuknya Pasal 52a KUHP ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang "Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. l Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana", disahkan pada tanggal 20 September 1958. Di samping itu, undang-undang ini juga meneabut Pasal XVI Undang Undang No. 1 Tahun 1946 dan memasukkan beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 142a, Pasal l54a, termasuk Pasal 52a sebagaimana dikemukakan di atas, yang kesemuanya menyangkut bendera Indonesia dan bendera negara sahabat. C. Dasar Pemberat Pidana Karena Residive Adanya peryataan bahwa residive adalah sama tuanya dengan kejahatan tampak memang ada benarnya. Dilihat dari sistem hukum yang berlaku di dunia, pengaturan tentang residive sudah ada dalam Hukum Romawi berabad-abad lamanya. Pengaturan tentang residive ini
kemudian dituangkan juga dalam Eode Penal Praneis yang merupakan eikal bakal hukum pidana Belanda (W.v.S). Pada waktu Eode Penal Praneis diberlakukan di Belanda maka berlaku aturan bahwa bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana apa saja merupakan sorang residivis. Untuk itu, ia juga akan diperberat pidananya sesuai dengan ketentuan tentang residive. Di masyarakat sering sekali terdengar adanya perbineangan mengenai seorang residivis dalam beberapa peristiwa kriminal. Masyarakat pada umumnya mengartikan bahwa residivis adalah seorang penjahat yang telah selesai menjalankan pidananya atau seorang penjahat yang telah keluar dari penjara. Biasanya dikonotasikan sebagai orang jahat, kejam, bengis, tidak beragama, tidak berperikemanusiaan, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residivis adalah orangnya sedangkan untuk perbuatannya dapat disebut dengan residive. Kiranya telah dapat dimengerti bahwa reeidive adalah sama dengan pengulangan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, reeidive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (in kraeht van gewysde), kemudian melakukan suatu tidak pidana lagi. Senada dengan itu, I Made Widnyana mengatakan bahwa reeidive itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatanpidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Demikian juga pendapat A. Zainal Abidin Farid tampaknya sama dengan pendapat Barda Nawawi Arief dan I Made Widnyana tentang reeidive. A. Zainal Abidin Faridm menyatakan bahwa reeidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik.Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa residive adalah sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, Akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya. Residive merupakan salah satu alasan pemberat pidana yang bersifat primer. Menurut I Made Widnyana, adapun yang menjadi alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat bagi residivis adalah sebagai berikut:"Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian ia melakukan perbuatan itu lagi, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik.
Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka reeidivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam Lembaga Pemasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Tetapi meskipun demikian teh juga ia melakukan perbuatan pidana lagi". Menurut Adami Ehazawi, rasio dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini adalah terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu: 1. Faktor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana; 2. Faktor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama; 3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. Adapun sistem pemberatan pidana berdasarkan residive pada umumnya dikenal adanya 2 (dua) sistem, yaitu residive umum dan residive khusus. Berikut 1. ini Residive bandingannya: umum.
Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulanganya, maka dalam sistem ini tidak ada daluarsa 2. Residive khusus.\ Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan untuk pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana teitentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula. Di samping kedua sistem pemberatan pidana untuk reeidive di atas, ada juga yang menambahkan dengan sistem ketiga, yaitu: tussen stelsel. Artinya, sistem yang tempatnya antara reeidive umum dan reeidive khusus. Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Aehmad, sistem antam atau tussen stelsel untuk reeidive ini adalah pengatuian tentang reeidive berdasarkan pengelompokan beberapa kejahatan yang menurut sifatnya dianggap sama. Beberapa kejahatan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan apabila terjadi pengulangan dalam kelompok kejahatan tersebut maka si pelakunya dapat dikenai pemberatan tentang reeidive. reeidive.
Sementara itu, I Made Widnyana menjelaskan tussen stelselsebagai berikuezs "Tussen stelsel terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan lagi atau kembali orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undangundang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang". Lebih lanjut, beliau menjelaskan maksud dari "perbuatan pidana menurut penggolongan undang-undang" dalam hal tussen stelsel. Adapun maksudnya adalah undang-undang menentukan dulu sejumlah perbuatan pidana, dan dibaginya dalam golongan-golongan yang menurut sifatnya dianggap sama. Dan semua perbuatan pidana yang sifatnya sama itu dimaksudkan dalam satu golongan. Dalam hal demikian, tindak pidana yang menurut sifatnya dianggap sama seperti tindak pidana peneurian, penggelapan dan perampasan. Ketiga tindak pidana tersebut merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan (asal tertuju dalam harta kekayaan). Misalnya: A melakukan peneurian, setelah diadili dan dipidana serta menjalani pidananya kemudian A dikembalikan ke masyarakat bebas. Bilamana kemudian A melakukan delik lagi yang sifatnya sama dengan delik terdahulu (misalnya: penggelapan dan perampasan), maka pidananya dapat diperberat. Bagaimana pengaturan reeidive dalam KUHP? Berdasarkan doktrin, pengaturan reeidive dalam KUHP tidak mengenal reeidive unum, melainkan menganut sistem tussen stelsel dan reeidive khusus. Namun ada juga yang menyatakan bahwa pengaturan reeidive dalam KUHP hanya menganut sistem reeidive khusus. Berdasarkan pengertian dari reeidive khusus (pengulangan hanya untuk delik yang sama: pembunuhan diulangi dengan pembunuhan, peneurian diulangi dengan peneurian, pemerkosaan diulangi dengan pemerkosaan, dan sebagainya) maka penulis sependapat untuk menyatakan bahwa pemberatan pidana karena reeidive yang dianut dalam KUHP adalah menganut sistem tussen stelsel dan reeidive khusus. Berikut akan dijelaskan tentang kedua sistem tersebut. D. Dasar Pemberat Pidana Karena Gabungan/Perbarengan Tindak Pidana Apabila mempelajari pemberat pidana karena gabungan/perbarengan tindak pidana maka terlebih dahulu harus dipahami tentang pengertian dari gabungan/perbarengan tindak pidana itu sendiri. Dalam Bahasa Belanda, istilah gabungan/perbarengan tindak pidana disebut dengan samenloop van strafbare feiten. Singkatnya eukup samenloop. Disamping itu, dalam dunia ilmu pengetahuan hukum pidana istilah perbarengan/gabungan tindak pidana juga sering disebut
dengan istilah eoneursus. Sehubungan dengan itu, apabila dalam pembahasan bab ini menyebutkan eoneursus atau samenloop maka maknanya adalah gabungan/gmerbarengan tindak pidana. Menurut Lamintang 3 ajaran mengenai samenlaop merupakan salah satu ajaran yang tersulit di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Sehubungan dengan itu, Lamintangy kemudian menyatakan bahwa seseorang tidak akan dapat memahami apa yang sebenamya dimaksud dengan samenloop van strafbare feiten itu sendiri apabila tidak mengikuti perkembangan paham- paham mengenai perkataan feit yang terdapat di dalam rumusan pasalpasal yang mengatur masalah samenloop itu sendiri, khususnya yang terdapat di dalam rumusan Pasal 63 ayat (1).
E. Dasar Pemberat Pidana Dalam Beberapa Delik Tertentu (Dalam KUHP dan Dalam Berbagai Peraturan Perundangundangan Pidana di Luar KUHP). Selain dasar pemberat pidana yang diatur dalam Buku Kesatu KUHP, dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP juga mengatur adanya pemberatan pidana dalam pasal-pasal tertentu seeara khusus. Dasar pemberat pidana ini sebenamya mengacu pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang penerapan aturan pidana yang bersifat khusus (asas "Iex speeialis derogat legi generali"). Benar apa yang dikemukakan Jan Remmelink bahwa Pasal 63 ayat (2) KUHP kurang tepat dimasukkan dalam Bab tentang perbarengan tindak pidana. Sehubungan dengan itu, menurut penulis ketentuan ini akan lebih tepat kalau dimasukkan ke dalam aturan penutup dari Buku Kesatu KUHP. Tepatnya sebelum Pasal 103 KUHP, yang mana Pasal 103 KUHP juga dapat dikatakan mengandung asas "lex speeialis derogat legi generali". Akan tetapi patut diketahui bahwa logika hukum penerapan diantara kedua pasal itu memang berbeda. Pasal 103 merupakan pengeeualian dari Buku Kesatu KUHP dengan Undangundang Pidana Khusus di luar KUHP. Sementara Pasal 63 ayat (2) KUHP merupakan pengeeualian dari Buku Kedua dan Ketiga KUHP dengan Undang-undang Pidana Khusus. Di samping itu, Pasal 63 ayat (2) bisa juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam memilih pasalpasal yang bersifat khusus, baik pada Buku Kedua KUHP, Buku Ketiga KUHP dan juga pasalpasa1 yang bersifat khusus dalam Undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP, guna diterapkan pada suatu kasus yang bersifat khusus pula.
Pemberat Pidana yang Bersifat Sekunder
Maksud dari pemberat pidana yang bersifat sekunder adalah perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam surat tuntutan (requisitoir) dan putusan pengadilan. Hal ini sama dengan perumusan hal-hal yang meringankan pidana dalam surat tuntutan (requisitoir) dan putusan pengadilan yang harus disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab III tentang prinsip-prinsip peringan pidana. Sehubungan dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa pemberat pidana yang bersifat sekunder ini diterapkan pada proses mengadili, yaitu pada tahap penyusunan surat tuntutan (requisitoir) dan pada tahap penyusunan putusan pengadilan.
A. Pemberat Dalam Surat Tuntutan (Requisitoir) Materi tentang pemberat pidana dalam surat tuntutan (requisitoir) di sini memiliki dasar beriikir yang sama dengan materi tentang peringan pidana dalam surat tuntutan (requisitair). Oleh karena perumusan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam surat tuntutan (requisitoir) diletakkan dalam susunan yang bergandengan. Sebelum mengajukan tuntutan pidana maka seorang jaksa penuntut umum akan merumuskan hal-hal yang memberatkan dan diikuti dengan merumuskan hal-hal yang meringankan.
B. Pemberat dalam Putusan Pengadilan (PN, PT, MA) Materi tentang pemberat pidana dalam putusan pengadilan memiliki keterkaitan dengan materi peringan pidana dalam putusan pengadilan. Keterkaitan ini disebabkan karena perumusan hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan pengadilan merupakan satu rangkaian dengan perumusan hal-hal yang meringankan pidana. Dirumuskan seeara bergantian dalam sam paket.
Anda mungkin juga menyukai
- Materi Pertemuan Ke 5 (Status Personal Dan Kaitannya Dengan Prisnsip Kewarganegaraan Dan Domisilli)Dokumen7 halamanMateri Pertemuan Ke 5 (Status Personal Dan Kaitannya Dengan Prisnsip Kewarganegaraan Dan Domisilli)Hani AmaliaBelum ada peringkat
- Quiz Hukum AdministrasiDokumen7 halamanQuiz Hukum AdministrasiMarsyanda UlfaBelum ada peringkat
- Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraDokumen15 halamanKompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraDemmyAugustaBelum ada peringkat
- Asas Legalitas Perbandingan HukumDokumen7 halamanAsas Legalitas Perbandingan HukumAgungMuzoffarBelum ada peringkat
- Legal Reasoning Kelompok 3Dokumen29 halamanLegal Reasoning Kelompok 3Redika JanasutaBelum ada peringkat
- Analisis Pasal 6 Uu TppuDokumen3 halamanAnalisis Pasal 6 Uu TppuDifa BaariqBelum ada peringkat
- Etika Profesi PolisiDokumen10 halamanEtika Profesi PolisiMutia KhairunisaBelum ada peringkat
- Sahrul Ghoffar Ramadhan PDFDokumen9 halamanSahrul Ghoffar Ramadhan PDFghoffar ramadhanBelum ada peringkat
- Hukum AdatDokumen3 halamanHukum AdatanggiditaBelum ada peringkat
- Uts TelematikaDokumen3 halamanUts TelematikaMarwah Hamid100% (1)
- Korupsi Dan KUHPDokumen8 halamanKorupsi Dan KUHPEdy Siswanto100% (2)
- Hukum Perlindungan KonsumenDokumen22 halamanHukum Perlindungan KonsumenfhiaalisyaBelum ada peringkat
- Norma Hukum UmumDokumen3 halamanNorma Hukum UmumKemal Kusuma WardanaBelum ada peringkat
- Press Release NarkobaDokumen6 halamanPress Release NarkobaEstiningsihBelum ada peringkat
- Sampul Proposal Juan Geraldo TuranganDokumen4 halamanSampul Proposal Juan Geraldo Turanganfarah dibaBelum ada peringkat
- Makalah HanDokumen16 halamanMakalah Hanmeyrista13Belum ada peringkat
- Fahma S - MPH NormatifDokumen21 halamanFahma S - MPH NormatifFahma ShihsalamadhinaBelum ada peringkat
- Konflik Tanah Di Hutan Pubabu: Masyarakat Adat Besipae VS Pemerintah Provinsi NTTDokumen11 halamanKonflik Tanah Di Hutan Pubabu: Masyarakat Adat Besipae VS Pemerintah Provinsi NTTheri28Belum ada peringkat
- Prof Erlyn Filsafat Hukum Ujian Akhir Semester Genap 2019-2020 S1 17-06-20 0700Dokumen1 halamanProf Erlyn Filsafat Hukum Ujian Akhir Semester Genap 2019-2020 S1 17-06-20 0700Tanpa Nama100% (1)
- Pembantu PengusahaDokumen5 halamanPembantu Pengusaha32. Safira NabilaBelum ada peringkat
- Analisis Fiktif Positif Dan Fiktif NegatifDokumen12 halamanAnalisis Fiktif Positif Dan Fiktif NegatifAli RahmanBelum ada peringkat
- Rangkuman Materi Hukum InternasionalDokumen13 halamanRangkuman Materi Hukum InternasionalFauzil Mahfuz Aziz100% (1)
- Tindak Pidana Pencucian Uang - Kel 9Dokumen17 halamanTindak Pidana Pencucian Uang - Kel 9Matahari SuhaimiBelum ada peringkat
- Putusan Kppu Tentang Kartel SmsDokumen5 halamanPutusan Kppu Tentang Kartel SmsDewi Adithyanti PramithaBelum ada peringkat
- Etika Profesi HakimDokumen39 halamanEtika Profesi HakimsangrudiBelum ada peringkat
- Analisis Cek, Wesel, Dan Surat SanggupDokumen6 halamanAnalisis Cek, Wesel, Dan Surat Sanggupdidha narin aizaBelum ada peringkat
- Asas Peradilan MiliterDokumen8 halamanAsas Peradilan MiliteranggiaaaaaaaaBelum ada peringkat
- Perbandingan UU No 23 Tahun 1997 Dan UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan LingkunganDokumen3 halamanPerbandingan UU No 23 Tahun 1997 Dan UU No 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan LingkunganHery KurniawanBelum ada peringkat
- Materi Pertemuan Ke 13 (Sejarah Pendekatan Hukum Perdata Internasional Indonesia)Dokumen8 halamanMateri Pertemuan Ke 13 (Sejarah Pendekatan Hukum Perdata Internasional Indonesia)wira ahmadBelum ada peringkat
- Translate Video Think Like A LawyerDokumen5 halamanTranslate Video Think Like A LawyerAtiqah RevalinaBelum ada peringkat
- Makalah Delik DelikDokumen23 halamanMakalah Delik DelikIqra0% (1)
- Hakekat Hukum I-Wps OfficeDokumen8 halamanHakekat Hukum I-Wps OfficeDimas SanjayaBelum ada peringkat
- Dasar Hukum Pengaturan CekDokumen4 halamanDasar Hukum Pengaturan Cekfadli999mksBelum ada peringkat
- Jawaban Uts Hukum Pidana KhususDokumen5 halamanJawaban Uts Hukum Pidana KhususSatriya BismaBelum ada peringkat
- Hukum Ham Lanjutan Perkawinan Campuran Akibat Perpindahan PendudukDokumen4 halamanHukum Ham Lanjutan Perkawinan Campuran Akibat Perpindahan Pendudukayu gendis saraswatiBelum ada peringkat
- Metode RechtsvervijningDokumen2 halamanMetode RechtsvervijningMuhyiddin Alwari'iBelum ada peringkat
- Makalah Sistem Peradilan PidanaDokumen25 halamanMakalah Sistem Peradilan PidanaSi GembulBelum ada peringkat
- PEMBUKUANDokumen8 halamanPEMBUKUANJeanBelum ada peringkat
- Penggabungan DakwaanDokumen4 halamanPenggabungan DakwaanAini SjahabBelum ada peringkat
- Viktimologi DGN KriminologiDokumen11 halamanViktimologi DGN KriminologiocisenjayaSHMHBelum ada peringkat
- Urgensi Predicate Crime Dalam Uu TppuDokumen29 halamanUrgensi Predicate Crime Dalam Uu TppuJanuar Abdul Razak100% (1)
- Pemakaian Merek Dagang SOSIS Dengan Pemakaian Merek Dagang ZOSIS Dikaitkan Dengan Pasal 5 Undang Undang No 15 Tahun 2001Dokumen3 halamanPemakaian Merek Dagang SOSIS Dengan Pemakaian Merek Dagang ZOSIS Dikaitkan Dengan Pasal 5 Undang Undang No 15 Tahun 2001YogaBelum ada peringkat
- Praktik Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di JermanDokumen3 halamanPraktik Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di JermanMutiara KhadijahBelum ada peringkat
- Analisa Pasal 2 Dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Serta Kaitkan Dengan Putusan Ma Dan MKDokumen3 halamanAnalisa Pasal 2 Dan 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Serta Kaitkan Dengan Putusan Ma Dan MKraja brahmandaBelum ada peringkat
- P4 Peradilan Administrasi Murni Dalam Hukum PajakDokumen18 halamanP4 Peradilan Administrasi Murni Dalam Hukum PajakAisha Rachma100% (2)
- Bagaimanakah Hubungan Hukum Dengan Politik Dilihat Dari Perspektif Politik HukumDokumen6 halamanBagaimanakah Hubungan Hukum Dengan Politik Dilihat Dari Perspektif Politik Hukumhery hutomoBelum ada peringkat
- Jurnal Pena Hukum (JPH)Dokumen15 halamanJurnal Pena Hukum (JPH)Reizha Hanafi100% (1)
- Arti Minutasi DLM SidangDokumen39 halamanArti Minutasi DLM Sidangmbah wilBelum ada peringkat
- Kerangka LuarDokumen10 halamanKerangka Luarcitra husadaBelum ada peringkat
- Praperadilan, Ganti Kerugian Dan RehabilitasiDokumen13 halamanPraperadilan, Ganti Kerugian Dan RehabilitasiAswi SiregarBelum ada peringkat
- Kuliah Ke-7Dokumen15 halamanKuliah Ke-7sariBelum ada peringkat
- Pemeriksaan PidanaDokumen15 halamanPemeriksaan Pidanaisrofatu lailaBelum ada peringkat
- Kasus Hi Pin - Membuka Rahasia Dagang Racikan KopiDokumen2 halamanKasus Hi Pin - Membuka Rahasia Dagang Racikan KopiSalsalsa SalsalsaBelum ada peringkat
- MAKALAH Hukum Perdata InternasionalDokumen10 halamanMAKALAH Hukum Perdata InternasionalselinBelum ada peringkat
- 40 SoalDokumen3 halaman40 SoalTiiara PratiwiiBelum ada peringkat
- Tugas Telematika ADokumen3 halamanTugas Telematika ADirga PutraBelum ada peringkat
- Penyelesaian Kasus Sengketa Pelanggaran HAM Oleh Pengadilan Dan Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil Di IndonesiaDokumen15 halamanPenyelesaian Kasus Sengketa Pelanggaran HAM Oleh Pengadilan Dan Eksistensi Organisasi Masyarakat Sipil Di IndonesiaWisnu KarmaBelum ada peringkat
- Sifat Pemberat PidanaDokumen9 halamanSifat Pemberat PidanaC Kurniawan Putra100% (1)
- Tugas 1 Hukum PidanaDokumen4 halamanTugas 1 Hukum Pidanaeka wisnawaBelum ada peringkat
- Razananda Skandiva 1810611214 Tgs HukMilDokumen3 halamanRazananda Skandiva 1810611214 Tgs HukMilEl GringoBelum ada peringkat