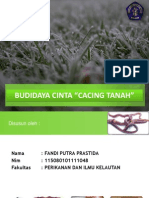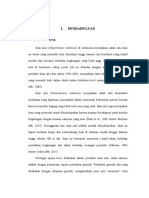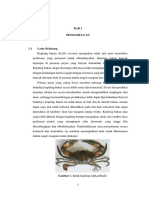Budidaya Cacing Tanah Lumbricus Rubellus Dengan Media Dan Pakan Fermentasi
Budidaya Cacing Tanah Lumbricus Rubellus Dengan Media Dan Pakan Fermentasi
Diunggah oleh
ZepHemaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Budidaya Cacing Tanah Lumbricus Rubellus Dengan Media Dan Pakan Fermentasi
Budidaya Cacing Tanah Lumbricus Rubellus Dengan Media Dan Pakan Fermentasi
Diunggah oleh
ZepHemaHak Cipta:
Format Tersedia
1
1
1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan masyarakat dunia pada abad ke 21 telah menunjukkan
kecenderungan adanya perubahan perilaku dan gaya hidup serta pola
konsumsinya ke produk perikanan. Dengan keterbatasan kemampuan pasok
hasil perikanan dunia, ikan akan menjadi komoditas strategis yang dibutuhkan
oleh masyarakat dunia. Oleh karena itu, permintaan komoditas perikanan dimasa
datang akan semakin tinggi sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk,
kualitas dan gaya hidup masyarakat dunia (Sukadi, 2002).
Perikanan budidaya merupakan andalan bagi pemenuhan kebutuhan
sumber protein ikan yang semakin meningkat sementara sumber dari
penangkapan semakin menurun.Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan
benih ikan yang berkualitas dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan.
Penyediaan benih bermutu dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai
faktor salah satunya adalah manajemen pakan yang harus mencukupi kebutuhan
gizi untuk proses tumbuh kembang bagi ikan komoditas budidaya (Kristanto,
2007).
Cacing tanah termasuk dalam kelas Oligochaeta yang mempunyai banyak
suku (famili).Terdapat 4 spesies cacing tanah yang sudah banyak dibudidayakan
yaitu Lumbricus rubellus, Eisenia foetida, Pheretima asiatica, dan Eudrilus
eugeniae (Hadisoewignyo dan Rendy, 2013).
Cacing tanah sangat potensial untuk dikembangkan dengan kandungan
gizinya yang cukup tinggi, terutama kandungan protein yang mencapai 6476%.Protein yang sangat tinggi pada tubuh cacing tanah terdiri dari setidaknya
sembilan macam asam amino essensial dan empat macam asam amino nonessensial yang berguna bagi kesehatan manusia.
Pemanfaatan cacing tanah sebagai pakan ikan didasarkan pada hasil
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa cacing tanah memiliki kandungan
protein, lemak dan mineral yang sangat tinggi.Kualitas protein cacing tanah
olahan yang lebih tinggi daripada protein daging maupun ikan tersebut membuat
cacing tanah sangat berpeluang sebagai bahan pakan ikan (Palungkun, 1999).
Hasil analisis didapatkan bahwa kandungan protein tepung cacing tanah
sebesar 60-70%, lemak kasar 7%, kalsium 0,55%, fosfor 1%, serat kasar 1,08%
(Palungkun, 1999). Lumbricus rubellus mempunyai kandungan Lumbricin yang
merupakan antibiotika berupa peptide, berasal dari protein bersifat bakteriostatik
sehingga termasuk anti bakteri bakteriosin. Bakteriosin sendiri berfungsi sebagai
penghambat pertumbuhan bakteri lain dengan cara absorbs ke dalam
permukaan dinding sel bakteri (Pelczar et al.,1998).
Dengan memperhatikan banyaknya manfaat cacing tanah inilah, dewasa
ini masyarakat termotivasi untuk melakukan budidaya cacing tanah.Pada praktek
kerja lapang ini mengambil judul budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus)
dikarenakan perlunya informasi dan pengetahuan tentang cara budidaya cacing
tanah yang baik dan benar sehingga proses produksi cacing tanah dapat
maksimal dan menghasilkan profit yang besar.
2
Maksud dan Tujuan
Maksud dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk mengetahui dan
mempelajari secara langsung serta mendapatkan gambaran secara jelas dan
menyeluruh tentang teknik budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus) di Unit
Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT) Kepanjen, Malang, Jawa Timur.
Tujuan dari Praktek Kerja Lapang ini adalah untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja dalam bidang budidaya
cacing tanah (Lumbricus rubellus) di Unit Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT)
Kepanjen.Juga untuk membandingkan antara teori yang telah dipelajari dengan
kenyataan yang ada di lapangan.
3
Kegunaan
Praktek Kerja Lapang ini dilakukan dengan harapan agar mahasiswa dapat
menambah wawasan, informasi dan pengetahuan serta dapat memadukannya
dengan teori yang telah didapatkan tentang budidaya cacing tanah (Lumbricus
rubellus) sehingga mahasiswa dapat menjadi lebih tanggap dalam menghadapi
masalah-masalah yang dihadapi di lapangan.Selain itu, dapat dijadikan informasi
bagi para usahawan atau siapa saja yang berkeinginan membuka usaha di
bidang ini.
4
Tempat dan Waktu
Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dilaksanakan di Unit Pengelola Budidaya
Air Tawar (UPBAT) Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini
dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2014.
II. METODE PELAKSANAAN
2.1 Metode Pengambilan Data
Menurut Suryabrata (1991), metode deskriptif adalah suatu metode yang
menggambarkan keadaan atau kejadian-kejadian pada suatu daerah tertentu.
Dalam metode ini pengambilan data dilakukan tidak hanya terbatas pada
pengumpulan dan penyusunan data, tapi meliputi analisis dan pembahasan
tentang data tersebut.Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara
umum, sistematis, aktual dan valid mengenai fakta dan sifat-sifat populasi daerah
tersebut.
2.2 Teknik Pengambilan Data
Pengambilan data pada Praktek Kerja Lapang akan dilakukan dengan
mengambil dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder, dimana data
primer pengumpulannya dilakukan dengan cara mencatat hasil observasi,
wawancara serta partisipasi aktif, sedangkan data sekunder diperoleh dari
lapangan.
2.2.1 Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung
dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang
memerlukannya. Data ini diperoleh secara langsung dengan melakukan
pengamatan dan pencatatan dari hasil observasi, wawancara dan partisipasi aktif
(Hasan, 2002).
a. Observasi
Menurut Menurut Arikunto (2002), observasi dapat disebut juga
pengamatan, yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek
dengan menggunakan alat indra yaitu melalui penglihatan, penciuman,
pendengaran, peraba dan pengecap.Dalam participant observation, peneliti
melakukan hal meliputi melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Mencatat
kejadian, perilaku dan setting social secara sistemik. Adapun data yang
dikumpulkan selama observasi adalah deskripsi program, perilaku, perasaan dan
pengetahuan, mencatat apa yang terjadi, bagaimana terjadinya dan siapa yang
ada disana, dan semua kejadian atau perilaku yang dianggap penting oleh
peneliti. Dalam praktek kerja lapang ini kegiatan observasi dilakukan dengan
cara mengamati dan mencatat serta mendokumentasikan kegiatan
pembudidayaan cacing tanah (Lumbricus rubellus) di Unit Pengelola Budidaya
Air Tawar (UPBAT) Kepanjen, Malang, Jawa Timur.
b. Wawancara
Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan
cara tanya jawab kepada nara sumber secara langsung. Menurut Kusumawati et
al. (2011), wawancara merupakan proses perolehan keterangan untuk tujuan
penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan
responden.
c. Partisipasi Aktif
Menurut Natzir (1983), partisipasi aktif adalah keterlibatan dalam suatu
kegiatan yang dilakukan secara langsung di lapang. Pada partisipasi aktif,
peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, tetapi data yang
diperoleh belum sepenuhnya lengkap. Partisipasi aktif pada praktek kerja lapang
iniyaitu suatu kegiatan turut serta dan berperan langsung dalam
kegiatanpemudidayaan Lumbricus rubellus di Unit Pengelola Budidaya Air Tawar
(UPBAT) Kepanjen guna mendapatkan data dan informasi mengenai teknik
pemudidayaan cacing tanah Lumbricusrubellus di Unit Pengelola Budidaya Air
Tawar (UPBAT) Kepanjen, Malang, Jawa Timur.
2.2.2 Data Sekunder
Menurut Koswara et al. (2001), penelitian dalam menggunakan data
sekunder tidak perlu hadir, kapan dan di manapun data dikumpulkan. Informasi
yang mula-mula dikumpulkan, apakah diperoleh melalui wawancara, kuisioner,
observasi atau gabungan di antara ketiganya, dibatasi konteks ruang dan waktu
si peneliti. Hanya ketika orang lain bisa menggunakannya, data itu menjadi
bebas dari pembatasan ini. Keterbatasan semacam itu tidak ditemukan, ketika
penelitian menggunakan sumber sekunder. Data dikumpulkan untuk tujuan ilmiah
yang tidak terikat konteks ruang dan waktu sebagaimana data yang mula-mula
dikumpulkan.
III. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG
3.1 Keadaan Umum Lokasi Praktek Kerja Lapang
3.1.1 Sejarah UPBAT Kepanjen
UPBAT Kepanjen berdiri pada tahun 1957. Di awal mula berdirinya, balai ini
merupakan Dinas Perikanan Darat Kabupaten Malang. Pada tahun 1963, UPBAT
Kepanjen berubah menjadi Kursus Pengamat Perikanan Darat Kepanjen. Dalam
kurun waktu lima tahun (1968), balai ini kemudian berubah fungsi menjadi
Training Centre Perikanan Darat. Empat tahun kemudian, pada tahun 1972
UPBAT Kepanjen berubah menjadi Training Centre Aquaculture. Dalam kurun
waktu tujuh tahun, pada tahun 1979 UPBAT Kepanjen berfungsi sebagai Unit
Pembinaan Budidaya Air Tawar. Kemudian pada tahun 2002, berubah nama
menjadi Balai Benih Ikan Kepanjen. Akhirnya, berdasarkan SK Kepala Dinas
Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur No. 061/6614/116.01/2010, BBI
Kepanjen berubah nama menjadi Unit Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT)
Kepanjen.
3.1.2 Letak Geografis dan Topografis
Secara geografis, UPBAT Kepanjen terletak di Jalan Trunojoyo No. 12,
Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Berada pada
garis 112o 34 30 BT dan 8o 7 30 LS. Daerah ini termasuk dataran rendah
dengan ketinggian 358 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata berkisar
antara 25-30oC dan curah hujan rata-rata 600-1.000mm/tahun. Batas sebelah
utara dari balai ini adalah Jalan Raya KepanjenGondanglegi.Sebelah selatan
merupakan tanah hak dari suatu yayasan, sebelah timur berbatasan langsung
dengan perumahan penduduk dan persawahan, sebelah barat berbatasan
dengan Jalan Raya KepanjenSengguruhyang terdapat markas tentara angkatan
darat Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur 5). Luas total areal UPBAT ini adalah
31.400 m2 dengan luas perumahan, kantor, aula dan asrama 12.990, 39 m2
serta luas sarana fisik kegiatan produksi, budidaya dan laboratorium adalah
18.409, 61 m2. Denah dan lokasi UPBAT Kepanjen pada citra satelit
digambarkan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.
3.1.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur Nomor: 061/6614/116.01/2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis Dinas pada Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur, susunan organisasi UPBAT Kepanjen secara skematis
digambarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi UPBAT Kepanjen
3.1.4. Tugas dan Fungsi UPBAT Kepanjen
Unit Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT) melaksanakan sebagian tugas
dinas di bidang kegiatan produksi, penerapan teknologi perbenihan dan budidaya
perikanan air tawar, pelaksanaan pengujian secara laboratories kesehatan ikan
dan lingkungan serta pelatihan dan keterampilan bagi masyarakat umum.
Fungsi dari UPBAT Kepanjen adalah :
1. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya/ perbenihanserta
kaji terap teknologi budidaya air tawar;
2. Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air tawar;
3. Pelaksanaan pelatihan dan kaji terap teknologi perbenihan dan budidaya
perikanan air tawar kepada petugas teknis lapangan;
4. Pelaksanaan pengujian secara laboratories kesehatan ikan dan lingkungan;
5. Pelaksanaan dan memfasilitasi standarisasi mutu benih dan hasil budidaya air
tawar;
6. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3.1.5 Tugas, Pokok dan Fungsi Masing-masing Bagian
1. Kepala UPBAT
Tugas dari kepala UPBAT yaitumemimpin, mengkoordinasikan,
mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penerapan budidaya air tawar,
ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Tugas dari Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
a.Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan
dan kearsipan;
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
d. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perlengkapan kantor;
e. Menghimpun, menyusun, mengusulkan rencana kerja dan mengevaluasi serta
melaporkan pelaksanaan kegiatan unit;
10
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
3. Seksi Produksi Benih Dan Teknik Budidaya
Tugas dari Seksi Produksi Dan Teknik Budidaya meliputi :
a. Melaksanakan tugas perawatan ikan, memproduksi induk, benih danpellet
(makanan ikan);
b. Melaksanakan pencatatan data kegiatan produksi benih sebagai bahan
evaluasi dan laporan;
c. Melaksanakan kegiatan perawatan kolam/ saluran/ pematang, pengujian,
pengelolaan kolam percontohan serta usaha penanggulangan hama penyakit
ikan;
d. Melaksanakan tugas penjualan induk/ benih ikan dan pellet;
e. Melaksanakan tugas perawatan dan keamanan perlengkapan/ peralatan;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
4. Seksi Pengamatan dan Perlindungan Lingkungan
Tugas dari Seksi Pengamatan dan Perlindungan meliputi :
a. Melaksanakan tugas yang meliputi kegiatan pengamatan dan upaya
penanggulangan pencemaran perairan;
b. Melaksanakan tugas perawatan dan keamanan terhadap lingkungan;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit.
3.1.6 SDM (Sumber Daya Manusia)
UPBAT Kepanjen memiliki jumlah personalia sebanyak 21 orang yang
dalam pelaksanaan kegiatan produksinnya terdiri dari beberapa tim, misalnya tim
produksi ikan Nila (Oreochromis niloticus). Secaraumum, personalia UPBAT
Kepanjen terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang tenaga
kontrak. Data-data tentang jumlah pegawai UPBAT Kepanjen terinci pada Tabel2.
11
Tabel 2. Data jumlah pegawai UPBAT Kepanjen
NO
1
2
Status
PNS
Tenaga kontrak
Jumlah
IV
-
Ruang/ Golongan
III
II
12
5
12
5
Jumlah
I
1
3
4
18
3
21
3.2 Prasarana dan Sarana UPBAT Kepanjen
3.2.1 Prasarana
Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh UPBAT Kepanjen, selain terdapat
kolam-kolam tempat budidaya ikan dan produksi calon induk ikan Lele, juga
tersedia fasilitas-fasilitas prasarana penunjang yang terdapat pada Tabel 3
berikut ini:
Tabel 3. Prasarana UPBAT Kepanjen
No
1
Fasilitas
Jalan dan Transportasi
Luas/kapasitas
-
Jumlah
1
Jaringan Listrik
Perpustakaan
24 m2
Ruang kelas/pertemuan
50 orang
Auditorium/gedung pertemuan
250orang,385 m2
35 orang, 515 m2
Asrama
66 m2
Ruang makan
9 unit
Ruang dapur
54 m2
Kamar mandi
10
Bangunan unit produksi pellet
11
Guest house
12
Rumah jaga
13
Musholla
12
14
Genset
3.2.2 Sarana
UPBAT Kepanjen dilengkapi dengan banyak sarana pendukung dan
fasilitas-fasilitas yang memadai serta luas bangunan yang cukup untuk
mendukung proses produksinya. Kolam induk, kolam pemuliaan, kolam
pendederan, kolam pembenihan, kolam budidaya pakan alami hingga tong
pembesaran belut semua tersedia dan masih dalam keadaan baik serta terawat.
UPBAT Kepanjen memiliki tiga laboratorium, diantaranya ialah Laboratorium
Kualitas Air dan Hama Penyakit, Laboratorium Basah dan Laboratorium kering.
Bak tandon air, bak pengendapan air, kandang katak serta ruang kantor. Adapun
sarana pendukung proses produksi budidaya yang terdapat pada UPBAT
Kepanjen dapat dilihat pada Tabel 4 adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Sarana UPBAT Kepanjen
No
Nama ruangan
Luas
Jumlah
13
Ruang kantor
103 m2
Laboratorium kering
60 m2
Laboratorium basah
54 m2
Lab. Kualitas air dan hama
penyakit
5
Kolam induk lele produksi
Kolam pembenihan dan
pendederan lele
Kolam induk lele pemuliaan
Kolam pembenihan dan
pendederan lele pemuliaan
27
24
Kolam induk ikan mas
10
Kolam pembenihan ikan mas
11
Kolam pendederan ikan mas
12
Kolam pembenihan ikan nila
13
Kolam pembenihan tawes
14
Kolam induk gurami
15
Kolam pendederan gurami
16
Kolam induk koi
17
Kolam pembenihan koi
18
Kolam pendederan benih koi
19
Kolam induk patin
20
Kolam pembenihan patin
21
Kolam induk betutu
22
Kolam induk belut
23
Tong pembesaran belut
24
Kandang katak
16
14
25
Kolam budidaya pakan alami
26
Bak pengendapan air
27
Bak tandon air
3.3 Biologi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)
3.3.1 Klasifikasi dan Morfologi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)
Klasifikasi Cacing Tanah (Lumbricus rubellus) menurut Sugiri (1988) adalah
sebagai berikut :
Filum
: Annelida
Kelas
: Oligochaeta
Ordo
: Opisthophora
Famili
: Opisthophora
Genus
: Lumbricus
Spesies
: Lumbricus rubellus
Sugiri (1984), menyatakan bahwa Cacing tanah Lumbricus rubellus
mempunyai bentuk tubuh yang gilig dengan panjang tubuh 8-14 cm. Tubuh
bagian ventral lebih pipih dan pucat dari bagian dorsal. Warna tubuh cacing ini
15
adalah merah sampai coklat dengan bagian dorsal yang lebih merah tua. Cacing
Lumbricus rubellus mempunyai tubuh bersegmen dimana pada seluruh tubuhnya
terdapat 85-140 segmen. Setiap segmen kecuali segmen pertama dan terakhir
terdapat 4 pasang seta menjulur ke arah lateral dan ventral. Gambaran umum
cacing tanah (Lumbricus rubellus) terdapat pada Gambar 2.
Gambar 2.Lumbricus rubellus (Dokumen pribadi, 2014)
3.3.2 Habitat dan Penyebaran
Cacing tanah dapat ditemukan pada kedalaman 8-12 inci dari permukaan
tanah. Cacing tanah juga sangat sensitive terhadap konsentrasi ion hydrogen
(kadar keasaman tanah). Banyak spesies cacing tanah yang menyukai pH
sekitar 7,0. Ada juga yang berpendapat bahwa cacing tanah umumnya menyukai
pH media pada kisaran 6,0-7,2 (Herayani, 2001).
Cacing tanah umumnya hidup di tempat yang kadar kelembabannya
terjaga dan stabil. Kelembaban yang terlalu tinggi akan berdampak kurang baik
bagi pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah, karena makin lembab
udara maka kandungan oksigen yang berada dalam sarang akan semakin
berkurang. Sebaliknya, jika kelembaban rendah berarti udara terlalu kering yang
akan merusak kulit cacing tanah yang berdampak pada pernafasannya. Secara
ekologi, cacing tanah diklasifikasikan menjadi lima kategori umum yaitu epigeic,
16
aneceiq, endogeic, coprophagic dan arboricolous. Cacing tanah epigeic
merupakan cacing tanah yang aktif di permukaan tanah, memililiki pigmen tubuh
dan pada umumnya tidak suka membuat terowongan dalam tanah. Cacing tanah
aneceiq memiliki tubuh besar dan dapat membuat terowongan yang dalam.
Cacing tanah endogeic merupakan cacing tanah yang hidup dekat dengan
permukaan tanah yang mengandung bahan organic. Cacing tanah coprophagic
merupakan cacing tanah yang hidup di dalam kotoran hewan ternak, sedangkan
cacing tanah arboricolous adalah kategori cacing tanah yang hidup dalam hutan
hujan tropis (Paoletti, 1999).
Cacing tanah (Lumbricus rubellus) ini tergolong dalam cacing epigeic
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hidupnya di permukaan tanah
dengan kandungan bahan organic yang tinggi. Secara umum, terdapat dua
golongan cacing berdasarkan warna. Akan tetapi cacing tanah (Lumbricus
rubellus) ini tergolong dalam cacing merah (the red worm).
3.3.3 Reproduksi
Cacing tanah merupakan binatang yang bersifat hemaprodit atau biseksual
karena di dalam tubuhnya terdapat alat kelamin jantan dan betina. Cacing ini
tergolong dalam hemaprodit protandri, yakni bagian kelamin jantan dulu yang
mengalami kematangan pada saat dalam stadia benih untuk kemudian pada saat
usia dewasa, alat kelamin betina mengalami proses pematangan. Alat kelamin
jantan terdiri atas dua pasang testis yang terletak pada segmen ke-10 dan ke-11.
Sperma yang sudah matang mengalir ke kantong testis, corong sperma, tabung
sperma dan keluar melalui porus genital di bagian ventral segmen ke-15. Alat
kelamin betina terdiri dari ovarium yang membentuk telur dan terdapat dalam
segmen ke-13. Telur yang sudah matang akan masuk ke dalam infundibulum
yang terletak di permukaan posterior segmen ke-13, kemudian menuju ke ovidak
yang bermuara pada bagian ventral segmen ke-14. Lubang dalam ovidak
17
berhubungan secara langsung dengan kantong telur yang merupakan tempat
penyimpanan telur yang sudah matang. Untuk melakukan proses pembuahan,
cacing tanah tidak dapat melakukannya sendiri dan harus dilakukan oleh
sepasang cacing tanah (Herayani, 2001).
Telur dan sperma dikeluarkan dari masing-masing induk ke dalam kokon
yang disekresikan oleh klitelium, sehingga fertilisasi terjadi secara eksternal.
Cacing tanah berkembang mulai dari telur yang tersimpan dalam kokon yang
akan menetas sekitar 14-21 hari setelah terlepas dari tubuh cacing tanah. Embrio
mendapat nutrisi dari cairan yang terdapat di dalam kokon (Pechenik, 2000).
3.3.4 Siklus Hidup
Siklus hidup cacing tanah dimulai dari kokon, cacing muda (juvenile),
cacing produktif, dan cacing tua. Lama siklus hidup ini tergantung pada
kesesuaian kondisi lingkungan, cadangan makanan, dan jenis cacing tanah. Dari
berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh lama siklus
hidup cacing tanah Lumbricus rubellus mulai kokon hingga mati adalah 1-5 tahun
(Palungkun, 2010).
Siklus produktif cacing tanah berkisar 40-60 hari. Hal ini dikarenakan
cacing tanah memiliki kemampuan untuk memperbanyak jumlahnya dalam waktu
yang singkat. Cacing tanah yang telah berumur 35-45,5 hari (dewasa kelamin)
akan menghasilkan kokon setiap 7-10 hari sekali melalui alat reproduksinya
(klitelium). Butuh waktu 14-21 hari bagi kokon agar menetas, dan setiap kokon
akan menghasilkan 1-8 ekor anak. Kokon cacing tanah berdiameter sekitar 1.2
cm (Sihombing, 2002).
3.4 Manfaat Cacing Tanah Bagi Perikanan
18
Palungkun (2010), menyatakan bahwa manfaat cacing tanah diantaranya
adalah sebagai umpan pancing. Manfaat cacing tanah sebagai umpan pancing
dapat ditunjukkan oleh kegemaran memancing yang dimiliki oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia, dan semakin menjamurnya tempat memancing hampir di
seluruh wilayah nusantara. Akibatnya, permintaan cacing sebagai umpan pun
semakin meningkat. Selain sebagai umpan memancing, cacing tanah dapat
dijadikan alternatif pakan ikan. Selain kandungan gizinya yang baik, cacing tanah
merupakan salah satu cacing yang diproduksi secara massal dan paling banyak
dikomersilkan. Cacing tanah sebagai alternatif pakan disajikan sebagai pakan
segar untuk ikan dengan berbagai cara pemberian tergantung pada ukuran
ikannya. Pada ikan besar seperti ikan Lele, cacing bisa diberikan dalam bentuk
utuh, namun terlebih dahulu dibersihkanseperlunya. Sedangkan untuk ikan-ikan
kecil perlu dipotong-potong terlebih dahulu disesuaikan dengan ukuran mulut
ikan tersebut.
Dalam penelitiannya Palungkun (1999), menjelaskan kandungan asam
amino yang terkandung dalam tubuh cacing tanah seperti yang terdapat pada
Tabel 5 berikut ini :
Tabel 5. Kandungan asam amino cacing tanah (Lumbricus rubellus)
Asam Amino
Kandungan (%)
19
Asam amino essensial
Arginin
Histidin
Isoleusin
Leusin
Lisin
Metionin
Fenilalanin
Treonin
Valin
Asam amino non-esensial
Sistein
Glisin
Serin
Tirosin
4, 13
1, 56
2, 58
4, 84
4, 33
2, 18
2, 25
2, 95
3, 01
2, 29
2, 92
2, 88
1, 36
Dalam bidang perikanan, cacing tanah juga di produksi sebagai pengganti
tepung ikan. Lazim diketahui bahwa tepung ikan merupakan bahan baku
pembuat pakan atau pelet. Tepung ikan mengandung protein yang mutlak
diperlukan dalam ransum pakan, akan tetapi mahalnya harga bahan baku tepung
ikan membuat harga pakan ikan ikut terderak naik. Hal inilah yang melatar
belakangi penggunaan tepung cacing tanah sebagai pengganti tepung ikan.
Pemanfaatan cacing tanah sebagai pakan ternak unggas didasarkan pada hasil
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa cacing tanah memiliki kandungan
protein, lemak dan mineral yang sangat tinggi. Kualitas protein cacing tanah
olahan yang lebih tinggi daripada protein daging maupun ikan tersebut membuat
20
cacing tanah sangat berpeluang sebagai bahan pakan ternak unggas dan ikan.
Tepung cacing pernah juga dilaporkan mampu menekan pengaruh racun dalam
ternak (Palungkun, 1999).
3.5 Persyaratan Lokasi dan Konstruksi Bangunan Budidaya
3.5.1 Persyaratan Lokasi dan Konstruksi Bangunan Budidaya
Hermawan (2014), menjabarkan persyaratan lokasi untuk budidaya cacing
tanah adalah sebagai berikut :
a. Bahan organik yang tinggi
Tanah sebagai media hidup cacing tanah harus mengandung bahan organik
dalam jumlah yang besar. Bahan organik tanah dapat berasal dari serasah,
kotoran ternak atau tanaman dan hewan yang mati. Ini disebabkan karena
cacing tanah menyukai bahan-bahan yang mudah membusuk karena lebih
mudah dicerna oleh tubuhnya.
b. pH
Untuk pertumbuhan yang baik, cacing tanah memerlukan tanah yang sedikit
asam sampai netral dengan kisaran pH 6-7,2 karena dengan kondisi ini,
bakteri yang tedapat dalam tubuh cacing tanah dapat bekerja secara optimal
untuk mengadakan pembusukan atau fermentasi.
c. Kelembaban
Kelembaban optimal bagi pertumbuhan dan perkembang biakan cacing tanah
berkisar antara 15-30%.
d. Suhu
Suhu yang diperlukan untuk pertumbuhan cacing tanah dan penetasan kokon
adalah sekitar 15-25oC atau suam-suam kuku. Suhu yang lebih dari kisaran
tersebut dinilai masih baik asal ada naungan yang cukup dan kelembaban
dalam kisaran optimal.
e. Lokasi
Lokasi pemeliharaan cacing tanah sebisa mungkin ditempatkan pada tempat
yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selain itu,
lokasi haruslah mudah dijangkau dengan tujuan mempermudah pengawasan
dan penanganan sepanjang proses budidaya mulai dari awal sampai akhir.
21
Wadah budidaya juga sebaiknya terbuat dari bahan-bahan yang bersifat tidak
meneruskan sinar matahari dan tidak menyimpan panas.
Konstruksi bangunan budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus)
bermacam-macam jenisnya. Kolam beton, rak dari alumunium dan juga rak dari
kayu dapat dijadikan sebagai tempat budidayanya. Kotak bekas yang tidak
terpakai juga bisa dimanfaatkan sebagai wadah budidaya cacing tanah
(Lumbricus rubellus). Hal inilah yang membuat usaha budidaya cacing tanah
(Lumbricus rubellus) layak untuk dijadikan usaha sampingan skala rumah tangga
karena tidak memerlukan lahan yang luas.
Gambar 3. Konstruksi kolam beton (Dokumen pribadi, 2014)
Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5 menunjukkan beberapa jenis
konstruksi wadah budidaya yang didapat dari beberapa tempat di kota Malang
tepatnya di Kecamatan Sukun.
Gambar 4.Konstruksi rak dengan wadah ember berukuran sedang
(Dokumen pribadi, 2014)
22
Gambar 5. Konstruksi rak bambu dengan wadah karung bekas
(Dokumen pribadi, 2014)
3.5.2 Bangunan Pelindung
Budidaya cacing tanah harus terletak ditempat yang teduh, artinya tidak
terpapar cahaya matahari ataupun terkena air hujan secara langsung yang akan
berdampak pada usaha cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang sedang
dibudidayakan. Bangunan pelindung mutlak diperlukan untuk memaksimalkan
proses budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus). Konstruksi bangunan
pelindung di UPBAT Kepanjen digambarkan pada Gambar 6 berikut ini.
Gambar 6. Bangunan Pelindung (Dokumen pribadi, 2014)
Bangunan pelindung dapat disiasati dengan memanfaatkan bahan-bahan
yang mudah didapat di sekitar rumah dan harganya murah. Dalam
pembuatannya Hermawan (2014), berpendapat bahwa konstruksi bangunan
pelindung adalah sebagai berikut :
Bangunan sederhana, terbuat dari papan/sisa-sisa pakan
Bangunan permanen, yang terbuat dari bahan kayu atau beton.
3.6 Media Budidaya
23
3.6.1 Tanah
Terdapat banyak jenis media dalam budidaya cacing tanah. Paradigma
masyarakat Indonesia secara umum, cacing tanah dibudidayakan dalam media
tanah. Secara umum komposisi tanah terdiri dari empat komponen utama yaitu
bahan mineral, bahan organik, udara dan air tanah. Kadar komposisi tanah ini
nantinya akan berpengaruh terhadap bentuk, warna, tekstur dan kesuburan
tanah (Wahyudi, 2011).
Suhardi (1983), menyatakan bahwa tanah merupakan lapisan permukaan
bumi yang memiliki tiga fungsi utama. Secara fisik berfungsi sebagai tempat
tumbuhnya akar tanaman serta sebagai suplai kebutuhan air dan udara. Secara
kimiawi, tanah berfungsi gudang penyuplai hara atau nutrisi. Dan secara biologi,
tanah berfungsi sebagai habitat organisme yang berpartisipasi aktif dalam
penyediaan hara seperti cacing tanah Lumbricus rubellus untuk menghasilkan
biomass dan produksi yang baik.
3.6.2 Log Jamur
Serbuk kayu mengandung beragam zat yang didalamnya dapat
menstimulasi pertumbuhan atau sebaliknya. Zat-zat yang dibutuhkan jamur untuk
tumbuh yaitu karbohidrat, serat dan lignin. Zat yang dapat menghambat
pertumbuhan yaitu zat metabolit sekunder atau yang umum dikenal sebagai
getah dan atsiri. Dalam pembuatan 100 kg log jamur diperlukan serbuk gergaji
sebanyak 100 kg pula, bekatul 10 kg, kapur 0,5 kg, tepung jagung 0,5 kg, air 4560% dari total berat, TSP 0,5 kg dan gipsum 0,5 kg (Muchlisin, 2013).
Log jamur tiram merupakan pencampuran dari beberapa bahan,
diantaranya serbuk gergaji kayu (Susilawati dan Budi, 2010). Komposisi yang
mengandung bahan organik tinggi inilah yang membuat log jamur merupakan
media yang baik untuk budidaya cacing tanah. Selain itu, dengan atau tanpa
24
fermentasi, log jamur merupakan bahan yang siap digunakan untuk budidaya
cacing tanpa perlu melewati banyak proses yang rumit terlebih dahulu.
3.6.3 Rumen Sapi dan Kotoran Sapi
Menurut Arora (1989), kandungan nutrisi dalam rumen sapi terdiri dari air
16,30%; abu 13,25%; PK 16,20%; SK 28,32%; kalsium 0,38%; dan phospor
0,55%. Selain itu isi rumen juga kaya akan vitamin khususnya vitamin B
kompleks dan K yang merupakan hasil sintesa mikroorganisme di dalam rumen
dan mineral.
Kotoran sapi merupakan bahan organik yang secara spesifik berperan
dalam meningkatkan ketersediaan phospor dan unsur mikro. Kotoran sapi
banyak mengandung hara yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen, phospor,
kalium, kalsium, magnesium dan boron (Nurmawati dan Anang, 2000).
3.7 Teknik Budidaya Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)
3.7.1 Persiapan Media
Sebelum dilakukan budidaya cacing tanah, terlebih dahulu dilakukan
sejumlah persiapan antara lain persiapan media dan persiapan wadah budidaya.
Di UPBAT Kepanjen, kegiatan budidaya cacing tanah dilakukan dengan media
log jamur. Log jamur merupakan media yang terbuat dari sisa proses budidaya
jamur tiram. Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pemilihan
media log jamur disebabkan oleh ketersediaan bahan organik yang tinggi pada
log jamur itu sendiri karena komposisi log jamur yang terbuat dari serbuk gergaji
dan bahan-bahan lain. Sehingga log jamur merupakan bahan jadi siap pakai
untuk budidaya.Namun, untuk meningkatkan nilai kandungan unsur hara itu
sendiri terlebih dahulu dilakukan proses fermentasi media menggunakan
probiotik. Media pemeliharaan cacing tanah terdiri dari serbuk gergaji dengan
campuran kompos (kotoran hewan) dan bahan organik (limbah pertanian dan
25
limbah pasar) dengan perbandingan 2:1:1, kemudian di fermentasi dengan
menggunakan probiotik dengan dosis 1 liter/m3selama 1 bulan lamanya dalam
kondisi tertutup, tidak terkena sinar matahari secara langsung dan tidak tembus
udara.Proses ini dilakukan pada bak fiber dan ditutup meggunakan terpal. Log
jamur dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Log Jamur (Dokumen pribadi, 2014)
Adapun langkah-langkah persiapan media meliputi fermentasi dan
pengering-anginanseperti yang ditunjukkan pada Gambar 8 dan Gambar 9
adalah sebagai berikut :
Dipersiapkan media log jamur pada kolam yang sebelumnya telah dilapisi
terpal.
Disiapkan probiotik sebanyak 1 liter. Dosis ini digunakan untuk fermentasi
media sebanyak 1m3.
Dihomogenkan probiotik dan media dengan cara pengadukan manual
menggunakan tangan.
Pemberian probiotik dilakukan sedikit demi sedikit agar kelembaban
media dapat merata pada seluruh bagian media.
Difermentasi selama 1 bulan dengan kondisi kedap udara serta tidak
terkena cahaya matahari secara langsung.
Setelah 1 bulan dibuka lalu dikering-anginkan dan siap digunakan.
26
Gambar 8. Fermentasi log jamur (Dokumen pribadi, 2014)
Gambar 9. Proses pengering-anginan media (Dokumen pribadi, 2014)
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai indikator media yang
baik adalah sebagai berikut :
Media harus terdiri dari bahan organik yang berserat dan sudah mengalami
pelapukan serta tidak mengeluarkan gas yang tidak diinginkan cacing tanah.
Media harus mampu menahan kelembaban. Kelembaban yang baik untuk
perkembangan cacing tanah adalah 35-50%
Media harus gembur dan mudah terdekomposisi.
Kandungan protein media rendah (15%) dan suhu sekitar 20-30oC.
Setelah media siap digunakan, maka media diletakkan pada wadah
budidaya. Untuk wadah berupa kolam beton, maka ketebalan media yang
optimal untuk pertumbuhan cacing pertama kali adalah 10 cm. Sedangkan untuk
sistem rak, ketebalan media berkisar antara 2 sampai 5 cm.
Fermentasi yang dilakukan memang bertujuan untuk menambah nilai
nutrisi yang ada pada media. Hal ini sependapat dengan pernyataan Pumphrey
dan Julien (1996), yang mengemukakan bahwa fermentasi merupakan suatu
teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk melakukan proses produksi
dalam rangka mendapatkan sebuah produk yang baru dan produk yang
dihasilkan akan mengalami pertambahan kandungan nutrisi.
3.7.2 Wadah Pemeliharaan
27
Wadah yang digunakan dalam pemeliharaan cacing tanah memiliki banyak
jenis. Di UPBAT Kepanjen sendiri, wadah budidaya cacing tanah terdiri dari
kolam beton dan sistem rak. Kolam beton yang digunakan untuk budidaya cacing
tanah di UPBAT Kepanjen berukuran 3mx3m dan 2,5mx2,5m dengan ketinggian
masing-masing kolam adalah 100 cm atau 1 meter.Untuk sistem rak dengan
wadah berupa karung bekas berukuran 90 cm x 30 cm dengan kapasitas volume
karung terhadapmedia setebal 15 cm, masing-masing rak terdiri dari 3 shaf
sebanyak 60 unit.
Ketinggian optimum bagi budidaya cacing tanah system kolam beton adalah
10 cm dengan padat tebar per meter persegi sebanyak 2,5 kg. Media pada
system rak setebal 5 cm dengan padat tebar sebanyak 0,5 kg.
Karung bekas digunakan karena efektif, efisien dan mudah didapat. Dalam
hal ini, yang perlu diperhatikan oleh pembudidaya dalam pemeliharaan dengan
sistem rak adalah jarak antara susunan rak sebaiknya tidak terlalu rapat, juga
tidak terlalu renggang. Jarak dari lantai ke alas rak pertama sebaiknya tidak
terlalu mepet. Hal ini untuk menghindari jangkauan hama atau binatang
pengganggu dan wadah tidak mudah terendam genangan air pada saat hujan.
Jarak yang baik dari lantai ke alas pertama minimal 50 cm. Semua jenis wadah
ini sesuai untuk semua fase stadia perkembangan cacing tanah. Baik itu
indukan, telur, larva maupun bibit cacing tanah. Tidak ada ketentuan berapa
jumlah shaf maksimal dalam satu rak, karena jumlah shaf menyesuaikan dengan
jangkauan ketinggian masing-masing orang yang berbeda.Wadah budidaya di
UPBAT Kepanjen ditunjukkan pada Gambar 10, Gambar 11 dan Gambar 12.
28
Gambar 10. Wadah pemeliharaan sistem rak (Dokumen pribadi, 2014)
(a) (b)
Gambar 11(a) Kolam beton berukuran 2,5 m x 2,5 m x 1 m
(b) Kolam beton berukuran 3 m x 3 m x 1 m
(Dokumen pribadi, 2014)
Hermawan (2014) mengemukakan bahwa selain kolam beton dan sistem
rak, wadah yang digunakan dapat berupa kotak plastik berukuran 45 cm x 35 cm
x 16 cm, kotak kayu yang berukuran 45 cm x 45 cm x 25 cm dan anyaman
bambu (besek).
3.7.3 Pemeliharaan Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)
a. Pemilihan Bibit Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)
Salah satu indikator bibit cacing tanah yang baik adalah yang sudah
dewasa dan sehat. Cacing tanah yang sudah dewasa adalah cacing tanah yang
sudah memiliki klitelium pada tubuhnya.Klitelium adalah bagian tubuh yang
menebal dan terletak pada segmen 26-32 dari bagian atas tubuh cacing. Pada 1
kg cacing dewasa diasumsikan terdapat sebanyak 1.000 ekor cacing tanah. Bibit
cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang siap menjadi induk ditunjukkan pada
Gambar 12.
Cacing tanah dewasa adalah cacing yang sudah memasuki umur 2,5-3
bulan sejak menetas dari kokon dengan panjang tubuh sekitar 8-14 cm. Warna
tubuh bagian punggung merah hingga ungu kemerahan serta berwarna krem
pada bagian perut. Jika sudah memenuhi beberapa indikator seperti ini, maka
29
cacing tanah sudah dapat dikategorikan cacing tanah yang sudah dewasa dan
siap untuk dijadikan bibit cacing tanah untuk diperbanyak jumlahnya dan
diproduksi dalam skala besar (Hermawan, 2014).
Gambar 12. Bibit Cacing Tanah (L. rubellus)
(Dokumen pribadi, 2014)
b. Penebaran Bibit
Setelah bibit cacing tanah tersedia, selanjutnya dilakukan penebaran bibit
pada media yang telah disiapkan. Pada kolam beton, padat penebaran yang
optimal per meter persegi sebanyak 2 kg. Wadah berupa sak berukuran 90 cm x
30 cm dengan kapasitas volume karung terhadap media setebal 15 cm, masingmasing rak terdiri dari 3 shaf sebanyak 60 unit pada sistem rak dapat diisi
dengan 400-500 gram cacing tanah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
pemantauan pertumbuhan cacing tanah pada sak. Cara penebaran bibit di
gambarkan pada Gambar 13. Adapun cara penebaran bibit cacing tanah adalah
sebagai berikut :
Bibit cacing tanah yang telah disiapkan dikeluarkan sebagian dari dalam
wadah pengangkutan dan bibit cacing tanah dihindarkan dari sinar matahari
langsung.
Ambil bibit cacing tanah dan letakkan di beberapa titik media secara merata.
Amati beberapa saat, bila terlihat bibit langsung masuk dalam media, maka
bibit yang lainnya dapat dimasukkan. Artinya, media pemeliharaan telah
sesuai dengan syarat hidup cacing. Apabila terjadi sebaliknya, maka media
30
tersebut tidak disukai cacing akibat media terlalu kering dan perlu dilakukan
pemberian air secukupnya sedikit demi sedikit hingga dirasa media sudah
cukup lembab dan tidak terlalu basah. Jika media terlalau basah, maka media
harus segera diganti dengan yang baru atau diberikan penambahan media
secukupnya. Jika media mengeluarkan bau, maka media harus segera
diganti.
Gambar 13. Penebaran Bibit Cacing Tanah (L. rubellus)
(Dokumen pribadi, 2014)
Dalam beternak cacing tanah secara komersial, sebaiknya digunakan bibit
yang sudah ada karena diperlukan pengembangan dalam jumlah yang besar.
Namun, bila akan dimulai dari skala kecil dapat pula digunakan bibit dari alam,
yang diperoleh dari tumpukan sampah yang membusuk atau dari tempat
pembuangan kotoran hewan (Hermawan, 2014).
c. Pembesaran Cacing Tanah (Lumbricus rubellus)
Setelah bibit ditebar lalu dilihat bagaimana responnya terhadap media
selama 12 jam dan ternyata cacing menyebar ke dalam media, maka dapat
disimpulkan bahwa media telah sesuai untuk cacing dan cacing telah mampu
beradaptasi dengan baik pada media tersebut. Kegiatan yang dilakukan
berikutnya adalah pemeliharaan atau pembesaran cacing tanah (Lumbricus
Rubellus). Pada masa awal usaha budidaya cacing, diperlukan waktu selama 2-3
bulan agar cacing dapat tumbuh dan jumlahnya semakin banyak. Hal ini
31
bertujuan untuk proses budidaya yang berkelanjutan. Pada saat cacing berumur
2 bulan, cacing dikategorikan cacing dewasa dan siap kawin. Cacing yang
sedang dalam proses perkawinan, maka keduanya akan saling melekat rapat.
Meskipun cacing adalah hewan hemaprodit protandri, tetapi untuk menghasilkan
kokon tetap dilakukan oleh sepasang cacing. Seekor cacingmenghasilkan 1
kokon dan setiap kokon akan menetaskan rata-rata 4 ekor anakan cacing.
Dalam penelitiannya, Mubarok dan Lili (2000) menyatakan bahwa sejak
awal siklus hidupnya, cacing tanah (Lumbricus rubellus) akan mengalami masa
produktif pada bulan ke 4 10 masa pemeliharaan sebelum kemudian
produktifitasnya akan menurun hingga cacing mengalami kematian.
d. Pemberian Pakan
Cacing tanah diberi pakan sekali dalam sehari semalam sebanyak berat
cacing tanah yang ditebar. Apabila cacing yang ditebar sebanyak 2 kg, maka
pakan yang diberikan sebanyak 2 kg pula. Secara umum pakan cacing tanah
adalah berupa semua kotoran hewan, kecuali kotoran yang hanya dipakai
sebagai media serta dapat pula digunakan limbah bahan organik sebagai pakan.
Pemberian pakan di hari selanjutnyaterlebih dahulu dilakukan pengamatan pada
media budidaya, apabila masih tersisa pakan pada media, maka pakan harus
diaduk kedalam media dan pemberian pakan dikurangi. Tetapi apabila tidak
terdapat sisa pakan dalam media, maka pemberian pakan perlu dilakukan
penambahan jumlahnya.
Pakan yang diberikan berupa limbah sayur pasar serta ampas tahu yang
terlebih dahulu di fermentasi. Pakan berupa limbah sayur di fermentasi maksimal
4 hari dalam wadah yang kedap udara dan diletakkan pada ruangan tertutup
untuk mempercepat proses fermentasi. Apabila fermentasi melebihi waktu 4 hari,
maka akan terjadi penurunan nilai nutrisi pada pakan yang difermentasi dan
memicu tingginya kadar alkohol di dalam pakan sehingga pakan tidak layak
untuk diberikan pada cacing karena dikhawatirkan akan terjadi keracunan yang
32
menyebabkan kematian cacing dalam jumlah yang besar. Pakan ampas tahu dan
sayuran fermentasi di tunjukkan pada Gambar 14.
Gambar 14. Ampas tahu dan limbah sayur fermentasi
(Dokumen pribadi, 2014)
Adapun cara pembuatan pakan limbah sayur fermentasi adalah sebagai
berikut :
Limbah sayur terlebih dahulu dicacah sampai ukurannya menjadi kecil.
Limbah sayur ditempatkan pada bak fermentasi
Ditambahkan probiotik secukupnya dan dihomogenkan
Dimasukkan kedalam kantung plastik lalu ditutup rapat dan jangan sampai
ada rongga udara di dalam plastik
Plastik dimasukkan ke dalam karung yang lebih besar dengan tujuan
mencegah kebocoran udara dan terhindar dari sinar matahari langsung.
Dibiarkan selama maksimal 3 - 4 hari dan pakan fermentasi siap diberikan
pada cacing
Pakan ampas tahu bisa langsung di fermentasi dan dibiarkan maksimal
selama 3 4 hari pula lalu diberikan pada cacing.
Dalam kondisi yang tepat, cacing tanah dapat makan sebanyak berat
tubuh mereka per harinya. Dengan kata lain, FCR cacing adalah 1. Untuk
menghasilkan 1 kg cacing maka harus diberikan pakan sebanyak 1 kg pula.
Namun, pada awal pemeliharaan sebaiknya cacing diberi makan sebanyak
setengah dari berat tubuhnya untuk selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan
makan cacing. Jika makanan terlalu banyak dan cacing tidak mampu
menghabiskan dalam waktu yang relatif lama, maka media dan tempat
pemeliharaan akan menjadi bau. Tetapi jika terlalu sedikit, cacing akan kelaparan
dan stress (Hermawan, 2014).
e. Penanganan Telur (Kokon)
Cacing merupakan hewan hemaprodit yang pembuahan sel telur terjadi
secara eksternal atau diluar tubuh induk. Maka letak kokon dalam media akan
33
sangat sulit dibedakan karena bentuknya yang tidak terlalu besar. Apabila tidak
diamati secara jeli dan mendetail, tidak akan dapat dibedakan mana kokon dan
seresah-seresah sisa pakan yang ada didalam media. Kokon akan menetas
pada hari ke 14 sampai 21 hari setelah terlepas dari tubuh induknya.
Di UPBAT Kepanjen tidak dilakukan pemanenan kokon. Dalam artian,
apabila kokon ditemukan didalam media maka kokon tersebut dibiarkan menetas
didalam media hinggamenjadi larva dan anakan cacing. Setelah dirasa media
terlalu padat karena pertumbuhan cacing dan jumlah cacing yang semakin
banyak, barulah dilakukan pemanenan secara parsial cacing dewasa yang sudah
berada dibagian atas media. Sementara cacing yang masih anakan dan berada
dibagian tengah ditinggalkan dan dibesarkan. Begitu seterusnya. Kokon cacing
tanah (Lumbricus rubellus) dapat dilihat pada Gambar 15.
Gambar 15. Kokon (Dokumen pribadi, 2014)
Hermawan (2014), mengemukakan bahwa perkembangan kokon dimulai
dari 2 minggu setelah cacing bertelur. Kokon yang baru dihasilkan masih
berwarna kuning kehijauan dan akan menjadi kemerahan saat akan menetas.
Faktor yang mempengaruhi produksi kokon adalah kelembaban media,
cadangan makanan yang cukup serta lingkungan yang bersuhu antara 16-60oC.
Apabila tanah lembab, maka kokon akan diletakkan di permukaan tanah. Namun
apabila tanahnya kering, maka kokon diletakkan didalam tanah.
f. Pemeliharaan Larva
Setelah kokon menetas, maka dihasilkan larva cacing. Pemeliharaan larva
dilakukan pada wadah yang sama. Artinya, tidak dilakukan pemindahan atau
pemanenan larva. Hal ini dikarenakan ukuran larva yang masih sangat kecil.
Larva dipelihara pada media dengan ketinggian optimal 10 cm. Namun jika
34
dilakukan pemanenan pada induk secara total beserta penggantian media, maka
media yang ditempati larva akan dikembalikan pada tempatnya dan diberikan
sedikit penambahan media baru. Larva diberi perlakuan berbeda pada pakan
dan komposisinya, namun tetap dilakukan proses fermentasi terlebih dahulu.
Pakan larva cacing berupa bubur. Ini untuk memudahkan cacing dalam
mencerna pakan. Larva dan pemberian pakan larva dalam bentuk bubur di
tunjukkan pada Gambar 16 dan Gambar 17. Berikut penjelasan tentang
komposisi pakan, cara membuat serta pemberian pakan bagi larva :
Limbah sayur dan kotoran hewan digiling menggunakan air dengan
perbandingan antara bahan dan air sebanyak 1:1
Difermentasi menggunakan probiotik selama 2 minggu
Pakan dimasukkan kedalam plastik lalu ditutup dengan karung bekas atau
terpal atau bahan lain yang tidak tembus cahaya.
Pakan siap diberikan
Cara pemberian pakan yaitu dengan cara bubur yang sudah jadi ditaburkan
rata diatas media, tetapi
2
3 bagian media tidak boleh tertutup agar tetap
ada sirkulasi udara.
Gambar 16. Larva cacing tanah (L. rubellus) (Dokumen pribadi, 2014)
35
Gambar 17. Pemberian pakan larva (Dokumen pribadi, 2014)
Mubarok dan Lili (2000), pemberian pakan pada larva cacing tanah
dilakukan sebagaimana mestinya saat pembesaran cacing tanah. Artinya, tidak
dilakukan pembedaan perlakuan pemberian pakan antara cacing tanah yang
sudah dewasa dengan yang berada pada stadia larva. Pengontrolan pakan
harus dilakukan dengan tujuan agar pakan selalu habis tepat waktu dan
menghindari kekurangan jumlah pakan. Bila ternyata tidak habis tepat waktu
maka pakan akan menggumpal dan secepatnya harus diaduk atau diremahkan
dan disebar di seluruh bagian permukaan agar merata dan dapat di makan
secara langsung oleh cacing tanah.
g. Pemanenan
Pada proses budidaya cacing tanah, terdapat 2 produk utama yang dapat
dihasilkan, yaitu cacing tanah itu sendiri serta kascing (bekas cacing) yang
sangat baik untuk kegiatan pertanian. Cacing dapat dipanen untuk kali pertama
pada saat berumur 3 bulan. Ini bertujuan untuk memperbanyak jumlahnya
terlebih dahulu dalam rangka proses budidaya yang berkelanjutan. Setelah itu,
cacing tanah dapat dipanen setiap 1 bulan sekali. Rata-rata, survival rate (SR)
dari cacing tanah adalah 100% dengan jumlah produksi yang dihasilkan
sebanyak 2 kali lipat populasi awal. Artinya, jika dalam tebar awal per meter
persegi diberi bibit sebanyak 2 kg maka akan didapat hasil panen sebanyak 4 - 5
kg.
Teknik pemanenan cacing tanah di UPBAT Kepanjen yaitu dengan cara
memanfaatkan sifat alami cacing tanah yang tidak menyukai cahaya. Dengan
menggunakan lampu petromaks, cacing tanah akan berkumpul dibagian bawah
media lalu dilakukan pengambilan cacing. Juga dengan cara yang lain yakni
36
dengan cara mengambil cacing yang bergerombol beserta medianya pada
bagian pinggir wadah budidaya lalu cacing tanah ditempatkan pada tempat yang
terang. Cacing yang terkena cahaya akan berusaha melarikan diri dan masuk
kedalam media serta bergerombol dalam jumlah besar. Untuk memisahkan
antara cacing dengan media, cara yang paling mudah dilakukan yakni dengan
mengambil media beserta cacing yang terambil digundukkan lalu dikikis sedikit
demi sedikit medianya. Hindari proses penyinaran yang terlalu lama karena akan
berakibat pada kematian cacing. Hal ini dikarenakan ketika cacing terkena
panas, maka ia akan memproduksi lendir dalam jumlah besar untuk
mendinginkan tubuhnya. Apabila dalam kondisi seperti ini, maka cacing akan
lemas kemudian mati. Pemanenan cacing tanah ditunjukkan pada Gambar 18di
bawah ini.
Ada cara panen yang lebih ekonomis, yakni dengan membalikkan sarang.
Cara ini diaplikasikan pada wadah yang tidak terlalu besar seperti besek maupun
bak plastik. Dibalik sarang yang gelap ini, cacing biasanya berkumpul dan akan
lebih mudah terkumpul. Kemudian sarang dibalik kembali dan dipisahkan antara
cacing yang dipanen dan cacing yang sengaja ditinggal untuk dibesarkan lagi
dan akan dipanen pada tahap selanjutnya (Hermawan, 2014).
Gambar 18. Pemanenan Cacing tanah (Lumbricus rubellus)
(Dokumen pribadi, 2014)
h. Pemasaran
37
Setelah proses pemanenan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah
pengepakan. Cacing diletakkan pada jaring dan pada jaring itu diberi media serta
pakan dan memiliki ukuran rongga tidak terlalu besar agar cacing tidak melarikan
diri lalu ujungnya diikat rapat, kemudian diletakkan pada wadah berupa
sterofoam. Tujuan pemberian media dalam wadah adalah agar cacing dapat
bertahan hidup selama dalam perjalanan dan tentu saja kelembaban media
merupakan perhatian utama. Karena apabila media terlalu kering akan
mengakibatkan cacing stress. Ketika cacing stress maka cacing akan
mengeluarkan lendir untuk menyesuaikan diri. Ketika dalam kondisi
mengeluarkan banyak lendir dan media tidak sesuai inilah yang menyebabkan
turunnya bobot cacing sampai 50% dari berat awal biomassnya serta kematian.
Pemberian pakan juga bertujuan agar persediaan pakan selama dalam
perjalanan mencukupi kebutuhan. Setiap wadah berisi cacing sebanyak 1 kg.
Cacing siap di pasarkan. Selama ini, cacing dipasarkan pada pengepul di daerah
Sukun, Malang untuk kemudian didistribusikan pada wilayah yang lebih luas lagi.
Packing cacing tanah (L. rubellus) ditunjukkan pada Gambar 19 berikut ini.
Gambar 19. Pengepakan Cacing Tanah (L. rubellus)
(Dokumen pribadi, 2014)
Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pendistribusian cacing
tanah (L. rubellus) menurut Hermawan (2014) adalah sebagai berikut :
Cacing disimpan terlebih dahulu dalam penampungan selama 2 hari
38
Diberi makanan ampas tahu atau ongok untuk meningkatkan bobot atau
perbaikan gizi
Bila produk cacing akan digunakan sebagai bahan pembuat obat, tepung
cacing dan cacing kering sebaiknya cacing dibudidayakan pada media yang
halal atau bukan kotoran ternak. Misalnya media ampas aren atau ampas
tebu. Ini berfunsi untuk perbaikan gizi, juga agar bakteri yang bersifat
merugikan hilang
Saat cacing akan dikirim, perlu diperhitungkan lama waktu transportasi untuk
menentukan berapa banyak media yang diperlukan agar cacing tidak mati
i.
karena kekurangan media
Gunakan bahan-bahan yang tembus udara dan kuat.
Pengendalian Hama dan Penyakit
Dalam suatu usaha budidaya, selalu terdapat banyak kendala. Begitu pula
dengan budidaya cacing tanah. Kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya
cacing tanah (Lumbricus rubellus) pun beragam. Mulai dari faktor lingkungan
yang sulit diatasi seperti suhu dan musim yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan cacing tanah, juga adanya hama maupun
penyakit yang menyerang cacing tanah. Selama ini, hama yang menyerang
cacing tanah berupa semut, tikus, predator seperti ayam dan bebek serta kutu
tanah yang berperan sebagai kompetitor pakan. Salah satu usaha pencegahan
hama penyakit pada cacing tanah (L. rubelllus) ditunjukkan pada Gambar 20.
Berbagai langkah dilakukan untuk menanggulangi gangguan hama ini.
Diantaranya adalah sebagai berikut :
Pemberian kapur semut pada bagian luar wadah budidaya untuk mencegah
semut masuk kedalam media.
Pemberian jaring (paranet) pada bagian atas media budidaya untuk
mencegah predator seperti tikus, ayam dan bebek masuk ke dalam wadah.
Pemberian air (perendaman) pada bagian kaki rak atau bagian luar wadah
budidaya.
Pengontrolan secara rutin.
39
Gambar 20. Pencegahan hama dengan pemberian paranet
(Dokumen pribadi, 2014)
Selain semut, tikus, ayam dan bebek, terdapat juga hama yang lain.
Hermawan (2014), menuliskan dalam bukunya bahwa lintah juga merupakan
hama bagi cacing. Lintah membunuh cacing tanah dengan menghisap darah
cacing tanah sampai habis. Cara mencegah lintah sederhana saja, yakni dengan
cara menaburkan tembakau pada permukaan media.
j.
Perawatan Media
Selain memperhatikan dan memantau kualitas media (kelembaban)
secara rutin, hal lain yang perlu dilakukan adalah perawatan media. Gambar 21
menunjukkan proses perawatan media budidaya cacing tanah (Lumbricus
rubellus). Log jamur merupakan media yang siap pakai dan mengandung bahan
organik yang tinggi. Sementara itu, peranan cacing tanah di alam sebagai
dekomposer juga menjadikan kandungan bahan organik yang ada dalam log
jamur lama-lama akan habis. Oleh sebab itu media akan menjadi kehitamhitaman menyerupai tanah. Rata-rata penggantian media dilakukan dalam
jangka waktu berkisar 5-6 bulan. Apabila dibiarkan tanpa dilakukan penggantian
maka cacing tanah akan terhambat proses pertumbuhannya bahkan menurun
produktifitasnya karena mengalami kematian. Untuk itu, pergantian atau
pembongkaran media akan dilakukan secara total apabila :
Dilakukannya proses panen total
Media berbau busuk, yang ditandai dengan banyaknya cacing tanah yang
keluar dari media budidaya
Mortilitas yang tinggi
Ketinggian media sudah lebih dari 80 cm
Jika media terendam air karena hujan atau sebab lain.
40
Hermawan (2014), berpendapat bahwa selain penggantian media, maka
juga dilakukan proses pengadukan agar media menjadi gembur dan sirkulasi
oksigen dalam media menjadi lancar. Pengadukan dilakukan setiap 3-4 hari
sekali. Penyiraman media dilakukan saat pengadukan media tampak kering
dengan jumlah air secukupnya agar media tidak terlalu basah. Media yang terlalu
basah atau terlalu kering bisa menyebabkan cacing stress dan mati. Serta
pengukuran suhu dan pH agar tumbuh kembang dapat berjalan secara optimal.
Gambar 21. Pembalikan media (Dokumen pribadi, 2014)
3.8 Hambatan dan Potensi Pengembangan Usaha
3.8.1 Permasalahan yang Dihadapi
Hambatan atau permasalahan yang sering dihadapi pada saat budidaya
cacing tanah di UPBAT Kepanjen adalah sebagai berikut :
Suhu udara yang fluktuatif, sehingga menyebabkan proses tumbuh kembang
yang tidak maksimal karena cacing mengalami stress.
Ketersediaan log jamur. Log jamur terkadang sulit di dapat karena jarangnya
pemilik usaha budidaya jamur tiram di wilayah sekitar UPBAT Kepanjen.
Sulitnya mendapat pakan ampas tahu karena berebut dengan peternak sapi
dan jauhnya lokasi pabrik tahu.
Pemasaran yang hanya terbuka pada satu jalur atau satu pengepul.
Kendala-kendala ini dapat diatasi dengan cara mempersiapkan tahap awal
dengan baik. Dalam artian, pelaku budidaya harus mempunyai contact person
dari beberapa pembudidaya jamur tiram dalam rangka ketepatan dan ketepatan
suplai log jamur. Juga dengan cara pemasaran yang lebih variatif berkenaan
dengan kemajuan teknologi dan komunikasi.
41
3.8.2 Potensi Pengembangan Usaha
Pengembangan dan peningkatan usaha budidaya cacing tanah (L.
rubellus) masih memiliki peluang yang besar. Hal ini seiring dengan
meningkatnya permintaan terhadap produksi cacing tanah (L. rubellus) sebagai
bahan baku dari berbagai jenis produk kebutuhan manusia. Peningkatan tersebut
dapat dicapai jika ditunjang dengan fasilitas yang baik serta keterampilan
pembudidaya dalam mendukung aspek-aspek budidaya.
3.9 Analisis Usaha
Usaha apapun akan kehilangan daya tariknya apabila usaha tersebut tidak
menjanjikan keuntungan yang besar. Untuk mengetahui besarnya keuntungan
yang akan diperoleh maka diperlukan analisis usaha yang dapat
dipertanggungjawabkan. Secara umum, analisis usaha hanya dilihat dari sisi
ekonomis saja.
Dengan adanya analisis usaha dalam budidaya ini maka biaya-biaya yang
tidak penting dapat dihindari, selain itu dapat juga diperkirakan seberapa besar
modal yang diperlukan. Analisis usaha adalah perhitungan biaya usaha dan
hasil yang diperoleh dari usaha tersebut. Tujuan disusunnya analisis usaha
adalah untuk mengetahui berapa banyak modal yang perlu diinvestasikan dalam
usaha dan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh selanjutnya.
Perhitungan analisis usaha dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai
kebutuhan pembudidaya. Adapun perhitungan yang digunakan dalam analisis
usaha pada laporan ini mencakup perhitungan tentang permodalan, biaya
produksi, analisis keuntungan, R/C ratio, rentabilitas dan BEP (Break Event
Point).
3.9.1 Analisis Jangka Pendek
42
a. Analisis Rugi Laba
Analisis rugi laba bertujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan atau
kerugian dari usaha yang dikelola. Keuntungan diperoleh dari jumlah total
penerimaan selama 1 siklus produksi dikurangi dengan total biaya produksi
(Rahardi et al., 2005).
Keuntungan = penerimaan - biaya operasional
= Rp. 9.000.000,00 Rp. 300.000,00
= Rp. 8.700.000,00
Budidaya cacing tanah (L. rubellus) menghasilkan keuntungan Rp.
8.700.000,00 selama 1 siklus atau 3 bulan (perhitungan dapat di lihat pada
Lampiran 2).
b. AnalisisBreak Event Point (BEP)
Menurut Suryanto (2008) menjelaskan bahwa analisisBreak Event Point
(BEP) adalah keadaan dimana seluruh penerimaan (total revenues) secara
persis hanya mampu menutup seluruh pengeluaran (total cost). Dengan kata lain
pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Keadaan
ini menunjukkan bahwa usaha ini berada pada posisi tidak memperoleh
keuntungan dan tidak mengalami kerugian.
Pada usaha budidaya cacing tanah (L. rubellus) diperoleh nilai BEP unit
sebesar 0,33kg. Artinya, produksi yang dihasilkan berada pada kondisi impas
apabila produksi per siklusnya dapat dijual minimal 0,33 kg cacing tanah.
Sedangkan nilai BEP atas dasar rupiah sebesar Rp.589.057,00 yang berarti
bahwa usaha pembenihan ini impas apabila jumlah pendapatan dalam 1 siklus
sebesar Rp. 589.057,00 (perhitungan selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran
2).
c. AnalisisRevenue Cost Ratio (R/C)
43
Analisis R/C ratio merupakan alat analisis untuk melihat keuntungan relatif
suatu usaha dalam satu tahun terhadap biaya yang dipakai dalam kegiatan
tersebut. Menurut Praptowo (2008), R/C rasio merupakan perbandingan antara
total penerimaan dengan total biaya yang digunakan untuk melakukan proses
produksinya. Suatu usaha dikatakan layak apabila R/C lebih besar dari 1 (R/C >
1), impas apabila (R/C = 1) dan tidak layak apabila (R/C < 1). Hal ini
menggambarkan semakin tinggi nilai R/C maka tingkat keuntungan suatu usaha
akan semakin tinggi. Dalam kegiatan budidaya cacing tanah (L. rubellus) ini
diketahui nilai R/C (perhitungan dapat di lihat pada Lampiran 2) adalah 2,8. Hal
ini menunjukkan bahwa kegiatan produksi dapat dikatakan layak untuk
dikembangkan karena nila R/C dapat melebihi 1.
d. Analisis Rentabilitas
Menurut Riyanto (1984), rentabilitas merupakan suatu perusahaan
menunjukkan perbandingan antar laba dengan aktiva atau modal yang
menghasilkan laba tersebut. Besarnya nilai rentabilitas pada usaha budidaya
cacing tanah (Lumbricus rubeluus) adalah 171%. Angka tersebut berarti bahwa
dari Rp 100,00 yang diinvestasikan akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp.
171,00. Untuk lebih jelasnya, perhitungan rentabilitas dapat dilihat pada
Lampiran 2.
3.9.2 Analisis Jangka Panjang (Payback Period)
Payback Periode adalah suatu periode yang menunjukkan berapa lama
modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut dapat kembali (Niwanputri,
2007). Dari perhitungan PP (perhitungan dapat di lihat pada Lampiran 2)
diketahui bahwa keseluruhan modal yang digunakan untuk budidaya cacing
tanah (L. rubellus) dapat dikembalikan dalam jangka waktu 0, 09 tahun atau 1,16
bulan.
44
45
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Dari Praktek Kerja Lapang (PKL) yang telah dilaksanakan di UPBAT
Kepanjen, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
Budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus) terdiri dari persiapan media,
persiapan wadah, pemilihan bibit, penebaran bibit, pembesaran, pemberian
pakan, pemeliharaan larva, pemanenan dan pemasaran.
Lama waktu pemeliharaan cacing tanah (Lumbricus rubellus)selama 1 siklus
adalah 3 bulan untuk proses produksi awal dan selanjutnya 1 bulan.
Pemberian pakan dilakukan sebanyak sekali dalam sehari dengan FCR 1.
Sedangkan untuk larva, pakan yang diberikan haruslah dijadikan bubur
terlebih dahulu agar dapat dicerna dengan mudah oleh larva cacing tanah itu
sendiri.
Padat tebar optimum untuk budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus)sistem
kolam beton adalah sebanyak 2 kg per meter persegi dan 0,5 kg untuk
budidaya sistem rak. Ketebalan media yang baik dalam proses budidaya
cacing tanah (Lumbricus rubellus) berkisar antara 5-10 cm.
Survival rate (SR) cacing tanah sebesar 100%, jumlah produksi dapat
mencapai 3 kali lipat jumlah tebar awal.
Harga beli bibit cacing tanah adalah sebesar Rp. 50.000 per kilogram serta
harga jual cacing tanah adalah Rp. 30.000 per kilogram
Analisis usaha dari budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus)dilakukan
dengan menghitung keuntungan, R/C ratio, BEP dan Payback periode. Dari
kegiatan budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus) ini diperoleh keuntungan
sebesar Rp. 8.700.00,00, R/C Ratio sebesar 2,8, BEP (unit) sebesar 0,33kg
dan BEP (rupiah) sebesar Rp. 589.057,00 dan Payback Period (PP) dalam
jangka waktu 0,085 tahun atau 1,02 bulan serta nilai rentabilitas sebesar
171%.
46
4.2 Saran
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapang dapat disarankan agar budidaya
cacing tanah (Lumbricus rubellus) dilakukan dengan baik dan benar agar para
pembudidaya tidak mengalami kerugian. Selain itu, perlu juga dikembangkan
budidaya cacing tanah spesies lain misalnya, Eisenia foetida, Pheretima asiatica,
dan Eudrilus eugeniae agar semakin beragam jenis cacing tanah yang
dibudidayakan.
47
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2002. Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek. Rineka Cipta.
Jakarta. 85 hlm.
Arora, S. P. 1989. Pencernaan mikroba pada ruminansia. Gadjah Mada
University Press: Jogyakarta. 39 hlm.
Hadisoewignyo, Lannie dan Yohanes Rendy. 2013. Formulasi kapsul ekstrak
Lumbricus rubellus dengan laktosa sebagai bahan pengisi dan PVP K-30
sebagai bahan pengikat. Jurnal Farmasi. 1 (1): 1-7.
Herayani, Yanti. 2001. Pertumbuhan dan perkembangbiakan cacing tanah
Lumbricus rubellus dalam media kotoran sapi yang mengandung tepung
daun murbei Morus multicaulis. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan. IPB.
Bogor.
Hermawan, Rudi. 2014. Usaha budidaya cacing Lumbricus multiguna dan
prospek ekspor tinggi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta. 176 hlm.
Hoerunisa, Novia. 2013. Pengaruh pendekatan taktis terhadap hasil belajar
permainan bola tangan dan implikasinya terhadap nilai-nilai kerjasama.
Skripsi.Universitas Pendidikan Indonesia.
Hasan, I. 2002. Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
Ghalia Indonesia. Jakarta. 260 hlm.
Koswara, E., Salam, D., dan Ruzhendi, A. 2001. Metode dan Masalah Penelitian
Sosial. Refika Aditama. Bandung. 348 hlm. Terjemahan dari Black, J.A.
dan Champion, D.J. 1999.Methods and issues in sosial research.
Kristanto, Anang Hari. 2007. Penguasaan teknologi budidaya untuk
menghasilkan benih ikan air tawar. Balai Riset Perikanan Budidaya Air
Tawar. 30 hlm.
Kusumawati, P., A. Rosyid., dan A.M. Kohar. 2011. Upaya peningkatan kinerja
usaha perikanan melalui peningkatan lingkungan usaha pada alat
tangkap cantrang (boat seine) dan kebijakan pemerintah daerah di
kabupaten rembang. J. Saintek Perikanan. 6 (1): 36-45.
48
Mubarok, Ahmad dan Lili Zalizar. 2000. Budidaya cacing tanah sebagai usaha
alternatif di masa krisis ekonomi. Karya Alternatif Mahasiswa. Universitas
Muhammadiyah Malang. Malang. 7 hlm.
Muchlisin, C. 2013. Membedah komposisi media tanam (baglog) jamur
tiram.http://cincinjamurmurah.blogspot.com/p/membedah-komposisimedia-tanam-baglog_19.html. Diakses pada 24 Agustus 2014 pukul 08.00
WIB.
Natzir. 1983. Metode penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Niwanputri, G. S. 2007. Penggunaaan pohon dalam decision tree analysisuntuk
pengambilan keputusan investasi dalam perencanaan bisnis. Diakses dari
http://www.informatika.org pada tanggal 30 September 2014pukul 21.00
WIB.
Nurmawati, S dan Anang, S. 2000. Studi perbandingan penggunaan pupuk
kotoran sapi dengan pupuk kascing terhadap produksi tanaman selada
(Lactuca Sativa var.crispa).IPB. Bogor. 47 hlm.
Palungkun, R. 1999. Sukses beternak cacing tanah Lumbricus rubellus.PT.
Penebar swadaya. Bogor. 124 hlm.
Palungkun, R. 2010. Usaha ternak cacing tanah.Swadaya. Jakarta. 124 hlm.
Paoletti, M. G. 1999. The role of earthworm for assessment of sustainability and
as bioindicators.Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment.74
(2): 137-155.
Pechenik, J.A. 2000. Biology of The Invertebrates. Fourth edition.McGraw Hill.
Companies Inc: Boston. 578p.
Pelczar, M.J dan Chan E. C. S. 1998. Dasar-dasar mikrobiologi 2. Angka
Penerbit UI-Press. Jakarta. 78 hlm.
Praptowo, K.W. 2008. Analisis trend penjualan dan prospek usaha
obatphyllanthus pada agroindustri obat tradisional tradimun kasus pada
49
agroindustriobat tradisional tradimun kabupaten gresik. Diakses dari
http://digilib.unej.ac.idpada tanggal 20September 2014.
Pumphrey, Brian and Christian Julien. 1996. An introduction to fermentation.
Fermentation Basics. Netherlands. 24 p.
Rahardi, F, Regina K dan Nazaruddin. 2005. Agribisnis perikanan. Penebar
Swadaya. 63 hlm.
Riyanto, B. 1984. Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan. Yayasan Badan
Penerbit Gadjah Mada. Yogyakarta. 318 hlm.
Sihombing, D. T. H. 2002. Satwa harapan I. pengantar ilmu dan teknologi
budidaya. Wirausaha muda: Bogor. 254 hlm.
Sugiri, N. 1984.Zoo avertebrata Vol 1. Pusat Antar Universitas. IPB. Bogor. 120
hlm.
Sugiri, N. 1988.Zoo avertebrata Vol 2. Pusat Antar Universitas. IPB. Bogor. 120
hlm.
Suhardi. 1983. Dasar-dasar bercocok tanam. Kanisius: Yogyakarta. 217 hlm.
Sukadi, M. Fatuchri. 2002. Peningkatan teknologi budidaya perikanan. Jurnal
Iktiologi Indonesia.2 (2): 61-66.
Suryabrata. 1991. Metodologi penelitian. CV. Rajawali. Jakarta. 96 hlm.
Susilawati dan Budi H. 2010. Budidaya jamur tiram (Pleorotus ostreatus var
florida) yang ramah lingkungan. Materi Pelatihan Agribisnis bagi KMPH. 9
hlm.
Wahyudi. 2011. Panen cabai sepanjang tahun. PT. Agromedia Pustaka: Jakarta.
179 hlm.
Anda mungkin juga menyukai
- Budidaya Cacing TanahDokumen9 halamanBudidaya Cacing TanahTutik HandayaniBelum ada peringkat
- Kandang SapiDokumen30 halamanKandang SapiFrengki Paskason TaekBelum ada peringkat
- Pedoman Pupuk PetroganikDokumen6 halamanPedoman Pupuk PetroganikMeydina Arri SetianingatiBelum ada peringkat
- Laporan Pemeliharaan ItikDokumen31 halamanLaporan Pemeliharaan Itikvicho ajeBelum ada peringkat
- Buidaya Cacing TanahDokumen14 halamanBuidaya Cacing TanahFandiPutraBelum ada peringkat
- Budidaya Cabe Merah KeritingDokumen14 halamanBudidaya Cabe Merah KeritingWidodo Slamet0% (1)
- Pakan Lengkap PDFDokumen26 halamanPakan Lengkap PDFLisa SilabanBelum ada peringkat
- Penyakit Kambing Dan DombaDokumen6 halamanPenyakit Kambing Dan DombaJoe SaragihBelum ada peringkat
- Petunjuk Teknis Beberapa Komoditas PertanianDokumen603 halamanPetunjuk Teknis Beberapa Komoditas Pertanianivan ara100% (1)
- Ulat HongkongDokumen9 halamanUlat HongkongAjun JunaediBelum ada peringkat
- Cara Hitung Keuntungan Peternakan BroilerDokumen45 halamanCara Hitung Keuntungan Peternakan BroilerRaka SaNdhy100% (3)
- Pengelolaan Indukan LeleDokumen7 halamanPengelolaan Indukan Leleselo_indri100% (1)
- Rahmat Proposal Ayam KampungDokumen10 halamanRahmat Proposal Ayam KampungSudarto SamBelum ada peringkat
- Budidaya KatakDokumen13 halamanBudidaya KatakelisabetBelum ada peringkat
- Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Pemotongan Ayam - UnggasDokumen11 halamanPenerapan Kesejahteraan Hewan Pada Pemotongan Ayam - Unggasnvp16Belum ada peringkat
- Budidaya Ayam PetelurDokumen12 halamanBudidaya Ayam Petelurcumi ajah100% (1)
- Membangun Kandang Sapi Yang Benar Dan SehatDokumen5 halamanMembangun Kandang Sapi Yang Benar Dan SehatKhorin Agus PriadanaBelum ada peringkat
- AkuaponikDokumen51 halamanAkuaponikZaki Fuady100% (3)
- 02-Pengolahan & Pengawetan Hijauan IDokumen22 halaman02-Pengolahan & Pengawetan Hijauan IRisma Dian Utami100% (2)
- PeralatanDokumen3 halamanPeralatanKenko RomanovaBelum ada peringkat
- KELINCIDokumen6 halamanKELINCIRinaBelum ada peringkat
- Pengolahan Pakan Sapi PerahDokumen23 halamanPengolahan Pakan Sapi PerahFaisal akbarBelum ada peringkat
- SOP-2 Ternak Lele (Penyempurnaan SOP-1)Dokumen10 halamanSOP-2 Ternak Lele (Penyempurnaan SOP-1)Sugiharto Hadi Wibowo PhlBelum ada peringkat
- Kompos Jerami H Zaka PDFDokumen17 halamanKompos Jerami H Zaka PDFIsroi.comBelum ada peringkat
- Panduan Praktis Cara Budidaya Azolla MicrophyllaDokumen3 halamanPanduan Praktis Cara Budidaya Azolla MicrophyllaEko WahyudiBelum ada peringkat
- Perencanaan Bangunan Dan Peralatan KandangDokumen14 halamanPerencanaan Bangunan Dan Peralatan KandangErlangga Ghiry100% (1)
- OBAT - OBATAN KambingDokumen18 halamanOBAT - OBATAN KambingMbak Nike100% (1)
- Budidaya Lele Sistem BosterDokumen31 halamanBudidaya Lele Sistem Bosterarthur36Belum ada peringkat
- Serius Dengan EntokDokumen12 halamanSerius Dengan Entokpaijo klimpritBelum ada peringkat
- Ikan LeleDokumen31 halamanIkan LeleDeddy SernBelum ada peringkat
- Analisis Tataniaga Telur Ayam KampungDokumen139 halamanAnalisis Tataniaga Telur Ayam KampungDiah Dwi Swastiati50% (2)
- Laporan Praktikum Non RuminansiaDokumen16 halamanLaporan Praktikum Non RuminansiaFitriani Etho AntyBelum ada peringkat
- SOP Pembibitan Kacangan Kelapa SawitDokumen6 halamanSOP Pembibitan Kacangan Kelapa SawitSaman KurniawanBelum ada peringkat
- Pupuk Organik Dan HayatiDokumen14 halamanPupuk Organik Dan HayatiPuguh IndarsoBelum ada peringkat
- Jenis-Jenis Kambing BudidayaDokumen4 halamanJenis-Jenis Kambing Budidayalalu ahmad faisalBelum ada peringkat
- Cara Membuat Ikan Nila Jantan Semua DenganDokumen13 halamanCara Membuat Ikan Nila Jantan Semua DenganVirdha Melinda Amalia100% (1)
- Makalah Ayam KetawaDokumen8 halamanMakalah Ayam KetawaWarnet DInetBelum ada peringkat
- Buku Pupuk Organik GranulDokumen68 halamanBuku Pupuk Organik GranulIsroi.com100% (10)
- Budidaya Grass CarpDokumen28 halamanBudidaya Grass CarpkhairuzzuhdiBelum ada peringkat
- Makalah Bebek PedagingDokumen68 halamanMakalah Bebek PedagingRani RulistianiBelum ada peringkat
- Proposal PKL CacingDokumen20 halamanProposal PKL CacingNadiaPanggitawatiBelum ada peringkat
- AuraDokumen36 halamanAuraAuraa HuaidaaBelum ada peringkat
- Laporan Update Fix KoreksiDokumen31 halamanLaporan Update Fix KoreksiIsya Andar SyamdaniBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Alim Amry Nusantara (I1a2 16 070)Dokumen16 halamanTugas Makalah Alim Amry Nusantara (I1a2 16 070)Ainun SalsabilaBelum ada peringkat
- Tugas Laporan PraktikumDokumen17 halamanTugas Laporan PraktikumAinun SalsabilaBelum ada peringkat
- Laporan PraktikumDokumen13 halamanLaporan Praktikumnova prityBelum ada peringkat
- Rizal Aprilio - PROPOSAL PKL PT. KMLDokumen9 halamanRizal Aprilio - PROPOSAL PKL PT. KMLRizal AprilioBelum ada peringkat
- Hepi 22Dokumen9 halamanHepi 22Leoni hayu sabrina putriBelum ada peringkat
- 302 2116 1 PBDokumen10 halaman302 2116 1 PBAndrianiBelum ada peringkat
- Sinopsis Praktek Lapang (RIZKI NOVITA SARI)Dokumen6 halamanSinopsis Praktek Lapang (RIZKI NOVITA SARI)Afni BerutuBelum ada peringkat
- Salsabila A'Zahra - Review Jurnal - MarikulturDokumen6 halamanSalsabila A'Zahra - Review Jurnal - Marikulturazahrasalsa123Belum ada peringkat
- Bab 1Dokumen5 halamanBab 1Mhd Adi Firmansyah DaulayBelum ada peringkat
- 05 LAPORAN AKHIR UPR Ikan CompressedDokumen75 halaman05 LAPORAN AKHIR UPR Ikan CompressedWahyu RomadhanBelum ada peringkat
- Laporan PKL Dwiko HB 230210080058 FixDokumen38 halamanLaporan PKL Dwiko HB 230210080058 Fixdwiko100% (1)
- Makalah Kepiting BakauDokumen40 halamanMakalah Kepiting BakaudhaviraBelum ada peringkat
- Aktivitas Harian Owa Jawa Di PPKA Bodogol TNGGP, Jawa Barat - Nina Deslina - 1304617059 (Revisi)Dokumen18 halamanAktivitas Harian Owa Jawa Di PPKA Bodogol TNGGP, Jawa Barat - Nina Deslina - 1304617059 (Revisi)Nina DeslinaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Teknologi Budidaya Perairan LautDokumen39 halamanLaporan Praktikum Teknologi Budidaya Perairan LautFarid100% (1)
- Model Pengembangan Tambak Udang Secara BerkelanjutanDokumen27 halamanModel Pengembangan Tambak Udang Secara BerkelanjutanUrif Syarifudin100% (1)
- Laporan Pengantar Ekonomi PerikananDokumen15 halamanLaporan Pengantar Ekonomi Perikananlenda mariellaBelum ada peringkat
- MAGANG PresentationDokumen20 halamanMAGANG Presentationnova iman sariBelum ada peringkat