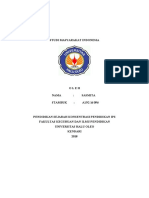Sejarah Lokal Sultra Yuningsih
Diunggah oleh
Yuningsih Yuni0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
28 tayangan14 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
28 tayangan14 halamanSejarah Lokal Sultra Yuningsih
Diunggah oleh
Yuningsih YuniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 14
Tugas
Sejarah Lokal
”Sejarah Lokal Sultra Kesultan Buton”
OLEH
YUNINGSIH
A1N1 17 112
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH PEMINATAN PENDIDIKAN SOSIOLGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2020
Sejarah Lokal Sultra : Kesultanan Buton
A. Persekutuan Lima Kerajaan
Sebelum terbentuknya Kerajaan Buton, wilayah Sulawesi Tenggara bagian kepulauan
terdiri atas ratusan kerajaan kecil yang dinamakan ‘kedatuan’. Kerajaan-kerajaan kecil ini
mempunyai pemerintahan sendiri dengan sistem dan struktur yang berbeda-beda, wilayah dan
komunitasnya terbatas, biasanya pada setiap pulau, dengan istilah atau sebutan pemimpin mereka
yang berbeda-beda pula. Di antara kerajaan-kerajaan kecil itu kemudian berkembang menjadi
lebih besar dan berpengaruh bahkan kemudian membentuk satu kerajaan yang lebih kuat. Di
antaranya adalah Kerajaan Muna, Kerajaan Tiworo, Kerajaan Lipu (Kalingsusu), Kerajaan
Kahedupa, Kerajaan Kamaru, Kerajaan Tobe-Tobe, Kerajaan Kotua, dan masih banyak lagi. Di
daratan Buton empat kerajaan kecil berkoalisi membentuk satu kerajaan baru yaitu Kerajaan
Wolio yang dalam perkembangannya kemudian bernama Kerajaan Buton selanjutnya berubah
menjadi Kesultanan Buton.
Kerajaan Wolio menjalin kerjasama dengan kerajaan Muna, Tiworo, Lipu (Kalingsusu),
dan Kehedupa. Kerjasama kemudian dikukuhkan dalam bentuk aliansi (persekutuan) lima
kerajaan melalui konvensi Kapeo-peo pada masa pemerintahan La Kilaponto (Sultan Kaimuddin
I alias Murhum) sebagai raja Wolio ke-6. Persekutuan tersebut dibangun atas
prinsip Soilaompo (rajutan sero) dan Torumbalili (mahkota bergilir). Pada masa pemerintahan
Dayanu Iksanuddin (La Elangi) sebagai Sultan Buton ke-4, kedua prinsip tersebut mengalami
transformasi menjadi konsep Barata dan Kamboru-mboru Talupalena. Uraiannya lihat halaman
5.
B. Kerajaan Wolio : Cikal Bakal Kerajaan Buton
Pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14, tiba di Buton rombongan dari Semenanjung
Johor (Malaka). Para pemuka di antara mereka adalah Panjonga (Sipanjonga), Tamanajo
(Sitamanajo), Jawangkati (Sijawangkati), dan Malui (Simalui). Keempat orang pemuka inilah
yang dinamakan Mia Patamiana (bahasa Wolio, artinya empat orang). Mereka mendarat di dua
tempat. Rombongan Panjonga dan Malui mendarat di Kalampa (sekitar perkampungan Lipu di
Katobengke sekarang) dan rombongan kedua mendarat di Walalogusi sekitar Kapuntori
sekarang. Kedatangan mereka nampaknya bukan sebagai pedagang melainkan seperti seorang
raja dan rakyatnya. Mereka berpakaian serba indah dengan mengibarkan sebuah bendera yang
dinamakan Sula. Mereka kemudian bersatu di Kalampa, selanjutnya membuka perkampungan
baru di sebuah bukit (Lelemangura) yang agak jauh dari pesisir pantai untuk menghindari
gangguan bajak laut (Tobelo dan Mangindanao). Tempat ini kemudian dinamakan Wolio, dari
kata welia artinya membabat, maksudnya membabat atau menebang hutan belukar untuk
membangun perkampungan.
Ketika berada di Buton, ada dua kerajaan kecil yang telah ada di Buton yaitu Kerajaan
Tobe-Tobe dengan rajanya bernama Dungkucangia dan Kerajaan Kamaru dengan rajanya
Baubesi. Para pendatang itu menjalin kerjasama yang baik dengan kedua kerajaan tersebut.
Dalam perkembangan selanjutnya, seirama dengan pertambahan jumlah penduduk, terbentuklah
perkampungan baru yaitu Gundu-Gundu dan Barangkatopa. Kampung (limbo) Gundu-Gundu
dikepalai oleh Jawangkati dan Barangkatopa oleh Tamanajo, masing-masing dengan
gelar bonto (semacam kepala kampung, raja kecil). Keduanya dilantik di atas sebuah batu yang
dinamakan ‘batu Gundu-Gundu’ untuk pelantikan Bonto Gundu-Gundu dan ‘batu Barangkatopa’
untuk pelantikan Bonto Barangkatopa. Pelantikan di atas batu ini menjadi tradisi pelantikan raja-
raja atau sultan-sultan Buton selanjutnya. Pelantikan dua orang bonto turut dihadiri oleh Raja
Tobe-Tobe, Dungkucangia. Dengan Kerajaan Kamaru dilakukan politik perkawinan. Putra
Panjonga bernama Betoambari dikawinkan dengan putri Raja Kamaru bernama Waguntu dan
melahirkan seorang putra bernama Sangariarana. Akibatnya dua kerajaan (Tobe-Tobe dan
Kamaru) kemudian menyatakan diri bergabung dengan Wolio.
Dalam perkembangan selanjutnya, terbentuk lagi kampung baru, yaitu kampung Peropa
dan Baluwu, sehingga Wolio menjadi suatu pemukiman yang ramai, layaknya suatu kota.
Betoambari pun kemudian dilantik menjadi Bonto Peropa dan Sangariarana sebagai Bonto
Baluwu. Maka genaplah empat orang bonto dalam pemukiman Wolio (sekarang Keraton Buton).
Empat orang bonto itu dinakakan Pata Limbona (empat orang kepala kampung, limbo artinya
kampong; pata artinya empat). Wolio berkembang terus, terbentuk lagi kampung-kampung baru
(yaitu kampung Gama, Wandailolo, Rakia, dan Siompu) yang masing-masing dikepalai oleh
seorang bonto. Pada masa Raja Buton III, Bataraguru, perkampungan yang ada di Wolio
bertambah sembilan dengan terbentuknya kampung baru yakni Melai. Kesembilan kepala
kampung dari masing-masing limbo tersebut dinamakan Sio Limbona (sio artinya sembilan)
yang kelak menjadi semacam Dewan Kerajaan Buton (Dewan Siolimbona) yang tugas utamanya
mengangkat dan memberhentikan sultan, mengawasi jalannya pemerintahan, menegakan adat.
Raja Buton I adalah Wakaka, seorang perempuan. Ia dilantik oleh Dewan Pata
Limbona (Gundu-Gundu, Barangkatopa, Tobe-Tobe, dan Kamaru) di atas sebuah batu ponu atau
batu popaua. Wakaka kawin dengan Sibatara, seorang bangsawan dari Majapahit. Ratu Wakaka
dilengkapi perangkat kerajaan, yaitu sepuluh orang anak laki-laki keturunan para bonto yang
dinamakan Belobaruga untuk melayani peralatan kebesaran raja, sepuluh orang anak perempuan
asal keturunan kaum rendahan, dan 60 orang laki-laki perkasa yang bertugas sebagai pengawal
istana. Dasar pemerintahannya adalah “poromu yinda sangu, poga yinda kolota”, artinya bersatu
tidak menyatu, bercerati tidak berantara. Falsafah hidupnya adalah pobinci-binciki kuli (saling
cubit kulit) yang dijabarkan ke dalam empat nilai, yaitu; poma-masiaka (saling
menyayangi), poangka-angkata (saling mengangkat), popia-piara (saling memelihara), pomae-
maeka (saling menakuti). Wakaka diganti oleh putri satu-satunya bernama Bulawambona.
C. Masuknya Agama Islam Di Buton
Raja Buton VI bernama La Kilaponto, putra Raja Muna, keturunan raja-raja Buton. Di
kalangan masyarakat Konawe ia dikenal dengan nama Haluoleo (Bahasa Tolaki-Konawe,
artinya; halu = delapan, oleo = hari) karena mempunyai hubungan darah dengan raja-raja
Konawe. Di Buton sendiri lebih populer dengan nama Murhum. Ia dinobatkan menjadi Raja
Buton karena keberhasilannya memimpin pertempuran melawan bajak laut Tobelo yang
dipimpin oleh La Bolontio, seorang “jendral” bermata satu, panglima perang Tobelo yang
berkedudukan di Banggai.
Agama Islam pertama kali masuk di Buton (bagian Timur) pada tahun 1412 oleh seorang
ulama Patani (mungkin Syekh Muhammad Salim yang diabadikan namanya menjadi Lasalimu di
pantai Timur Pulau Buton) melalui jaringan pelayaran niaga. Di Burangasi Islam masuk pada
tahun 1526 oleh Abdul Wahid. Di Wangi-Wangi tahun 1234 oleh pedagang Persia bernama A.
Muhammad. Tahun 1260 raja pertama Kahedupa bergelar Muhammad Ndangi Tongka Allamu.
Kita ketahui bahwa kawasan Buton Timur dan Selatan masuk dalam spices road (jalur rempah-
rempah, jalur laut) sehingga dengan mudah Islam masuk melalui jalur perdagangan. Ada
pendapat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Raja Buton V, bernama Mulae, sudah
menganut agama Islam. Namun Islam diterima secara resmi sebagai agama kerajaan nanti pada
saat pelantikan raja menjadi sultan tahun 948 H atau 1540 M. Pada tahun itu Raja Buton VI, La
Kilaponto, menyatakan diri masuk Islam. Ia juga menyatakan bahwa Islam sebagai “agama
negara” yang wajib dianut oleh seluruh masyarakat Buton. Ia dinobatkan sebagai Sultan Buton I
oleh Syekh Abdul Wahid bin Sulaiman sebagai pembawa agama Islam pertama di Keraton
Buton. Ketika dinobatkan sebagai Sultan Buton I, La Kilaponto oleh Syekh Abdul Wahid, ia
mencetuskan falsafah perjuangan Islam yang berbunyi :
Bolimo arataa somanamo karo,
Bolimo karo somanamo lipu,
Bolimo Lipu somanamo agama.
Artinya ;
Tiada perlu harta asalkan diri selamat,
Tiada perlu diri asalkan negeri selamat,
Tiada perlu negeri asalkan agama selamat.
Sumber lain menyebutkan ;
Yinda-yindamo arata somana karo,
Yinda-yindamo karo somana lipu,
Yinda-yindamo lipu somana sara,
Yinda-yindamo sara somana agama.
Artinya ;
Korbankan harta demi keselamatan diri,
Korbankan diri demi keselamatan negara,
Korbankan negara demi keselamatan pemerintah,
Korbankan pemerintah demi keselamatan agama (Islam).
Sejak itu Islam mulai disebarluaskan ke seluruh penjuru wilayah Kesultanan Buton
melalui berbagai jalur, terutama jalur perkawinan.
Dalam rangka penyebaran Islam, La Kilaponto semakin mempererat hubungan dengan
kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya seperti Muna, Tiworo, Kalingsusu (Kulisusu), dan Kaedupa
(Kaledupa). Bahkan berusaha mengintegrasikan kerajaan-kerajaan kecil tersebut ke dalam
wilayah Kesultanan Buton, integrasi mana kemudian dikukuhkan oleh Sultan Buton IV, Dayanu
Ikhsanuddin (La Elangi) dalam Martabat Tujuh (Konstitusi Kesultanan Buton) pada awal abad
ke-17. Kerajaan-kerajaan yang diintegrasikan itu adalah Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan
Kaedupa dengan status barata (daerah yang memiliki hak otonom).
Islam yang masuk di Buton pada umumnya bercorak tasauf. Hal ini tercermin dalam
pembukaan Martabat Tujuh yang berbunyi “man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu”
artinya barangsiapa yang mengenal keadaan dirinya yang sejati, tentunya ia mengenal keadaan
Tuhannya yang kekal. Tokoh-tokoh Islam yang berjasa besar dalam pengembangan Islam
(terutama tasauf) di Buton adalah Syekh Abdul Wahid, Syarif Muhammad, Sayyid Alawi,
Sayyid Raba, Haji Ipada, Muhammad Idrus Kaimuddin, Haji Abdul Gani (Kenepulu Bula), Haji
Abdul Hadi, dan Muhammad Salih. Lima tokoh yang disebutkan terakhir adalah putra asli Buton
yang banyak melahirkan tulisan-tulisan tentang Islam (tasauf), misalnya Yajonga Yinda
Malusa (artinya “pakaian yang tidak luntur”) dan Kalipopo Mainawa (artinya ”bintang terang”)
ditulis oleh Kanepulu Bula, Jauharana Manikamu ditulis oleh Muhammad
Idrus, Kaokabi (artinya “bintang”) oleh Haji Abdul Hadi, Ibtida Sair Allah ila Intiha Sirr
Allah oleh Muhammad Salih. Masih banyak lagi tulisan-tulisannya yang lain.
D. Puncak Kemajuan Kesultanan Buton
Buton mengalami kemajuan (kejayaan) pada masa pemerintahan Sultan IV (1578-1615),
La Elangi, dengan gelar Dayanu Ikhsanuddin. Namanya sangat populer karena prestasi
pemerintahannya, sehingga diabadikan ke dalam nama Universitas Dayanu Ikhsanuddin di
Baubau sekarang.
Pada masa pemerintahannya, ia menyusun suatu Undang-Undang Dasar yang
dinamakan Martabat Tujuh (artinya tujuh martabat atau tingkatan) yang diumumkan pada tahun
1610. Dalam penyusunannya, ia mendapat bantuan dan nasehat dari Syarif Muhammad, seorang
berkebangsaan Arab, pembawa tarekat Qadiriyyah (tarekat Syekh Abdul Qadir Jailani) dan
ajaran insan kamil di Buton, pengikut ajaran Hamzah Fansuri dan Syamsuddin As Sumatrani
yang membawa ajaran wujudiyyah (wahdah al wujud). Ajaran ini bersumber dari Ibn Arabi yang
disebarkan ke Indonesia oleh Muhammad Ibn Fadulullah al Burhanpuri. Tujuh martabat itu
adalah martabat la ta ayyun atau martabat ahadiyyah, martabat at-ta ayyun al awwal atau
martabat al wahdah, martabat at-ta ayyun as-sani atau martabat al wahidiyyah, maratabt alam
arwah, martabat alam al missal, martabat alam al ajsam, martabat al insan.
Martabat Tujuh berisi tentang ideologi pemerintahan, syarat-syarat pemerin-tahan,
struktur pemerintahan dan tugas masing-masing, pembagian wilayah pemerintahan, dan
kedudukan Barata Patapalena (Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaedupa). Kata pembukaan
Martabat Tujuh berbunyi “man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu”, artinya barang siapa yang
mengenal keadaan dirinya yang sejati, tentunya ia menganal keadaan Tuhannya yang kekal.
Idiologi pemerintahannya adalah pobinci-binciki kuli (artinya saling mencubit kulit), dijabarkan
ke dalam empat falsafah yakni pomae-maeka, popia-piara, pomaa-masiaka, dan poangkaa-
angkataka.
Pada masa pemerintahan La Elangi, demokrasi mulai ditumbuhkan. Sistem pemilihan
Sultan dan jabatan-jabatan tinggi lainnya mulai dilakukan meskipun masih terbatas pada kaum
bangsawan (kaomu). Kaum bangsawan dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu
bangsawan Tanailandu dari La Elangi (ketika itu menjabat Sultan) dan keturunannya,
bangsaawan Kumbewaha dari La Singga (ketika itu menjabat Sapati) dan keturunannya, dan
bangsawan Tapi-Tapi dari La Bula (ketika itu menjabat Kenepulu) dan keturunannya. Ketiga
golongan ini dalam adat Buton dinamakan Kamborumboru Talu Palena (tiga golongan
bangsawan).
Sultan mengintegrasikan Muna, Tiworo, Kalingsusu, dan Kaedupa sebagai bagian dari
Kesultanan Buton dengan status sebagai barata (semacam negara bagian yang mempunyai hak
otonom). Keempatnya dinamakan Barata Patapalena (empat bagian barata). Penyatuan keempat
kerajaan ini ke dalam Buton karena faktor kepentingan keamanan bersama. Baik Buton maupun
keempat kerajaan kecil tersebut sama-sama menginginkan terciptanya keamanan bersama,
terhindar dari ancaman bajak laut (Tobelo dan Mangindanao) dan dominasi Kerajaan Gowa,
Ternate, dan Belanda. Karena itu Buton mengumpamakan negerinya sebagai perahu cadik yang
memiliki empat penguat, dua di sisi kiri dan dua di sisi kanan. Sebagaimana diketahui bahwa
perahu cadik tidak mudah terbalik sekaligus dihantam angin dan badai besar karena ditopang
oleh cadiknya. Yang dimaksud dengan “empat penguat”, yaitu Muna, Tiworo, Kulisusu, dan
Kaedupa. Keempat kerajaan inilah yang terus-menrus menopang Kesultanan Buton selama
ratusan tahun dari berbagai ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam.
Sultan juga menciptakan mata uang yang dinamakan kampua sebagai alat tukar yang sah.
Nilai nominalnya tergantung ukurannya, semakin besar ukurannya semakin tinggi nilainya.
Mulai merintis pembangunan benteng Kraton Buton, tapi penyelesaiannya pada masa
pemerintahan Sultan Buton VI, La Buke (Gafurul Waduudu). Di masa pemerintahannya untuk
pertamakali mulai masuk pengaruh Belanda di Buton. Pada tanggal 5 Januari 1613,
ditandatangani perjanjian antara Komandeur Appolonius Schet atas nama VOC dengan Sultan
Dayanu Ikhsanuddin. Perjanjian ini dalam sejarah Buton dikenal dengan istilah janji baana (janji
pertama).
E. Sistem Dan Struktur Pemerintahan Kesultanan Buton Serta Aktivitas Menonjol
Sistem pemerintahan Kesultanan Buton, terutama setelah masuknya agama Islam, adalah
system pemerintahan monarkhi konstitusional bercorak Islam dan demokrasi.
Dikatakan monarkhi konstitusional karena pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja (sultan)
secara turun-temurun terbatas pada golongan bangsawan (karena itu disebut monarkhi) tetapi
dilakukan secara demokrasi (pemilihan dari tiga subgolongan bangsawan, yakni bangsawan
Tanailandu, Tapi-Tapi, dan Kumbewaha), dengan masa jabatan tidak terbatas. Pemerintahan
berdasarkan konstitusi (karena itu disebut konstitusional). UU yang dijalankan didasarkan pada
ketentuan agama (menegakan syariat Islam) sehingga raja yang berkuasa diberi gelar sultan.
Rakyatnya diwajibkan beragama Islam sehingga negaranya dinamakan kesultanan (khilafah).
Kesultanan Buton dipimpin oleh seorang sultan yang mereka anggap sebagai wakil
Tuhan di muka bumi (khalifah fil ard). Ia adalah pemimpin tertinggi, termasuk dalam bidang
keagamaan. Karena itu seorang sultan harus suci dan bersih. Urusan agama sehari-hari ditangani
khusus oleh suatu lembaga yang dinamakan Syara Agama (pemerintah agama) yang
bertanggungjawab langsung kepada sultan. Pelaksanaan pemerintahan diawasi oleh suatu
lembaga legislatif yang mereka namakan Sio Limbona (Dewan Sembilan). Selain itu terdapat
suatu Dewan Spritual yang dinamakan Bhisa Patamiana yang bertugas menangani masalah-
masalah spiritual, semacam “supranatural”. Tugas pemerintahan sehari-hari dipercayakan kepada
seorang sapati (semacam Perdana Menteri) dibantu oleh seorang sekretaris yang mereka
namakan kenepulu. Urusan pertahanan dan keamanan dipimpin oleh dua orang panglima perang
yang dinamakan kapitalao, yaitu Kapitalao Matanaeo (panglima perang Buton Bagian
Timur, matanaeo artinya tempat terbitnya matahari yaitu sebelah timur) dan Kapitalao
Sukanaeo (panglima perang Buton Bagian Barat, sukanaeo artinya tempat terbenamnya
matahari yaitu sebelah barat). Wilayahnya dibagi menjadi 72 kadie (daerah) yang dibagi ke
dalam dua bagian. Pada tahun 1838 dibentuk 18 kadie baru sehingga menjadi 90 kadie. Masing-
masing bagian dipimpin oleh seorang Bonto Ogena (Kepala Daerah Besar), yaitu Bonto Ogena
Matanaeo (untuk Buton Timur, didampingi oleh Kapitalao Matanaeo) dan Bonto Ogena
Sukanaeo (untuk Buton Barat didampingi oleh Kapitalao Sukanaeo). Urusan pajak ditangani oleh
seorang Tunggu Weti (penarik pajak). Yang menangani masalah pelabuhan adalah
seorang sabandara (sahbandar).
Di luar wilayah kadie, terdapat empat daerah otonom (semacam negara bagian) yang
keempatnya mereka namakan Barata Patapalena (barata empat), yaitu Muna, Tiworo,
Kalingsusu, dan Kaedupa. Dikatakan sebagai daerah otonom karena memiliki Undang-Undang
tersendiri yang dinamakan Syarana Barata dengan struktur pemerintahan masing-masing yang
berbeda antara barata yang satu dengan barata lainnya. Masing-masing barata dipimpin oleh
seorang “raja kecil” yang dinamakan lakina (Lakina Muna, Lakina Tiworo, Lakina Kalingsusu,
dan Lakina Kaedupa) yang dipilih oleh Syara Barata atas persetujuan Sultan Buton. Fungsi
utama barata adalah menjaga pertahanan dan keamanan bersama dari ancaman yang datang dari
luar.
Aktivitas masyarakat yang paling menonjol adalah di bidang perdagangan maritim
(pelayaran niaga). Orang Buton, menurut Fox, masuk ke dalam tiga suku yang paling ekspansif
dan dominan dalam kegiatan pelayaran, terutama di Nusantara Bagian Timur, yaitu Bugis-
Buton-Makassar (disingkat BBM). Orang Buton, menurut Southon dan Hughes, masuk ke dalam
enam suku maritim di Indonesia, yaitu Bajau, Makassar, Bugis, Buton, Mandar, dan Madura.
Perahunya dinamakan lambo atau bhangka. Mereka berlayar ke seantero Nusantara, bahkan
sampai ke Malaysia, Singapura, Filipina Selatan, Australia Utara, dan Kepulauan Palau di Lautan
Teduh. Bahkan ada yang sampai ke India. Mereka menekuni bidang pelayaran karena keadaan
alamnya yang tandus, terletak di antara Laut Banda dan Laut Flores, penghubung ekonomi antara
Nusantara Bagian Timur terutama Maluku dan Irian sebagai penghasil rempah-rempah, kopra,
dan hasil bumi lainnya dengan Nusantara Bagian Barat terutama Jawa tempat memasarkan hasil
bumi dan produksi barang kebutuhan rumah tangga yang laku di Nusantara Bagian Timur.
F. Pengaruh Belanda Dan Berakhirnya Kesultanan Buton
Pertama kali orang Belanda menginjakan kaki di Buton pada awal tahun 1613. Pada
tanggal 5 Januari 1613, ditandatangani perjanjian antara Komandeur Appolonius Schet atas nama
VOC dengan Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Perjanjian ini biasa disebut “Kontrak Perjanjian Shcet-
Elangi” dan dalam sejarah Buton dikenal dengan istilah janji baana (janji pertama), karena untuk
pertamakali Buton menjalin hubungan dengan Belanda, terutama kerjasama perdagangan dan
keamanan. Kerjasama ini menjadi cikal bakal monopoli perdagangan dan awal penjajahan
Belanda di Buton karena kemudian ditindaklanjuti dengan kontrak perjanjian berikutnya yang
semakin lama semakin merugikan Buton. Pada tanggal 31 Januari 1667, di atas
kapal Thertolen sebuah kapal pemburu milik Kompeni Belanda, Speelman dan Sultan La
Simbata (Sultan Buton X), menutup perjanjian, yang pada pokoknya di seluruh Kepulauan
Tukang Besi terutama di Kaledupa dan Wangi-Wangi, dinyatakan semua pohon cengkeh dan
pala harus ditebang dan sekaligus dimusnahkan di bawah pengawasan orang-orang Kompeni.
Hak ekstirpasi (extirpatie) yang dimiliki oleh VOC ini dikukuhkan pada tanggal 25 Juni 1667.
Atas penebangan pohon cengkeh dan pala ini, Kompeni membayar kepada Buton setiap
tahun 100 ringgit atau seratus rijksdaalders sebagai pengganti kerugian (recognitie-penning).
Perjanjian Speelman-Simbata tersebut dikenal dalam sejarah Buton dengan istilah janji
limaanguna, artinya perjanjian yang kelima. Isi perjanjian tersebut sesungguhnya merupakan
intervensi atas kedaulatan Buton, terutama dalam hak ekstirpasi, yakni hak VOC untuk
melakukan penebangan pohon rempah-rempah di Kepulauan Tukang Besi, terutama Kaledupa,
Wanci-Wanci, dan Binongko. Meskipun tidak sebanyak produksi di kepulauan Maluku Tengah,
pohon cengkeh di Kepulauan Tukang Besi, terutama Wanci dan Kaledupa merupakan ancaman
bagi monopoli VOC .
Selanjutnya pada tanggal 25 Juni 1667 diadakan lagi perjanjian Speelman-Simbata di atas
kapal Thoff van Zeeland. Perjanjian ini sesungguhnya merupakan pengukuhan dan penegasan
kembali dari perjanjian sebelumnya. Dua dari 13 pasal isi perjanjian ini (pasal 1 dan pasal 2)
adalah (1) Semua pohon cengkeh dan pala yang terdapat di Pulau-Pulau Tukang Besi harus
ditebang dan dimusnahkan dimana Kompeni membayar kepada Buton tiap tahun 100 ringgit
sebagai pengganti kerugian dan akan berlaku pada akhir tahun 1667; (2) Juga di tempat-tempat
lain di dalam kekuasaan Raja Buton, yang sekarang ataupun kemudian, bila ditemukan pohon
cengkeh dan pala boleh ditebang.
Ganti rugi penebangan cengkeh dan pala tersebut kemudian diatur sebagai berikut : 100
real untuk kerajaan, 50 real isi meja (antona meja) untuk pribadi Sapati Baluwu (dinyatakan
dalam keputusan tersendiri), jurubasa dan tau-tau mengambil 10 real dan dari uang meja lima
real seluruhnya 15 real dibagi dua masing-masing tujuh boka dan dua suku. Lebihnya 90 real
masih kurang lagi karena pengeluaran untuk kompanyia yaitu anggota kometer yang keempat
yang kembali satu boka, jurubasa di Ujung Pandang satu boka, opasi satu boka, yang membawa
surat dua suku, dan yang memegang uang dua suku.
Pada tanggal 8 April 1906 ditatandatangani perjanjian antara Sultan Buton ke-33,
Muhammad Asyikin, dengan Residen Belanda bernama Brugman, sehingga lebih dikenal dengan
sebutan Perjanjian Asyikin-Brugman. Perjanjian atau Korte Verklaring (perjanjian pendek) ini
adalah strategi politik Belanda untuk memperkokoh cengkeraman kekuasaannya di Buton.
Perjanjian ini menandai dualisme pemerintahan di Kesultanan Buton. Di satu pihak Buton tetap
diperbolehkan menjalankan pemerintahannya sendiri seperti keadaan sebelumnya, di pihak lain
harus mengakui kedaulatan Belanda atas daerahnya. Sejak itu Kesultanan Buton menjalankan
sistem pemerintahan sendiri yang dinamakan Zelfbesturende Landschappen di bawah lindungan
dan pengawasan pemerintah Hindia Belanda.
Pemerintah Hindia Belanda berangsur-angsur menancapkan kekuasaannya melalui
berbagai macam peraturan yang semakin mempersempit kekuasaan Sultan Buton dan aparatnya
ke bawah hingga dibentuknya pemerintahan Afdeling Buton en Laiwui pada tanggal 24 Februari
1940 yang salah satu daerah bawahannya adalah Onderafdeling Buton dan Pulau-Pulau Tukang
Besi yang dikepalai oleh seorang Controleur Belanda, struktur mana tidak berubah hingga masa
pendudukan Jepang (1942-1945). Sesuai perjanjian Asykin-Brugman, maka sejak tahun 1910,
wilayah Kesultanan Buton telah direstrukturisasi ke dalam sistem district, menjadi tidak kurang
dari 22 distrik. Masing-masing distrik membawahi beberapa onderdistrict. Beberapa jabatan
penting mulai ditiadakan seperti Raja Sorawolio, Raja Badia, Kapitalao Matanaeo dan Sukanaeo,
Kapita dan Sabandara, sistem barata sejak itu mulai ditiadakan. Semua limbo (kadie) yang
berada berubah status menjadi onderdistrik.
Pada masa pendudukan Jepang, sistem pemerintahan dualisme Belanda tetap
dipertahankan. Pembagian wilayah bawahan tidak berubah, yang diubah hanya nama kesatuan
wilayah dan pejabat pemerintahan sipil. Afdeling menjadi Ken dengan
kepala Kenriken. Onderafdeling menjadi Bunken dengan kepala Bun Kenriken. District
/Onderdistrict menjadi Gun dengan kepala Gunco. Kampung menjadi Son yang dikepala
oleh Sonco. Jabatan Kenriken dan Bun Kenriken dijabat oleh orang Jepang sedangkan
jabatan Gunco dan Sonco oleh orang Indonesia. Istilah Jepang kemudian ditiadakan bersamaan
dengan berakhirnya masa pendudukan. Ketika memasuki zaman kemerdekaan, pihak
pemerintahan Swapraja Buton berupaya memulihkan kembali jabatan-jabatan penting yang
dibekukan sejak tahun 1910, akan tetapi kembali ditiadakan oleh pemerintah pada tanggal 15
Januari 1951 melalui kebijakan demokrasi sering hingga sultan tinggal seorang diri didampingi
oleh empat orang pembantu sampai tahun 1960 ketika dibentuk empat Daerah Tingkat II
(Kabupaten) di Sulawesi Tenggara. Empat kabupaten tersebut adalah Kabupaten Buton
ibukotanya Bau-Bau, Kabupaten Muna ibukotanya Raha, Kabupaten Kendari ibukotanya
Kendari dan Kabupaten Kolaka ibukotanya Kolaka. Pada tahun 1964 dibentuk Provinsi Sulawesi
Tenggara ibukotanya Kendari yang wilayahnya mencakup empat kabupaten tersebut (Buton,
Muna, Kendari, dan Kolaka).
G. Reaksi Masyarakat Atas Dominasi Belanda
Kontrak perjanjian Belanda-Buton, menimbulkan dua keadaan. Di satu pihak kekuasaan
Belanda (VOC dan Hindia Belanda) atas Buton semakin lama semakin kokoh, di pihak lain
Buton semakin lama semakin tidak berdaya, semakin tertindas dan melarat. Penguasa Buton
semakin lama semakin menjadi alat kekuasaan Belanda melalui berbagai ikatan kontrak
perjanjian, sementara rakyat Buton semakin miskin dan menderita. Akibatnya timbul reaksi
masyarakat baik secara individual maupun berkolompok atau gabungan keduanya. Reaksi
masyarakat timbul dalam dua bentuk perlawanan, fisik dan nonfisik, di seluruh wilayah
kekuasaan Buton termasuk di empat Barata. Di Buton ada nama La Walanda karena
kegigihannya melawan politik devide et impera Belanda ia tewas dipenggal kepalanya oleh
Steven Barentzoon (seorang pejabat Belanda di Buton) pada tahun 1644 pada saat pembuatan
benteng Keraton Buton.
Bahwa distribusi uang 100 ringgit ganti rugi penebangan pohon cengkeh dan pala yang
ada di Wangi-Wangi dan Kaledupa sebagian besar hanya dinikmati oleh pejabat tinggi
Kesultanan Buton. Akibatnya timbul reaksi keras dari masyarakat di ke dua pulau tersebut.
Mereka sama sekali tidak memberikan dukungan terutama terhadap empat orang anggota
detasemen pengawas penebangan pohon cengkeh dan pala yang ditempatkan di Kepulauan
Tukang Besi, mereka tidak memberikan bantuan tumpangan dari satu pulau ke pulau lainnya.
Fakta sukses VOC di satu pihak berakibat pada munculnya masalah ekonomi, yang dihadapi
rakyat di pihak lain. Hal itu dapat dilihat dari berbagai cara yang dilakukan penduduk untuk
menghindari ekstirpasi. Cara-cara tertentu misalnya dengan tindakan “mengelabui” yang sering
kali dilakukan untuk menghindari ekstirpasi. Dalam kegiatan ekstirpasinya, di Kepulauan
Tukang Besi, tiga orang serdadu VOC mengeluh karena tidak mendapat bantuan penuh dari
penduduk setempat.
Tokoh yang paling menentang perjanjian Speelman-Simbata karena dirasakan langsung
oleh rakyatnya adalah Kapita Waloindi di Binongko. Ia memimpin gerakan perlawanan rakyat
melawan Belanda jelang akhir abad ke-17 hingga akhir hayatnya. Selama empat kali ia
bertempur melawan Belanda hingga ia tewas pada tahun 1680. Sisa-sisa pasukannya sebagian
melarikan diri ke Ambon, di antara mereka ada yang diduga sebagai Patimura. Di Muna ada
tokoh bernama La Ode Ngkadiri (Sangia Kaindea) terpaksa diasingkan ke Ternate pada tahun
1667 karena menentang perjanjian Speelman-Simbata. Perjuangannya dilanjutkan oleh
permaisurinya bernama Wa Ode Wakelu hingga tahun 1668. Di Buton ada nama La Karambau
alias Himayatuddin Muhammad Saidi alis Oputa Yi Koo. Selama dua kali menjabat Sultan
Buton (ke-20 dan ke-23). Ia memimpin gerakan perlawanan rakyat terhadap Belanda (1751-
1763). Karena kuatir akan merugikan Buton, maka ia dipecat dari jabatannya sebagai Sultan
Buton oleh Syara.
Di Kulisusu terdapat seorang tokoh pejuang bernama La Ode Gure alias Raja Jin yang
berhasil menenggelamkan sebuah kapal Belanda bernama Bark de Noteboom. Akibatnya Buton
terkena sanksi harus menyerahkan 100 orang budak kepada Kompeni Belanda karena tindakan
La Ode Gure. Yang lain adalah La Ode Gola bersama pasukannya berhasil menenggelamkan
kapal Belanda, Rust en Werk pada tahun 1906 sebagai reaksi atas penolakan perjanjian Asyikin-
Brugman (1906). Kapten kapal bernama Van den Burg (ada yang menyatakan dari nama ini
menjadi Wa Ode Buri). Pada tahun 1914 ia tewas dalam pertempuran melawan Belanda di
Kulisusu. Penentang lain perjanjian Asyikin-Brugman adalah Ani Abdul Latif. Ia dan kawan-
kawannya kemudian dipenjarakan di Ujung Pandang pada tahun 1907. La Ode Boha melakukan
serangan ke kapal Belanda di teluk Bau-Bau hingga tewas pada tahun 1912. Pemimpin
pemberontakan lainnya adalah Mantalagi di Pasar Wajo (1914), La Ode Sampela dan La Ode
Ebo di Tiworo (1914), La Ode Ijo dan La Ode Pulu di Muna (1914).
Tiga orang tokoh penting Moronene yang menentang Korte Verklaring (Perjanjian
Asyikin-Brugman) adalah Sangia Dowo, Mbohogo, dan I Ule. Pemimpin pejuang, Sangia Dowo,
tewas diracun Belanda dalam suatu perundingan tahun 1911. Sebelum menghembuskan nafas
terakhir, ia masih sempat mengucapkan pernyataan patriotik yang berbunyi “mati adalah soal
biasa, tetapi munafik itu hukumannya dosa. Mati adalah pilihan seorang pahlawan yang
mencintai tanah airnya. Meskipun aku telah mati karena tipu muslihatmu, namun jiwaku tetap
hidup dan melawan bangsamu”. Ia mati sebagai perisai perjuangan dalam usia 37 tahun, suatu
usia yang masih sangat muda. Jenazahnya diusung pulang ke istana dan dimakamkan secara adat
kebesaran kerajaan. Kepadanya diberi gelar Sangia Nilemba yang berarti raja yang diusung.
Perjuangannya dilanjutkan oleh Mbohogo dan I Ule. Tahun 1912, Mbohogo dibuang ke Nusa
Kambangan dan tewas di tiang gantungan di Nusa Kambangan. Sementara I Ule pada tahun yang
sama tewas di tiang gantungan dalam status pembuangan di Bau-Bau.
Anda mungkin juga menyukai
- Sejarah Singkat ButonDokumen7 halamanSejarah Singkat ButonNoffrizal D'Zaim50% (2)
- Di Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan: Membongkar Dominasi Kultural Kesultanan Buton Di KulisusuDokumen24 halamanDi Bawah Bayang-Bayang Kekuasaan: Membongkar Dominasi Kultural Kesultanan Buton Di KulisusuNurlinBelum ada peringkat
- SUKU Si Sulawesi TenggaraDokumen36 halamanSUKU Si Sulawesi TenggaraAncha HamsahBelum ada peringkat
- Kebudayaan Buton Laode Andri HariyanaDokumen4 halamanKebudayaan Buton Laode Andri Hariyanaﹺ ﹺ ﹺ ﹺ ﹺ ﹺBelum ada peringkat
- Kerajaan ButonDokumen3 halamanKerajaan Butonsri f. Rahmwati100% (1)
- History of Buton EmpireDokumen5 halamanHistory of Buton EmpiremailBelum ada peringkat
- Sejarah ButonDokumen4 halamanSejarah ButonAde SalamBelum ada peringkat
- Makalah Suku ButonDokumen16 halamanMakalah Suku ButonRahmat Ibnu UmarBelum ada peringkat
- Makalah Suku ButonDokumen16 halamanMakalah Suku ButonAHMAD AL ISLAMI100% (3)
- Makalah Suku ButonDokumen16 halamanMakalah Suku ButonAHMAD AL ISLAMI50% (2)
- Mengenal Muasal Masyarakat ButonDokumen22 halamanMengenal Muasal Masyarakat Butonfaat100% (1)
- SEJARAH Kesultanan ButonDokumen2 halamanSEJARAH Kesultanan ButonAinul SyabanBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Kebudayaan MunaDokumen12 halamanMakalah Sejarah Kebudayaan MunaWarnet Vast RahaBelum ada peringkat
- Kerajaan Buton - Ilham Xa6Dokumen10 halamanKerajaan Buton - Ilham Xa6Ilham InsanBelum ada peringkat
- Latar Belakang Sejarah Buton 2Dokumen7 halamanLatar Belakang Sejarah Buton 2rizki_nugroho_3100% (1)
- Kesultanan Buton Gowa FixDokumen20 halamanKesultanan Buton Gowa FixOoji futari iiBelum ada peringkat
- Makalah Falsafah Perjuagan Orang ButonDokumen16 halamanMakalah Falsafah Perjuagan Orang ButonLA ODEBelum ada peringkat
- Suku Buton - InfoDokumen7 halamanSuku Buton - InfoRisma YunitaBelum ada peringkat
- MAKALAH SejjaraahDokumen11 halamanMAKALAH SejjaraahMarvenxive17Belum ada peringkat
- Resensi Buku Sejarah Buton Yang TerabaikanDokumen11 halamanResensi Buku Sejarah Buton Yang TerabaikanFitriyana100% (1)
- Kesultanan BoneDokumen9 halamanKesultanan BonesalmaBelum ada peringkat
- Kerajaan ButonDokumen2 halamanKerajaan ButonGendisBelum ada peringkat
- Kerajaan Islam Di SulawesiDokumen5 halamanKerajaan Islam Di SulawesiEkho SyahputraBelum ada peringkat
- Sejarah Kota BaubauDokumen66 halamanSejarah Kota Baubauayansari dina pratiwi0% (1)
- UTYUUDokumen18 halamanUTYUUWesnuSnuBelum ada peringkat
- Sejarah Suku BugisDokumen19 halamanSejarah Suku BugisAhndreyRhuchidhiiverBelum ada peringkat
- Buton KagebunshinDokumen6 halamanButon KagebunshinDevita MaharaniBelum ada peringkat
- T2 - 752013009 - Bab IiiDokumen33 halamanT2 - 752013009 - Bab IiiSmart Quiddity of Socio SQS ChannelBelum ada peringkat
- Kerajaan Islam Di SulawesiDokumen3 halamanKerajaan Islam Di SulawesiBlonk Net CisolokBelum ada peringkat
- Sejarah Kerajaan Buton: Rauf, R. "Islamisasi Kesultanan Buton"Dokumen3 halamanSejarah Kerajaan Buton: Rauf, R. "Islamisasi Kesultanan Buton"Lawren HU Zakaria Pualam lawren0870fis.2021Belum ada peringkat
- SejarahDokumen15 halamanSejarahCitra ApriliaBelum ada peringkat
- SulawesiDokumen14 halamanSulawesiAnonymous eDZwyFWYlBelum ada peringkat
- Suku ButonDokumen5 halamanSuku ButonAbin CitimediaBelum ada peringkat
- Kliping RahmatDokumen10 halamanKliping Rahmathidayah apri klanandaBelum ada peringkat
- Topik 6 - Shofia Nabila NurintanDokumen5 halamanTopik 6 - Shofia Nabila NurintanShofia Nabila NurintanBelum ada peringkat
- MakalahDokumen10 halamanMakalahamildayaniBelum ada peringkat
- Jaman NcuhiDokumen4 halamanJaman NcuhirabakodoBelum ada peringkat
- Kerajaan BoneDokumen13 halamanKerajaan BoneAndi NurhikmahBelum ada peringkat
- Document 1Dokumen3 halamanDocument 1Andi Izza Nour HafifahBelum ada peringkat
- Pemerintahan Raja Muna Sebelum IslamDokumen13 halamanPemerintahan Raja Muna Sebelum IslamWarnet Vast RahaBelum ada peringkat
- Artikel Kerajaan Di SulawesiDokumen16 halamanArtikel Kerajaan Di SulawesirositaBelum ada peringkat
- Suku BugisDokumen10 halamanSuku BugisKykhy Interisti La BeneamattaBelum ada peringkat
- Makalah Kerajaan Islam Di SulawesiDokumen12 halamanMakalah Kerajaan Islam Di SulawesiWahyu Utama100% (1)
- Makalah Falsafat Pandangan Hidup MbojoDokumen15 halamanMakalah Falsafat Pandangan Hidup MbojoRahmatHidayatBelum ada peringkat
- Kelompok 5 Pengantar AntropologiDokumen9 halamanKelompok 5 Pengantar AntropologiIl HyamBelum ada peringkat
- Imaginative Mind Without Spent in Writing Such As Bottles Without ContentDokumen14 halamanImaginative Mind Without Spent in Writing Such As Bottles Without ContentJhuni Junior BuselBelum ada peringkat
- Tugas Pekan 9 (Ade Widya Cahyani Liana Putri)Dokumen9 halamanTugas Pekan 9 (Ade Widya Cahyani Liana Putri)Ardin Y. HasBelum ada peringkat
- Falsafah Hidup Yang Berkaitan Dengan Falsafah Hidup KebutonanDokumen11 halamanFalsafah Hidup Yang Berkaitan Dengan Falsafah Hidup KebutonanMuhammad WardimanBelum ada peringkat
- Kerajaan Islam Di Sulawesi - SejarahDokumen30 halamanKerajaan Islam Di Sulawesi - SejarahKezia Angelina83% (6)
- Sejarah WajoDokumen12 halamanSejarah WajoPorlanButar-butarBelum ada peringkat
- Bagus PrayogaDokumen22 halamanBagus PrayogaIwanda Luluatul MBelum ada peringkat
- Kerajaan Ternate Dan Tidore 2Dokumen8 halamanKerajaan Ternate Dan Tidore 2nabilaBelum ada peringkat
- Penyebaran Agama DisutraDokumen4 halamanPenyebaran Agama Disutratehgelas2711Belum ada peringkat
- Suku BugisDokumen17 halamanSuku BugisAan Andrian100% (1)
- Sejarah SultengDokumen22 halamanSejarah SultengNi Wayan RimayaniBelum ada peringkat
- Tugas Laporan Bacaan Sejarah LokalDokumen3 halamanTugas Laporan Bacaan Sejarah Lokalselmaha17Belum ada peringkat
- 7 Kerajaan Islam Di Sulawesi Dan Maluku Beserta PenjelasannyaDokumen10 halaman7 Kerajaan Islam Di Sulawesi Dan Maluku Beserta PenjelasannyaSiti PaqihaBelum ada peringkat
- Ab IDokumen7 halamanAb IUjilPutraPasundanBelum ada peringkat
- Kingdom Islamic in The IndonesianDokumen38 halamanKingdom Islamic in The IndonesianDhiyhanzHadhiyhanzMajiedEpisodeIIBelum ada peringkat
- Surat Pernyataan ULFADokumen1 halamanSurat Pernyataan ULFAYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Absen KLS IvDokumen1 halamanAbsen KLS IvYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Soal MTKDokumen3 halamanSoal MTKYuningsih YuniBelum ada peringkat
- No Ruang Kelas PasDokumen3 halamanNo Ruang Kelas PasYuningsih YuniBelum ada peringkat
- BHS Indo 3Dokumen21 halamanBHS Indo 3Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Jadwal Mapel Semester GenapDokumen1 halamanJadwal Mapel Semester GenapYuningsih YuniBelum ada peringkat
- LJ SDN LombokitaDokumen1 halamanLJ SDN LombokitaYuningsih YuniBelum ada peringkat
- PKN KLS 2 Smester 1Dokumen3 halamanPKN KLS 2 Smester 1Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- SBDP Kls 2 Semester 1Dokumen2 halamanSBDP Kls 2 Semester 1Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Cover SDDokumen1 halamanCover SDYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Jadwal Pengawas SDN Lombokita. Semester GenapDokumen1 halamanJadwal Pengawas SDN Lombokita. Semester GenapYuningsih YuniBelum ada peringkat
- SBDPDokumen2 halamanSBDPYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Soal Bahas IndonesiaDokumen4 halamanSoal Bahas IndonesiaYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Kebersihan Kelas 2Dokumen2 halamanKebersihan Kelas 2Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Matematika Kls 2 Semester 1Dokumen2 halamanMatematika Kls 2 Semester 1Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Mate Ma TikaDokumen2 halamanMate Ma TikaYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Bahasa Kelas 2 Semester 1Dokumen3 halamanBahasa Kelas 2 Semester 1Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Kunci Jawaban IpasDokumen3 halamanKunci Jawaban IpasYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Bahasa IndonesiaDokumen2 halamanBahasa IndonesiaYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Identitas Siswa Kelas 2Dokumen1 halamanIdentitas Siswa Kelas 2Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Jadwal KLS 2Dokumen3 halamanJadwal KLS 2Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Soal Seni RupaDokumen3 halamanSoal Seni RupaYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Soal PancasilaDokumen4 halamanSoal PancasilaYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Pranata Sosial Dalam Kehidupan Dalam MasyarakatDokumen10 halamanPranata Sosial Dalam Kehidupan Dalam MasyarakatYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Soal IpasDokumen3 halamanSoal IpasYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Sasmita (A1N216096)Dokumen14 halamanSasmita (A1N216096)Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Daftar HadirDokumen1 halamanDaftar HadirYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Silabus Mila 2Dokumen12 halamanSilabus Mila 2Yuningsih YuniBelum ada peringkat
- Pengertian Hubungan Sosial Dalam MasyarakatDokumen11 halamanPengertian Hubungan Sosial Dalam MasyarakatYuningsih YuniBelum ada peringkat
- Materi Sosiologi Kelas 8 (Mikro)Dokumen20 halamanMateri Sosiologi Kelas 8 (Mikro)Yuningsih YuniBelum ada peringkat