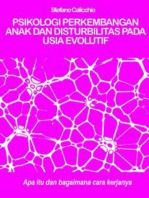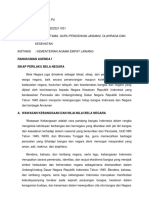High Touch (Analisis Pelaksanaan (A Dan B) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
High Touch (Analisis Pelaksanaan (A Dan B) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
Diunggah oleh
feni listari0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
17 tayangan5 halamanHigh Touch ( Analisis Pelaksanaan (a Dan b) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
Judul Asli
High Touch ( Analisis Pelaksanaan (a Dan b) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHigh Touch ( Analisis Pelaksanaan (a Dan b) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
17 tayangan5 halamanHigh Touch (Analisis Pelaksanaan (A Dan B) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
High Touch (Analisis Pelaksanaan (A Dan B) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
Diunggah oleh
feni listariHigh Touch ( Analisis Pelaksanaan (a Dan b) Di Sekolah (Dengan Menggunakan BMB3)
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
High touch dalam Pendidikan
a. Konsep dan prinsip high touch dalam pendidikan
b. Praktek high touch dalam pendidikan
c. Analisis pelaksanaan (a dan b ) di sekolah (dengan menggunakan BMB3)
Proses pembelajaran harus mampu mengembangkan segenap potensi peserta
didik. Pengembangan itu mencakup keseluruhan hakekat dan dimensi kemanusian serta
pancadaya yang dimiliki peserta didik melalui teraplikasinya kewibawaan ( high-touch)
dalam setiap proses pembelajaran yang diselenggarakan. Sebaliknya, pendidik yang
kurang memahami peserta didik akan menyebabkan terjadi praktik-praktik pembelajaran
yang kurang memberikan kemungkinan terhadap pengembangan potensi peserta didik.
Akibatnya potensi peserta didik akan terabaikan, tersia-siakan dan bahkan mungkin
terdholimi. Sebab kewibawaan pendidik yang meliputi unsur pengakuan, kasih sayang
dan kelembutan, pengarahan, penguatan dan tindakan tegas yang mendidik serta
keteladanan tidak teraplikasikan dalam proses pembelajaran.
Di sekolah, disinyalir masih banyak pendidik yang belum memahami dan
mengetahui hakikat peserta didik secara baik dan benar. Akibatnya dalam proses
pembelajaran, belum sepenuhnya terlihat adanya internalisasi nilai-nilai yang terkandung
dalam materi pelajaran dalam usaha pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik
yang mencangkup berbagai dimensi kemanusian dan pancadaya mereka. Kenyataan ini
dapat terlihat pada adanya perlakuan-perlakuan yang kurang mendidik dari pendidik
terhadap peserta didik, antara lain, membentak di dapan umum, melabeli dengan gelar
yang buruk. Hasil penelitian yang dilakukan Robinson (1986) menyimpulkan bahwa
pemberian label kepada peserta didik di sekolah memiliki pengaruh yang kuat terhadap
keberhasilan atau kegagalan peserta didik. Label yang buruk akan menyebabkan peserta
didik identik dengan label yang diberikan. Sedangkan label yang baik akan meningkatkan
harapan besar bagi peserta didik untuk meraih keberhasilan.
Pendidik dituntut tanggung jawabnya untuk melaksanakan proses pembelajaran
secara professional, yaitu praktik pendidikan yang didasarkan pada kaidah-kaidah
keilmuan pendidikan. Esensi permasalahan peningkatan profesionalisme pendidikan
menurut Winarno (2005) adalah masalah akuntabilitas pendidik. Ia melontarkan sinisme
bahwa praktik pendidikan yang dilaksanakan oleh pendidik di sekolah tidak didasari oleh
ilmu pendidikan atau “pentip” (pendidikan-tanpa-ilmu pendidikan)
Pendidikan secara leluasa “mementip” peserta didik dalam proses pembelajaran
tanpa dasar ilmu pendidikan yang kuat atau bahkan tidak dimiliki sama sekali. Praktik
pendidikan demikian ini, tentu saja tidak dapat mengembangkan potensi yang dimiliki
peserta didik, dan mungkin bisa merapuhkan dan bahkan mematikannya. “Pentip” dapat
menimbulkan brbagai permasalahan belajar dan permasalahan umum lainnya (Ida
Umami, 2004). Kenyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Prayitno., dkk (2005) yang
mengungkapkan banyaknya permasalahan yang dialami peserta didik terkait dengan
proses pembelajaran yang kurang efektif disebabkan pembelajaran yang kurang
mengindahkan kewibawaan tetapi terfokus pada aspek kewiyataan.
Kelas yang efektif ditunjang iklim sekolah yang memfasilitasi tugas pendidik
menjadikan semua ruang kelas sebagai effevtive classrooms. Mohd Ansyar (2005:1) juga
mengemukakan bahwa diperlukannya adanya perbaikan yang mendasar pada proses
pembelajaran di dalam kelas (classroom change) sesuai konsep pembelajaran yang baik.
Sehingga banyak kelas harus berfungsi sebagai basis pembelajaran dari pada sebagai
arena pembelajaran. Untuk itu diperlukannya srtategi dalam pembelajaran. Strategi
pembelajaran terdapat dua pilar pembelajaran yaitu kewibawaan dan kewiyataan (Anidar,
2016).
1. Kewibawaan
Antara pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi tentunya menbangun
hubungan interpersonal melalui praktik kewibawaan pendidik, diantarnya yaitu
unsur-unsur :
a) Pengakuan dan penerimaan pendidik terhadap peserta didik secara tulus
dan terbuka.
b) Ketulusan rasa kasih dan kesejukan sikap yang ditampilkan pendidik.
c) Memberikan penguatan kepada peserta didik atas hal positif yang telah
dilakukan.
d) Memberikan TTM (tindakan tegas pendidik) tanpa harus/ selalu memberi
hukuman atas tindakan peserta didik yang kurang tepat.
e) Pemberian teladan dan arahan kepada peserta didik dengan persisten.
2. Kewiyataan
Dalam situasi hubungan kewibawaan social tersebut, pendidik mendirikan pilar
selanjutnya, yaitu kewiyataan yang dimunculkan oleh pendidik melalui
keahliannya tentang :
a) Menguasai materi yang diajarkan, dalam hal ini materi dalam konseling.
b) Mampu mengunakan metode pembelajaran, dalam hal ini metode
konseling, beragam jenis layanan dan kegiatan pendukung konseling,
melalui beragam model, pendekatan dan teknik-tekniknya.
c) Mampu memanfaatkan media/alat bantu pembelajaran, dalam hal ini alat
bantu proses konseling.
d) Penyiapan atau pengaturan lingkungan pembelajaran, dalam hal ini tempat
dilaksankannya kegiatan konseling.
e) Penilaian hasil pembelajaran, dalam hal ini penilaian terhadap hasil
pelayanan konseling.
Lebih jauh, pilar kewibawaan dan kewiyataan dilengkapi dengan strategi
pembelajaran yang bersifat transformatif ( bukan sekedar transaksional), yang
dikenakan terhadap peserta didik. Strategi pembelajaran yang dimaksud itu
diselenggarakan dengan mengaktifkan dinamika BMB3, yaitu :
B = Berfikir
M = Merasa
B = Bersikap
B = Bertindak
B = Bertanggung jawab
Sehingga Meaningfull Learning (pembelajaran bermakna) akan terwujud melalui
dinamika BMB3 yang diaktifkan oleh pendidik. Pengaktifan BMB3 ini
berlangsung aktual dan kontestual, jelas dan terkait, kontiyu, dan konsisten sesuai
dengan tingkat kemampuan (perkembangan ) peserta didik.
Materi pembelajaran merupakan muatan proses pembelajaran. Selanjutnya
aktivitas BMB3 peserta didik bermuatan materi pembelajaran yang menjadi
pokok bahasan selama pembelajaran berlangsung. Lebih dari itu, aktivitas BMB3
dengan materi pembelajaran tersebut dapat berlanjut pasca proses pembelajaran.
Materi pembelajaran pada umumnya meliputi unsure-unsur WPKNS ( wawasan,
pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) dengan substansi AIPTEKSBUD (
agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya ).
Sedangkan Upaya menbangun dinamika BMB3 pada konselor, idealnya
memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Syukur & Zahri,
2019). Berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan professional tentu dapat
dilaksanakan melalui pilar kewibawaan dan kewiyataan yang perlu dilakukan
konselor dengan strategi kreatif agar tidak hanya pada tataran diketahui dan
dihafal namun dapat terinternalisasi dalam diri pribadi konselor. Stategi yang
dapat dilakukan konselor adalah :
a. Penghadiran Role Model
Sosok konselor professional yang mampu menginternalisasi dimensi
BMB3 dalam diri pribadi ketika melakukan kegiatan konseling, dapat
dihadirkan sebagai role model. Keteladanan adalah penempilan positif
dan normatif konselor yang diterima dan ditiru oleh konseli. Dasar dari
keteladanan adalah konformitas sebagai hasil pengaruh social dari orang
lain, dari yang berpola compliance, identification, sampai internalization.
( Praytno, 2008 : 125)
b. Pelibatan Kearifan Lokal
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan aneka ragam budaya dan
kearifan local. Potensi keragaman tersebut menjadi kekuatan tentang
dimanfaatkanya kearifan lokal dalam membangun dinamika BMB3 pada
konselor. Pelibatan kearifan lokal tersebut dapat berbentuk pemaknaan
pepatah daerah, lagu daerah, dan aspek lain yang mengandung filosofi
luhur dan terkait dengan upaya membangun dinamika BMB3. Misalnya ,
pada pepatah jawa terdapat ungkapan “ajining diri gumantung ono ing
lathi”, yang memiliki makna bahwa “ harga diri seseorang dapat dilihat
dari cara dia berbicara”. Selain itu, pepatah dari suku bugis yang
berbunyi” aju maluruemi riala parewa bola (hanya kayu yang lurus
dijadikan ramuan rumah)’. Makna pepatah dari jawa dan Bugis tersebut
memiliki penuh arti. Pepatah dari jawa mengindikasikan bahwa sebagai
seorang konselor harus memiliki nilai kepribadian berupa nilai
kesopanan, dalam bertutur kata kaitannya dengan bersikap dan bertindak
(dalam BMB3), konselor mampu mengucapkan perkataan yang sopan
dan menyejukkan hati bagi konseli. Sementara itu, pepatah dari bugis
mengisyaratkan bahwa dalam menjadi pemimin, hanyalah orang yang
memiliki akhlak lurus atau akhlak penuh kebenaran dan dapat berprilaku
sesuai norma yang ada. Makna tersebut berkaitan dengan nilai
professional yaitu nilai kebenaran. Konselor yang merupakan pemimpin
dalam proses konseling, yang mengatur dan memfasilitasi kegiatan
konseling sebagai kegiatan yang membantu konseli, maka perlu memiliki
nilai kebenaran dalam berfikir, merasa, bersikap, bertindak dan
bertanggung jawab terkait pengembangan dinamika BMB3.
Anda mungkin juga menyukai
- PSIKOLOGI, DEPRESI DAN DISTURBILITAS HUMOR: Memahami mekanisme dasarDari EverandPSIKOLOGI, DEPRESI DAN DISTURBILITAS HUMOR: Memahami mekanisme dasarPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3)
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Makalah Indikator Dan Tujuan PemelajaranDokumen21 halamanMakalah Indikator Dan Tujuan Pemelajaranismi azizah82% (11)
- Diskusi 4 Perspektif Pendidikan SDDokumen5 halamanDiskusi 4 Perspektif Pendidikan SDHendra CapcomBelum ada peringkat
- Pengertian Kualitas Pembelajaran Dan Indikator Kualitas PembelajaranDokumen16 halamanPengertian Kualitas Pembelajaran Dan Indikator Kualitas Pembelajaranmuhammad choerul umam91% (11)
- Inovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Revisi PDFDokumen38 halamanInovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Revisi PDFMaya putrinya radjaBelum ada peringkat
- LK - Resume Pendalaman Materi PPG 2022Dokumen4 halamanLK - Resume Pendalaman Materi PPG 2022Ikhwani AndidBelum ada peringkat
- Mengeloloa Pembelajaran Secara EvektifDokumen16 halamanMengeloloa Pembelajaran Secara EvektifSyukri2212Belum ada peringkat
- Inovasi Pembelajaran KompetensiDokumen8 halamanInovasi Pembelajaran Kompetensinovinda ayuBelum ada peringkat
- Aksi Nyata Topik 4Dokumen7 halamanAksi Nyata Topik 4lalu sukmawanBelum ada peringkat
- Makalah Interaksi Berbasis KarakterDokumen24 halamanMakalah Interaksi Berbasis Karaktermeiranty100% (1)
- Tugas Akhir Pedagogi 1 - Choirul AnamDokumen8 halamanTugas Akhir Pedagogi 1 - Choirul AnamAgoes SoelaimanBelum ada peringkat
- Refisi Fix Skripsi Bab IDokumen14 halamanRefisi Fix Skripsi Bab IZakiyatul MardhiyahBelum ada peringkat
- Review Kesimpulan Materi Pedagogik Modul 1Dokumen2 halamanReview Kesimpulan Materi Pedagogik Modul 1Alexander Saragih RumahorboBelum ada peringkat
- Resume - Muhhamad Hilman JaelaniDokumen3 halamanResume - Muhhamad Hilman JaelaniMuhhamad Hilman JaelaniBelum ada peringkat
- Uraian Program Penguatan KarakterDokumen11 halamanUraian Program Penguatan KarakterPujianto Sofi100% (1)
- SOAL UTS - Landasan - Pendidikan BiologiDokumen5 halamanSOAL UTS - Landasan - Pendidikan BiologiVinBelum ada peringkat
- Artikel Modul 2.1Dokumen2 halamanArtikel Modul 2.1tri agustinaBelum ada peringkat
- Laporan FixDokumen56 halamanLaporan FixHeryBelum ada peringkat
- Refleksi Pembelajaran Pedagogik1Dokumen2 halamanRefleksi Pembelajaran Pedagogik1Khafidz NhBelum ada peringkat
- Refleksi Egia Prananta PinemDokumen7 halamanRefleksi Egia Prananta PinemEgia Prananta pinemBelum ada peringkat
- Resume Standar Kompetensi Guru Dan Tips Mengajar Yang BaikDokumen2 halamanResume Standar Kompetensi Guru Dan Tips Mengajar Yang BaikHaidaroh Faiqotul MunaBelum ada peringkat
- Makalah Karakteristik Guru BK Yang BaikDokumen21 halamanMakalah Karakteristik Guru BK Yang Baikgita rona meifina0% (1)
- Etika Profesi Kelompok 4Dokumen6 halamanEtika Profesi Kelompok 4Elok robiatulBelum ada peringkat
- Template Resume KB 3 2023Dokumen5 halamanTemplate Resume KB 3 2023Ceceng MuhajirBelum ada peringkat
- Assgmnt Elmk 3063Dokumen17 halamanAssgmnt Elmk 3063Geethu PrincessBelum ada peringkat
- Materi Ajar KB-5Dokumen20 halamanMateri Ajar KB-5Nur Risma RusdiBelum ada peringkat
- Bahan Bacaan-Supervisi-Cks 260820Dokumen35 halamanBahan Bacaan-Supervisi-Cks 260820andi hasnahBelum ada peringkat
- Isi Bab I-VDokumen218 halamanIsi Bab I-VYustina AyuBelum ada peringkat
- Proposal Hilwa Maharani-1Dokumen31 halamanProposal Hilwa Maharani-1Hilwa MaharaniBelum ada peringkat
- Nuryanti Nim 2021010002Dokumen4 halamanNuryanti Nim 2021010002NuryantiBelum ada peringkat
- Asas Asas PembelajaranDokumen12 halamanAsas Asas PembelajaranTaufiq KamilBelum ada peringkat
- Dinamika Pendidikan Dalam MasyarakatDokumen6 halamanDinamika Pendidikan Dalam MasyarakatLuluk Zulfa HumamBelum ada peringkat
- Uts DDPDokumen7 halamanUts DDPrahayuBelum ada peringkat
- 1Dokumen10 halaman1Lulu Anggun100% (1)
- MakalahDokumen8 halamanMakalahahmad Fauzi akjBelum ada peringkat
- Nurul Rahma - 21.1.2248 - BAB 1,2,3, & 4Dokumen42 halamanNurul Rahma - 21.1.2248 - BAB 1,2,3, & 4Nurul RahmaBelum ada peringkat
- Makalah Perlunya Perubahan ParadigmaDokumen14 halamanMakalah Perlunya Perubahan ParadigmaBot comBelum ada peringkat
- Modul 4 Kurikulum Berbasis KompetensiDokumen6 halamanModul 4 Kurikulum Berbasis KompetensiI Made agus dharmawanBelum ada peringkat
- BK Dalam Kurikulum 2013 PDFDokumen24 halamanBK Dalam Kurikulum 2013 PDFMuhammad Ariyansyah Noor0% (1)
- Kuis Tutorial 2 - Ditapratiwi - 856715164 - 3aDokumen4 halamanKuis Tutorial 2 - Ditapratiwi - 856715164 - 3aPolebel DipuBelum ada peringkat
- Peran Guru Mapel Layanan BKDokumen7 halamanPeran Guru Mapel Layanan BKJajang MuhidinBelum ada peringkat
- Tantangan Guru Dalam Pembelajaran & Reformasi PendidikanDokumen25 halamanTantangan Guru Dalam Pembelajaran & Reformasi PendidikanEunooBelum ada peringkat
- Bab IDokumen9 halamanBab IsyarkiahBelum ada peringkat
- Jurnal Refleksi - Dea Wulandari - PPDPDokumen3 halamanJurnal Refleksi - Dea Wulandari - PPDPppg.deawulandari92Belum ada peringkat
- Model Pembelajaran Berdifferensiasi Dalam Pembelajaran FiqihDokumen16 halamanModel Pembelajaran Berdifferensiasi Dalam Pembelajaran FiqihserhliadelliaBelum ada peringkat
- Tugas Essay Bin Itri Diana-1Dokumen7 halamanTugas Essay Bin Itri Diana-1Itri DianaBelum ada peringkat
- AKSI NYATA TOPIK 4 (Diana Boimau) PDFDokumen4 halamanAKSI NYATA TOPIK 4 (Diana Boimau) PDFFitry YabesBelum ada peringkat
- Defenisi Evaluasi Pembelajaran: Pengukuran, Penilaian, Dan Evaluasi Hasil Belajar Peserta DidikDokumen6 halamanDefenisi Evaluasi Pembelajaran: Pengukuran, Penilaian, Dan Evaluasi Hasil Belajar Peserta DidikStevan SianturiBelum ada peringkat
- Makalah Standar Proses,,Selfiana FotiartiDokumen12 halamanMakalah Standar Proses,,Selfiana FotiartiTaim NesantoBelum ada peringkat
- Buku MicroTeaching ADokumen52 halamanBuku MicroTeaching APutri AnjasariBelum ada peringkat
- 3b. LISKE Format Laporan Mahasiswa PGPDokumen21 halaman3b. LISKE Format Laporan Mahasiswa PGPliskemintarsih64Belum ada peringkat
- Refleksi MK PPDP - Desta Dara DK - X902308227Dokumen5 halamanRefleksi MK PPDP - Desta Dara DK - X902308227astri nurmalaBelum ada peringkat
- Cara Mengimplementasikan Prinsip Dan Strategi Pembelajaran Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Dan Asesmen Yang EfektifDokumen2 halamanCara Mengimplementasikan Prinsip Dan Strategi Pembelajaran Paradigma Baru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Dan Asesmen Yang EfektifSalma YudantiBelum ada peringkat
- Makalah STBM Yang BaruDokumen10 halamanMakalah STBM Yang BaruCianny Avolita Marpaung100% (1)
- Proposal PenelitianDokumen46 halamanProposal PenelitianYahya AuweBelum ada peringkat
- Model-Model PembelajaranDokumen15 halamanModel-Model PembelajaranMI Mujahidin MujahidinBelum ada peringkat
- Skripsi TrilistiaDokumen100 halamanSkripsi TrilistiaFathur MuttaharBelum ada peringkat
- Resume Micro Teaching & Pendidikan Nilai Mas'ulahDokumen4 halamanResume Micro Teaching & Pendidikan Nilai Mas'ulahmasulahh22Belum ada peringkat
- ppt 10Dokumen10 halamanppt 10feni listariBelum ada peringkat
- PPT KEL 5Dokumen12 halamanPPT KEL 5feni listariBelum ada peringkat
- ppt 3Dokumen14 halamanppt 3feni listariBelum ada peringkat
- Psikologi BK 3Dokumen37 halamanPsikologi BK 3feni listariBelum ada peringkat
- ppt BK KARIR trendDokumen6 halamanppt BK KARIR trendfeni listariBelum ada peringkat
- ppt 9Dokumen10 halamanppt 9feni listariBelum ada peringkat
- PSIKOLOGI BK 4Dokumen25 halamanPSIKOLOGI BK 4feni listariBelum ada peringkat
- Makalah Kel 4 BK Karir Trend BK KarirDokumen19 halamanMakalah Kel 4 BK Karir Trend BK Karirfeni listariBelum ada peringkat
- PEDAGOGI .Dokumen9 halamanPEDAGOGI .feni listariBelum ada peringkat
- Kelompok - 8 BK KarierDokumen11 halamanKelompok - 8 BK Karierfeni listariBelum ada peringkat
- ppt 4Dokumen10 halamanppt 4feni listariBelum ada peringkat
- Ringkasan Pembahasan Diskusi Kelompok Materi dosenMAKALAH KELOMPOK 1 MATA KULIAH PENDAGOGDokumen2 halamanRingkasan Pembahasan Diskusi Kelompok Materi dosenMAKALAH KELOMPOK 1 MATA KULIAH PENDAGOGfeni listariBelum ada peringkat
- 2 Konseling EgoDokumen29 halaman2 Konseling Egofeni listariBelum ada peringkat
- 3 PPT Kelompok 3Dokumen13 halaman3 PPT Kelompok 3feni listariBelum ada peringkat
- 3 Konseling Psikologi Individual (Titik Wiyul Fithri)Dokumen12 halaman3 Konseling Psikologi Individual (Titik Wiyul Fithri)feni listariBelum ada peringkat
- Makalah Manajemen Kelompok 4Dokumen22 halamanMakalah Manajemen Kelompok 4feni listariBelum ada peringkat
- PPT Psi - BK Kelompok 1Dokumen9 halamanPPT Psi - BK Kelompok 1feni listariBelum ada peringkat
- 2 PPT Kelompok 2Dokumen14 halaman2 PPT Kelompok 2feni listariBelum ada peringkat
- TUGAS Ringkasan Materi Dosen 2Dokumen5 halamanTUGAS Ringkasan Materi Dosen 2feni listariBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - PedagogiDokumen12 halamanKelompok 1 - Pedagogifeni listariBelum ada peringkat
- Manajemen BK Resume 1 (Maulida Fitri 23151014)Dokumen14 halamanManajemen BK Resume 1 (Maulida Fitri 23151014)feni listariBelum ada peringkat
- 4 PPT Tugas Makalah Pendekatan Dan Teknik BK Kel IvDokumen14 halaman4 PPT Tugas Makalah Pendekatan Dan Teknik BK Kel Ivfeni listariBelum ada peringkat
- Kel 1 BK KarirDokumen13 halamanKel 1 BK Karirfeni listariBelum ada peringkat
- 3 PPT Kelompok 3 Pendekatan Dan Teknik Dalam KonselingDokumen9 halaman3 PPT Kelompok 3 Pendekatan Dan Teknik Dalam Konselingfeni listariBelum ada peringkat
- BIMBINGAN KONSELING KARIR Feni ListariDokumen15 halamanBIMBINGAN KONSELING KARIR Feni Listarifeni listariBelum ada peringkat
- TUGAS OKE Pengelolaan Kelas TERBARUDokumen15 halamanTUGAS OKE Pengelolaan Kelas TERBARUfeni listariBelum ada peringkat
- Resume Psikologi BKDokumen11 halamanResume Psikologi BKfeni listariBelum ada peringkat
- Metopen (R&D)Dokumen11 halamanMetopen (R&D)feni listariBelum ada peringkat
- Jurnal ArzanDokumen10 halamanJurnal Arzanfeni listariBelum ada peringkat