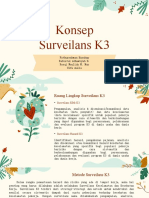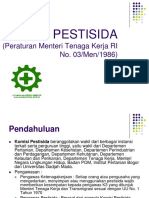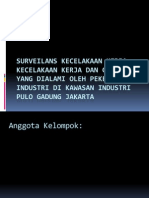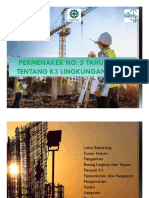01 PDF
01 PDF
Diunggah oleh
lukiJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
01 PDF
01 PDF
Diunggah oleh
lukiHak Cipta:
Format Tersedia
BUKU PEDOMAN
PRAKTIK DASAR-DASAR K3
TIM PENYUSUN PEDOMAN PRAKTEK DASAR-DASAR K3 TAHUN 2014
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2014
KATA PENGHANTAR
Penerbitan Buku Pedoman Praktikum Dasar-Dasar K3 ini merupakan salah satu upaya
untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes
Jakarta II Jurusan Kesehatan Lingkungan.
Dengan menggunakan Buku Pedoman Praktikum ini, maka proses bimbingan
pelaksanaan praktikum, baik bagi mahasiswa maupun pengajar akan lebih terstruktur,
sehingga target kompetensi yang akan dicapai menjadi lebih tepat. Dengan adanya buku
pedoman praktikum, maka tahapan kegiatan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan
praktik, serta kegiatan paska praktikum, peserta praktik dapat memahami dan mampu
dalam menggunakan alat-alat praktikum yang ada di Jurusan Kesehatan Lingkungan,
baik yang berkaitan dengan bahan praktikum, keamanan selama praktik serta waktu
yang di perlukan. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, perkembangan akan selalu
mengikuti, sehingga suatu saat ditemukan hal baru yang berkaitan dengan buku
pedoman praktikum ini. Oleh karena itu saran dan kritik atas buku pedoman praktikum
ini selalu terbuka.
Harapan kami, Buku Pedoman Praktikum Dasar-Dasar K3 memberikan manfaat bagi
para penggunanya.
Jakarta, Desember 2014
Tim Penyusun
Buku Pedoman Praktikum Dasar - dasar K3
Wastyo Wiarawan
Yusuf Dawudi
Editor
Wakhyono Budianto,SKM.,Msi
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan i
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ii
I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………… 1
1.2 Maksud Dan Tujuan ……………………………………………………………………………………………….. 2
1.2.1 Maksud ……………………………………………………………………………………………………… 3
1.2.2 Tujuan ………………………………………………………………………………………………………. 3
1.2.2.1 Tujuan Umum …………………………………………………………………………………………. 3
1.2.2.2 Tujuan Khusus ………………………………………………………………………………………….. 3
II. PENENTUAN SAMPEL 4
2.1 Penentuan Titik Pengambilan Sampel di lingkungan kerja …………………………. 4
2.2 Pengambilan sampel ada beberapa metode berdasarkan periode
waktunya Menurut National Institute Ocupational Safety and Health
(NIOSH) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2.3 Lokasi Pengambilan Sampel berdasarkan lokasi / area dapat di
bedakan dalam beberapa tempat …………………………………………………………………….. 5
2.4 Pelaksanaan Pengambilan sampel berdasarkan peralatan sampling ………. 5
III. PENGUKURAN FAKTOR BAHAYA KERJA ……………………………………………………………… 6
3.1 Faktor Bahaya Fisik …………………………………………………………………………………………………. 6
3.1.1 Pengukuran Tekanan Panas / Iklim Kerja ………………………………………….. 6
3.1.2 Pengukuan Intensitas Penerangan di Tempat Kerja ………………………… 10
3.1.3 Pengukuan Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja …………………………… 15
3.2 Faktor Bahaya Ergonomi ……………………………………………………………………………………….. 20
3.3 Faktor Bahaya Kimia ………………………………………………………………………………………………. 29
3.4 Faktor Psikososial ……………………………………………………………………………………………………… 32
Daftar Pustaka ……………………………………………………………………………………………………………………….. 38
Format Laporan Praktikum ………………………………………………………………………………………………… 39
Soal Latihan ……………………………………………………………………………………………………………………………. 40
1. Tekanan Panas ……………………………………………………………………………………………. 40
2. Kebisingan …………………………………………………………………………………………………….. 40
3. Pencahayaan ……………………………………………………………………………………………….. 41
4. Debu ………………………………………………………………………………………………………………. 41
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan ii
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan ilmu multi disiplin yang menerapkan
upaya pemeliharaan dan peningkatan kondisi lingkungan kerja , keselamatan kerja
dan melindungi tenaga kerja terhadap resiko bahaya dalam melakukan pekerjaan
serta mencegah terjadinya kerugian akibat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja,
kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan kerja. Tujuan keselamatan dan
kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan
kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan jaminan
keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja serta menciptakan
lingkungan kerja yang aman dan nyaman dimana tenaga kerja dapat terhindar dari
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
Berdasarkan teori penyebab kecelakaan , di ketahui bahwa kecelakaan kerja dapat
di hindari apabila penyebabnya dapat di ketahui dan dihilangkan. Faktor penyebab
atau di sebut hazard terdiri atas fisik , kimia, biologis, ergonomi dan psikososial.
Hazard kimia adalah faktor bahaya di lingkungan kerja, kadar debu, kadar gas CO,
kadar CO2 , kadar gas amonia dan sebagainya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
gangguan kesehatan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan
produktivitas tenaga kerja.
Hazard fisik adalah faktor bahaya dilingkungan kerja seperti tingkat kebisingan,
tekanan panas, penerangan, getaran, radiasi sinar ultra violet dan gelombang
elektromagnetik. Hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan kesehatan tenaga
kerja yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja.
Hazard biologis adalah faktor bahaya di lingkungan kerja potensi bahaya yang di
sebabkan oleh mahluk hidup (biologi) gangguan kesehatan pada pekerja yang
terpajan . Potensi bahaya yang menyebabkan alergi / iritasi akibat bahan-bahan
biologis (debu kapas, dedaunan, bulu, bunga, dll) Bahaya faktor biologi atau
biological hazard (biohazard) didefinisikan sebagai agen infeksius atau produk yang
dihasilkan agen biologi atau biological agent didefinisikan sebagai mikroorganisme,
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 1
Hazard ergonomi adalah melakukan gerakan yang sama berulang-ulang. Resiko
yang timbul bergantung dari berapa kali aktifitas tersebut dilakukan, kecepatan
dalam pergerakan/perpindahan, dan banyaknya otot yang terlibat dalam kerja
tersebut. Gerakan yang berulang-ulang ini akan menimbulkan ketegangan pada
syaraf dan otot yang berakumulatif. Dampak resiko ini akan semakin meningkat
apabila dilakukan dengan postur/posisi yang kaku dan penggunaan usaha yang
terlalu besar.
Hazard Psychosocial adalah suatu bahaya non fisik yang timbul karena adanya
interaksi dari aspek-aspek (uraian tugas) job description, disain kerja dan organisasi
serta managemen di tempat kerja serta konteks lingkungan sosial yang berpotensi
menimbulkan ganggua fisik, sosial dan psikologi.
Pentingnya mempelajari Bahaya Psychosocial dan Stress Kerja adalah agar
produktivitas kerja dapat tetap terjaga. Hal ini dapat ditinjau dari dua faktor yaitu:
a. Dari aspek Kesehatan adalah untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan
yang timbul karena faktor-faktor yang ada di tempat kerja, dan
a. Dari aspek Keselamatan adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan karena
orang yang terkena stress memiliki risiko yang lebih besar untuk terjadinya
kecelakaan.
Dalam praktikum dasar-dasar k3 mahasiswa akan di latih untuk dapat melakukan
praktik identifikasi hazard, analisis resiko dan merencanakan tindakan pengendalian,
jenis-jenis hazard yang di evaluasi di sesuaikan dengan peralatan yang ada.
1.2 Maksud dan Tujuan
1.2.1 Maksud
Tersedianya penduan praktikum Kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat di
jadikan pedoman dalam melakukan pengukuran / monitoring dan evaluasi
dilingkungan kerja.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 2
1.2.2 Tujuan
1.2.2.1 Tujuan Umum
Diharapkan praktikum dapat menerapkan pengetahuan tentang
peralatan, pengujian dan evaluasi faktor-faktor bahaya di tempat kerja.
1.2.2.2 Tujuan Khusus
Diharapkan praktikum dapat :
Melakukan pengukuran faktor kimia (kadar debu partikel di
lingkungan kerja ).
Melakukan pengukuran faktor fisik (kebisingan, pencahayaan, tekanan
panas, di lingkungan kerja ).
Melakukan pengukuran faktor biologi
Melakukan pengukur factor psikososial (kelelahan dan stress kerja).
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 3
II. PENGAMBILAN SAMPEL
2.1 Penentuan Titik Pengambilan Sampling di Lingkungan Kerja
Pengambilan titik sampling sangat penting karena dapat menggambarkan kondisi
sesungguhnya pada lokasi dan tempat tertentu merupakan langkag awal untuk
mendapatkan sampel yang representatif, sebelum menentukan lokasi titik
pengambilan sampel lingkungan kerja. Ada 3 langkah yang harus di perhatikan dan
perlu dibandingkan:
1. Langkah Awal
Menentukan titik pengukuran ,
Pengenalan Lingkungan (Hazar Indentifikasi)
Memahami tahap-tahap proses produksi atau kegiatan yang menyangkut
kegiatan operasional perusahaan dan faktor-faktor bahaya yang timbul
dalam proses tersebut, jumlah tenaga kerja yang terpapar sehingga dapat
mengetahui bagian mana dan parameter apa dapat diketahui secara jelas.
2. Langkah Kedua
Penilaian Lingkungan (Risk Assesment) pada tahap ini di ketahui bagian apa
dan parameter apa diadakan pengukuran di lapangan dan pengambilan
sampel dengan menggunakan peralatan sesuai yang di butuhkan, setelah
sampling di analisis, hasil nya di bandingkan dengan Standart Nilai Ambang
Batas (NAB).
3. Langkah Ketiga
Pengendalian (Risk Control) dalam tahap ini setelah didapat hasil analisa di
bandingkan dengan NAB, ternyata melebihi NAB yang telah ditentukan,
maka langkah pengendalian dari faktor-faktor lingkungan tersebut.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 4
2.2 Pengambilan sampling ada beberapa metode berdasarkan periode
waktunya Menurut National Institute Ocupational Safety and Health
(NIOSH) :
1. Pengambilan Sampel selama 8 jam ( Full Periode )
Pengambilan sampel selama waktu 8 jam di sesuaikan dengan jam kerja.
2. Pengambilan Sampel kurang dari 8 jam ( Full Periode Single Sample )
3. Pengambilan Sampel kurang dari 8 jam ( Full Periode Consecutif Sample )
4. Pengambilan Sampel Sesaat ( Random / Grab Sample )
2.3 Lokasi Pengambilan Sampling berdasarkan lokasi / area dapat di
bedakan dalam beberapa tempat :
1. Pada Sumber Kontaminan
Langsung didekatkan pada sumber
2. Pada Lokasi Kerja di dekat Tenaga Kerja
Langsung dekatkan ke pekerja
3. Pada tempat-tempat yang sering dilalui tenaga kerja
Langsung / tempatkan pada lokasi yang sering pekerja lalui
4. Pada Personal / Perorangan.
Langsung pada pekerja / alat di kenakan pekerja selama jam kerja
2.4Pelaksanaan Pengambilan sampling berdasarkan peralatan sampling
dapat di bedakan 2 yaitu :
1. Direct Reading
Pengambilan sampel dengan pembacaan langsung tanpa melalui analisia
laboratorium.
2. Indirect Reading
Pengambilan sampel dengan mengunakan analisa laboratorium .
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 5
III. PENGUKURAN FAKTOR BAHAYA KERJA
3.1 Faktor Bahaya Fisik
3.1.1 Pengukuran Tekanan Panas / Iklim Kerja
1. Dasar Teori
Tekanan panas adalah faktor di tempat kerja yang ditimbulkan oleh perpaduan
kondisi suhu udara, kelembaban, kecepatan gerakan udara dan radiasi. Pengujian
yang dilakukan ditentukan dengan mengukur suhu kering, suhu basah dan suhu
bola dimana satuan dan rumus yang digunakan dinyatakan sebagai Indeks Suhu
Basah dan Bola ( ISBB).
2. Tujuan
Memahami konsep dasar pengukuran tekanan panas di dan melakukan
pengukuran di lingkungan kerja dengan menggunakan parameter Indeks Suhu
Basah dan Bola (ISBB), sesuai dengan Nilai Amabang Batas (NAB) yang
ditentukan.
3. Alat
Area Heat Stress Monitor
Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan panas pada area kerja
4. Cara Kerja
a. Tentukan lokasi dan titik sampling
b. Lakukan pengukuran tekanan panas di dekat tenaga kerja yang sedang
melakukan aktivitas.
c. Posisikan Area Heat Stress Monitor berada di dekat tenaga kerja.
d. Tekan tombol On pada alat heat stress monitor diamkan selama 10 menit
berada ditempat pengukuran.
e. Setelah 10 menit amati dan baca pada layar monitor tercantum suhu
udara kering, suhu udara basah, suhu udara basah, suhu udara bola
(globe), kelembaban udara, indeks suhu bola basah (ISBB) Indoor dan Out
door.
f. Catat pda formulir hasil pengukuran tekanan panas
g. Bandingkan dengan Nilai Ambang Batas (NAB) Kepmenakertrans No : 13
tahun 2011 tentang NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR
KIMIA DI TEMPAT KERJA
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 6
ISBB (˚C )
Pengaturan waktu kerja setiap jam Beban Kerja
Ringan Sedang Berat
75% - 100% 31,0 28,0 -
50 % - 75% 31,0 29,0 27,5
25% - 50% 32,0 30,0 29,0
0% - 25% 32,2 31,1 30,5
Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di luar ruangan dengan panas radiasi:
ISBB = 0,7 Suhu basah alami + 0,2 Suhu bola + 0,1 Suhu kering.
Indeks Suhu Basah dan Bola untuk di dalam atau di luar ruangan tanpa panas
radiasi :
ISBB = 0,7 Suhu basah alami + 0,3 Suhu bola.
Catatan :
Beban kerja ringan membutuhkan kalori sampai dengan 200 Kilo
kalori/jam.
Beban kerja sedang membutuhkan kalori lebih dari 200 sampai dengan
kurang dari 350 Kilo kalori/jam.
Beban kerja berat membutuhkan kalori lebih dari 350 sampai dengan
kurang dari 500 Kilo kalori/jam.
5. Rumus Indeks suhu bola basah bola
a) Rumus yang dikembangkan berdasarkan perpindahan lokasi kerja. Dalam
hal pemaparan ISBB yang berbeda-beda karena lokasi kerja yang
berpindah-pindah menurut waktu, maka berlaku ISBB rata-rata dengan
rumus sebagai berikut:
(ISBB1) (t1) + (ISBB2) (t2) +………+(ISBBn) (tn)
ISBB rata-rata = ---------------------------------------------------------------
t1 + t2 +……………….+.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 7
Keterangan :
0
C : Derajat Celcius
ISBB : Indeks Suhu Basah dan Bola
ISBB1 : Indeks Suhu Basah dan Bola menurut waktu 1
ISBB2 : Indeks Suhu Basah dan Bola menurut waktu 2
ISBBn : Indeks Suhu Basah dan Bola menurut waktu n
ISBB rata-rata : Indeks Suhu Basah dan Bola diterima rata-rata selama waktu
tertentu
SBA : Suhu Basah Alami
SK : Suhu Kering
SB : Suhu Bola
t1, t2, tn, : Jangka waktu pemaparan selama ISBB1, ISBB2, ISBBn yang
bersangkutan, dinyatakan dalam menit. (Catatan : Waktu
pemaparan selama 30-60 menit, dan waktu pengukuran
dilakukan 3 kali dalam 8 jam kerja yaitu awal, tengah, dan akhir
shift kerja.
Catatan :
1. Hasil dari ISBB rata-rata adalah hasil yang digunakan untuk dibandingkan
dengan regulasi yang dijadikan acuan yaitu peratuan-peraturan yang terkait.
2. Waktu Kerja dan Istirahat disesuaikan dengan lamanya waktu kerja yang
dilakukan oleh pekerja di ruangan tersebut, yang dinyatakan dalam
persentase.
3. Perhitungan kategori beban kerja adalah sebagai berikut :
a. Grandjen (1998),menyatakan bahwa salah satu pendekatan untuk
mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan menghitung nadi
kerja, konsumi oksigen, kapasitas vasilitas paru & suhu inti tubuh.
PENILAIAN BEBAN KERJA
(Christensen,1991.Encyclopaedia of Occupational Health and Safety.ILO Geneva)
Beban kerja Konsumsi 02 Ventilasi paru Suhu rectal Denyut
l/mnt l/mnt Jantung
ringan 0,5-1,0 11-20 37,5 75-100
sedang 1,0-1,5 20-31 37,5-38 100-125
berat 1,5-2,0 31-43 38-38,5 125-150
Sangat berat 2,0-2,5 43-56 38,5-39 150-175
Sgt berat sekali 2,5-4,0 60-100 >39 >175
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 8
b. Penilaian beban kerja dapat dilakukan berdasarkan berat badan pekerja
dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
Kebutuhan Kalori Perjam Menurut Jenis Aktivitas
Sumber (SUMA’MUR,1982)
Contoh : Seorang pekerja dengan berat badan sekitar 65 kg bekerja sebagai tukang
batu dibawah terik matahari , maka berdasarkan data tersebut diatas / baris 21 ,
diperoleh jumlah kalori yang dibutuhkan adalah :
5,71 x 65 kg = 371 Kilocal / jam.
Beban kerja ini termasuk dalam kategori beban kerja berat ( > 350- 500 Kilokal
/jam-----Kepmenaker No.51 th 1999)
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 9
Formulir Tekanan Panas
Nama Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alamat Perusahaan : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Petugas : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tanggal Sampling : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lokasi Hasil Pengukuran
No Pengukuran Waktu Beban Kerja Keterangan
SK 0C SB 0C RH % ISBB 0C
3.1.2 Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
1. Dasar Teori
Intensitas penerangan di tempat kerja dimaksudkan untuk menberikan
penerangan kepada benda-benda yang merupakan obyek kerja, peralatan atau
mesin dan proses produksi serta lingkungan kerja. Untuk itu diperlukan intensitas
penerangan yang optimal. Selain menerangi obyek kerja, penerangan juga
diharapkan cukup memadai menerangi keadaan sekelilingnya.
2. Tujuan
Untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai dalam suatu ruang, maka
diperlukan sistem pencahayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sistem
pencahayaan di ruangan, termasuk di tempat kerja.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 10
3. Alat
Lux Meter
Mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian eneergi listrik
diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor.
4. Penentuan Titik Pengukuran
a. Penerangan Setempat
Obyek kerja, berupa meja kerja maupun peralatan dan pengukuran dapat
di lakukan di atas meja.
b. Penerangan Umum
Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan pada setiap jarak
tertentu setinggi 1 (satu) meter. Jarak tertentu tersebut dibedakan
berdasarkan luas ruangan.
Luas ruangan kurang dari 10 m² .
Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada
jarak 1 (satu) meter.
Luas ruangan antara 10 sampai 100 m² .
Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada
jarak 3 (tiga) meter.
Luas ruangan lebih dari 100 m² .
Titik potong garis horizontal panjang dan lebar ruangan adalah pada
jarak 6 (enam) meter.
5. Cara Kerja
a. Hidupkan Luxmeter
b. Letakan alat ke titik pengukuran yang telah ditentukan, baik penerangan
setempat atau umum.
c. Baca hasil pengukuran pada layar monitor setelah menunggu beberapa
saat sehingga didapat nilai angka yang stabil.
d. Catat hasil pengukuran pada lembar hasil.
e. Matikan lux meter setelah pengukuran.
f. Bandingkan dengan Nilai Ambang Batas (Permenkes) Nomor :
1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan
Kerja Perkantoran dan Industri.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 11
6. Rumus Pengolahan Data
a) Pencahayaan Umum
Rumus pengolahan data pencahayaan umum adalah sebagai berikut :
Dalam satu titik dilakukan 3 kali pembacaan/pengukuran karena angka
yang tertera pada alat lux meter / light meter berubah-ubah tidak stabil.
Perhitungan rata-rata pencahayaan per titik : P1 + P2 + P3 = .... lux
∑P
Dalam satu ruangan akan diperoleh beberapa titik pengukuran
tergantung dari luas ruangan yang telah di ukur, sehingga mendapatkan
beberapa titik pengukuran.
Perhitungan rata-rata pencahayan ruangan : T1 + T2 + .......... + Tn = .... lux
∑T
Keterangan :
P1 = Pembacaan/pengukuran pertama
P2 = Pembacaan/pengukuran kedua
P3 = Pembacaan/pengukuran ketiga
∑ P = Jumlah pembacaan/pengukuran
T1 = Titik pertama
T2 = Titik kedua
Tn = Titik ke- n
∑ T = Jumlah Titik
Catatan :
Hasil dari perhitungan rata-rata pencahayaan ruangan adalah hasil yang
digunakan untuk dibandingkan dengan regulasi yang dijadikan acuan yaitu
peraturan-peraturan yang terkait.
b) Pencahayaan Setempat
Rumus pengolahan data pencahayaan setempat adalah sebagai berikut :
Dalam satu titik tempat kerja (objek kerja) dilakukan 3 kali
pembacaan/pengukuran karena angka yang tertera pada alat lux meter
/ light meter berubah-ubah tidak stabil.
Perhitungan rata-rata pencahayaan per titik (objek kerja) :
P1 + P2 + P3 = .... lux
∑P
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 12
Keterangan :
P1 = Pembacaan/pengukuran pertama
P2 = Pembacaan/pengukuran kedua
P3 = Pembacaan/pengukuran ketiga
∑ P = Jumlah pembacaan/pengukuran
Catatan :
1. Hasil dari perhitungan rata-rata pencahayaan per titik (objek kerja)
adalah hasil yang digunakan untuk dibandingkan dengan regulasi yang
dijadikan acuan yaitu peraturan yang terkait.
2. Tentukan kategori ruangan yang dijadikan objek pengukuran agar bisa
menentukan nilai/besaran pencahayaan (lux) yang akan dijadikan
perbandingan dari hasil pengukuran.
Formulir Intensitas penerangan setempat
1. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Jenis Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Jumlah Tenaga Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Ruangan Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Jenis Lampu : ………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tanggal Pengukuan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Denah penerangan setempat
Meja Kerja 1 Meja Kerja 2
Meja Kerja 3 Meja Kerja 4
Meja Kerja 5 Meja Kerja 6
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 13
Hasil Pencatatan Pengukuran penerangan setempat
Hasil (Lux)
Ruangan Rata-rata
Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukran 3
Formulir Intensitas penerangan umum
1. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Jenis Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Jumlah Tenaga Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Ruangan Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Jenis Lampu : ………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tanggal Pengukuan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Denah penerangan umum meter
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 14
Hasil Pencatatan Pengukuran penerangan umum
Hasil (Lux)
Ruangan Pengukuran 1 Pengukuran 2 Pengukran 3 Rata-rata
3.1.3 Pengukuran Intensitas Kebisingan di Tempat Kerja
1. Dasar Teori
Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-
alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat
menimbulkan gangguan pendengaran.
2. Tujuan
Memahami konsep dasar intensitas kebisingan dan melakukan pengukuran
kebisingan dengan Sound Level Meter di lingkungan kerja. Dengan prinsip
kebisingan diterima oleh mikrofon pada sound level meter dan dirubah menjadi
gelombang listrik yang kemudian dibaca pada monitor dalam satuan desibel (dB).
3. Alat
Integrating Sound Level Meter (SLM)
Alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan pada frequensi yang
berbeda-beda dan untuk mengukur intensitas bunyi dengan frequensi
tertentu.
Noise Dosimeter
Merupakan sound level meter yang digunakan untuk mengukur dose
paparan bising hubungan dengan waktu, alat ini di pergunakan
pengukuran kebisingan personal yang diterima oleh pekerja selama 8
jam/hari terutama bagi tenaga kerja yang berpindah-pindah.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 15
4. Penentuan Titik Pengukuran
Pengukuran dengan titik sampling
Pengukuran ini dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas
hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat
dilakukan untuk mengevalusai kebisingan yang disebabkan oleh suatu
peralatan sederhana, misalnya Kompresor/generator. Jarak pengukuran
dari sumber harus dicantumkan, misal 3 meter dari ketinggian 1 meter.
Selain itu juga harus diperhatikan arah mikrofon alat pengukur yang
digunakan.
Pengukuran dengan peta kontur
Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam
mengukur kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar
tentang kondisi kebisingan dalam cakupan area. Pengukuran ini dilakukan
dengan membuat gambar isoplet pada kertas berskala yang sesuai dengan
pengukuran yang dibuat. Biasanya dibuat kode pewarnaan untuk
menggambarkan keadaan kebisingan,
1. warna hijau untuk kebisingan dengan intensitas dibawah 85 dBA,
2. warna orange untuk tingkat kebisingan yang tinggi diatas 90 dBA,
3. warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 85 – 90 dBA.
Pengukuran dengan Grid
Untuk mengukur dengan Grid adalah dengan membuat contoh data
kebisingan pada lokasi yang di inginkan. Titik–titik sampling harus dibuat
dengan jarak interval yang sama diseluruh lokasi. Jadi dalam pengukuran
lokasi dibagi menjadi beberpa kotak yang berukuran dan jarak yang
sama, misalnya : 10 x 10 m. kotak tersebut ditandai dengan baris dan kolom
untuk memudahkan identitas.
5. Nilai Ambang Batas Kebisingan
Nilai ambang Batas Kebisingan adalah angka 85 dB yang dianggap aman untuk
sebagian besar tenaga kerja bila bekerja 8 jam/hari atau 40 jam/minggu. Nilai
Ambang Batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan
merupakan rata-rata yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa
mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 16
tidak lebih dari dari 8 jam sehari atau 40 jam seminggunya. Waktu maksimum
bekerja , bandingkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia (MENAKERTRANS), Nomor : Per.13/MEN/X/2011, Tentang Nilai
Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja.
Waktu pemaparan per hari Intensitas kebisingan dalam dBA
8 Jam 85
4 88
2 91
1 94
30 Menit 97
15 100
7,5 103
3,75 106
1,88 109
0,94 112
28,12 Detik 115
14,06 118
7,03 121
3,52 124
1,76 127
0,88 130
0,44 133
0,22 136
0,11 139
6. Cara Kerja
a. Tentukan lokasi dan titik pengukuran .
b. Tekan tombol on pada sound level meter
c. Tekan tombol Respon (jenis suara) slow / fast.
d. Atur tombol Jaringan A atau C.
e. Baca angka yang tertera pada monitor
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 17
7. Pengolahan Data Intensitas Kebisingan
Pengolahan data pengukuran kebisingan dilakukan dengan menggunakan
Distribusi Frekuensi sebelum dimasukkan kedalam rumus, yaitu menentukan nilai
dengan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1) Array yaitu urutkan dari data yang terkecil sampai dengan data yang
terbesar.
2) Range yaitu cari nilai Range dengan menggunakan menghitung selisih dari
data terbesar dikurangi data terkecil.
Range = Data max. – Data Min.
3) Kelas (K) yaitu mencari banyaknya kelas dengan menggunakan rumus
Sturgess.
K = 1 + 3,3 log n
4) Interval (I) yaitu mencari nilai interval dengan membagi Nilai Range dengan
Nilai Kelas.
I=R/K
5) Kemudian masukkan kedalam Tabel Distribusi Frekuensi
No. Interval Kelas (X) Frekuensi (f) Nilai Tengah (Xi)
1 .................. - .................. ....................... .......................
Banyaknya 2 .................. - .................. ....................... .......................
Kelas ... .................. - .................. ....................... .......................
Dst Dst.
Batas Bawah Batas Atas
Mencari nilai tengah dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan
batas bawah kemudian dibagi 2.
6) Setelah mendapatkan frekuensi dan nilai tengah, kemudian hitunglah
menggunakan rumus sebagai berikut :
Ls = 10 log 1/n Tn.100,1Ln
= 10 log 1/n (T1.100,1L1 + T2.100,1L2 + …. + Tn.100,1Ln)
= 10 log 1/n ( .....................)
= ..........
Keterangan :
Ls = Titik Sampling ke- n
Tn = Frekuensi Kelas ke- n
T1 = Frekuensi Kelas Pertama
T2 = Frekuensi Kelas Kedua
Ln = Nilai Tengah Kelas ke- n
L1 = Nilai Tengah Kelas Pertama
L2 = Nilai Tengah Kelas Kedua
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 18
Urutan perhitungan yang harus dilakukan adalah langkah sebagai berikut :
1) Hitung dahulu 0,1 x Nilai Tengah ke- n
2) Kemudian hitung 10 dipangkatkan dengan hasil dari langkah No. 1
3) Kemudian hitung dengan mengalikan Frekuensi ke-n dengan hasil dari
langkah No.2
4) Kemudian lakukan urutan langkah dari No. 1 sampai dengan langkah No.3
sesuai dengan banyaknya kelas yang di dapat
5) Kemudian jumlahkan hasil dari seluruh banyaknya kelas yang telah dilakukan
proses langkah No.1 – langkah No. 3
6) Kemudian hitung 1/n ,n itu adalah (jumlah banyaknya data)
7) Kemudian hitung hasil dari langkah No.5 dikalikan dengan hasil dari langkah
No.6
8) Kemudian cari nilai log (logaritma) dari hasil langkah No. 7
9) Kemudian yang terakhir adalah kalikan hasil nilai log (logaritma) dari langkah
No.8 dengan (10).
10) Langkah No. 9 adalah hasil akhir yang akan dibandingkan dengan regulasi
(peraturan)
Tabel Distribusi Frekwensi
No. Interval Kelas (X) Frekuensi (f) Nilai Tengah (Xi)
1 .................. - .................. ....................... .......................
2 .................. - .................. ....................... .......................
3 .................. - .................. ....................... .......................
4 .................. - .................. ....................... .......................
5 .................. - .................. ....................... .......................
6 .................. - .................. ....................... .......................
dst
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 19
Formulir Hasil Pengukuran Intensitas Kebisingan di tempat kerja
1. Nama Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Jenis Perusahaan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Alat yang digunakan : ………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Ruangan Kerja : ………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Petugas : ………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Tanggal Pengukuran : ………………………………………………………………………………………………………………………….
No Lokasi Waktu Intenstas Kebisingan Leq
Pengukuran Pengukuran
3.2 Faktor Bahaya Ergonomi
1. Dasar Teori
Untuk merencanakan tempat kerja dan perlengkapannya (meja, kursi, dan
perlengkapan lainnya) diperlukan ukuran-ukuran tubuh yang menjamin sikap
tubuh paling alamiah dan memungkinkan dilakukan gerak-gerakan yang
dibutuhkan. Dimensi tubuh manusia sangat bervariasi antara satu orang dengan
orang lainnya, antara laki-laki dan perempuan dan beberapa suku bangsa.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 20
1. Tujuan
Beberapa ukuran tubuh yang penting untuk penerapan ergonomi ditempat kerja
Posisi Berdiri
Pada posisi berdiri, ukuran-ukuran tubuh yang paling penting adalah tinggi
badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul, depa dan panjang
lengan.
Posisi Duduk
Pada posisi duduk, ukuran-ukuran tubuh yang penting adalah tinggi duduk,
panjang lengan atas, panjang lengan bawah dan tangan, jarak lekuk lutut
dan garis punggung, serta jarak lekuk lutut dan telapak kaki.
2. Alat
Alat ukur tinggi
Meteran kain
Pengaris segitiga
Busur
Lembar pengamatan
3. Cara Kerja
Langkah-langkah dalam melakukan praktikum pengukuran Antropometri
adalah sebagai berikut :
Dengan menggunakan alat-alat yang telah disediakan, ukurlah dimensi-
dimensi tubuh manusia.
Untuk memudahkan pengamatan, gambar antropometri bisa dilihat di
lampiran dengan keterangan sebagai berikut :
4. Pedoman Pengukuran
A. Tinggi tempat duduk
a) Tinggi tempat duduk
Tinggi tempat duduk diukur dari lantai sampai pada permukaan atas
bagian depat alas duduk.
Tinggi alas duduk harus sedikit lebih pendek dari panjang lekuk lutut
sampai ke telapak kaki (tinggi belakang lutut sampai telapak kaki).
Ukuran yang disarankan adalah 38 - 48 cm (tergantung ukuran
antropometri pekerja).
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 21
b) Panjang alas duduk
Diukur dari garis proyeksi permukaan sedepan sandaran duduk
permukaan atas alas duduk.
Harus lebih pendek dari jarak lekuk lutut sampai garis punggung
(jarak dari belakang lutut sampai pantat/tulang ekor).
Ukuran yang disarankan adalah 36cm.
c) Lebar tempat duduk
Diukur pad garis tengah alas duduk melintang.
Harus lebih besar dari lebar pinggul.
Ukuran yang disarankan 40-45cm (Australia)
d) Sandaran pinggang
Bagian atas sandaran pinggang tidak melebihi tepi bawah ujung
tulang belikat dan bagan bawahnya setinggi garis pinggul.
Sandaran pinggang dapat disetel ke atas dan ke bawah dan bergerak
8 - 12 cm di atas alas duduk.
Dalamnya sadaran pinggang adalah 35-38cm dari ujung depan epan
alas duduk
e) Sandaran tangan(bila ada)
Jarak antara tepi dalam kedua sandaran lebih lebar dari lebar
pinggul dan tidak melebihi lebar bahu.
Tinggi sandaran tangan adalah setinggi siku (dalam keadaan duduk).
Panjang sandaran tangan adalah sepanjang lengan bawah.
Ukuran yang di perkenakan adalah:
‡ Jarak antara tepi dalam kedua sandaran tangan adalah 46-48 cm
‡ Tinggi sandaran tangan adalah 20 cm dari alas duduk.
‡ Panjang sandaran tangan adalah 21 cm.
f) Sudut alas duduk
Alas duduk harus sedemikian rupa sehingga memberikan
kemudahan pada pekerjaan untuk melaksanakan pemilihan-
pemilihan gerakan dan posisi.
Alas duduk adalah horisontal.
Sudut kemiringan yang disarankan adalah 3 - 5 derajat.
g) Tinggi meja
Tinggi meja dan bagian bawah alas meja (kolong) harus melebihi dari
tinggi lutut depan.
Tinggi meja tidak melebihi tinggi dada dan tidak lebih rendah dari
tinggi siku pada saat posisi duduk.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 22
B. Komputer
Lokasi peralatan kontrol dan display harus mudah diraih.
Pekerjaan harus memiliki kebebasan bergerak atau merubah posisi.
Gerakan yang repetitif ,sering berlebihan dengan rotasi badan atau
pinggang yang ekstrim harus dihindari.
Posisi layar adalah sedikit di bawah level mata pengguna komputer
Keyboard dan layar terpisah.
Layar dapat diubah sudutnya.
Warna huruf /obyek gelap dengan latar belakang bewarna lebih
terang/kontras.
Jarak mata ke layar sebaiknya sekitar 50 cm - 70 cm.
Jarak mata ke keyboad adalah sekitar 45 cm - 50 cm.
Apabila sudut antar pinggul dan paha lebih dari 90 maka perlu
diberikan penyanggan kaki bagi pekerja.
OSHA (2000) dalam Health & Safety Guidelines For Video Diaplay
Terminal in Workplace, juga menetapkan beberapa kriteria ,antara lain
sebagai berikut :
a. Layar display (monitor)
Karakter (huruf ) tidak boleh berkedip-kedip.
Tulisan dan simbol-simbol tidak boleh kelihatan pecah atau buyar.
Ukuran karakter harus cukup untuk jarak pandang (ANSI/HFS-
100,1988)
Pekerja harus dapat mengatur program untuk meningkatkan
ukuran karakter sehingga mudah dibaca.
Layar harus mempunyai pengatur tingkat keterangan (brightness)
dan kontras dan operator harus mengetahui cara mengaturnya.
Warna background harus kontras dengan warna karakter.
Sisi atas layar tepat atau seikit dibawah posisi pandangan operator.
Jarak pandang adalah 16-29 inch.
b. Keyboards
Harus terlepas dari monitor untuk mendapatkan posisi dan sudut
yang dapat diatur sesuai kebutuhan.
Keyboard harus tipis untuk meminimalkan masalah pada
pergelangan tangan (pegal).
Tuts harus cukup sensitif dan mengeluarkan suara yang tida terlalu
keras.
Permukaan keyboard tumpul.
Keyboard mempunyai alas pergelangan tangan yang tingginya
tidak melebihi tuts baris pertama.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 23
c. Mouse
Tinggi mouse sama dengan tinggi keyboard.
Letak mouse adalah di samping keyboard.
Pada saat meggunakan mouse, lengan harus selalu berada dekat
dengan tubuh.
Lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan usahakan
berada pada satu garis lurus,sedikit tinggi di atas mouse.
d. Document holder
Documen holder harus stabil dan dapat diatur tinggi,jarak dan
sudut pandangnya.
Document holder dapat diletakan disamping layar/monitor atau
antara monitor dan keyboard,sehingga meminimalkan gerakan
kepala dan leher operator.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 24
PENGUKURAN ANTROPOMETRI STATIS/DIMENSI TUBUH
Nama : ……………………………………………… Jenis olahraga yang dilakukan : …………………………………………………
Umur : ……………………………………………… Jumlah jam/minggu : …………………………………………………
Jenis Kelamin : ………………………………………………
Suku Bangsa : ………………………………………………
Berat badan : ……………………………………………..
Tanggal ukur : ……………………………………………..
ANTROPOMETRI STATIS No Data Yang Diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)
1. Tinggi badan tegak. tbt
(Tinggi tubuh posisi tegak
berdiri yaitu : dari lantai
s/d ujung kepala)
2. Tinggi mata berdiri. tmb
(Eye height, Tinggi mata
dalam posisi berdiri tegak)
3. Tinggi bahu berdiri tbhb
4. Tinggi siku berdiri tsb
5. Tinggi panggul berdiri , tpgb
Hip height
6. Tinggi buku tangan berdiri tbtgb
(Knuckle height, Tinggi
buku tangan yang terjulur
lepas dalam posisi berdiri
tegak)
7. Tinggi kepalan tangan tkpltgb
berdiri
(Fingertip height, Tinggi
kepalan tangan yang
terjulur lepas dalam posisi
berdiri tegak)
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 25
ANTROPOMETRI STATIS No Data Yang Diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)
8. Tinggi duduk tegak tdt
(Tinggi tubuh dalam posisi
duduk : dukur dari atas
tempat duduk/pantat
sampai dengan kepala)
9. Tinggi mata duduk. (Tinggi tmd
mata dalam posisi duduk)
10. Tinggi bahu duduk . (Tinggi tbd
bahu dalam posisi duduk)
11. Tinggi siku duduk (Tinggi tsd
siku dalam posisi duduk
(siku tegak lurus)
12. Tebal paha tp
15. Tinggi lutut berdiri. (Tinggi tlb
lutut yang bisa diukur baik
dalam posisi berdiri
ataupun duduk)
16. Tinggi tubuh dalam posisi
duduk yang diukur dari
lantai sampai dengan paha
20. Tebal dada berdiri tdb
ANTROPOMETRI STATIS No Data Yang Diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)
13. Pantat ke lutut pkl
(panjang paha yang diukur
dari pantat sampai dengan
ujung lutut)
14. panjang paha yang diukur pkb
dari pantat sampai dengan
bagian belakang dari
lutut/betis
20 Lebar dari dada dalam ldbng
keadaan membusung
21 Tebal perut duduk tpd
26 Panjang kepala Pk
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 26
ANTROPOMETRI STATIS No Data Yang Diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)
17. Lebar lengan llgn
18. Lebar bahu lb
Lebar dari bahu (bisa
diukur dalam posisi berdiri
ataupun duduk)
19. Lebar pinggul lp
27 Lebar kepala lk
ANTROPOMETRI STATIS No Data Yang Diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)
22 Tinggi siku sampai dengan
bahu
23 Siku ke siku sks
Panjang siku yang diukur
dari siku sampai dengan
ujung jari – jari dalam posisi
siku tegak lurus
35 Jangkauan tangan ke atas
Tinggi jangkauan tangan
dalam posisi duduk tegak,
diukur dari pantat sampai
dengan telapak tangan
yang terjangkau lurus
keatas (vertikal tetapi
dalam posisi duduk)
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 27
ANTROPOMETRI STATIS No Data Yang Diukur Simbol Hasil Pengukuran (cm)
24 Jangkauan tangan ke jtd
depan
Panjang jangkauan tangan
diukur dari bahu sampai
dengan ujung jari tangan
25 Panjang jangkauan tangan,
diukur dari bahu sampai
dengan ujung ibu jari
34 Jangkauan tangan ke atas jta
Tinggi jangkauan tangan
dalam posisi berdiri tegak,
diukur dari lantai sampai
dengan telapak tangan
yang terjangkau lurus
keatas (vertikal)
36 Panjang jangkauan tangan
diukur dari tebal bahu
sampai dengan ujung ibu
jari
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 28
3.3 Faktor Bahaya Kimia
3.3.1 Pengukuran Kadar Debu Total di Udara Tempat Kerja.
1. Dasar Teori
Analisa bahan kimia dalam udara memerlukan beberapa langkah diantaranya
pengukuran kadar debu total di udara tempat kerja secara gravimetri yang
meliputi tahap persiapan, pengambilan contoh, penimbangan dan perhitungan
kadar debu total.
2. Tujuan
Mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran debu di ruang kerja, mengetahui
kadar debu di udara ruang kerja, membandingkan kadar debu dengan standar /
peraturan perundangan dan membuat rencana pengendalian debu di ruang
kerja.
3. Alat
LVS (Low Volume Sampler) atau HVS (High Volume Sample)
Timbangan Analitik
Oven
Pinset
Desikator
Thermohygrometer
4. Cara Kerja
Timbang Kertas saring dengan Analitic Balance (timbangan elektrik)
Keringkan filter dengan menggunakan oven temperature 1000C selama 30
menit, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 15 menit.
Timbang filter kering dengan menggunakan timbangan elektrik dengan
teliti (A)
Masukkan filter kedalam filter holder, rangkaian dengan pompa hisap
Nyalakan pompa dan atur volume udara yang akan dihisap (Flow Rate)
selama 1 jam
Matikan alat, lepas filter holder dan dengan hati-hati keluarkan filter
Keringkan kembali lakukan seperti sebelum ditimbang
Timbang kembali filter (B) dan lakukan penghitungan
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 29
5. Pengolahan data pengukuran kadar debu
Pengolahan data di dalam pengukuran kadar debu total menggunakan rumus
perhitungan sebagai berikut :
Kadar Debu Total = W2 – W1
Q x t
Keterangan :
W2 = Berat kertas saring setelah pengukuran
W1 = Berat kertas saring sebelum pengukuran
t = Lamanya waktu pengukuran yang digunakan
Q = Tekanan (daya hisap) pompa yang digunakan
Catatan :
1. Lamanya waktu pengukuran yang digunakan berbeda tergantung
dari alat ukur yang digunakan, HVS (High Volume Sample) atau LVS
(Low Volume Sample). Untuk pengukuran yang menggunakan alat
HVS lamanya waktu pengukuran adalah 30 menit, sedangkan
pengukuran yang menggunakan alat LVS lama waktu pengukuran
adalah 60 menit.
2. Tekanan (daya hisap) pompa yang digunakan berbeda tergantung
dari alat ukur yang digunakan, HVS (High Volume Sample) atau LVS
(Low Volume Sample). Untuk pengukuran yang menggunakan alat
HVS tekanan yang digunakan dalam satuan m3/menit, sedangkan
pengukuran yang menggunakan alat LVS tekanan yang digunakan
dalam satuan liter/menit.
3. Lakukan konversi hasil dari berat kertas saring dari gram (g) menjadi
miligram (mg) dan konversikan juga tekanan (daya hisap) alat LVS
dari liter/menit menjadi m3/menit terlebih dahulu, karena satuan
yang dipakai pada NAB adalah mg/m3.
1 gram = 1000 mg
1 liter/menit = 10-3 atau 0,001 m 3/menit
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 30
RUMUS PERHITUNGAN KADAR DEBU BERDASARKAN SNI 16-7058-2004
(W2 - W1) - (B2 - B1)
C = ----------------------------------- (mg/l)
V
Atau
( W2 - W1 ) - ( B2 - B1 )
C = ----------------------------------- x 103 (mg/m3)
V
Keterangan :
C = kadar debu total (mg/l) atau (mg/ m3);
W2 = berat filter contoh setelah pengambilan contoh (mg);
W1 = berat filter contoh sebelum pengambilan contoh (mg);
B2 = berat filter blanko setelah pengambilan contoh (mg);
B1 = berat filter blanko sebelum pengambilan contoh (mg);
V = volume udara pada waktu pengambilan contoh (l) atau (m3).
Formulir pengukuran kadar debu total di udara tempat kerja
Nama perusahaan :..........................................
Alamat perusahaan :..........................................
Jenis perusahaan :..........................................
Tanggal pengukuran :..........................................
Data pengukuran kadar debu total di udara tempat kerja
Waktu
Lokasi Nomor Flowrate SK RH Keterangan
No Pengukuran
Pengukuran Filter (l/menit) (ºC) (%)
(menit)
CATATAN Pengukuran suhu dan kelembaban adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan saat
pengambilan contoh.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 31
3.4Faktor Bahaya Psikososial
3.4.1 Kelelahan Kerja di tempat kerja
1. Dasar Teori
Kata Kelelahan menunjukkan keadaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya
berakibat kepada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh. Terdapat
dua jenis kelelahan yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot
merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri yang terdapat pada otot.
Kelelahan umum ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang
sebabnya adalah persyaratan atau psikis (Suma’mur).
2. Tujuaan
Tujuan ada dua yaitu :
Kerja otot dinamis, yaitu kerja otot yang rythmis dan berirama, dimana
pengerutan dan pengendoran terjadi silih berganti, bekerja sebagai pompa
peredaran darah, berjalan sesuai dengan tingkat kontraksi otot.
Kerja otot statis, yaitu kerja otot yang menetap untuk periode tertentu
secara kontinyu, dimana pembuluh darah akan tertekan dan peredaran
darah berkurang, sehingga otot tubuh merasa sakit dan mudah lelah.
3. Permeriksaan kelelahan secara subyektif
a). Penilaian secara subyektif (Industrial Fatique Research Committee/IFRC : dari Jepang)
Kuesioner kelelahan 30 item/daftar pertanyaan
Pertanyaan :
No Urut 1 s/d 10 = Pertanyaan tentang pelemahan kegiatan
No Urut 11 s/d 20 = Pertanyaan tentang pelemahan motivasi
No Urut 21 s/d 30 = Pertanyaan tentang pelemahan fisik
Cara pengisian
Contoh desain penilaian kelelahan kerja subyektif dengan 4 skala
likert,dimana :
Skor – 1 = tidak pernah merasakan
Skor – 2 = kadang-kadang merasakan
Skor – 3 = sering merasakan
Skor – 4 = sering sekali merasakan
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 32
b). Klasifikasi tingkat kelelahan subyektif berdasarkan total skor individu
Penentuan Interval
C = Xn – Xi
K
Keterangan:
K(kelas) = 4 (rendah,sedang,tinggi, dan sangat tinggi)
Xn = 4 x 30
Xi = 1 x 30
Interval = (4 x 30) – (1 x 30)
4
= 120 – 30
4
= 22
Tingkat Total Skor Klasifikasi
Tindakan Perbaikan
Kelelahan Individu Kelelahan
1 30 – 52 Rendah Belum diperlukan tindakan
perbaikan
Mungkin diperlukan tindakan
2 53 – 75 Sedang
kemudian hari
3 76 – 98 Tinggi Diperlukan tindakan segera
4 99 – 120 Sangat Tinggi Diperlukan tindakan
menyeluruh sesegera mungkin
Pedoman diatas merupakan pedoman sederhana untuk menentukan klasifikasi
kelelahan subyektif
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 33
Nama tenaga kerja Tanggal tes
Bagian Jenis kelamin L/P
Shift kerja Umur Tahun
Masa kerja Bulan/tahun Berat badan Kg
Petugas/paraf Tinggi badan Cm
Pertanyaan tentang pelemahan Skoring
No
Kegiatan, Motivasai, dan Fisik 1 2 3 4
1 Perasaan berat di kepala
2 Menjadi Lelah seluruh badan
3 Kaki merasa berat
4 Menguap
5 Merasa kacau pikiran
6 Menjadi mengantuk
7 Merasakan beban pada mata
8 Kaku dan canggung dalam gerakan
9 Tidak seimbang dalam berdiri
10 Mau berbaring
11 Merasa susah berpikir
12 Lelah untuk berbicara
13 Menjadi gugup
14 Tidak dapat berkonsentrasi
15 Sulit memusatkan perhatian
16 Mudah Lupa
17 Kurang Kepercahaya diri
18 Merasa Cemas
19 Sulit mengontrol sikap
20 Tidak tekun dalam kerja
21 Tidak dapat tekun dalam pekerjaan
22 Sakit di kepala
23 Kaku di bahu
24 Nyeri di punggung
25 Sesak napas
26 Haus
27 Suara serak
28 Merasa pening
29 Tremor pada anggota badan
30 Merasa Kurang sehat
Jumlah skor pada kolom 1,2,3,dan 4
Total skor strees individu
Langkah:
1. Hitunglah jumlah skor pada masing-masing kolom(1,2,3 dan 4) dari 30
pernyataan di atas.
2. Kemudian Jumlahkan masing-masing hasil jumlah skor kolom 1,2,3, dan 4.
3. Kemudian hasil penjumlahan tersebut dimasukan kedalam klasifikasi
kelelahan yang ada yaitu termasuk kelelahan rendah,sedang,tinggi dan sangat
tinggi(skor terendah 30 dan skor tertingi 120).
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 34
3.4.2 Stress Kerja
1. Dasar Teori
Stress akibat kerja merupakan gangguan fisik dan emosional sebagai akibat
ketidak sesuaian antara kapabilitas, sumber daya atau kebutuhan pekerja yang
berasal dari lingkungan pekerjaan. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya stress
karena beban kerja yang tidak sesuai, buruknya lingkungan sosial, konflik yang
terjadi, lingkungan kerja yang berbahaya. Kondisi tempat kerja yang tidak
nyaman tersebut menjadi peranan yang penting dalam menyebabkan terjadinya
stress kerja. Padahal stress kerja secara langsung dapat mempengaruhi
keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini dikarenakan stress kerja dapat
memicu terjadinya gangguan kesehatan bahkan terjadinya kecelakaan kerja.
2. Tujuan
Mengidentifikasi faktor – faktor stress kerja : lingkungan organisasi ( TuntutanTugas,
tuntutan Peran, tuntutan sosial, struktur organisasi, Kepemimpinan, dan
pengembangan organisasi ), Individu (masalah dalam keluarga,masalah ekonomi
keluarga)
Cara cepat untuk mendeteksi stress kerja
Nama tenaga kerja Tanggal tes
Bagian Jenis kelamin L/P
Shift kerja Umur Tahun
Masa kerja Bulan/tahun Pendidikan
Petugas/paraf Jabatan
NO PERTANYAAN YA TIDAK
1 Saya tidak mempunyai waktu untuk melakukan hobi atau
kegiatan lain di luar pekerjaan
2 Saya sering membawa pekerjaan ke rumah dan mengerjakannya
pada malam hari
3 Saya tidak dapat melakukan pekerjaan atau tugas sebaik biasanya
. Kadang-kadang saya merasa penilaian saya kabur dan tidak
sebaik biasanya
4 Kelihatannya pada hari kerja saya tidak tersedia cukup waktu
untuk mengerjakan semua hal yang harus saya kerjakan
5 Saya sering merasa tidak sabar dengan kecepatan kerja yang ada
6 Kadang-kadang saya sangat enggan pergi kerja
7 Saya coba menyelesaikan tugas banyak dalam waktu yang lebih
sedikit. Hal ini kadang-kadang mengakibatkan saya tidak
mempunyai waktu lagi untuk mengatasi masalah – masalah yang
timbul tak terduga
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 35
NO PERTANYAAN YA TIDAK
8 Nafsu makan saya berubah.Kadang-kadang saya ingin
kudapan/ngemil terutama makan yang manis-manis, atau kadang-
kadang saya malah kehilangan nafsu makan
9 Saya merasa terlalu banyak tenggang waktu yang harus dipenuhi
baik dalam pekerjaan ataupun dalam hidup saya,yang sulit untuk
dipenuhi.
10 Kadang – kadang saya merasa marah dan kesal pada sesuatu yang
tidak jelas atau merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, tetapi saya
tidak tahu apa yang hilang itu
11 Rasa percaya diri fan kepuasan diri saya lebih rendah dari biasanya.
12 Saya sering kali mempunyai sedikit perasaan bersalah jika saya
relaks dan tidak mengerjakan sesuatu meskipun dalam waktu
sebentar saja
13 Saya sering berfikir tentang masalah pribadi,bisnis atau kehidupan
professional saya yang harus saya kerjakan.Masalah-masalah
tersebut seringkali mengganggu pikiran saya pada saat saya sedang
menikmati aktivitas rekreasi
14 Kadang-kadang saya merasa sangat kelelahan.Saya juga meraskan
kelelahan itu disaaat saya bangun tidur
15 Saya mencoba mengajak orang lain untuk cepat-cepat
mengerjakan tugasnya. Semua orang kelihataannya bergerak
terlalu lamban.
16 Kadang –kadang saya menyela dan menyelesaikan kalimat orang
lain
17 Walau saya kelihatan sedang mendengarkan pembicaraan orang
lain,tapi sebenernya saya sedang sibuk dengan pikiran saya sendiri
18 Saya mempunyai kecenderungan untuk makan,
berbicara,bergerak,berjalan dan mengerjakan hamper segala
sesuatunya dengan cepat
19 Saya merasa sangat sakit dan nyeri, terutama pada leher atau
kepala,dada,punggung bawah, bahu dan rahang.(pada wanita:
siklus menstruasi seringakali tidak teratur)
20 Saya menja marah dan meradang jika mobil atau lalu lintas
didepan saya bergerak terlalu lambat. Saya merasa perustasi jika
sedang mengantri.
21 Kadang – kadang saya merasa desfresi, mudah tersinggung,mudah
terluka, cepat marah, tegang, ceroboh,daya ingat dan konsentrasi
terganggu. Kadang- kadang saya berkeringat berlebihan .
22 Gairah sex yang menurun , atau saya merasa tihdak puas pada
kehidupan sexual saya.
23 Saat mengerjakan tugas rutin, saya menjadi tidak sabar.
24 Saya menggertakan gigi saya , terutama jika saya merasa stress
atau tidak sabar.
25 Saya mempunyai ketergantungan yang besar pada
alcohol,rokok,kopi,atau obat-obatan (baik obat resep atau obat
bebas).
Sumber : Suicide and material health association international 2004-2006
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 36
3. Interprestasi hasil tes
a) Nilai 4
Anda tidak dalam keadaan stress akibat kerja dan tidak mudah dan
kemungkinan kecil untuk menjadi stress akibat kerja.
b) Nilai 5 – 13
Anda cenderung untuk mendapat stress akibat kerja dan menderita efek
negative dan stress kerja. Anda sebaiknya melakukan pengendalian tergadap
stress dan mengikuti konseling.
c) Nilai ≥ 14
Anda sangat mudah kena stress akibat kerja dan dampak negatifnya. Dan
harus secepatnya mengatasi hal tersebut segera konsultasi ke dokter dan
mencari konselor yang ahli dalam manajemen stress.
Keterangan :
Bila jawaban responden “ya” bernilai 1 sedangkan jawaban responden “tidak”
bernilai 0
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 37
Daftar Pustaka
1. SNI (Standar Nasional Indonesia) 16-7061-2004 Pengukuran Iklim Kerja (panas)
dengan parameter Indeks Suhu Basah dan Bola. (ICS 17.200.10 Badan Standar
Nasional / BSN)
2. SNI (Standar Nasional Indonesia) 16-7058-2004 Pengukuran kadar debu total di
udara tempat kerja. (ICS 17.060 Badan Standar Nasional / BSN)
3. SNI (Standar Nasional Indonesia) 16-7062-2004 Pengukuran intensitas penerangan di
tempat kerja (ICS 17.180.20 Badan Standar Nasional / BSN)
4. SNI (Standar Nasional Indonesia) 16-7231-2009 Metode pengukuran intensitas
kebisingan di tempat kerja (ICS 13.140 Badan Standar Nasional / BSN)
5. SNI (Standar Nasional Indonesia) 7269-2009 Penilaioan beban kerja berdasarkan
tingkat kebutuhan kalori menurut pengeluaran energi (ICS 13.100 Badan Standar
Nasional / BSN)
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
(Permenakertrans) Nomor Per.13.MEN/X/2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor
Fisika dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor :
1405/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Perkantoran dan Industri.
8. Sumadi, SKM.,MM, Laboratorium Keselamatan dan Kesehatan KerJa (K3)
9. Kuat Prabowo, SKM.,M.Kes, Mata Kuliah IKL 3901 Hyperkes II , Ergonomi dan
Biomekanika .
10. Nurmianto, Eko, 1996, Ergonomi Konsep Dasar dan Aplikasinya Edisi Pertama, Jurusan
Teknik Industri ITS, PT. Candimas Metropole, Jakarta.
11. Suma’mur PK, Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, PT Gunung Agung, Jakarta.
12. Rachman A, dkk, Pedoman Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja, Depkes RI
Jakarta, 1990
13. Harrington & Gill F.S, Buku Saku Kesehatan Kerja, EGC,2005
14. OSHA (2000), Health & Safety Guidelines For Video Diaplay Terminal in Workplace.
15. National Institute Ocupational Safety and Health (NIOSH) U.S Department of Health,
Education, and welfare Public Health Service.Center for Disease Control, 1977.
16. Subjective Self Rating Test dari Industrial Fatigue Research Committee (IFRC) Jepang
17. Suicide and Material Health Association International 2004-2006
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 38
FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM
1. Judul
Jenis pengukuran yang dilakukan.
2. Tujuan
Tujuan dari dilakukannya pengukuran tersebut.
3. Manfaat
Manfaat bagi mahasiswa dan pekerja yang tempat kerjanya dilakukan
pengukuran.
4. Tinjauan Pustaka
Pustaka yang mendukung isi pembahasan dari hasil praktikum, berisi teori
dan peraturan yang mendukungnya.
5. Alat dan Bahan
Peralatan dan bahan yang digunakan pada saat melakukan praktikum.
6. Cara Kerja
Cara kerja pada saat melakukan praktikum, hal-hal yang di ukur dan
diamati pada saat pengukuran.
7. Hasil
Data hasil pengukuran yang telah dilakukan pengolahan.
8. Pembahasan
Pembahasan hasil pengolahan data, dibandingkan dengan teori atau
peraturan yang ada.
9. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari hasil yang telah di analisis serta saran yang dapat dilakukan
untuk tindakan perbaikan.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 39
SOAL LATIHAN
1. TEKANAN PANAS
Sebuah perusahaan textile melakukan kegiatan identifikasi bahaya fisik rutin
terkhusus kepada masalah tekanan panas yang ada pada bagian spinning.
Pengukuran dilakukan menggunakan alat pengukur tekanan panas manual
berupa termometer suhu basah alami, termometer suhu kering, dan termometer
suhu bola yang dirakit pada satu rangkaian statif. Waktu pengukuran dibagi
kedalam 3 kali pengukuran selama 8 jam kerja yaitu awal shift kerja sekitar jam
08.30 WIB, pertengahan kerja sekitar jam 11.30 WIB, dan akhir shift kerja sekitar
jam 14.30 WIB. Lama pemaparan tekanan panas yang dilakukan tiap-tiap waktu
adalah 30 menit.
Dari pengukuran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Awal Kerja : SBA = 28 0C, SB = 29 0C, dan SK = 30 0C
2) Pertengahan Kerja : SBA = 29 0C, SB = 31 0C, dan SK = 30 0C
3) Akhir Kerja : SBA = 29 0C, SB = 30 0C, dan SK = 31 0C
Hitunglah ISBB rata-rata di dalam ruangan spinning tersebut, jika beban kerjanya
termasuk beban kerja sedang dan waktu kerjanya 75-100%. Kemudian
lakukan pembahasan hasil ISBB rata-rata yang didapat dibandingkan dengan
regulasi yang digunakan yaitu PERMENAKER No. 13 Tahun 2011 tentang
NAB faktor fisik dan kimia.
2. KEBISINGAN
Sebuah perusahaan manufacture melakukan kegiatan identifikasi bahaya fisik
rutin terkhusus kepada masalah kebisingan yang ada pada bagian Chucking
Machine. Pengukuran dilakukan menggunakan Sound Level Meter. Titik
pengukuran dibagi kedalam 3 titik sampling dimana ada aktvitas dari si pekerja.
Lama pengukuran kebisingan yang dilakukan adalah 5 menit yang di ambil
datanya setiap 1 menit/5 detik.
Dari pengukuran tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :
1) Titik Pertama :
95, 93, 92, 88, 87, 93, 91, 90, 87, 89, 90, 88, 89, 86, 90, 88, 87, 89, 90, 88
88, 87, 85, 84, 88, 89, 94, 86, 91, 90, 88, 85, 84, 87, 89, 90, 87, 86, 91, 95
89, 92, 88, 86, 84, 86, 91, 93, 89, 95, 84, 86, 87, 85, 84, 86, 89, 92, 88, 91
2) Titik Kedua :
93, 90, 87, 86, 84, 85, 82, 86, 87, 89, 88, 92, 88, 85, 93, 86, 89, 85, 82, 85
88, 87, 89, 93, 86, 88, 87, 86, 85, 82, 88, 90, 86, 87, 91, 86, 87, 92, 87, 84
86, 91, 87, 93, 84, 82, 86, 90, 86, 92, 87, 90, 87, 85, 82, 86, 89, 93, 88, 86
3) Titik Ketiga :
91, 86, 84, 89, 87, 85, 80, 82, 80, 85, 88, 90, 84, 85, 87, 91, 86, 88, 85, 84
89, 86, 83, 81, 85, 90, 87, 89, 86, 84, 85, 89, 90, 87, 91, 86, 87, 84, 80, 81
85, 88, 87, 90, 87, 91, 87, 85, 83, 86, 87, 90, 86, 83, 82, 86, 85, 80, 84, 86
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 40
Hitunglah kebisingan masing-masing titik di bagian Chuncking Machine tersebut.
Kemudian lakukan pembahasan hasil yang didapat dibandingkan dengan regulasi
yang digunakan yaitu PERMENAKER No. 13 Tahun 2011 tentang NAB
faktor fisik dan kimia.
3. PENCAHAYAAN
Sebuah perusahaan melakukan kegiatan identifikasi bahaya fisik rutin terkhusus
kepada masalah pencahayaan yang ada pada ruangan administrasi. Pengukuran
dilakukan menggunakan lux meter dan di ukur dengan metode pengukuran
pencahayaan umum dan setempat. Waktu pengukuran dilakukan pada pagi hari
sekitar jam 09.00 WIB. Cahaya yang ada di dalam ruangan adalah hanya cahaya
buatan yang bersumber dari lampu TL/neon. Luas ruangan adalah 60m2 sehingga
diperoleh 6 titik pengukuran di setiap 3x3 meter. Di dalam ruangan ada 4 meja
kerja yaitu meja kerja Pak Wanda, Pak Tono, Ibu Sri, dan Ibu Kiki.
Dari pengukuran pencahayaan umum diperoleh hasil sebagai berikut :
Titik 1 = 98 lux, 110 lux, 107 lux
Titik 2 = 100 lux, 103 lux, 99 lux
Titik 3 = 102 lux, 92 lux, 90 lux
Titik 4 = 100 lux, 90 lux, 93 lux
Titik 5 = 107 lux, 112 lux, 115 lux
Titik 6 = 108 lux, 99 lux, 103 lux
Dari pengukuran pencahayaan setempat diperoleh hasil sebagai berikut :
Meja Pak Wanda = 90 lux, 85 lux, 92 lux
Meja Pak Tono = 100 llux, 98 lux, 103 lux
Meja Ibu Sri = 98 lux, 105 lux, 100 lux
Meja Ibu Kiki = 89 lux, 85 lux, 86 lux
Hitunglah pencahayaan secara umum dan setempat dari ruangan administrasi
tersebut menggunakan rumus yang sesuai dengan tipe pengukuran pencahayan
yang digunakan. Kemudian lakukan pembahasan hasil yang di dapat secara
umum dan setempat dibandingkan dengan regulasi yang dijadikan acuan yaitu
Kepmenkes 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri.
4. DEBU
Sebuah perusahaan melakukan kegiatan identifikasi bahaya fisik rutin terkhusus
kepada masalah kadar debu total yang ada pada ruangan produksi. Pengukuran
dilakukan menggunakan HVS (High Volume Sample) untuk bagian Cold Forming.
Waktu pengukuran dilakukan pada 3 kali yaitu pada pagi hari sekitar jam 09.00
WIB, siang hari jam 12.00 WIB, dan Sore hari jam 15.00 WIB.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 41
Dari pengukuran menggunakan LVS (Low Volume Sample) diperoleh
hasil sebagai berikut :
1. Pagi Hari
W1 = 0,09562 g
W2 = 0,09570 g
t = 60 menit
V = 10 liter/menit
2. Siang Hari
W1 = 0,09551 g
W2 = 0,09561 g
t = 60 menit
V = 10 liter/menit
3. Sore Hari
W1 = 0,09557 g
W2 = 0,09568 g
t = 60 menit
V = 10 liter/menit
Hitunglah kadar debu total dari alat LVS diruangan Cold Forming tersebut.
Kemudian lakukan pembahasan hasil yang di dapat secara umum dan setempat
dibandingkan dengan regulasi yang dijadikan acuan yaitu Kepmenkes 1405
Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja
Perkantoran dan Industri.
Buku Pedoman Praktik Dasar-dasar K3 Jurusan Kesehatan Lingkungan 42
Anda mungkin juga menyukai
- Tugas K3 Industri KecilDokumen35 halamanTugas K3 Industri KecilRiani DwianasariBelum ada peringkat
- Buku Pedoman Praktek Kawasan K3 D4 2017Dokumen27 halamanBuku Pedoman Praktek Kawasan K3 D4 2017Rani SelviaBelum ada peringkat
- Konsep Surveilans K3Dokumen14 halamanKonsep Surveilans K3Rabiatul AdhwiyahBelum ada peringkat
- Reacktion TimerDokumen5 halamanReacktion TimerJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Tugas Individu Promosi EvauasiDokumen20 halamanTugas Individu Promosi EvauasiNur Indah LBelum ada peringkat
- Modul Kuliah K3Dokumen29 halamanModul Kuliah K3Mardiana SkmBelum ada peringkat
- Gizi Kerja Dan Penyelenggaraan MakananDokumen20 halamanGizi Kerja Dan Penyelenggaraan MakananrizkiBelum ada peringkat
- SMK3Dokumen75 halamanSMK3guinevere_honey100% (2)
- Contoh Laporan magang-PENERAPAN METODE HIRARCDokumen190 halamanContoh Laporan magang-PENERAPAN METODE HIRARCBunda QeisBelum ada peringkat
- Ruang Lingkup Kesling IndustriDokumen36 halamanRuang Lingkup Kesling IndustriNabilaaaBelum ada peringkat
- k3 Industri Kecil (Kelompok 3)Dokumen21 halamank3 Industri Kecil (Kelompok 3)Dine NadineBelum ada peringkat
- Perbedaan ISO 45001 Dan Ohsas 18001Dokumen5 halamanPerbedaan ISO 45001 Dan Ohsas 18001muhammad farhanBelum ada peringkat
- BRP Risiko Dan Biaya K3Dokumen21 halamanBRP Risiko Dan Biaya K3DEDI CHANDRABelum ada peringkat
- 1.konsep ErgonomiDokumen28 halaman1.konsep Ergonomiisna lailatunBelum ada peringkat
- K3 PestisidaDokumen27 halamanK3 PestisidaHandyta Anindyasarathi0% (1)
- SEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI INDUSTRI (Cover)Dokumen4 halamanSEJARAH PERKEMBANGAN PSIKOLOGI INDUSTRI (Cover)Setya Wiguna MBelum ada peringkat
- Aplikasi Ergonomi Untuk Pengaman MesinDokumen13 halamanAplikasi Ergonomi Untuk Pengaman MesinBela Sendita RusmanBelum ada peringkat
- Sejarah K3Dokumen14 halamanSejarah K3ayu prima kartika100% (1)
- Laporan PKL KLP 3 Batch 3Dokumen6 halamanLaporan PKL KLP 3 Batch 3DinoHarjoBelum ada peringkat
- Pelaksanaan Rencana K3Dokumen44 halamanPelaksanaan Rencana K3rachmatsulaeman03Belum ada peringkat
- Baiq Dewi Asma Susilawati-20282126-Laporan Magang K3Dokumen18 halamanBaiq Dewi Asma Susilawati-20282126-Laporan Magang K3amrullah megaBelum ada peringkat
- 8.promosi K3Dokumen13 halaman8.promosi K3Ismi IstiqamahBelum ada peringkat
- K3Dokumen5 halamanK3whidiarthaBelum ada peringkat
- Contoh Laporan Praktikum Pengukuran AntropometriDokumen5 halamanContoh Laporan Praktikum Pengukuran AntropometriHahmad Al-paseriBelum ada peringkat
- Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (k3)Dokumen37 halamanKeselamatan Dan Kesehatan Kerja (k3)Luluk QomariyahBelum ada peringkat
- Laporan PKMDokumen64 halamanLaporan PKMFahmi HidayatBelum ada peringkat
- Soal Gizi KerjaDokumen6 halamanSoal Gizi KerjaHalka MusicBelum ada peringkat
- Human Diversity-ErgonDokumen30 halamanHuman Diversity-ErgonCasey Puspa AvriliantoroBelum ada peringkat
- Potensial Hazard Di Lingkungan PertanianDokumen17 halamanPotensial Hazard Di Lingkungan PertanianSaga SabaraBelum ada peringkat
- Perilaku K3Dokumen33 halamanPerilaku K3dwi pranandaBelum ada peringkat
- #1-Hirarki Peraturan Perundangan K3Dokumen12 halaman#1-Hirarki Peraturan Perundangan K3Gazza ayuBelum ada peringkat
- Hygiene Lingkungan KerjaDokumen20 halamanHygiene Lingkungan KerjaAdhinningtyas RachmawatiBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen22 halamanBab 2Rudy FahleviBelum ada peringkat
- Surveilans Kecelakaan Kerja - Kecelakaan Kerja Dan CederaDokumen21 halamanSurveilans Kecelakaan Kerja - Kecelakaan Kerja Dan CederaNessia Rachma100% (1)
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja PDFDokumen19 halamanPermenaker No. 5 Tahun 2018 Tentang K3 Lingkungan Kerja PDFAyu AdheriskaaBelum ada peringkat
- Iso 45001 - Kel 5 - AiDokumen16 halamanIso 45001 - Kel 5 - Aiiin kristalinBelum ada peringkat
- Teknik MultivotingDokumen6 halamanTeknik MultivotingINSTALASI KESLING & K3 RSUD SEKARWANGIBelum ada peringkat
- MODUL MI 2.f - Pemb. ErgonomiDokumen18 halamanMODUL MI 2.f - Pemb. ErgonomiMuh JafarBelum ada peringkat
- k3rs PsDokumen41 halamank3rs PsAnonymous jYVGA4jBelum ada peringkat
- Faal ErgonomiDokumen13 halamanFaal ErgonomiDominic Lovian TorettoBelum ada peringkat
- Higiene IndustriDokumen200 halamanHigiene Industrisujidah100% (2)
- Jurnal Analisis k3 Industri Tahu 3Dokumen11 halamanJurnal Analisis k3 Industri Tahu 3rahayuBelum ada peringkat
- Risk AssessmentDokumen18 halamanRisk AssessmentRiri100% (1)
- Analisis Swot Pada Pejerja LaundryDokumen13 halamanAnalisis Swot Pada Pejerja LaundryTryani WalnizamBelum ada peringkat
- UEU Surveilens Kesehatan Kerja Pertemuan 2Dokumen20 halamanUEU Surveilens Kesehatan Kerja Pertemuan 2sertakao sullivanBelum ada peringkat
- Makalah Promosi K3Dokumen20 halamanMakalah Promosi K3sofy dewiBelum ada peringkat
- Toksikologi IndustriDokumen75 halamanToksikologi IndustriAngga ProgrestBelum ada peringkat
- RM - Menentukan Fokus MasalahDokumen13 halamanRM - Menentukan Fokus Masalahhally zahra100% (1)
- BAB II ToksikologiDokumen10 halamanBAB II ToksikologiArdy Avriansyah MadjidBelum ada peringkat
- Kesehatan KerjaDokumen51 halamanKesehatan KerjaDoviFebrina100% (1)
- Pengawasan Norma SMK3Dokumen38 halamanPengawasan Norma SMK3raisa hukmiBelum ada peringkat
- Pemahaman Dasar SMK3 PP No.50 Tahun 2012 (Part 1 For Peserta)Dokumen34 halamanPemahaman Dasar SMK3 PP No.50 Tahun 2012 (Part 1 For Peserta)Tatak Bay Ahmed100% (1)
- MakalahDokumen14 halamanMakalahAdindaBelum ada peringkat
- Faktor Biologi Higiene IndustriDokumen3 halamanFaktor Biologi Higiene IndustriRasmawati Ridwan100% (1)
- Modul 6. Higiene PerusahaanDokumen46 halamanModul 6. Higiene Perusahaanilasdalimunthe100% (1)
- Faktor Bahaya Lingkungan KerjaDokumen49 halamanFaktor Bahaya Lingkungan KerjaSilvia Kumala DewiBelum ada peringkat
- Kapasitas KerjaDokumen7 halamanKapasitas Kerjaintan wahyuni100% (2)
- Siti Marwa - Mid - Bahasa IndonesiaDokumen19 halamanSiti Marwa - Mid - Bahasa IndonesiaLAODE MIDSYAMBelum ada peringkat
- Pedoman K3 Laboratorium-Teknik TekstilDokumen54 halamanPedoman K3 Laboratorium-Teknik Tekstilumamkhairul0% (1)
- SOAL UJIAN UAS LAB.K3 (KLAS KHUSUS) UMJ Sabtu, 19-Nop.'22.Dokumen13 halamanSOAL UJIAN UAS LAB.K3 (KLAS KHUSUS) UMJ Sabtu, 19-Nop.'22.muhammad ighfirliBelum ada peringkat
- KebisinganDokumen10 halamanKebisinganJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Penentuan Titik Pengukuran Kebisingan LingkunganDokumen5 halamanPenentuan Titik Pengukuran Kebisingan LingkunganJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Noise Dosimeter Dan Vibration MeterDokumen2 halamanNoise Dosimeter Dan Vibration MeterJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Prosedur Pengukuran KEBISINGANDokumen2 halamanProsedur Pengukuran KEBISINGANJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Alur Pembuatan Video Untuk Praktikum 2020Dokumen1 halamanAlur Pembuatan Video Untuk Praktikum 2020Joshua RobbinsBelum ada peringkat
- Cara Pengukuran IsbbDokumen2 halamanCara Pengukuran IsbbJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- AUDIOMETRIDokumen4 halamanAUDIOMETRIJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- PROSEDUR KERJA Tekanan PanasDokumen2 halamanPROSEDUR KERJA Tekanan PanasJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Tata Cara Menggunakan Lux MeterDokumen1 halamanTata Cara Menggunakan Lux MeterJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- SOP Mikrobilogical Air Sampler-1Dokumen2 halamanSOP Mikrobilogical Air Sampler-1Joshua RobbinsBelum ada peringkat
- Vibration MeterDokumen3 halamanVibration MeterJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- SDL800Dokumen8 halamanSDL800Joshua RobbinsBelum ada peringkat
- Cara Pengukuran NOISE DOSE METERDokumen3 halamanCara Pengukuran NOISE DOSE METERJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Pencahayaan Di Tempat KerjaDokumen9 halamanPencahayaan Di Tempat KerjaJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Contoh MSDS 1Dokumen62 halamanContoh MSDS 1Joshua RobbinsBelum ada peringkat
- ISPUDokumen15 halamanISPUJoshua RobbinsBelum ada peringkat
- Noise Dose Meter 1Dokumen15 halamanNoise Dose Meter 1Joshua RobbinsBelum ada peringkat
- Form Penilaian Sanitasi Rumah SakitDokumen3 halamanForm Penilaian Sanitasi Rumah SakitJoshua RobbinsBelum ada peringkat