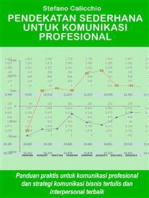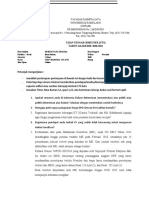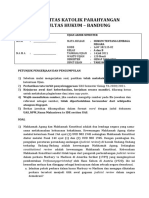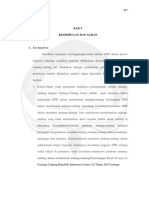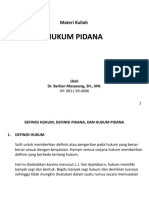Dua Cara Agar Putusan Mahkamah Konstitusi Selalu Dipatuhi
Diunggah oleh
Budy AryantoJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Dua Cara Agar Putusan Mahkamah Konstitusi Selalu Dipatuhi
Diunggah oleh
Budy AryantoHak Cipta:
Format Tersedia
Menu Masuk
Dua cara agar putusan
Mahkamah Konstitusi
selalu dipatuhi
Diterbitkan: Maret 27, 2020 12.13pm WIB
Antoni Putra, Indonesian Center for Law and Policy Studies
(PSHK)
Bagus Indahono/EPA
Akhir Januari lalu, Ketua Mahkamah
Konstitusi (MK) Anwar Usman
mengungkapkan kekhawatirannya
terhadap kondisi sistem peradilan
konstitusi karena banyak putusan MK yang
tidak dipatuhi.
Penelitian yang dilakukan lewat kerja sama
antara MK dan Fakultas Hukum Universitas
Trisakti menunjukkan bahwa antara 2013
dan 2018, dari total 109 putusan MK,
terdapat 24 putusan (22%) yang tidak
dipatuhi sama sekali.
Penelitian itu juga menemukan bahwa
enam putusan (5.5%) hanya dipatuhi
sebagian. Hanya 59 putusan (54.1%) saja
yang dipatuhi seluruhnya, serta sisanya 20
putusan belum dapat diidentifikasi dengan
jelas.
Untuk memastikan putusan MK dipatuhi
ada dua hal yang bisa dilakukan. Sanksi
perlu dibuat bagi subjek yang tidak
melaksanakan putusan MK. Putusan MK
juga perlu diperkuat kedudukannya dalam
hierarki perundang-undangan.
Dapatkan catatan mingguan
tentang isu penting politik dan
masyarakat.
Daftar sekarang
Baca juga: Mengapa peradilan Indonesia
mengabaikan putusan Mahkamah
Konstitusi?
1. Penetapan sanksi
Pemerintah perlu menetapkan sanksi bagi
subjek putusan yang tidak mematuhi
putusan MK. Hal ini dapat dilakukan
dengan cara merevisi Undang Undang (UU)
No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Ketentuan
tentang sanksi bisa dimasukkan menjadi
bagian dari UU MK.
Cara lain untuk menetapkan sanksi bagi
yang tidak mematuhi putusan MK adalah
dengan membentuk UU Penghinaan
terhadap Peradilan (contempt of court) yang
saat ini tidak dimiliki Indonesia.
Saat ini, putusan MK tidak memiliki daya
paksa sama sekali. Tidak ada sanksi yang
mengancam bila putusan MK tidak
dilaksanakan. Ironis, mengingat putusan
MK bersifat final dan mengikat.
2. Masukkan putusan MK dalam
hierarki peraturan perundang-
undangan
Selain penetapan sanksi, putusan MK harus
dimasukkan ke dalam hierarki peraturan
perundang-undangan. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara merevisi UU No 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
Saat ini, hierarki peraturan perundang-
undangan adalah sebagai berikut:
1. UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
3. UU atau Peraturan Pemerintah
Pengganti UU
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam pengujian UU, putusan MK
merupakan putusan yang lahir akibat
adanya UU yang diuji terhadap UUD 1945.
Bila UU yang diuji tersebut bertentangan
dengan UUD 1945, maka putusan tersebut
akan dibatalkan MK melalui putusannya,
dan terhadap putusan MK tersebut sudah
tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat
dilakukan. Oleh sebab itu, putusan MK
seharusnya berada setingkat di atas UU.
Putusan tidak dilaksanakan
Tanpa dua hal tersebut keputusan MK
sering diabaikan. Ada beberapa contoh
menonjol putusan MK yang tidak
dilaksanakan.
Salah satunya adalah putusan MK dalam
pengujian undang-undang (judicial review)
tentang peninjauan kembali kasus pidana.
Pengujian ini diajukan oleh mantan ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Antasari Azhar.
Dalam putusan No. 34/PUU-XI/2013 ini,
MK menyatakan bahwa peninjauan
kembali dalam suatu kasus dapat dilakukan
berkali-kali.
Namun, tak lama kemudian Mahkamah
Agung (MA) merespons putusan ini dengan
Surat Edaran MA (SEMA) yang bertolak
belakang, yakni SEMA No. 7 Tahun 2014
yang membatasi pengajuan peninjauan
hanya sekali.
MA beralasan bahwa peninjauan kembali
juga diatur dalam Undang-Undang (UU)
No. 14 Tahun 1985 tentang MA dan UU
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
Seharusnya, setelah adanya putusan tahun
2013 itu, secara mutatis mutandis putusan
MK itu membatalkan ketentuan dalam dua
UU tersebut. Mutatis mutandis dalam hal ini
maksudnya adalah putusan MK juga
berlaku terhadap ketentuan sama yang
disebut dalam dua UU tersebut.
Rancangan UU (RUU) Cipta Kerja yang
dibuat pemerintah juga berpotensi
melanggar putusan-putusan MK jika
disahkan–belum ditambah bahwa
penyusunannya bermasalah.
Sedikitnya ada 31 ketentuan RUU tersebut
yang bertentangan dengan putusan MK
sebelumnya.
Salah satu yang paling terlihat adalah Pasal
166 dalam RUU tersebut yang
menyebutkan bahwa Peraturan Presiden
bisa membatalkan Peraturan Daerah
(perda).
Ini bertentangan dengan putusan MK
tahun 2016 yang menyebutkan bahwa
kewenangan membatalkan perda ada pada
MA melalui mekanisme judicial review.
Satu contoh lain: Pasal 86 RUU Cipta Kerja
menyebutkan frasa “perjanjian kerja untuk
waktu tertentu” terkait praktik Pekerjaan
Waktu Tertentu dan outsourcing.
Padahal MK pada 2011 telah menetapkan
agar frasa tersebut dihapus dari dua pasal
dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan karena tidak
mengisyaratkan adanya perlindungan hak–
hak bagi pekerja/buruh.
Baca juga: Mengapa Indonesia tidak
membutuhkan Omnibus Law Cipta Kerja
Sifat putusan MK
MK adalah lembaga yudisial yang terlahir
sebagai anak kandung Reformasi yang
putusannya bersifat final dan mengikat
(final and binding).
Artinya, sejak putusan dibacakan oleh
hakim konstitusi dalam sidang pleno yang
terbuka untuk umum, maka putusan
putusan tersebut harus dipatuhi dan
mengikat semua orang, serta tidak tersedia
lagi upaya hukum untuk membatalkan
putusan tersebut.
Putusan MK tidak dapat dibatalkan bahkan
dengan UU baru sekalipun. Bila sebuah
norma hukum yang telah dinyatakan
inkonstitusional mau dihidupkan kembali,
caranya hanyalah dengan perubahan
konstitusi, yaitu mengubah UUD 1945.
Ini sejalan dengan fungsi MK sebagai
pengawal konstitusi: tidak boleh ada
peraturan perundang-undangan yang
bertentangan dengan konstitusi. Putusan
MK merupakan penafsiran dari konstitusi
dalam bentuk putusan yang seharusnya
secara hierarki memiliki kedudukan di atas
UU.
Bila subjek yang tidak melaksanakan
putusan MK diberi sanksi dan putusan MK
menempati hierarki yang tinggi dalam
perundang-undangan tentu putusan MK
akan memiliki daya paksa untuk
dijalankan, serta menjadikan putusan MK
sebagai putusan yang benar-benar
menyelesaikan masalah.
Ikuti perkembangan terbaru seputar isu
politik dan masyarakat selama sepekan
terakhir. Da"arkan email Anda di sini.
Hukum reformasi Undang-undang
Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung
perundang-undangan omnibus law Reformasi hukum
Peradilan
Mungkin Anda juga suka
Kasus Aice: dilema buruh perempuan di
Indonesia dan pentingnya kesetaraan
gender di lingkungan kerja
Bagaimana mewujudkan UU
Perlindungan Data Pribadi yang
kuat di Indonesia
Mengapa Indonesia tidak
membutuhkan Omnibus Law
Cipta Kerja
Sejauh mana legalisasi ganja
bisa bermanfaat?
Pembaca kami
Jumlah pembaca The Conversation sebanyak 18 juta
pengguna setiap bulan, dan melalui Creative Commons
republikasi menjangkau 42 juta pembaca.
Mau menulis?
Tulis artikel dan bergabung dengan komunitas akademisi
dan peneliti yang terus tumbuh dengan lebih dari 157.700
dari 4.535 lembaga.
Daftar sekarang
Tentang kami
Piagam The Conversation
Tim kami
Blog kami
Mitra dan donor
Informasi untuk media
Hubungi kami
Editorial Policies
Standar komunitas
Panduan republikasi
Analisis data
Umpan web kami
Dapatkan newsletter
Kebijakan privasi
Syarat dan ketentuan
Koreksi
Pedoman media siber
Hak cipta © 2010–2023, The Conversation
Anda mungkin juga menyukai
- Pendekatan sederhana untuk komunikasi profesional: Panduan praktis untuk komunikasi profesional dan strategi komunikasi bisnis tertulis dan interpersonal terbaikDari EverandPendekatan sederhana untuk komunikasi profesional: Panduan praktis untuk komunikasi profesional dan strategi komunikasi bisnis tertulis dan interpersonal terbaikBelum ada peringkat
- Naskah Akademik Pendirian Badan Pengatur Jalan TolDari EverandNaskah Akademik Pendirian Badan Pengatur Jalan TolPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (8)
- Tugas 2 Ilmu Perundang-Undangan-04Dokumen4 halamanTugas 2 Ilmu Perundang-Undangan-04Tri Oviyanti CiciBelum ada peringkat
- Pengantar Ilmu HukumDokumen5 halamanPengantar Ilmu HukumHafiza Lubna100% (2)
- Tugas 2 Ilmu Perundang UndanganDokumen2 halamanTugas 2 Ilmu Perundang UndanganFadli amrullohBelum ada peringkat
- Diskurus Omnibus LawDokumen17 halamanDiskurus Omnibus LawIndah Zaharni100% (1)
- Latar Belakang Putusan MKDokumen17 halamanLatar Belakang Putusan MKDymaz Mpoa PaBelum ada peringkat
- Perseroan 2Dokumen10 halamanPerseroan 2오부자Belum ada peringkat
- Mengupas Omnibus Law Bikin GakLaw 8Dokumen24 halamanMengupas Omnibus Law Bikin GakLaw 8Haliza Nur RifdahBelum ada peringkat
- Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MKDokumen10 halamanCara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MKIji MuiziBelum ada peringkat
- HTN Jawaban UTSDokumen4 halamanHTN Jawaban UTSSchadijahBelum ada peringkat
- Evy Nurinayah - 030846784Dokumen13 halamanEvy Nurinayah - 030846784Evy InayahBelum ada peringkat
- Pembaharuan Hukum MK Dan MaDokumen13 halamanPembaharuan Hukum MK Dan MaKepegKI DJKIBelum ada peringkat
- Soal UAS HTLN A, B 2020-2021 - FixDokumen7 halamanSoal UAS HTLN A, B 2020-2021 - FixMuhammad NunoBelum ada peringkat
- Cara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MKDokumen6 halamanCara Memaknai Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan MKsofia manikBelum ada peringkat
- HKUM4403 - Tugas 3Dokumen5 halamanHKUM4403 - Tugas 3Andina KluniariBelum ada peringkat
- Soal Hkum4403 tmk1 2Dokumen2 halamanSoal Hkum4403 tmk1 2War SixBelum ada peringkat
- Ujian Tengah Semester Tahun Akademik Ganjil 2022Dokumen7 halamanUjian Tengah Semester Tahun Akademik Ganjil 2022Abdul Musyfiq Al-ay TamiBelum ada peringkat
- Legal Drafting Kel 2 RevisiDokumen23 halamanLegal Drafting Kel 2 Revisisuci tobingBelum ada peringkat
- Putusan Inkonstitusional Bersyarat Menciptakan Ketidakpastian Hukum Dalam UU Cipta KerjaDokumen6 halamanPutusan Inkonstitusional Bersyarat Menciptakan Ketidakpastian Hukum Dalam UU Cipta KerjaNava RatuBelum ada peringkat
- Naskah Hkum4403 Tugas3Dokumen2 halamanNaskah Hkum4403 Tugas3Andina KluniariBelum ada peringkat
- Joki Paper 1Dokumen21 halamanJoki Paper 1HarrisBelum ada peringkat
- Transplantasi Common Law System Kedalam Penyelesaian Sengketa Konsumen I Putu Rasmadi Arsha Putra AbstrakDokumen23 halamanTransplantasi Common Law System Kedalam Penyelesaian Sengketa Konsumen I Putu Rasmadi Arsha Putra Abstrakhady putraBelum ada peringkat
- Billyo Rentas Tugas II Tugas Ilmu Perundang-UndanganDokumen8 halamanBillyo Rentas Tugas II Tugas Ilmu Perundang-UndanganBillyo Rentas DkdrBelum ada peringkat
- PERNYATAAN SIKAP 16 Januari 2023Dokumen3 halamanPERNYATAAN SIKAP 16 Januari 2023sumarlan1Belum ada peringkat
- BJT - Umum - tmk1 - Dinora RefiasariDokumen3 halamanBJT - Umum - tmk1 - Dinora RefiasariPengadilan Agama KruiBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Konstitusi HederDokumen31 halamanMakalah Hukum Konstitusi HederFadilah AssegafBelum ada peringkat
- Tgs Final HKM Undang c16 04020200262Dokumen12 halamanTgs Final HKM Undang c16 04020200262raflimu012Belum ada peringkat
- Berita Acara Perkuliahan Kelompok 1Dokumen5 halamanBerita Acara Perkuliahan Kelompok 1jurnaljogorotoBelum ada peringkat
- MAKALAH KLP 7 - Pancasila Pekan Ke-XI-1Dokumen11 halamanMAKALAH KLP 7 - Pancasila Pekan Ke-XI-1alwan athBelum ada peringkat
- Bab IvDokumen19 halamanBab Ivvidyanuralifah63Belum ada peringkat
- 5MIH01783Dokumen8 halaman5MIH01783Sindy PramuditaBelum ada peringkat
- Skrip ModeratorDokumen10 halamanSkrip Moderatorm.a rizki pratamaBelum ada peringkat
- Analisis Putusan MK Tentang OmnibuslawDokumen6 halamanAnalisis Putusan MK Tentang Omnibuslawencep iik muzakirBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen13 halaman1 SMsyahroniBelum ada peringkat
- Tugas Hukum InternasionalDokumen4 halamanTugas Hukum InternasionalMR Law FirmBelum ada peringkat
- Konstruktional DPR Terhadap KPKDokumen17 halamanKonstruktional DPR Terhadap KPKAisyah WulandariBelum ada peringkat
- Akibat Rangkap Ganda DokterDokumen11 halamanAkibat Rangkap Ganda DokterEsau IndrawahanaBelum ada peringkat
- Tugas PHKPDokumen5 halamanTugas PHKPangelos gogo siregarBelum ada peringkat
- 1518-Article Text-5863-1-10-20211119Dokumen14 halaman1518-Article Text-5863-1-10-20211119futeaji2Belum ada peringkat
- Makalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-UndanganDokumen13 halamanMakalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-UndanganRosita IslinBelum ada peringkat
- Pembaharuan HukumDokumen23 halamanPembaharuan HukumKepegKI DJKIBelum ada peringkat
- Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaDokumen16 halamanKewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta KerjaBUMDES MUTIARABelum ada peringkat
- Contoh Proposal OrangDokumen29 halamanContoh Proposal OrangHarry Dwi SeptianBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen14 halaman1 SMMohamad Jaenal ArifinBelum ada peringkat
- Kel 6 FixDokumen16 halamanKel 6 Fixbaiqnesya9Belum ada peringkat
- Faktor Penegak HukumDokumen7 halamanFaktor Penegak HukumEndeavourBelum ada peringkat
- Tugas Ilmu Perundang-UndanganDokumen9 halamanTugas Ilmu Perundang-UndanganAfandi IhtisabBelum ada peringkat
- Makalah Hubungan Antara Perundang UndanganDokumen17 halamanMakalah Hubungan Antara Perundang UndanganOwencell OwencellBelum ada peringkat
- Audit Perpu Cipta Kerja Kudeta Terhadap Konstitusi, Membahaya-Kan Kehidupan Demokrasi, Negara Hukum Dan Hak Asasi ManusiaDokumen39 halamanAudit Perpu Cipta Kerja Kudeta Terhadap Konstitusi, Membahaya-Kan Kehidupan Demokrasi, Negara Hukum Dan Hak Asasi ManusiaMiss HearBelum ada peringkat
- Ambivalensi Penegakan Kode Etik Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Kode EtikDokumen18 halamanAmbivalensi Penegakan Kode Etik Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Kode EtikDutapBelum ada peringkat
- Surat Presiden 16 Januari 2023Dokumen3 halamanSurat Presiden 16 Januari 2023sumarlan1Belum ada peringkat
- SHI UTS Oktavian HIBDokumen3 halamanSHI UTS Oktavian HIBA. OktvnBelum ada peringkat
- Filsafat HUKUM UU CIPTakerDokumen6 halamanFilsafat HUKUM UU CIPTakerAnas HamamiBelum ada peringkat
- Makalah Omnibus Law 2003 FixDokumen9 halamanMakalah Omnibus Law 2003 FixBoy BhaskaraBelum ada peringkat
- Vol 1 No 2 Ke 1 PDFDokumen16 halamanVol 1 No 2 Ke 1 PDFilham daniBelum ada peringkat
- Final Hasil Eksaminasi Publik KEPALDokumen23 halamanFinal Hasil Eksaminasi Publik KEPALRois W. SatriawanBelum ada peringkat
- 40-Andriatul Munawir (19010000188) (Tugas Ngerangkum)Dokumen55 halaman40-Andriatul Munawir (19010000188) (Tugas Ngerangkum)Andriatul MunawirBelum ada peringkat
- Muhammad Ridwan Efendi - 210710101176Dokumen3 halamanMuhammad Ridwan Efendi - 210710101176Muhammad Ridwan EfendiBelum ada peringkat
- MAKALAH KEBIJAKAN KESEHATAN Kelompok 2Dokumen10 halamanMAKALAH KEBIJAKAN KESEHATAN Kelompok 2halimah thusyakdyahBelum ada peringkat
- Fungsi Peraturan Perundang-UndanganDokumen19 halamanFungsi Peraturan Perundang-UndanganBudy AryantoBelum ada peringkat
- Hukum Pidana: Materi KuliahDokumen12 halamanHukum Pidana: Materi KuliahBudy AryantoBelum ada peringkat
- Sahnya Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat Jawa: M.SyaifulDokumen7 halamanSahnya Pernikahan Menurut Hukum Perkawinan Adat Jawa: M.SyaifulBudy AryantoBelum ada peringkat
- Jepretan Layar 2022-07-04 Pada 18.15.13Dokumen11 halamanJepretan Layar 2022-07-04 Pada 18.15.13Budy AryantoBelum ada peringkat
- Ujian Akhir Semester SosiologiDokumen2 halamanUjian Akhir Semester SosiologiBudy AryantoBelum ada peringkat
- Perkawinan CirebonDokumen19 halamanPerkawinan CirebonBudy AryantoBelum ada peringkat
- Bagaimana Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Menurut Nurcholish Madjid? Ini Penjelasan AthoillahDokumen1 halamanBagaimana Penerapan Hukum Islam Di Indonesia Menurut Nurcholish Madjid? Ini Penjelasan AthoillahBudy AryantoBelum ada peringkat