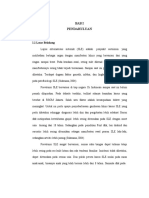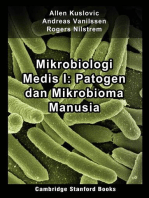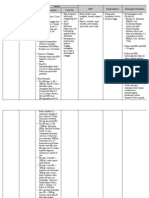Diabetes Tipe I Terjemahan
Diunggah oleh
yuriskamaydaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Diabetes Tipe I Terjemahan
Diunggah oleh
yuriskamaydaHak Cipta:
Format Tersedia
DIABETES TIPE I: ETIOLOGI, IMUNOLOGI, DAN STRATEGI TERAPI
I. PENDAHULUAN
Diabetes mellitus baik tipe 1 maupun tipe 2 (T1D, T2D) memiliki kesamaan
yang level glukosa darah yang tinggi (hiperglikemia) yang dapat menyebabkan
komplikasi kesehatan yang serius antara lain ketoacidosis, gagal ginjal, penyakit
jantung, stroke, dan kebutaan. Pasien seringkali terdiagnosis dengan diabetes
yang datang ke dokter karena ada gejala-gejala klinis seperti sering haus, sering
kencing, dan sering lapar. Gejala-gejala tersebut disebabkan oleh kondisi
hiperglikemia yang sebenarnya disebabkan oleh kurangnya fungsionalitas insulin
dalam tubuh. Pada T2D, yang seringkali terkait obesitas dan usia tua, seringkali
kurangnya fungsionalitas insulin tersebut disebabkan oleh resistensi insulin di
mana sel otot atau sel adiposa tidak berespon secara adekuat terhadap insulin
dalam level normal yang diproduksi oleh sel beta yang intak. Lain halnya dengan
T1D, yang biasanya dimulai saat usia <30 tahun sehingga juga disebut dengan
juvenile onset diabetes, meskipun sebenarnya onsetnya dapat terjadi pada usia
berapapun. T1D merupakan sebuah gangguan autoimun kronis yang muncul
pada individu dengan kerentanan genetik tertentu akibat faktor pencetus dari
lingkungan. Sistem imun dari tubuh kemudian menyerang sel beta di islet
Langerhans di pancreas, sehingga terjadi kehancuran atau kerusakan sel beta
tersebut yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi insulin. Pada kondisi
yang langka, namun makin meningkat kejadiannya, T1D dan T2D terdiagnosis
pada satu pasien.
Berdasarkan American Center for Disease Control, 23.6 juta orang, 7.8%
dari populasi, menderita T1D atau T2D, dan 1.6 juta kasus baru diabetes
didiagnosis pada orang dengan usia 20 tahun pada tahun 2007. Prevalensi T1D
pada penduduk US berusia 0-19 tahun adalah 1.7/1.000 orang. Insiden T1D
secara global meningkat selama dekade terakhir hingga 5.3% setiap tahunnya di
US. Bila trend ini terus berlanjut, diprediksi akan terjadi peningkatan insiden
kasus baru T1D dua kali lipat di populasi anak di Eropa usia <5 tahun antara
tahun 2005 hingga 2020, dan prevalensi kasus pada individu <15 tahun juga
akan meningkat hingga 70%, yang menunjukkan trend semakin muda. Penelitian
mengenai faktor pencetus telah berlangsung bertahun-tahun dan sejauh ini
hanya didapatkan bukti-bukti tidak langsung, khususnya yang menunjukkan
adanya infeksi virus. Saat ini diketahui dengan baik bahwa sebuah konstitusi
genetik spesifik juga harus ada pada seseorang untuk menyebabkan diabetes.
Meski demikian, tingkat konkordansi kejadian T1D di antara kembar monozigotik
hanya 50%, sedangkan di antara kembar dizigotik hanya ~10%. Dengan follow
up yang lebih panjang didapatkan bahwa mayoritas pasien kembar identik yang
menderita T1D mengekspresikan autoantibodi anti-islet yang berkembang
menjadi diabetes, namun auto-antibodi anti-islet pada saudara kembarnya baru
muncul 30 tahun setelah saudaranya menderita diabetes. Sehingga tampaknya
kerentanan genetic ini bertahan selama hidup, dan pencegahan untuk
berkembang menjadi diabetes biasanya didahului oleh masa prodromal yang
panjang dari ekspresi auto-antibodi anti-islet selama bertahun-tahun. Namun
demikian, meskipun tingkat konkordansi untuk kembar monozigotik lebih tinggi
dari yang sebelumnya diperkirakan, namun masih dibawah nilai universal, dan
terhadap perbedaan kuat dalam waktu terjadinya T1D. Hal ini menunjukkan
bahwa komponen lingkungan berperan penting dalam perkembangan T1D.
Sejak awal 1920an, diabetes telah diterapi dengan penggantian insulin,
yang pada kasus ideal, hanya akan memperpendek usia ~10 tahun. Hal ini
memberikan batas keamanan yang tinggi untuk intervensi berbasis imunitas
apapun. Bahkan lebih dari itu, teknologi terbaru (monitor glukosa darah kontinyu,
insulin lepas lambat, etc) dapat menurunkan kemungkinan episode hipoglikemik
yang mengancam jiwa akibat over dosis insulin. Sehingga, intervensi berbasis
imunologis idealnya harus efektif, berlangsung lama, dan memiliki efek samping
minimal untuk mengganti terapi substitusi insulin dengan sebuah kesembuhan.
Saat ini, meskipun masih banyak tantangan dalam bidang imunoterapi T1D,
namun telah banyak progress bagus yang dihasilkan.
Dalam tinjauan ini, kami menyediakan tinjauan komprehensif mengenai
etiologi dan imunologi T1D dan akan mendiskusikan strategi biologis preventif
ataupun terapeutik yang telah diteliti atau saat ini telah dilaksanakan.
II. GENETIKA DIABETES TIPE I
Tinjauan komprehensif mengenai data genetic pada tikus dan manusia
tidak dibahas dalam artikel ini. Namun kami akan memfokuskan tentang
bagaimana berbagai kerentanan genetic dan pencetus lingkungan dapat sesuai
dengan model mekanistik etiologi T1D.
A. Bentuk-bentuk Monogenik yang Jarang
Diabetes autoimun jarang disebabkan oleh defek mutasi pada sebuah gen
tunggal. Bentuk-bentuk monogenic ini biasanya disertai oleh kondisi autoimun
lain akibat gangguan pada pathway regulasi umum. Satu contohnya dapat dilihat
pada sindroma IPEX (immune dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy,
X-linked), di mana mutasi pada faktor transkripsi Foxp3 menyebabkan terjadinya
disfungsi regulasi sel T (Tregs) dan terjadinya autoimun multiorgan. Sekitar 80%
anak yang terkena akan mengalami diabetes autoimun dan secara umum akan
meninggal dengan cepat akibat kondisi autoimunitas menyeluruh. Contoh lain
bisa dilihat pada autoimmune polyendocrinopathy syndrome type 1 (APS-1 atau
APECED untuk autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal
dystrophy). Mutasi pada faktor transkripsi AIRE (regulator autoimun)
menyebabkan kondisi autoimun yang berat, dan ~20% dari kasus berkembang
menjadi T1D. Defisiensi AIRE akan menghambat ekspresi molekul perifer,
contohnya insulin di thymus. Penurunan ekspresi ini memungkinkan sel T
autoreaktif untuk lolos ke perifer, karena penurunan ekspresi ini mengganggu
proses delesi thymus. Bentuk-bentuk monogenik yang langka ini
merepresentasikan sejumlah kecil kasus T1D, namun menggarisbawahi dua
karakteristik utama terkait etiologi T1D. Pertama, observasi bahwa beberapa
kondisi autoimun yang telah diketahui dengan baik berkembang secara paralel
sehingga dapat digarisbawahi adanya mekanisme toleransi umum yang
mencegah munculnya penyakit ini pada individu-individu sehat. Kedua, meskipun
genetik dan lingkungan mungkin berinteraksi dalam sebuah spektrum yang
kontinyu pada sebagian besar pasien dengan penyakit autoimun, namun
penyebab monogenik pada IPEX dan APS-1 mengilustrasikan bahwa konstitusi
genetik dapat lebih dominan pada kasus tertentu yang ekstrim.
B. Gen HLA
Penelitian-penelitian awal mengindikasikan bahwa regio HLA pada
kromosom 6p21 (umumnya disebut IDDM1, untuk lokus insulin dependent
diabetes mellitus) merupakan lokus dengan kerentanan kritis untuk banyak
penyakit autoimun pada manusia, termasuk T1D. Temuan-temuan awal tersebut
telah merevolusi pengertian kita tentang etiologi T1D ke dalam dua cara,
sebagaimana dinyatakan oleh Nerup et al, dalam kesimpulannya pada tahun
1974: (1) T1D merupakan sebuah entitas penyakit yang berbeda, sesuai hasil
dan bukti histopatologis; dan (2) sebuah respon imun seluler aberant, yang
mungkin dipicu oleh infeksi virus, dapat mengawali onset tersebut. Sejumlah
lokus rentan yang baru kemudian ditemukan sejak penelitian tersebut, namun
tidak ada satupun yang memiliki keterkaitan kuat seperti pada regio HLA.
Tampaknya tidak mungkin ditemukan loci baru lagi yang memiliki resiko dramatis
perkembangan T1D selain HLA. Pada penelitian genetik, odds ratio secara
statistik digunakan untuk mengkalkulasi apakah sebuah single nucleotide
polymorphisme (SNP) terkait dengan penyakit. Sebuah odds ratio yang bernilai 1
menandakan bahwa kejadian ini sama antara kelompok pasien dan kelompok
kontrol. Odds ratio dari alel yang merupakan faktor predisposisi penyakit yang
kompleks, biasanya bernilai sedang, antara 1.2-1.3, dan bahkan regio HLA
hanya memiliki nilai prediktif (predictive value) sebesar 6.8. Hal ini menunjukkan
bahwa predisposisi genetik memang merupakan sebuah faktor dominan dalam
perkembangan T1D, dan masih banyak SNP lain yang masih harus ditemukan.
Setelah beberapa dekade sejak ditemukannya hubungan HLA, gen klas II masih
merupakan kontributor genetik yang paling kuat. Beberapa gen HLA klas II
sangat penting sehingga alel-alel dari gen tersebut ditemukan dapat menentukan
kerentanan genetik secara hirarkis mulai dari gen proteksi hingga gen beresiko
tinggi. Haplotipe DRB1*1501-DQA*0102-DQB1*0602, ditemukan ~20% populasi,
namun hanya 1% dari pasien, yang memberikan proteksi dominan terhadap T1D.
Di sisi lain dari spektrum kerentanan genetis ada individu dengan haplotipe
DR3/4-DQ8 heterozigot (DR3 adalah DRB1*03-DQB1*0201, DR4 adalah
DRB1*04-DQB1*0302, DQ8 adalah DQA1*0301-DQB1*0302). Penting untuk
dicatat bahwa hanya 30-50% pasien dengan T1D yang memiliki genotip DR3/4-
DQ2/8. Sebuah studi di Denver, Colorado, menemukan haplotipe resiko tinggi
tersebut pada 2.4% naonatus dan lebih dari 20% anak yang menderita T1D, dan
adanya haplotipe ini menandai kemungkinan resiko sebesar 55% terjadinya
diabetes saat usia 12 tahun. Saudara kandung dengan DR3/4-DQ2/8 dengan
HLA identik diabetik memiliki resiko hingga 80% untuk terjadinya auto-antibodi
anti-islet persisten dan 60% kemungkinan terjadinya diabetes pada usia 15
tahun.
Ditemukan juga sebuah hubungan yang konsisten, meskipun kurang
terlihat, untuk alel-alel klas I. Sebuah penelitian terbaru oleh Nejentsev et al
menemukan bahwa, setelah dilakukan penghitungan mengenai pengaruh
dominan gen klas II, sebagian besar sisa-sisa asosiasi pada regio HLA dapat
dikaitkan dengan gen-gen HLA-B dan HLA-A. Yang paling penting yakni
keberadaan alel HLA-B*39 ditemukan dapat menjadi faktor resiko yang signifikan
dan terkait dengan makin mudanya usia saat diagnosis T1D ditegakkan. Selain
itu, HLA-A*02 semakin menambah resiko individu yang memiliki haplotiple klas II
DR3/4-DQ8 yang beresiko tinggi. HLA-A*0201 merupakan salah satu alel klas I
yang paling banyak dijumpai, dengan frekuensi >60% pada pasien T1D.
Terdapat makin banyak bukti mengenai keberadaan dan fungsi HLA-A*02 yang
terbatas pada sel T-CD8 yang bereaksi terhadap antigen sel beta seperti insulin,
glutamate decarboxylase (GAD), dan IAPP pada pasien T1D dan pasien yang
menjalani transplant islet. Tikus NOD transgenik telah dibuat untuk
mengekspresikan molekul HLA-A*02 manusia, dan makin cepatnya onset
diabetes pada tikus tersebut membuktikan adanya bukti fungsional keterlibatan
alel klas I ini.
C. Gen Insulin
Predisposisi genetik lain dari T1D berasal dari lokus IDDM2 pada
kromosom 11 yang mengandung regio gen insulin. Sebuah regio polimorfik yang
terletak pada 5 gen insulin pertama kali dilaporkan terkait dengan T1D pada
tahun 1984 pada ras Kaukasoid. Setelah ditetapkan sebagai autoantigen primer
pada T1D, tidak mengherankan bahwa mutasi pada regio insulin dapat
berkontribusi terhadap kerentanan individu terhadap diabetes. Pemetaan rinci
menunjukkan bahwa kerentanan terletak pada polimorfisme variable number of
tandem repeat (VNTR) di regio promoter gen insulin. Besarnya resko sangat
berkorelasi dengan jumlah dari pengulangan tandem tersebut. VNTR tipe I
(dengan pengulangan pendek) pada individu homozigot memiliki kategori resiko
yang paling tinggi dan VNTR tipe III (pengulangan panjang) dapat melindungi
individu carrier terhadap T1D. Hipotesis utama yang diajukan adalah bahwa
VNTR tersebut meregulasi level ekspresi insulin pada thymus dengan
mempengaruhi ikatan AIRE dengan regio promoternya. Pentingnya ekspresi
insulin oleh sel epithel medulla thymus yang dilakukan oleh AIRE (mTECs) baru-
baru ini ditemukan melalui sebuah observasi delesi insulin spesifik mTEC akan
menyebabkan diabetes pada hewan. Konsekuensinya, pada VNTR tipe I
ditemukan transkripsi insulin dan prekursor insulin di thymus yang lebih rendah
sehingga menyebabkan penurunan toleransi insulin dan perkembangan T1D.
Sebaliknya, sel T reaktif insulin seringkali secara efisien dieliminasi melalui
seleksi negatif di thymus pada individu dengan varian alel VNTR tipe III yang
protektif.
D. PTPN22
Perangkat gen yang rentan T1D yang relatif baru ditemukan adalah
PTPN22, yang mengkode lymphoid protein tyrosine phosphatase (LYP). Varian
alel ini juga memediasi beberapa penyakit autoimun lainnya, yang menunjukkan
keterlibatan axis sinyal yang krusial. Dan memang, protein LYP merupakan
regulator negatif yang penting dari sinyal reseptor sel T melalui defosforilasi
golongan kinase Src yakni Lck dan Fyn, ITAMs dari kompleks TCR/CD3, serta
ZAP-70, Vav, valosin containing protein, dan molekul sinyal kunci lainnya.
Penjelasan mekanismenya masih kontradiktif. Mutasi loss-of-function (hilang
fungsi) dapat menyebabkan penurunan ambang batas aktivasi sel T autoreaktif di
perifer. Sebaliknya, mutasi gain-of-function yang mensupresi sinyal TCR selama
perkembangan thymus dapat menyebabkan sel T autoreaktif lolos dari seleksi
negatif.
E. IL2RA
Variasi alel pada regio gen interleukin (IL)-2 receptor- juga berperan
dalam faktor resiko genetik yang menyebabkan T1D. Rantai alfa dari kompleks
reseptor IL-2 (IL2R, CD25) merupakan molekul penting yang diekspresikan
pada sel T saat terjadi aktivasi dan pada Tregs alami saat kondisi normal. Tregs
bergantung pada Il-2 selama pertumbuhan dan kehidupan sel. Adanya subunit
IL2R akan meningkatkan afinitas reseptor IL-2 secara signifikan. Pada penyakit
multiple sclerosis (MS) dan kondisi autoimun lainnya, ditemukan peningkatan
level IL2R terlarut (sIL2R) dalam darah. Karena peran IL-2 pada fungsi Treg
yang tidak tergantikan dan potensi dari sIL2R untuk menetralisir IL-2, maka
dapat diduga bahwa varian beresiko dari alel IL2RA dapat mengganggu
fungsionalitas Treg melalui upregulasi sIL2R. Namun, baru-baru ini ditemukan
bahwa kerentanan genotip IL2RA pada T1D terkait dengan rendahnya level
sIL2R. Selain itu, pada sel mononuklear darah perifer yang distimulasi secara in
vitro dari individu dengan T1D, ditemukan bahwa sel-sel tersebut memproduksi
lebih sedikit sIL2R daripada sel dari individu kontrol. Hal ini mungkin
mengindikasikan adanya defek subset seluler yang merupakan sumber dari
IL2R. Alternatif penjelasan lainnya adalah bahwa, bahkan pada frekuensi Tregs
yang normal pada T1D, polimorfisme IL2R dapat berperan dalam defek
fungsional kompartemen Tregs. Kesimpulannya, meskipun tampaknya
variabilitas genetik dari gen IL2RA terkait dengan beberapa penyakit autoimun
termasuk T1D, namun mekanisme dan jangkauan sejauh mana level IL2RA
dapat memediasi kondisi-kondisi tersebut sangat jauh berbeda.
F. CTLA-4
Alel beresiko untuk terjadinya T1D lain yang telah dikonfirmasi terletak
pada gen yang mengkode cytotoxic T lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4)
pada regio IDDM12. CTLA-4 merupakan sebuah molekul vital untuk regulasi
negatif yang sesuai dalam respon imun, sebagaimana dibuktikan dari munculnya
kondisi gangguan limfoproliferatif berat bila gen ini dihilangkan pada tikus.
Sebagaimana regio lain, keterkaitan resiko dari varian alel regio CTLA-4 tidak
eksklusif hanya dengan T1D, namun juga pada beberapa gangguan autoimun
lainnya, di antaranya multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus (SLE),
dan rheumatoid arthritis. SNP juga telah ditemukan pada regio promoter dan
pada exon-1 CTLA-4 manusia. Polimorfisme A49G merupakan satu-satunya
polimorfisme yang merubah sekuens asam amino primer pada CTLA-4. Pada
penelitian in vitro terhadap A49G-CTLA-4 menunjukkan bahwa bentuk mutan dari
CTLA-4 secara acak diproses di dalam retikulum endoplasma yang
menyebabkan penurunan ekspresi di permukaan. Namun bagaimana tepatnya
polimorfisme ini mempengaruhi fungsi CTLA-4 masih belum jelas. Selain efek
terhadap proses dan perjalanan intrasel, mutasi ini mungkin juga berpengaruh
terhadap oligomerisasi dan retensi permukaan. Namun demikian, hipotesis
utama yang diajukan pada manusia adalah bahwa varian alel akan menurunkan
level mRNA pada varian splice CTLA-4 terlarut.
G. Penelitian Keterkaitan Genome dan Polimorfisme Langka pada Gen IFIH1
Kemajuan penelitian genome-wide association (GWA) telah memungkinkan
analisis silang tingkat tinggi terhadap SNP di seluruh genome manusia, pada hal-
hal yang sebelumnya tidak dapat dicapai, pada ribuan orang yang tidak
berkaitan, dan pada sebuah pola yang tidak didasarkan pada hipotesis. Hasil-
hasil yang dipublikasikan dari berbagai penelitian GWA dan meta-analisis yang
dilakukan terhadap penelitian-penelitian tersebut mengkonfirmasikan adanya
asosiasi dari gen-gen yang telah didiskusikan sebelumnya dan berhasil
mengidentifikasi sejumlah besar lokus baru yang beresiko. Penelitian GWA
paling baru yang berfokus pada T1D menemukan bahwa terdapat lebih dari 40
lokus yang beresiko menyebabkan T1D, termasuk regio yang baru diidentifikasi
yang berfungsi mengkode molekul imunoregulasi seperti IL-10. Dapat
disimpulkan dari penelitian komprehensif tersebut bahwa penyakit autoimun
memang memiliki banyak kesamaan faktor resiko genetik, sehingga
menunjukkan pathway yang sama. Tambahan terhadap pernyataan tersebut
yakni penemuan paling baru berupa SNP beresiko pada gen kandidat fungsional
TYK2, yang berimplikasi terhadap sinyal interferon (IFN)-, IL-6, IL-10, dan IL-12.
Hubungan ini sebelumnya ditemukan pada kondisi MS, ankylosing spondylitis,
SLE, dan penyakit thyroid autoimun. Kami tidak akan merangkum semua gen
yang beresiko dan berspekulasi mengenai implikasi etiologisnya terhadap T1D.
Namun kami akan menggarisbawahi polimorfisme terkait T1D pada regio IFIH1,
karena polimorfisme ini terkait dengan dengan konstitusi genetik dan faktor
lingkungan pencetus.
Interferon induced helicase-1 (IFIH1) mengkode sebuah helicase yang
diinduksi oleh IFN yang berkontribusi terhadap pengenalan dsRNA dari
picornavirus. Karena itu, IFIH1 berfungsi sebagai sensor sitoplasma terhadap
infeksi virus. Sebagaimana akan kami jelaskan selanjutnya, bahwa salah satu
virus terkait T1D yang paling dominan adalah coxsackievirus B (CVB), sebuah
enterovirus yang masuk dalam famili picornavirus. Studi pada tikus
mengkonfirmasi bahwa IFIH1 dan molekul adaptornya yakni MAVS, sangat
penting dalam proses respon interferon tipe 1 terhadap CVB, khususnya pada
fase akhir. Sehingga, defek genetik pada IFIH1 dapat berpotensi mengganggu
deteksi dan pembersihan virus sehingga menyebabkan respon imun
diabetogenik yang abnormal. Sebuah penelitian independen mengkonfirmasi
adanya polimorfisme terkait T1D pada gen IFIH1 dan menunjukkan bahwa level
ekspres gen pada PBMC lebih tinggi daripada individu dengan genotip yang
rentan. Hipotesis yang mungkin adalah bahwa pada individu-individu tersebut
dengan level IFIH1 yang lebih tinggi, infeksi virus mungkin terutama dikenali
melalui pathway IFIH1, yang menyebabkan eksaserbasi imunitas antivirus dan
produksi interferon tipe I. Sesuai dengan hipotesis tersebut, telah berhasil
diidentifikasi adanya varian protektif IFIH1 pada T1D yang sangat langka. Satu
dari varian protektif tersebut adalah mutasi non-sense yang menyebabkan
percabangan protein, sedangkan dua varian lain mungkin terkait dengan
gangguan pemecahan normal transkripsi IFIH1. Prediksi awal adalah bahwa
varian-varian tersebut menurunkan fungsi protein IFIH1, sehingga menurunkan
resiko T1D, sebagaimana dikonfirmasi melalui penelitian.
H. Paralelisme antara Genetika Manusia dan Genetika NOD Tikus
Mayoritas data mekanis mengenai patogenesis dan intervensi potensial
T1D berasal dari penelitian pada tikus. Sehingga, penting untuk memahami
predisposisi genetik dari model-model tikus yang sering digunakan, yakni tikus
NOD. Sama dengan terminologi lokus IDDM pada manusia, regio genetik yang
mengontrol perkembangan ke arah T1D pada NOD juga merupakan lokus insulin
dependent diabetes (Idd). Salah satu pendekatan dalam melakukan analisis
fungsional rinci terhadap lokus beresiko adalah dengan membuat tikus kongenik,
di mana lokus dengan kerentanan penyakit yang spesifik digant dengan gen
protektif dari strain yang tidak beresiko diabetes. Penelitian-penelitian ini
mengkonfirmasi bahwa, sebagaimana pada manusia, gen major histocompatibiliy
complex (MHC) class II (Idd1) secara khusus berperan sebagai gen dominant
yang berkontribusi terhadap predisposisi penyakit pada tikus NOD. Selain itu,
lebih dari 20 regio Idd non-MHC telah ditemukan dapat memediasi resiko
penyakit. Kami akan memfokuskan beberapa lokus rentan yang sama antara
manusia dan tikus.
Lokus resiko pertama yang menunjukkan korespondensi antara manusia
dengan tikus adalah Ctla4 (Idd5.1). Manusia mengekspresikan dua variant splice
utama yang mengkode CTLA-4 dalam bentuk terikat membran ataupun dalam
bentuk bebas (terlarut dalam darah). Tikus mengekspresikan sebuah varian yang
tidak memiliki domain ikatan B7, yang disebut ligand-independenti CTLA-4 (li-
CTLA-4). Efek proteksi genetik pada strain tikus kongenik Idd5.1 diketahui
dimediasi oleh level ekspresi isoform liCTLA-4 yang lebih tinggi, yang
memodulasi negatif respon sel T. Hal ini mengkonfirmasi konsep bahwa
polimorfisme mempengaruhi level isoform CTLA-4 yang berkontribusi terhadap
kerentanan T1D.
Kerentanan genetik pada manusia dan tikus juga sama-sama didapatkan
pada variasi pathway sinyal IL-2. Namun, bila kerentanan pada manusia terkait
dengan regio gen IL2RA, varian pada NOD terletak pada gen IL-2 (pada Idd3).
Konsisten dengan peran yang tidak tergantikan dari sinyal IL-2 untuk mencegah
T1D, beberapa laporan menyebutkan adanya korelasi antara Idd3 dengan
penurunan level IL-2 yang menyebabkan gangguan induksi toleransi dan
fungsionalitas Tregs. Bila dilihat secara umum, derajat kesamaan antara kedua
spesies ini menandakan pentingnya peran pathway IL-2 dalam menjaga toleransi
insulin. Meskipun terjadi gangguan pada berbagai bagian kaskade sinyal IL-2,
outcome-nya dapat sama yakni gangguan homeostasis sel T dan ekspansi
subset sel T diabetogenik.
Beberapa observasi menunjukkan bahwa ortolog PTPN22 pada tikus akni
Ptpn8, mempengaruhi penyakit pada NOD, namun hubungan ini masih harus
dikonfirmasi. Hingga saat ini, belum ada lokus Idd yang diketahui meregulasi
ekspresi insulin thymus seperti yang sudah ditemukan pada manusia. Namun
demikian, konsep level insulin thymus sebagai regulator penting selama seleksi
negatif telah dikonfirmasi pada penelitian terhadap tikus NOD dengan berbagai
derajat defisiensi gen pengatur dosis insulin. Terlepas dari perbedaan evolusi
dari kedua spesies ini, beberapa keterbatasan juga disebabkan oleh translasi
data genetik dari model NOD ke manusia. Contohnya, tikus NOD mengalami
insulitis yang lebih berat daripada yang ditemukan pada islet manusia (Gambar
3). Selain itu, translasi intervensi imunomodulasi pada model tikus terhadap
pasien T1D juga tidak dapat dilakukan secara langsung.
III. FAKTOR PENCETUS
Saat ini telah diketahui bahwa manifestasi klinis dari T1D merefleksikan
konsekuensi dari sebuah proses autoimun berkepanjangan di baliknya.
Contohnya, auto-antibodi terhadap antigen islet dapat dideteksi sebelum muncul
onset klinis T1D. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah sekuens yang memulai
kejadian sebelum hiperglikemia selama setidaknya beberapa bulan, namun
mungkin juga bisa beberapa tahun. Jarak yang lebar antara inisiasi dan deteksi
kejadian diabetogenik yang sedang berjalan, memberikan suatu masalah besar
dalam pencarian pemicu lingkungan yang menyebabkan proses inisiasi. Selain
itu, juga terdapat kemungkinan bahwa faktor pemicu bersifat hit and run
sehingga tidak meninggalkan jejak molekuler. Alternatif lain, mungkin diperlukan
pemicu dari lingkungan yang tidak hanya satu untuk dapat memicu autoimunitas,
dan masing-masing pasien mengalami kombinasi faktor pemicu yang berbeda-
beda. Setelah mendiskusikan kontribusi genetik utama terhadap kerentanan
T1D, selanjutnya kita akan mendiskusikan data epidemiologis yang
mengindikasikan bahwa makin meningkatnya insiden T1D berkaitan dengan
perubahan lingkungan.
A. Infeksi Virus
Sebuah pencarian di database PubMed menggunakan kata kunci virus
dan diabetes tipe 1 menghasilkan 1.355 judul tulisan, yang menggambarkan
betapa besarnya usaha untuk memahami peran infeksi virus dalam T1D. Tanggal
tertua dari publikasi adalah tahun 1926 berupa dokumen variasi musiman onset
diabetes dan dikaitkan dengan beberapa infeksi virus. Meskipun sudah dilakukan
berbagai usaha tersebut, masih belum ada bukti langsung untuk strain virus
tertentu yang menjadi penyebab T1D.
1. Enterovirus
Sejumlah besar data menyatakan bahwa enterovirus, atau lebih spesifiknya
coxsackievirus sebagai kandidat virus utama yang dapat mencetuskan T1D.
Penelitian pertama menunjukkan adanya hubungan antara infeksi coxsackievirus
dengan T1D berdasarkan temuan tingginya titer antibodi netralisasi pada serum
pasien dengan onset baru dibandingkan kelompok kontrol. Data-data ini
selanjutnya dikonfirmasi menggunakan teknologi PCR. Beberapa penelitian juga
memeriksa antibodi terhadap virus lain secara paralel, namun coxsackievirus
selalu menjadi yang paling banyak ditemukan. Kemungkinan adanya hubungan
kausatif ini kemudian diteliti lebih lanjut dengan berbagai tingkat kesuksesan baik
pada studi manusia maupun studi hewan. Pada tahun 1971, terjadi kejadian
menarik yakni sebuah studi yang dilakukan terhadap insiden diabetes setelah
epidemia infeksi coxsackievirus B4 (CVB4) pada pulau Pribilof yang terisolasi.
Lima tahun setelah epidemi, insiden diabetes pada individu yang terinfeksi CVB4
dibandingkan dengan individu yang tidak terinfeksi CVB4 ditemukan tidak
berbeda, sehingga disimpulkan tidak ada hubungan antara infeksi CVB4 dengan
onset T1D. Dengan pengetahuan kita saat ini mengenai kontribusi genetik, maka
bisa dinyatakan bahwa infeksi virus saja tidak dapat menyebabkan T1D pada
latar belakang genetik apapun. Yoon et al, dalam penelitian selanjutnya
memberikan dukungan lebih banyak untuk keterlibatan CVB4 dengan
mendemonstrasikan bahwa virus tersebut dapat mengnfeksi sel beta dan
menyebabkan insulitis serta diabetes pada strain tikus yang rentan. Selain itu,
penelitian ini juga berhasil mengisolasi strain CVB4 dari anak dengan T1D onset
baru. Data fungsional menunjukkan adanya penguatan respons sel T terhadap
protein CVB4 pada anak dengan T1D setelah munculnya onset penyakit
tersebut. Di antara sel-sel yang reaktif CVB4 tersebut, fenotip efektor/memori
lebih mendominasi di saat-saat mendekati diagnosis. Terakhir, penelitian yang
dilakukan pada populasi Finlandia menunjukkan adanya hubungan antara infeksi
enterovirus dan perkembangan diabetes pada sebuah penelitian prospektif.
Meskipun infeksi enterovirus tampaknya tidak merepresentasikan penyebab
eksklusif untuk makin tingginya insiden T1D di Finlandia, namun mungkin infeksi
ini merupakan kontributor yang penting.
Pada penelitian besar tahun 1987, Foulis et al, melaporkan adanya
sejumlah besar HLA klas I dan IFN- pada islet anak dengan diabetes onset
baru, sehingga memicu ketertarikan akan peran virus pada T1D. Dapat diterima
bahwa infeksi terhadap sel beta dapat meng-up-regulasi baik HLA klas I maupun
IFN- sehingga meninggalkan sebuah tanda virus molekuler. Hal ini juga dapat
menjelaskan mengapa respon imun mengarah secara spesifik terhadap islet.
Namun sayangnya, pada sebuah penelitian follow up mengenai protein virus
pada sel beta gagal untuk mendeteksi adanya komponen virus di sel beta,
namun penelitian ini pada akhirnya juga merevisi kesimpulannya setelah
dilakukan re-analisis dari metode cohort yang dilakukan menggunakan
metodologi yang lebih optimal. Bukti adanya enterovirus ditemukan pada islet
pada 44 dari 72 pasien dengan diabetes onset baru dibandingkan dengan 3 dari
50 kontrol, yang menunjukkan indikasi hubungan kausatif paling dekat saat ini.
Namun demikian, islet pada 10 dari 25 pasien diabetes tipe 2 juga menunjukkan
adanya jejak enterovirus, sehingga muncul perhatian terhadap reagen yang
digunakan. Meski begitu, Dotta et al, baru-baru ini mereplikasi deteksi
imunohistokimia protein enterovirus dan mengkonfirmasi hasilnya dengan
sequencing. Sampel pankreas unik seperti yang didapatkan oleh Foulis et al,
saat ini jarang tersedia karena perkembangan manajemen klinis T1D yang
sangat signifikan. Sehingga, replikasi hasil bergantung pada pendanaan seperti
Juvenile Diabetes Research Fund yang mendanai Network for Pancreatic Organ
Donors (nPOD) yang bertujuan mengumpulkan jaringan yang relevan dengan
penelitian T1D dari seluruh negara.
Meski adanya partikel enterovirus di islet pancreas menunjukkan bahwa
T1D merupakan konsekuensi dari infeksi virus selektif terhadap sel beta, namun
data-data yang ada juga memberikan kemungkinan mekanisme alternatif.
Kesamaan sequence yang ekstrim antara protein 2C dari coxsackievirus dan
GAD, auto-antigen mayor pada T1D, menyebabkan diajukannya postulasi
mimikri virus dalam etiologi T1D. Hasil-hasil penelitian selanjutnya ada yang
mendukung ataupun menentang mekanisme tersebut, dan beberapa penelitian
menyatakan pentingnya kontribusi HLA-DR3 dalam kerentanan terhadap mimikri
virus. Meskipun terdapat kesamaan sequence antara GAD dan hsp60, namun
hubungan antara autoimunitas dengan hsp60 dan T1D tidak dapat diteliti ulang.
Waktu terjadinya infeksi enterovirus terkait dengan onset T1D masih
merupakan sebuah isu kontroversial. Selain adanya jejak-jejak infeksi pada
individu dengan T1D onset baru, infeksi enterovirus juga ditemukan sebelum
onset pada anak pre-diabetes dengan auto-antibodi positif. Infeksi enterovirus
selama kehamilan juga diidentifikasi sebagai faktor resiko T1D. Secara umum,
data-data ini menunjukkan bahwa infeksi virus dapat memicu respon imun. Meski
demikian, data dari tikus NOD menunjukkan bahwa diperlukan adanya kondisi
insulitis agar infeksi coxsackievirus dapat menginduksi diabetes. Bila diterapkan
pada manusia, individu dengan kerentanan genetik mungkin telah mengalami
insulitis subklinis selama bertahun-tahun hingga terjadi infeksi virus yang memicu
percepatan destruksi sel beta dan hiperglikemia. Observasi menarik lainnya
mengenai kondisi ini adalah bahwa baru-baru ini enterovirus ditemukan pada
sampel biopsi usus 75% kasus T1D bila dibandingkan kelompok kontrol yang
hanya 10%. Hal ini mungkin merefleksikan infeksi enterovirus yang persisten
pada mukosa usus yang berfungsi sebagai reservoir virus yang tidak terdeteksi di
mana reservoir ini dapat meluas ke area pankreas dan menyebabkan insulitis.
CVB menginduksi up-regulasi kemokin CXCL10 pada sel beta pankreas
baru-baru ini diketahui sebagai salah satu konsekuensi awal dari infeksi.
Hiperekspresi dan adanya infeksi virus, keduanya ditemukan bersamaan pada
T1D fulminant (berat), sebuah varian T1D yang sangat agresif yang ditemukan
di populasi Jepang. Studi pada hewan telah menemukan peran penting dari
CXCL10 pada rekrutmen sel T autoreaktif yang mengekspresikan CXCR3 pada
kondisi infeksi virus.
Secara kumulatif, data yang tersedia menunjukkan keterlibatan CVB pada
setidaknya satu subset kasus T1D dan memberikan peringatan untuk
pencegahan infeksi pada individu yang rentan. Namun demikian, yang lebih
merumitkan situasi adalah ditemukannya efek proteksi dari CVB terhadap T1D
pada kondisi eksperimental tertentu, yang mendukung hipotesis higien.
Kelompok kami juga telah menunjukkan bahwa proteksi ini secara mekanis diatur
melalui dua pathway yang berbeda, termasuk penguatan Treg fungsional dan up-
regulasi reseptor ko-inhibisi PD-L1 pada sel limfoid. Data-data ini memberikan
titik terang pada ambiguitas peran infeksi virus dalam konteks autoimunitas.
2. Virus lain
Infeksi virus lain juga dikaitkan dengan T1D, namun hubungan kausatifnya
masih belum terbukti.
Hubungan potensial antara T1D dengan rotavirus, penyebab utama
gastroenteritis pada anak, didasarkan pada kemungkinan mimikri molekul.
Kesamaan tersebut pada awalnya ditemukan antara epitop sel T pada GAD dan
IA-2 serta pada protein virus. Sebuah penelitian lanjutan di Australia menemukan
adanya hubungan antara infeksi rotavirus dan auto-antibodi islet pada anak
dengan resiko, namun sejumlah kelompok penelitian pada Finlandia gagal untuk
mengkonfirmasi hubungan ini. Kelompok penelitian di Finlandia ini kemudian juga
tidak berhasil menemukan hubungan antara respon sel T yang spesifik terhadap
rotavirus dengan adanya auto-antibodi terkait T1D. Sehingga, status saat ini
mengenai infeksi rotavirus sebagai etiologi T1D masih belum dapat dikonfirmasi.
Senada dengan hal itu, banyak laporan awal mengenai peran potensial virus-
virus lain pada T1D, seperti cytomegalovirus, parvovirus, dan encephalo-
myocarditis virus, yang juga masih harus dikonfirmasi lagi pada populasi pasien
yang besar.
Yang secara konseptual menarik adalah adanya hubungan antara infeksi
rubella kongenital dan onset diabetes setelah lahir, sebuah topik yang baru-baru
ini diangkat oleh Gale. Sindroma rubella kongenital terdiri atas sejumlah
gangguan baik fisik ataupun perilaku dan ditandai dengan penyakit multisistem.
Menariknya, progres menjadi diabetes dihubungkan dengan tingginya frekuensi
halotipe HLA-A1-B8-(DR3-DQ2) yang rentan terhadap T1D, namun bukti
langsung terhadap autoimunitas yang spesifik terhadap islet masih sangat
jarang. Sebuah mekanisme alternatif bahwa virus akan mengganggu
perkembangan massa sel beta saat ini lebih dipilih. Sebagai konsekuensi dari
karakteristik atipikal ini, beberapa konsensus guideline klinis memasukkan
diabetes rubella kongenital dalam sebuah kategori terpisah yakni diabetes tipe
spesifik lain. Namun argumen paling penting dari pernyataan bahwa infeksi
rubella tidak bertanggung jawab terhadap peningkatan insiden T1D secara global
adalah karena virus ini telah dieliminasi dari negara-negara maju sejak
diperkenalkannya vaksin pada tahun 1969. Pernyataan tersebut juga
mengeksklusi infeksi mumps meskipun terdapat laporan terbaru pada kasus T1D
fulminant.
Karena vaksinasi tidak menurunkan insiden T1D, dipertanyakan apakah
program vaksinasi di seluruh dunia terkait dengan peningkatan insiden. Memang,
pemberian imunisasi secara umum pada anak dan makin meningkatnya T1D di
negara maju tampaknya terjadi bersamaan. Meski demikian, beberapa penelitian
besar menemukan tidak adanya bukti hubungan kausatif antara imunisasi pada
anak dengan T1D, sehingga dilihat dari rasio resiko-manfaat tetap dianjurkan
untuk memberikan imunisasi sebagai usaha proteksi terhadai infeksi.
B. Bakteri
Komposisi bakteri di usus telah diketahui sebagai sebuah variabel penting
dalam perkembangan T1D. Bukti langsung didapatkan pada hewan pengerat,
karena diabetes semakin berat dalam kondisi spesifik bebas patogen atau
dengan pemberian antibiotik. Namun pada penelitian lain, pemberian antibiotik
justru dapat mencegah diabetes. Mungkin terjadi kondisi autoimunitas saat
keseimbangan mikroba yang rumit di usus terganggu. Selain itu, dinding usus
tidak tampak memiliki kapasitas yang sama dalam membentuk sebuah barrier
yang koheren yang memisahkan bakteri lumen dengan sistem imun pada model
T1D bila dibandingkan dengan kontrol. Hal tersebut diistilahkan dengan fenotip
leaky gut (usus bocor) yang diduga dapat meningkatkan eksposure antigen
bakteri terhadap sistem imun. Di usus pasien dengan T1D, juga telah ditemukan
aktivasi imun subklinis dan bukti adanya gangguan subset Treg. Kami telah
menyebutkan adanya enterovirus di spesimen usus, yang mungkin menjadi salah
satu pemicu fenotip inflamasi di usus tersebut. Sebaliknya, pemberian probiotik
yang spesifik mungkin dapat mencegah autoimunitas terhadap islet pada kondisi
tertentu dan penelitian klinis saat ini masih berlangsung untuk memvalidasi
hipotesis tersebut. Secara kolektif, tampaknya antibiotik dan probiotik dapat
mempengaruhi perkembangan T1D dengan mengubah keseimbangan mikroba
usus bisa ke arah tolerogenik ataupun non tolerogenik, tergantung dari konstitusi
mikroflora usus saat pemberian antibiotik dan probiotik tersebut.
Sebuah penelitian oleh Wen et al memberikan titik terang terhadap
beberapa mekanisme yang mengatur keseimbangan rumit di level usus tersebut.
Tikus NOD yang tidak memiliki komponen sinyal TLR yang penting yakni MyD88
justru terproteksi dari diabetes. Selain itu, pemberian sel T CD4+ yang
mengekspresikan reseptor TCR diabetogenik BDC2.5, gagal untuk memperluas
limfonodi pankreas (LN) dari MyD88-/- pada tikus NOD. Dipostulasikan bahwa
pengenalan abnormal terhadap beberapa bakteri usus tertentu mungkin terjadi
pada perkembangan diabetes pada model NOD reguler, di mana pathway ini
tidak terjadi pada varian MyD88. Pemberian antibiotik spektrum luas terhadap
tikus NOD MyD88-/- meningkatkan kembali kemungkinan terjadinya diabetes,
dan tikus MyD88-/- yang bebas bakteri juga menunjukkan resiko T1D bila
dibandingkan dengan tikus NOD MyD88-/- yang tumbuh di lingkungan SPF
rumah. Temuan yang terakhir ini mengindikasikan bahwa setidaknya beberapa
anggota komunitas mikroba di usus mungkin dapat memberikan proteksi
terhadap diabetes secara independen dari MyD88. Meskipun gambaran mekanis
ini jauh dari sempurna, hasil-hasil ini memberikan bukti prinsip peran penting
homeostasis imunitas usus dalam mencegah T1D.
Faktor resiko bakterial yang baru-baru ini ditemukan adalah Mycobacterium
avium subspesies paratuberkulosis (MAP), yang merupakan penyebab
paratuberkulosis pada hewan pemamah biak. Penting dicatat bahwa bakteri ini
juga terdapat pada susu dari sapi yang terinfeksi dan dapat melewati
pasteurisasi. Respon humoral yang secara klinis signifikan terhadap antigen
MAP dan lisis seluruh sel, didapatkan pada pasien dengan T1D. Selain itu,
keberadaan antigen MAP juga ditemukan pada pasien T1D melalui kultur dari
isolat darah. Selanjutnya dilaporkan bahwa polimorfisme dalam gen SLC11A1
terkait dengan adanya DNA MAP pada pasien T1D. Karena MAP bertahan dalam
makrofag dan diproses oleh sel dendritik, disimpulkan bahwa bentuk mutan dari
SLC11A1 dapat mengubah prosesing atau presentasi antigen MAP sehingga
menyebabkan respon diabetogenik. Kami mencatat bahwa semua studi yang
menjadi referensi dari topik ini berasal dari kelompok yang sama yang
mendokumentasikan hubungan dalam populasi Sardinia yang terisolasi. Masih
harus dilihat lebih jauh apakah temuan ini akan dikonfirmasi melalui penelitian
lain dengan pasien yang berbeda.
Kesimpulannya, sebagaimana virus, terdapat banyak bukti tidak langsung
yang mengharuskan kita fokus terhadap bakteri sebagai agen potensial pemicu
T1D.
C. Pencetus Lingkungan Lainnya
Kami telah menemukan kemungkinan kerentanan dari homeostasis
imunitas usus pada T1D, yang menandakan peran potensial dari flora bakterial.
Jelas terdapat banyak substansi lain yang mungkin mengganggu respon
fisiologis di lokasi sistem imun mukosa, beberapa di antaranya diduga
merupakan faktor kausatif pada T1D.
1. Susu Sapi
Susu sapi, dan terutama komponen albumin di dalamnya, diduga memicu
autoimunitas terhadap islet, karena ditemukan adanya reaktivitas silang antara
antibodi serum terhadap albumin dan ICA-1 (p69), sebuah protein permukaan sel
beta. Beberapa penelitian menunjukkan pemberian susu sapi di usia awal
kehidupan menjadi faktor predisposisi diabetes yang berkebalikan dengan durasi
pemberian ASI dalam waktu lama selama bayi. Ide baru mengenai pemberian
susu sapi sebagai kontributor T1D segera mendapat tentangan dari penelitian-
penelitian yang tidak menemukan adanya relevansi kausatif. Sejak saat itu, topik
ini selalu menjadi kontroversi, karena bahkan pada tikus NOD dan strain BB
ditemukan hasil yang saling bertentangan. Hasil yang mendukung adanya
hubungan kausatif dilaporkan dari populasi pasien di Finlandia. Penelitian TRIGR
(Trial to Reduce IDDM in the Genetically at Risk) secara khusus mencatat dan
meneliti hal tersebut. TRIGR akan memeriksa apakah formula bayi terhidrolisis
dapat menurunkan resiko T1D dibandingkan dengan formula berbasis susu sapi
pada anak dengan kondisi genetik yang beresiko. Data-data awal menunjukkan
bahwa formula terhidrolisis memberikan beberapa proteksi dan bahwa antibodi
maternal dapat memberikan proteksi bayi yang mendapatkan ASI terhadap
enterovirus. Penelitian di Finlandia lainnya juga menemukan bahwa polimorfisme
PTPN22 dapat mempengaruhi autoimunitas terhadap islet hanya bila anak
terekspose terhadap susu sapi selama masa awal kehidupan, yang memicu
dikeluarkannya berbagai penjelasan terkait banyaknya temuan yang kontradiktif.
Hingga saat ini, pernyataan-pernyataan yang mendukung peran patogenik dari
protein susu sapi pada T1D masih sedikit. Harrison dan Honeyman memberikan
suatu sudut pandang menarik yakni bahwa peningkatan imunitas terhadap
protein susu sapi, mungkin merefleksikan gangguan umum dalam imunitas
mukosa, dan bukan merupakan faktor resiko yang unik.
2. Protein gandum
Meskipun tidak sebesar susu sapi, protein gandum, atau lebih spesifiknya
gluten, saat ini makin banyak diperhatikan. Sebuah diet bebas susu, berbasis
gandum menghasilkan frekuensi diabetes yang lebih tinggi pada tikus BB dan
NOD, dan pada tikus NOD diet ini menginduksi bias sitokin Th1-type di usus.
Pada pasien T1D, peningkatan reaktivitas sel T darah perifer terhadap gluten
gandum lebih sering ditemukan dibandingkan dengan kelompok kontrol.
Selanjutnya juga dilaporkan bahwa waktu eksposure awal terhadap cereal pada
bayi juga mempengaruhi onset autoimunitas terhadap islet pada anak dengan
resiko. Pola ini menghilang pada celiac disease (CD), sebuah penyakit autoimun
yang diinduksi oleh pemberian gluten pada individu dengan resiko genetik.
Tumpang tindih antara kedua penyakit tersebut telah lama diketahu, dan
prevalensi CD yang tidak terdiagnosis di antara pasien T1D dan keluarganya
ternyata lebih tinggi dari dugaan. Namun tidak seperti pasien CD, belum ada
bukti kuat untuk mengasumsikan bahwa gluten menyebabkan inisiasi
autoimunitas pada T1D. Analog dengan protein susu sapi, reaktivitas imun
terhadap protein gandum pada T1D dapat menjadi konsekuensi umum dari
respon mukosa acak, dan bukan pemicu spesifik autoimunitas terhadap islet.
3. Vitamin D
Beberapa komponen diet mungkin dapat meningkatkan kemungkinan T1D,
namun pengetahuan-pengetahuan saat ini justru mengarah pada efek protektif
vitamin D terhadap T1D. Vitamin D tidak hanya didapatkan dari nutrisi, namun
juga disintesis di kulit saat terekspose matahari. T1D memiliki onset musiman,
dan mandi sinar matahari selama beberapa jam setiap bulan memiliki korelasi
terbalik dengan insiden T1D. Vitamin D secara efektif menghambat diferensiasi
sel dendritik dan aktivasi imun. Level metabolit vitamin D ditemukan lebih rendah
pada plasma pasien dengan T1D saat-saat mendekati onset, dan peningkatan
intake vitamin D dapat menurunkan insiden T1D pada tikus dan manusia.
Pencarian polimorfisme genetik dalam reseptor vitamin D (VDR)
mendapatkan hasil yang bertentangan terhadap korelasi vitamin D dengan T1D
pada sebagian besar penelitian, dan sebuah meta analisis terbaru menyimpulkan
bahwa tidak terdapat bukti adanya hubungan tersebut. Penelitian-penelitian baru-
baru ini mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat hubungan antara polimorfisme
VDR dengan autoimunitas sel beta, namun penelitian-penelitian teresebut
berhasil mengidentifikasi polimorfisme terkait T1D pada gen yang mengkode
enzim yang terlibat dalam metabolisme vitamin D. Menariknya, ditemukan
interaksi antara VDR dan alel HLA yang dimediasi oleh elemen responsif vitamin
D yang ada di regio promoter alel HLA-DRB180301. Dapat diduga bahwa
kurangnya asupan vitamin D pada awal masa kanak-kanak dapat berkontribusi
terhadap perkembangan T1D akibat rendahnya ekspresi DRB1*0301 di thymus.
Singkatnya, vitamin D dapat dianggap sebagai sebuah faktor lingkungan yang
penting dalam menjaga toleransi imun terhadap diri sendiri dan mencegah
autoimunitas. Penting untuk dicatat, penggunaan metabolit vitamin D untuk terapi
pada manusia, masih terhambat oleh efeknya terhadap kalsium dan metabolisme
tulang. Sehingga, saat ini telah didesain analog struktural yang memberikan efek
imunomodulator yang lebih dominan. Terapi aktif T1D dengan analog vitamin D
masih merupakan suatu hal yang menjanjikan di masa depan, dan individu yang
beresiko seharusnya juga berusaha menghindari defisiensi vitamin D.
Sejumlah besar komposisi diet dan pemicu lingkungan juga diketahui dapat
mempengaruhi perkembangan diabetes pada model hewan, dan beberapa di
antaranya adalah asam lemak omega 3, namun bukti pada manusia masih
terbatas.
IV. TIMELINE PATOGENESIS DIABETES TIPE I
Beberapa model timeline telah diajukan untuk memberikan gambaran
outcome dari interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Gambar 1
memberikan tinjauan visual mengenai beberapa hipotesis yang dominan yang
diajukan selama bertahun-tahun. Hipotesis penurunan sel beta linier yang
dipostulasikan oleh Eisenbarth pada tahun 1986, masih merupakan model utama
yang dijadikan referensi untuk T1D. Berdasarkan model ini (Gambar 1A), individu
yang memiliki kerentanan genetik yang pada waktu tertentu terekspose agen
lingkungan tertentu yang dapat memicu autoimunitas terhadap islet akan
mengalami penurunan massa sel beta dalam pola linier, mengalami peningkatan
produksi autoantibodi, hiperglikemia, dan hilangnya C-peptide. Meski hipotesis ini
memberikan penjelasan lengkap mengenai sequence kejadian yang terjadi
selama perjalanan T1D, namun hipotesis ini tidak mengintegrasikan faktor-faktor
yang berkontribusi terhadap variabilitas axis waktu selama fase pre-diabetes.
Beberapa peneliti menyatakan bahwa progres penyakit T1D bukan merupakan
proses yang linier, namun lebih merupakan proses dengan variasi kecepatan
sesuai masing-masing pasien. Pada bab sebelumnya, kami telah mendiskusikan
efek dari polimorfisme genetik spesifik terhadap kerentanan terjadinya T1D.
Tampaknya bisa diterima bahwa bila spektrum polimorfisme genetik sangat
ekstrim (contoh: IPEX dan APS-1, serta mungkin juga haplotipe HLA) maka
hanya dibutuhkan pemicu yang rendah dari lingkungan untuk menimbulkan
penyakit, dan pasien akan kehilangan massa sel beta dalam pola linier apapun
pemicunya (Gambar 1Bi). Di sisi lain, bila mutasi yang terjadi tidak terlalu berat,
maka tidak akan berkembang menjadi T1D bila tidak ada pemicu (Gambar 1Bii),
atau membutuhkan pemicu lingkungan yang berat (contoh: IFIH1 dan infeksi
virus) untuk pada akhirnya menyebabkan hiperglikemia (Gambar 1B, iii dan iv).
Kelompok kami, mengambil kesimpulan yang sama dengan Bonifacio et al, yakni
mengajukan sebuah versi yang lebih mendetail dari model non-linier yang
menggambarkan T1D sebagai sebuah penyakit yang kambuh-kambuhan
(Gambar 1C). Secara spesifik, kami menyatakan bahwa ketidakseimbangan
antara sel T efektor autoreaktif dan Tregs dapat terjadi seiring waktu dan pada
akhirnya dapat menyebabkan penurunan massa sel beta. Saat keseimbangan
bergeser ke arah autoimunitas terhadap islet, maka efek ini untuk sementara
akan dilawan oleh respon proliferatif dari sel beta, sehingga menghasilkan suatu
fase penurunan kebutuhan insulin pengganti yang disebut honeymoon phase
(Gambar 2). Untuk menyesuaikan peran agen infeksi ke dalam model T1D
sementara ini, kami memperkenalkan hipotesis fertile field. Fertile field (Gambar
1D) dideskripsikan sebagai sebuah jendela waktu saat terjadi infeksi virus, yang
dapat bervariasi sesuai tipe infeksi, lokasi anatomis , dan durasi respon inflamasi
akibat virus. Fertile field ini akan memicu ekspansi sel T autoreaktif melalui
mekanisme mimikri molekuler atau aktivasi bertahap dan mungkin akan
mengakibatkan autoimunitas total serta T1D.
Gambar 1. Timeline untuk diabetes tipe 1. A: model penurunan massa sel beta
secara linier, sebagaimana diajukan oleh Eisenbarth. Dalam hal predisposisi
genetic, pemicu lingkungan akan menginduksi autoimunitas terhadap islet dan
kematian sel beta sehingga menyebabkan kondisi pre-diabetik dan selanjutnya
terjadi onset klinis. B: Telah diakui secara luas bahwa jangka waktu antara
inisiasi autoimunitas dan onset klinis sangat bervariasi. Chatenoud dan
Bluestone mengajukan beberapa scenario terkadi variabilitas tersebut. Interaksi
antara faktor genetic dan faktor lingkungan seperti infeksi virus sangat mungkin
akan menyebabkan fluktuasi massa sel beta sebelum muncul onset. C: kami
telah mengajukan konsep T1D sebagai suatu penyakit kambuh-kambuhan,
bergantung dari disrupsi dan pengembalian keseimbangan yang siklis antara sel
T efektor dan Tregs dan mungkin dapat menghambat proliferasi sel beta. Model
ini juga memberikan suatu alasan mekanis untuk perjalanan klinis T1D yang
bervariasi. D: Hipotesis fertile field mempostulasikan adanya jangka waktu
setelah infeksi virus di mana seorang individu dengan resiko dapat mengalami
autoimunitas. Infeksi oleh virus tertentu akan menciptakan suatu fertile field untuk
sementara waktu. Eksposure awal terhadap virus (contoh: melalui presentasi
APC, sel purple) akan menciptakan suatu respon antivirus normal (sel T hijau),
kemudian pembentukan sel T autoreaktif (sel T merah) dapat terjadi melalui
reaktivitas silang dengan antigen virus (mimikri molekul) ataupun melalui
pengenalan langsung terhadap autoantigen (aktivasi bystander). Aktivasi
bystander diduga dimediasi oleh APC yang memproses dan mempresentasikan
self-antigen, dengan potensi untuk menimbulkan suatu sel T autoreaktif hanya
bila terdapat sinyal bahaya dari virus.
Gambar 2. Bagaimana T1D bisa muncul. Gambar ini merepresentasikan massa
atau fungsi sel beta (garis oranye) serta perbedaan fase imunologis (kolom
dengan alphabet di atasnya) yang terjadi pada lokasi anatomis yang relevan
(baris dengan angka di sebelah kanannya). Kejadian spesifik akan dikaitkan
melalui koordinat alfa-numerik dalam penjelasan sebagai berikut. Saat garis
oranye dari fungsi sel beta menurun hingga zona merah, individu tersebut dapat
didiagnosis secara klinis dengan T1D. Sebuah seri kejadian yang kompleks
sudah mendahului proses tersebut dan sebagian besar tidak terdeteksi. Pada
awalnya, terjadi sebuah kelainan sehingga menimbulkan kerentanan genetic (a1)
yang berinteraksi dengan sebuah pemicu dari lingkungan (a2) sehingga
kemudian terjadi dua hal yang menyebabkan individu tersebut mengalami
diabetes. Di pancreas, sel beta akan meng-up-regulasi IFN- (b3) dan
selanjutnya MHC klas I (c3). Hal ini akan membuat sel beta mudah diserang oleh
sel T CD8 autoreaktif yang spesifik terhadap antigen dalam pancreas.
Konsekuensinya, antigen sel beta yang terlepas akan diambil oleh sel APC di
sekitarnya (c3) dan ditransfer ke limfonodi yang mendrainase pancreas (c2).
Sedangkan di perifer (c1), pemicu dari lingkungan akan menyebabkan
pergeseran metabolomik sehingga menciptakan suatu lingkungan pro inflamasi
yang meningkatkan respon sel T efektor lebih dari fungsi Tregs. Antigen sel beta
yang dipresentasikan dalam kondisi inflamasi tersebut dan dengan bantuan CD4
(c2) akan menginisiasi konversi sel B menjadi sel plasma (d2) dan produksi
autoantibodi insulin (serokonversi) (d1). Selain itu, sel T CD8 juga akan
terstimulasi untuk berproliferasi (d2) dan bermigrasi ke pancreas (d3). Stress
kedua yang diinduksi oleh kematian sel beta (d3), yang melibatkan perforin, IFN-
, dan TNF-, akan menyebabkan beberapa sel beta menghentikan produksi
insulin (pseudoatrofi). Kematian ini juga menyebabkan pelepasan antigen sel
beta yang baru yang akan diambil oleh APC, termasuk sel B yang bermigrasi
(d3), dan pada akhirnya akan dibuang ke limfonodi pancreas (d3-d2). Ini
menciptakan suatu spesifisitas baru untuk CD4 (e2) dan CD8 (e1) dalam sebuah
proses yang disebut penyebaran epitope. Kematian sel beta yang terjadi
selanjutnya akan lebih berat dan biasanya menyebabkan penurunan hebat fungsi
dan massa sel beta (e3). Menariknya, inflamasi autoimun juga dapat
menstimulasi beberapa proliferasi sel beta (f3), sehingga massa sel beta untuk
sementara waktu dapat dikembalikan. Selain itu, terkadang Tregs dapat
meningkat dan menurunkan respon sel T efektor (f3). Fluktuasi antara respon
autoreaktif yang destruktif dan penurunan respon oleh regulasi imun dan
proliferasi sel beta mungkin akan menciptakan suatu siklus sembuh-kambuh
yang non-stop terhadap massa sel beta (garis oranye). Pada akhirnya hal
tersebut akan dimenangkan oleh respon autoreaktif, dan T1D akan terdiagnosis
pada 10-30% massa sel beta yang tersisa. Remisi yang terjadi setelah diagnosis
klinis diabetes ditegakkan diistilahkan dengan fase honeymoon (f3), sebuah
tahap temporer di mana terjadi produksi insulin yang relative cukup.
V. FAKTOR IMUNOLOGI DALAM DIABETES TIPE I
Beberapa kejadian imunologis tanpa gejala terjadi selama sebelum muncul
gejala klinis diabetes tipe1. Beberapa yang paling penting yakni produksi
autoantibodi, aktivasi limfosit self-reactive, di mana limfosit ini kemudian
menginfiltrasi pankreas sehingga menghancurkan sel beta yang memproduksi
insulin di islet Langerhans. Kerusakan spesifik yang persisten ini mungkin terjadi
tanpa diketahui selama bertahun-tahun, dan gejala klinis utama hanya akan
tampak setelah mayoritas sel beta rusak atau mengalami disfungsi, sehingga
individu tersebut akan bergantung pada pemberian insulin dari luar (gambar 2).
Sehingga, saat ini diprioritaskan pencarian biomarker yang dapat menandai
respon autoimun yang sedang terjadi. Kami akan menggarisbawahi beberapa
kejadian imunologis yang penting di sini. Informasi tambahan mengenai interaksi
silang antar sel imun pada T1D akan dibahas di lain bab.
A. Perubahan Metabolik: Keterkaitan Kausatif dengan Faktor Imunitas?
Sejauh ini, serokonversi menjadi autoantibodi positif merupakan tanda
utama yang dapat dideteksi dari respon autoimun yang sedang berjalan. Namun
Oresic et al, baru-baru ini menyatakan bahwa disregulasi metabolik terjadi lebih
dulu sebelum muncul autoimunitas pada T1D. Peningkatan konsentrasi
lysophosphatidylcholine (lysoPC) di serum, mendahului munculnya auto-antibodi
islet. Pada sampel yang diambil dari penelitian cohort Finnish DIPP, perubahan
karakteristik metabolit serum hanya ditemukan pada anak-anak yang pada
nantinya menderita T1D. Perubahan ini mencakup penurunan suksinat, PC,
fosfolipid, dan ketoleusin dalam serum, serta peningkatan asam glutamat dalam
serum. Produk sampingan lipid yang reaktif tersebut memiliki kapasitas untuk
mengaktivasi molekul pro-inflamasi, yang berfungsi sebagai pendukung alami
sistem imun. Namun masih belum diketahui apakah kejadian metabolik tersebut
dapat memicu periode autoimun, atau hanya karena lebih mudah dideteksi.
Namun, temuan ini memberikan kesempatan untuk menegakkan diagnosis dini.
B. Sel B Memproduksi Auto-antibodi Anti-Islet yang Berkaitan dengan
Diabetes
Autoantibodi utama pada T1D bersifat reaktif terhadap empat autoantigen
islet (islet cell autoantibodies atau ICA): insulinoma-associated antigen-2 (I-A2,
ICA512), insulin (mikro IAA atau mIAA), glutamic acid decarboxylase 65
(GAD65), dan zinc transporter 8 (ZnT8). Adanya autoantibodi dini
menggambarkan peran dari sel B plasma dalam memproduksi antibodi di awal
proses imunologis. Memang, sel B dengan jelas berkontribusi terhadap
patogenesis T1D pada manusia. Pada model NOD, sel B menginfiltrasi pankreas
selama tahap awal insulitis, dan ablasi sel B baik secara genetik ataupun
dimediasi oleh antibodi pada tikus NOD, dapat memberikan efek proteksi.
Bagaimana, kapan, dan di mana sel B berkontribusi terhadap onset diabetes
masih diperdebatkan dan didiskusikan dengan detail di lain topik. Singkatnya,
karena autoantibodi yang diproduksi oleh sel B merefleksikan sebuah
pendahuluan kondisi autoimunitas, sel B sangat mungkin berpartisipasi aktif
dalam respon imun karena kapasitasnya untuk mempresentasikan antigen ke sel
T CD4 dan CD8 diabetogenik.
C. Sel T yang Spesifik terhadap Islet di Perifer
Definisi tekstual dari T1D dapat berupa sebuah penyakit autoimun di mana
sel T CD4+ dan sel T CD8+ menginfiltrasi islet of Langerhans, sehingga
menyebabkan destruksi pada sel beta. Memang, sel T dianggap sebagai
eksekutor terakhir destruksi sel beta. Hal ini dibuktikan melalui presipitasi
ataupun prevensi dari diabetes melalui transfer atau eliminasi sel T CD4 atau sel
T CD8. Perusakan sel beta oleh sel T CD8 merupakan mekanisme mayor
destruksi sel beta. Sel-sel T CD8 yang ditemukan pada lesi insulitik tikus NOD
dan manusia (Gambar 3), dapat merusak sel-sel beta melalui aktivasi MHC klas I
yang diekspresikan pada sel beta. Dan memang, defisiensi MHC klas I akibat
kurangnya mikroglobulin beta-2, ataupun defisiensi MHC-I spesifik sel beta,
sudah cukup untuk menghentikan perkembangan diabetes dan mencegah
destruksi sel beta pada NOD. Secara mekanis, destruksi sel beta dapat
melibatkan pelepasan granula sitolitik oleh sel T CD8 yang mengandung perforin
dan granzyme, atau melalui interaksi Fas dan Fas ligand. Sel T CD4
kemungkinan besar membantu sel T CD8 dan sel B dengan menyediakan
sitokin, seperti IL-21, dan sebuah positive feedback loop melalui interaksi CD40L-
CD40 terhadap sel APC, yang pada akhirnya meningkatkan respon autoreaktif
sel T CD8. Keberadaan sel T CD4 pada lesi insulitik menunjukkan adanya peran
sel tersebut dan kapasitasnya dalam inflamasi.
Pertanyaan-pertanyaan mengenai epitop sel T autoreaktif telah terpusat di
sekitar empat macam protein yang juga merupakan target utama auto-antibodi:
proinsulin (PI), GAD65, I-A2, dan ZnT8. Sejauh ini, masih belum dapat ditentukan
secara sistematis kapan autoantibodi dan sel T autoreaktif muncul di perifer bila
dikaitkan satu sama lain. Sebuah sumber menarik dalam topik ini dapat dilihat
pada tinjauan yang dilakukan oleh Di Lorenzo et al yang membuat sejumlah
besar portofolio mengenai epitop-epitop yang teridentifikasi hingga saat ini. Yang
penting diketahui adalah, bahwa secara umum epitop utama dari sel T CD4+
yang diketahui, berasal dari GAD65, I-A2, dan PI baik pada manusia maupun
tikus. Selain itu, ada pula sedikit kontribusi dari heat shock protein (HSP)-60 dan
islet specific glucose-6-phosphatase catalytic subunit-related protein (IGRP),
sebagaimana HSP70 pada manusia. Di sisi lain, epitop CD8 autoreaktif manusia
terutama berasal dari preproinsulin signal peptida, dan sebagian kecil berasal
dari IA2, human islet amyloid polypeptide (IAPP) precursor protein, IGRP, cation
efflux transporter ZnT8 (Slc30A8), dan GAD65. Di tikus, epitop CD8 terutama
berasal dari IGRP dan GAD65/67, dan ~30% berasal dari PI serta 10% dari
dystrophia myotonica kinase (DMK). Menariknya, epitop peptida CD8
diidentifikasi dari human preproinsulin signal peptide melalui elusi dari molekul
HLA-A2. Hal ini mengarahkan pada konsep bahwa sel beta secara langsung
berkontribusi terhadap kehancuran dirinya sendiri, karena sel beta akan semakin
banyak menjadi target penghancuran saat distimulasi untuk menghasilkan lebih
banyak insulin. Secara umum, data-data memberikan bukti kuat bahwa
autoreaktifitas sel T CD8 terkait dengan destruksi sel beta pada T1D di manusia.
Gambar 3. Derajat infiltrasi pancreas pada pasien T1D terbatas bila
dibandingkan dengan infiltrasi pada tikus NOD di saat-saat onset diabetes.
Infiltrasi di dalam atau di sekitar islet Langerhans di pancreas terdiri atas sel T
CD8, sel T CD4, juga sel B, makrofag, dan sedikit sel dendritic. Dalam hal tipe-
tipe sel infiltrate tersebut, sudah dibuktikan melalui irisan pancreas pada manusia
maupun tikus NOD. Namun derajat inflamasi pancreas dan islet, yang dilihat dari
jumlah sel-sel infiltrate, jauh lebih sedikit pada manusia dibandingkan dengan
tikus NOD. A: derajat khas infiltrasi pada T1D onset baru di pancreas manusia.
Pewarnaan irisan pancreas untuk insulin (hijau) dan sel T CD8 (merah)
mengindikasikan bahwa hanya sedikit sel T CD8 yang dapat dilihat di sekitar
islet. Derajat infiltrasi yang sama rendahnya juga terlihat dari jumlah sel T CD4
dan sel B di irisan pancreas pasien T1D (tidak ditunjukkan). Informasi lebih lanjut
dapat dilihat pada Referensi 99. B: inflamasi khas saat-saat onset diabetes pada
tikus NOD betina. Pewarnaan untuk insulin (biru) dan CD8 (coklat-merah)
menunjukkan infiltrasi berat sel T CD8 di islet. Tipe dan derajat infiltrasi sel T
CD4 di saat-saat onset tersebut biasanya juga sama beratnya.
D. Faktor Imunologis di Pankreas Manusia
Baru-baru ini kami mengkaji status terbaru pengetahuan kami terhadap
histopatologi T1D. Kami menyimpulkan bahwa pengertian dasar kami mengenai
apa yang terjadi di pankreas adalah berdasarkan observasi di masa lalu, hingga
tahun 1960an.
Pada tahun 1965, Willy Gepts pertama kali mengidentifikasi infiltrasi
limfositik pada islet pankreas. Sejak saat itu, hal tersebut menjadi karakteristik
utama T1D yang disebut insulitis. Pada sebuah laporan kasus tahun 1985,
Bottazzo et al, menunjukkan upregulasi molekul MHC klas I yang dramatis dan
menunjukkan sel T CD8+ sebagai subset yang dominan di sekitar islet.
Observasi ini dikonfirmasi melalui sebuah pengumpulan sampel dalam jumlah
besar oleh Foulis et al. Beberapa pandangan utama di kemudian hari didasarkan
pada analisis lanjutan dari spesimen tersebut. Salah satu penelitian utama
menunjukkan bahwa upregulasi MHC klas I merupakan karakteristik umum
dalam islet diabetik di saat-saat mulai muncul onset. Patut dicatat bahwa
sejumlah besar IFN- ditemukan secara eksklusif di sel beta. Hal ini menambah
ketertarikan akan kemungkinan adanya etiologi virus, karena IFN- biasanya
muncul sebagai respon seluler terhadap infeksi virus. Secara umum, temuan-
temuan ini menyusun ide bahwa T1D merupakan sebuah penyakit autoimun
dengan banyak tahap (Gambar 2).
Telah diakui secara luas bahwa proses autoimun sangat bervariasi, baik
antar pasien ataupun dalam satu pasien seiring waktu. Foulis et al
mengestimasikan bahwa jumlah limfosit yang terkait dengan inflamasi islet
adalah ~85%. Sekitar 23% islet yang masih memproduksi insulin mengandung
limfosit, dan hanya 1% islet yang defisien insulin yang mengandung islet. Pada
penelitian di Jepang, dengan menggunakan biopsi, tidak ditemukan atau hanya
sedikit (2-62 sel MN di 3-33% islet) tanda insulitis. Penelitian dari Jepang ini
kurang akurat dalam hal pengambilan sampel, karena hanya mengambil area
pankreas yang terbatas.
Willcox et al, baru-baru ini memeriksa kembali berbagai temuan lama
dengan menggunakan reagen-reagen modern terhadap sampel yang
dikumpulkan oleh Foulis et al. Sel-sel T CD8+ dkonfirmasi merupakan sebuah
komponen seluler dari lesi insulin. Juga, jumlah puncak CD8 terkait dengan
derajat kerusakan dan kehilangan sel beta dari islet yang mengalami
pseudoatrophy (contoh: defisien insulin). Sel B ditemukan juga dengan pola yang
sama. Di sisi lain, makrofag hanya terdapat dalam jumlah sedang selama proses
penyakit. Menariknya, Tregs terdeteksi dalam islet hanya pada satu pasien. Hal
ini menunjukkan bahwa teritori asli dari Tregs adalah pada limfonodi pancreas
atau limpa. Alternatif lain adalah bahwa ketiadaan Tregs ini merupakan alasan
mengapa dapat terjadi insulitis.
Konsekuensi logis dari autoimunitas terhadap sel beta adalah tentunya
induksi apoptosis. Meski begitu, penelitian histologi cross-sectional menunjukkan
hanya sedikit terjadi apoptosis sel beta. Rentang estimasi mulai dari nol, 0.2 sel
beta per islet, hingga 6% dari keseluruhan sel beta. Rendahnya tingkat apoptosis
sel beta secara keseluruhan pada setiap waktu, merefleksikan alasan utama
lambatnya perjalanan penyakit T1D. Peran potensial dari survivin, sebuah
molekul yang terlibat dalam proteksi terhadap apoptosis, baru-baru ini ditemukan
dalam model hewan dan pasien T1D.
Sel beta memiliki kapasitas besar untuk beregenerasi melalui proliferasi,
yang kemungkinan merupakan respon terhadap inflamasi akibat imunitas,
setidaknya hal ini terjadi pada tikus NOD. Beberapa bukti pada manusia,
menggunakan marker proliferasi Ki-67, mengindikasikan tidak ada, terbatas, atau
ekstensif proliferasi sel beta pada berbagai tahap penyakit. Salah satu
penjelasan yang mungkin mengenai perbedaan antar spesies tersebut mungkin
karena kurangnya kondisi inflamasi pada manusia. Karakterisasi T1D pada
pankreas melalui pemeriksaan imunohistokimia telah dilakukan pada sampel dari
individu-individu dengan onset baru. Data-data dari tahap awal penyakit pada
pasien predibetes akan sangat berharga. Karena adanya insulitis dan status
autoantibodi di saat-saat munculnya onset sangat berkaitan, maka skrining
serum terhadap individu yang sehat dapat dilakukan untuk mengidentifikasi
abnormalitas imunologis awal di sekitar islet pasien pre-diabetes dengan
autoantibodi yang positif. Hanya satu penelitian yang secara sistematis
memeriksa donor sehat dengan autoantibodi yang positif. Penelitian ini
menunjukkan sangat rendahnya insiden insulitis yakni hanya 2 pada 62 kasus,
pada <10% islet. Outcome ini mungkin merefleksikan proses diabetogenik yang
sangat samar pada sebagian besar kasus pada manusia, yang mungkin
menandakan perjalanan penyakitnya yang kambuh-kambuhan. Alternatif lain,
data-data ini mungkin mengilustrasikan progres lobular yang besar, sehingga
dengan mudah terlewatkan.
E. Fase Honeymoon: Apakah Sel Beta Hidup Kembali Sementara Waktu?
Sudah jelas bahwa pasien sudah berada pada tahap akhir penyakit saat
presentasi klinis mulai muncul. Presentasi klinis muncul saat 60-90% sel beta
sudah rusak atau mengalami disfungsi. Namun jumlah pastinya sel beta yang
masih tersisa saat onset penyakit dimulai masih belum diketahui karena kurang
akuratnya pemeriksaan imaging non invasif untuk menghitung fungsi massa sel
beta pada manusia. Faktanya, pemeriksaan massa sel beta melalui deteksi
insulin melalui imunohistokimia mungkin akan menghasilkan suatu hasil yang di
bawah kenyataan sebenarnya. Penelitian-penelitian pada tikus NOD menemukan
sebuah kutub sel beta yang substansial namun non-fungsional (tidak
menghasilkan insulin) saat onset hiperglikema. Pengetahuan mengenai besarnya
jumlah sel beta yang mengalami penurunan fungsi sangat penting karena lebih
dapat dilakukan penghidupan kembali sel beta daripada regenerasi sel beta.
Sebuah kesempatan yang paling berharga untuk upaya tersebut adalah pada
masa honeymoon, sebuah fase remisi sementara yang terjadi hingga pada 60%
pasien setelah diberikan terapi awal insulin (Gambar 2). Fase honeymoon
tampaknya makin sering terjadi seiring meningkatnya usia saat onset dan dapat
berlangsung 3-6 bulan, namun juga dapat berlangsung hingga 2 tahun. Dalam
periode ini, dosis insulin dapat diturunkan secara signifikan atau bahkan tidak
diberikan sama sekali. Mekanisme yang dapat memperbaiki fungsi sel beta pada
fase ini masih belum dimengerti sepenuhnya, namun diduga bahwa stimulus
hiperglikemia yang konstan pada akhirnya akan membuat sel beta kelelahan.
Pemberian insulin awal akan menurunkan faktor stress tersebut terhadap sel
beta dan untuk sementara waktu memungkinkan sel beta yang mengalami
disfungsi untuk memperbaiki diri. Kami telah meneliti fase remisi ini dari
perspektif imunologis. Pada sebuah penelitian cohort terhadap pasien, kami
memfokuskan terhadap respon sitokin dari sel T terhadap antigen di darah
perifer. Menariknya, kami menemukan level FoxP3 yang lebih rendah pada sel
CD4+, sel CD25+, Tregs, dan rendahnya jumlah sel yang memproduksi IL-10
pada pasien remisi bila dibandingkan pasien dengan onset baru. Pada sebuah
peelitian cross sectional prospektif yang terbatas, kami menemukan bahwa
ekspresi FoxP3 yang lebih tinggi saat diagnosis, menjadi prediksi kontrol glikemik
yang lebih buruk, namun tingginya jumlah sel yang memproduksi IL-10 terkait
dengan kontrol glukosa yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian lain
melaporkan rendahnya level IFN- pada pasien remisi. Secara umum, data-data
tersebut menunjukkan bahwa mungkin terdapat komponen imunologis yang
mendasari fase honeymoon, yang menyebabkan imunomodulasi spesifik
terhadap antigen sehingga mengakibatkan autoimunitas segera setelah
diagnosis. Terakhir, masih harus dilihat kembali apakah temuan di sirkulasi
perifer ini terkait dengan kejadian-kejadian imunologis lokal di pankreas.
Pertanyaan ini khususnya sulit untuk dijawab karena sulitnya akses ke sampel
pasien.
F. NOD Tikus: Sebuah Gambaran yang Sangat Berbeda
Fase honeymoon tidak terjadi pada tikus NOD. Hal ini mengindikasikan
perjalanan penyakit yang lebih akut pada tikus NOD. Karenanya,
memperbandingkan histopatologi khas dari pasien T1D dengan tikus NOD onset
baru, seperti melihat pada dua penyakit yang berbeda (Gambar 3).
Progress diabetes pada tikus NOD betina ditandai dengan peri-insulitis non
destruktif, yang pada awalnya mengandung sel dendritik dan makrofag,
kemudian diikuti oleh sel B. Fase ini selanjutnya mengalami transgresi menjadi
sebuah destruksi sempurna terhadap sel beta yang dimediasi oleh sel T pada
usia 4-6 bulan. Level inflamasi pada akhirnya menjadi sangat ekstensif bahkan
terjadi infiltrasi hingga struktur limfoid tersier lokal. Karakteristik ini jauh lebih
agresif dibandingkan proses imunitas pada manusia yang samar dan kronis.
Parameter lain yang berbeda pada NOD termasuk kemampuan potensial sel
beta untuk berproliferasi dalam kondisi inflamasi dan besarnya massa sel beta
non fungsional saat onset penyakit. Masih belum diketahui apakah hal ini terjadi
pada T1D manusia. Secara keseluruhan, perbedaan ini mungkin menjelaskan
mengapa banyak strategi pencegahan dan terapi yang sukses pada model NOD,
yang tidak dapat diterapkan di klinis.
VI. IDENTIFIKASI INDIVIDU PRE-DIABETES
Secara klinis, pre-T1D merupakan periode destruksi sel beta yang sedang
berjalan di mana masih terdapat cukup banyak massa sel beta yang fungsional
untuk menjaga homeostasis glukosa. Para klinisi dan peneliti setuju bahwa
serangan diabetogenik yang samar di tahap sangat awal destruksi sel beta
merupakan waktu yang paling tepat untuk memulai terapi T1D. Hal ini karena
mungkin sekali untuk menjaga terapi dalam dosis yang rendah sehingga hanya
sedikit memberikan efek samping. Secara diagnostik, penentuan destruksi sel
beta yang sedang berjalan sangat sulit, namun individu dengan resiko tinggi
dapat diperiksa melalui seperangkat pemeriksaan (Tabel 1).
A. Skrining Genetik
Di atas kami telah mendiskusikan komponen genetik dari T1D. Kerentanan
genetik dari T1D ditentukan oleh gen yang terkait dengan fungsi imun dengan
pengecualian terhadap gen insulin. Komponen kerentanan genetik pada T1D
memungkinkan beberapa strategi pencegahan primer terhadap anggota keluarga
pasien dengan T1D, namun diketahui tidak ada pewarisan total dari penyakit ini.
Meski begitu, resiko terjadinya T1D tetap 10-15 kali lebih besar dibandingkan
dengan orang tanpa riwayat keluarga. Meskipun ~70% individu dengan T1D
membawa genotip beresiko pada lokus HLA, hanya 3-7% carrier resiko genetik
tersebut yang mengalami diabetes.
Sehingga, fokus lebih diberikan terhadap keluarga dari individu dengan
diabetes, khususnya saudara kembar, dan juga genotip yang terkait dengan
resiko tinggi T1D, contohnya genotip heterozigot DR3/4-DQ2/8.
B. Auto-antibodi Anti-Islet terkait Diabetes
Diduga jumlah autoantibodi, bukan spesifisitas autoantibodi, yang lebih
prediktif dalam proses perjalanan diabetes. Pada penelitian BABYDIAB hampir
tidak ada anak yang hanya mengekspresikan satu jenis antibodi yang mengalami
diabetes. Di sisi lain, hampir semua individu yang mengekspresikan berbagai
antibodi terkait diabetes akan ber-progress menuju diabetes dalam follow up
jangka panjang. Dalam penelitian cohort lainnya, dikonfirmasi bahwa ekspresi
dari dua atau lebih antibodi terkait dengan resiko yang sangat tinggi untuk
diabetes tipe I, dan jarang bersifat sementara. Meski demikian, autoantibodi
dapat berfluktuasi atau bahkan menghilang sama sekali. Sebuah contoh dapat
ditemukan pada penelitian American Diabetes Autoimmunity Study in the Young
(DAISY), yang mengarah pada usia anak karena dilakukan follow up mulai lahir.
Sekitar 95% anak pre-diabetes mengekspresikan autoantibodi anti-insulin namun
saat onset, hanya 50% yang tetap mengekspresikan autoantibodi anti insulin.
Sama dengan yang terjadi pada tikus NOD, autoantibodi anti insulin dapat
bersifat sementara selama proses menuju diabetes. Sehingga, spesifisitas ganda
dari autoantibodi-autoantibodi yang ada juga harus diperiksa. Skrining untuk
autoantibodi terhadap ICA512, insulin, dan GAD65 dapat dilakukan oleh dokter
layanan primer, namun untuk ZnT8 tidak tersedia atau hanya dapat dilakukan
pada fase penelitian. Informasi lainnya dapat dicari di sumber lain.
Tabel 1 Metode Skrining Saat Ini dan Masa Depan untuk Diagnosis T1D
Skrining Kriteria Pertimbangan
Genetic Hubungan dengan individu diabetic
(biasanya saudara derajat pertama)
atau teridentifikasi memiliki genotip
HLA resiko tinggi (DR3/4-DQ2/8)
Hanya 30-50% pasien T1D
yang memiliki genotip HLA
DR3/4-DQ2/8
Hanya 50-80% kembar
monozigot yang menderita
diabetes
Serologis Autoantibodi serum terkait dengan sel
beta islet (ICA): I-A2, IAA atau mIAA,
GAD65, ZnT8
Adanya autoantibodi dapat
berfluktuasi
Metabolik Produksi insulin fase pertama (oleh C-
peptida) cukup rendah sehingga
menghasilkan resiko diabetes >50%
dalam 5 tahun kedepan dan/atau IFG
atau IGT
Defek pada control glukosa
mungkin sudah terlalu
terlambat untuk dilakukan
terapi pencegahan yang
efektif
Sel T Immunoblot seluler, Elispot, dan
tetramers
Masih belum ada standarisasi
dan reprodusibiliti antar pusat
pemeriksaan
Metabolomik Peningkatan konsentrasi lysoPCs di
serum
Validasi spesifisitas, akses,
hingga spektrometri massa
Massa sel beta PET menggunakan IC2 Ab yang Validasi spesifisitas
dilabel
C. Pemeriksaan Sel-T yang Spesifik terhadap Islet
Meskipun sel T berkontribusi kuat terhadap patogenesis penyakit,
keberadaan sel T yang autoreaktif tidak selalu rutin diperiksa. Penjelasan untuk
hal ini adalah masih kurangnya pemahaman mengenai epitop dan kurangnya
pemeriksaan yang cukup kuat untuk mendeteksi sel T dengan afinitas rendah
atau frekuensi rendah. Juga masih belum pasti apakah sirkulasi darah perifer
dapat merefleksikan kutub sel T yang tepat (sama seperti di pankreas).
Contohnya, sel T autoreaktif mungkin secara selektif tersekuestrasi di islet atau
limfonodi paralimfatik, yang menyebabkan sulitnya deteksi melalui sirkulasi darah
perifer. Selain itu, lingkungan mikro di pankreaas mungkin juga dapat merubah
respon dari sel T. Data-data terbaru memang menunjukkan bahwa pemeriksaan
seluler yang dilakukan di darah perifer memberikan akurasi yang tinggi.
Pemeriksaan sel T dapat membedakan respon dari pasien T1D dengan subyek
sehat, namun reprodusibilitas dari pemeriksaan tersebut tampaknya terbatas,
khususnya untuk respon CD4. Namun jika dikombinasikan dengan pemeriksaan
autoantibodi, pemeriksaan akan mencapai tingkat sensitivitas sebesar 75%
dengan spesifisitas sebesar 100% dalam membedakan pasien diabetes dengan
kontrol. Penjelasan yang mungkin untuk hal ini adalah mungkin respon sel T
terhadap epitop individu berfluktuasi seiring waktu, sedangkan autoreaktifitas
tetap bertahan pada pasien diabetik.
Pemeriksaan sel T akan lebih sensitif di masa depan, dan data longitudinal
sistemik pada respon sel T yang spesifik epitop juga akan tersedia. Hal tersebut
akan dapat memfasilitasi usaha-usaha untuk menentukan jumlah dan/atau fungsi
sel T autoreaktif dan marker imun lainnya dalam kondisi-kondisi berikut ini.
1. Skrining Pencegahan
Terdapat kebutuhan mendesak akan sebuah biomarker terkait dengan
proses awal dan perjalanan penyakit T1D. Skrining terhadap spesifisitas sel T
menunjukkan bahwa jumlah, kapasitas fungsional, dan spesifisitas dari
reaktivitas autoimun dapat mengekspose aktivitas penyakit. (1) Jumlah
menunjukkan apakah dan seberapa ekstensifkah sel T autoreaktif yang telah
terlibat. (2) Kapasitas fungsional merupakan sebuah parameter yang
membandingkan pro-inflamasi versus sitokin imunoregulasi. Contohnya, individu
yang memiliki HLA-DR4 yang mengandung sel T CD4+ reaktif terhadap islet dan
memproduksi IL-10, dapat menderita T1D 7 tahun lebih akhir daripada individu
yang tidak memiliki gen dan leukosit tersebut. (3) Spesifisitas mengindikasikan
apakah dan seberapa banyak autoantigen islet untuk CD4 maupun CD8 yang
telah menjadi target, serta apakah sudah muncul epitop sekunder (setelah
penyebaran epitop). Hasil skrining karakterisasi sel T ini akan memungkinkan kita
untuk menyusun strategi yang mengarah langsung pada respon imun. Antigen
yang optimal untuk induksi Tregs juga dapat dipilih, atau juga dapat dilakukan
pendekatan yang lebih sistemik. Dalam hal ini, beberapa terapi dapat mencegah
diabetes bila diberikan di awal proses autoimun, namun dapat memperberat
respon imun bila diberikan saat sudah ada sel T CD8 autoreaktif di perifer.
2. Transplantasi
Transplantasi islet dan terapi penggantian sel beta memberikan
kesempatah khusus untuk memonitor kemungkinan destruksi islet ulang akibat
autoimun dalam waktu yang relatif singkat. Pemantauan terhadap respon sel T
sebelum dan sesudah transplantasi menunjukkan bahwa respon imun terhadap
allograft islet terkait dengan hilangnya fungsi sel beta. Pemantauan sel T ini juga
dapat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat dalam proses
tersebut serta membedakan efikasi dari berbagai protokol supresi imun yang
berbeda. Memang, perlu untuk secara ketat memonitor respon sel T dalam
penelitian transplantasi islet. Contohnya, sel T autoreaktif dapat berekspansi
secara homeostasis setelah diberikan regimen imunosupresan yang digunakan
dalam transplantasi islet, di mana hal ini menjelaskan mengapa independendi
insulin tidak dapat dipertahankan secara permanen dalam protokol Edmonton.
3. Marker primer dan Marker follow up untuk Hasil-hasil Penelitian
Kami mengusulkan bahwa efikasi imunologis dan keamanan dari
pemberian intervensi imunologis untuk dimonitor melalui penelitian perubahan
autoreaktifitas sel T. Pemeriksaan-pemeriksaan yang saat ini tersedia sudah
memungkinkan untuk dilakukannya pengukuran yang sensitif, spesifik, dan
reprodusibel terhadap hilangnya atau tidak berfungsinya islet akibat sel T
autoreaktif, ataupun keberadaan populasi sel Tregs. T-cell ELISPOT analysis
(ISL8Spot) menunjukkan bahwa pergeseran, baik frekuensi maupun imuno-
dominansi dari respon sel T CD8+, terjadi lebih cepat daripada perubahan titer
autoantibodi pada T1D di manusia. Baru-baru ini, teknologi tetramer HLA-A2
digunakan untuk melihat peningkatan sel T CD8+ reaktif GAD65 dan sel T CD8+
reaktif InsB-peptide pada terapi anti-CD3 terhadap pasien T1D. Pemeriksaan-
pemeriksaan tersebut mungkin juga dapat membantu mengidentifikasi pasien
yang akan mengalami fase honeymoon.
Kesimpulannya, kombinasi pemeriksaan autoantibodi dan autoreaktivitas
dari sel T dengan beberapa biomarker, akan dapat memberikan gambaran yang
lebih lengkap mengenai aktivitas penyakit. Sebuah evaluasi yang lebih baik
terhadap respon pasien akan lebih meningkatkan outcome dan keamanan dari
pasien.
D. Skrining Metabolomik
Pencegahan yang paling efektif terhadap T1D membutuhkan deteksi
terhadap kejadian yang paling awal dalam penyakit tersebut. Autoimunitas
mungkin merupakan mekanisme efektor yang paling dominan dalam T1D, namun
mungkin bukan penyebab primernya. Sebuah laporan menarik baru-baru ini
diberikan oleh Oresic et al, yang menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi
serum lysophosphatidylcholine mendahului keberadaan autoantibodi islet, dan
pasti mendahului proses autoimunitas, pada T1D. Bila hasil ini dapat divalidasi
oleh penelitian cohort lain, seperti penelitian BABYDIAB di Jerman, DAISY di US,
dan PANDA, serta penelitian internasional TEDDY, maka skrining metabolomik
seharusnya ditambahkan dalam panel skrining untuk dapat dengan efektif
mengidentifikasi individu pre-diabetes untuk dilakukan terapi preventif.
E. Pemeriksaan Massa Sel
Jumlah sel beta dari islet yang ada saat lahir sebagian besar berasal dari
diferensiasi dan proliferasi sel progenitor pankreas, dalam sebuah proses yang
disebut neogenesis. Setelah lahir, hanya sejumlah kecil sel beta yang masih
mampu berekspansi. Hal ini mungkin sudah cukup untuk mengkompensasi
kebutuhan insulin, namun mungkin tidak untuk regenerasi setelah terjadi injury
jaringan yang ekstensif. Data-data dari sampel patologi mengindikasikan bahwa
hanya 10-30% massa sel beta yang tersisa pada pasien T1D jangka panjang.
Masih belum jelas seberapa banyak massa sel beta yang tersisa saat terjadi
onset diabetes. Defisit massa sel beta memerlukan pemeriksaan massa sel beta
in vivo, namun masih belum ada pemeriksaan yang dapat melakukannya dengan
akurat dan sensitif dengan cara non-invasif atau invasif minimal.
Imaging sel beta non invasif menggunakan peralatan diagnostik modern
dapat memberikan sensitivitas yang tinggi baik pada manusia maupun tikus,
namun tetap ada beberapa masalah. Pertama, resolusi sel tunggal masih belum
dapat dicapai untuk memungkinkan diferensiasi antara islet yang tersebar, sel
beta tunggal, ataupun jaringan sekitarnya. Kedua, teknik imaging saat ini
didasarkan pada marker molekul yang spesifik. Saat ini, antibodi IgM monoclonal
IC2, yang secara spesifik berikatan dengan permukaan sel beta, mungkin
menjadi satu-satunya marker yang tersedia untuk imaging non invasif dan
kuantifikasi sel beta. Kandidat lainnya, seperti antibodi terhadap ZnT8 atau ligand
terhadap vesicular monoamine transporter type 2 (VMAT-2), yang disebut
dihydrotetrabenazine (DTBZ) dan digunakan dalam penelitian klinis
(NCT00771576), masih belum spesifik.
Pengetahuan mengenai jumlah massa sel beta dapat membantu
pengambilan keputusan mengenai tipe terapi dan follow up selama terapi.
Contohnya, obat yang dapat menstimulasi proliferasi sel beta dapat dipilih bila
masih banyak massa sel beta yang tersisa, sedangkan bila massa sel beta
hanya tinggal sedikit, maka lebih baik dilakukan transplantasi islet, obat trans-
differensiasi, atau terapi stem cell. Teknologi ini mungkin juga dapat membantu
menjawab pertanyaan dasar: Berapa fraksi minimal massa sel beta yang
diperlukan untuk mempertahankan homeostasis glukosa? Terakhir, deteksi dini
terhadap hilangnya massa sel beta setelah dilakukan transplantasi islet mungkin
juga dapat membantu untuk mengatur terapi imunomodulasi sesuai waktu dan
dengan strategi yang lebih fokus.
VII. PENELITIAN PENCEGAHAN
Keberhasilan suatu pencegahan bergantung pada (1) Prediksi/identifikasi
yang tepat terhadap individu beresiko dan (2) Intervensi yang sangat aman
sehingga tidak membahayakan individu-individu tersebut yang belum mengalami
T1D. Pemahaman mengenai penyebab primer T1D mungkin tidak krusial,
bahkan pada tahap pencegahan. Statemen ini didasarkan pada fakta bahwa
modulasi imun tampaknya dapat bekerja pada berbagai model T1D dan berbagai
tahapan penyakit yang berbeda. Namun demikian, banyak penelitian mengenai
pencegahan yang didasarkan pada data dari model tikus NOD yang telah
membantu meningkatkan pemahaman kita mengenai patofisiologi penyakit.
Sebuah analisis komprehensif oleh Shoda et al, menunjukkan bahwa beberapa
pernyataan populer mengenai intervensi terhadap NOD masih belum
terkonfirmasi yakni semua terapi tidak mencegah penyakit, dosis dan waktu
pemberian terapi sangat mempengaruhi efikasi, dan beberapa terapi telah
berhasil pada tikus dengan diabet. Sehingga, berita baiknya adalah bahwa
beberapa strategi preventif tampaknya memiliki kesempatan untuk dapat
menyembuhkan penyakit, bahkan pada saat destruksi sel beta mencapai tahap
lanjut. Contoh dari terapi yang sukses pada tikus NOD adalah ATG, anti-CD3,
hsp, dan vaksin DNA pro-insulin. Idealnya, keseimbangan antara efikasi terapi
dan tahap penyakit harus sudah diketahui sebelum dicobakan pada manusia.
Masalah utama pada penelitian mengenai pencegahan ini adalah bahwa
diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum dapat diambil kesimpulan.
Sebagaimana dilihat dalam tabel 2, penelitian pencegahan terbagi dalam dua
kelas utama. Kategori pertama terutama mencakup suplemen nutrisi non-antigen
spesifik: vitamin D3 (NCT00141986), susu sapi terhidrolisasi (TRIGR;
NCT00179777), dan docosahexaenoic acid (DHA; NCT00333554). Pendekatan
pencegahan dengan non-antigen spesifik lainnya tidak memiliki atau hanya
sedikit memberikan efek yakni dengan menggunakan ketotifen, cyclosporine,
nicotinamide, atau kombinasi ketiganya. Contohnya, cyclosporine dapat
memperlambat onset T1D, namun tidak mencegah T1D. Kategori penelitian
pencegahan yang kedua bertujuan untuk menginduksi tolerasi oral yang spesifik
terhadap antigen. Selama proses perjalanan penyakit pada model hewan dan
manusia, autoimunitas sel T secara progresif menyebar di intra dan inter-
molekuler di antara autoantigen sel beta seperti insulin, GAD65, HSP, dan IGRP.
Meski begitu, pendekatan spesifik antigen hanya menggunakan satu jenis
antigen (Tabel 2) untuk mentolerir terhadap banyak jenis autoreaktivitas. Ide
utama yang diharapkan dari pendekatan ini adalah untuk menginduksi supresi
antigen di sekitarnya melalui Tregs. Tregs yang diinduksi melawan satu
autoantigen akan berproliferasi saat menemui autoantigen lainnya di limfonodi
pankreas dan mungkin juga di islet. Tregs tersebut juga akan mensekresikan
sitokin yang dapat menurunkan fungsi imun atau memodulasi APC. Sehingga
secara keseluruhan akan terbentuk suatu imunosupresi spesifik antigen lokal dan
terjadi penurunan serangan autoimun. Namun, penerapannya pada T1D manusia
masih sulit karena belum ada biomarker fungsional yang dapat mengindikasikan
apakah jumlah tepat, rute, serta antigen yang digunakan telah mencapai supresi.
Contohnya, saat Diabetes Prevention Trial-1 (DPT-1) gagal mendemonstrasikan
manfaat dari terapi insulin oral atau subkutan untuk mencegah T1D, analisis
subkelompok post hoc justru mengindikasikan adanya penundaan T1D pada
subyek dengan titer autoantibodi insulin yang tinggi yang diberikan terapi insulin
oral. Sebuah penelitian klinis baru mengenai penggunaan terapi insulin terhadap
keluarga yang beresiko, saat ini sedang berlangsung (NCT00419562). Contoh
lain adalah T1D Prediction and Prevention Study. Penelitian ini tidak berhasil
mendemonstrasikan efek menguntungkan dari pemberian terapi insulin intranasal
harian dalam pencegahan ataupun penundaan diabetes, bahkan saat terapi
mulai diberikan segera setelah terjadi serokonversi. Sebaliknya, Intranasal Insulin
Trial menunjukkan bahwa pemberian insulin intranasal terhadap individu dengan
resiko tinggi mengalami T1D, akan meningkatkan antibody dan menurunkan
respon sel T terhadap insulin, dan dari sini makin banyak penelitian klinis yang
kemudian dilakukan.
Tabel 2. Penelitian Pencegahan pad T1D
Agen Mekanisme/Target Fase
Vitamin D3 Induksi Tregs Pilot, NCT00141986*, CDA
Asam lemak
omega 3
Anti inflamasi Phase II, NCT00333554*, NIDDK
Susu sapi
terhidrolisa
Penanganan protein asing
intak yang abnormal
TRIGR, Phase II, NCT00179777*,
CHEO
Insulin oral Toleransi spesifik antigen
(oral)
Phase II, NCT00419562*, NIDDK
Insulin nasal Toleransi spesifik antigen
(mucosal)
Phase III, NCT00223613*, University of
Turku
Phase II, NCT00850161*, CPEX
Pharma
Phase II, NCT00336674*, Melbourne
Health
VIII. PENELITIAN DIABETES TIPE 1 ONSET BARU
Penelitian mengenai intervensi lebih mudah dilakukan daripada penelitian
mengenai pencegahan, karena subyek telah teridentifikasi dan efikasinya dapat
dievaluasi dalam waktu yang relative lebih singkat. Terapi post onset saat ini
dapat bersifat substitutive (contoh: berbagai formulasi insulin), paliatif
(penggunaan anti inflamasi atau agen imunosupresan jangka panjang), spesifik
antigen (Tregs yang diinduksi antigen islet), atau kombinasinya.
A. Penelitian Mengenai Intervensi yang Spesifik terhadap Antigen pada T1D
Secara umum, ide mengenai terapi berbasis antigen adalah kemungkinan
untuk menginduksi respon Tregs (toleransi aktif) atau meng-anergi/menghapus
sel T patogenik (toleransi pasif) tanpa ada efek samping supresi imun jangka
panjang. Toleransi terhadap insulin atau GAD65 telah terbukti efektif dalam
beberapa penelitian. Pendekatan ini juga telah terbukti sukses untuk pasien T1D.
Penelitian di masa depan juga harus menargetkan peptide lainnya, karena
beberapa penelitian pada tikus dengan resiko diabetes menyatakan bahwa
determinan dari antigen-antigen sel beta yang selam aini diacuhkan merupakan
pilihan yang lebih optimal untuk menghambat penyakit autoimun tahap lanjut.
Beberapa penelitian mengenai intervensi klinis menargetkan insulin, karena
insulin merupakan agen inisiasi dalam model NOD dan juga merupakan
autoantigen mayor pada T1D manusia. Sebuah penelitian fase I telah
mengkonfirmasi data-data pada model hewan bahwa vaksinasi incomplete
Freunds adjuvant (IFA)-enhanced human insulin B-chain aman dan dapat
menginduksi Tregs spesifik insulin selama sekitar 2 tahun sejak dilakukan
vaksinasi. Sebuah penelitian follow up yang sedang dilakukan, akan meneliti
efeknya terhadap kontrol glikemia. Pendekatan lainnya menggunakan vaksin
CpG-free proinsulin-based DNA plasmid BHT-3021 (Bayhill Therapeutics).
Vaksin ini didesain untuk mentolerir sistem imun terhadap pro-insulin dengan
mengkombinasikan kodon DNA dengan peptide insulin yang imunodominan dan
oligonucleotide CpG imunomodulator. Data-data terbaru dari penelitian terhadap
tikus NOD diabetes onset baru menyatakan bahwa BHT-3021 menginduksi
Tregs spesifik pro-insulin yang dapat berperan sebagai supresor. Pada pasien
dengan onset baru, vaksin dapat mempertahankan C-peptida dan menurunkan
HbA1c. Hal ini menunjukkan efikasi yang lebih besar dari BayHill plasmid bila
dibandingkan dengan generasi pertama plasmid insulin B-expressing pCMV.
Target lain untuk terapi spesifik antigen adalah GAD65. GAD-Alum adalah
sebuah formulasi aluminium hydroxide (Alum) dari rekombinan GAD65 manusia
(Diamyd Therapeutics). Terapi ini terbukti aman dan dapat mempertahankan
sekresi residual insulin pada subyek dengan late onset autoimun diabetes of
adulthood (LADA). Sebuah penelitian lanjutan fase III terhadap T1D onset baru
menunjukkan adanya preservasi sekresi residual insulin yang signifikan dan
respon imun spesifik GAD, baik humoral maupun seluler. Saat ini, penelitian-
penelitian fase III sedang berlangsung di Eropa dan US. Pasien-pasien dalam
berbagai penelitian tersebut dipilih berdasarkan peningkatan autoantibodi
GAD65. Formulasi ini penting untuk obat Dyamids GAD karena (1) adjuvant
dapat mereduksi kuantitas antigen dan (2) garam aluminium lebih dipilih untuk
menginduksi respon imun humoral daripada seluler. Pembacaan respon imun
menunjukkan adanya peningkatan FoxP3 dan transforming growth factor- pada
sel-sel dari pasien yang diberikan terapi GAD-Alum bila dibandingkan dengan
pasien yang diberi placebo setelah 15 bulan.
Meskipun penelitian-penelitian tersebut cukup menjanjikan, masih terlalu
dini untuk mengatakan bahwa GAD65 dan/atau insulin merupakan target antigen
optimal untuk menginduksi Tregs sehingga dapat terjadi modulasi perjalanan
T1D pada manusia. Terapi kombinasi dengan modulator imun jangka pendek
yang sesuai, juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efikasi terhadap
pasien dengan onset baru.
Tabel 3. Penelitian Intervensional dan Monoterapi Spesifik Antigen
Agen Target Fase Detail Referensi
Diap277 Induksi Tregs
melalui TLR
Fase III
(Dewasa)
Fase I: Preservasi C-peptide
hingga 18 bulan
351
NCT00615624 Fase II: tidak ada efek
terhadap T1D dewasa atau
anak
240
NCT00644501 Fase III: rekrutmen 381
Andromeda
Biotech
Ins B pada IFA Vaksinasi toleransi
terhadap rantai
insulin B
Fase I/II
NCT00057499
ITN
Sedang berlangsung 111, 299
NBI 6024
APL dari Insulin
Vaksinasi toleransi
terhadap insulin
Fase I/II Fase I: Pergeseran Th1 ke
Th2 protektif
14
NCT00873561
Neurocrine
Fase II: Tidak efek terhadap
massa sel beta residual dan
kebutuhan insulin
466
BHT 3021
Vaksin
proinsulin
Vaksinasi toleransi
terhadap insulin
Fase I/II Penurunan titer autoAb
insulin, preservasi C-peptida
dan penurunan HbA1c
162
NCT00453375
BayHill Therp.
Tidak ada efek samping
GAD65 Alum Toleransi terhadap
GAD 65,
menggeser Th1
menjadi Th2
Fase II (LADA
NCT00456027
Diamyd
Preservasi sekresi insulin
residual, GAD-spesifik respon
imun humoral dan seluler,
namun tidak ada efek
protektif terapi >6 bulan
setelah diagnosis, tidak ada
perubahan C-peptide puasa
setelah 15 bulan
7
8
256
Fase II (T1D)
NCT00435981
Sedang berlangsung
Fase III
NCT00723411
Sedang berlangsun, Eropa
Fase III
NCT00751842
Sedang berlangsung, USA
(DIAPREVENT)
Peptida
autoantigen dari
islet dari HLA
klas II manusia
Regulasi respon
imun
Fase I
DVDC
- 400
B. Penelitian Mengenai Intervensi yang Tidak Spesifik terhadap Antigen
pada T1D
Karena autoimunitas merupakan mekanisme efektor utama pada T1D,
banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi intervensi
menggunakan regimen obat untuk menghentikan/memodulasi respon imun,
terutama yang tidak memberikan efek negative terhadap Tregs (Tabel 4).
Regimen-regimen imuno-supresan tersebut juga akan terbukti bermanfaat, atau
bahkan penting, untuk kesuksesan proses transplantasi islet dan/atau terapi
regenerasi sel beta.
Agen imuno-supresan pertama yang digunakan dalam sebuah penelitian
klinis terkontrol placebo dan double blind untuk T1D adalah cyclosporine A.
Cyclosporine A menghambat calcineurin, yang bertanggung jawab untuk aktivasi
transkripsi IL-2. Kurangnya IL-2 dan sitokin lainnya akan menurunkan fungsi sel
T efektor, namun sayangnya, juga menurunkan fungsi Tregs. Terapi cyclosporine
dapat menginduksi remisi T1D, namun penggunaannya dalam jangka panjang
masih dilarang karena efek sampingnya masih belum dapat diterima. Namun
demikian, kesuksesan untuk sementara waktu ini mengindikasikan bahwa imuno-
supresi dapat menurunkan proses inflamasi autoimun dalam T1D.
DiaPep277 pada awalnya digunakan pada terapi spesifik antigen. Ide
mengenai hal tersebut adalah bahwa peptide yang berasal dari HSP60 ini dapat
menjadi autoantigen dalam T1D karena adanya reaktivitas silang. Pandangan
yang lebih baru menyatakan bahwa Diap277 merupakan sebuah modulator
sistemik: HSP60 menginduksi Treg melalui Toll-like receptor (TLR)-2. Sebuah
penelitian fase II menunjukkan bahwa DiaPep277 dapat mempertahankan C-
peptida hingga 18 bulan pada pasien T1D dewasa dengan onset baru.
Preservasi sel beta terkait dengan produksi IL-10 sebelum terapi dan penurunan
proliferasi sel T spesifik autoantigen setelah terapi. Namun sejauh ini, belum ada
Tregs spesifik DiaPep277 yang telah dikarakterisasi pada manusia ataupun
tikus.. Namun demikian, meskipun penelitian fase III masih berjalan pada
dewasa, belum ada efek terapi yang didapatkan pada anak-anak dengan T1D.
Terdapat sekelompok modulator imun biologis, yang terdiri dari antibody-
antibodi yang mentarget reseptor pada sel T. Contohnya, antibody monoclonal
FcR-non-binding anti CD3 (mAbs) sejauh ini telah menunjukkan hasil yang paling
menjanjikan dalam terapi T1D. Anti-CD3 mAb bekerja pada berbagai level. Anti-
CD3 mAb ini dapat menginternalisasi kompleks TCR-CD3 jangka pendek
sehingga membuat sel menjadi buta terhadap antigen. Selain itu, Anti-CD3 mAb
ini dapat mengubah transduksi sinyal yang dimediasi TCR sehingga dapat
menginduksi anergi atau apoptosis pada sel Th1 yang telah teraktivasi.
Apoptosis sebagian juga dimediasi oleh interaksi CD95-CD95L dengan sel-sel di
sekitarnya. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa kematian sel T efektor paling
dramatis saat densitas sel T paling tinggi, contohnya pada lokasi inflamasi.
Selain itu, terapi anti CD3 juga menginduksi perkembangan Treg. Diduga Treg
dapat melindungi sel T efektor dari kerusakan jauh setelah obat dieliminasi dari
tubuh. Untuk mendapatkan efek-efek tersebut, penting untuk memberikan dosis
yang optimal. mAb dengan dosis yang terlalu rendah akan menyebabkan
modulasi dan generasi Treg yang insufisien, sedangkan dosis mAb yang terlalu
tinggi dapat menyebabkan stimulasi sel T efektor dan pelepasan sitokin.
Berbagai penelitian klinis telah dilakukan dan didasarkan pada dua antibody
yang berbeda, keduanya merupakan IgG1 yang fully humanized, non mitogenik
dan spesifik terhadap CD3 (Tabel 4): Teplizumab (penelitian di US) dan
TRX4/Otelixizumab (penelitian Eropa). Teplizumab dapat menghentikan progress
T1D onset baru selama lebih dari 1 tahun pada sebagian besar pasien (fase II).
Tiga tahun setelah terapi, tetap terjadi preservasi level C-peptida dan
penggunaan insulin yang lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol.
TRX4/Otelixizumab juga dapat mempreservasi fungsi sel beta dengan sangat
efisien dan menurunkan kebutuhan insulin dengan drastic, bahkan hingga 18
bulan terapi tunggal. Namun, tidak satupun dari terapi-terapi tersebut yang dapat
mencapai euglikemia. Penelitian di Eropa juga menunjukkan adanya dua efek
samping. Pertama, antibody anti-idiotipik yang terdeteksi 2-3 minggu setelah
injeksi obat. Hal ini akan menjadi masalah bila diperlukan terapi berulang. Kedua,
terjadi reaktivasi Epstein-Barr virus, namun hanya bersifat sementara, lokal, dan
dapat sembuh sendiri.
Pendekatan lainnya adalah dengan penggunaan antibody poliklonal anti sel
T (ALS) dan anti thymocyte globulin (ATG) yang dalam jangka waktu tertentu
dapat mengeliminasi sejumlah besar sel T dari aliran darah. Pada tikus NOD,
ATG murine dapat mencegah diabetes pada tahap lanjut dan dapat menginduksi
Tregs. Masih belum jelas apakah ATG akan seefisien anti CD3. Terapi pasien
T1D dengan rATG (ATG-Fresenius) dapat memperpanjang periode honeymoon
dan memperbaiki level C-peptida hingga 12 bulan masa penelitian.
Konsekuensinya, monoterapi ATG saat ini diteliti pada penelitian fase II, Study of
Thymoglobulin to Arrest T1D (START). Namun terapi ATG juga membawa
resiko. ATG dapat menyebabkan sindroma pelepasan sitokin dan mungkin
menyebabkan pertumbuhan sel T autoreaktif yang berlebih akibat limfopenia,
sebagaimana terbukti pada imunosupresi delesi lainnya. Terapi kombinasi
dengan ATG kuda dan prednisone, sebuah steroid yang dapat melawan
sindroma pelepasan insulin, dapat memperpanjang fase honeymoon pada T1D
onset baru. Namun yang paling menjanjikan dari penelitian ATG adalah bahwa
beberapa subyek mengalami remisi sempurna dan dapat independen dari insulin
selama setidaknya 1 bulan.
Sebuah obat imunomodulasi yang diadopsi dari arena transplantasi adalah
rituximab mAb spesifik CD20 (Rituxan; Genentech dan Biogen Idec). Rituximab
bertujuan untuk mengurangi populasi sel B yang berpotensi kuat untuk
mempresentasikan antigen tanpa mempengaruhi produksi antibody sel plasma
jangka panjang. Data dari tikus NOD dengan jelas menunjukkan bahwa sel B
diperlukan dalam T1D. Sebuah penelitian klinis fase II menunjukkan adanya
preservasi level C-peptida untuk 3-6 bulan, yang menunjukkan bahwa sel B juga
berkontribusi dalam pathogenesis T1D pada manusia. Meski demikian,
efikasinya masih kecil bila dibandingkan dengan terapi anti CD3. Mungkin
Ocrelizumab, sebuah antibody anti-CD20 humanized yang digunakan dengan
sukses pada RA, mungkin dapat meningkatkan efikasi deplesi sel B pada T1D.
mAb anti-CD25 seperti basiliximab (chimeric mouse human monoclonal
antibody) dan daclizumab (humanized IgG1 mAb) tidak menyebabkan sindroma
pelepasan sitokin. Sehingga, kedua obat ini makin banyak digunakan sebagai
terapi induksi ATG. Namun, pada T1D, mAb anti-CD25 hanya digunakan pada
terapi kombinasi.
Kelompok target lainnya terdiri atas beberapa molekul ko-stimulator. CTLA-
4-Ig (Abatacept), yakni sebuah CTLA-4 yang digabungkan dengan rantai
immunoglobulin, dapat mengganggu ko-stimulasi sel T. Wajarnya, interaksi
CD28/B7 dapat memediasi ko-stimulasi dan secara signifikan meningkatkan
respon sel T perifer. Sebaliknya, CTLA-4, yang berinteraksi dengan molekul B7
yang sama, akan menurunkan aktivitas sel T. Sehingga, CTLA-4-Ig akan
memberikan efek melalui pencegahan ko-stimulasi positif CD28 oleh B7 selama
aktivasi sel T. Hal tersebut akan membatasi ekspansi klon sel T, menginduksi
kematian sel secara pasif, dan menginduksi produksi IDO pada APC. Profil
keamanan dari terapi CTLA-4-Ig mungkin lebih baik daripada agen
imunosupresan lainnya, karena CTLA-4-Ig tidak mendeplesi sel T. Namun,
karena CD28 berperan dalam perkembangan dan kehidupan Treg, maka CTLA-
4-Ig mungkin akan memberikan efek negative pada Tregs. Dikatakan bahwa
terapi CTLA-4-Ig tidak mempengaruhi Tregs pada transplantasi renal. Monoterapi
CTLA-4-Ig saat ini sedang dalam penelitian klinis fase II (data tidak
dipublikasikan). Selain itu, sebuah varian CTLA-4-Ig (LEA29Y, betalacept)
dengan afinitas tinggi sedang diteliti pada transplantasi islet dalam penelitian
fase I/II (NCT00501709). Dan sebuah penelitian klinis fase II LEA29Y Emory
Edmonton Protocol (LEEP, NCT00468403) sedang mengkombinasikan CTLA-4-
Ig dengan daclizumab atau basiliximab (terhadap rejeksi transplan akut) dan
mycophenolate mofetil (terapi imunosupresan maintenance).
Manipulasi sitokin juga baru-baru ini makin banyak diminati. Baik sitokin
yang mempengaruhi respon sel T (contoh: IL-2, IL-15) maupun sitokin yang
berperan dalam inflamasi dan kematian sel beta, dapat menjadi target. Telah
diketahui bahwa IL-1 merupakan sitotoksik selektif terhadap sel beta tikus dan
manusia secara in vitro. Terapi anti IL-1 dapat menurunkan insiden diabetes
pada model pencegahan di hewan. Sebagaimana terjadi pada RA, berbagai
penelitian klinis telah banyak yang meneliti apakah terapi IL-1 dapat berguna
pada T1D. Hasil dari sebuah penelitian fase I/II lengkap dengan menggunakan
IL-1RA (anakinra, Kineret oleh Amgen) pada T1D yang baru terdiagnosis masih
belum dipublikasikan. Pada sebuah penelitian fase II/III yang sedang
berlangsung, pasien akan menginjeksi dirinya sendiri dengan Anakinra satu kali
per hari selama 2 tahun, di mana hal ini memerlukan komitmen yang tinggi dari
pasien. Juga terdapat beberapa penelitian fase II yang ditunda. Salah satu
penelitian akan meneliti tentang Canakinumab, sebuah antibody monoclonal anti-
IL-1 yang sepenuhnya berasal dari manusia, pada pasien T1D dengan onset
baru. Penelitian lain akan memeriksa anti-IL-1 mAb Xoma52 pada T1D yang
telah tegak sebelumnya dan terkontrol (2 tahun). Penelitian RID-1 akan meneliti
Rilonacept, sebuah fusi protein dimer yang berfungsi sebagai penjebak sitokin
untuk IL-1, setelah didapatkannya data yang bagus dari gout arthritis.
Sitokin TNF- (tumor necrosis factor-) merupakan regulator utama pada
respon inflamasi di banyak sistem organ. Antagonis TNF-, seperti etanercept
(sebuah reseptor TNF terlarut) dan infliximab (sebuah antibody), sudah
digunakan dengan sukses pada RA. Pada T1D, data-data penelitian fase II
menunjukkan bahwa terapi dengan etanercept dapat menurunkan HbA1C dan
meningkatan produksi insulin endogen, yang menandakan adanya preservasi
fungsi sel beta. Namun, ceritanya tidak sesederhana itu. TNF- mungkin
berperan ganda dalam T1D. Contohnya, TNF dan sebuah agonis TNFR2 dapat
secara selektif membunuh sel T CD8 autoreaktif pada manusia. Pada model
hewan, TNF- akan mempercepat respon diabetogenik pada masa awal proses
T1D, sebaliknya justru akan mengurangi respon diabetogenik pada akhir proses
T1D. Dan yang semakin menambah kebingungan adalah beberapa laporan
kasus klinis yang menunjukkan adanya progress T1D pada pasien arthritis (JIA
atau RA) setelah diberikannya terapi etanercept, namun juga terdapat resolusi
T1D pada pasien yang diberikan terapi anti-TNF- untuk RA. Hasil-hasil yang
masih bertentangan ini harus segera diklarifikasi. Patut dicatat bahwa vaksin
Bacille Calmette-Guerin (BCG) dapat meningkatkan level TNF- sistemik dan
digunakan dalam sebuah penelitian intervensional yang kurang sukses. Harus
dilakukan sebuah penelitian follow up untuk menentukan waktu dan dosis yang
paling baik.
Para peneliti lain mengajukan hipotesis bahwa autoimunitas disebabkan
oleh kurangnya IFN tipe I. IFN tipe I dapat melawan kerja IFN tipe II, yang
mungkin menjadi faktor pusat dalam inflamasi autoimun. Penelitian-penelitian
klinis sejauh ini telah menunjukkan bahwa pemberian ingesti rhIFN- dosis
rendah aman dan lebih efektif dalam mempreservasi level C-peptida bila
dibandingkan dengan dosis tinggi. Secara mekanis, ingesti rhIFN- dapat
menurunkan level TNF- pada pasien MS, yang mengindikasikan terdapat
hubungan dengan terapi blokade TNF-. Meski begitu, secara keseluruhan
hipotesis ini masih kontroversial. Para peneliti lain menyatakan bahwa aktivasi
TLRs oleh dsRNA atau poli I:C (mirip virus) melalui induksi oleh IFN- dapat
mengaktivasi atau mempercepat destruksi sel beta akibat autoimun.
Granulocyte colony stimulating factor (GCSF), sebuah agen mobilisasi
neutrophil, dapat mencegah diabetes pada tikus NOD dengan menginduksi sel
dendritic tolerogen dan Tregs. Keamanan dan preservasi C-peptida selama
terapi GCSF (Neulasta) saat ini masih diteliti dalam sebuah penelitian klinis fase
I/II. Sebuah penelitian kombinasi dengan ATG juga masih berlangsung.
Sudut pandang penelitian lain yakni bertujuan untuk menunda kematian sel
beta dengan menurunkan jumlah insulin yang disekresikan. Hal ini dilakukan
untuk menurunkan stress pada sel beta akibat status diabetic dan mungkin juga
menurunkan autoantigen yang ada, seperti (pro)insulin. Diazoxide, sebuah
pembuka kanal kalium yang sensitif ATP, menghasilkan preservasi produksi
insulin residual pada pasien T1D onset baru, namun juga menyebabkan efek
samping yang substansial. Sebuah penelitian fase IV baru-baru ini
mengindikasikan bahwa dosis yang tidak menyebabkan efek samping juga tidak
efektif dalam mempreservasi fungsi sel beta.
Tabel 4. Penelitian Intervensional dan Monoterapi Non-Spesifik Ag
Agen Mekanisme Fase Detail Referensi
Calmette-Guerin
(BCG)
Hipotesis higien Fase I
NCT00607230
MGH
Penelitian baru: rekrutmen
Penelitian 10 thn lalu:
tidak ada efek
13
Diazoxide Melawan
overstimulasi sel beta
kronis
Fase IV
NCT00131755
V. Grill, MD
Tidak ada efek terhadap
fungsi sel beta
Efek samping (eliminasi
dengan menurunkan
dosis)
46, 168,
321
IFN- ingestan T1D merupakan
sindroma
imunodefisiensi IFN
tipe 1
Fase II
NCT00005665
NCCR
Aman
Dosis rendah lebih efektif
dalam mempreservasi C-
peptida
Membutuhkan dosis yang
lebih baik
66, 369
Cyclosporin A Supresi imun Selesai Remisi sukses selama
terapi, namun dengan
efek samping berat
21, 59
Anti CD3
(hOKT3) g1
(Ala-Ala)
MGA031
Teplizumab
(US)
Imunomodulasi sel T
dan meningkatkan
Treg dengan mAb
anti CD3 non-binding
FcR
Fase I/II Remisi hingga 24 bulan 182, 184-
186
Selesai
ITN (Herold)
Fase I/II
NCT00378508
JDRF/NIDDK
Fase II AbATE
NCT00129259
ITN (Herold)
Fase II/III
Protg
NCT00385697
Efek positif terhadap C-
peptida selama 36 bulan
Pemeriksaan: Ab tunggal
diberikan 14 hari pada px
4-12 bulan post dx
Dosis ganda: 2 dosis Ab
diberikan dalam jarak 1
tahun
Hasil: level C-peptida
Hasil: kebutuhan insulin,
HbA1c
Makrogenik
mAb anti CD3
(ChAglyCD3)
TRX4
Otelixizumab
(Eropa)
Imunomodulasi sel T
dan meningkatkan
Treg dengan mAb
anti CD3 non-binding
FcR
Fase II 6 Hari terapi: level C-
peptida dipertahankan
dengan baik, penurunan
kebutuhan insulin hingga
18 bulan
91, 228
Selesai 2005 Selama terapi: nyeri
kepala, mual, nyeri badan,
gejala seperti flu lain; 6
minggu setelah terapi:
infeksi EBV kembali aktif,
nyeri tenggorokan, dan
pembengkakan KGB
(ringan dan sementara)
Fase II TTEDD
NCT00451321
JDRF/TolerRx
Fase III
DEFEND-1
NCT00678886
JDRF/TolerRx
Fase I
NCT00946257
GSK
Pemeriksaan: regimen
multidosis
Pemeriksaan: terapi 8 hari
Penelitian: pemberian
subkutaneus
ATG
Thymoglobulin/
Atgam
Deplesi sel T,
meningkatkan
populasi Treg
Fase II START
NCT00515099
NIAID/ITN
Dapat menyebabkan
sindroma pelepasan
sitokin
398
mAb anti CD20
Rituximab
Deplesi sel beta Fase II/III AUC C-peptida pada
MMTT lebih baik pada
12 bulan
197, 334
NCT00279305
TrialNet
Pada 3-6 bulan: tingkat
penurunan AUC C-peptida
sama dengan placebo
CTLA4 Ig Blokade ko-stimulasi Fase II Rekrutmen 50, 239
Abatacept,
Belatacept
NCT00505375
NIDDK
IL-1 antagonis
anakinra
Canakinumab
Xoma 052
Anti inflamasi dan
memperbaiki survival
sel beta
Fase II/III
(AIDA)
NCT00711503
STENO/JDRF
Fase I/II
NCT00645840
UTSMC
Rekrutmen
http://www.aidastudy.org
Tidak ada publikasi hasil,
meski sudah selesai
116, 335
Fase II
NCT00947427
NIDDK
Ditunda
Fase I/II
NCT00998699
Zurich Univ
Ditunda
Rilomacept
Arcalyst
Menjebak IL-1 Fase II
NCT00962026
UTSMC
Ditunda 427
Blokade TNF-
Etanercept
Anti inflamasi Fase I/II
NCT00730392
Amgen
Menurunkan HbA1c dan
kebutuhan insulin,
meningkatkan AUC C-
peptida
Tidak ada efek samping,
namun inhibitor TNF
terkait dengan
peningkatan reaktivasi TB
laten
274
31, 94, 480
GCSF
Neulasta
Meningkatkan jumlah
Treg
Fase I/II
NCT00662519
JDRF/NIH
Rekrutmen
Byetta, exendin-
4, exenatide
Analog GLP-1,
stimulasi sekresi
insulin
Fase IV
NCT00456300
Baylor College
Sedang berlangsung
Pada T2D: waktu paruh
pendek, efek samping GI,
muncul antibodi
171, 370,
478, 479
Liraglutide Analog GLP-1, Fase II/III Sedang berlangsung 76, 104,
stimulasi sekresi
insulin
NCT00993720
Hvidovre U.
Hospital
Pada T2D: HbA1c turun,
efek samping lebih sedikit
daripada exenatide
290, 341
Sitagliptin Inhibitor DPP4, enzim
degradator GLP-1
Fase I
NCT00813288
NIDDK
Fase IV
NCT00978796
BDC
Rekrutmen (fungsi imun)
Rekrutmen (efek glukosa)
230, 231
EGF Neogenesis islet,
proliferasi sel-
Fase II (E1-INT)
Transition Therp
Insulin harian menurun
35-75% pada 3-4 pasien.
Penurunan penggunaan
insulin harian terjadi
setelah hari 28 dan
puncak 1-2 bulan post
terapi (control glikemia
stabil)
Website
perusahaan
Pioglitazone Stimulasi PPAR- Fase I
NCT00545857
Stony Brook Uni
Rekrutmen (menilai
perjalanan T1D)
44, 224,
491
Peptida INGAP Regenerasi sel islet Fase II
NCT00995540
Exsulin Corp
Meningkatkan sekresi C-
peptida pada pasien T1D
Menurunkan HbA1c (-
0.4%)
122, 338,
366
C. Terapi Tolerogenik Berbasis Sel
Didorong oleh bukti-bukti dari model hewan, imunoterapi tolerogen
berbasis sel semakin banyak diteliti (Tabel 5). Ide awalnya adalah untuk
mengkompensasi defisiensi yang ada dengan mentransfer sel-sel dengan
kapasitas imunomodulasi.
Imunoterapi seluler menggunakan Tregs merepresentasikan sebuah
pendekatan yang menarik dan mudah dilakukan untuk menyembuhkan T1D. Hal
tersebut pertama kali ditunjukkan melalui munculnya imuno-toleransi setelah
dilakukan transfer adoptif dari Tregs spesifik autoantigen atau Tr1 ke tikus NOD.
Sebuah penelitian klinis telah direncanakan untuk menterapi T1D dengan
mengisolir Tregs pasien kemudian dilakukan ekspansi di luar tubuh dan
diinfuskan kembali dalam jumlah besar. Para ahli dalam bidang ini mengakui
banyak masalah teknis yang mungkin akan dijumpai: seperangkat marker yang
tepat untuk Tregs murni manusia (saat ini adalah CD4+ CD127
rendah/minus
CD25+), rendahnya frekuensi Tregs di sirkulasi (~5-7% dari sel T CD4+), jumlah
sel yang harus ditransfer, frekuensi transfer, metode ekspansi in vitro,
kemungkinan hidup sel-sel tersebut in vivo, penghantaran kembali ke jaringan
yang tepat, ketidakmampuan untuk mengeliminasi sel yang ditransfer, dan
ketidakstabilan fungsi regulasi. Sehingga, bidang ini kemudian terbagi menjadi
yang percaya dan tidak percaya. Beberapa orang menyatakan bahwa terapi
tolerogenik berbasis sel merupakan pendekatan rutin klinis yang dapat dicapai.
Beberapa yang lain lebih memilih untuk mentarget antigen sel beta yang
digabungkan dengan molekul kecil atau mAb untuk meningkatkan sel
imunoregulasi spesifik islet secara langsung in vivo.
Immunoregulatory dendritic cells (iDC) juga dapat mencegah diabetes pada
tikus NOD. Pada penelitian klinis terbaru di Pittsburgh, DC autolog yang berasal
dari monosit secara in vivo diberikan oligonucleotide yang telah dimodifikasi oleh
antisense phosphorothioate yang menargetkan transkripsi primer dari molekul
ko-stimulasi CD40, CD80, dan CD86. Satu perhatian adalah bahwa instabilitas
dari penghilangan antisense ini mungkin dapat menyebabkan ekspresi ulang dari
molekul target tersebut. Terapi ini juga meningkatkan produksi IL-7 oleh iDC
sebagai faktor survival untuk Treg. Namun IL-7 juga penting untuk sel T nave
dan sel T memori, sehingga juga penting untuk sel T autoreaktif. Patut dicatat,
sel B dengan fenotip regulator mengalami peningkatan pada beberapa pasien
yang menerima DC imunomodulasi.
Tabel 5. Penelitian Intervensi dan Monoterapi Berbasil Sel
Agen Mekanisme Fase Detail Referensi
Terapi sel T
regulator
Meningkatkan jumlah
Tregs
Fase I (pending) Resiko konversi Treg
menjadi T efektor
343, 344,
422
Stem cell
mesenkim
Menurunkan inflamasi
dan membantu
Fase II
NCT00690066
Sedang berlangsung
manusia
dewasa
(Prochymal)
perbaikan jaringan
Infus darah
umbilical cord
autolog
Meningkatkan jumlah
sel Treg
Fase I/II
Univ Florida,
JDRF
NCT00305344
Tidak ada efek preservasi
C-peptide
Tidak ada efek samping
Stem cell
hematopoietik
Efek pengkondisian
ulang imunitas
Fase I/II
NCT00315133
Univ Sao Paulo
Beberapa bebas insulin,
C-peptide AUC meningkat,
HbA1c menurun
Pneumonia nosocomial
bilateral, disfungsi
endokrin lambat,
oligospermia, tidak ada
mortalitas
100,101,
458
Terapi sel
dendritic autolog
Vaksin tolerogenik Fase I
NCT00445913
Univ Pittsburgh
Sedang berlangsung 179, 261
D. Penggantian Kekurangan Sel Beta
Serangan autoimun pada T1D akan menurunkan massa dan/atau fungsi
sel beta hingga titik kritis di mana muncul gejala klinis diabetes (Gambar 1, A dan
B, Gambar 2). Beberapa terapi ditujukan langsung untuk mengkompensasi
hilangnya sel beta ini. Pendekatan yang paling sederhana dan paling banyak
digunakan adalah pemberian injeksi insulin. Terapi lain meningkatkan massa
atau fungsi sel beta dengan mengeksploitasi kapasitas regenerative yang
ditunjukkan oleh sel beta dalam responnya terhadap serangan autoimun atau
stimulus non autoimun. Terdapat lima pendekatan yang dianggap dapat
mengganti kekurangan sel beta (Tabel 4, bawah): (1) stimulasi sekresi insulin, (2)
neogenesis islet dari sel-sel progenitor, (3) regenerasi islet dari massa sel beta
yang ada, (4) transplantasi islet, dan (5) transplantasi stem cell. Sejauh ini,
semua massa restorasi sel beta masih membentur masalah-masalah imunologis.
Hal ini dikarenakan sel beta yang baru diregenerasi atau ditransplantasi terus
memproduksi antigen yang sama-sama rentannya terhadap serangan autoimun.
Pendekatan transplantasi islet dan allogeneic stem cell membentur suatu
masalah klasik yakni respon alloimun. Hal inilah mengapa sebagian besar graft
islet akan hilang dalam 4-5 tahun pertama, meskipun dilakukan pemberian agen
imunosupresan. Pendekatan-pendekatan ini akan bermanfaat untuk
membuktikan berbagai strategi untuk mengontrol autoimunitas jangka panjang,
yang mungkin melalui terapi kombinasi.
1. Stimulasi sekresi insulin
Diadaptasi dari terapi T2D, analog hormone incretin yakni glucagon like
peptide-1 (GLP-1) dengan waktu paruh yang cukup, dapat menstimulasi sekresi
insulin pada massa sel beta yang tersisa. Beberapa contoh di antaranya adalah
Exenatide (Byetta oleh Amylin Pharmaceuticals dan Eli Lilly), sebuah versi
sintetis dari hormone exendin-4 yang ditemukan pada saliva dari hewan Gila-
monster, dan Liraglutide (Victoza dari Novo Nordisk), sebuah analog GLP-1
lepas lambat karena berikatan dengan albumin. Aktivasi reseptor GLP-1 dapat
menunda onset diabetes pada tikus NOD. Secara mekanis, exenatide tidak
hanya menstimulasi sekresi insulin, namun juga meningkatkan replikasi dan
neogenesis sel beta pada tikus, memproteksi sel beta dari kematian akibat IFN-,
dan meningkatkan frekuensi Treg pada tikus NOD. Namun demikian, efek-
efeknya terhadap sel beta dan sistem imun masih kontroversial. Monoterapi
exenatide sudah berada dalam tahap penelitian fase IV, namun penelitian
kombinasi antara exenatide dan daclizumab memberikan hasil yang
mengecewakan. Di sisi lain, liraglutide mendukung proses penanaman graft dan
fungsi dari transplan islet singenik pada tikus NOD, yang telah memasuki
penelitian fase II/III untuk monoterapi.
Pendekatan lain untuk meningkatkan sekresi insulin adalah dengan
memperlambat degradasi fisiologis dari GLP-1. Sitagliptin dapat menghambat
enzim dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) yang berfungsi mendestruksi GLP-1.
Sitagliptin dapat memperpanjang survival graft islet dan dapat membalik diabetes
secara parsial pada tikus NOD. Penelitian klinis harus dilakukan untuk
memeriksa efek sitagliptin, baik sebagai terapi tunggal atau dengan kombinasi
transplantasi islet atau terapi spesifik antigen. Sebuah penelitian fase I juga telah
dimulai baru-baru ini untuk mempelajari efek inhibitor DDP-4 terhadap sistem
imun.
2. Neogenesis sel beta
Pada model hewan, gastrin dapat menstimulasi neogenesis sel beta tanpa
meningkatkan proliferasi dan hipertrofi, dan tanpa menurunkan kematian sel
beta. Selain itu, kapasitas mitogenik sel beta dari epidermal growth factor (EGF)
juga dapat membantu restorasi massa sel beta. Pada sebuah penelitian fase II,
analog EGF yakni E1-INT (Transition Therapeutics) dapat menurunkan
penggunaan insulin harian hingga 35-75% dan membantu menstabilkan glukosa
darah sebagaimana terefleksi pada pengukuran HbA1c pada beberapa pasien
T1D. Berdasarkan perusahaan pemroduksi, hasil yang sama juga didapatkan
pada tikus NOD. Namun, penelitian-penelitian telah menunjukkan bahwa gastrin
dan EGF harus dikombinasikan untuk meningkatkan massa sel beta dan
membalik kondisi hiperglikemia pada tikus NOD dengan onset baru. Saat ini,
sebuah penelitian fase I (E1+G1 INT, NCT00853151) sedang berjalan.
3. Regenerasi sel islet
Terapi dengan menggunakan peptida islet neogenesis associated protein
(INGAP) dapat menginduksi regenerasi sel islet dari sel-sel progenitor yang
berada dalam pancreas sedemikian rupa sesuai perkembangan islet selama
embryogenesis normal. Peptida INGAP dapat meningkatkan massa sel beta dan
membalik kondisi hiperglikemia pada model hewan. Pada penelitian fase I dan II,
injeksi peptida INGAP terbukti aman dan dapat meningkatkan sekresi C-peptida,
namun tidak meningkatkan level HbA1c. Saat ini masih berjalan penelitian
mengenai dosis optimal yang diperlukan.
4. Transplantasi islet
Pada sebagian besar negara maju, transplantasi pancreas merupakan
satu-satunya prosedur yang diijinkan untuk mencapai normoglikemia. Serial
kasus Edmonton menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga resipien dapat
menikmati masa bebas insulin selama 1 tahun setelah menerima infusi islet
terakhirnya. Hasil jangka panjang masih belum memuaskan . Fungsi islet akan
menurun seiring waktu hingga akhirnya <10% pada 5 tahun post transplantasi.
Mengapa terjadi? Singkatnya, allosensitisasi terhadap transplan yang berasal
dapat beragam donor dapat dikontrol dengan pemberian immuno-supresan,
namun regimen-regimen yang ada saat ini mungkin secara terbalik justru
mendorong autoreaktivitas jangka panjang dan bahkan berefek negative
terhadap fungsionalitas sel beta. Pada protokol Edmonton yang asli, pasien
diinfus dengan islet pancreas dari beragam donor cadaver dan secara simultan
juga menerima immuno-supresan dalam bentuk mAb CD25 humanized
(daclizumab) dan pemberian kontinyu rapamycin dosis rendah (sirolimus), yang
dapat menghambat respon terhadap IL-2, dan FK-506 (tacrolimus), sebuah
inhibitor calcineurin yang menghambat produksi IL-2. Namun, regimen ini terbukti
dapat menyebabkan limfopenia dan peningkatan level sitokin homeostatic yang
mendorong ekspansi sel T CD8 autoreaktif. Konsekuensinya, protokol Edmonton
harus dimodifikasi dengan beberapa cara. Contohnya, ATG ditambah anercept
(blokade TNF-) dan imunosupresan menggunakan cyclosporine dan everolimus
(derivate sirolimus) dapat membuat lima dari enam orang menjadi independen
insulin selama 1 tahun, dan empat dari enam selama 3 tahun. Sebuah penelitian
fase I/II baru-baru ini akan meneliti apakah terapi dengan mAb anti-CD3,
sirolimus, dan tacrolimus dosis rendah dapat mencegah rejeksi transplant islet.
Namun, penelitian pada hewan telah menunjukkan bahwa anti-CD3 tidak lagi
dapat menginduksi toleransi saat diberikan bersama tacrolimus, meskipun terus
dapat memberikan efek supresi imun. Penelitian fase II lainnya akan memeriksa
efikasi dari protokol bebas imunosupresan dari inhibitor calcineurin yang
diberikan tanpa steroid, untuk transplantasi islet (NCT00315627), berdasarkan
sirolimus, MMF, dan Campath-1. Pemeriksaan terhadap parameter autoimun
tertentu sebelum dilakukannya transplantasi mungkin juga dapat meningkatkan
kesuksesan transplantasi islet. Memang, pasien T1D yang menerima sel islet
intraportal dalam terapi ATG-tacrolimus-MMF memiliki fungsi graft yang lebih
rendah bila telah terdeteksi sel T autoreaktif sebelum transplantasi.
Obat imunosupresif saat ini juga dapat mengganggu fungsi sel beta.
Secara spesifik, rapamycin (sirolimus) mengganggu penanaman graft,
mengganggu angiogenesis, menginduksi resistensi insulin, dan menghambat
replikasi sel . Rapamycin juga, seperti halnya steroid, tacrolimus, dan MMF,
dapat menurunkan transkripsi insulin. Terakhir, sebuah penelitian terbaru
menunjukkan bahwa MMF juga menghambar neogenesis sel beta.
Teknik isolasi islet masih belum memuaskan karena untuk mengembalikan
normoglikemia pada resepien, diperlukan ~12.000 islet per kilogram berat badan.
Hanya ~2.000 subyek di US yang mendapat manfaat dair transplant islet setiap
tahun, karena hanya separuh dari upaya isolasi yang mendapatkan islet sesuai
untuk transplantasi dan resepien biasanya membutuhkan beragam donor.
Penggunaan islet xenogenetik, sebagian besar dari babi atau babi transgenic,
dapat mengisi kebutuhan transplantasi islet. Islet babi diketahui sebagai sel
produsen insulin xenogenetik yang paling kompatibel untuk manusia. Sifat alami
xenogenetiknya membutuhkan imunoproteiksi dalam sebuah kapsul yang
memungkinkan aliran nutrisi dan glukosa ke dalam dan aliran insulin ke luar.
5. Transplantasi stem cell
Generasi sel beta memberikan kemungkinan pendekatan yang menarik
untuk menyembuhkan T1D (Tabel 5). Hal ini dapat dilakukan melalui diferensiasi
embryonic stem cell (ES) atau pluripotent stem cell (IPS) atau pemrograman
ulang dari fenotip awal mereka menjadi sel beta. Stem cell dapat meregenerasi
massa sel beta secara in vivo, sebagaimana ditunjukkan pada transfer stem cell
dari bone marrow pada tikus dengan imunodefisiensi yang diinduksi secara kimia
untuk mengalami kerusakan pancreas. Namun pada sebuah penelitian fase I/II,
stem cell dari darah umbilical cord tidak dapat mempreservasi C-peptida.
Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) autolog non-myeloablatif
memberikan hasil yang lebih baik untuk T1D yang baru terdiagnosis. Dapat
dicapai kondisi independen insulin, namun hilang setelah 4-5 tahun pada
sebagian besar resipien, dan efek samping yang muncul juga membuat terapi ini
tidak dianjurkan sebagai terapi universal.
Stem cell juga berpotensi untuk berdiferensiasi menjadi sel beta secara in
vitro. Penggunaan stem cell autolog dapat menghindari reaksi alloimun, namun
tidak autoimun, yakni respon terhadap sel beta yang ditransplantasikan.
Sejumlah besar usaha dilakukan untuk melakukan teknik enkapsulasi untuk
melindungi sel atau islet yang ditransplantasikan. Contohnya, Viacyte
mendiferensiasi hESCs menjadi endodermal pancreas dan direncanakan untuk
selanjutnya membungkus sel-sel tersebut dengan sebuah kapsul permeable
untuk transplantasi (Encaptra). Idenya bahwa struktur seperti islet dapat
membentuk dan menjadi responsive secara fungsional terhadap glukosa in vivo.
Sebuah pendekatan enkapsulasi ini sudah dapat dilihat pada usaha untuk
melindungi allograft fibroblast manusia dari rejeksi pada monyet rhesus. Selain
itu, implantasi sel beta tikus primer dilakukan dengan kapsul yang sama untuk
menurunkan diabetes pada tikus NOD. Yang paling penting, Viacyte,
sebelumnya NovoCell, mempublikasikan bahwa diferensiasi menjadi hESCs
dapat menciptakan suatu sel produsen insulin yang responsive terhadap glukosa
yang dapat memproteksi terhadap diabetes akibat streptozocin pada tikus.
Namun, data-data terbaru yang meneliti pendekatan tersebut pada tikus athymik
tidak dapat sepenuhnya mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Memang struktur
seperti islet dapat dikembangkan melalui hESCs yang berdiferensiasi menjadi
endodermal pancreas, namun pembentukan sel endokrin dan fungsi sekresinya
dianggap jauh dari cukup untuk relevan secara klinis. Alternatifnya, sebuah
mikrokapsul alginate yang mengandung islet babi dari DiabeCell, juga
memungkinkan produksi insulin hingga 9.5 tahun setelah implant dan saat ini
sedang diteliti dalam penelitian fase I/II (NCT00940173, Living Cell
Technologies). Seperti juga hal tersebut, Cell Pouch merupakan sebuah alat
yang diimplantasi secara sub kutan sebelum penghantaran sel yang
ditransplantasi ke target jaringan yang diinginkan dan pembentukan pembuluh
darah (Sernova). Terakhir teknologi Sertolin dengan memberikan sel-sel Sertoli
bersamaan dengan sel beta untuk memberikan lingkungan imun yang terproteksi
untuk sel atau islet yang ditransplantasikan (Sernova). Sebuah penelitian skala
kecil pada manusia menunjukkan survival transplan jangka panjang dan efek
positif terhadap kontrol metabolic, namun penelitian klinis yang ekstensif belum
dimulai. Meskipun menjanjikan, dapat terjadi dua masalah: (1) penyumbatan
yang dapat menghalangi influx nutrisi dan glukosa serta efflux insulin, dan (2)
mediator terlarut yang menginduksi kematian sel beta masih dapat mencapai sel-
sel hasil transplantasi.
E. Kombinasi Penelitian Intervensi pada T1D
Seperti terapi kanker, terapi T1D mungkin dapat menguntungkan bila
dilakukan kombinasi dari berbagai pendekatan yang sinergi untuk membalik
proses autoimunitas, menciptakan toleransi imunitas, dan memberikan efek
samping yang terbatas. Kami mengulangi di sini proposal awal kami di mana
terapi kombinasi harus mencapai tiga tujuan utama: (1) pembekuan respon
imun aktif dan penurunan respon autoreaktif apapun tanpa efek samping yang
kuat; (2) pembentukan Tregs yang dapat mempertahankan toleransi jangka
panjang; dan (3) regenerasi massa sel beta dari titik kritis untuk
mempertahankan euglikemia tanpa pemberian injeksi insulin berulang.
Kami yakin bahwa terapi kombinasi akan berintegrasi ke dalam terapi T1D
dan seharusnya akan dapat meredakan isu kepemilikan senyawa individual
antara perusahaan. Karena isu terkait dengan masalah regulasi ini, tahap awal
penggunaan terapi kombinasi yang paling logis adalah dengan kombinasi
monoterapi yang terbukti bermanfaat pada T1D atau kombinasi terapi yang telah
terbukti efektif pada penyakit autoimun lainnya (Tabel 6).
Hingga saat ini, hanya dua penelitian klinis mengenai kombinasi terapi
yang telah mempublikasikan hasilnya, dan keduanya mengecewakan. Penelitian
fase III baru-baru ini yang meneliti mAb anti-CD25 (daclizumab) dengan
kombinasi MMF (mofetil, CellCept oleh Roche) melaporkan tidak terjadi
preservasi fungsi sel beta. mAb anti-CD25 mengeblok pathway sinyal IL-2 pada
sel T yang telah teraktivasi, namun tidak mengganggu Tregs. MMF merupakan
obat adjuvant yang secara selektif menghambat proliferasi sel limfosit T dan B
dengan mensupresi sintesis purine de novo. Pada tikus BB, MMF dan anti-CD25
tunggal ataupun kombinasi, terbukti dapat menunda dan mencegah diabetes.
Kedunya imunosupresan sistemik tersebut juga terbukti efektif pada penyakit
autoimun lainnya, dan dalam kombinasi, dapat mencegah rejeksi graft akut.
Penelitian lain yang juga tidak berhasil, meneliti tentang exenatide yang
dikombinasi dengan daclizumab, menunjukkan tidak adanya perbaikan fungsi
sisa sel beta pada pasien dengan T1D yang telah terdiagnosis dalam waktu lama
(21.310.7 tahun).
Penelitian fase I baru yakni Proleukin dan Rapamune akan meneliti
kombinasi IL-2 dan rapamycin (yang menghambat respon terhadap IL-2).
Pemikirannya adalah bahwa IL-2 akan memicu ekspansi Treg melebihi sel T
efektor bila ekspansi efektor telah dihambar secara simultan oleh rapamycin.
Sehingga, delesi dari sel Th1 autoreaktif menyebabkan pergeseran dari sel Th1
menjadi Th2 dan Th3. Pendekatan ini telah didukung oleh keberhasilan
penelitian pre-klinis yang menunjukkan pencegahan onset T1D spontan pada
NOD.
Sebuah penelitian klinis swasta (Helmsley Trust) akan memeriksa apakah
kombinasi antara ATG dan GCSF dapat membalik diabetes onset baru pada
manusia, berdasarkan data dari tikus NOD. Pemikiran yang digunakan adalah:
ATG untuk sementara menurunkan sel T dalam aliran darah, sedangkan GCSF
memobilisasi granulosit dan stem sel hematopoietic dari bone marrow dan
menginduksi sel dendritic tolerogen. Selain itu, baik ATG maupun GCSF dapat
menginduksi populasi Treg untuk memastikan proteksi jangka panjang.
Penelitian klinis Diamyd-Sitagliptin-Lansoprazole fase II sedang dalam
tahap rekrutmen pasien untuk memeriksa kombinasi dari induksi toleransi
spesifik antigen dan regenerasi sel beta. GAD Alum dapat mencegah destruksi
akibat imun dan menunda atau mencegah onset diabetes pada tikus NOD.
Sitagliptin secara tidak langsung menstimulasi sekresi insulin. Lansoprazole
adalah sebuah proton pump inhibitor yang memberikan pembalikan kondisi
parsial pada tikus NOD, namun efeknya menguat bila dikombinasikan dengan
DPP-4 inhibitor.
Tabel 6. Penelitian Intervensional dan Terapi Kombinasi
Agen Mekanisme Fase Detail Referensi
Exenatide +
Daclizumab
Stimulasi sekresi
insulin dan blokade
sinyal IL-2
Fase II
NCT00064714
NIDDK
Kombinasi terapi insulin
intensif, exenatide, dan
daclizumab tidak
menginduksi perbaikan
fungsi sisa sel beta
370
IL-2 +
Rapamycin
Proleukin dan
Rapamune
Down-regulasi efektor
T tanpa menurunkan
fungsi Treg
Promosi Treg
Fase I
NCT00525889
NIAID, ITN
Rekrutmen 347, 420
MMF + anti
CD25
Zenapax,
Daclizumab
Thymoglobulin +
Neulasta
Inhibisi selektif
proliferasi sel T dan
sel B atau blokade
sinyal IL-2
Induksi Treg dan
tolerogenik DC,
rekrutmen
granulosit/HSC
Fase III
NCT00100178
NIDDK/TrialNet
Fase II
Helmsley Trust
Tidak ada preservasi
fungsi sel beta
162
EGF dan gastrin
(E1 + G1 INT)
Regenerasi sel beta
dan neogenesis islet
Fase I
NCT00239148
Transition Therp
Selesai, hasil belum
dipublikasi
409, 412,
413
GAD Alum
(Diamyd)
Lansoprazole,
Imunomodulasi
spesifik GAD,
PPI
Fase II
NCT00837759
NIDDK
Rekrutmen 8, 230,
231, 256
sitagliptin DPP-4 inhibitor
IX. STRATEGI TERAPI SAMPINGAN YANG MENJANJIKAN
A. Penggantian Insulin
Banyak formulasi insulin di pasaran yang telah meningkatkan kualitas
hidup pasien T1D secara dramatis. Insulin bukanlah suatu penyembuhan, namun
masih menjadi terapi utama jangka pendek dan mungkin akan digunakan
sebagai suplementasi untuk terapi lain jangka panjang. Monitor glukosa darah
secara kontinyu atau closed loop insulin delivery system, seperti sebuah
pancreas buatan, akan membuat manajemen diabetes menjadi lebih mudah,
namun tetap akan memberikan beberapa masalah. Sebuah pendekatan yang
patut dicatat dengan data klinis yang menguntungkan adalah SmartInsulin yang
mengandung sebuah polimer berlapis, bio-kompatibel, dan biodegradable yang
terikat dengan molekul pengikat glukosa buatan. Insulin hanya akan dilepas bila
terdapat konsentrasi glukosa tertentu.
B. Kombinasi Terapi Menggunakan Imuno-Modulator dan Vaksin Antigen
Islet
Kami telah menunjukkan bahwa dosis suboptimal dari FcR-non-binding anti
CD3 F(ab)2 yang digabungkan dengan pemberian peptide pro-insulin intranasal
dapat membalik kondisi diabetes pada dua model tikus diabetes. Pada
pemberian kedua agen tersebut, terjadi induksi Tregs spesifik insulin, yang
mensekresi sitokin imunomodulator seperti TGF- dan IL-10, dan memberikan
toleransi dominan saat transfer pada resipien tikus dengan diabetes onset baru.
Penelitian follow up menunjukkan potensi aplikasi yang lebih luas dari
pendekatan ini: anti-CD3 digabungkan dengan vaksinasi plasmid GAD65 dapat
bersinergi dengan kuat pada model T1D RIP-LMCV. Namun, kesuksesan
bergantung pada latar belakang genetic, mungkin pada bagaimana antigen
dipresentasikan ke Tregs.
C. Kombinasi Terapi Menggunakan Imuno-Modulator dan Senyawa Penguat
Massa atau Fungsi Sel Beta
Anti-CD3 bersama dengan exenatide akan mengkombinasikan efek induksi
toleransi imun melalui FcR non-binding anti-CD3 mAb dengan stimulasi sekresi
insulin pada sel beta yang tersisa. Karena pendekatan ini mencoba mengatasi
dua masalah pada T1D, maka diharapkan pendekatan ini memiliki kemungkinan
sukses yang lebih besar daripada agen regenerasi sel beta yakni gastrin dan
exenatide, yang tidak memiliki efek imunomodulasi untuk menghentikan
serangan autoimun terhadap sel beta pancreas. Dikatakan bahwa efek
menguntungkan pada tikus NOD diabetic telah membawa gastrin dan exenatide
ke dalam penelitian tahap II, sedangkan penelitian anti CD3 + exenatide akan
dilaksanakan dalam waktu dekat.
D. Terapi Berbasis Sitokin
Interferensi terhadap sitokin pada intervensi imunologis merupakan sebuah
hal yang kompleks, karena efikasinya memiliki rentang yang lebar dan efek
samping yang berbahaya. Mayoritas manipulasi sitokin akan memberikan efek
ganda tergantung dari waktu, dosis, dan rute pemberian. Contohnya, baik IL-18
maupun TNF- dapat mempercepat atau menghambat T1D pada NOD saat
diberikan pada tahap awal atau akhir dari penyakit. Kompleksitas inilah yang
menghambat penelitian klinis dari strategi tersebut. Satu strategi yang
dipertimbangkan akan masuk penelitian klinis adalah kombinasi dari pemberian
rapamycin dengan fusi protein dari antagonis IL-2-Fc dan antagonis IL-15-Fc,
yang terbukti memberikan toleransi jangka panjang untuk model
allotransplantasi. Diharapkan strategi tersebut dapat membatasi aktivasi dan
ekspansi sel T efektor (dengan mengeblok sinyal IL-15) dan menginduksi Tregs
(IL-2 dan rapamycin). Yang patut dicatat adalah peran penting dari axis
IL21/IL21R terhadap diabetes autoimun pada NOD dan perannya dalam
kerentanan genetic pada T1D.
X. KESIMPULAN
Insiden T1D meningkat dengan cepat, khususnya di negara maju, dan
waktu munculnya onset bergeser ke arah usia yang lebih muda. T1D
kemungkinan besar diakibatkan oleh kombinasi dari kerentanan genetic dan
eksposure terhadap pemicu dari lingkungan. Mekanisme efektor utama adalah
jelas reaksi autoimun, yang juga terbukti saat dilakukan diagnosis klinis. Hal ini
memberikan dua konsep terapi klinis: (1) pemahaman mengenai penyebab lebih
penting dalam proses pencegahan daripada terapi saat onset; dan (2) terapi
saat onset atau mendekati onset memerlukan suatu komponen yang dapat
menurunkan atau memodulasi imun. Pendapat kami saat ini adalah bahwa kita
harus melaksanakan penelitian dengan terapi seperti anti-CD3 yang efektif saat
onset (baik tunggal ataupun kombinasi), namun pemberian terapi harus dimulai
sesuai deteksi dini dan bukan menunggu hingga terjadi hiperglikemia. Deteksi
dini juga diperlukan untuk mempreservasi sisa massa sel beta dengan maksimal,
karena kemampuan untuk mensekresi bahkan sejumlah kecil insulin, dapat
membuat kontrol teerhadap penyakit menjadi lebih mudah dan membantu
meminimalisir komplikasi kontrol glikemik kronis yang inadekuat. Usaha skrining
idealnya harus menyatukan semua hasil pemeriksaan mulai dari genetic (HLA-
DR3/4-DQ2/8, genetic keluarga), metabolomik (lysophosphatidylcholine), dan
pemeriksaan pelepasan C-peptida dengan titer autoantibodi (insulin, GAD65,
ICA512, ZnT8) dan pemeriksaan sel T autoreaktif (Proinsulin, GAD65, I-A2, dan
ZnT8).
Banyak dari pemahaman kami saat ini mengenai T1D yang berasal dari
model tikus NOD. Untuk lebih memfokuskan pada aplikasi pada manusia,
penting untuk melihat lebih dari sekedar model tikus NOD untuk kemudian
diambil manfaatnya pada model-model lain yang ada. Dan bahkan kemudian,
mayoritas terapi T1D yang ditemukan pada model tikus masih belum dapat
diaplikasikan pada manusia. Kemungkinan-kemungkinan terapi yang ada telah
berubah akibat perubahan prospek bahwa progress T1D mungkin dapat
dihambat oleh stimulasi aktif dari toleransi yang diinduksi melalui imunisasi
spesifik terhadap auto-antigen untuk menginduksi produksi Tregs. Kesuksesan
akan sangat bergantung pada (1) pilihan protein atau peptide yang diberikan, (2)
dosis, (3) tahap perjalanan penyakit, dan (4) rute pemberian. Sebuah kombinasi
biostimulasi yang diciptakan oleh computer (in silico) dan penelitian wet lab
dapat meningkatkan kemungkinan dan menurunkan waktu yang diperlukan untuk
menemukan terapi imun yang sesuai.
Tujuan utama dari terapi autoimun adalah untuk menghentikan serangan
imun terhadap diri sendiri tanpa mengorbankan ketahanan tubuh pasien
terhadap infeksi. Hal ini paling mungkin diciptakan melalui terapi yang
mengkombinasikan agen imuno-supresan non-spesifik (contoh: anti-CD3), agen
induksi Tregs yang spesifik antigen (contoh: Proinsulin, GAD65), dan senyawa
yang sesuai yang dapat meningkatkan massa atau fungsi sel beta. Untuk pasien
dengan level C-peptida >0.5 (nM), maka dapat diberikan dua senyawa terapi,
karena riset preklinis menunjukkan bahwa masih dapat terjadi regenerasi sel
beta secara alami. Pasien dengan level C-peptida 0.2-0.5 mungkin memerlukan
senyawa regenerasi sel beta tambahan, seperti gastrin dan exenatide. Level C-
peptida di bawah 0.2 mengindikasikan kebutuhan akan transplantasi islet
pancreas.
Sayangnya, kenyataan yang ada tidak memungkinkan kombinasi dari satu
atau lebih obat yang belum diterima. Pandangan yang ada saat ini adalah setiap
senyawa dalam terapi kombinasi harus memiliki efikasi dari telah dilisensi untuk
masing-masing kegunaannya. Hal ini mengharuskan dilakukannya penelitian
keamanan untuk masing-masing senyawa dan penelitian efikasi untuk terapi
kombinasi. Selain itu, masih terdapat isu hak kepemilikan dari masing-masing
perusahaan. Sehingga, masih diperlukan usaha-usaha besar untuk benar-benar
mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dari
penelitian mengenai diabetes autoimun.
Anda mungkin juga menyukai
- Referat CrohnDokumen32 halamanReferat CrohnSonyaSellyH100% (1)
- DM Tipe 1Dokumen19 halamanDM Tipe 1parta anantamaBelum ada peringkat
- Steven Johnson SyndromeDokumen17 halamanSteven Johnson Syndromelalaputri36Belum ada peringkat
- JANTUNG REUMATIKDokumen24 halamanJANTUNG REUMATIKWidyanisa DwianastiBelum ada peringkat
- Referat Dermatitis HerpetiformisDokumen13 halamanReferat Dermatitis HerpetiformisElisha RosalynBelum ada peringkat
- DM Vs TBDokumen9 halamanDM Vs TBDhellaa NovianaBelum ada peringkat
- Dermatitis Eksfoliativa GeneralisataDokumen22 halamanDermatitis Eksfoliativa GeneralisatacaturprianwariBelum ada peringkat
- CrsDokumen45 halamanCrsWinarti RimadhaniBelum ada peringkat
- Diabetes Mellitus - StatPearls - Rak Buku NCBIDokumen10 halamanDiabetes Mellitus - StatPearls - Rak Buku NCBIrahmatia alimunBelum ada peringkat
- Systemic Lupus Erythematosus (SLE) Adalah Penyakit AutoimunDokumen89 halamanSystemic Lupus Erythematosus (SLE) Adalah Penyakit AutoimunTria RangkutiBelum ada peringkat
- PENGARUH FAKTOR GENETIK DAN HORMONAL PADA SLEDokumen84 halamanPENGARUH FAKTOR GENETIK DAN HORMONAL PADA SLERosiBelum ada peringkat
- Referat Lupus NephritisDokumen44 halamanReferat Lupus NephritisHelvin Eka PutraBelum ada peringkat
- IBD-PENYAKITDokumen23 halamanIBD-PENYAKITGina Puspita PertiwiBelum ada peringkat
- Sel LE dan Faktor RisikoDokumen11 halamanSel LE dan Faktor RisikoSevriRombe MadikaBelum ada peringkat
- DM Tipe 1Dokumen22 halamanDM Tipe 1Nitha Koli100% (2)
- Penyakit Jantung BawaanDokumen7 halamanPenyakit Jantung BawaanwarmanlicyBelum ada peringkat
- Graves' PenyakitDokumen24 halamanGraves' PenyakitHera HeraBelum ada peringkat
- Refarat SLEDokumen36 halamanRefarat SLERizka MardhatillahBelum ada peringkat
- Referat PerinaDokumen23 halamanReferat PerinaDwi CahyaBelum ada peringkat
- SLE ReferatDokumen34 halamanSLE ReferatResi Lystianto PutraBelum ada peringkat
- Dermatitis Atopik Dan Sindrom Metabolik AlvinDokumen7 halamanDermatitis Atopik Dan Sindrom Metabolik AlvinSeruni EstariBelum ada peringkat
- Kehamilan Dengan SleDokumen27 halamanKehamilan Dengan SleNur Rosida AisianaBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Diabetes Melitus Tipe 1Dokumen24 halamanAsuhan Keperawatan Diabetes Melitus Tipe 1aisyalfi pratimiBelum ada peringkat
- Referat Lupus Dan Penilaian AktivitasDokumen38 halamanReferat Lupus Dan Penilaian AktivitasDebbyBelum ada peringkat
- Patofisologi Gangguan Sistem Endokrin - DM JuvenileDokumen8 halamanPatofisologi Gangguan Sistem Endokrin - DM JuvenileazizahBelum ada peringkat
- (Referat) Muh. Afdhal Ruslan-Penyakit CrohnDokumen40 halaman(Referat) Muh. Afdhal Ruslan-Penyakit CrohnhadiBelum ada peringkat
- Case Report Sle 18 Feb 2Dokumen66 halamanCase Report Sle 18 Feb 2Jongga SiahaanBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Kad AnastasiaDokumen32 halamanLaporan Kasus Kad AnastasiaA'tasia ManangsangBelum ada peringkat
- Diabetes Melitus Tipe 1Dokumen28 halamanDiabetes Melitus Tipe 1Gita Ratnasari100% (2)
- Diabetes MelistusDokumen11 halamanDiabetes MelistusFrank MBelum ada peringkat
- Penyakit PtiDokumen21 halamanPenyakit PtiWahyu Ismail SiagianBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Rawat Inap AllDokumen21 halamanLaporan Kasus Rawat Inap AllLestary NyomanBelum ada peringkat
- Lampiran PBK I 2022Dokumen56 halamanLampiran PBK I 2022Kecebong SawahBelum ada peringkat
- SISTEM LUPUS ERITEMATOSUSDokumen13 halamanSISTEM LUPUS ERITEMATOSUSAgus SuryawanBelum ada peringkat
- Blok Kardiovaskular Sken 3Dokumen19 halamanBlok Kardiovaskular Sken 3anggiBelum ada peringkat
- TB DM 1Dokumen14 halamanTB DM 1Purnama Aji Saputra0% (1)
- Makalah TB Paru Dengan DMDokumen23 halamanMakalah TB Paru Dengan DMTaufiq Andrian100% (3)
- SLE Pada KehamilanDokumen23 halamanSLE Pada KehamilanJene Namikaze YonathanBelum ada peringkat
- ISIDokumen36 halamanISIika dundaBelum ada peringkat
- Referat SLE NewDokumen29 halamanReferat SLE NewYudi PUtraBelum ada peringkat
- TUBERKULOSIS DENGAN DIABETESDokumen24 halamanTUBERKULOSIS DENGAN DIABETESMindy PasumaBelum ada peringkat
- Referat TB DMDokumen9 halamanReferat TB DMDinda MutiaraBelum ada peringkat
- HSP PenyakitDokumen32 halamanHSP PenyakitAni Martiningsih100% (2)
- Steven Johnson SyndromeDokumen17 halamanSteven Johnson SyndromeUzi Mardha PhoennaBelum ada peringkat
- RismaDianty LP (TB+DM) 125Dokumen23 halamanRismaDianty LP (TB+DM) 125Risma PutriBelum ada peringkat
- SLE PatogenesisDokumen50 halamanSLE PatogenesisWilliam OmarBelum ada peringkat
- Referat SLEDokumen20 halamanReferat SLEbasimah100% (2)
- Askep Lupus Eritematosus Sistemik Les 1Dokumen21 halamanAskep Lupus Eritematosus Sistemik Les 1Nur RahayuBelum ada peringkat
- Refrat AOSD Rizky MaulanaDokumen22 halamanRefrat AOSD Rizky Maulanamedical fighterBelum ada peringkat
- SJSDokumen16 halamanSJSRizky SofyanBelum ada peringkat
- Grave Anemia Hemolitik AutoimunDokumen35 halamanGrave Anemia Hemolitik AutoimundiegoBelum ada peringkat
- Journal Reading Syphilis PresentationsDokumen10 halamanJournal Reading Syphilis PresentationsKoko PurnamaBelum ada peringkat
- Graves Disease GejalaDokumen30 halamanGraves Disease GejalarahmanBelum ada peringkat
- Sindroma Evan Pada KehamilanDokumen21 halamanSindroma Evan Pada KehamilanRangga LunesiaBelum ada peringkat
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatDari EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Bismilah..semoga Ilmu Ini Bermanfaat Dan Menjadi Lading Amal Jariyah Kelak.. AminnnnnnDokumen1 halamanBismilah..semoga Ilmu Ini Bermanfaat Dan Menjadi Lading Amal Jariyah Kelak.. AminnnnnnyuriskamaydaBelum ada peringkat
- Darah Dari PlasentaDokumen2 halamanDarah Dari PlasentayuriskamaydaBelum ada peringkat
- Anatomi OtakDokumen2 halamanAnatomi OtakyuriskamaydaBelum ada peringkat
- Ringkasan Imunisasi PDFDokumen9 halamanRingkasan Imunisasi PDFNurima Ulya Dwita100% (1)
- BismillahDokumen32 halamanBismillahyuriskamaydaBelum ada peringkat
- Ringkasan Imunisasi PDFDokumen9 halamanRingkasan Imunisasi PDFNurima Ulya Dwita100% (1)
- Ringkasan Imunisasi PDFDokumen9 halamanRingkasan Imunisasi PDFNurima Ulya Dwita100% (1)
- 5 Menit Pertama Saat Yang Paling Menentukan Bagi Bayi Baru Lahir PDFDokumen34 halaman5 Menit Pertama Saat Yang Paling Menentukan Bagi Bayi Baru Lahir PDFmus2013Belum ada peringkat
- BismillahDokumen32 halamanBismillahyuriskamaydaBelum ada peringkat
- BismillahDokumen32 halamanBismillahyuriskamaydaBelum ada peringkat