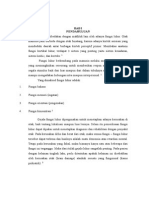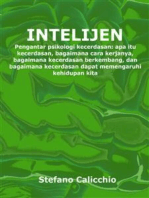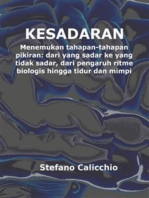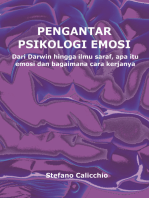Afasia
Afasia
Diunggah oleh
DeVi K. NinGsihJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Afasia
Afasia
Diunggah oleh
DeVi K. NinGsihHak Cipta:
Format Tersedia
Cermin
1 9 8 4
Dunia Kedokteran
34. Masalah Otak
No 34, 1984
Cermin
Dunia Kedokteran
International Standard Serial Number : 0125913X Diterbitkan oleh :
Pusat Ps'nelitian dan P.np.mbanpan P.T. Kalbe Farina
Cermi n
Dunia Kedokteran
34. MasalahOtak
Karya Sriwidodo
Tulisan dalam majalah ini merupakan pandang-
an/pendapat masing-maeing penulie dan tidak
eelalu merupakan pandangan atau kebijakan
inetansl/lembaga/bagian tempat kerja ai penulie.
Artikel :
3 Afasia Sebagai Gangguan Komunikasi Pada Kelainan
Otak
7 Gangguan Bahasa, Persepsi dan Memori Pada Kelainan
Otak
12 Disfungsi Otak Minor
Kesulitan Belajar ditinjau dari Segi Neurologis
15 Gangguan Kesadaran
20 Beberapa Obat yang Digunakan pada Insufisiensi
Serebral dan Demensia
25 Penanggulangan Bencana Peredaran Darah di Otak
28 Peranan Radiologik Pada Kelainan Otak
32 Cedera Otak dan Dasar-dasar Pengelolaannya
39 Infeksi Intrakranial
42 Tumor Otak : Tinjauan Kepustakaan
47 Ketulian : Pemeriksaan dan Penyebabnya
50 Rodamin B dan Metanil Kuning ("Metanil Yellow")
Sebagai Penyebab Toksik pada Mencit dan Tikus
Percobaan
56 Perkembangan : Obat-obat & Insomnia
Pengobatan Preleukemia
58 Hukum & Etika : Tepatkah Tindakan Saudara ?
60 Catatan Singkat
61 Humor Ilmu Kedokteran
63 Ruang Penyegar dan Penambah Ilmu Kedokteran
64 Abstrak-abstrak
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 3
Artikel
Afasia Sebagai Gangguan Komunikasi
Pada Kelainan Otak
dr. Lily Sidiarto dan dr. Sidiarto Kusumoputro
Klinik Gangguan Wicara - Bahasa Bagian Neurologi FKUI/RSCM, Jakarta
PENDAHULUAN
Dengan bertambahnya jumlah gangguan peredaran darah
otak (CDV) dan trauma kapitis, maka jumlah kasus dengan
gejala sisa neurologik juga makin meningkat. Gejala sisa ele-
menter yang paling menyolok adalah hemiparesis dan gejala sisa
fungsi luhur yang paling banyak adalah afasia. Pada kasus CVD,
kemungkinan seorang pasien menderita afasia adalah 25%,
karena separuhnya menderita hemiparesis dekstra dan separuh
dari ini mungkin menderita afasia. Karena afasia tergolong
kelainan komunikasi dan komunikasi merupakan bagian yang
penting dalam kehidupan manusia, maka rehabilitasi afasia tidak
dapat diabaikan. Mungkin saja seorang dengan gejala sisa
kelumpuhan menduduki jabatannya semula tetapi akan sangat
sulit bagi orang yang menderita afasia. Bukannya ini berarti
tidak mungkin; sebagian pasien afasia dapat juga kembali
menduduki jabatan semula asal afasinya yang tidak terlalu berat
mendapatkan rehabilitasi yang cepat dan tepat. Untuk maksud
itu, kecepatan dan ketepatan diagnosis sangat diperlukan untuk
menolong nasib pasien afasia.
Makalah ini menguraikan secara singkat masalah afasia ditin-
jau secara klinik.
GANGGUAN KOMUNIKASI
Seorang yang berkomunikasi menggunakan sederetan fungsi
sebagai berikut :
1. simbolisasi, yaitu melakukan formulasi dan menyimak ba-
hasa dan simbol-simbol lain yang lazim disebut berbahasa.
2. respirasi, yang diperlukan untuk mendapatkan tenaga gu-
na berbicara (speech).
3. resonansi : menghasilkan nada-nada tertentu.
4. fonasi (pembunyian) : tenaga yang didapat dipakai untuk
menggerakkan pita suara.
5. artikulasi : menghasilkan vokal dan konsonan untuk berbicara.
6. lafal : menghasilkan pengucapan bunyi bahasa.
7. prosodi : yang membuat lagu kalimat.
8. kemampuan komunikasi, yaitu kemauan, kesediaan dan
kemampuan untuk berinteraksi lewat komunikasi.
Jenis gangguan komunikasi dapat disebabkan oleh kelainan
pada salah satu atau beberapa dari fungsi tersebut diatas.
Bagan gangguan wicara-bahasa (speech and language disorder)
Gangguan komunikasi juga disebut sebagai gangguan wicara
bahasa dan istilah ini lebih sering dipakai. Gangguan ini dapat
terjadi pada anak dan dewasa.
Sebuah bagan sederhana disajikan dibawah ini :
Gangguan wicarabahasa
a. gangguan multimodalitas :
afasia
b. gangguan modalitas tunggal :
agnosia
apraksia
c. gangguan "berpikir" :
demensia
conf usion (kusut pikir)
psikogemic
Untuk memahami jenis-jenis gangguan wicara-bahasa se-
baiknya dikenal juga komponen-komponen dari proses pusat
bahasa di otak. Menurut Brown, model pusat bahasa di otak
gangguan wicara mencakup
fungsi dasar :
- respirasi
- resonansi
- fonasi
- artikulasi
- lafal
- prosodi
terdiri dari 4 komponen :
1. kosa kata (leksikal) yang didapat sejak kecil dan dikem-
bangkan terus seumur hidup.
2. sintaktikal, suatu aturan yang dikuasai untuk membentuk
kalimat yang benar.
3. rentang ingatan auditif (auditory retention span) yang cu-
kup lama untuk dapat memproses apa yang didengar.
4. pemilihan saluran, suatu kemampuan untuk menyaring
dan memilih masukan (input) dan keluaran (output) yang
diperlukan untuk berbahasa menurut hirargi.
Komponen-komponen ini diperlukan untuk mempelajari
bahasa dan mempergunakannya secara baik dan benar. Pene-
rapan penggunaan komponen-komponen tersebut dalam ber-
bahasa dapat dilihat dari ketrampilan penggunaan modalitas
bahasa sebagai berikut :
1. berbicara
2. menyimak
3. menulis
4. membaca
Jenis-jenis gangguan bahasa dapat diterangkan berdasarkan
ketrampilan menggunakan modalitas bahasa diatas.
GANGGUAN WICARABAHASA
Seseorang dapat terganggu wicaranya saja (speech disorder)
ataukah bahasanya (language disorder). Kedua gangguan yang
disatukan tersebut sebenarnya mempunyai perbedaan yang
nyata. Gangguan wicara : bersifat perifer, disebabkan oleh
kelainan-kelainan saraf perifer, otot dan struktur yang dipakai
untuk berbicara.
Gangguan bahasa : bersifat sentral, disebabkan oleh kelainan
pada korteks serebri (fungsi luhur).
1. Gangguan wicara : Sering disebut juga sebagai gangguan
wicara dan suara (speech and voice disorder), karena memang
mencakup kedua fungsi tadi. Lazim juga disebut dengan satu
kata "disartria" untuk kemudahan. Kelainan-kelainan neuro-
logik banyak yang menyebabkan gangguan wicara ini dan letak
lesinya dapat ditetapkan berdasarkan gangguan fungsi dasar
yang ditemukan. Juga penyakit-penyakit lain seperti THT,
mulut, gigi-geligi, paru dan sebagainya dapat menyebabkan
gejala
"
disartria" ini. Kami tidak membahas hal ini lebih lanjut.
2. Gangguan bahasa : Gangguan ini lebih kompleks sifatnya.
Gangguan bahasa dapat ditinjau dari aspek gangguan modal itas
bahasa (berbicara, menyimak, menulis dan membaca), untuk
membedakan afasia dari agnosia dan apraksia. Sedangkan dari
aspek gangguan
"
berpikir
"
dan
"
cara penggunaan bahasa" dapat
dibedakan demensia, kusut pikir (confusion) dan kasus
psikiatrik.
gangguan multimodalitas bahasa : Afasia adalah gangguan
bahasa yang meliputi semua modalitas yaitu berbicara,
menyimak, menulis dan membaca. Tidak ada afasia yang
salah satu modalitasnya masih sempurna. Biasanya semua
terkena, hanya yang satu lebih berat daripada yang lain.
gangguan modalitas tunggal : Sering dijumpai pasien tidak
4 Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984
dapat berbicara dan menyimak bahasa, tetapi masih dapat
menulis dan membaca. Pasien ini menderita agnosia auditif.
Sebaliknya pasien yang menderita apraksia tidak mampu
menulis, tetapi mampu berbicara.
gangguan
"
berpikir" : Penggunaan bahasa yang tidak benar
dapat juga disebabkan oleh gangguan cara berpikir dan salah
menggunakan bahasa. Hal ini membedakan dari afasia,
agnosia dan apraksia yang disebabkan oleh gangguan mo-
dalitas bahasa. Contoh dari gangguan
"
berpikir" adalah de-
mensia, kusut pikir (confusion) dan kasus psikiatrik. Di
bawah ini akan dibahas sepintas tentang pola berbahasa pada
contoh tersebut untuk memberikan gambaran bahwa ada
gangguan bahasa yang non-afasia. Pola berbahasa pada
pasien demensia menunjukkan kesalahan-kesalahan pada
semua segi bahasa. Yang menyolok ialah ketidak mampuan
untuk memberikan makna sebuah pepatah. Tidak mampu
melaksanakan tugas verbal yang abstrak, seperti tidak dapat
menyebutkan nama-nama benda dalam satu kategori (nama-
nama hewan piaraan rumah). Reaksinya lambat, sukar
mengikuti pembicaraan yang beralih dari satu judul ke judul
yang lain. Pasien lupa apa yang baru saja dibicarakan. Selain
gangguan bahasa, pasien demensia juga menunjukkan
gangguan fungsi luhur lainnya seperti gangguan persepsi,
memori, kognitif dan emosi.
Pola berbahasa pasien kusut pikir (confused) tampaknya
sepintas masih normal. la masih dapat menyebutkan nama
benda, membaca kalimat pendek dan mudah, berhitung se-
derhana. Tetapi mengalami kesukaran kalau tugas tersebut agak
sulit. Pasien akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan
yang terbuka, yang harus ia jawab dengan menyusun kalimat. la
akan mengalami kesulitan pula dalam memberi makna sebuah
pepatah. Walaupun kalimatnya benar tetapi isinya sering tidak
cocok. la tidak sadar bahwa ia telah membuat kesalahan dalam
pembicaraannya. Pasien juga mengalami gangguan orientasi
waktu, orang dan tempat disamping gangguan yang tersebut
diatas. Juga pasien sukar mempertahankan interaksinya dengan
orang lain dalam waktu lama dan tidak dapat mengikuti
pembicaraan terus menerus. Biasanya keadaan kusut pikir ini
sementara (transient) sifatnya. Pola berbahasa pada kasus
psikiatrik tidak dibahas disini.
SINDROMA AFASIA
Afasia adalah gangguan bahasa yang multimodalitas, artinya
tidak mampu berbicara, menyimak, menulis dan membaca.
Tergantung dari jenis afasinya, ketidak mampuan dalam moda-
litas tersebut tidak merata tetapi satu lebih menonjol dari yang
lain.
Dari segi klinik, jenis afasia yang mudah dikenali adalah :
1. afasia Broca (menonjol : tidak dapat bicara)
2. afasia Wernicke (menonjol : tidak dapat menyimak)
3. afasia anomik (menonjol : tidak dapat menyebut nama benda)
4. afasia konduksi (menonjol : tidak dapat mengulang kalimat)
5. afasia global (semua tidak dapat)
Masih ada jenis-jenis afasia lain yang tidak dicantumkan, ka-
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 5
rena jarang dan sukar dikenali secara klinik.
Ciri-ciri afasia
Afasia adalah gangguan bahasa dan biasanya tanpa gangguan
fungsi luhur lainnya seperti gangguan persepsi, memori, emosi
dan kognitif (kalaupun ada tidak seberat gangguan bahasanya).
Disini letak perbedaan dengan demensia, yang mengalami
gangguan pada semua fungsi luhur secara merata.
Afasia dapat dibagi dalam 2 golongan besar : afasia non-fluent
dan afasia fluent. Penggolongan ini dilakukan dengan memper-
inci ciri-ciri bicara spontan pasien. Afasia dapat ditentukan
jenisnya dari analisis kemampuan linguistiknya (bicara spontan,
menyimak, mengulang dan menyebut). Afasia yang berat dan
sedang dapat ditetapkan secara klinik non formal, sedangkan
afasia yang ringan atau meragukan perlu ditetapkan secara
formal dengan tes afasia. Penetapan jenis afasia (Broca,
Wernicke dan sebagainya) diperlukan untuk menentukan letak
lesi di otak (diagnostik) dan program rehabilitasinya (bina wicara
= speech therapy).
Langkah-langkah penetapan afasia
1. menentukan bahasa yang dikuasai pasien.
2. menentukan kecekatan tangan (handedness)
3. menetapkan golongan afasia non fluent dan fluent.
4. menetapkan jenis afasia.
5. menetapkan fungsi-fungsi luhur lainnya (persepsi, memori,
emosi, kognitif).
6. menetapkan dengan tes formal (Token Test, Peabody Vo-
cabulary Test, Boston Diagnostic Aphasia Test).
7. menetapkan fungsi-fungsi luhur lainnya dengan formal (tes
psikometrik).
Cara dan makna penetapan
1. Pada afasia, biasanya bahasa ibu merupakan bahasa yang
paling sedikit terkena dibandingkan bahasa-bahasa lain yang
dipelajari oleh pasien poliglot.
2. Hemisfer kiri pada orang kinan (right-handed) dianggap me-
rupakan hemisfer yang dominan. Dominansi serebral ini dapat
diketahui dari kecekatan tangan pasien. Kemutlakan dominansi
serebral dapat dipakai sebagai ancar-ancar untuk menentukan
prognosis afasia. Dikatakan bahwa dominansi yang mutlak
mempunyai prognosis yang kurang baik dibandingkan do-
minansi yang tidak mutlak. Kemutlakan ini dapat diketahui dari
kecekatan tangan, mata dan kaki pasien. Orang dianggap kinan
mutlak bila ia cekat dalam hal penggunaan tangan, mata dan
kaki kanan serta tidak ada keluarga yang kidal. Orang dianggap
kinan tidak mutlak bila cekat tangan kanan disertai cekat mata
atau kaki kiri, atau bila ada keluarga yang kidal. Cara
menentukan cekat tangan biasanya dilihat dari tangan mana yang
dipakai untuk bekerja, menulis dan makan minum. Cekat mata
ditentukan dengan mata mana pasien mengintip sebuah lubang
dan cekat kaki dengan cara kaki mana yang dipakai untuk
berdiri diatas satu kaki. Cara-cara tersebut sudah cukup untuk
menentukan kecekatan. Ada cara-cara lain yang lebih terperinci
yang tidak dibahas disini. Hal-hal tersebut tidak berlaku
seluruhnya bagi pasien kidal.
3. Bicara spontan yang non fluent dan fluent dapat ditentu-
kan dengan menganalisis ciri-ciri bicara sebagai berikut :
- tempo berbicara menurun meningkat
- usaha bicara meningkat normal
- banyak bicara menurun meningkat (logore)
- isi substantif predikatif
- panjang frase pendek panjang
- parafasia jarang
ada
Menentukan ciri bicara ini penting dalam menetapkan letak lesi.
Afasia non fluent : biasanya letak lesi di bagian anterior he-
misfer kiri (dominan).
Afasia fluent : letak lesi biasanya di bagian posterior.
Pada penentuan ciri bicara ini pasien disuruh berbicara secara
spontan untuk beberapa saat. Dari pembicaraannya dapat dinilai
ciri-ciri tadi. Tentu hal ini dilakukan secara global dalam
penetapan secara klinik. Dalam penetapan formal terdapat
patokan penilaian tertentu dari ciri bicara ini.
4. Penetapan jenis afasia dipakai kemampuan linguistik bicara
spontan, menyimak, mengulang dan menyebut sebagai patokan.
Secara klinik, bicara spontan telah. dibahas diatas. Penyimakan
bahasa dapat ditentukan secara klinik dengan menanyakan
beberapa pertanyaan pada pasien dan pertanyaan yang diajukan
mula-mula sederhana makin lama makin kompleks. Pertanyaan
dibuat sedemikian hingga cukup dijawab oleh pasien dengan ya
atau tidak, bila perlu dengan anggukan dan gelengan kepala. Hal
ini terutama bila kita memeriksa pasien afasia yang non-fluent.
Contoh pertanyaan : "Apakah ibu yang ada disamping saya ini
istri bapak?" "Apakah bapak sudah sarapan pagi tadi?"
Pertanyaan dapat disusun dan disesuaikan dengan latar bela-
kang pendidikan dan kedudukan social pasien. Pertanyaan-
pertanyaan formal pada tes afasia tentu menggunakan kalimat
yang dibuat sedemikian rupa hingga mempunyai kesukaran
linguistik. Pengulangan kata/kalimat juga dimulai dari yang
sederhana sampai yang sulit. Contoh kata yang sederhana "ma-
kan" dan yang sulit "menjajagi
"
. Kalimat mudah "Udara hari ini
cerah" dan kalimat sulit "Musim kemarau yang panjang dan
kering tahun ini merupakan bencana bagi kami
"
.
Penyebutan nama benda dapat dilakukan dengan menyuruh
pasien menyebutkan beberapa nama benda yang ada diseki-
tarnya.
Jenis afasia ditentukan dengan kemampuan linguistik sebagai berikut :
Afasia bicara spontan penyimakan pengulangan penyebutan
Wernicke
Broca
konduksi
global
anomik
fluent
non-fluent
fluent
non-fluent
fluent
buruk
baik
baik
buruk
baik
buruk
buruk
buruk
buruk
baik
buruk
buruk
buruk
buruk
buruk
Penetapan jenis afasia ini mempunyai makna : diagnostik,
prognostik dan terapeutik sebagai berikut :
Afasia Broca terletak di bagian anterior di daerah posterior
girus frontalis.
Fluent
Ciri bicara Non-fluent
Afasia Wernicke terletak di bagian posterior di daerah girus
temporalis posterior-superior
Afasia konduksi lesinya berada di fasikulus arkuatus diantara
Broca dan Wernicke.
Afasia global mempunyai lesi yang luas meliputi seluruh
korteks. Prognosisnya juga sangat buruk ada yang menye-
butnya sebagai afasia irreversible Jenis inilah yang sering
mirip dengan demensia.
Afasia anomik atau anomia dapat terjadi di beberapa tempat.
Tidak mempunyai nilai lokalisasi. Paling sering di daerah
girus angularis. Sering mgrupakan gejala sisa dari afasia yang
berat.
5. Penetapan afasia dengan tes formal yang dipakai di Klinik
Gangguan Wicara Bahasa FKUI/RSCM dipilihkan dari tes yang
bersifat multilingual. Artinya, tes yang dapat dialih bahasakan
ke bahasa lain. Namun demikian, kesulitan linguistik dalam
modifikasi tes tersebut masih ada. Afasia adalah ilmu yang
prinsip, konsep dan tes formalnya tidak dapat diambil alih
begitu saja dari bahasa aslinya.
Penanganan terpadu afasia oleh neurolog, psikolog, linguist dan
ahli bina-wicara sangat mutlak.
DASAR-DASAR REHABILITASI
Bina wicara (speech therapy) pada afasia didasarkan pada :
1. Dimulai seawal mungkin. Segera diberikan bila keadaan
umum pasien sudah memungkinkan pada fase akut penya-
kitnya.
2. Dikatakan bahwa bina wicara yang diberikan pada bulan
pertama sejak mula sakit mempunyai hasil yang paling baik.
3. Hindarkan penggunaan komunikasi non-linguistik (seperti
isyarat).
4. Program terapi yang dibuat oleh terapis sangat individual dan
tergantung dari latar belakang pendidikan, status sosial dan
kebiasaan pasien.
5. Program terapi berlandaskan pada penumbuhan motivasi
pasien untuk mau belajar (re-learning) bahasanya yang hi-
lang. Memberikan stimulasi supaya pasien memberikan
tanggapan verbal. Stimuli dapat berupa verbal, tulisan atau-
pun taktil. Materi yang telah dikuasai pasien perlu diulang-
ulang (repetisi).
6. Terapi dapat diberikan secara pribadi dan diseling dengan
terapi kelompok dengan pasien afasi yang lain.
7. Penyertaan keluarga dalam terapi sangat mutlak.
KEPUSTAKAAN
1. Benson DF. Aphasia, Alexia and Agraphia. New York: Churchill
Livingstone, 1979.
2. Darley FL. And Spriestersbach DC. Diagnostic Methods in Speech
Pathology. New York: Harper and Row, 1978.
3. Eisenson J. Adult Aphasia, Assessment and Treatment. San Fran-
cisco: Appleton-Century-Crofts, 1973.
4. Espir M and Rose FC. The Neurology of Speech. London : Black-
well Scientific Publications, 1976.
5. Watson R. How to examine the patient with aphasia. Geriatrics, Des.
1975; 73- 77.
S I M D I TteWu N
MEN66G6cr R KA N
K A t . D l N 6 A N .
A PA K A H B E N 4 ?
B a N A R , SA yA TEL-414
MEN6606URkAN
KEHAMb.14N 100 E?coR
TlKtdS ( L t K
PERCOBA A N (LMIA
6 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 7
Gangguan Bahasa, Persepsi dan Memori
Pada Kelainan Otak
dr. Sidiarto Kusumoputro dan dr. Lily Sidiarto
Klinik Gangguan Wicara - Bahasa Bagian Neurologi FKUI/RSCM, Jakarta
PENDAHULUAN
Tiga unsur tingkah laku manusia terhadap alam sekeliling-
nya ialah pengamatan, pikiran dan tindakan. Dalam bidang
neurologi tiga unsur tersebut tertuang dalam fungsi sensorik.
luhur dan motorik. Dalam keadaan sakit, unsur-unsur tadi dapat
terganggu. Gangguan tersebut dapat berupa gejala neurologik
elementer, misalnya hemiparesis, hemihipestesia, koma, kejang
dan sebagainya tetapi dapat pula berupa gejala neurologik luhur,
yang merupakan kelainan integratif yang kompleks dari ke tiga
fungsi di atas.
Yang dimaksud dengan fungsi luhur atau fungsi kortikal
luhur adalah fungsi-fungsi :
1. bahasa
2. persepsi
3. memori
4. emosi
5. kognitif
Dalam neurologi, gejala elementer dan luhur dipergunakan un-
tuk menetapkan adanya kerusakan di otak, baik tentang loka-
lisasi maupun luas lesinya. Ke dua fungsi tersebut sama pen-
tingnya dalam penetapan diagnosis. Juga keduanya menuruti
prinsip organisasi lateral dan longitudinal serebral yang akan
diuraikan kemudian. Karena gejala fungsi luhur ini kerap di-
lupakan atau diabaikan, maka penulis ingin menguraikan secara
singkat peranan fungsi ini, terutama fungsi bahasa, persepsi dan
memori pada kelainan otak. Kelainan otak disini dibatasi pada
penyakit-penyakit yang frekuen, yaitu gangguan peredaran darah
di otak (Cerebro-Vascular Disorder) dan trauma kapitis.
Peranan fungsi luhur dalam klinik
Seperti halnya gejala elementer, maka gejala fungsi Iuhur ini
dapat dipakai untuk menetapkan diagnosis dan rehabilitasi pasien
dengan penyakit otak. Pada kerusakan difus dan berat
dari otak, maka semua fungsi-fungsi luhur tersebut dapat ter-
kena dan hasilnya adalah suatu demensia atau retardasi mental.
Tetapi pada kerusakan yang fokal, maka biasanya hanya satu
atau beberapa dari fungsi ini terganggu. Justru pada kerusakan
otak yang fokal inilah, gejala luhur mempunyai peranan penting.
Pada pasien dengan kelainan tingkah laku, perlu ditentukan
apakah kelainan ini disebabkan oleh kerusakan otak (brain
damage) ataukah sesuatu yang fungsional (kasus psikiatrik).
Penelusuran gangguan fungsi luhur inilah yang dapat membe-
dakan kedua kemungkinan tadi.
Menetapkan gangguan fungsi luhur
Melakukan anamnesis dan pemeriksaan neurologik memer-
lukan waktu yang cukup lama dan kompleks. Apabila di dalam
pemeriksaan itu juga dibebani penetapan fungsi Iuhur secara
rutin, maka waktu pemeriksaan akan bertambah lama lagi.
Untuk menghemat waktu, maka penetapan fungsi luhur secara
artifisial dapat dilakukan bertahap. Tahap awal merupakan
observasi terhadap kemungkinan adanya gangguan fungsi
luhur, yang dilakukan selama pemeriksaan neurologik rutin.
Apabila diduga adanya gangguan fungsi luhur ini, maka pasien
bersangkutan perlu diperiksa lebih teliti secara klinis pada tahap
berikutnya. Selanjutnya pada tahap terakhir dipertimbangkan
untuk suatu penetapan secara formal dengan tes psikometrik.
Tahap terakhir ini melibatkan psikolog yang berwenang
melakukan tes tersebut. Jenis tes akan dipilih yang khusus
dipergunakan untuk menentukan adanya gangguan otak (a.l.
Raven's Progressive Matrices). Khusus untuk gangguan bahasa
perlu dilakukan tes afasia (a.l. Token Test) yang melibatkan ahli
bina wicara. Dokter sebaiknya mengenal penetapan awal dan
klinis gangguan fungsi Iuhur ini, karena dialah yang akan
berhadapan pertama kali dengan pasien-pasien dengan gangguan
tersebut.
Tahap-tahap penetapan fungsi luhur
1. Penetapan awal.
Pada saat membuat anamnesis dan melakukan pemeriksaan
neurologik rutin, sebaiknya menambah anamnesis yang tertuju
untuk mengungkapkan gangguan fungsi luhur. Syarat mutlak
adalah pasien harus kompos mentis.
Pertanyaan-pertanyaan meliputi :
data-data lengkap tentang pribadi pasien termasuk riwayat
dahulu.
mengapa ia dirawat atau datang berobat dan apa sakitnya.
dimana ia sekarang berada dan siapa orang yang ada dide-
katnya serta jam berapa sekarang ini.
dimana ia tinggal, bagaimana ia mencapai tempat ini.
dengan apa dan siapa ia datang kemari.
apa yang ia lakukan selama 24 jam terakhir ini.
Kejadian apa yang diketahuinya atau dibacanya akhir-akhir
ini (peristiwa sekitar rumah, dalam kota, dalam negeri
atau luar negeri).
cobalah pasien disuruh mengurangi angka 100 dengan 7
dan hasilnya dikurangi lagi dengan 7 dan seterusnya.
cobalah suruh pasien mengulangi 6 digit yang kita sebutkan.
cobalah suruh pasien memberi makna sebuah pepatah.
cobalah suruh pasien mengulangi kalimat pendek dan pan-
jang yang kita sebutkan.
cobalah suruh pasien menyebut nama benda yang kita
tunjukkan.
nilailah cara bicara pasien dari segi kecepatan, lagu dan
panjang kalimat.
Sekali lagi, pasien harus sadar, kompos mentis. Kalau ada per-
tanyaan yang kurang benar jawabnya, maka ada alasan untuk
menduga adanya gangguan fungsi luhur.
2. Penetapan klinis.
Akan diuraikan kemudian.
3. Penetapan secara formal dilakukan oleh psikolog.
Sebaiknya diberikan pengarahan tentang apa yang kita kehen-
daki supaya tidak menyulitkan psikolog mencari tes yang tepat.
Penetapan fungsi luhur secara klinis
Dalam menetapkan secara klinis dianut prinsip organisasi
lateral dan longitudinal serebral. Artinya, bagian-bagian otak
tertentu mempunyai fungsi tertentu. Prinsip pusat lokalisasi
fungsi pada otak ini tidak mutlak. Pusat-pusat di otak ini me-
rupakan suatu sistem pusat fungsional yang kompleks (Luria).
Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa me-
nempati hemisfer kiri (disebut hemisfer dominan bagi orang yang
kinan atau right-handed), fungsi persepsi menempati hemisfer
kanan (non-dominan) dan fungsi memori menempati hemisfer
kanan dan kiri, tepatnya di lobus temporalis. Dengan demikian
dikenal sindroma hemisfer kiri dan kanan dengan perincian
sebagai berikut :
Sindroma hemisfer dominan terdiri dari :
1. sindroma afasia (termasuk aleksia dan agrafia)
2. sindroma Gerstmann (right-left confusion, agnosia jari,
agrafia dan akalkulia).
8 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Sindroma hemisfer non-dominan terdiri dari :
1. neglect
2. anosognosia
3. kesukaran visuospatial
4. apraksia konstruksional
5. apraksia berpakaian
Sindroma ini tidak ditulis lengkap, masih ada gejala yang tidak
dicantumkan.
Sindroma lobus temporalis kiri dan kanan terdiri dari gangguan:
1. immediate memory
2. short-term memory
3. long-term memory
Gangguan memori disebut sebagai amnesia; bila mengenai lobus
temporalis kiri menyebabkan gangguan memori verbal dan bila
kanan menyebabkan memori visual.
Sindroma afasia
Secara klinis kita kenal afasia :
1. Broca
2. Wernicke
3. konduksi
4. anomia
5. global
Uraian masing afasia secara singkat ialah sebagai berikut :
Afasia Broca : ciri bicara spontan pasien ialah lambat, ter-
bata-bata, monoton dan kalimat pendek-pendek (disebut non
fluent). Penyimakan bahasa baik, pengulangan kalimat buruk
dan penyebutan nama benda buruk.
Afasia Wernicke : ciri bicara spontan cepat, kadang-kadang
terlalu cepat, lagu kalimat baik, panjang kalimat cukup
(disebut fluent). Penyimakan bahasa buruk, pengulangan
kalimat buruk dan penyebutan nama benda buruk.
Afasia konduksi : ciri bicara fluent, penyimakan dan pe-
nyebutan nama benda baik, hanya pengulangan kalimat
buruk.
Afasia nominal atau anomia : ciri bicara spontan fluent, hanya
penyebutan nama benda yang buruk, yang lain baik. Afasia
global : ciri bicara spontan non-fluent, lain-lain buruk
semua.
Dengan menilai gangguan segi bahasa tersebut, dapat di-
tentukan pasien menderita jenis afasia apa dan dimana letak
lesinya. Broca terletak di bagian anterior, Wernicke di bagian
posterior, konduksi di jaras antara Broca dan Wernicke, global
di seluruh hemisfer kiri dan anomia tidak mempunyai letak lesi
yang tetap.
Sindroma Gerstmann
lalah sekelompok gejala yang terdiri dari agnosia jari (tidak
mengenali jari-jari sendiri dan pemeriksa), right-left dis-
orientation, disgrafia (tidak mampu menulis) dan akalkulia
(tidak mampu berhitung). Sindroma ini disebabkan kerusakan
hemisfer kiri daerah lobus parietalis.
Right-left disorientation ialah ketidak mampuan pasien mem-
bedakan kanan dan kiri dari anggota tubuh sendiri dan dari
ruang sekitarnya. Pasien tidak sanggup menunjuk tangan ka-
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 9
nannya, kaki kirinya, dan juga tidak dapat menunjukkan tangan
yang benar dari pemeriksa bila diminta.
Unilateral Spatial neglect merupakan gangguan persepsi ruang
yang sering mengakibatkan pasien membentur benda yang ber-
ada di sisi kirinya atau pasien tampak mengabaikan benda-benda
yang berada di lapangan pandang kirinya. Kelainan ini dapat
dikenali dengan menyuruh pasien membuat gambar yang
simetris dan ia akan menghilangkan sisi kiri dari gambar tadi.
Misalnya disuruh membuat gambar jam, maka hasilnya ialah
sebuah gambar jam yang angka-angka 8, 9 dan 10 tidak
tergambar.
Anosognosia ialah gangguan persepsi karena kerusakan hemis-
fer non-dominan lobus parietalis. Pasien tidak mempunyai
pandangan dan kesadaran tentang dirinya dan anggota tubuh-
nya. Pasien tidak memberi perhatian pada kelainan tubuhnya,
bahkan sampai menyangkal bahwa anggota tubuhnya lumpuh.
Gangguan visuospatial ialah gangguan utuk menafsirkan posisi,
jarak, gerak, bentuk dan hubungan anggota tubuhnya terhadap
objek sekitarnya. la seakan-akan tidak tahu terhadap konsep
atas-bawah, depan- belakang, dan dalam-luar. Pasien meng-
alami kesukaran bila harus melewati sebuah gang, ia tidak ingat
lagi tata ruang yang pernah dikenalnya, tidak tahu letak kamar
tidurnya, tidak kenal peta rumah tinggalnya. Pasien tidak dapat
menjiplak sebuah gambar bergaris, tidak sanggup menggambar
kubus atau binatang dan tidak dapat menyusun balok-balok yang
diperlihatkan kepadanya. Gangguan orientasi ini disebabkan
kelainan hemisfer non-dominan.
Apraksia konstruksional : ketidak mampuan untuk mencontoh
bentuk- bentuk gambar dan menyusun balok-balok atau batang-
batang korek api menurut contoh yang diberikan. Kemampuan
ini termasuk fungsi kognitif yang kompleks dan diperankan
oleh semua lobi dengan lobus parietalis non-dominan yang
terpenting.
Apraksia berpakaian merupakan gangguan orientasi ruang yang
menyebabkan pasien sukar mengenakan pakaian karena sukar
membedakan bagian mana yang diperuntukkan lengan, tungkai
dan sebagainya.
Amnesia
Gangguan immediate memory mudah dikenali dengan menyu-
ruh pasien mengulangi 6 digit yang kita sebutkan. Gangguan
short-term memory dapat dikenali karena pasien tidak dapat
mengingat apa yang telah terjadi beberapa saat yang lalu. Ia tidak
dapat menceritakan kejadian pada hari itu. Sedangkan long-term
memory terganggu bila pasien tidak lagi mengenali riwayat
hidupnya.
Umumnya amnesia yang terjadi adalah gangguan short-term
memory. Pada kelainan lobus temporalis kiri menyebabkan
gangguan memori verbal (tidak ingat apa yang disebutkan)
sedangkan lobus temporalis kanan menyebabkan memori visual
(apa yang diperlihatkan). Gangguan memori ini merupakan
gangguan yang paling sering dikeluhkan. _
Peranan pada gangguan peredaran darah di otak (cerebro-vas-
cular disorder).
1. Gangguan memori yang disebut sebagai transient global am-
nesia sering menjadi manifestasi dari gangguan peredaran darah
otak jenis transient ischemic attack
'
s (TIA's) . Jenis CVD ini
umumnya dikenal karena adanya gangguan neurologik ele-
menter seperti hemiparesis, hemihipestesia dan sebagainya yang
timbul secara tiba-tiba dan sentara (transient) dan berlangsung
tidak lebih dari 24 jam serta tanpa memberikan gejala sisa.
Serangan sentara ini dapat berulang-ulang. Tidak jarang
serangan ini berupa gangguan bahasa seperti afasia atau
gangguan memori seperti amnesia. TIA'S dengan gejala afasia
mudah dikenali karena gejala yang jelas, tetapi tidak demikian
halnya dengan gangguan memori. Transient global amnesia
sebagai manifestasi TIA's biasanya dikenali dari perubahan
tingkah laku pasien. Pasien tampak seperti bingung-bingung,
banyak bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh dirinya.
Kalau kita agak waspada dan mengajukan pertanyaan pada
pasien akan terungkap bahwa ia tidak ingat apa yang telah
dilakukan beberapa saat yang lalu, tetapi orientasi pasien,
immediate memory dan long-term memory masih baik. Perlu
dibedakan dengan keadaan confuse. Ungkapan adanya TIA's
sangat penting karena merupakan suatu peringatan bahwa suatu
ketika pasien dapat mengalami stroke serebral yang manifes bila
tidak diobati.
2. Sering pula, gangguan bahasa, afasia, merupakan satu-satu-
nya gejala gangguan peredaran darah otak yang menetap (iso-
lated stroke). Pada afasia Broca, gejala tunggal ini mudah dike-
nali, tetapi anomia lebih sulit dikenali sedangkan afasia Wernic-
ke sering sukar dikenali karena pasien dengan bicara spontan
banyak akan disalah tafsirkan sebagai kasus psikiatrik.
3. Walaupun pada gangguan peredaran darah otak terdapat gejala
hemiparesis yang nyata hingga diagnosis mudah ditegakkan,
sebaiknya adanya gangguan bahasa, persepsi dan memori perlu
mendapat perhatian. Hal ini perlu untuk rehabilitasi pasien
selanjutnya terutama pada hemiparesis kiri.
Peranan pada trauma kapitis.
1. Pada keadaan akut trauma kapitis, maka gangguan memori
mempunyai peranan penting. Amnesia post- trauma kapitis dapat
meliputi kejadian sebelum trauma (retrograd amnesia) atau
setelah trauma (anterograd amnesia). Lamanya amnesia tersebut
dapat dipakai sebagai patokan akan luas lesi yang terjadi di otak.
Umumnya amnesia ini meliputi gangguan short-term memory
saja. Apabila ternyata long-term memory juga terkena maka ini
menandakan adanya kelainan otak yang difus, berat dan
mempunyai prognosis yang kurang baik. Juga disini perlu dicatat
bahwa pasien umumnya hanya terganggu memorinya tanpa
kehilangan fungsi-fungsi lain.
2. Pada keadaan lanjut trauma kapitis, dapat dijumpai berbagai
kelainan fungsi luhur, baik sebagai gejala tunggal atau bersama-
sama gejala elementer. Pada keadaan yang pertama kita perlu
waspada karena gejala yang tidak jelas. Sering pasien mengeluh
tentang kurangnya konsentrasi, cepat lupa setelah mengalami
trauma kapitis. Masalah yang juga disebut sebagai sindroma post
- trauma kapitis ini perlu penanganan serius. Perlu dibedakan
antara keadaan pribadi yang neurastenis yang sudah ada
premorbid dengan gejala gangguan persepsi, memori atau bahasa
yang disebabkan trauma. Keadaan akhir
10 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
ini dapat dikenali kalau kita sempat melakukan observasi selama
pasien mengalami trauma. Pada mulanya lebih banyak gejala
yang ditemukan yang lambat laun makin berkurang dan akhirnya
hanya tersisa satu atau dua gejala saja. Selain yang akut, trauma
kapitis menahun juga membawa pengaruh terhadap timbulnya
gangguan luhur ini. Salah satu contoh trauma kapitis menahun
ialah olah raga tinju. Sudah sering diungkapkan bahwa olah raga
ini dapat merusak saraf. Yang dimaksudkan kerusakan saraf ini
ialah gangguan fungsi luhur, bukan gangguan elementer yang
mudah dikenali oleh awam.
Adanya afasia ringan, gangguan persepsi atau memori pada
trauma kapitis akut dan menahun perlu ditelusuri. Penelusuran ini
perlu karena biasanya pasien tidak mengeluh secara jelas. Lagi
pula gejala fungsi luhur post-trauma kapitis ini dapat
menyebabkan masalah dalam hubungan kerja pasien dengan
majikan. Pasien mengeluh tetapi majikan tidak melihat alasan
keluhan tadi. Atau juga bagi dokter yang harus menentukan
apakah pasien dengan trauma kapitis sudah sembuh benar dan
dapat kembali kerja menduduki jabatan semula. Tentu kita harus
berhati-hati kalau
.
berhadapan dengan kasus demikian. Dan yang
terakhir yang akan menyebabkan masalah adalah asuransi
kesehatan.
Rehabilitasi
Disamping rehabilitasi gejala hemiparesis pada CVD, maka
rehabilitasi terhadap gangguan bahasa, persepsi perlu mendapat
perhatian. Terutama hal ini penting bagi pasien dengan
hemiparesis kiri. Sering pasien demikian ini juga menunjukkan
gejala gangguan persepsi-orientasi yang menghambat latihan-
latihan untuk paresisnya. Pasien tidak acuh terhadap tungkainya
yang lumpuh, pasien tidak mengenali posisi tungkainya, pasien
tidak memperhatikan lapangan pandang sisi kirinya, semua ini
menyukarkan fisioterapi. Sebaiknya rehabilitasi juga ditujukan
kepada gangguan persepsi orientasi ini. Demikian pula pada
pasien dengan hemiparesis kanan yang menderita juga afasia.
Latihan fisioterapi perlu disertai latihan bina wicara (speech
therapy).
Latihan afasia berupa bina wicara dapat diberikan oleh
seorang yang profesional dan oleh keluarga yang telah mendapat
petunjuk-petunjuk untuk ini di rumah, karena pasien
membutuhkan latihan terus menerus. Prinsip bina wicara ialah
motivasi, stimulasi dan repetisi. Pasien perlu mendapat motivasi
untuk melatih bicaranya. Jangan dibiarkan menggunakan bahasa
isyarat dalam percakapan sehari-hari, juga di rumahnya.
Keluarga diberi tahukan untuk tidak membiarkan pasien
memakai bahasa isyarat. Pasien harus dipaksakan mengucapkan
kata disamping isyarat yang dipakainya. Terapis akan membuat
program latihan bagi pasien yang disesuaikan dengan latar
belakang pendidikan dan berat-ringan afasinya. Program ini
ditujukan untuk memberikan stimulasi yang kontinu secara
auditif atau tertulis. Pengulangan atau repetisi perlu dilakukan
secara teratur. Stimulasi taktil juga dapat dipakai bila diperlukan.
Pada gangguan anosognosia dimana pasien mengabaikan
anggota tubuhnya yang sakit, maka anggota bersangkutan perlu
dirangsang supaya lambat laun pasien menyadarinya.
Pasien dilatih untuk memandangi anggota yang sakit terse-but
yang sedang digerak-gerakan oleh terapis kesegala arah, juga
arah melewati garis tengah tubuhnya. Selanjutnya pasien
diminta melakukan hal tersebut tanpa bantuan terapis, tetapi
dengan bantuan anggotanya yang tidak sakit. Pasien dilatih
menunjuk benda yang dipegang oleh terapis dan digerak-ge-
rakan kesegala arah termasuk arah melewati garis tengah tu-
buhnya. Pasien diminta berdiri diatas garis lantas menempatkan
kaki-kakinya diatas tempat-tempat yang telah diberi tanda.
Pasien diminta menirukan terapis yang menunjuk-nunjuk
anggota tubuhnya. Kemudian pasien diminta menunjuk atas
perintah terapis.
Pada pasien yang mengalami gangguan visuospatial, dimana
ia mengalami kesukaran menafsir keadaan dirinya terhadap
ruang sekelilingnya, maka tata ruang dimana pasien tinggal
perlu mendapat perhatian. Ruangan sebaiknya tidak terlalu
penuh dengan alat-alat rumah tangga dan benda-benda, cukup
terang, tidak berwarna terlalu menyolok dan tenang. Hal-hal ini
akan membantu pasien dalam kehidupan sehari-hari. Pada
pasien lebih baik diberikan instruksi secara verbal yang jelas
daripada instruksi yang menggunakan isyarat. Cermin yang
besar sangat menolong pasien dalam menafsirkan dirinya ter-
hadap ruang sekitarnya. Latihan-latihan menjiplak gambar-
gambar perlu diberikan.
Pasien dengan gangguan unilateral spatial neglect, yang me-
nyebabkan pasien mengabaikan lapangan pandang sisi kirinya,
perlu dibantu dengan mengatur tata ruangnya secara khusus.
Semua alat mmah tangga dan benda diletakkan ke arah kanan
dari titik pusat aktivitas pasien. Dengan letak khusus ini di-
maksudkan supaya pasien dapat melihat bila ada orang lain yang
sedang bekerja di dalam ruangnya. Juga Ietak TV, meja kursi
perlu diatur demikian. Letak makanan dalam piringnya juga
perlu mendapat perhatian. Latihan memberikan rangsangan
verbal dan taktil perlu diberikan dari arah kiri pasien.
Pasien dengan apraksia konstruksional perlu dilatih menyu-
sun balok atau batang korek api membuat konstruksi 3 dimen-
sional. Mula-mula bentuk sederhana, kemudian makin kom-
pleks.
Latihan-latihan mengenakan pakaian perlu diberikan pada
pasien dengan apraksia berpakaian. Bila perlu diberikan tanda
pada salah satu bagian baju atau celananya untuk dijadikan
patokan bagi pasien dalam mengenakan pakaian tadi. Secara
ringkas dapat disebutkan bahwa rehabilitasi pasien dengan
gangguan bahasa umumnya perlu :
1. menimbulkan motivasi agar pasien mau belajar berbicara lagi,
2. memberikan banyak stimulasi verbal dan tulisan.
3. melakukan repetisi secara kontinu.
Pada rehabilitasi pasien dengan gangguan persepsi perlu :
1. mengatur ruangannya supaya sederhana, tidak semrawut.
2. aktivitas rutin yang di-arahkan pada latihan penguatan
(reinforces learning) dan dilakukan banyak repetisi.
3. stimulasi sensorik yang menimbulkan kesadaran (awa-
reness)
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 11
KEPUSTAKAAN
4.
University Press, 1976.
Luria AR. The Working Brain. London The Penguin Press, 1973.
1. Benson DF. Aphasia, Alexia and Agraphia. New York: Churchill
5. O'Brien MT and Pallett PJ. Total care of the Stroke patient USA:
2.
Livingstone, 1979.
Cummings J, Benson F, and Lovermen S. Reversible Dementia.
6.
Little, Brown and Company (Inc), 1978.
Valenstein E. Making sense of cerebral dominance and syndrome
JAMA. 243, 1980; 2434 - 2439. of the nondominant hemisphere. Geriatrics, Nov. 1976; 111 - 117.
3. Lezak M.D. Neuropsychological Assessment. New York: Oxford
Disfungsi Otak Minor
Kesulitan Belajar Ditinjau Dari Segi Neurologis
dr. Lily Sidiarto
Klinik Gangguan Wicara - Bahasa Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RSCM, Jakarta.
PENDAHULUAN
Di Amerika dilaporkan bahwa lebih kurang 10% dari jumlah
anak usia sekolah mengalami kesulitan belajar (Silver, 1982).
WHO melaporkan 5 - 25% dari anak-anak usia sekolah
menderita disfungsi otak minor. Belum ada data mengenai anak-
anak usia sekolah yang mengalami disfungsi otak minor di
Indonsia, karena sering tidak terdeteksi. Anak-anak dengan
disfungsi otak minor biasanya mengalami kesulitan belajar di
sekolah. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh beberapa hal,
yaitu :
1. retardasi mental
2. gangguan fungsi sistem saraf
3. problema emosional primer
Anak-anak dengan kesulitan belajar karena retardasi mental
lebih mudah dideteksi/dikenal, dan untuk anak-anak ini telah ada
wadahnya yaitu Sekolah Pendidikan Luar Biasa C. Lagi pula
gangguan fungsi sistem sarafnya lebih difus, mencakup hampir
semua fungsi kortikal, sehingga tidak akan disinggung dalam
makalah ini. Problema emosional primer yang merupakan
penyebab lain dari kesulitan belajar merupakan bidang
psikologi/psikiatri. Yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah
anak-anak dengan kesulitan belajar tertentu/spesifik, yang di-
sebabkan karena gangguan pada beberapa fungsi sistem saraf
pusat atau lebih terkenal dengan nama Minimal Brain Dys-
function (M .B .D), atau Disfungsi Otak Minor (D.0.M.). Anak-
anak dengan D.O.M. sering tidak terdiagnosis, sehingga tidak
mendapat penanganan yang semestinya. Ini mengakibatkan
timbulnya problema sosial dan emosional sekunder. Bila hal ini
terjadi, maka akan merupakan problema hidup (life disability),
dimana penanganan akan lebih kompleks.
SINDROMA KLINIS
Disfungsi Otak Minor atau Minimal Brain Dysfunction
(M.B.D) terdiri dari berbagai macam gejala klinis, merupakan
12 Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984
suatu sindroma sehingga lebih tepat bila digunakan nama Mi-
nimal Brain Dysfunction Syndrome atau Sindroma Disfungsi
Otak Minor (S.D.O.M.).
Apakah definisi dari S.D.O.M
Anak-anak dengan S.D.O.M. adalah anak-anak dengan inteli-
gensi mendekati rata-rata, rata-rata (average) atau diatas rata-
rata dengan kesulitan belajar dan perilaku (behaviour) yang
disertai dengan kelainan fungsi sistem saraf.
Gejala klinis
Gejala klinis dapat berupa :
1. Kesulitan belajar yang spesifik (satu atau lebih).
2. Hiperaktivitas dan/atau distraktibilitas dengan short attention
span.
3. Disfungsi motorik.
4. Problema emosional sekunder.
Gejala-gejala tersebut di atas tidak harus ada seluruhnya, dapat
berupa kombinasi dari satu atau lebih gejala tersebut.
Kesulitan belajar yang spesifik
Kesulitan belajar dapat dimanifestasikan dalam gangguan
memproses (processing) masukan sensoris (gangguan persepsi),
gangguan dalam mengintergrasikan masukan tersebut (gang-
guan kognitif), gangguan dalam menyimpan dan mendapatkan
kembali data (gangguan memori), atau gangguan dalam mem-
proses keluaran (gangguan bahasa, gangguan motorik). Beberapa
ahli menekankan pada problema spesifik yang timbul, sehingga
disebut dengan disleksia (kesulitan membaca), disgrafia
(kesulitan menulis), diskalkuli (kesulitan menghitung) dan
disfasia (kesulitan berbahasa).
Hiperaktivitas/hiperkinetik
Hiperaktivitas atau aktivitas motorik yang berlebihan pada
S.D.O.M. bersifat fisiologis. Ini harus dibedakan dari hiper-
aktivitas yang disebabkan oleh keadaan cemas (anxiety). Hi-
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 13
peraktivitas pada S.D.O.M. timbul pada setiap saat dan dimana
saja, tidak tergantung dari tempat dan waktu, sedangkan yang
disebabkan oleh keadaan cemas, hiperaktivitas hanya timbul pada
saat-saat tertentu. Perbedaan ini perlu diketahui oleh seorang
dokter, karena terapi yang diberikan berlainan. Silver
mengemukakan bahwa hiperaktivitas terdapat pada kira-kira 40%
dari kasus dengan S.D.O.M.
Masukan sensoris baik visual maupun auditoris yang masuk
ke korteks tidak dapat disaring, karena untuk proses tersebut
diperlukan perhatian. Anak ini menunjukkan suatu distrakti-
bilitas. Karena perhatian cepat dialihkan pada setiap rangsangan
visual maupun auditoris, maka timbul short attention span.
Disfungsi motorik
Biasanya kelainan yang menonjol dalam bentuk gangguan
motorik halus dan koordinasi. Dalam klinik disamping peme-
riksaan neurologis umum, dilakukan pemeriksaan neurologis
minor.
Problema emosional sekunder
Telah disebutkan di atas bahwa sering kesulitan belajar
spesifik tidak dikenal dan tidak mendapatkan penanganan yang
tepat, sehingga anak-anak ini karena mengalami kegagalan demi
kegagalan menjadi frustrasi. Sehingga stres emosional akan
menjadi suatu kelainan perilaku atau problema watak (character)
. Bila hal ini terjadi, kadang-kadang sukar untuk membedakan
apakah problema emosional ini bersifat primer atau sekunder,
sehingga penanganan kurang memuaskan hasilnya. Lagi pula
anak-anak ini akan mendapatkan kesulitan dalam perkembangan
psikososial selanjutnya. Problema yang dihadapi akan lebih
kompleks, karena problema ini tidak saja melibatkan anak itu
sendiri, tetapi juga keluarganya, sekolahnya dan masyarakat. Hal
ini sudah merupakan suatu sindroma yang multi-dimensional,
dimana banyak pihak yang terlibat dalam penanganannya.
PENYEBAB/ETIOLOGI
- Kelainan genetik.
- Kelainan metabolik.
- Gangguan otak (brain insult) pada masa prenatal dan
perinatal.
- Penyakit dan trauma dari susunan saraf pusat terutama
pada masa krisis dari perkembangan dan maturasi dari
susunan saraf pusat.
TATALAKSANA
Untuk dapat mendiagnosis S.D.O.M., diperlukan data leng-
kap yang mencakup :
RIWAYAT MEDIS
Meliputi riwayat pada masa kehamilan (prenatal), perinatal dan
posnatal terutama 2 tahun pertama.
Aktivitas yang kurang wajar dari sejak bayi : tidak dapat diam
dalam gendongan ibu, berguling-guling dalam box, lari sebelum
berjalan, makan tidak dapat diam di kursi, tidak betah
menonton TV dan sebagainya.
Riwayat perkembangan : Biasanya riwayat perkembangan mo-
torik kasar tidak terlambat, tapi adanya riwayat anak sering
tersandung dan jatuh mengingatkan pada suatu inkoordinasi.
Riwayat motorik halus : kesulitan mengikat tali sepatu, meng-
ancing baju, kesulitan menggunting, melipat dan mewarnai.
Adanya riwayat anak sering "bengong" atau kejang-kejang.
Riwayat keluarga : adanya kasus kesulitan belajar dalam ke-
luarga, hubungan antar keluarga.
PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Sindroma Disfungsi Otak Minor terdiri dari :
1. Pemeriksaan neurologik umum
2. Pemeriksaan daya penglihatan dan pendengaran (sensoric
input)
3. Pemeriksaan jenis hiperaktivitas (fisiologik atau emosional).
4. Pemeriksaan neurologik minor :
a. penetapan dominansi serebral (kecekatan tangan, mata dan
kaki).
b. penetapan fungsi kortikal luhur :
fungsi persepsi-orientasi
fungsi kognitif (abstraksi dan matematik)
fungsi memori
fungsi Wicara-bahasa
c. pemeriksaan koordinasi motorik halus (ketrampilan)
d. pemeriksaan koordinasi motorik kasar (ketangkasan)
PENANGGULANGAN
1. Terapi medikamentosa :
a. untuk hiperaktivitas yang berdasarkan fisiologik dapat
diberikan psikostimulan seperti golongan amfetamin, efedrin
dan sebagainya. Penggunaan dalam jangka waktu lama dapat
menyebabkan kemunduran psikik.
b. pada hiperaktivitas karena keadaan cemas dapat diberikan
anxiolitik. Pemberian obat-obat ini tidak tanpa gejala sam-
ping, hingga dianjurkan pemberian dalam jangka waktu
pendek dan dosis yang tepat.
c. obat golongan cerebro-metabolic-vasodilators dapat diberi-
kan untuk stimulasi metabolisme otak.
2. Remedial teaching programme
Program pendidikan khusus yang diberikan di sekolah dapat
memperbaiki penampilan anak.
3. Untuk membantu anak-anak dengan kesulitan belajar secara
menyeluruh, para profesional perlu mengikut-sertakan orang tua
dalam program pendidikan. Orang tua diberi keterangan
mengenai kelemahan dan kemampuan dari anaknya, serta
bagaimana cara menanganinya guna memperoleh keberhasilan
secara maksimal dan mengurangi kegagalan se-minimal
mungkin.
KESIMPULAN
Setiap anak dengan kesulitan belajar sebaiknya dilakukan
pemeriksaan neurologik untuk mengenali adanya disfungsi
otak minor. Hal ini akan sangat membantu dalam penanggu-
langannya.
KEPUSTAKAAN
1. Peter FE, Romine JS and Dykman RA. A Special
-
Neurological
Examination of Children with Learning Disabilities. Develop Med Child
Neurol 1975;17 : 63 - 78.
2. Pray BS. Learning Principles from Psychoneurology. People With
Special Needs, Down Syndrome Report. Vol 5 No 3, 1983.
3. Touwen BCL and Sporrel T. Soft Signs and MBD. Develop Med Child
Neurol. 1979; 21 : 528 - 529.
4. Wilson EB. Sensory Integrative Therapy for Children With Learning
Disorders. Rehabilitation in Australia. Jan 1975; 27 - 29.
5. Wright FS, Schain RJ, Weinberg WA and Rapin I. Learning disabilitie
and associated conditions. In : The Practice of Pediatric neurology
Edited by Swaiman KF & Wright FS. Saint Louis : The CV Mosby
Company, 1975; pp 883 - 926.
14 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Gangguan Kesadaran
dr. Manthurio dan dr. P Nara
Laboratorium Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin/RSU Ujung Pandang
PENDAHULUAN
Kesadaran merupakan fungsi utama susunan saraf pusat.
Untuk mempertahankan fungsi kesadaranyang baik, perlu suatu
interaksi yang konstan dan efektif antara hemisfer serebri yang
intak dan formasio retikularis di batang otak. Gangguan pada
hemisfer serebri atau formasio retikularis dapat menimbulkan
gangguan kesadaran.
l
Bergantung pada beratnya kerusakan, gangguan kesadaran
dapat berupa apati, delirium, somnolen, sopor atau koma. Koma
sebagai kegawatan maksimal fungsi susunan saraf pusat
memerlukan tindakan yang cepat dan tepat, sebab makin lama
koma berlangsung makin parah keadaan susunan saraf pusat
sehingga kemungkinan makin kecil terjadinya penyembuhan
sempurna.
2
Makalah ini membahas anatomi fisiologi, etiologi, patofi-
sologi, klinik serta penanggulangan gangguan kesadaran.
ANATOMI FISIOLOGI :
Lintasan asendens dalam susunan saraf pusat yang menya-
lurkan impuls sensorik protopatik, propioseptik dan perasa
pancaindra dari perifer ke daerah korteks perseptif primer di-
sebut lintasan asendens spesifik atau lintasan asendens lem-
niskal.
3-5
Ada pula lintasan asendens aspesifik yakni formasio
retikularis di sepanjang batang otak yang menerima dan me-
nyalurkanimpuls dari lintasan spesifikmelalui koleteral ke pusat
kesadaran pada batang otak bagian atas serta meneruskannya ke
nukleus intralaminaris talami yang selanjutnyadisebarkan difus ke
seluruh permukaan otak
4,5
Pada hewan, pusat kesadaran(arousal centre) terletak di rostral
formasio retikularis daerah pons sedangkan pada manusia pusat
kesadaran terdapat didaerah pons, formasio retikularis daerah
mesensefalon dan diensefalon. Lintasan aspesifik ini
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 15
Sub dan
Hip otalamus Pons
Mesensefalon Med. oblong
Sistema aseudens difus aspesifik
Neuron substansia reau-
laris diensefalon, "peng-
galak kewaspadaan".
c
e
m
e
oleh Merruzi dan Magoum disebut diffuse ascending reticular
activating system (ARAS). Melalui lintasan aspesifik ini, suatu
impuls dari perifer akan menimbulkan rangsangan pada seluruh
permukaan korteks serebri.
6
Dengan adanya 2 sistem lrntasan
tersebut terdapatlah penghantaran asendens yang pada pokok-
nya berbeda.
Lintasan spesifik menghantarkan impuls dari satu titik pada
alat reseptor ke satu titik pada korteks perseptif primer.
Sebaliknya lintasan asendens aspesifik menghantarkan se-
tiap impuls dari titik manapun pada tubuh ke seluruh korteks
serebri.
Neuron-neuron di korteks serebri yang digalakkan oleh
impuls asendens aspesifik itu dinamakan neuron pengemban
kewaspadaan, sedangkan yang berasal dari formasio retikularis
dan nuklei intralaminaris talami disebut neuron penggalak
kewaspadaan. Gangguan pada kedua jenis neuron tersebut oleh
sebab apapun akan menimbulkan gangguan kesadaran.
4,5
hipoglikemia, diabetik ketoa-
sidosis, uremia, gangguan he-
par, hipokalsemia, hiponatre-
mia.
penyakit paru berat, kegagalan
jantung berat,
anemia be-
rat.
toksik : keracunan CO, logam berat, obat, alkohol.
B. Menurut mekanisme gangguan serta letak lesi :
- gangguan kesadaran pada lesi supratentorial.
gangguan kesadaran pada lesi infratentorial.
gangguan difus (gangguan metabolik).
Benyamin Chandra
l
menggunakan istilah cemented yang me-
rupakan huruf-huruf pertama penyebab gangguan kesadaran.
=circulation (gangguan sirkulasi darah).
= ensefalomeningitis.
metabolisme (gangguan metabolisme).
elektrolit and endokrin (gangguan elektrolit dan endok-
rin)
neoplasma.
trauma kapitis.
epilepsi
drug intoxication.
16 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
PATOFISIOLOGI
Lesi Supratentorial
Pada lesi supratentorial, gangguan kesadaran akan terjadi
baik oleh kerusakan langsung pada jaringan otak atau akibat
penggeseran dan kompresi pada ARAS karena proses terse-but
maupun oleh gangguan vaskularisasi dan edema yang di-
akibatkannya. Proses ini menjalar secara radial dari lokasi lesi
kemudian ke arah rostro-kaudal sepanjang batang otak.
4
'
6
Gejala-gejala klinik akan timbul sesuai dengan perjalan pro-
ses tersebut yang dimulai dengan gejala-gejala neurologik fokal
sesuai dengan lokasi lesi. Jika keadaan bertambah berat dapat
timbul sindroma diensefalon, sindroma meseisefalon bahkan
sindroma ponto-meduler dan deserebrasi.
2
'
4
'
6
Oleh kenaikan tekanan intrakranial dapat terjadi herniasi
girus singuli di kolong falks serebri, herniasi transtentoril dan
herniasi unkus lobus temporalis melalui insisura tentorii.
4
'
6
Lesi infratentorial
Pada lesi infratentorial, gangguan kesadaran dapat terjadi
karena kerusakan ARAS baik oleh proses intrinsik pada batang
otak maupun oleh proses ekstrinsik.
2
'
6
Gangguan difus (gangguan metabolik)
Pada penyakit metabolik, gangguan neurologik umumnya
bilateral dan hampir selalu simetrik. Selain itu gejala neurolo-
giknya tidak dapat dilokalisir pada suatu susunan anatomik
tertentu pada susunan saraf pusat.
2
Penyebab gangguan kesadaran pada golongan initerutama
akibat kekurangan 0
2
, kekurangan glukosa, gangguan sirkulasi
darah serta pengaruh berbagai macam toksin.
6
Kekurangan 0
2
Otak yang normal memerlukan 3.3 cc 0
2
/100 gr otak/menit
yang disebut Cerebral Metabolic Rate for Oxygen (CMR 02).
CMR 0
2
ini pada berbagai kondisi normal tidak banyak berubah.
Hanya pada kejang-kejang CMR 0
2
meningkat dan jika timbul
gangguan fungsi otak, CMR 0
2
menurun. Pada CMR 0
2
kurang
dari 2.5 cc/100 gram otak/menit akan mulai terjadi gangguan
mental dan umumnya bila kurang dari 2 cc 0
2
/100 gram
otak/menit terjadi koma.
6
Glukosa
Energi otak hanya diperoleh dari glukosa. Tiap 100 gram otak
memerlukan 5.5 mgr glukosa/menit. Menurut Hinwich pada
hipoglikemi, gangguan pertama terjadi pada serebrum dan
kemudian progresif ke batang otak yang letaknya lebih kaudal.
Menurut Arduini hipoglikemi menyebabkan depresi selektif
pada susunan saraf pusat yang dimulai pada formasio reti-
kularis dan kemudian menjalar ke bagian-bagian lain.
6
Pada
hipoglikemi, penurunan atau gangguan kesadaran merupakan
gejala dini.
Gangguan sirkulasi darah
Untuk mencukupi keperluan 0
2
dan glukosa, aliran darah ke
otak memegang peranan penting. Bila aliran darah ke otak
berkurang, 0
2
dan glukosa darah juga akan berkurang.
ETIOLOGI
A. Menurut kausa : 1.
1. Kelainan otak
trauma
gangguan sirkulasi
radang
neoplasma
epilepsi
2. Kelainan sistemik
gangguan metabolis- :
me dan elektrolit
hipoksia
komosio, kontusio, laserasio,
hematoma epidural, hematoma
subdural.
perdarahan intraserebral, in-
fark otak oleh trombosis dan
emboli.
ensefalitis, meningitis.
primer, metastatik.
status epilepsi.
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 17
Toksin
Gangguan kesadaran dapat terjadi oleh toksin yang berasal
dari penyakit metabolik dalam tubuh sendiri atau toksin yang
berasal dari luar/akibat infeksi.
KLINIK
Kesadaran mempunyai 2 aspek yakni derajat kesadaran dan
kualitas kesadaran. Derajat kesadaran atau tinggi rendahnya
kesadaran mencerminkan tingkat kemampuan sadar seseorang
dan merupakan manifestasi aktifitas fungsional ARAS terhadap
stimulus somato-sensorik.
Kualitas kesadaran atau isi kesadaran menunjukkan kemam-
puan dalam mengenal diri sendiri dan sekitarnya yang merupa-
kan fungsi hemisfer serebri.
2
Perbedaan kedua aspek tersebut
sangat penting sebab ada beberapa bentuk gangguan kesadaran
yang derajat kesadarannya tidak terganggu tetapi kualitas
kesadarannya berubah.
3,4,5,7
Dalam klinik dikenal tingkat-tingkat kesadaran : kompos
mentis, inkompos mentis (apati, delir, somnolen, sopor, koma)
Kompos mentis : Keadaan waspada dan terjaga pada seseorang
yang bereaksi sepenuhnya dan adekuat terhadap rangsang vi-
suil, auditorik dan sensorik.
Apati : sikap acuh tak acuh, tidak segera menjawab bila ditanya.
Delir : kesadaran menurun disertai kekacauan mental dan mo-
torik seperti desorientasi, iritatif, salah persepsi terhadap
rangsang sensorik, sering timbul ilusi dan halusinasi.
Somnolen : penderita mudah dibangunkan, dapat lereaksi se-
cara motorik atau verbal yang layak tetapi setelah membe-
rikan respons, ia terlena kembali bila rangsangan dihentikan.
Sopor (stupor) : penderita hanya dapat dibangunkan dalam
waktu singkat oleh rangsang nyeri yang hebat dan berulang-
ulang.
Koma : tidak ada sama sekali jawaban terhadap rangsang nyeri
yang bagaimanapun hebatnya.
PENENTUAN TINGKAT KESADARAN
Batas antara berbagai derajat kesadaran tidak jelas.
Untuk menentukan derajat gangguan kesadaran dapat digunakan:
A. Glasgow Coma Scale = CGS
8
, yang pertama kali diperke-
nalkan oleh Teasdale & Jennet dalam tahun 1974 dan banyak
digunakan dalam klinik.
B. Glasgow Pitsburgh Coma Scale = GPCS (modifikasi CGS)
2
Pada GSC tingkat kesadaran dinilai menurut 3 aspek :
1. kemampuan membuka mata : EY E opening = E
2. aktifitas motorik : MOTOR response =M
3. kemampuan bicara : VERBAL response =V
1. Kemampuan membuka mata
a. dapat membuka mata sendiri secara spontan : 4
b. dapat membuka mata atas perintah : 3
c. dapat membuka mata atas rangsang nyeri : 2
d. tak dapat membuka mata dengan rangsang : 1
nyeri apapun
2. Aktifitas motorik
Dinilai anggota gerak yang memberikan reaksi paling baik
dan tidak dinilai pada anggota gerak dengan fraktur/kelum-
puhan. Biasanya dipilih lengan karena gerakannya lebih
bervariasi daripada tungkai.
a. mengikuti perintah : 6
b. adanya gerakan untuk menyingkirkan rang- : 5
sangan yang diberikan pada beberapa tempat
c. gerakan fleksi cepat disertai dengan abduksi : 4
bahu
d. fleksi lengan disertai aduksi bahu : 3
e. ekstensi lengan disertai aduksi : 2
f. tidak ada gerakan : 1
3. Kemampuan bicara
Menunjukkan fungsi otak dengan integritas yang paling ting-
gi
.
a. orientasi yang baik mengenai tempat, orang : 5
dan waktu
b. dapat diajak bicara tetapi jawaban kacau : 4
c. mengeluarkan kata-kata yang tidak dimenger- : 3
ti
d. tidak mengeluarkan kata, hanya bunyi : 2
e. tidak keluar suara : 1
tgl.
jam
kemampuan membuka mata E
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
aktifitas motorik M
a. 6
b. 5
c. 4
d. 3
e. 2
f. 1
Kemampuan bicara V
a. 5
b. 4
c 3
d. 2
e. 1
-' - ~ i
` J
- --~ ~---
E + M + V = 3 - 15
E + M + V : bergeser antara 3 dan 15. Teasdale & Jennet
menemukan pada 700 kasus trauma kepala skor E+M+V se-
bagai berikut : >9 tidak ada kasus koma, nilai 8 : 58% dengan
koma dan <7 : koma 100%. Penilaian aspek kesadaran
18 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
harus dilakukan tiap hari beberapa jam sekali yang dicatat pada
tabel sehingga memberikan suatu grafik. Keuntungan sistem ini.
7
sangat sederhana dan tidak memerlukan alat khusus.
mudah dikerjakan oleh petugas kesehatan.
derajat dan lamanya kesadaran dapat diukur secara kuan-
titatif.
PEMERIKSAAN KLINIK
Pemeriksaan klinik penting untuk etiologi dan letaknya
proses patologik (hemisfer batang otak atau gangguan siste-
mik). Pemeriksaan sistematis dilakukan sebagai berikut :
Anamnesis
penyakit-penyakit yang diderita sebelumnya.
keluhan penderita sebelum terjadi gangguan kesadaran.
obat-obat diminum sebelumnya.
apakah gangguan kesadaran terjadi mendadak atau perla-
han-lahan.
Pemeriksaan fisik
tanda-tanda vital : nadi, pernapasan, tensi, suhu.
kulit : ikterus, sianosis, luka-luka karena trauma
toraks : paru-paru, jantung.
abdomen dan ekstremitas
Pemeriksaan neurologis' '
3,9
1. OBSERVASI UMUM .
gerakan primitif : gerakan menguap, menelan dan memba-
sahi mulut.
posisi penderita : dekortikasi dan deserebrasi.
2. POLA PERNAPASAN : dapat membantu melokalisasi lesi dan
kadang-kadang menentukan jenis gangguan.
Cheyne-Stokes
Pernapasan makin lama makin dalam kemudian makin dangkal
baik.
Hiperventilasi neurogen sentral
pernapasan cepat dan dalam dengan frekuensi 25 per menit.
Lokasi lesi pada tegmentum batang otak antara mesensefalon
dan pons.
j \ k y i Ai\ ) (
i, ;1111
, , i
I i U ~ i v ~ 4 Y '~~'~rrr~ Ill
Apnestik
inspirasi yang memanjang diikuti apnoe dalam; ekspirasi de-
ngan frekuensi 1 - 2/menit. Pola pernapasan ini dapat diikuti
Klaster ("Cluster breathing")
respirasi yang berkelompok diikuti oleh apnoe. Ditemukan pa-
da lesi pons.
Ataksik
pernapasan tidak teratur, baik dalamnya maupun iramanya. Lesi
di medulla oblongata dan merupakan stadium preterminal.
3. KELAINAN PUPIL : Perlu diperhatikan besarnya pupil (normal,
midriasis, miosis), bentuk pupil (isokor, anisokor), dan refleks.
Midriasis dapat terjadi oleh stimulator simpatik (kokain, efedrin,
adrenalin dan lain-lain), inhibitor parasimpatik (atropin,
skopolamin dan lain-lain).
Miosis dapat terjadi oleh stimulator parasimpatik dan inhibitor
simpatik. Lesi pada mesensefalon menyebabkan dilatasi pupil
yang tidak memberikan reaksi terhadap cahaya. Pupil yang
masih bereaksi menunjukkan bahwa mesensefalon belum rusak.
Pupil yang melebar unilateral dan tidak bereaksi berarti adanya
tekanan pada saraf otak III yang mungkin dapat disebabkan oleh
herniasi tentorial.
4. REFLEKS SEFALIK : Refleks-refleks mempunyai pusat pada
batang otak. Dengan refleks ini dapat diketahui bagian mana
batang otak yang terganggu misalnya refleks pupil (me-
sensefalon), refleks kornea (pons), Doll's head manoeuvre (
pons), refleks okulo-auditorik (pons), refleks okulo-vestibuler =
uji kalori (pons), gag reflex (medulla oblongata).
5. REAKSI TERHADAP RANGSANG NYERI :
Penderita dengan kesadaran menurun dapat memberikan respons
yang dapat dikategorikan sebagai berikut :
a. sesuai (appropriate)
Penderita mengetahui dimana stimulus nyeri dirasakan. Hal
ini menunjukkan utuhnya sistem sensorik dalam arti sistem
asendens spesifik.
b. tidak sesuai (inappropriate)
Dapat terlihat pada jawaban berupa rigiditas dekortikasi dan
rigiditas deserebrasi.
6. FUNGSI TRAKTUS PIRAMIDALIS : Bila terdapat hemiparesis,
dipikirkan ke suatu kerusakan strukturil. Ella traktus piramidalis
tidak terganggu, dipikirkan gangguan metabolisme.
7. PEMERIKSAAN LABORATORIK :
darah : glukose, ureum, kreatinin, elektrolit dan fungsi hepar.
pungsi likuor untuk meningitis dan ensefalitis.
funduskopi mutlak dilakukan pada tiap kasus dengan kesa-
daran menurun untuk melihat adanya edema papil dan tan-
i o t
p i
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 19
da-tanda hipertensi.
dan lain-lain seperti EEG, eko-ensefalografi, CT-scan dila-
kukan bila perlu.
PENANGGULANGAN
Harus dilakukan cepat dan tepat. Gangguan yang berlang-
sung lama dapat menyebabkan kerusakan yang ireversibel
bahkan kematian. Terapi bertujuan mempertahankan homeos-
tasis otak agar fungsi dan kehidupan neuron dapat terjamin.
Terapi umum :
1. resusitasi kardio-pulmonal-serebral meliputi :
a. memperbaiki jalan napas berupa pembersihan jalan
napas, sniffing position, artificial airway, endotracheal
inlubation, tracheotomy.
b. pernapasan buatan dikerjakan setelah jalan napas sudah
bebas berupa :
pernapasan mulut ke mulut/hidung.
pernapasan dengan balon ke masker.
pernapasan dengan mesin pernapasan otomatis.
c. peredarah darah
Bila peredaran darah terhenti, diberikan bantuan sirkulasi
berupa :
kompresi jantung dari luar dengan tangan.
kompresi jantung dari luar dengan alat.
d. obat-obatan
Dalam keadaan darurat dianjurkan pemberian obat secara
intravena, seperti epinefrin, bikarbonas, deksametason,
glukonas kalsikus dan lain-lain.
e. elektrokardiogram dilakukan untuk membuat diagnosis
apakah terhentinya peredaran darah karena asistol, fib-
rilasi ventrikel atau kolaps kardiovaskuler.
f. resusitasi otak tidak banyak berbeda dengan orang dewasa,
bertujuan untuk melindungi otak dari kerusakan lebih
lanjut.
g. intensive care
2. anti konvulsan bila kejang.
Terapi kausal : segera dilakukan setelah diagnosis ditegakkan.
RINGKASAN
Untuk mempertahankan fungsi kesadaran yang baik, perlu
interaksi yang konstan dan efektif antara hemisfer serebri dan
formasio retikularis di batang otak. Penyebab gangguan
kesadaran ialah multi faktorial dengan proses patologis yang
berlokasi supratentorial, infratentorial ataupun difus dalam
susunan saraf pusat.
Pada lesi supratentorial dan infratentorial, gangguan kesa-
daran terjadi karena kerusakan pada
"
ARAS" sedangkan gang-
guan difus oleh kekurangan 0
2
, kekurangan glukosa, gangguan
peredaran darah serta pengaruh toksin.
Kesadaran meliputi dua aspek yakni derajat kesadaran dan
kualitas kesadaran. Tingkat kesadaran dapat berupa kompos
mentis, apati, delir, sopor dan koma.
Untuk menentukan derajat gangguan kesadaran sehari-hari
dalam klinik dapat digunakan Glasgow Coma Scale yang
menilai kesadaran menurut 3 aspek yaitu kemampuan membu-
ka mata, aktifitas motorik dan kemampuan bicara.
Pemeriksaan klinik dan neurologik secara sistematis perlu
untuk dapat mengetahui etiologi dan letaknya proses patologik
penyebab gangguan kesadaran.
Penanggulangan gangguan kesadaran harus dilakukan cepat
dan tepat untuk menghindari terjadinya kematian dan kerusakan
otak yang lebih berat.
KEPUSTAKAAN
1. Chandra B. Diagnostik dan penanggulangan penderita dalam koma
Cermin Dunia Kedokteran, nomor khusus, 1979; 95 - 100.
2. Yusuf Misbach. Penatalaksanaan umum penderita koma. Media
Aesculapius 30 September 1983.
3. Bannister R. Consciousness and Unconciousness. Brain's clinical
Neurology 5
th
ed. Oxford : The English Book Society Oxford
University Press, 1978; pp 150 - 160.
4. Mahar Mardjono dan Priguna Sidharta. Kesadaran dan fungsi luhur.
Neurologi klinis Dasar, cetakan 3 PT Dian Rakyat, Jakarta 1978;
hal. 184 - 200.
5. Priguna Sidharta. Penilaian derajat dan kualitas kesadaran. Tata
Pemeriksaan Dalam Neurologi, cetakan 1 PT Dian Rakyat, Jakarta
1980; bal. 500 - 512.
6. Rizal T. Rumawas. Patologi dan patofisiologi gangguan kesadaran.
Simposium Koma, Jakarta 3 September 1983; hal 1 - 13.
7. Andrari S. Penilaian tingkat gangguan kesadaran dengan Glasgow
Coma Scale Simposium Koma, Jakarta 3 September 1983; hal 71-77.
8. Teasdale G and Jennet B. Assessment of coma and impaired cons-
ciousness Lancet 1974; 2 : 81 - 83.
9. Pedoman Praktis Pemeriksaan Neurologi FK UI. Jakarta 1978; hal. 39
- 40.
10. Kasim YA. Cardio-Pulmonal-Cerebral-Resuscitation pada anak.
Critical Care Pediatrics Berita Klink 1980; 6 : 17 - 41.
11. Lumbantobing SM. Koma. Kedaruratan dan kegawatan medik. FK UI,
Jakarta 1981; hal. 55 - 61.
Beberapa Obat Yang Digunakan Pada
Insufisiensi Serebral dan Demensia
dr. Sardjono O. Santoso dan dr. Santoso Wibowo
Bagian Farmakologi dan Bagian Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
PENDAHULUAN
Otak merupakan organ penting bagi manusia, karena otaklah
yang membedakan manusia dengan mahluk-mahluk Tuhan lain
yang hidup di dunia ini. Meskipun besarnya kalah dibandingkan
dengan otak gajah atau kerbau misalnya, tetapi otak manusia
jauh lebih unggul.
Walaupun ukuran otak relatif kecil dibandingkan dengan
ukuran tubuh manusia secara keseluruhan, otak menerima darah
yang cukup banyak yakni 750 ml per menit atau 15 persen dari
seluruh curah jantung dalam keadaan istirahat. Aliran darah yang
menuju ke jaringan otak adalah 50 - 55 ml per 100 grarn otak per
menit.
l
Jumlah darah yang mengalir ini relatif tidak mengalami
variasi yang begitu besar walau dalam keadaan yang ekstrim
sekalipun. Ini disebabkan terdapatnya mekanisme khusus yang
mengatur tetapnya aliran darah ke otak. Tentu saja terdapat
kekecualian yakni bila terdapat karbondioksida yang berlebihan
dalam otak atau otak mengalami kekurangan oksigen yang berat.
Pada usia lanjut, fungsi-fungsi sentral menurun, sehingga
antara lain terjadi penurunan proses belajar dan berpikir,
aktivitas seksual, kebutuhan tidur, motivasi dan aktivitas pada
umumnya. Dalam proses menua yang berjalan normal, massa
otak pada usia 70 tahun menurun sampai 10 - 15%. Belum jelas
apakah terjadi penurunan jumlah sel atau terjadi suatu
"pengerutan". Pada kira-kira 10% manusia yang berumur 60 - 70
tahun, terjadi penurunan massa otak sampai lebih dari 30% dan
terdapat 3 golongan yaitu :
1. Demensia senilis/presenilis dari type Alzheimer dengan atrofi
primer berupa degenerasi atau penurunan jumlah sel dari
otak besar.
2. Demensia multiinfark dengan kausa vaskuler sebagai akibat
suatu arterioklerosis serebral.
3. Bentuk-bentuk lain terutama karena kausa ekstrakranial.
2
Dengan sendirinya suatu terapi farmakologik hanya bisa
berhasil bila terdapat suatu gangguan fungsional pada SSP.
20 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Perubahan-perubahan fisiologik dan patologik pada proses
menua sangat kompleks, dan bisa menyebabkan gangguan afek-
tif serta intelektual.
ANATOMI - FISIOLOGI ALIRAN DARAH OTAK
Aliran darah yang menuju otak berasal dari dua buah arteri
karotis dan sebagian berasal dari arteri vertebralis. Kedua arteri
vertebralis bergabung membentuk arteri basilaris otak belakang
dan arteri ini berhubungan dengan kedua arteri karotis interna
yang juga berhubungan satu dengan lainnya membentuk suatu
sirkulus Willisi. Dengan demikian terjadilah jalinan kolateral
yang cukup besar pada arteri-arteri besar yang mengurus
jaringan otak. Adanya kolateral yang besar ini, maka pada orang
muda kedua arteri karotis biasanya dapat disumbat tanpa
menimbulkan efek yang merugikan fungsi serebral. Sedangkan
pada orang tua, arteri besar pada dasar otak sering mengalami
sklerosis dan menyumbat arteri karotis, sehingga penyediaan
darah ke otak berkurang sedemikian rupa sampai terjadi
gangguan fungsi serebral.
3
Terdapat beberapa hal yang mengatur aliran darah otak, yakni
1. Pengaturan metabolisme
Bila metabolisme neuronal meningkat, produk CO
2
akan me-
ningkat, sedangkan pH ekstra seluler akan menurun sehingga
terjadi vasodilatasi serebral yang menyebabkan peningkatan
aliran darah.
2. Autoregulasi serebral
Pengaturan ini merupakan kapasitas bawaan pembuluh darah
untuk mempertahankan aliran darah otak. Pembuluh darah otak
menyesuaikan lumennya pada ruang lingkupnya sedemikian
rupa, sehingga aliran darah menetap, walaupun tekanan perfusi
berubah. Pengaturan diameter lumen ini di sebut autoregulasi.
Walaupun teori ini cukup menarik, tetapi terdapat bukti-bukti
yang menunjukkan pengaruh faktor neurogenik pada
autoregulasi ini.
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 21
3. Pengaturan neurogenik
Peran faktor neurogenik telah dibuktikan yakni berupa
pengawasan susunan saraf otonom yang terletak di batang otak
dan diensefalon, serta inervasi alfa dan beta adrenergik dan
kolinergik. Adrenergik alfa bersifat vasokonstriktif, sedangkan
adrenergik beta dan kolinergik mengakibatkan vasodilatasi.
Peningkatan aliran darah hemisferik dapat disebabkan oleh
perangsangan formasio retikularis. Agaknya hal ini diakibatkan
oleh peran faktor neurogenik dan akibat meningkatnya
metabolisme otak.
PATOFISIOLOGI INSUFISIENSI SEREBRAL DAN DEMEN
SIA
Insufisiensi serebral merupakan salah satu jenis penyakit
serebrovaskuler yang banyak dijumpai terutama pada usia lanjut.
Proses patologik yang terjadi yaitu iskemia otak, yakni aliran
darah ke suatu bagian otak berkurang sehingga menimbulkan
manifestasi klinik berupa gangguan fungsi serebral. Tergantung
dari bagian otak yang mengalami iskemia maka gangguan
fungsi serebral dapat berupa : tinitus, vertigo, gangguan berfikir,
dan sebagainya. Terjadinya insufisiensi serebral dan gangguan
metabolisme otak saling berkaitan. Kelainan yang satu dapat
menyebabkan atau memperberat kelainan yang lain. Oleh karena
itu, kadang-kadang obat-obat yang digunakan atau dinyatakan
bermanfaat pada insufisiensi serebral dapat pula digunakan
untuk meningkatkan atau memperbaiki metabolisme otak.
Pada usia lanjut terjadi penurunan katekolamin terutama
fungsi-fungsi dopamin pada berbagai daerah otak, sehingga bisa
terjadi suatu ketidak-seimbangan antara dopamin dan asetikolin
atau lebih baik disebut antara dopamin dan GABA. Dilain fihak
juga terjadi penurunan dari sistem kolinergik yaitu asetilkolin,
asetikolinesterase dan asetilkolinetransferase, dimana antara lain
telah diperiksa bahwa pada usia 50 tahun terjadi penurunan 40 -
60% dari asetilkolintransferase dibanding dengan pada umur 20
tahun.
Pada proses berpikir, maka informasi didapat lalu disimpan
(teoritis disimpan sampai mati), sehingga seharusnya informasi
tersebut setiap waktu dapat dipanggil (diingat) kembali.
Penyimpanan (Storage. ) mula-mula terjadi pada proses
pemikiran jangka pendek (PPJP) (KZG =Kurzzeitgedacht-
nis) yang lamanya beberapa detik sampai menit, mungkin
juga beberapa hari, kemudian disimpan dalam :
Proses Pemikiran Jangka Panjang (PPJPa) (LZG =Lang-
zeitgedachtnis) dimana isi pikiran dikonsolidasi.
Ada pendapat bahwa sebelum PPJP terdapat suatu Fase Inisial
yang pendek dan antara PPJP dan PPJPa juga terdapat suatu
Fase Peralihan. Mekanisme fase pertama (PPJP) agaknya
terjadi dalam neuron-neuron pertama sedangkan pada fase kedua
(PPJPa), terjadi sintesis protein yang diperkuat atau diubah
sebagai akibat suatu peninggian RNA. Yang masih belum jelas
ialah apakah dalam fase kedua (PPJPa) ini :
isi pikiran disimpan di dalam kode/file berupa sekuens asam
amino atau :
apakah karena perubahan morfologik terjadi proses transmisi
pada berbagai sinaps yang lebih efisien.
Adalah suatu kenyataan bahwa tiap-tiap fase proses berpikir
dapat dipengaruhi secara farmakologik.
Beberapa contoh :
Fase Inisial dan mungkin juga PPJP dapat dipengaruhi antara
lain oleh renjatan listrik (Elektroshock) dan Narkosis.
Skopolamin menghambat konsolidasi atau pemindahan isi
pikiran dari PPJP ke PPJPa dan efek ini dapat dihilangkan
dengan Fisostigmin : juga Benzodiazepin agaknya mem-
punyai efek yang sama.
Zat-zat yang dengan suatu cara tertentu mempengaruhi
mekanisme transmisi dalam sinaps terutama bekerja pada
PPJP, tetapi juga ada pengaruh pada PPJPa, sedangkan
zat-zat yang mempengaruhi sintesis protein (seperti Puro-
misin, Sikloheksimid, dan Anisomisin) terutama hanya
mempengaruhi PPJP dalam arti suatu amnesia retrograd.
Efek zat-zat tersebut pada proses berpikir tidak hanya tergantung
dari dosis tapi juga dari waktu kapan diberikan.
Anatomi lokalisasi proses berpikir belum jelas benar tetapi
umumnya dianggap terdapat suatu kerjasama antara diense-
falon, hipokampus dan struktur-struktur fungsi limbik yang lain.
Secara eksperimental zat-zat yang mempengaruhi proses berpikir
dinilai dari kerjanya zat-zat tersebut pada proses belajar.
Idealnya ialah bila bisa dibuktikan bahwa dengan pengaruh
suatu zat terjadi suatu reaksi tertentu yang lebih cepat dengan
kesalahan yang lebih sedikit dan dapat dikerjakan terus menerus
dalam waktu yang lebih lama.
OBAT-OBAT YANG DIGUNAKAN UNTUK GANGGUAN
FUNGSI SEREBRAL
Gangguan fungsi serebral dapat disebabkan oleh berbagai
macam sebab. Obat-obat yang dibicarakan di sini adalah untuk
gangguan fungsi akibat insufisiensi serebral dan menurunnya
metabolisme otak. Manfaat obat-obat ini untuk menanggulangi
gangguan fungsi serebral masih belum mantap, karena data yang
tersedia umumnya pada hewan percobaan sedangkan data uji
klinik pada manusia belum meyakinkan. Selain itu, parameter
perbaikan fungsi serebral sukar diukur dengan pasti dan di-
perlukan waktu yang lama dan dana yang besar untuk menilai
manfaat penggunaan obat-obat ini.
Penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya :
1. Zat-zat dengan kerja utama pada peredaran darah serebral
vasodilator misalnya Naftidrofuril, xantinolnikotinat.
antikoagulan, plasmaekspander, penghambat agregasi.
2. Zat-zat dengan kerja utama pada sel saraf
zat yang mempengaruhi transmisi sinaps misalnya L-DOPA
dan zat-zat sejenis DOPA (lergotril, Amfetamin); Inhibitor
MAO; Fisostigmin.
Psikostimulan dan Analeptik sentral seperti Pemolin, Di-
metilantinoetanol, Fenkamfamin, Meklofenoksat.
zat-zat yang mempengaruhi sintesis protein misalnya asam
orotik.
Lain-lain misalnya Piritinol, Pirasetam, Kavain dan Prokain.
Seringkali terjadi tumpang tindih dalam penggolongan di atas
misalnya Amfetamin yang merupakan zat sejenis DOPA juga
adalah suatu Psikostimulan.
Penggolongan obat berdasarkan struktur kimianya :
Alkaloid misalnya Dihidroergotoksin, Papaverin, derivat-
derivat vitamin.
Xanthin : Pentifilin, Pentoksifilin, Xantinol.
Piperazin : Cinarizin, Flunarizin, Piribedil.
Derivat asam Fenoksiasetat : Fenoksedil, Feksikain, Meklo-
fenoksat.
Feniletanolamin : Isoksuprin, Nilidrin, Oksifedrin, Tinofedrin.
Lain-lain : Bensiklan, Betahistin, Siklandelat, Naftidrofuril,
Pirasetam, Piritinol.
Pada usia lanjut, maka prestasi serebral bisa menurun karena
gangguan peredaran darah dan atau berkurangnya fungsi sel-sel
saraf, sehingga bisa dibenarkan untuk memberikan obat-obat
tersebut di atas. Tidak boleh dilupakan bahwa perbaikan selain
oleh pengaruh obat bisa juga disebabkan oleh efek plasebo dan
perbaikan yang spontan. Walaupun efek zat-zat tersebut masih
sering dianggap kontroversial, akan tetapi pemikiran yang ingin
dicapai antara lain ialah :
perbaikan utilisasi/pemakaian 0
2
dan glukosa oleh SSP
peningkatan resistensi jaringan otak terhadap hipoksia
peningkatan sintesis protein
perbaikan sirkulasi serebral
perbaikan prestasi dalam proses belajar dan berpikir.
Obat-obat ini diindikasikan pada penurunan prestasi serebral
yang disebabkan oleh berbagai kausa baik vaskuler maupun non-
vaskuler.
Obat-obat untuk insufisiensi serebral
Golongan obat ini terutama diindikasikan untuk kelainan
fungsi serebral yang diduga akibat gangguan penyediaan darah,
atau berkurangnya aliran darah ke jaringan otak.
1. Heksobendin
Heksobendin (N, N-bis (3- (3,4,5-trimetoksi)-propil)-etilen--
diamindihidroklorid merupakan vasodilator kuat yang dapat
meningkatkan aliran darah otak (cerebral blood flow) dan pasien
iskemia serebral dan infark, baik pada daerah iskemik maupun
pada daerah yang normal, tanpa adanya efeksteal
4,5
. Aliran darah
otak total dan regional ini diukur dengan metode penyuntikan
Xenon 133 intra karotis.
6
Heksobendin diberikan intravena dan
30 menit kemudian dilakukan pengukuran aliran darah otak.
Selama penyelidikan ini diukur juga tekanan darah sistemik dan
diambil contoh darah arteri dan vena jugularis untuk
pemeriksaan pCO
2
dan pO
2
. Terlihat peningkatan aliran darah
otak sebanyak 15%, dengan penurunan resistensi vaskuler intra
serebral yang menetap untuk 35 menit.
7
Pemberian heksobendin
secara oral juga meningkatkan aliran darah otak.
22 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Infra cerebral steal dapat terjadi pada pemberian CO
2
kon-
sentrasi tinggi, sehingga berdasarkan teori ini dibuatlah postulat
bahwa pengobatan dengan vasodilator tidak efektif bahkan
berbahaya pada pasien dengan infark akut. Tetapi penelitian lain
pada anjing menunjukkan peningkatan aliran darah otak pada
pemberian inhalasi campuran CO
2
5% dalam 0
2
, yakni
konsentrasi yang sama seperti yang dianjurkan pada pemberian
inhalasi intermiten pada manusia.
a
Peningkatan cerebral blood
flow ini terjadi melalui sirkulasi kolateral ke daerah yang
iskemik.
Pemberian heksobendin intravena meningkatkan aliran darah
hemisferik pada daerah infark dengan sedikit atau tanpa
penurunan tekanan darah sistemik.
9
Heksobendin juga tidak
mempengaruhi metabolisme otak.
2. Gabungan heksobendin, etamivan dan etofilin (Instenon)
Etamivan merupakan perangsang susunan saraf pusat, yang
tempat kerjanya diduga di substansia retikularis pada pusat
pernafasan dan sirkulasi. Pemberian etamivan saja ternyata
tidak memberikan perubahan yang berarti pada aliran darah.
6
Etifilin meningkatkan aliran darah koroner, mempunyai efek
inotropik positif terhadap jantung serta mempunyai efek diuretik
yang mengurangi edema serebri serta memperbaiki metabolisme
jaringan otak. Etofilin meningkatkan aliran darah pada daerah
iskemik, sedangkan pada daerah normal perubahan hanya
sedikit atau hampir tidak ada.
6
Gabungan dari ke tiga preparat ini rupa-rupanya mempunyai
efek sinergistik yakni meningkatnya aliran darah otak secara
nyata. Penggunaan baik heksobendin maupun gabungan tiga
preparat ini cukup popular di Eropa, tetapi di Amerika Serikat
penggunaannya masih terbatas pada keperluan penelitian.
5,9
Di
Indonesia penggunaan obat ini masih dalam taraf permulaan dan
belum pernah ada uji klinik atau publikasi mengenai
penggunaan obat ini.
3. Bensiklan
Obat ini merupakan suatu sikloalkano eter yang menyebab-
kan vasodilatasi dengan jalan relaksasi otot-otot pembuluh da-
rah tanpa adanya perubahan pada transmitor adrenergik di
daerah inervasi adrenergik. Dengan demikian maka terjadi
vasodilatasi yang lebih banyak pada jaringan kolateral yang
tadinya tidak berfungsi disekitar daerah yang iskemik, dan alir-
an darah mikrosirkuler juga meningkat. Oleh karena terjadi
peningkatan aliran darah di daerah iskemik yang lebih besar
(40%) daripada di daerah lain (20%) maka tidak terjadi suatu
steal syndrome.
Obat ini meninggikan jumlah glukosa di otak, menimbulkan
toleransi pada keadaan anoksia serta meningkatkan akumulasi
glukosa dan kinin. Dengan demikian metabolisme otak disti-
mulasi, dan terjadi suatu perubahan mekanisme transpor glu-
kosa dan substrat yang lain pada sawar darah otak dengan jalan
meningkatkan permeabilitas sawar darah otak.
l0
Selain itu
terjadi pengurangan tendensi aglutinasi platelet. Sesuai dengan
cara kerjanya, maka obat ini terutama bermanfaat bila terdapat
suatu insufisiensi sirkulasi otak. Dengan dosis 300-600 mg/hari
selama 8 minggu, terlihat perbaikan dalam kriteria obyektif
maupun subyektif pada gangguan sirkulasi serebral
11
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 23
4. Co-dergokrin mesilat
Obat ini terdiri dari dihidroergokornin mesilat, dihidroergo-
kristin mesilat dan dihidroergokriptin mesilat dalam jumlah yang
sama banyaknya.
Khasiat campuran komponen-komponen ini antara lain adalah :
reaktivasi neurotransmisi sentral dengan cara yang menye-
rupai dopamin dan serotonin, yaitu stimulasi reseptor-reseptor
post sinaptik
menggantikan sebagian dari defisiensi neurotransmitor akibat
proses menua dan menggunakannya secara lebih efisein
sebagai suatu agonis dopamin dan serotonin maka obat ini
memulihkan fungsi serebral sehingga diharapkan terjadi
kemajuan-kemajuan gejala demensia.
Obat ini meningkatkan aliran darah serebral (CBF) dan kon-
sumsi oksigen, juga terjadi aktivasi suksinik oksidase (MAO),
dan melakukan inhibisi ATP-ase, adenil siklase dan fosfodies-
terase sehingga mengkonservasi konsumsi ATP.
12
Dosis yang
dianjurkan adalah 3 - 6 mg/hari dan perbaikan gejala diharapkan
dalam 3 - 4 minggu, sehingga dianjurkan pemakaian dalam
jangka waktu lama.
5. Pentoksifilin
Obat ini merupakan suatu derivat Xantin yang mempunyai
mekanisme sebagai berikut :
menghambat agregasi platelet dan eritrosit, memperbaiki
deformabilitas eritrosit serta mengurangi viskositas darah,
sehingga terjadi peningkatan aliran darah otak
memperbaiki utilisasi Oksigen dan glukosa otak memperbaiki
permeabilitas dinding sel serta fungsi sel otak sehingga
edema serebri berkurang.
13
Dari mekanisme kerja obat ini maka dapat dimengerti bahwa
obat ini terutama diindikasikan pada keadaan-keadaan di mana
terdapat insufisiensi aliran darah otak. Dosis yang dianjurkan
berkisar antara 300 - 1200 mg/hari selama 8 minggu.
13-15
Obat-obat yang meningkatkan atau memperbaiki metabolis-
me otak
Golongan obat ini diindikasikan untuk kelainan fungsi se-
rebral yang terutama diduga akibat menurun atau terganggunya
metabolisme otak.
1. Pirasetam
Obat ini adalah suatu derivat siklik gamma amino-butyric
acid (GABA), tetapi tidak mempunyai sifat-sifat GABA.
16
Obat
ini disebut suatu Nootropik yang berarti :
a. tidak mempunyai vasoaktivitas yang langsung, yakni tidak
menyebabkan vasodilatasi atau vasokonstriksi, tidak mem-
pengaruhi aliran darah serebral total (total CBF) dan tidak
menyebabkan suatu steal phenomenon.
b. tidak menyebabkan perubahan pada aktivitas dasar EEG. Obat
ini tidak mengubah ritme dasar EEG, tetapi menurunkan
jumlah gelombang-gelombang delta.
c. melewati sawar darah otak (blood brain barrier) dalam ke-
adaan normal maupun patologik
d. mempunyai efek samping yang minimal
e. tidak mempengaruhi sistem kardiovaskuler maupun per-
napasan.
12
Mekanisme kerja obat ini adalah sebagai berikut :
aktivasi metabolik peredaran darah otak
meningkatkan kecepatan metabolik serebral oksigen dan
glukosa regional
menormalkan aliran darah ke daerah iskemik, bukan dengan
suatu aktivitas langsung tetapi sekunder
menurunkan rasio laktat/piruvat
Dosis yang dianjurkan ialah 2,4 - 4,8 g/hari, selama 6 - 12
minggu.
16-18
Status obat ini masih dimintakan persetujuan kepada
FDA (Food Drug Administration).
2. Piritinol
Suatu derivat B
6
(piridoksin), yang termasuk juga golongan
Nootropik, menyebabkan peningkatan aliran darah otak secara
selektif terutama ke substansia grisea. Pada penyelidikan
ditemukan peningkatan aliran darah sebanyak 12% ke substan-
sia grisea dan 4% ke substansia alba di daerah-daerah yang
mempunyai sirkulasi patologik. Peningkatan aliran darah ini
merupakan akibat sekunder dari peningkatan metabolisme.
19
Dengan pemberian obat ini, konsumsi glukosa oleh otak dinor-
malkan kembali.
20
Piritinol juga menurunkan permeabilitas sawar
darah otak terhadap fosfat, menurunkan kadar GABA dan
GABA-transaminase dan meningkatkan RNA residual dan RNA
ribosomal.
12
Aktivasi umum yang disebabkan obat ini
diperkirakan karena pengaruhnya terhadap membran fosfolipid
eritrosit, di tempat mana terjadi peningkatan pengaturan molekul-
molekul pada lapisan ganda fosfolipid.
21
Dosis yang dianjurkan ialah 600 - 800 mg/hari dan efeknya
baru terlihat setelah 3 minggu dan jelas bermakna terhadap
plasebo setelah 6 - 9 minggu.
22
Beberapa penyelidik menge-
mukakan, bahwa dengan dosis 600 mg/hari atau lebih selama 2 -
4 bulan jelas memberikan hasil yang lebih baik daripada dengan
dosis rendah atau plasebo pada organic brain syndrome
termasuk demensia.
22-24
Manfaat obat ini terutama pada pasien
dengan gangguan serebral yang berhubungan dengan gangguan
metabolisme glukosa.
25
Walaupun demikian perlu dilakukan
penelitian uji klinik yang lebih luas dengan rancangan yang lebih
baik untuk memastikan manfaat obat ini.
KESIMPULAN
Telah dibicarakan beberapa obat yang lazim dipakai pada
kelainan insufisiensi serebral dan demensia. Walaupun efek obat-
obat tersebut masih sering dianggap kontroversial dan perlu
diadakan penelitian uji klinik yang luas dengan rancangan
penelitian yang mantap untuk dapat menilai manfaat obat-obat
ini secara tuntas, namun agaknya persoalannya mempunyai titik
awal pada penentuan jenis kausanya terlebih dulu.
Dengan mengingat penggolongan obat berdasarkan cara
kerjanya, maka obat-obat yang kerja utamanya pada sel saraf
atau meningkatkan metabolisme sel-sel saraf dapat diberikan
pada keadaan-keadaan degeneratif. Sedangkan obat-obat yang
kerja utamanya pada peredaran darah serebral, dapat di berikan
pada keadaan insufisiensi serebral. Disamping itu perlu
diperhatikan pengobatan penyakit yang mendasari kelainan
serebral yang merupakan kausa ekstrakranial.
Dengan demikian maka terapi farmakologik diharapkan da-
pat memberikan manfaat yang optimal.
KEPUSTAKAAN
1. Guyton AC. Blood flow through special areas of the body. Text book
of medical Physiology, 4th. edition, WB Saunders Co, 1971; p.
367.
2. Stumpf C. Pharmaka and Mirnleistung, in Neuropharmakologie,
Springer Verlag, Wien New York, 1983; pp 157 - 163.
3. Rasyad RS. Efek gabungan Hexobendin, Etamivan dan Etofilin pada
penderita CVD, makalah Joint-session Neuropharmacology,
Agustus, 1982.
4. Marshall J. The management of cerebrovascular disease, 3rd ed.
Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1976; 1 - 60.
5. Meyer JS. Modern concepts of cerebrovascular disease, Spectrum
publications, New York, 1975.
6. Meiss, WD. Drug effects on regional cerebral blood flow in focal
cerebrovascular disease, Journal of the Neurological Science, 1973,
19 : 461 - 482.
7. Meyer JS et al. Effects of hexobendine on cerebral hemispheric
blood flow and metabolism. Neurology 1971; 121. 7 : 691 - 702.
8. Kraupp D et al. The effect of Hexobendine on cerebral blood flow
and metabolism, Arzneim-Forsch, 1969; 19 : 1691 - 1698.
9. McHenry L et al. Regional cerebral blood flow and cardiovascular
effect of hexobendine in stroke patiens, Neurology, vol. 22, 1972;
3 : 2 1 3 : 2 1 7 - 2 2 3 .
10. Hapke HJ. The effect of Fludilat on the Blood Brain Barrier, The-
rapie Woche, English Edition 24. Nr 25, 17; 1974.
11. Bartles H & Schneider B. Investigation of the pharmacodynamic
action of Fludilat in the
.
treatment of cerebrovascular insuffi-
ciency, Med. Welt 1978; 29 : 1056 - 1060.
12. Skondia V. Criteria for Clinical Development and Classification of
Nootropic Drugs. International Symposium on Nootropic Drugs,
Rio de Janeiro, 1979; pp 7 - 20.
13. Muller R & Lehrach F. Haemorheology and Cerebrovascular Di-
sease : Multifunctional approach with Pentoxifylline, Curr Med
Res Opin Vol 7 : No. 4, 1981.
14. Buckert D & Harwart D. Trials of BL 191 in double blind test, II
Farmaco, 1976;5, 31.
15. Takamatsu S, Sato K, Takamatsu M, Sakuta S & Mizuno S. Cha-
nges in haematological and blood chemical parameters after treat-
ment of aged arteriosclerotic patients with Pentoxifylline, Phar-
matherapeutica, Vol. 2, No. 3, 1979.
16. Chouinard G, Annable L, Olivier M, Fontaine F & Ross Chouinard
A. Psychotropic and Neurophysiologic effects of Piracetam in
Geratric Psychiatr Patients. a controlled study. preliminary report.
International Symposium on Nootropic Drugs, Rio de Janeiro,
1979; pp 23 - 30.
17. Castellanos V & Suarez MV. The use of Piracetam in the Psycho-
Organic Syndrome of Senility. International Symposium on
Nootropic Drugs, Rio de Janeiro, 1979; pp 49 - 60.
18. Mendivil MAC. Clinical work in Patients with a Psyeho-Organic
Syndrome of Senility using the Drug Piracetam. International
Symposium on Nootropic Drugs, Rio de Janeiro, 1979; pp 31 - 48.
19. Herrschaft H. Die Wirkung von Pyritinol ouf die Gehirndurchblu-
tung des Menschen,.Munchen Medizinische Wochenschrift, 60,
1978.
20. Becker K & Hoyer S. Hirnstoffwechseluntersuchungen unter der
Behandlung mit Pyrithioxin, Deutsche Zeitschrift fur Nervenheil-
kunde, p1966; pp 188 - 200.
21. Martin KJ. On the Mechanism of Action of Encephabol, J. int. Med.
Res, Vol. 2. no. 2, 1983.
22. Hamouz W. The use of Pyritinol in patients with moderate to se-
vere organic psychosyndrome, Pharmatherapeutica, Vol. 1 No. 6,
1977.
23. Cooper AJ & Magnus RV. A placebo-controlled study of Pyritinol
in Dementia, Pharmatherapeutica, Vol 2, No. 5, 1980.
24. Glatzel J. Dose-Effect Relationship of Drally Administered Pyriti-
nol in the Chronic Brain Syndrome, Med. Klinik, 1978; 73. 1117-
1121.
25. Hoyer S, Oesterreich K & Stoll KD. Effects of Pyritinol HCL on
blood flow and oxidative metabolism of the brain in patients with
Dementia, Arzneim Forsch 1977; 27, 671.
26. Kohimeyer K. The effect of Bencyclane on the General and Re-
gional Blood supply of the brain. Investigation with the Xenon 133
clearance method. Herz/Kreislauf 4. Nr. 5, 1972; 196 - 203.
9A RAH
24 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 25
Penanggulangan Bencana
Peredaran Darah di Otak
Dr. Sahala Mari ngan Lumban Tobi ng
Bagian Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RSCM, Jakarta
PENDAHULUAN
Bencana peredaran darah di otak (BPDD) sering dikenal
dengan kata stroke atau cerebrovascular accident, merupakan
penyebab invaliditas yang paling sering pada golongan umur di
atas 45 tahun Di negara industri BPDD merupakan penyebab
kematian nomor tiga setelah penyakit jantung dan keganasan
Otak merupakan organ yang membutuhkan banyak oksigen
dan glukosa Zat ini diperolehnya dari darah. Di otak hampir
tidak ada cadangan oksigen, sehingga jaringan otak sangat
bergantung kepada keadaan aliran darah setiap saat. Beberapa
detik saja aliran darah terhenti maka fungsi otak akan ter-
ganggu; bila aliran darah kesuatu daerah otak terhenti selama
kira-kira 3 menit maka jaringan otak akan mati (infark). Gang-
guan aliran darah di otak dapat diakibatkan oleh gangguan di
pembuluh darah darah atau jantung atau gabungan ketiga faktor
tersebut Adanya BPDD dapat dengan mudah diketahui, yaitu
dari terjadinya defisit neurologik yang timbul secara mendadak
misalnya lumpuh sebelah badan mendadak.
Kita mengenal dua jenis stroke, yaitu :
Stroke non-hemoragik
Stroke hemoragik
"Stroke" non-hemoragik
Didapatkan penurunan aliran darah sampai di bawah titik kri-
tis, sehingga terjadi gangguan fungsi pada sebagian jaringan
otak Bila hal ini lebih berat dan berlangsung lebih lama dapat
terjadi infark dan kematian. Berkurangnya aliran darah ke otak
dapat disebabkan oleh berbagai hal : misalnya trombus, emboli
yang menyumbat salah satu pembuluh darah, atau gagalnya
pengaliran darah oleh sebab lain, misalnya kelainan jantung
(fibrilasi, asistol).
Stroke non-hemoragik lebih sering dijumpai daripada yang
hemoragik. Diagnosis mudah ditegakkan, yaitu timbulnya defi-
sit neurologik secara mendadak (misalnya hemiparesis), dan
kesadaran penderita umumnya tidak menurun.
Pada stroke yang ringan, iskemia berlangsung singkat, defisit
neurologik dapat pulih sempurna. Bila pemulihan sempurna ini
terjadi dalam jangka waktu 24 jam, ia dinamakan "serangan
iskemia sepintas
"
(transient ischemic attack atau disingkat TIA).
Bila pulih sempurna terjadi setelah waktu 24 jam, disebut defisit
neurologik iskemia yang reversibel (reversible ischemic
neurologic deficit atau disingkat RIND).
Pada iskemia yang lebih berat atau berlangsung lama, terjadi
defisit neurologik yang irreversibel, yang menetap, dan
merupakan cacad.
'Stroke" hemoragik
Stroke hemoragik terjadi karena salah satu pembuluh darah di
otak (aneurisma, mikroaneurisma, kelainan pembuluh darah
kongenital) pecah atau robek. Keadaan penderita stroke
hemoragik umumnya lebih parah. Kesadaran umumnya menurun.
Mereka berada dalam keadaan somnolen, sopor atau koma pada
fase akut.
PENANGGULANGAN "STROKE"
Perawatan umum
Memonitor, dan bila perlu memperbaiki fungsi pernafasan,
tekanan darah dan jantung.
Mengusahakan keadaan metabolisme yang optimal, mem-
perhatikan kebutuhan akan : cairan, kalori dan elektrolit.
Memperhatikan fungsi miksi dan defekasi.
Mencegah terjadinya dekubitus, pneumonia ortostatik.
Mendeteksi dan bila perlu mengobati faktor risiko :
Hipertensi
diabetes mellitus
kelainan jantung
hiperlipidemia, hiperkolesterolemia
obesitas
berhenti merokok
Memberikan pengobatan atau tindakan khusus.
antiedema
antiagregasi, antikoagulasi
antifibrinolisis
meningkatkan aliran darah dan metabolisme otak.
Tindakan bedah
Mengeluarkan hematoma (bila perlu)
Melakukan EC-IC shunt.
Melakukan rehabilitasi.
Mencegah berulangnya stroke.
Hipertensi
Sebagian terbesar penderita stroke adalah penderita hiper-
tensi. Hipertensi adalah faktor risiko yang paling "kuat" bagi
terjadinya stroke. Bila hipertensi diobati secara adekuat, maka
jumlah penderita stroke dapat dikurangi. Pada fase akut kita
harus hati-hati menurunkan tensi. Oleh karena keadaan iskemia,
maka fungsi autoregulasi menjadi terganggu. Aliran darah di
otak bergantung kepada tekanan perfusi (tekanan darah sistemik
- tekanan venous).
Bila tekanan diastole pada fase akut tidak melebihi 115 mm Hg
tidak diberikan obat anti-hipertensi. Bila memberikan obat anti-
hipertensi pada fase akut, harus dijaga agar turunnya tensi tidak
terlalu banyak, cukup bila sudah mencapai 160/110 mm Hg. Bila
fase akut sudah berlalu, maka pengobatan hipertensi adalah
sebagai biasanya.
Obat antiedema
Edema di otak dapat mengakibatkan terganggunya aliran darah
otak, terutama "mikrosirkulasi", dan dapat pula mengakibatkan
herniasi jaringan otak yang berakibat fatal.
Deksametason : Steroid adalah obat anti-inflamasi yang ampuh,
yang juga dapat mengurangi sembab-otak, mungkin melalui
pen-stabilan membran sel dan menncegah terjadinya edema intra
dan ekstraselular. Deksametason merupakan steroid yang paling
sering digunakan sebagai antiedema otak. Walaupun khasiatnya
sudah dapat dibuktikan dalam mengobati edema otak pada
keganasan (neoplasma) di otak, namun khasiatnya dalam
mengobati edema oleh infark dan hemoragi di otak masih
kontroversial.
Deksametason dapat diberikan dalam dosis permulaan 10 mg
intravena atau intramuskular, kemudian diikuti oleh 5 mg tiap 6
jam sampai selama satu minggu dan kemudian dihentikan
secara bertahap (tapering off).
Efek samping steroid cukup banyak, kita harus mempertim-
bangkan untung-ruginya pada tiap kasus. Bila terdapat riwayat
tukak lambung sebaiknya tidak diberikan !
Gliserol : Larutan hiperosmolar ini dapat menarik air dari otak,
dengan demikian mengurangi edema otak. Dosis yang di-
anjurkan per infus ialah larutan 10% diberikan sebanyak 24-30
tetes per menit, sampai jumlah 1 gram gliserol/kg berat ba-
dan/hari; Di klinik kami, untuk orang dewasa kami berikan 1
kolf 500 ml larutan 10% gliserol sehari yang diberikan dalam
waktu kira-kira 6 jam (28 tetes/menit). Gliserol dapat pula
diberikan per oral, dengan dosis 1,5 gram/kg berat badan sehari,
dibagi dalam 4 kali pemberian. Laporan mengenai hasil
pengobatan dengan gliserol masih kontroversial.
26 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Obat anti-agregasi trombosit
Trombosit mempunyai kemampuan untuk beragregasi dan dapat
membentuk trombus atau tromboemboli. Diduga bahwa
tromboemboli mempunyai peranan pada banyak kasus stroke.
Untuk mencegah hal ini digunakan obat-obat anti-agregasi.
Telah banyak dilakukan penyelidikan mengenai khasiat obat anti
-agregasi untuk mencegah berulangnya stroke pada penderita
TIA (transient ischemic attack) atau stroke ringan. Banyak
laporan yang mengemukakan bahwa obat anti-agregasi seperti
asetosal dapat mengurangi kambuhnya stroke pada penderita
stroke ringan. Obat anti-agregasi yang dapat digunakan ialah :
asetosal, dipiridamol, sulfinpirazon, pentoksifilin. Obat yang
paling banyak diselidiki ialah asetosal. Dosis yang digunakan
bermacam-macam, ada yang melakukan penyelidikan dengan
dosis 2 x 650 mg sehari, ada dengan 2 x 500 mg sehari; 500 mg
sehari 10 mg/kg berat badan sehari.
1
Bahkan ada yang
melaporkan bahwa Asetosal dengan dosis rendah mempunyai
manfaat, yaitu 40 mg sehari.
2
Lamanya pengobatan berkisar
antara 2 sampai 5 tahun. Obat lainnya, yaitu dipiridamol,
sulfinpirazon dan pentoksifilin masih kurang banyak diselidiki.
Masih ditunggu hasil penyelidikan yang lebih luas. Hasil
sementara melaporkan bahwa dipiridamol dan sulfinpi razone
bila diberikan tersendiri tidak mempunyai khasiat, tetapi bila
diberi bersama sama asetosal ada khasiatnya.
3
Obat antifibrinolisis
Beberapa penyelidikan telah dilakukan guna menilai manfaat
obat antifibrinolisis dalam mencegah perdarahan-ulang pada
penderita perdarahan subaraknoid. Hasilnya masih kontrover-
sial. Obat yang digunakan ialah asam aminokaproat dan asam
traneksamat.
Meningkatkan aliran darah dan metabolisme otak
Manfaat vasodilatansia dalam meningkatkan aliran darah di
daerah iskemia belum dapat dibuktikan. Vasodilatansia yang
pernah digunakan ialah : dioksida karbon, papaverin, hekso-
bendin, betahistin dihidroergonovin, nilidrin, siklandelat.
Pemberian oksigen juga tidak berguna, kecuali bila kadar ok-
sigen arterial memang menurun. Vasopressor pernah dicoba
untuk meningkatkan aliran darah ke daerah iskemia. Landasan
teoritiknya ialah : autoregulasi di daerah iskemik terganggu,
dengan demikian aliran darah bergantung kepada tekanan per-
fusi, yaitu tekanan darah iskemia - tekanan vena. Meningkatkan
tekanan darah akan meningkatkan tekanan perfusi. Penyelidikan
mengenai hal ini belum cukup dilakukan, namun ada laporan
yang mengemukakan hasil baik. hiperventilasi untuk
mengurangi PaCO
2
tidak bermanfaat dalam pengobatan stroke.
PENUTUP
Stroke atau bencana peredaran darah di otak dapat didefinisikan
sebagai gangguan yang mendadak daripada suplai darah di otak,
atau perdarahan setempat di otak. Walaupun didapatkan
kemajuan yang pesat dalam bidang diagnostik serta pemahaman
patofisiologi daripada stroke, namun dalam bi-
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 27
dang pengobatan kemajuan sangat lambat. Bila stroke sudah
terjadi infark atau perdarahan otak sudah terjadi maka penga-
ruh pengobatan tidak banyak artinya. Oleh karena itu tujuan
utama ialah pencegahan. Saat ini telah diketahui beberapa
faktor yang menyebabkan seseorang lebih rentan terhadap
stroke. Bila faktor risiko ini ditanggulangi dengan baik. ke-
mungkinan mendapatkan stroke dapat dikurangi.
KEPUSTAKAAN
1. Bousser MG Eschwege E, Haguenau M, Lefaucconnier, Thibult N,
Toubould D, Touboul PJ. "AICLA" controlled trial of aspirin and
dipyridamole in the secondary prevention of atherothrombotic ce-
rebral ischemia. Stroke 1983; 14: 5 - 14.
2. Weksler BB, Scherer P, Kent J, Rudolph D. Low dose aspirin effec-
tively inhibits platelet function in patients with recent cerebral is-
chemia. Stroke 1984; 15 : 183.
3. Yatsu FM. Acute medical therapy of strokes. Stroke 1982; 13 : 524-
526.
Peranan Radiologik Pada Kelainan Otak
dr. Susworo
Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RSCM, Jakarta
PENDAHULUAN
Pemeriksaan radiologi pada kelainan otak dapat dibagi atas :
1. Konvensional
tanpa kontras (foto polos)
dengan kontras (positif atau negatif)
2. Radioisotop
3. CT scanning
Indikasi paling sering untuk melakukan pemeriksaan-peme-
riksaan ini adalah kelainan karena trauma dan tumor (proses
desak ruang). Dalam jumlah kecil dilakukan pada kelainan-ke-
lainan bawaan serta degeneratif. Kelainan akibat infeksi, se-
kalipun sering ditemukan di Indonesia jarang dilakukan peme-
riksaan radiologik karena kurangnya manifestasi langsung yang
dapat dilihat.
A. FOTO POLOS
Perubahan-perubahan yang tampak pada gambaran radiologik
adalah merupakan akibat dari peninggian tekanan intrakranial.
Keadaan ini telah diketahui sejak tahun tiga puluhan oleh
Schuller, dan makin lama makin banyak fakta-fakta yang
terungkap pada kelainan tersebut. Sepertiga dari penderita-
penderita dengan tanda-tanda peninggian tekanan intrakranial,
baik itu disebabkan tumor, abses atau hidrosefalus, pada orang
dewasa atau kanak-kanak, akan menunjukkan tanda-tanda
tersebut pada foto polos kepala. Sedangkan pada 20% penderita
yang dengan pemeriksaan radiologik menunjukkan tanda-tanda
kenaikan tekanan intrakranial, pada pemeriksaan klinis belum
didapatkan adanya edema papil.
TANDA-TANDA RADIOLOGIK
Pada foto polos kepala kelainan intrakranial dapat menim-
bulkan perubahan yang sifatnya umum atau lokal.
28 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Perubahan umum
1. Peninggian tekanan intrakranial.
a. Terjadi pelebaran dari ukuran sela tursika (ballooning).
b. Pelebaran dari sutura.
c. Ekspansi dari rongga tengkorak.
d. Penipisan tulang batok kepala.
e. Pelebaran dari foramina.
2. Atrofi atau perkembangan jaringan otak yang terhambat.
a. Penebalan tulang batok kepala.
b. Rongga tengkorak yang kecil dengan kompensasi per-
tumbuhan struktur organ-organ didalamnya.
c. Sutura cepat menutup.
Perubahan setempat
1. Didapatkan tanda-tanda terdorongnya struktur normal oleh
proses desak ruang.
a. Korpus pineale mungkin terdorong sebagai akibat lang-
sung dari tumor, atau sekunder karena herniasi jaringan
otak melalui tentorium serebri.
b. Pendorongan pada pleksus koroideus, falks atau tento-
rium yang semuanya berkalsifikasi.
2. Erosi setempat pada tulang akibat penekanan.
3. Penipisan setempat atau penonjolan setempat tulang akibat
penekanan massa yang berlangsung lama.
4. Adanya tumor atau malformasi arteriovenosa akan me-
nimbulkan kelainan pada tulang tengkorak.
5. Hiperostosis.
6. Adanya struktur tulang tengkorak yang abnormal dapat
mengakibatkan kelainan neurologik yang sekunder.
7. Akibat peradangan pada organ-organ yang berdekatan se-
perti mastoid atau sinus frontalis.
8. Adanya fraktur atau akibat penyembuhan dari fraktur.
9. Pembentukan tulang yang abnormal (anomali) dengan
kelainan neurologik.
10. Adanya kalsifikasi patologik intrakranial.
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 29
Gambar 1 : Angiogram karotis normal.
Keadaan-keadaan yang mengakibatkan peninggian tekanan
intrakranial adalah :
1. Massa intrakranial yang besar seperti neoplasma, abses atau
hematoma akan menimbulkan tekanan intrakranial yang
meninggi.Otak lebih sering tertekan dari pada tulang kepala
apabila tumbuhnya dengan cepat.
2. Terjadinya obstruksi parsial atau komplit dari aliran likuor
serebrospinal, baik oleh massa intrakranial ataupun kelainan
kongenital, atau oleh perlekatan setelah infeksi dapat
mengakibatkan terjadinya hidrosefalus.
3. Edema serebral yang terjadi sebagai akibat neoplasma, ab-
ses, ensefalitis, infark serebri atau hipertensi vaskuler.
4. Kronio stenosis, yaitu suatu keadaan dimana tengkorak te-
lah berhenti berkembang pada saat jaringan otak masih
membutuhkan tempat untuk berkembang.
Manifestasi radiologik dari peninggian tekanan intrakranial
sangat bergantung pada : periode timbulnya peninggian tersebut
(akut atau kronik), apakah terjadinya pada saat masih bayi,
kanak-kanak atau dewasa. Biasanya kelainan radiologik timbul
apabila tekanan intrakranial yang tinggi telah berlangsung 5
sampai 6 minggu. Dua daerah menjadi pegangan akan ada
tidaknya peninggian tekanan intrakranial ini, yaitu sutura pada
kanak-kanak dan sela tursika pada orang dewasa.
KELAINAN RADIOLOGIK
Efek pada tulang tengkorak
Apabila kenaikan tekanan intrakranial ini terjadi pada periode
ante-natal sampai minggu pertama setelah kelahiran, tulang-
tulang tengkorak akan tampak lebih tipis dari pada normal,
kadang-kadang menunjukkan kegagalan dalam proses
penulangan (sebuah bentuk dari kraniolakuna). Tetapi kenaikan
tekanan intrakranial yang terjadi secara akut tidak akan
mempengaruhi penebalan atau bentuk tulang tengkorak. Tanda
lain dari kenaikan tekanan intrakranial pada kanak-kanak adalah
yang dinamakan impressiones digitatae (Convolutional
impressions) yang terjadi pada bagian atas tulang frontal dan
parietal. Tetapi apabila gambaran ini tampak pada tulang teng-
korak 2/3 bawah ia tidak mempunyai nilai diagnostik, melainkan
dianggap merupakan respons dari tulang yang sedang tumbuh
terhadap jaringan otak di bawahnya.
Pada orang dewasa, kelainan yang berlangsung lama kadang-
kadang menimbulkan penipisan kalvaria secara menyeluruh.
Tetapi apabila tekanan intrakranial yang tinggi ini berlangsung
sejak masa kanak-kanak, misalnya pada_ stenosis akuaduk akan
terjadi pelebaran bagian supratentorial, kecuali fossa posterior
serebri.
Efek pada sutura
Dalam pertumbuhan seorang anak, sutura akan menyempit
pada rata rata usia 1 tahun pertama. Apabila sutura ini tetap lebar
maka patut dicurigai adanya peninggian tekanan intrakranial.
Yang paling jelas adalah sutura lambdoidea. Diastasis dari sutura
ini lebih nyata apabila telah terjadi osifikasi yang sempurna.
Untuk dapat melihat dengan nyata, maka diperlukan pengaturan
posisi kepala anak sehingga tidak terjadi superposisi dengan
jaringan lain.
Efek pada sela tursika
Sela tursika merupakan salah satu bagian intrakranial yang di
gunakan sebagai tolok-ukur ada tidaknya kenaikan intrakranial.
Untuk mendeteksi perubahan dini pada sela tursika akibat
kenaikan tekanan intrakranial ini, diperlukan syarat-syarat
radiologik yaitu :
Posisi pemotretan harus lateral murni, arah sinar-X
tegak lurus pada bidang yang melalui sela tursika.
(bidang sagital).
Teknik pemotretan harus sedemikian rupa sehingga
dapat dilihat adanya perubahan yang men-detail pada tulang.
Kelainan radiologik yang tampak pada sela tursika sebagai
akibat kenaikan tekanan intrakranial, oleh du Boulay dan El
Gammal dibagi dalam 3 kategori :
I. Tampak erosi pada garis korteks sela tursika dekat basis dari
dorsum sela.
II. Destruksi dari puncak dorsum sela prosesus (klinoideus
anterior) dengan kecendrungan terdorongnya sisa dari
lamina dura.
III. Apabila erosi tulang sedemikian rupa sehingga telah meli-
batkan planum sfenoidale.
Harus dapat dibedakan kelainan yang timbul akibat tumor
intra atau suprasellar. Tumor intrasellar akan mengakibatkan
fosa hipofisi yang membengkak seperti balon (ballooning) se-
dangkan tumor-tumor suprasellar menimbulkan pendataran dari
sela (flattening).
Pada penelitian penulis terhadap 83 orang Indonesia dewasa
"
normal" mendapat ukuran sela tursika rata rata : 1,17 cm.
Gambar 2 : Angiogram karotis menunjukkan penekanan pada a. serebri
anterior ke medial dan a. serebri medial ke bawah (tanda
panah).
B. FOTO DENGAN KONTRAS
Foto polos tengkorak digunakan untuk menilai akibat dari
kelainan otak pada tulang tengkorak, sedangkan jaringan otak-
nya sendiri tidak akan tergambar, kecuali adanya pengapuran.
Selain itu juga kelainan yang sifatnya akut, kecuali fraktur tidak
menimbulkan jejak pada tulang tengkorak. Karena itu,
usahakanlah melakukan pemeriksaan jaringan otak dengan
menggunakan kontras. Pada hakekatnya, pemeriksaan dengan
kontras terdiri atas : kontras positif, yang menimbulkan ba-
yangan opak (angiografi); kontras negatif, apabila menimbulkan
bayangan lusen (dengan udara; pneumoensefalografi).
Angiografi serebral dilakukan dengan memasukkan kontras
ke dalam pembuluh-pembuluh otak melalui arteri karotis,
dengan pertolongan jarum atau kateter atau dengan modifikasi
teknik Seldinger yang menggunakan kanula. Karena aliran darah
arteri yang cepat, maka pemotretan pun harus dilaksanakan
secara seri (serial), sehingga setiap fase di mana kontras berada
tidak akan terluput. Fase tersebut adalah fase arteriil, kapiler dan
venosa. Selain berseri, pemotretan sekaligus dilakukan pada
proyeksi lateral dan anteroposterior.
Selain angiografi karotis untuk mengevaluasi tumor-tumor
pada muka atau nasofaring dilakukan angiografi karotis ekstema.
Indikasi pemeriksaan ini terutama adanya proses desak ruang.
30 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Adanya tumor serebral akan mengakibatkan distribusi yang
normal dari pembuluh darah otak terganggu. Lesi-lesi di daerah
oksipital dan temporal sebelah posterior akan lebih sulit terdeteksi
daripada bagian lainnya. Kadang-kadang jenis tumor dapat
diperkirakan berdasarkan gambaran pembuluh darah tumor
tersebut terutama pada jenis meningioma dan glioblastoma
multiforme
Perdarahan subaraknoid : Angiografi karotis merupakan salah
satu sarana diagnostik yang menentukan adanya perdarahan
subaraknoid. Bila faktor trauma disangkal, maka perdarahan yang
terjadi, 50 - 70% diakibatkan aneurisma arteri intrakranial. Pada
kasus-kasus hipertensi, perdarahan subaraknoid sering disertai
perdarahan intraserebral yang spontan. Pada Stenosis pembuluh
darah otak yang mengakibatkan iskemia, maka angiografi
serebral ini diperlukan benar untuk mengetahui lokalisasi pasti
dari penyumbatan.
Trauma kepala dengan kecurigaan perdarahan intraserebral
memerlukan angiografi karotis segera, sehingga hematoma dapat
ditemukan dengan segera dan tindakan adekuat dapat pula
dilaksanakan.
Pada hidrosefalus, tindakan angiografi karotis jarang dila-
kukan dan lebih bermanfaat untuk mengevaluasi hasil tindakan.
Kelainan yang tampak pada angiografi serebral dapat di-
kelompokkan sebagai berikut :
1. Pendorongan pembuluh darah akibat proses desak ruang.
2. Tanda-tanda dilatasi ventrikuler.
3. Tanda-tanda herniasi melewati foramen magnum atau ten-
torium.
4. Tanda-tanda atrofi serebral.
5. Sirkulasi vaskuler yang bertambah pada tumor dan angioma.
6. Aneurisma.
7. Tanda-tanda penyakit serebro vaskuler.
8. Kelainan kongenital.
9. Tanda-tanda yang berhubungan dengan trauma kepala (he-
matoma).
Ventrikulografi dan pneumoensefalografi (PEG) :
Pneumoensefalografi lumbal adalah memasukkan udara ke
dalam ruangan ventrikel melalui pungsi-lumbal sehingga seluruh
ventrikel IV, akuaduk serta sisterna fosa posterior serebri, juga
sistim ventrikel yang lain terisi udara.
Sedangkan ventrikulografi adalah tindakan mengisi ventrikel
secara langsung dengan udara steril, yang sebelum cairan di
dalamnya di-tap terlebih dulu untuk memberi tempat pada udara
tersebut.
Indikasi untuk melakukan ventrikulografi serta PEG adalah:
pada kasus-kasus yang klinis menunjukkan tekanan intrakranial
yang meninggi namun tidak tampak pada pemeriksaan
radiografik biasa. Ensefalografi terutama dilakukan untuk semua
kasus-kasus tumor ekstra serebral yang asalnya dari basis kranii,
pada tumor-tumor yang berasal dari cerebello-pontin angle.
Dikatakan bahwa ventrikulografi lebih superior dibandingkan
dengan PEG pada tumor-tumor serebelum serta tumor-
tumor intra serebral.
Cermin Dunia Kedokteran No. 31, 1984 35
Gambar 3 : Pneumoensefalografi normal.
Secara umum penggunaan kontras negatif ini dilakukan
apabila dengan foto polos atau kontras positif tidak didapatkan
kelainan, padahal klinis amat mengarah ke hal tersebut. Makin
lama penggunaan kontras udara ini makin terdesak karena
tindakan ini dinilai terlalu "tidak enak" (uncomfortable), apalagi
dengan dikembangkannya penggunaanradio isotop dan lebih-
lebih lagi sekarang telah digunakan orang Computerized
Tomography Scanning yang benar-benar tidak ada faktor ma-
nipulasi pada penderita.
PEMERIKSAAN JARINGAN OTAK DENGAN RADIO-
ISOTOP
Apabila sejumlah kecil isotop radio aktif mencapai aliran
darah maka ia akan segera disebar keseluruh tubuh dalam jum-
lah yang berbeda-beda. Banyak sedikitnya zat radio aktif dalam
jaringan dapat diketahui dari jumlah radiasi yang dapat
ditangkap kamera, sehingga akan tercipta suatu pola penyebaran
radio aktif dalam jaringan.
RISA (radio iodinated Serum albumen) serta technetium 99
dalam bentuk pertechnetate merupakan materi yang digunakan
untuk mendeteksi adanya tumor otak. Adanya proses
patologik pada otak, seperti tumor, mengakibatkan bertam-
bahnya cairan ekstra seluler. Komponen radio aktif diatas akan
mengalami kumulasi terutama pada cairan ekstra seluler tadi,
karena itu bagian ini akan memancarkan sinar radio aktif paling
tinggi yang akan tampak sebagai hot-spot. Sebaliknya gambaran
cold-spot menunjukkan daerah dengan vaskuler yang rendah
pada daerah tersebut.
Kegunaan pemeriksaan radioisotop pada jaringan otak ter-
utama pada tumor primer (glioma, meningioma), metastasis
tumor. Pada abses
.
dan hematoma jarang dilakukan karena ku-
rang spesifik.
CT SCAN PADA KELAINAN OTAK
Merupakan teknik pemeriksaan yang mutakhir, mempunyai
risiko pemeriksaan yang rendah dan memberikan nilai
diagnostik yang amat tinggi. Hampir semua kelainan pada ja-
ringan otak dan dasar tengkorak dapat dideteksi dalam keadaan
yang masih dini. Sekalipun demikian, pemeriksaan ini tidak
dapat seluruhnya menggantikan fungsi-fungsi pemeriksaan yang
telah diuraikan sebelum ini, melainkan harus saling melengkapi.
Kekurangan lain adalah masih langkanya sarana dan masih
mahalnya biaya pemeriksaan ini.
KEPUSTAKAAN
1. Shanks SC, Kerley P. A textbook of X-rayDiagnosis. 4th ed., Phi-
ladelphia: WB Saunders Co., 1959.
2. Susworo. Pengukuran Sella Tursica Pada Sejumlah Orang Indonesia
Secara Radiologik. Majalah Radiologi Indonesia 1980; 4 : 5 - 13.
Cedera Otak
dan Dasar-dasar Pengelolaannya
dr. Leksmono PR*, dr. A Hafid**, dr. M Sajid D**
* Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RS Dr. Soetomo, Surabaya
** Sie Bedah Saraf Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RS Dr. Soetomo, Surabaya
PENDAHULUAN
Cedera otak yang akan dibicarakan dalam makalah ini adalah
cedera akibat rudapaksa kepala (trauma kapitis). Di negara maju,
kecelakan lalu lintas merupakan penyebab kematian utama pada
umur antara 2 - 44 tahun, dimana 70% diantaranya mengalami
rudapaksa kepala
1-3
Di Surabaya, frekuensi trauma kapitis
meningkat dengan 18% setiap tahunnya
4
Secara klasik kita kenal pembagian : komosio, kontusio dan
laserasio serebri. Pada komosio serebri kehilangan kesadaran
bersifat sementara tanpa kelainan PA. Pada kontusio serebri
terdapat kerusakan dari jaringan otak, sedangkan laserasio
serebri berarti kerusakan otak disertai robekan duramater.
Pembagian lain menyebutkan bahwa pada komosio serebri,
penurunan kesadaran kurang dari 15 menit dan post traumatic
amnesia kurang dari 1 jam. Bila penurunan kesadaran melebihi 1
jam dan post traumatic amnesia melebihi 24 jam berarti telah
terjadi kontusio serebri. Perlu ditambahkan juga ada atau
tidaknya gejala cedera otak fokal yang dini, dan hasil rekaman
EEG.
5
Pembagian seperti di atas ternyata tidak memuaskan, karena
batas antara kontusio dan komosio serebri sering kali sulit
dipastikan.
5,6
MEKANISME
Rudapaksa kepala dapat menyebabkan cedera pada otak
karena adanya aselerasi, deselerasi dan rotasi dari kepala dan
isinya.
1,7,8
Karena perbedaan densitas antara tengkorak dan
isinya, bila ada aselerasi, gerakan cepat yang mendadak dari
tulang tengkorak diikuti dengan lebih lambat oleh otak. Ini
mengakibatkan benturan dan goresan antara otak dengan bagian-
bagian dalam tengkorak yang menonjol atau dengan sekat-sekat
duramater. Bita terjadi deselerasi (pelambatan gerak), terjadi
benturan karena otak masih bergerak cepat pada saat tengkorak
sudah bergerak
32 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
lambat atau berhenti. Mekanisme yang sama terjadi bila ada
rotasi kepala yang mendadak. Tenaga gerakan ini menyebabkan
cedera pada otak karena kompresi (penekanan) jaringan,
peregangan maupun penggelinciran suatu bagian jaringan di atas
jaringan yang lain. Ketiga hal ini biasanya terjadi bersama-sama
atau berturutan.
7
Kerusakan jaringan otak dapat terjadi di tempat benturan
(coup), maupun di tempat yang berlawanan (countre coup).
Diduga countre coup terjadi karena gelombang tekanan dari sisi
benturan (sisi coup) dijalarkan di dalam jaringan otak ke arah
yang berlawanan; teoritis pada sisi countre coup ini terjadi
tekanan yang paling rendah, bahkan se-ring kali negatif hingga
timbul kavitasi dengan robekan jaringan.
Selain itu, kemungkinan gerakan rotasi isi tengkorak pada
setiap trauma merupakan penyebab utama terjadinya countre
coup, akibat benturan-benturan otak dengan bagian dalam
tengkorak maupun tarikan dan pergeseran antar jaringan dalam
tengkorak.
1,7,8,9
Yang seringkali menderita kerusakan-kerusakan
ini adalah daerah lobus temporalis, frontalis dan oksipitalis.
PATOFISIOLOGI
Trauma secara langsung akan menyebabkan cedera yang
disebut lesi primer. Lesi primer ini dapat dijumpai pada kulit
dan jaringan subkutan, tulang tengkorak, jaringan otak, saraf
otak maupun pembuluh-pembuluh darah di dalam dan di sekitar
otak.
Pada tulang tengkorak dapat terjadi fraktur linier (70% dari
fraktur tengkorak), fraktur impresi maupun perforasi. Penelitian
pada lebih dari 500 penderita trauma kepala menunjukkan
bahwa hanya 18% penderita yang mengalami fraktur
tengkorak.
10
Fraktur tanpa kelainan neurologik, secara klinis
tidak banyak berarti.
7
Cermin Dunia Kedokteran No. 33, 1984 35
Fraktur linier pada daerah temporal dapat merobek atau
menimbulkan aneurisma pada arteria meningea media dan
cabang-cabangnya; pada dasar tengkorak dapat merobek atau
menimbulkan aneurisma a. karotis interna dan terjadi
perdarahan lewat hidung, mulut dan telinga. Fraktur yang
mengenai lamina kribriform dan daerah telinga tengah dapat
menimbulkan rinoroe dan otoroe (keluarnya cairan serebro
spinal lewat hidung atau telinga.
Fraktur impresi dapat menyebabkan penurunan volume
dalam tengkorak, hingga menimbulkan herniasi batang otak
lewat foramen magnum.
7,11
Juga secara langsung menyebabkan
kerusakan pada meningen dan jaringan otak di bawahnya
akibat penekanan.
Pada jaringan otak akan terdapat kerusakan-kerusakan yang
hemoragik pada daerah coup dan countre coup, dengan
piamater yang masih utuh pada kontusio dan robek pada
laserasio serebri. Kontusio yang berat di daerah frontal dan
temporal sering kali disertai adanya perdarahan subdural dan
intra serebral yang akut.
9
Tekanan dan trauma pada kepala akan
menjalar lewat batang otak kearah kanalis spinalis; karena
adanya foramen magnum, gelombang tekanan ini akan
disebarkan ke dalam kanalis spinalis. Akibatnya terjadi
gerakan ke bawah dari batang otak secara mendadak, hingga
mengakibatkan kerusakan-kerusakan di batang otak.
7
Saraf otak dapat terganggu akibat trauma langsung pada
saraf, kerusakan pada batang otak, ataupun sekunder akibat
meningitis atau kenaikan tekanan intrakranial.
7
Kerusakan pada saraf otak I kebanyakan disebabkan oleh
fraktur lamina kribriform di dasar fosa anterior maupun
countre coup dari trauma di daerah oksipital. Pada gangguan
yang ringan dapat sembuh dalam waktu 3 bulan.
2
Dinyatakan
bahwa 5% penderita tauma kapitis menderita gangguan ini.
7
Gangguan pada saraf otak II biasanya akibat trauma di
daerah frontal. Mungkin traumanya hanya ringan saja
(terutama pada anak-anak)
2
, dan tidak banyak yang
mengalami fraktur di orbita maupun foramen optikum.
7
Dari saraf-saraf penggerak otot mata, yang sering terkena
adalah saraf VI karena letaknya di dasar tengkorak.
11
Ini
menyebabkan diplopia yang dapat segera timbul akibat
trauma, atau sesudah beberapa hari akibat dari edema otak.
Gangguan saraf III yang biasanya menyebabkan ptosis,
midriasis dan refleks cahaya negatif sering kali diakibatkan
hernia tentorii
2,7,11
Gangguan pada saraf V biasanya hanya pada cabang supra-
orbitalnya, tapi sering kali gejalanya hanya berupa anestesi
daerah dahi hingga terlewatkan pada pemeriksaan.
Saraf VII dapat segera memperlihatkan gejala, atau sesudah
beberapa hari kemudian. Yang timbulnya lambat biasanya
cepat dapat pulih kembali, karena penyebabnya adalah
edema
2,7
Kerusakannya terjadi di kanalis fasialis, dan sering
kali disertai perdarahan lewat lubang teli-
nga.
Banyak didapatkan gangguan saraf VIII pada. trauma ke-
pala, misalnya gangguan pendengaran maupun keseim-
bangan.
2
Edema juga merupakan salah satu penyebab
gangguan.
7
Gangguan pada saraf IX, X dan XI jarang didapatkan,
mungkin karena kebanyakan penderitanya meninggal bila
trauma sampai dapat menimbulkan gangguan pada saraf-
saraf tersebut.
Akibat dari trauma pada pembuluh darah, selain robekan
terbuka yang dapat langsung terjadi karena benturan atau ta-
rikan, dapat juga timbul kelemahan dinding arteri. Bagian ini
kemudian berkembang menjadi aneurisma. Ini sering terjadi
pada arteri karotis interna pada tempat masuknya di dasar
tengkorak. Aneurisma arteri karotis interim ini suatu saat da-
pat pecah dan timbul fistula karotiko kavernosa.
7
Aneurisma pasca traumatik ini bisa terdapat di semua arteri,
dan potensial untuk nantinya menimbulkan perdarahan
subaraknoid. Robekan langsung pembuluh darah akibat gaya
geseran antar jaringan di otak sewaktu trauma akan menye-
babkan perdarahan subaraknoid, maupun intra serebral. Ro-
bekan pada vena-vena yang menyilang dari korteks ke sinus
venosus (bridging veins) akan menyebabkan suatu subdural
hematoma. Ada 3 macam yaitu yang akut - terjadi dalam 72
jam sesudah trauma; subakut dan kronik. Bentuk akut dapat
juga disebabkan oleh robekan pembuluh darah di korteks.
Hematoma subdural akibat robekan bridging veins disebut
juga hematoma subdural yang simple, sedangkan yang dari
pembuluh darah korteks disebut complicated. Hal ini sehu-
bungan dengan ada (complicated) atau tidaknya (simple) ke-
rusakan jaringan otak di bawah hematoma.
12
Perdarahan epidural biasanya terjadi karena robekan arteri/
vena meningea media atau cabang-cabangnya oleh fraktur li-
nier tengkorak di daerah temporal. Kumpulan darah di antara
duramater dan tulang ini akan membesar dan menekan jaring-
an otak ke sisi yang berlawanan, herniasi unkus dan akhirnya
terjadi kerusakan batang otak. Keadaan ini terdapat pada 1 - 3%
penderita trauma kapitis dan dapat berakibat fatal bila tidak
mendapat pertolongan dalam 24 jam.
7
Dalam perjalanan penyakit selanjutnya bila penderita tidak
meninggal oleh lesi primer tersebut di atas, terjadi proses
gangguan/kerusakan yang akan menimbulkan lesi sekunder.
Proses ini selain disebabkan faktor-faktor intrakranial juga di-
pengaruhi oleh faktor faktor sistemik.
Sebagai kelanjutan dari kontusio akan terjadi edema otak.
Penyebab utamanya adalah vasogenik, yaitu akibat kerusakan
B.B.B. (blood brain barrier). Disini dinding kapiler mengalami
kerusakan ataupun peregangan pada sel-sel endotelnya. Cairan
akan keluar dari pembuluh darah ke dalam jaringan otak ka-
rena beda tekanan intra vaskuler dan interstisial yang disebut
tekanan perfusi. Bila tekanan arterial meningkat akan mem-
percepat terjadinya edema dan sebaliknya bila turun akan
memperlambat.
13,14
Edema jaringan menyebabkan penekanan
pada pembuluh-pembuluh darah yang mengakibatkan aliran
darah berkurang. Akibatnya terjadi iskemia dan hipoksia.
Asidosis yang terjadi akibat hipoksia ini selanjutnya menim-
bulkan vasodilatasi dan hilangnya auto regulasi aliran darah,
sehingga edema semakin hebat. Hipoksia karena sebab-sebab
lain juga memberikan akibat yang sama.
15
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan suhu tubuh
menjadi 40
0
Celcius selama 2 jam akan menambah edema se-
besar 40% yang mungkin disebabkan oleh karena perubahan
penneabilitas kapiler dan kenaikan metabolisme.
16
Akibat lain dari trauma kapitis adalah kenaikan tekanan intra
kranial. Pada saat trauma, terdapat peningkatan tekanan pada
sisi benturan dan penurunan tekanan pada sisi yang ber-
lawanan. Kenaikan tekanan intrakranial yang terjadi beberapa
waktu kemudian dapat oleh karena edema otak atau kenaikan
volume darah otak. Bila timbulnya lebih lambat lagi (lebih dari
10 hari), ini mungkin disebabkan oleh adanya hematoma kronik
atau gangguan sirkulasi cairan serebro spinal.
Kenaikan tekanan intra kranial ini menyebabkan :
aliran darah ke otak menurun.
Brain shift maupun herniasi.
perubahan metabolisme, yaitu terjadi asidosis metabolik
yang selanjutnya memperberat edema.
gangguan faal paru-para.
Ini terjadi karena kerusakan pada batang otak sesudah trauma
mengakibatkan terjadinya apnea atau takipnea. Hal ini
menimbulkan edema paru-paru yang selanjutnya mengganggu
pertukaran gas. Gangguan ini menyebabkan hipoksia yang akan
memperberat edema di otak maupun di paru-paru.
1
Dari hal-hal di atas terlihat bahwa gangguan intrakranial
maupun sistemik sesudah trauma kapitis itu merupakan suatu
lingkaran kejadian sebab akibat yang makin lama makin mem-
perjelek keadaan penderita (
"
lingkaran setan").
PENGELOLAAN
Pemeriksaan
5,17,18,19
Anamnesis. Anamnesis dapat diambil dari famili, orang di-
sekitar kejadian, pegawai ambulans, polisi, mengenai :
Saat terjadinya kecelakaan, macam kecelakaan : lalu lin-
tas, pabrik dll.
cara kecelakaan, untuk dapat memperkirakan intensitas
trauma dan macam cederanya.
pada penderita yang sadar : ada tidaknya gangguan kesa-
daran sebelumnya, ada tidaknya amnesia, baik retrograde
maupun pasca traumatik. Makin lama amnesia post trau-
matik, prognosis makin jelek.
penyakit yang diderita : epilepsi, hipertensi, diabetes, jan-
tung dan lain-lain.
Obat-obat yang telah/sedang dipergunakan.
Pemeriksaan Fisik
fungsi-fungsi vital, kesadaran, gejala neurologik, antara lain
gejala vegetatif : mual, muntah, pucat, (dalam hal ini harus
dibedakan dengan pucat akibat perdarahan). Data-data
pemeriksaan awal ini penting sebagai dasar observasi
selanjutnya. Di Bagian Saraf dan Sie Bedah Saraf Bagian
Bedah RS Dr. Soetomo dipakai Glasgow Coma Scale (GCS)
untuk evaluasi kesadaran.
Tanda-tanda trauma di kepala, hematoma sekitar mata dan
hematoma di belakang telinga, darah dari orifisium-orifi-
34 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
sium di kepala.
Adanya tanda-tanda trauma di tempat lain, bila ada dapat
memperburuk prognosisnya.
X Foto Kepala : sebaiknya dibatasi
10,20
Dianjurkan dibuat pada :
-- trauma kepala tertutup dengan ekskoriasi ataupun hematoma
kulit kepala.
penderita dengan kelainan neurologik.
adanya fraktur impresi.
penderita akan dioperasi dengan dugaan hematoma intra-
kranial.
trauma kepala terbuka untuk mengetahui lokalisasi frak-
tur/fragmen-fragmennya.
Pemeriksaan Tambahan
17,21,22
1. Eko - Ensefalografi
Sebagian penulis menyatakan, pemeriksaan ini dapat mem-
bantu mengetahui adanya pergeseran garis tengah otak bila
dikerjakan oleh orang yang berpengalaman; penulis lain
berpendapat bahwa pemakaiannya kurang dapat dijamin.
2. Angiografi dan CT Scan
Keduanya merupakan cara pemeriksaan yang dapat dian-
dalkan untuk mengetahui adanya massa intrakranial.
Indikasi Masuk Rumah Sakit
18
Hal ini tergantung pada berat ringannya kerusakan yang terdapat
pada waktu masuk dan kemungkinan-kemungkinan komplikasi
yang akan terjadi.
1. Gangguan kesadaran.
2. Gangguan kelainan neurologik.
3. Fraktur tulang kepala yang menyilang jalan a. meningea media
(untuk observasi).
4. Kemungkinan fraktur dasar tengkorak.
5. Fraktur impresi terbuka dan trauma kepala terbuka yang lain.
6. Dipertimbangkan pada nyeri kepala, vertigo dan muntah yang
terus menerus.
Perawatan
Umum
a) menjaga agar jalan nafas tetap bebas/lancar, terutama bila
penderita koma. Posisi penderita sebaiknya miring (termasuk
badannya), ini untuk mencegah aspirasi dan penyumbatan laring
oleh lidah. Tungkai yang di atas sebaiknya fleksi, dan posisi
diubah setiap 2 jam.
Kalau perlu dapat dipertimbangkan pemasangan pipa endo-
trakea/trakeostomi.
Bila ada fasilitas analisa gas darah, p0
2
arteri dipertahankan
diatas 80 mmHg dan pCO
2
antara 25 - 30 mmHg.
b) Tekanan darah yang kurang dari 90 mmHg dengan nadi kecil,
harus dicari sebab-sebabnya diluar kepala, antara lain trauma
abdomen
26
, fraktur.
Syok harus segera diatasi dan perdarahan dihentikan. Bila ada
anemia harus segera diperbaiki (terutama pada penderita
arterioskeloris).
c) Cairan, Elektrolit, Nutrisi.
Pada umumnya diadakan pembatasan cairan ringan untuk
Cermin Dunia Kedokteran No. 35, 1984 35
mencegah adanya overhidrasi, terutama dalam 24 jam pertama.
27
Bila keadaan memungkinkan pemberian cairan intravena
setelah 2 hari dapat dikombinasi/diganti dengan sonde hidung.
Penderita dewasa, kebutuhan cairan minimal 2 liter/hari dan
tiap kenaikan suhu 1 C ditambah liter.
Kalori yang dibutuhkan pada penderita koma minimal 2000
kal/hari.
d) Miksi, defekasi, kulit, mata.
Urin ditampung untuk memperhitungkan kebutuhan cairan dan
menjaga agar tempat tidur tetap kering. Dipasang kondon atau
kateter. Kateter dipakai sesedikit mungkin untuk mencegah
bahaya infeksi.
Diusahakan tidak terdapat konstipasi yang terlalu lama ka-
rena bahaya ileus.
Untuk mencegah dekubitus, tempat tidur harus rata, kering
dan lunak.
Mata dapat dibasahi dengan larutan asam borat 2%.
e) Hipotermi
28
Dengan penurunan suhu tubuh menjadi 32 C, kebutuhan 0
2
otak menurun sebanyak 25%; ini mengurangi risiko terjadinya
hipoksia. Selain itu pendinginan tubuh ini juga membantu
mengeringkan sekret, mengurangi tonus otot di saluran napas,
dan mengurangi tekanan intrakranial.
Khusus/Pengobatan.
a) Kejang-kejang.
Sekitar 5% dari penderita mengalami kejang-kejang
6,21,29
Bila ada fraktur impresi, insidensi naik menjadi 10%. Angka-
angka ini untuk kejadian-kejadian pada minggu pertama,
(epilepsi traumatik dini).
7
Untuk mengatasi diberikan diazepam,
selanjutnya difenilhidantoin dan fenobarbital.
b) Penderita yang mulai sadar sering menjadi gelisah. Diusaha-
kan untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan penye-
babnya, misalnya kandung kemih yang penuh atau ikatan yang
terlalu kuat. Kegelisahan ini dapat menyebabkan peningkatan
tensi dan lain-lain hal yang tidak diinginkan. Bila perlu dapat
diberikan suntikan klorpromazin 25 mg
23
c) Suhu tubuh
Kenaikan suhu tubuh dapat memperberat edema otak. Harus
diusahakan untuk mencari penyebabnya dan mengendalikan-
nya. Kemungkinan penyebabnya: penggantian cairan tidak ba-
ik, infeksi pm-pm komplikasi trakeostomi, infeksi saluran
kencing, tromboflebitis, luka operasi, reaksi transfusi, drug
fever, gangguan hipotalamus dan batang otak.
d) Pengobatan edema otak
Deksametason
Terpenting adalah deksametason karena paling kuat kerjanya
diantara obat-obat glukokortikoid, dan dapat membantu fungsi
membran sel dalam pertukaran ion Na+ K+ (sodium pump)
22
Takaran permulaan 8 - 12 mg dilanjutkan dengan 4 mg tiap 6
jam selama 7 - 10 hari kemudian perlahan-lahan dihentikan.
Dosis untuk anak-anak 1 - 4 mg kemudian 0,25 - 0,50 mg/kg/
hari dibagi dalam 4 kali pemberian.
20
Pada trauma berat dapat
diberikan dosis yang lebih besar. Sebaiknya diberikan juga
antasida dan simetidin untuk mencegah terjadinya perdarahan
karena ulkus lambung.
31
Cairan Hipertonik
24
Yang biasa dipakai adalah Manitol 20%. Diberikan pada pen-
derita yang akan dioperasi dan bila keadaan kritis. Takaran 1 -
1,59 gr/kg dalam 10 menit. Marshal
13
menganjurkan 0,25
gr/kg. Pemberian dapat diulang menurut keperluan.
Diuretik
Efeknya dalam menurunkan tekanan intrakranial belum dapat
dipastikan.
Di rumah sakit yang lengkap peralatannya, dapat dilakukan
"
hiperventilasi yang terkontrol", dimana PaCO
2
dipertahankan
30 torr dan PaO
2
diatas 150 torr.
24,28
Observasi
Tujuannya untuk mengikuti perjalanan penyakit penderita,
mengetahui sedini mungkin terjadinya komplikasi, hingga dapat
secepatnya diambil tindakan. Sebagai dasar observasi adalah
data-data pemeriksaan fisik mengenai fungsi vital, kesadaran
penderita dan gangguan neurologik.
Observasi fungsi vital mencakup hal-hal yang tersebut
dalam Bab Perawatan.
Kesadaran
Kesadaran merupakan hal yang terpenting pada observasi. Ke-
sadaian diatur oleh dua pusat di otak yaitu oleh (Ascending
Reticular Activating System (ARAS) yaitu untuk off-on nya
misalnya reaksi membuka mata, sedangkan hemisfer otak me-
nentukan "isi" dari kesadaran tersebut. Kedua pusat ini harus
tetap dalam keadaan baik supaya seseorang dapat sadar dengan
sepenuhnya.
Untuk dapat memperoleh catatan/gambaran yang cukup
obyektif mengenai kesadaran penderita di Bagian Saraf FK
Unair dan Sie Bedah Saraf Bagian Bedah FK Unair selama be
berapa tahun telah dipakai Glasgow Coma Scale (GCS)
4,32,33
Skala ini disusun oleh Teasdale dan Jennett pada tahun 1974.
Disini dinilai tiga macam reaksi yaitu reaksi membuka mata,
reaksi verbal dan reaksi motorik (Lihat Tabel) Dalam skala ini
seseorang yang sadar sepenuhnya mendapat nilai 15, yaitu 4
untuk reaksi buka mata, 5 untuk reaksi verbal dan 6 untuk
reaksi motorik. Jadi penderita dapat membuka mata spontan,
bila diajak berbicara jawabannya berorientasi (mengenal diri,
waktu dan tempat), dan dapat melakukan hal-hal sesuai dengan
yang diperintahkan , misalnya mengangkat tangannya.
Penderita koma yang dalam mendapat jumlah nilai 3 yaitu
nilai 1 untuk masing-masing reaksi.
Dengan mengisi tabel ini pada waktu-waktu yang tertentu,
kita dapat menilai/mengikuti perkembangan kesadaran pen-
derita.
Gangguan Neurologik.
39
Disini antara lain diperiksa adanya lesi kompresi yang unila-
teral dan ada atau tidaknya perkembangan kerusakan dari kra-
nial (hemisfer) ke kaudal (batang otak/medula) --> kematian
penderita.
1. Lesi unilateral supratentorial.
a. Hemiparesis.
b. Gangguan saraf fasialis sentral.
c. Deviasi bola mata ke arah lesi.
d. Kompresi mesensefalon unilateral --
>
reaksi pupil ab-
normal.
TABEL
Bagian Saraf/Sie Bedah Saraf Bagian Bedah
Nama . Tn. X
Umur . 30 tahun ( l P
Ref. 007.84
Fakultas Kedokteran Unair/RS Dr. Soetomo
Surabaya
Tgl. 9 April 84 10 11
12 13
Hari Senin 1
2 3
4 5
S
K
A
L
A
K
O
M
A
Reaksi
buka
mata
Spontan I
thd. suara
~ . I
7
thd. nyeri
1
negatif
Reaksi
Verbal
berorientasi
bingung
tidak sesuai
I
tidak dimengerti
i
negatif
Reaksi
Moto-
rik
mengikuti perintah
I
melokalisir nyeri
I
~ .
_
. _
_
~
menarik diri
fleksi
j
ekstensi
negatif
2. Perkembangan kranio kaudal.
a. Pupil dan reaksinya : integritas batang otak.
besar normal/refleks cahaya (+) - - pin point/refleks (+) (
Normal) (lesi di pons)
b. Gerak refleks mata
Do l l
'
s head eye movement.
Rotasi cepat kepala penderita oleh pemeriksa akan
memberi reaksi gerak mata konjugat ke arah yang ber-
lawanan (batang otak masih baik).
Tes kalori (harus dicek utuhnya membrana Timpani).
Irigasi telinga dengan air dingin sesudah 20 - 30 detik
akan menimbulkan gerakan mata konjugat tonik ke
arah rangsangan (batang otak masih baik).
c. Reaksi motorik
Bila dirangsang nyeri dan lain-lain, posisi penderita akan
memperlihatkan gejala-gejala dekortikasi atau deserebrasi
atau flaksid. (Gangguan kranial , kaudal).
d. Tipe pernapasan
Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor matabolik.
Bila faktor-faktor tersebut dapat disingkirkan, hubungan
lokalisasi kurang lebih sebagai berikut :
36 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Cheyne stokes
~
lesi kortikal.
Hiperventilasi (sentral) . lesi mesensefalon.
Iregular ~ lesi tegmentum.
Ataksik Apnea ~ lesi medula.
Selain hal-hal tersebut diatas, diobservasi juga gejala-gejala
neurologik lain, misalnya kemungkinan timbulnya fistula
karotiko kavernosa dan emboli lemak.
Fistula karotiko kavernosa dapat timbul sejak beberapa jam
sesudah trauma. Penderita mendengar suara bising (bruit) da-
lam kepalanya, nyeri kepala dan penglihatan ganda. Pada pe-
meriksaan didapatkan pembengkakan dan penonjolan mata yang
merah dan berdenyut. Dapat ditemukan gangguangangguan
saraf kranial berturut-turut saraf 3,6,5,7,4 dan 2. Pada auskultasi
di daerah temporal, orbita, dan diatas arteri karotis dapat
terdengar suara bising yang sesuai dengan denyut nadi. Operasi
ligasi dilakukan setelah evaluasi dengan arteriografi dan EEG."
Emboli lemak dapat terjadi bila terdapat juga fraktur tulang-
tulang panjang. Gejala dapat timbul dari beberapa jam sampai 3
hari sesudah trauma. Mula mula akan timbul sindroma paru-
paru dengan hipoksia, takipnea dan sesak nafas, ta-
Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984 37
hap berikutnya terjadi sindroma serebral dengan kegelisahan,
suhu badan meningkat, penurunan kesadaran sampai koma
yang kadang-kadang disertai dengan gejala-gejala fokal misal-
nya hemiparesis ataupun kejang-kejang.
Pada X-foto torak dapat terlihat gambaran snowstorm. Peng-
obatan dengan pemberian kortikosteroid, 0
2
dan hipotermi.
7,25,35
Hasil-hasil observasi sangat menentukan tindakan apa yang
selanjutnya harus dikerjakan, antara lain perlu atau tidaknya
seseorang penderita segera dioperasi.
Tindakan bedah darurat.
Dari segi bedah saraf sangat penting adalah komplikasi intra-
kranial, lesi massa, khususnya hematoma intrakranial.
Hematoma epidural
12
Adalah komplikasi intrakranial yang paling mudah dicapai dan
paling baik hasilnya dari tindakan-tindakan bedah trauma ke-
pala. Pada umumnya alasan untuk merawat penderita dalam RS
didasarkan atas kemungkinan timbulnya hematoma ini.
Maka perjalanan penyakit serta gejala-gejalanya harus dikenal
dengan baik.
Gambaran klasik adalah kehilangan kesadaran sementara
pada waktu trauma. Gangguan kesadaran ini membaik tanpa
kelainan neurologik. Kemudian terjadi gangguan kesadaran
yang kedua dengan didahului oleh nyeri kepala. Pada saat
trauma, terjadi robekan dan perdarahan dari a. meningea me-
dia. Perdarahan kemudian berhenti oleh karena spasme pem-
buluh darah dan pembentukan gumpalan darah. Beberapa jam
kemudian terjadi perdarahan ulang; penumpukan darah di ruang
epidural_ini akan melepaskan duramater dari tulang tengkorak.
Pada waktu nyeri kepala menghebat dan kesadaran menurun,
telah terjadi kenaikan tekanan intrakranial yang kedua. Pada
saat ini timbul gejala-gejala distorsi otak.
Begitu kemampuan kompensasi ruang intrakranial habis,
keadaan umum penderita dengan cepat menurun. Tampak pe-
lebaran pupil ipsilateral (80%), oleh karena herniasi bagian
mesial dari lobus temporalis menekan n. okulomotorius.
penurunan kesadaran bertambah.
hemiparesis kontralateral (dapat juga ipsilateral).
deserebrasi.
Bila keadaan berlanjut tanpa tindakan, timbul
Pernapasan Cheyne Stokes.
refleks pupil dan respon kalorik negatif.
pernapasan paralitik, bradikardi dan akhirnya meninggal.
Maka sangat penting diagnosis ditegakkan sedini mungkin,
yaitu bila hanya nyeri kepala dan penurunan kesadaran saja
yang tampak. Pada saat ini diperlukan pemeriksaan tambahan
arteriografi atau bila mungkin CT. Bila telah tampak pelebaran
pupil dan atau hemiparesis maka tindakan secepatnya harus
diambil dengan atau tanpa bantuan sarana diagnosis tersebut.
Mengirimkan penderita ke pusat yang lebih lengkap seharus-
nya pada saat dini tersebut, yaitu pada saat baru timbul nyeri
kepala hebat dan penurunan kesadaran. Bila tidak mungkin
melakukan rujukan, atau bila diperkirakan terlambat untuk
dikirim berhubung gejalanya sudah nyata, seyogyanya tindak-
an bedah dapat dilakukan di RS setempat.
Beberapa petunjuk pembantu menentukan lokalisasi :
biasanya temporal (73%)
36
adanya jejas di kepala; laserasi kulit, hematoma subkutan,
ekskoriasi, perdarahan dari telinga.
x foto kepala terdapat fraktur tulang kepala.
Hematoma epidural terdapat pada/dibawah/sekitar garis
fraktur.
dipilih terutama pada sisi pupil yang melebar.
Pembedahan explorative burrhole, bila positif dilanjutkan
dengan kraniotomi evakuasi hematoma dan hemostasis yang
cermat.
Hematoma subdural
12
Yang terpenting dalam hal gawat darurat adalah hematoma
subdural akut (yang terjadi dalam waktu 72 jam sesudah trau-
ma). Hematoma subdural, khususnya yang berkomplikasi,
gejalanya tak dapat dipisahkan dari kerusakan jaringan otak
yang menyertainya; yang berupa gangguan kesadaran yang
berkelanjutan sejak trauma (tanpa lusid interval) yang sering
bersamaan dengan gejala-gejala lesi massa, yaitu hemiparesis,
deserebrasi satu sisi, atau pelebaran pupil.
Dalam hal hematoma subdural yang simple dapat terjadi
lusid interval bahkan dapat tanpa gangguan kesadaran. Sering
terdapat lesi multiple. Maka, tindakan CT Scan adalah ideal,
karena juga menetapkan apakah lesi multiple atau single.
Angiografi karotis cukup bila hanya hematoma subdural yang
didapatkan.
Bila kedua hal tersebut tak mungkin dikerjakan, sedang ge-
jala dan perjalanan penyakit mengarah pada timbulnya lesi
massa intrakranial, maka dipilih tindakan pembedahan. Tin-
dakan eksploratif burrhole dilanjutkan tindakan kraniotomi,
pembukaan dura, evakuasi hematoma dengan irigasi memakai
cairan garam fisiologis. Sering tampak jaringan otak edematous.
Disini dura dibiarkan terbuka, namun tetap diperlukan penu-
tupan ruang likuor hingga kedap air. Ini dijalankan dengan
bantuan periost. Perawatan pascabedah ditujukan pada faktor-
faktor sistemik yang memungkinkan lesi otak sekunder.
Fraktur impresi.
Fraktur impresi terbuka (compound depressed fracture). In-
dikasi operasi terutama adalah debridement, mencegah infeksi.
Operasi secepatnya dikerjakan. Dianjurkan sebelum lewat 24
jam pertama. Pada impresi tertutup, indikasi operasi tidak
mutlak kecuali bila terdapat kemungkinan lesi massa dibawah
fraktur atau penekanan daerah motorik (hemiparesis dan lain-
lain).
Indikasi yang lain (lebih lemah), ialah kosmetik dan ke-
mungkinan robekan dura. Diagnosis dengan x foto kepala 2
proyeksi, kalau perlu dengan proyeksi tangensial. Impresi lebih
dari tebal tulang kepala pada x foto tangensial, mempertinggi
kemungkinan robekan dura. X foto juga diperlukan untuk
menentukan letak fragmen-fragmen dan perluasan garis
fraktur; dengan ini ditentukan pula apakah fraktur menyilang
sinus venosus. Impresi fraktur tertutup yang menyilang garis
tengah merupakan kontra indikasi relatif untuk operasi,
dalam arti sebaiknya tidak diangkat bila tidak terdapat gejala
yang mengarah pada kemungkinan lesi massa atau penekanan
otak.
37
Dalam hal fraktur impresi terbuka yang menyilang sinus
venosus maka persyaratan untuk operasi bertambah dengan :
bila luka sangat kotor.
bila angulasi besar.
bila terdapat persediaan darah cukup.
bila terdapat ketrampilan (skill) dan peralatan yang cukup.
PROGNOSIS
Hal-hal yang dapat membantu menentukan prognosis :
Usia dan lamanya koma pasca traumatik,
38
makin muda usia,
makin berkurang pengaruh lamanya koma terhadap restitusi
mental.
Tekanan darah pasca trauma. Hipertensi pasca trauma mem-
perjelek prognosis.
38
Pupil lebar dengan fefleks cahaya negatif, prognosis jelek.
35
Reaksi motorik abnormal (dekortikasi/deserebrasi) biasanya
tanda penyembuhan akan tidak sempurna.
35
Hipertermi, hiperventilasi, Cheyne-Stokes, deserebrasi:
menjurus ke arah hidup vegetatif.
35,39
Apnea, pupil tak ada reaksi cahaya, gerakan refleks mata
negatif, tak ada gerakan apapun merupakan tanda-tanda
brain death. Ini perlu dilengkapi dengan EEG yang iso-
elektrik.
35
RINGKASAN
Dibicarakan mengenai cedera otak dan dasar-dasar pengelo-
laannya, sehubungan dengan makin meningkatnya korban ke-
celakaan lalu lintas dimana banyak diantaranya mengalami ce-
dera otak.
Akibat benturan kepala, terjadi cedera pada otak dan ja-
ringan sekitarnya yang disebut dengan lesi primer. Bila korban
dapat tetap bertahan, terjadi proses lebih lanjut yang dipenga-
ruhi oleh faktor-faktor intrakranial maupun sistemik. Proses ini
akan menghasilkan kerusakan-kerusakan yang disebut lesi
sekunder. Mekanisme terjadinya cedera akibat benturan kepala
dan patofisiologik proses selanjutnya telah dibicarakan; juga
kerusakan-kerusakan pada jaringan sekitar otak.
Pengelolaan meliputi pemeriksaan, observasi dan pengobat-
an penderita baik secara konservatif maupun yang memerlukan
tindakan operasi darurat. Dengan pengelolaan yang cepat,
terutama pada saat proses terjadinya lesi-lesi sekunder,
diharapkan dapat diperoleh hasil yang sebaik-baiknya bagi
penderita.
Daftar kepustakaan ada pada redaksi/penulis
38 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
dr. Hendro Susilo
Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RS Dr. Soetomo, Surabaya
Infeksi Intrakranial
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 39
PENDAHULUAN
Mekanisme Penanggulangan terhadap infeksi yang terjadi di
susunan saraf pusat diduga kurang efektif dibandingkan dengan
infeksi yang terjadi di bagian tubuh lain. Tidak jarang organisme
yang relatif memiliki derajat patogenitas rendah dapat
menyebabkan meningitis atau abses otak. Demikian pula cairan
serebrospinal (CSS) pada beberapa kasus justru merupakan
media yang ideal untuk pertumbuhan kuman disamping
hambatan antibodi dan sel radang untuk menembus jaringan
saraf pusat oleh karena adanya barrier darah otak.
Dari segi klinis, infeksi intrakranial seringkali menunjukkan
angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Hingga penting
untuk mengenal diagnosis secara dini dan memberikan
pengobatan yang segera, tepat dan rasional untuk menghindari
kematian dan gejala sisa yang menetap.
MENINGITIS
Istilah "meningitis" menunjukkan reaksi keradangan yang
mengenai satu atau semua lapisan selaput otak yang membung-
kus jaringan otak dan sumsum tulang. Dalam arti yang terbatas
menunjukkan infeksi difus yang mengenai lapisan pia dan
araknoid (lepto meningitis).
1
Pada umumnya infeksi tidak hanya
terbatas pada selaput otak namun juga mengenai jaringan otak
(ensefalitis) dan pembuluh darah (vaskulitis).
Pembagian klinis :
1. Meningitis bakteri akut
2. Meningitis subakut dan kronis.
MENINGITIS BAKTERI AKUT
Patogenesis : infeksi mencapai selaput otak melalui :
Implantasi langsung setelah luka terbuka kepala
Perluasan langsung dari infeksi telinga tengah, sinus para-
nasalis dan wajah
Lewat aliran darah (bakteriemia atau sepsis)
Perluasan dari tromboflebitis kortikal dan abses otak
Melalui lamina kribrosa pada rinore CSS yang kronis atau
rekuren.
Etiologi : Meningitis adalah kasus darurat yang memerlukan
pengobatan segera tanpa menunggu hasil pembiakan kuman,
sehingga perlu diketahui jenis organisme yang sering ditemukan
berdasarkan usia penderita.
2
Neonatus (sampai 30 hari) : Gram negatip enterobaccili,
Streptococcus grup B, Listeria monocytogenes
Bayi (30 - 60 hari) : Streptococcus grup B, Haemophilus
influenzae, Neisseria meningitidis.
Anak (2 - 4 tahun) : Haemophilus influenzae, Neisseria
meningitidis, Streptococcus pneumonia.
Anak (lebih 4 tahun) dan dewasa : Streptococcus
pneumonia. Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus,
Haemophilus influenzae.
Manifestasi klinis : Secara klinis meningitis purulenta pada de-
wasa ada 3 kelompok :
Kelompok I :
dengan panas, nyeri kepala dan kaku tengkuk mendadak di-
ikuti kesadaran yang menurun.
Kelompok II :
dengan panas, nyeri kepala dan kaku tengkuk yang berjalan
antara 1 - 7 hari, dengan tanda-tanda infeksi saluran napas
bagian atas; penderita hanya mengantuk tanpa penurunan
kesadaran yang jelas.
Kelompok III :
panas dan nyeri kepala mendadak diikuti keadaan syok
dengan hipotensi dan takikardia oleh karena sepsis.
Pemeriksaan neurologis seringkali dijumpai tanda rangsangan
selaput otak (seperti kaku tengkuk, tanda Kernig dan Brudzinki),
kelumpuhan saraf kranial (strabismus, gerakan bola mata
terganggu) dan tanda fokal lain. Pada bayi dan anak sering di-
jumpai kejang dan kesadaran yang menurun sampai koma.
Faktor predisposisi : Beberapa faktor predisposisi perlu di-
pikirkan seperti otitis media dan mastoiditis, pneumonia, dia-
betes mellitus, trauma kepala, abses otak, furunkulosis dan
selulitis. Meningitis dapat juga merupakan komplikasi dari
leukemia dan penyakit Hodgkin.
1,2
Diagnosis :
Pemeriksaan CSS menunjukkan tekanan meningkat dengan
warna keruh sampai purulen, dan peningkatan jumlah lekosit
(500 - 35000/cmm) yang terutama terdiri sel PMN (stadium
awal). Kadar protein meningkat dan kadar glukosa menurun.
Hendaknya dilakukan pengecatan CSS (Gram) disamping
pembiakkan kuman.
Pemeriksaan lain seperti X-foto tengkorak, sinus paranasalis
mastoid, toraks dan EEG.
Pengobatan :
Pengobatan kausal dengan antibiotika dosis tinggi sesuai
dengan usia penderita dan kuman penyebab.
Dosis dewasa yang biasanya diberikan adalah :
Ampisilin : 300 - 400 mg per kg (6 dosis) i.v
Kloramfenikol : 4 - 6 g/hari (4 dosis) i.v.
Gentamisin : 3 - 5 mg per kg (3 dosis) i.v
Oksasilin : 10 - 12 gram (6 dosis)
Pengobatan suportip dan simtomatik (cairan, elektrolit,
kejang, edema otak, febris).
MENINGITIS TUBERKULOSIS
Penyakit ini merupakan meningitis yang sifatnya subakut
atau kronis dengan angka kematian dan kecacadan yang cukup
tinggi. Menurut pengamatan, meningitis tuberkulosis merupakan
38,5% dari seluruh penderita dengan infeksi susunan saraf pusat
yang dirawat di bagian Saraf RS Dr Soetomo.
3
Manifestasi klinis : Penulis menemukan adanya panas (94%),
nyeri kepala (92%), muntah muntah, kejang dan pemeriksaan
neurologik menunjukkan adanya kaku tengkuk, kelumpuhan
saraf kranial (terutama N III, IV, VI, VII) (30%), edema papil
dan kelumpuhan ekstremitas (20%) serta gangguan kesadaran.
4
Diagnosis : Diagnosis Meningitis tuberkulosis ditegakkan atas
dasar :
1. Adanya gejala rangsangan selaput otak seperti kaku tengkuk,
tanda Kernig dan Brudzinski.
2. Pemeriksaan CSS menunjukkan :
peningkatan sel darah putih terutama limfosit
peningkatan kadar protein
penurunan kadar glukosa
3. Ditambah 2 atau 3 dari kriteria dibawah ini :
ditemukannya kuman tuberkulosis pada pengecatan dan
pembiakan CSS
kelainan foto toraks yang sesuai dengan tuberkulosis
Pada anamnesis kontak dengan penderita tuberkulosis aktif
Stadium : Pembagian klinis ke dalam 3 stadium :
40 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Stadium I :
kesadaran penderita baik disertai rangsangan selaput otak
tanpa tanda neurologik fokal atau tanda hidrosefalus.
Stadium II :
didapatkan kebingungan dengan atau tanpa disertai tanda
neurologis fokal misalnya kelumpuhan otot mata bagian luar
atau adanya hemiparesis.
Stadium III :
penderita dengan stupor atau delirium dengan hemiparesis/
paraparesis.
Pengobatan : Beberapa kombinasi obat pernah diberikan untuk
menanggulangi penyakit ini namun pada dasarnya obat tersebut
harus dapat menembus barrier darah otak, berada dalam CSS
dengan kadar yang cukup efektif dan aktivitas anti tuberkulosis
tinggi, resistensi dan kerja samping obat yang minimal.
Di RS Dr Soetomo dipakai kombinasi
3
:
Streptomisin 20 - 30 mg/kg/hari selama 2 minggu kemudian
dijarangkan 3 kali/minggu hingga klinis dan laboratorium
baik (perlu waktu kira-kira 6 minggu).
INH 20 - 25 mg/kg/hari pada anak anak atau 400 mg/hari
pada dewasa selama 18 bulan.
Etambutol 25 mg/kg/hari sampai sel cairan serebrospinal
normal, kemudian diturunkan 15 mg/kg/hari selama 18 bu-
lan.
Rifampisin 15 mg/kg/hari selama 6 - 8 minggu.
Kortikosteroid hanya dianjurkan bila ditemukan tanda edema
otak.
ABSES OTAK
Penanganan penderita dengan abses otak di RS Dr Soetomo
akhir-akhir ini mengalami kemajuan dengan adanya sarana di-
agnosis yang modern seperti CT scan, penanggulangan bedah
saraf yang memadai dan pengobatan yang adekuat. Namun perlu
diperhatikan pula adanya kegagalan dalam pengobatan, karena
adanya pembahan pola organisme seperti ditemukannya kuman
anaerob dan infeksi campuran serta resistensi terhadap
antibiotika.
5
Sumber infeksi :
Penyebaran langsung dari otitits media, mastoiditis atau
sinusitis frontalis, etmoidalis, sfenoidalis dan maksilaris.
Tromboflebitis kortikal, osteomielitis tulang tengkorak.
Luka tembus pada tulang tengkorak.
Emboli septik yang berasal dari paru (bronkiektasis, empie-
ma, abses paru), dan jantung (SBE, penyakit jantung ko-
ngenital).
Lokalisasi : Sering daerah lobus frontalis dan parietalis, juga
ditemukan pada lobus temporalis dan serebelum (otitis, media
dan mastoiditis) serta abses yang multiple.
Manifestasi klinis :
Gejala sistemik : panas, malaise, menggigil, bradikardia.
Gejala SSP non fokal : akibat kenaikan tekanan intrakranial
(nyeri kepala, muntah, gangguan kesadaran).
Gejala fokal SSP : tergantung lokalisasi abses (gangguan
motorik, mental, sensorik, kejang,ataksia).
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 41
Diagnosis :
Darah : sel lekosit dan laju endap darah meningkat.
X-foto tengkorak, mastoiditis, sinusitis, pergeseran
kelenjar pineal.
CT scan : sangat membantu diagnosis dini maupun
follow-up pasca pengobatan/bedah. Demikian pula CT scan
sangat membantu pada penderita dengan gejala meningitis
yang disertai tanda lateralisasi neurologi sebelum dilakukan
punksi lumbal
EEG dan arteriogram.
Pengobatan :
Pemberian antibiotika yang adekuat terutama stadium
serebritis baik terhadap kuman aerob maupun anaerob (Pe-
nisilin G, Kloramfenikol, Metronidazole).
6
Tindakan pembedahan.
Pengobatan suportif dan simtomatik.
KEPUSTAKAAN
1. Gilroy J, Meyer JS. Medical Neurology, 3rd Ed. New York : Mc Milian
Co, 1979; 387 - 444.
2. Sahs AL, Joynt RJ. Bacterial Meningitis. In Baker AB, Baker LH eds.
Clinical Neurology,Philadelphia : Harper & Row 1981; chap 15,
1 - 90.
3. Hasan M, Troeboes P. Penanggulangan dari tuberkulosa susunan sa-
raf pusat. Simposium Tuberkulosa, Surabaya, 1982.
4. Hendro S. Treatment of Tuberculous Meningitis with Prothionamide-
Isoniazid-Ethambutol and Streptomycin regimen, 5th Asian and
Oceanian Congress of Neurology. Manila, 1979.
5. Hendro S dkk. Penyulit Otitis Media Khronika-Mastoiditis Khronika
dalam bidang Neurologi. Kongres Nasional II PNPNCh, Bandung,
1980.
6. De Lauvois J. Antibiotic treatment of abscesses of the central nervous
system. Br Med J 1977; 2 : 985 - 87.
Tumor otak
Tinjauan Kepustakaan
dr. Ny. Herainy Hartono
Bagian Ilmu Penyakit Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RS Dr. Soetomo, Surabaya.
PENDAHULUAN
Di dalam era CT scan dewasa ini, sering kali dibuat diagnosis
penderita sebagai tumor otak. Dan sebagai gambaran umum
disebutkan bahwa kurang lebih 10% tumor pada manusia
mengenai susunan saraf pusat, dimana 80% dari padanya berada
didalam intrakranial dan 20% di medulla spinalis. Tumor
metastasis otak merupakan 20% dari tumor intrakranial.
Penyebab yang pasti belum dapat ditentukan, walaupun
penyelidikan-penyelidikan telah dilakukan. Faktor-faktor yang
diduga sebagai penyebab yaitu : keturunan, sisa-sisa sel em-
brional, perubahan neoplastik, trauma, virus dan bahan-bahan
karsinogenik.
Urutan-urutan frekuensi tumor otak adalah sebagai berikut :
1. Glioma 41%
2. Meningioma 17%
3. Adenoma hipofise 13%
4. Neurilemmoma/neurofibroma 12%
5. Tumor metastasis
6. Tumor pembuluh darah
Mengenai lokalisasi tumor otak, dilaporkan bahwa pada orang
dewasa kebanyakan di daerah supratentorial, sedangkan pada
anak-anak di daerah infratentorial.
Tumor-tumor metastasis otak kebanyakan berasal dari paru,
traktus digestivus, mamma serta ginjal, din-ma 70% terletak di
hemisfir serebri, sedangkan 30% di serebelum dan 70% multipel.
INSIDENSI
Insidensi umur :
Jenis tumor saraf mempunyai kecenderungan untuk ber-
kembang pada golongan umur tertentu. Tumor primer dari
susunan saraf pusat yang berasal dari jaringan embrional ba-
nyak dijumpai pada umur di bawah 10 tahun, dan jenis tumor
lain berkisar antara umur 20 - 60 tahun. Sedangkan tumor
metastasis otak sebagian besar terdapat pada umur 40 - 70 tahun.
42 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Tumor serebelum lebih sering pada anak-anak dari pada
orang dewasa. Glioma batang otak, praktisnya di Pons lebih
sering dijumpai pada anak-anak.
Berdasarkan pemeriksaan histopatologi tumor, digambarkan
sebagai berikut :
Meduloblastoma, pada dasa warsa I
Pinealoma dan astrositoma serebelum, pada dasawarsa II
Glioblastoma, pada dasa warsa V
Schwannoma, pada dasa warsa V - VI
Insidensi jenis kelamin :
Tumor otak yang banyak dijumpai pada laki-laki, yaitu :
Glioma : astrositoma, glioblastoma dan meduloblastoma
tumor-tumor di regio pineale
Tumor pituitari
Tumor-tumor kongenital
Kordoma
Sedangkan schwannoma dan meningioma lebih sering di-
jumpai pada wanita.
GEJALA KLINIS
Gejala klinis sangat dipengaruhi oleh lokalisasi dan histo-
patologik dari tumor.
Gejala-gejala tersebut dapat digolongkan menjadi :
Gejala umum
Gejala fokal
Gejala umum
Biasanya disebabkan oleh karena tekanan intrakranial yang
meningkat. Kenaikan tekanan intrakranial dapat disebabkan
oleh faktor-faktor :
langsung oleh masa tumor sendiri
edema serebri
obstruksi aliran cairan serebro spinalis
obstruksi sistema vena serebri
gangguan mekanisme absorbsi cairan serebro spinalis
Gejala-gejala ini dapat berupa :
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 43
1. Nyeri kepala
2. Muntah
3. Kejang
4. Gangguan mental
5. Pembesaran kepala
6. Papil edema
7. Sensasi abnormal di kepala
8. Nadi lambat dan tensi meningkat
9. False localizing sign
10. Perubahan respirasi
1. Nyeri kepala :
Merupakan keluhan utama pada kira-kira 20% kasus. Dapat
dirasakan selama perjalanan penyakitnya, dapat umum atau
terlokalisir pada daerah yang berlainan. Sifat nyerinya
digambarkan sebagai nyeri berdenyut atau dirasakan sebagai rasa
penuh di kepala dan seolah-olah kepala mau "meledak
"
.
Timbulnya dimulai pagi hari, dikaitkan oleh karena kenaikan
kadar CO
2
selama tidur. Adanya CO
2
ini menyebabkan aliran
darah serebral meningkat serta kongesti dari sistema vena
serebral. Ini mengakibatkan tekanan intrakranial meningkat.
Nyeri dapat diperhebat dengan gerakan manuver valsava, batuk,
bersin, mengejan, mengangkat barang ataupun ketegangan.
Nyeri intermiten sering didapat pada anak-anak. Gejala ini
mungkin karena hilang atau berkurangnya tekanan intrakranial
dengan jalan pelebaran sutura.
2. Muntah :
Muntah tidak berhubungan dengan lokalisasi tumor, sering
timbul pada pagi hari. Sifat muntah adalah khas, yaitu proyektil
atau muncrat dan tidak didahului rasa mual.
3. Kejang :
Kejang dapat merupakan manifestasi pertama tumor otak pada
15% kasus. Dikatakan, bahwa apabila terjadi kejang fokal pada
orang berumur di bawah 50 tahun, harus dipikirkan adanya
tumor otak, selama penyebab lain belum ditemukan.
Dalam hal terjadinya kejang, lokasi tumor lebih penting
daripada histologinya. Tumor yang jauh dari korteks motoris
akan jarang menimbulkan kejang. Meningioma pada konvek-
sitas otak, sering menimbulkan kejang fokal sebagai gejala dini.
Sedangkan kejang urnum biasanya terjadi, apabila kenaikan
tekanan intrakranial melonjak secara cepat misalnya pada
Glioblastoma multiforme.
4. Gangguan mental :
Gejala gangguan mental tidak perlu dihubungkan dengan
lokalisasi tumor, walaupun beberapa sarjana menyatakan bahwa
gejala ini sering dijumpai pada tumor lobus frontalis dan
temporalis. Juga dikatakan bahwa menigioma merupakan tumor
yang seting menimbulkan gangguan mental.
Gejalanya sangat tidak spesifik. Dapat berupa apatis, de-
mensia, gangguan memori, gangguan intelegensi, gangguan
tingkah laku, halusinasi sampai seperti psikosis.
5. Pembesaran kepala :
Keadaan ini hanya terjadi pada anak-anak, dimana suturanya
belum menutup. Dengan meningkatnya tekanan intrakranial,
sutura akan melebar dan fontanella anterior menjadi
menonjol. Pada beberapa anak sering terlihat pembendungan
vena didaerah skalp dan adanya eksoftalmos. Pada perkusi
terdengar suara yang khas, disebut crack pot signs (bunyi gendi
yang rengat).
6. Papil edema :
Papil edema dapat terjadi oleh karena tekanan intrakranial
yang meningkat atau akibat langsung dari tekanan tumor pada N
II. Derajat papil edema tidak sebanding dengan besarnya tumor
dan tidak sama antara mata satu dan lainnya.
Bila tekanan intrakranial meningkat dengan cepat, akan
terjadi pembendungan vena-vena N. Optikus dan diskus optikus
menjadi pucat serta membengkak. Sering disertai perdarahan-
perdarahan disekitar fundus okuli. Pada papil edema yang kronis
dapat menyebabkan gliosis N. Optikus dan akhirnya N. Optikus
mengalami atrofi sekunder dengan akibat kebutaan.
Dilaporkan bahwa 60% dari tumor otak memperlihatkan
gejala papil edema, dan 50% diakibatkan oleh tumor supra-
tentorial.
7. Sensasi abnormal di kepala :
Banyak penderita merasakan berbagai macam rasa yang
samar-samar. Sering dikeluhkan sebagai enteng kepala (light-
headness), pusing (dizziness) dan lain-lainnya. Keadaan ini
mungkin sesuai dengan tekanan intrakranial yang meningkat.
8. Bradikardi dan tensi meningkat : Keadaan ini dianggap
sebagai mekanisme kompensatorik untuk menanggulangi
iskemia otak.
9. False localizing sign :
False localizing signs dari tumor otak adalah merupakan
gejala yang tidak semuanya berhubungan dengan gangguan
fungsi pada tempat tumor tersebut. Biasanya terlihat sebagai
gejala fokal dari tempat-tempat yang jauh dari tumor itu sendiri.
Misalnya pada. tumor otak yang kecil disertai edema serebri
yang luas, akan memperlihatkan gejala-gejala klinis yang luas.
Sebaliknya tumor besar tanpa disertai edema serebri biasanya
tidak memberikan gejala klinis. Hal-hal inilah yang dapat
membingungkan untuk menentukan lokalisasi tumor. Keadaan-
keadaan tersebut dapat disebabkan oleh karena ada nya edema
serebri atau herniasi.
10. Perubahan respirasi :
Hal ini akibat tekanan intrakranial yang meningkat. Dapat
timbul respirasi tipe Cheyne Stokes, dilanjutkan dengan hiper-
ventilasi-respirasi irreguler-apneu, akhirnya kematian.
Gejala fokal
Gejala-gejala fokal sangat tergantung dengan lokalisasi tumor.
Gejalanya sesuai dengan fungsi jaringan otak yang ditekan atau
dirusak, dapat perlahan-lahan atau cepat. Dapat menimbulkan
disfungsi, misalnya hemiparesis, afasia motorik ataupun paresis
saraf kranial, sebelum tekanan intrakranial meninggi secara
berarti. Dalam hal ini, gejala dan tanda di atas mempunyai arti
lokalisasi/fokal.
Dibawah ini akan diuraikan tentang beberapa gejala dan
manifestasi fokal yang menunjukkan lokasi tumor otak.
Tumor lobus frontalis :
Tumor di daerah ini pada umumnya menimbulkan gang-
guan kepribadian dan mental. Dapat timbul perlahan-lahan,
beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Pada mulanya pende-
rita menjadi apatis, kurang atau hilangnya perhatian/kontrol,
kemudian kesukaran dalam pandangan kedepan (lack of fore
sight), kesukaran dalam pekerjaan dan akhirnya regresi dalam
tingkah laku sosial, kebiasaan dan penampilan, serta gangguan
psikoseksual. Euforia sering dijumpai dan senang berkelakar
(factitiousness) yang dalam beberapa kepustakaan disebut
sebagai
"
witzelsucht
"
.
Gejala fokal lain terjadi bila tumor meluas ke jaringan se-
kitarnya. Bila mengenai bagian posterior di dekat girus sentra-
lis anterior, Pada penderita didapatkan graps refleks (refleks
memegang). Kadang-kadang didapatkan spasme tonik pada
jarijari tangan atau kaki ipsilateral tumor, monospasme, kejang
fokal pada wajah dan transitory post convulsive paralysis
(Todd
'
s paralisis).
Bila mengenai area Broca pada hemisfer dominan dapat ter-
jadi afasia motorik.
Kejang tonik fokal merupakan simtom fokal dari bagian
atas posterior dari lobus frontalis di sekitar daerah premotor.
Bila mengenai traktus kortikospinalis mengakibatkan he-
miparesis sampai hemiplegia dengan tonus meningkat, refleks
meningkat dan adanya ekstensor plantar refleks yang positip.
Semua ini kontralateral lesi.
Bila tumor tumbuh ditengah atau timbul dari groove olfac-
torius, maka biasanya meluas ke posterior dan mengenai N.
Optikus. Pada penderita didapatkan tanda
"
sindroma Foster
Kennedy", yaitu anosmia sesisi lesi akibat tekanan N. I, atrofi
N. II ipsilateral akibat tekanan pada N. II, dan papil edema
kontralateral lesi akibat meningkatnya tekanan intrakranial.
Jika tumor tumbuh didaerah falks serebri setinggi daerah
presentral maka paraparesis inferior akan dijumpai.
Pada tumor lobus frontalis juga dijumpai kurangnya kontrol
sfingter dilanjutkan dengan hilangnya inhibisi kandung ken-
cing dan akhirnya jatuh dalam inkontinensia urine.
Urutan jenis tumor pada lobus frontalis adalah glioma (glio-
blastoma multiforme pada orang dewasa dan astrositoma pada
anak-anak), ependimoma, meningisma disusul kraniofaringio-
masis dan yang jarang adalah glioma dari N. Optikus.
Tumor lobus temporalis :
Lobus temporalis mempunyai ambang yang rendah untuk
timbulnya serangan epilepsi.
Tumor yang menekan atau timbul di Unkus mengakibatkan
uncinate fit yaitu kejang parsiil, yang dapat terjadi beberapa
kali dalam satu hari. Biasanya dimulai dengan halusinasi bau
atau rasa. 80% dengan halusinasi bau busuk dan 20% halu-
sinasi bau bunga. Ini merupakan sensasi yang pertama.
Tumor yang mengenai lobus temporalis dan insula, menim-
bulkan psikomotor epilepsi. Penderita dapat mengalami mo-
vement motoric automatic dengan sengaja. Penderita dapat
berjalan, berlari, menyetir mobil, membuka pakaian atau ben-
tuk-bentuk gerakan lain yang terkoordinir baik selama fase ini.
Biasanya jarang merupakan gerakan-gerakan yang anti sosial
atau agresip, dan bentuknya tetap (stereotype).
44 Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984
Bila tumor mengenai insula, menimbulkan kejang parsiil
dengan keluhan didaerah visera, termasuk nyeri epigastrium,
perasaan fluttering di epigastrik atau toraks.
Tumor pada temporalis posterior, menimbulkan kejang par-
siil. Dimulai dengan halusinasi visual.
Pada medial lobus temporalis, dapat meluas ke daerah basal
ganglia dengan akibat distonia unilateral, korea atetosis dan
tremor.
Pada daerah midtemporal dapat disertai halusinasi pende-
ngaran, berupa suara siulan (whistling), menyiut (hissing) atau
suara bel. Juga didapatkan gejala "dejavu" atau "jamais Vu
"
.
Jenis tumor pada lobus temporalis biasanya glioblastoma
multiforme, astrositoma, oligodendroglioma disusul tumor-
tumor metastasis.
Tumor lobus parietalis :
Tumor di daerah parietalis dapat merangsang korteks sen-
soris, sebelum manifestasi lain dijumpai. Area parietalis ini
berguna untuk diskriminasi tekstur, berat, ukuran, bentuk dan
identifikasi obyek yang diraba. Akibat rangsangan disini ialah
serangan Jackson sensorik. Jika tumor menimbulkan kerusakan
strukturil di daearah ini, maka segala macam perasaan di butuh
kontralateral sisi lesi, tidak dapat dirasakan dan dikenal.
Gangguan dapat berupa astereognosis, atopognosis,
hemianestesia, tidak dapat membedakan kanan atau kiri dan
loss of body image.
Jenis tumor lobus parietalis meliputi glioma, glioblastoma,
astrositoma, oligodendroglioma, meningioma, ependimoma,
tumor-tumor metastasis dan angioma.
Tumor lobus oksipitalis :
Tumor di daerah ini biasanya jarang. Gejala dini yang me-
nonjol sering berupa nyeri kepala di daerah oksipital, kemudi-
an disusul oleh adanya gangguan yojana penglihatan.
Tumor di daerah medial lobus oksipitalis, sering menim-
bulkan kuadrananopsia homonimus inferior kontralateral dan
dapat meluas menjadi hemianopsia homonim.
Tumor di daerah ini jenis glioma, angioma dan tumor-tumor
metastasis.
Tumor serebellum :
Tumor serebellum cepat mengadakan obstruksi aliran cairan
serebro spinalis, sehingga tumor ini cepat menimbulkan te-
kanan intrakranial yang meningkat. Gejala nyeri kepala, mun-
tah dan papil edema sering sebagai gejala dini, disusul dengan
gangguan gait dan gangguan koordinasi. Nyeri kepala dirasa-
kan didaerah oksipital dan dapat menjalar ke leher bawah.
Nyeri menghebat apabila terjadi herniasi tonsila serebellaris.
Gangguan koordinasi dapat diperiksa dengan finger to nose
test; heel to knee test, dan didapatkan disdiadokokinesia. Bila
berjalan akan jatuh ke sisi lesi, Romberg test positip, ataksia,
tremor, nistagmus hipotonia dan scanning speech positip.
Tumor di daerah ini meliputi medulloblastoma, astrositoma,
granuloma tuberkuloma, granuloma luetika dan tumor-tumor
metastasis.
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 45
"
UICC Classification for tumors of the brain and related structures
"
1. Nerve cells :
Ganglioneuroma, gangliocytoma, ganglioglioma
Ganglioneuroblastoma
Malignant ganglioneuroma, malignant gangliocytoma,
malignant ganglioglioma
Sympathicogonioma
Neuroblastoma, sympathicoblastoma.
2. Neuroepithelium :
Ependymoma :
Epthelial ependymoma
Papillary ependymoma
Cellular ependymoma
Malignant ependymoma, ependymoblastoma
Plexus papilloma
Olfactory neuroepithelioma.
3. Eye :
Medulloepithelioma of ciliary epithelium, dyktioma
Neuroepihtelioma, retinoblastoma
4. Glia :
Astrocytoma :
Fibrillary astrocytoma
Gemistocytic astrocytoma
Protoplasmatic astrocytoma
Astrocytoma of the nose, nasal glioma
Oligodendroglioma
Multiform glioblastoma
Polar spongioblastoma
Medulloblastoma
5. Peripheral and cranial nerves :
Neurinoma, neurolemmoma, schwannoma
Neurofibroma
Malignant neurinoma, malignant neurolemmoma,
malignant schwannoma
6. Meningens :
Meningioma
Epitheloid meningioma,
ngioma, endotheliomatous meningioma Fibroblastic
meningioma, fibromatous meningiom
a
Psammomatous
7. Vascular structure of central nervous system :
Hemangioma of cerebellum
Von Hippel-Lindau disease
8. Parapanglia :
Noncromaffm paraganglioma included, carotid body
tumor, glomus caroticum tumor
Chemodectoma
9. Pineal gland :
Pinealoma
10. Hypophysis :
Chromophobe adenoma : Diffuse
chromophobe adenoma Sinusoidal
chromophobe adenoma
Papillary chromophobe adenoma
Oxyphil adenoma, eosinophil adenoma, papillary
Basophil adenoma
Craniopharyngioma, adamantinoma of ductus,
craniopharyngeus
Chromophobe carcinoma.
meningotheliomatousmeni-
Di atas adalah kutipan kaasifikasi tumor otak berdasarkan "
Unio Internarnationalis Contra Cancrum" (UICC).
PROSEDUR DIAGNOSIS
Menegakkan diagnosis tumor otak secara klinis tidaklah be- .
gitu sulit, terutama apabila penderita menunjukkan trias gejala,
berupa nyeri kepala; muntah dan pada pemeriksaan didapatkan
papil edema. Namun sering kali beberapa tumor otak, hanya
menunjukkan gejala gangguan mental sebagai gejala
permulaan. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan
fisik, masih diperlukan beberapa pemeriksaan tambahan,
dimulai cara nontraumatik sampai yang traumatik.
1. X-foto tengkorak
Pemeriksaan ini dapat memperlihatkan :
a. Kalsifikasi intrakranial :
pada tumor otak kira-kira 10% mengalami kalsifikasi.
insidensi kalsifikasi tertinggi terjadi pada Kraniofaringi-
oma dan Oligodendroglioma.
b. Displacement calcif ied pineal gland :
Glandula pineale sering mengalami kalsifikasi pada orang
dewasa berupa suatu struktur di garis tengah yang tidak akan
berpindah ke lateral lebih dari 3 mm pada gambaran foto
tengkorak AP. Pergeseran lebih dari 3 mm sebagai indikasi
adanya tumor otak.
c. Tanda-tanda tekanan intra kranial yang meningkat :
Tanda paling dini dari kenaikan tekanan intrakranial
adalah dekalsifikasi prosessus klinoideus posterior, di-
lanjutkan dengan perubahan yang serupa di lantai dorsum
sella tursika. Pada jangka waktu yang lama, keadaan ini
dapat mengakibatkan lantai dorsum sella mengembung,
hilang atau rusak. Juga dapat disebabkan karena ekspansi
adenoma hipofise atau tumor-tumor disekitar sella tursika.
Impresio digiti.
Pelebaran sutura pada anak-anak.
d. Pembentukan tulang baru (Hyperostosis) :
Pada meningioma kira-kira 40% memperlihatkan gambaran
hiperostosis, terutama didaerah pterion, tuberkulum sella,
serebelepontin dan fosa kranii media. Sedangkan tumor jenis
lain sering pada daerah dasar tengkorak.
e. Destruksi tulang :
Kira-kira 10% meningioma menunjukkan penipisan
tulang. Dapat disebabkan karena infiltrasi tumor pada
tulang atau karena erosi tulang disebabkan tekanan dari
tumor yang tumbuh perlahan-lahan.
Kista epidermoid kadang-kadang dapat ditunjukkan
dengan adanya area yang mengalami destruksi.
2. X-foto toraks : Banyak tumor metastase otak berhubungan
dengan adanya lesi primer di paru.
3. "Computerized Tomography,Scan" (CT scan) :
Merupakan pemeriksaan yang nontraumatik dan dapat
mendeteksi adanya tumor otak kira-kira 95%.
4. "Electroencephalography" (EEG) :
Tumor pada hemisfer serebri, sering memberi gambaran EEG
abnormal pada 75 - 85% kasus. Sedangkan tumor pada fosa
posterior sering tidak memberikan kelainan EEG.
Tumor otak sendiri tidak memberi aktifitas listrik abnormal.
Hanya neuron-neuron yang membuat ini dan neuron-neuron pada
daerah dekat tumor menjadi abnormal sedemikian rupa sehingga
"hypersynchronisation" dari pelepasanpelepasan listrik dari
beribu-ribu atau berjuta-juta sel saraf membentuk gelombang
lambat atau gelombang runcing (spike) pada EEG. Mungkin
tumor ini memberi kelainan metabolik neuron-neuron
didekatnya, dengan tekanan langsung tumor, edema atau dengan
merusak enervasi darahnya. Edema serebri mungkin adalah
mekanisme yang paling penting.
5. Lumbal pungsi (LP) :
Penggunaan LP untuk metidiagnosis adanya tumor otak,
sudah banyak ditinggalkan. Lagi pula cara ini harus dikerjakan
pada indikasi yang tepat. L.P. masih tetap digunakan pada
dugaan adanya meningeal carcinomatosis, granuloma kronis atau
adanya dugaan proses desak ruang yang dengan pemeriksaan CT
scan negatip.
6. Arteriografi :
Dewasa ini pemeriksaan CT scan telah mendesak arteriog-
rafi. Arteriografi dapat memberikan tambahan dimensi tumor
otak dan serial arteriografi dapat membantu menggambarkan
mengenai blood supply dari tumor.
Tumor dari kelompok meningioma biasanya sangat vaskuler
(banyak pembuluh darah) dan sering menimbulkan pembesaran
pada pembuluh darah arteri yang diinervasi. Gambaran yang khas
pada meningioma adalah adanya pembuluh darah yang
menginervasi tumor oleh cabang-cabang dari sistim karotis
eksterna. Arteriografi juga membantu adanya dugaan proses
tumor di fosa posterior, tumor kecil di batang otak atau
neurilemmoma akustikus yang tidak tampak pada CT scan
.
7. Pneumoensefalografi dan Ventrikulografi :
Dapat menunjukkan paling jelas tumor intra ventrikuler dan
tumor yang letaknya dalam dekat pada ventrikel, atau
mengadakan invasi pada struktur di garis tengah (invading mid
line structures).
46 Cermin Dania Kedokteran No. 34, 1984
PENGOBATAN
Pengobatan tumor otak pada umumnya membutuhkan
intervensi dari bidang bedah saraf. Makin dini diagnosa dite-
gakkan dan makin mudah dicapai lesinya, makin baik hasilnya.
Pada prinsipnya pengobatan meliputi pengelolaan/penurunan
dari tekanan intrakranial, tindakan operatif, pemberian radiasi
dan obat-obat khemoterapi.
PROGNOSIS
Pada umumnya prognosis ditentukan oleh faktor keganasan
dan lokalisasi dari tumor otak.
Makin ganas jenis tumor seperti glioblastoma atau medulo-
blastoma prognosisnya makin buruk dan tidak tergantung dari
letak tumor. Sebaliknya tumor-tumor yang timbulnya perlahan
seperti meningioma, relatif memberikan prognosis yang lebih
baik. Disamping itu, tumor-tumor yang terletak di bagian yang
sukar dicapai akan memberikan prognosis yang kurang baik.
Demikian juga dengan tumor-tumor metastasis akan
memberikan prognosis yang jelek.
KEPUSTAKAAN
1. Ausman JI. Intracranial neoplasms. In : Baker AB & Bakker LB.
Rived ed. Vol I Chap Clinical neurology. Philadelphia:Harper &
Row Publ. 1981; pp. 6 - 103.
2. Chusid JG. Correlative neuroanatomy and functional neurology 17
th
ed.
Mauzen Asia (ptc) Ltd, 1979.
3. De Jong RN. The Neurologic Examination 4
th
ed. Hagertown, Ma-
ryland, New York, London : Harper Row Publ. 1979.
4. Gilroy J & Meyer IS. Tumor of the central nervous system. In: Me-
dical Neurology 2
nd
ed., Mac Milian Pub Co, 1975; pp. 591 - 645.
5. Merrit HH. Tumors in a Textbook of Neurology. 5
th
Ed. Tokyo:
Igaku Shoin Ltd 1973; pp. 377 - 388.
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 47
Ketulian : Pemeriksaan dan Penyebabnya
dr. MS Wiyadi
Bagian Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga/RS Dr. Soetomo, Surabaya
PENDAHULUAN
Yang dimaksud "ketulian" disini adalah sama dengan "ku-
rang pendengaran", yang dalam buku-buku ditulis deafness atau
hearing loss.
Di dalam buku pedoman praktis penyelenggaraan sekolah
luar biasa Departemen P dan K, kata
"
tuli" menggambarkan
adanya kekurangan pendengaran 70 db atau lebih pada telinga
yang terbaik.
l
Dalam tulisan ini antara kata-kata
"
ketulian",
"kurang pendengaran" dan
"
tuli" mempunyai arti yang hampir
sama.
Secara garis besar ketulian dibagi menjadi dua. Ketulian
dibidang konduksi atau disebut tuli konduksi dimana kelainan
terletak antara meatus akustikus eksterna sampai dengana tulang
pendengaran stapes. Tuli di bidang konduksi ini biasanya dapat
ditolong dengan memuaskan, baik dengan pengobatan atau
dengan suatu tindakan misalnya pembedahan.
Tuli yang lain yaitu tuli persepsi (sensori neural hearing-
loss) dimana letak kelainan mulai dari organ korti di koklea
sampai dengan pusat pendengaran di otak. Tuli persepsi ini
biasanya sulit dalam pengobatannya.
Apabila tuli konduksi dan tuli persepsi timbul bersamaan,
disebut tuli campuran.
Untuk mengetahui jenis ketulian diperlukan pemeriksaan
pendengaran. Dapat dari cara yang paling sederhana sampai
dengan memakai alat elektro-akustik yang disebut audiometer.
Dengan menggunakan audiometer ini jenis ketulian dengan
mudah dapat ditentukan.
Maksud dari tulisan ini adalah untuk memberi pengertian
yang lebih mendalam tentang ketulian.
PEMERIKSAAN PENDENGARAN
2
Dengan melakukan pemeriksaan pendengaran kita dapat
mengetahui :
Apakah seseorang kurang pendengaran atau tidak.
Sifat ketuliannya, tuli konduksi ataukah tub persepsi.
Derajat ketuliannya atau besar kekurang pendengarannya.
Dengan diketahui sifat ketulian berarti diketahui pula letak
kelainan, sehingga dapat ditentukan apakah perlu tindakan
operasi, pemberian obat-obatan saja atau hanya dapat
ditolong oleh Alat Pembantu Mendengar (APM) atau hearing
aid.
Macamnya tes pendengaran yaitu :
Tes yang paling sederhana ialah tes suara bisik dan perca-
kapan (
"
konversasi").
Tes dengan garpu suara.
Di klinik yang maju dipergunakan alat elektro-akustik yaitu
tes dengan audiometer dan,
Tes dengan Impedance meter.
1. Tes suara bisik
Caranya ialah dengan membisikkan kata-kata yang dikenal
penderita dimana kata-kata itu mengandung huruf lunak dan
huruf desis. Lalu diukur berapa meter jarak penderita dengan
pembisiknya sewaktu penderita dapat mengulangi kata-kata yang
dibisikan dengan benar. Pada orang normal dapat mendengar
80% dari kata-kata yang dibisikkan pada jarak 6 s/d 10 meter.
Apabila kurang dari 5 - 6 meter berarti ada kekurang
pendengaran. Apabila penderita tak dapat mendengarkan kata-
kata dengan huruf lunak, berarti tuli konduksi. Sebaliknya bila
tak dapat mendengar kata-kata dengan huruf desis berarti tuli
persepsi.
Apabila dengan suara bisik sudah tidak dapat mendengar dites
dengan suara konversasi atau percakapan biasa. Orang normal
dapat mendengar suara konversasi pada jarak 200 meter.
2. Tes Garpu Suara
Dengan garpu suara frekuensi 64, 128, 256, 512, 1024, 2048
dan 4096 hz, dibunyikan dengan cara tertentu lalu disuruh
mendengarkan pada orang yang dites. Bila penderita banyak tak
mendengar pada frekuensi rendah berarti tuli konduksi. Bila
banyak tak mendengar pada frekuensi tinggi berarti tuli
persepsi.
Kemudian dengan garpu suara frekuensi 256 atau 512 hz
dilakukan tes-tes Rinne, Weber dan Schwabach sehingga lebih
jelas lagi apakah tuli penderita dibagian konduksi atau persepsi.
3. Tes dengan Audiometer
Hasil dari tes pendengaran dengan audiometer ini digambar
dalam grafik yang disebut audiogram. Apabila pemeriksaan
dengan audiometer ini dilakukan, tes-tes suara bisik dan garpu
suara tak banyak diperlukan lagi, sebab hasil audiogram lebih
lengkap. Dengan audiometer dapat dibuat 2 macam audio-gram :
Audiogram nada murni (pure tone audiogram)
Audiogram bicara (speech audiogram)
Dengan audiometer dapat pula dilakukan tes-tes :
tes SISI (Short Increment Sensitivity Index), tes Fowler
dimana dapat diketahui bahwa kelainan ada di koklear atau
bukan.
tes Tone Decay dimana dapat diketahui apakah kelainan
dibelakang koklea (retro cochlear) atau bukan. Kelainan retro
coklear ini misalnya ada tumor yang menekan N VIII
Keuntungan pemeriksaan dengan audiometer kecuali dapat
ditentukan dengan lebih tepat lokalisasi kelainan yang me-
nyebabkan ketulian juga dapat diketahui besarnya ketulian
yang diukur dengan satu db (desibel).
4. Tes dengan
"
Impedance
"
meter
Tes ini paling obyektif dari tes-tes yang terdahulu. Tes ini
hanya memerlukan sedikit kooperasi dari penderita sehingga
pada anak-anak di bawah 5 tahun pun dapat dikerjakan dengan
baik. Dengan mengubah-ubah tekanan pada meatus akustikus
ekterna (hang telinga bagian luar) dapat diketahui banyak
tentang keadaan telinga bagian tengah (kavum timpani). Dari
pemeriksaan dengan Impedancemeter dapat diketahui :
Apakah kendang telinga (membrana timpani) ada lobang
atau tidak.
Apakah ada cairan (infeksi) di dalam telinga bagian tengah?
Apakah ada gangguan hubungan antara hidung dan telinga
bagian tengah yang melalui tuba Eustachii.
Apakah ada perlekatan-perlekatan di telinga bagian tengah
akibat suatu radang.
Apakah rantai tulang-tulang telinga terputus karena kece-
lakaan (trauma kepala) atau sebab infeksi.
Apakah ada penyakit di tulang telirigastapes (otosklerosis).
Berapa besar tekanan pada telinga bagian tengah.
DERAJAT KETULIAN
3-7
Untuk mengetahui derajat ketulian dapat memakai suara bisik
sebagai dasar yaitu sebagai berikut :
Normal bila suara bisik antara 5 - 6 meter
Tuli ringan bila suara bisik 4 meter
Tuli sedang bila suara bisik antara 2 - 3 meter
Tuli berat bila suara bisik antara 0 - 1 meter.
Apabila yang dipakai dasar audiogram nada murni, derajat
ketulian ditentukan oleh angka rata-rata intensitas pada fre-
kuensi-frekuensi 500, 1000 dan 2000 Hz yang juga disebut
48 Cermin Dunia Kedokteran No. 34. 1984
speech frequency. Konversasi biasa besarnya kurang lebih 50 db.
Derajat ketulian berdasar audiogram nada murni adalah sebagai
berikut :
Normal antara 0 s/d 20 db.
Tull ringan antara 21 s/d 40 db.
Tull sedang antara 41 s/d 60 db.
Tull berat antara 61 s/d 80 db.
Tull amat berat bila lebih dari 80 db.
PENYEBAB KETULIAN
8-10
Penyebab tuli konduksi
1. Pada meatus akustikus eksterna : cairan (sekret, air) dan
benda asing, polip telinga).
2. Kerusakan membrana timpani : perforasi, ruptura, sikatriks.
3. Dalam kavum timpani : kekurangan udara pada oklusio tuba,
cairan (darah atau hematotimpanum karena trauma kepala,
sekret pada otitis media baik yang akut maupun yang kronis),
tumor.
4. Pada osikula : gerakannya terganggu oleh sikatriks, meng-
alami destruksi karena otitis media, oleh ankilosis stapes pada
otosklerosis, adanya perlekatan-perlekatan dan luksasi karena
trauma maupun infeksi, atau bawaan karena tak terbentuk
salah satu osikula.
Penyebab tuli persepsi
Periode prenatal
1. Oleh faktor genetik
2. Bukan oleh faktor genetik.
Terutama penyakit-penyakit yang diderita ibu pada ke-
hamilan trimester pertama (minggu ke 6 s/d 12) yaitu pada
saat pembentukan organ telinga pada fetus. Penyakit-
penyakit itu ialah rubela, morbili, diabetes melitus, nefritis,
toksemia dan penyakit-penyakit virus yang lain.
Obat-obat yang dipergunakan waktu ibu mengandung
seperti salisilat, kinin, talidomid, streptomisin dan obat-
obat untuk menggugurkan kandungan.
Periode perinatal
Penyebab ketulian disini terjadi diwaktu ibu sedang melahirkan.
Misalnya trauma kelahiran dengan memakai forceps, vakum
ekstraktor, letak-letak bayi yang tak normal, partus lama. Juga
pada ibu yang mengalami toksemia gravidarum. Sebab yang lain
ialah prematuritas, penyakit hemolitik dan kern ikterus.
Periode postnatal
1. Penyebab pada periode ini dapat berupa faktor genetik atau
keturunan, misalnya pada penyakit familiar perception
deafness.
2. Penyebab yang bukan berupa faktor genetik atau keturunan:
Pada Anak-anak :
a. Penyakit-penyakit infeksi pada otak misalnya meningitis
dan ensefalitis.
b. Penyakit-penyakit infeksi umum : morbilli, varisela,
parotitis (mumps), influenza, deman skarlatina, demam
tipoid, pneumonia, pertusis, difteri dan demam yang tak
diketahui sebabnya.
c. Pemakaian obat-obat ototoksik pada anak-anak.
Pada orang dewasa :
a. Gangguan pada pembuluh-pembuluh darah koklea, dalam
bentuk perdarahan, spasme (iskemia), emboli dan trombosis.
Gangguan ini terdapat pada hipertensi dan penyakit jantung.
b. Kolesterol yang tinggi : Oleh Kopetzky dibuktikan bahwa
penderita-penderita tuli persepsi rata-rata mempunyai kadar
kolesterol yang tinggi dalam darahnya.
c. Diabetes Melitus : Seringkali penderita diabetes melitus tak
mengeluh adanya kekurangan pendengaran walaupun kalau
diperiksa secara audiometris sudah jelas adanya kekurang
pendengaran. Sebab ketulian disini diperkirakan sebagai
berikut :
Suatu neuropati N VIII.
Suatu mikroangiopati pada telinga dalam (inner ear).
Obat-obat ototoksik. Penderita diabetes sering ter-
kena infeksi dan lalu sering menggunakan antibiotika
yang ototoksik
d. Penyakit-penyakit ginjal : Bergstrom menjumpai 91 kasus
tuli persepsi diantara 224 penderita penyakit ginjal.
Diperkirakan penyebabnya ialah obat ototoksik, sebab
penderita penyakit ginjal mengalami gangguan ekskresi obat-
obat yang dipakainya.
e. Influenza oleh virus. Oleh Lindsay dibuktikan bahwa sudden
deafness pada orang dewasa biasanya terjadi bersama-sama
dengan infeksi traktus respiratorius yang disebabkan oleh
virus.
f. Obat-obat ototoksik : Diberitakan bahwa bermacam-macam
obat menyebabkan ketulian, misalnya : dihidrostreptomisin,
salisilat, kinin, neomisin, gentamisin, arsenik, antipirin,
atropin, barbiturat, librium.
g. Defisiensi vitamin. Disebut dalam beberapa karangan, bahwa
defisiensi vitamin A, B1, B kompleks dan vitamin C dapat
menyebabkan ketulian.
h. Faktor alergi. Diduga terjadi suatu gangguan pembuluh
darah pada koklea.
i. Trauma akustik : letusan born, letusan senjata api, tuli karena
suara bising.
j. Presbiakusis : tuli karena usia lanjut.
k. Tumor : Akustik neurinoma.
1. Penyakit Meniere
m. Trauma kapitis.
Psikogen
Ketulian psikogen dapat :
simulated (malingering)
fungsional (histeri)
Tak diketahui sebabnya (unknown)
Arnvig memberitakan bahwa 21,1% dari kasus-kasusnya tak
diketahui sebabnya. Menurut Harrison dan Livingstone besarnya
30%, menurut Fraser 38% dari 2355 kasus dan menurut Maran 28%
dari 464 kasus. Penulis sendiri menemukan 40,4%
dari 5556 kasus di seksi audiologi bagian THT RS Dr. Soetomo.
RINGKASAN
Telah dibicarakan pengertian tentang ketulian, pemeriksaan
pendengaran, derajat ketulian dan penyebab ketulian baik di
bagian konduksi maupun persepsi.
KEP US TAKAAN
1. Hendarmin H. Sebab Tuna Rungu di Indonesia. Kumpulan Naskah
Kongres Nasional V Perhati di Semarang 27 - 29 Oktober 1977;
hal 152.
2. Wiyadi MS. Beberapa Macam Test Pemeriksaan Pendengaran.
Airlangga. Pers Kampus Universitas Airlangga. Edisi Desember
1979, hal 5.
3. Katz J. Handbook of Clinical Audiology. Baltimore: The Williams
& Wilkins Co, 1972; p. 79.
4. Sedjawidada R dan Manukbua A. Test Bisik. Kumpulan
Naskah Kongres Nasional V Perhati di Semarang 27 - 29
Oktober 1977; hal 189 - 198.
5. Strome M. Differential Diagnosis in Pediatric Otolaryngology, 1st
ed. Boston : Little, Brown &Co, 1975; p 16.
6. Wiyadi MS dan Iskandar A. Pemeriksaan Pendengaran Pada
Calon Mahasiswa Universitas Airlangga. Konas Perhati ke-VI di
Medan 30 Juni s/d 2 Juli 1980.
7. Zaman M. Kuliah Test Suara Bisik pada Mahasiswa FK Unair
tahun 1975.
8. Maulani HS. Pengobatan Tuli Persepsi dengan Vitamin A.
Karya Untuk Memperoleh ljazah Keahlian THT Fakultas
Kedokteran Unair, 1981.
9. Wiyadi MS. Penyebab Ketulian di Seksi Audiologi Bagian THT
RS Dr. Soetomo/FK Unair 1974 - 1976. Kumpulan Naskah
Kongres Nasional V Perhati di Semarang 27 - 29 Oktober 1977;
hal 124 - 137.
10. Wiyadi MS. Pemeliharaan Pendengaran. Majalah Kedokteran Sura-
baya, 1979; 16 : 44 - 54.
Va, hidungnya mirip ayahnya.
Tapi saya perhatikan matanya
lebih mirip suami saya.
fF~T 1
v d J rY~~
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 49
Rodamin B dan Metanil Kuning ("Metanil
Yellow") Sebagai Penyebab Toksik
Pada Mencit dan Tikus Percobaan
G. Nainggolan Sihombing
Unit Penelitian Gizi Diponegoro
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dep Kes R.I., Jakarta
PENDAHULUAN
Dalam penyelidikan pada tahun 1978, ditemukan bahwa ro-
damin B dan metanil kuning dipakai sebagai pewarna makanan
di Jakarta.
1
Kedua bahan pewarna ini sebenarnya diproduksi
untuk mewarnai kertas, tekstil, kayu dan barang industri non
pangan lainnya.
2
Laporan tentang adanya kasus keracunan ma-
kanan yang mengandung rodamin B atau metanil kuning belum
diperoleh di kepustakaan Jakarta. Berhubung kedua bahan
pewarna ini telah terbukti sering dan banyak digunakan peda-
gang kecil di Jakarta untuk mewarnai makanan kecil dan mi-
numan, maka telah dilakukan percobaan biologik pada mencit
dan tikus putih. Data yang diperoleh kiranya dapat dipergu-
nakan oleh para ilmuwan untuk ditafsirkan pada manusia.
Diharapkan lambat laun masyarakat Indonesia dapat menge-
tahui bahwa rodamin B dan metanil kuning memang berbahaya
bagi kesehatan manusia dan menolak penggunaannya dalam
makanan.
BAHAN DAN METODE
1. Zat pewarna
Rodamin B diperoleh dari PT Krikras Jakarta asal produk
pabrik Ciech Organik B
2
Div Warsawa. (1 gram produk ekiva-
len dengan 210 mg rodamin B murni). Metanil kuning berasal
dari pabrik Imperial Chemical Industry Ltd London, PT Galic
Bina Mada Jakarta. (1 gram ekivalen dengan 435 mg metanil
kuning)
1
2. Makanan stok
Makanan stok diperoleh dari Unit Gizi Diponegoro Badan
Litbangkes Dep Kes Jakarta (Addendum 1).
3
Makanan yang dicampur dengan rodamin B (untuk perco-
baan I dan II) : 1 gram bahan pewarna rodamin B dicampur
dengan 3 kg makanan stok. Kadar rodamin B dalam makanan
*) Ringkasan naskah Ceramah Ilmiah di PT Kalbe Farma, Jakarta tanggal
22 Februari 1983.
50 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
ini adalah 7 mg per 100 gram.
Makanan yang dicampur dengan metanil kuning (untuk per-
cobaan I) : 1 gram bahan pewarna metanil kuning dicampur
dengan 3kg makanan stok. Kadar metanil kuning dalam ma-
kanan ini adalah 14,5 mg per 100 gram.
3. Hewan Percobaan
Mencit dan tikus putih sapihan diperoleh dari Unit Gizi
Diponegoro, Badan Litbangkes, Dep Kes, Jakarta.
4. Perlakuan hewan percobaan
Percobaan I
Delapan belas ekor mencit dibagi menjadi 3 grup, yang ma-
sing-masing terdiri dari 6 ekor. Grup I diberi makan stok yang
dicampur dengan rodamin B. Grup II diberi makanan stok yang
dicampur dengan matanil kuning. Grup III diberi makanan stok
saja dan dipakai sebagai grup kontrol. Semua hewan diberi
makan dan minum ad libitum selama 16 minggu (Tabel 1).
Percobaan II
Grup A (percobaan) dimulai dari seekor tikus jantan dan 2
ekor tikus betina yang berumur 3 bulan untuk dikawinkan se-
lama 3 hari. Kemudian ke dua ekor tikus betina itu dipisahkan
selama masa hamil sampai dekat pada hari melahirkan. Setelah
beranak, anak-ananya dibiarkan tetap bersama induknya sampai
umur 3 bulan. Pada umur ini dipilih secara acak 6 ekor anak
jantan dan 6 ekor anak betina untuk dipergunakan sebagai 6
pasang parent stok (FI). Sisa anak yang tidak terpakai dibuang
dan ke 6 parent stok (keturunan grup A) ini kemudian
dikawinkan. Dari hasil perkawinan dipilih lagi secara
acak 6 ekor anak jantan dan 6 ekor betina yang kemudian di-
pasangkan untuk dikawinkan (F2). Demikianlah seterusnya di-
lakukan sampai dengan generasi ke-6 (F6) (tabel 2). Semua ti-
kus mulai dari FI sampai F6 dari keturunan grup A ini diberi
makanan campuran dengan rodamin B selama 12 bulan.
Grup B (kontrol) juga dimulai dari seekor tikus jantan yang
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 51
ADDENDUM 1
dikawinkan dengan 2 ekor tikus betina berumur 3 bulan. Perlakuan
selanjutnya sama seperti pada grup A, untuk memperoleh 6 generasi (
F1 - F6). Kemudian pasangan F1 dari grup B (kontrol) merupakan
counter
.
part dari F1 grup A (percobaan). Demikian seterusnya
pasangan-pasangan F2 sampai dengan F6. Grup B menjadi counter
part masing-masing dari pasangan F2 sampai dengan F6 grup A (
percobaan). Semua tikus dari semua generasi grup B hanya diberi
makanan stok selama 12 bulan dan dipergunakan sebagai grup kontrol.
HASIL
Percobaan I
Mencit yang diberi makanan yang dicampur
dengan rodamin B dan metanil kuning selama 16
minggu. Pada grup rodamin G gejala menyolok
adalah bulu-bulu menjadi kasar dan pertumbuhan
badan terlambat kalau dibandingkan dengan
kelompok kontrol. Mata dan air seninya
berfluoresensi bila kena sinar matahari. Hewan-
hewan nampak aktif sadar. Pada minggu ke-7
mereka umumnya gelisah, sering menggaruk-garuk
badannya sehingga mendapat luka-luka dibe-
berapa tempat bagian tubuhnya (Gambar 1). Pada
minggu ke-8 keaktifan mereka mulai berkurang dan
geraknya lambat dan malas. Pada minggu ke-10
ditemukan seekor mencit mati (Tabel 1).
Pada kelompok mencit yang diberi meta-nil
kuning, pertumbuhan badan juga terlambat (lihat
Grafik), tetapi mereka aktif dan sadar. Di antara 6
ekor mencit ditemukan 2 ekor yang menderita
megalosefali (Gambar 2), dan 2 ekor lainnya
mendapat pembengkakkan pada ke dua kaki
depannya. Seperti halnya kelompok rodamin B,
pok metanil kuning pun mulai bergerak lam-ban
pada minggu ke-8 dan ke-9 masing-masing
ditemukan seekor mencit mati (Tabel 1).
Pada otopsi dari ke tiga ekor mencit yang mati (
1 ekor dari grup rodamin B dan 2 ekor dari grup
metanil kuning), hanya menunjukkan keadaan gizi
yang jelek dimana semua deposito lemak di dalam
tubuhnya habis sama sekali.
Sisa mencit grup 1 yang berjumlah 5 ekor
dibunuh pada akhir minggu ke-16. Pada hati seekor
mencit ditemukan 1 bungkul tumor hapatoma
dengan ukuran 0,5 x 0,5x 0,25 cm yang terletak
pada lobus hepatis dekstra.
Sisa mencit yang berjumlah 4 ekor dari grup II
dibunuh pada akhir minggu ke-16 juga. Dua ekor
diantaranya mengalami perubahan ginjal (ginjal
kistik). Terlihat jelas bahwa bagian pielum meluas
dan bagian korteks menipis.
Percobaan II
Enam pasang tikus selama 6 generasi diberi makanan yang
dicampur dengan rodamin B (Tabel2).
Gejala klinik yang nyata adalah perubahan warna yang menjadi
kemerah-merahan pada kulit dan ekor (mungkin kena sentuhan
makanan berwarna setiap hari atau mungkin konsentrasi rodamin B di
dalam darahnya lebih tinggi dari biasanya). Bola mata, air mata, dan air
seni mereka juga kemerahan-merahan, air seninya berfluoresensi kalau
kena sinar ma-
"COMPOSITION OF PREPARED STOCKDIETS FOR ALBINO - RATS, STRAIN L.M.R."
Basic
Foodstuff
Protein
%
Fat
%
Weight
in kg
Weight
in%
1. Rice
2. Soybean, boiled, dried
3. Peanut, chelled, fried
4. Skim milk powder, high quality
5. Coconut-oil
6. Kitchensalt
7. Bonemeal
8. Vit. B-complex tablet *
9. Vit. A + D
3
in starch **
10. Ferri - citrate
7.0
40
27
35
-
-
-
1
18
44
-
100
-
-
10.0
4.5
1.5
2.0
250 ml
0.15
0.075
30 tab.
+
+
54.3
24.4
8.1
10.8
1.3
0.8
0.4
+
+
+
18.4 kg 100%
Average Composition
as calculated : Crude Protein 19.6 %
Total Fat 9 %
Total Energy 370 Cals. %
NPU-standard 60
NPU-operative 50
as analysed : Crude Protein 20.3 %
For Comparison
: Composition of Purina Laboratory Chow :
(Ralston Purina Co St Louis, USA).
Crude Protein 23.0 %
Nitrogen free extract 50.6 %
Crude fat 5.8 %
Crude fibre 4.9 %
Ash 7.7 %
* B-complex, ** Rovimix A + D
3
Type 500/100 Roche :
Each table contains : 1 gram contains 500.000 IU Vit. A +
Thiamin HO 3 mg 100.000 IU Vit. D
Riboflavin 2 mg 12
5
grams Rovimix to 400 grains of starch
Pyridoxin HCl 0.5 mg For 18.4 kg of food use 8 grams of
Calcium pantothe- (Starch + Rovimix).
nate 2 mg (equiv. to 0.25 g Rovimix).
Nicotinamide 10 mg
Sumber Unit Gizi Diponegoro - Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, De-
partemen Kesehatan.
Kompleks Nutrition Centre, Seameo Tropmed - U.I.
Salemba 4 (Kampus U.l.) Jakarta.
October 1978
Tabel 1
Percobaan II : Disain percobaan dengan mencit, jumlah kematian dan jenis kelainan patologi pada mencit yang
diberi makanan yang dicampur rodamin B dan metanil kuning.*
Grup
Jenis
Makanan
Jumlah
Mencit
pada
permulaan
Jumlah kematian
Mencit pada
minggu ke
Jumlah
Total
Kelainan Patologi
Keterangan
_
VIII IX X Hati
Ginjal
I Rodamin B 6 0 0 1
1 1** 0 Hepatoma
(1 ekor)
H Metanil
kuning
6 1 1
0 2 0 2** Ginjal kistik
(2 ekor)
III Kontrol 6 0 0 0
0 0 0
Lama percobaan 16 minggu
Kandungan bahan pewarna rodamin B (tidak murni) adalah 1 gram (ekivalen dengan 7 mg) per 100 gram
stokdiet.
Kandungan bahan pewarna metanil kuning (tidak murni) adalah 1 gram (ekivalen dengan 14.5 mg) per 100
gram stokdiet.
** Kelainan patologi ditemukan pada mencit yang dibunuh pada akhir minggu.
Grafik : Perobahan berat badan mencit yang diberi masing masing dari
rodamin B dan metanil kuning dalam diet selama 16 minggu (
persen dari berat badan semula).
Kontrol
Metanil
kuning
Rodamin B
Diet &
pemberian
1 gram
per 3
1 gram
mg)
malcan
rodamin B (
ekuiv.
kg stokdiet
metanil kuning
per 3 kg stokdiet
dan minum ad.
210 mg)
(ekuiv. 435
libitum
Gambar 1 : Mencit yang mendapat benjolan dan luka pada kaki kanan,
karena pemberian rodamin B dalam diet pada percobaan
selama 16 minggu.
200
150
100
50
t
%
1 2 3 4
0
Bulan
52 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Gambar 2 : Mencit yang memperoleh metanil kuning dalam diet selama 16
minggu, menderita megalosefali pada minggu ke 10.
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 53
Tabel 2
Percobaan II : Jumlah tikus-tikus yang mati dan yang mendapat tumor pada pengamatan selama 6 minggu dengan pemberian makan-
an yang mengandung 7 mg Rodamin B murni dalam 100 gram diet selama 12 bulan, setiap generasi (F) terdiri dari 6 pa-
sang hewan.
Jumlah kematian dan Jumlah Tumor yang
Jumlah
Generasi Jumlah ditemukan pada bulan ke
ke
d
Jumlah
tikus
masmg
- Total
Kem
tal
Keterangan
(F)
mas
i
ng
I II III N V VI VII VIII IX X XI XII
F- 1 9 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2* 2 1 0 0 5 * Ditemukan
limfoma
F- i 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
6
pada 1 ekor
tikus
F-2
9
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1* 1 1 1 4
d
6 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4
F-3 9 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4
12
d
6 0 0 0 0 0 0 0 0 2* 0 0 0 0 4
F-4 9 6 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 3
12
d
6 0 0 0 0 0 2 2* 0 0 0 0 0 0 4
F-5 9 6 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
12
d
6 0 0 0 0 0 0 0 0 2* 0 1 0 0 3
F-6 9 6 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 2
12
d
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Catatan ; Pada kelompok kontrol tidak ada yang mati
Pada kelompok kontrol tidak ada pertumbuhan tumor
tahari. Tubuhnya rata-rata lebih kecil bila dibandingkan de-
ngan hewan kontrol (Gambar 3), akan tetapi semua hewan
menjadi aktif, malah banyak yang galak, agresif dan kanibal.
Tikus-tikus umumnya mengalami diare sebelum mati, dan yang
mati kemudian dimakan oleh tikus-tikus yang masih hidup dan
aktif. Mulai bulan ke-10 banyak tikus mengalami kerusakan
tubuh (Gambar 4).
Angka kematian pada generasi pertama cukup tinggi, akan
Gambar 3 : Perbedaan besar tubuh tikus yang diberi rodamin B dalam diet
dengan kontrol pada penelitian selama 12 bulan.
Gambar 4 Tikus yang mengalami kerusakan tubuh pada pemberian
rodamin B dalam diet pada penelitian selama 12 bulan.
tetapi makin lama pada generasi berikutriya menjadi makin
berkurang (Tabel 2).
Pada otopsi, ditemukan tumor limfoma masing-.masing 1
ekor pada Fl, F2, F3, F4, F5 dan F6 (Tabel 2). Waktu yang
diperlukan untuk menimbulkan tumor limfoma antara 6 sampai
9 bulan. Limfoma yang sering ditemukan berada pada me-
diastinum dan kadang-kadang pada mesenterium. Besarnya
bervariasi dari yang berdiameter 0,25 cm sampai 2,5 cm.
Tikus-tikus dari grup kontrol tidak ada yang mati dan pada
otopsi tidak ditemukan tumbuh ganda di dalam tubuhnya.
Gambar 5 Beginilah label dari kemasan plastik yang berisi bahan pe-
warna "makanan", dijual di pasaran bebas Jakarta. Per-
hatikan "Special Colours fo all Purposes".
Gambar 6 : Bahan pewarna dalam kemasan kaleng, botol, kantong plastik
dijual di pasaran bebas Jakarta sebagai pewarna makanan.
PEMBAHASAN
Data mengenai efek toksik yang diperoleh dari percobaan
bahan pewarna rodamin B dan metanil kuning pada mencit dan
tikus percobaan menimbulkan pertanyaan, apakah keracunan
serupa seperti yang terlihat pada hewan percobaan itu, akan
terjadi juga pada manusia yang sering makan makanan yang
mengandung pewarna rodamin B atau metanil kuning.
Mungkin ada gunanya juga kalau diutarakan di sini, bahwa
pada pembuatan bahan pewarna seperti pembuatan bahan-bahan
kimia organik pada umumnya dibutuhkan proses yang rumit
untuk memperoleh produk yang murni. Ada kalanya
54 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
terbentuk pula produk sampingan yang tidak dikenal sifatnya. Ini
mungkin berbahaya atau tidak berbahaya, tetapi kehadiran zat itu
tidak diinginkan.
4
Rodamin B dibuat dari meta-dietilaminofenol dan ftalik
anhidrid, kemudian diasamkan dengan asam hidroklorid. Kedua
bahan baku ini bukanlah bahan yang boleh dimakan. Se-
lanjutnya asam HC1 yang dipakai tentunya bertingkat "teknis"
dengan kadar logam logam berat yang cukup tinggi. Begitu juga
metanil kuning yang dibuat dari asam metanilat dan dife-
nilamin. Kedua bahan ini toksik. Jadi, dapat kita bayangkan
bahwa di dalam bahan pewarna baik rodamin B maupun meta-
nil kuning, berbagai bahan lain masih ada di dalamnya. Mereka
turut ambil bagian sebagai penyebab toksik tambahan pada
hewan percobaan. Memang kemurnian pewarna rodamin B dan
metanil kuning diusahakan tinggi oleh pabrik pembuatnya, tetapi
karena bahan pewarna ini dimaksudkan untuk mewarnai
sebangsa tekstil, kertas, kayu dan sebagainya, maka kehadiran
logam berat serta produk sampingan lainnya yang dianggap
rendah bagi industri non-pangan sudah cukup tinggi untuk
pewarna makanan.
Kontaminasi dapat pula terjadi dari kemasan bahan pewarna
non pangan yang kurang baik mutunya sehingga menambah
bahaya kesehatan manusia bila menggunakan bahan pewarna ini
untuk makanan.
4,5
KESIMPULAN
Pemberian rodamin B dan metanil kuning dalam diet mencit
dan tikus percobaan mengakibatkan efek toksik pada hewan
tersebut. Ini menegaskan keterangan yang ada dalam ke-
pustakaan, yaitu baik rodamin B maupun metanil kuning adalah
bahan pewarna untuk mewarnai barang-barang non pangan
2
, jadi
tidak dapat ditolerir untuk mewarnai makanan manusia.
Karena masyarakat Indonesia di Jakarta khususnya dan di
Indonesia umumnya memang senang pada makanan yang ber-
warna, maka pengadaan bahan pewarna makanan yang diizin-
kan dengan derajat Food Grade dan memenuhi persyaratan
higine, harus mendapat perhatian instansi pemerintah yang
berwenang c.q. Departemen Kesehatan, Departemen Perda-
gangan dan Departemen Perindustrian. Pengadaan ini hendak-
nya disertai dengan harga yang kompetitif dengan harga pewar-
na non pangan yang sebelumnya diperdagangkan sebagai pe-
warna pangan, sehingga dapat dijangkau masyarakat luas seperti
sediakala.
RINGKASAN
Dua pewarna non-pangan dikenal dengan nama rodamin B
yang memberi efek warna merah jambu, dan metanil kuning
yang memberi warna kuning telor digunakan luas sebagai pe-
warna makanan di Jakarta.
Sebagai bahan non-pangan pada umumnya bila berada di
dalam makanan kemudian dikonsumsi manusia, dapat dira-
malkan akan mengganggu kesehatan dalam jangka waktu pen-
dek atau panjang. Untuk pembuktiannya telah dilakukan per-
cobaan pada mencit dan tikus putih dengan mencampurkan
masing-masing dari kedua bahan pewarna non-pangan tersebut
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 55
ke dalam diet mereka sehari-hari.
Hasil penelitian menguatkan dugaan, bahwa kedua bahan
pewarna non-pangan ini dapat mengganggu kesehatan hewan
percobaan.
Ucapan terima kasih :
Kepada Dr. Iwan T. Budiarso, ahli patologi veteriner pada Puslitbang
Kanker, Badan Litbangkes, Dep Kes R.I., yang telah memberi penilaian
simtom patologi dari penelitian biologik ini.
KEPUSTAKAAN
1. Sihombing G. An Exploratory Study on Three Synthetic Colour-
ing Matters Commonly Used As Food Colours In Jakarta (Thesis),
1978; p. 37 - 82.
2. Fairhall LT. Industrial Toxicology, 2nd. Ed., New York: Hafner
Publishing Company, 1975 ; p. 235 - 236.
3. Unit Penelitian Gizi Diponegoro, Badan Litbangkes Depkes R.I.
Miller DS. Worksheet for Determination of Net Protein Utilisation
using Rats Body N Technique, 1978; p 2.
4. Jacobs MB. The Chemical Analysis of Foods and Food Products, 3rd.
Ed, New York : Robert E. Krieger Publishing Co., Inc. Hung-
tington, 1973; 11743, p. 103 - 105.
5. Imperial Chemical Industries. Edicol Colours for Foodstuffs, Pat-
tern leaflet 113.
Kalender Kegiatan Ilmiah
SECOND INTERNATIONAL CONGRESS on TRADITIONAL ASIAN MEDICINE
Dates : September 2, through September 7, 1984
I. Scientific programe :
Theme of the congress :
Traditional medicine in Asian countries and their place in
pluralistic health care systems.
Main subject areas of the congress :
1. The sources and histories of classical traditions
2. Popular medicine
3. Ethnobotany, ethnopharmacology, and allied subjects
4. Models of integration : problems and chances
5. The social construction of illness experience
6. Clinical and experimental studies of therapeutic practices
7. Primary health care and education of health care workers.
II. Social programme :
Ladies' Programme : traditional Indonesian beauty treatment with traditional drug
and traditional cosmetic.
III. Cultural evening.
Place : Bumi Hyatt Hotel, Jln. Basuki Rachmat 124 - 128.
Phone 031 - 470875, Surabaya .
Secretariat : Faculty of Pharmacy, Airlangga University
J1n. Dharmahusada 47, Surabaya
Phone (031). 43710
Registration fee: For Indonesian participant is : Rp. 50.000,-
and the accompanying person : Rp. 25.000,-
Sent payment to : ICTAM II, Bank Account : BNI 46
branch No. 11.02.090.8000 UNAIR
PERKEMBANGAN
Pengobatan Preleukemia
Istilah "preleukemia" dulu digunakan untuk menggambar-
kan sekelompok kelainan morfologik sel-sel darah yang diiden-
tifikasikan, secara retrospektif, sebagai pendahulu dari leukemia
mieloblastik akut. Sekarang, istilah ini banyak dipakai oleh para
hematolog, secara prospektif, untuk pasien yang diduga
menderita leukemia, dengan prognosis buruk, tapi belum tentu
berakhir sebagai leukemia akut. Perjalanan kliniknya bervariasi.
Cukup banyak penderita meninggal karena kegagalan sumsum
tulang, sebelum penyakitnya sendiri berkembang menjadi
leukemia akut. Gambaran dari sumsum tulang biasanya
hiperseluler; dan karena maturasi sel-sel darah kurang sem-
purna, maka pada darah tepi didapatkan sitopenia. Pada pasien-
pasien tua, atau bila transplantasi sumsum tulang tidak dapat
dilakukan, pengobatan suportif dengan tranfusi darah masih
merupakan pilihan utama. Usaha-usaha penyembuhan dengan
rejimen pengobatan anti-leukemia yang telah dikenal, biasanya
gagal. Juga telah dicoba pemakaian steroid androgen tanpa hasil
yang berarti.
Bagaimana caranya supaya sel-sel neoplastik tadi terinduk-
si hingga berdiferensiasi? Ini akan memperbaiki keadaan darah-
nya. Penemuan cara pembiakan dan "cloning" sel darah, baik
yang normal maupun leukemik, telah membuka jalan untuk
mempelajari beberapa zat kimia yang dapat menginduksi sel.
Pada percobaan in-vitro terbukti perlunya protein induser
supaya sel menjadi dewasa dan viable. Protein-protein ini
dihasilkan oleh beberapa jenis sel seperti fibroblas, limfosit,
makrofag, dan anehnya, ternyata juga dihasilkan oleh sel-sel
mieloid leukemik sendiri. Pada sel leukemia akut, kelainan
fenotip utamanya adalah ketidakmampuannya untuk berdi-
ferensiasi menjadi sel dewasa. Protein induser, penambahan zat-
zat kimia tertentu dan substansi-substansi alamiah seperti asam
retinoat dan metabolit dari vitamin D, semua ini dapat
menginduksi sel-sel leukemik untuk berdiferensiasi. Walaupun
beberapa bahan tadi cukup toksik untuk digunakan dalam klinik,
beberapa lainnya merupakan bahan standar sebagai kemoterapi.
Contohnya ialah sitarabin.
Klon spesifik dari sel-sel leukemik tikus akan terinduksi
untuk berdiferensiasi oleh sitarabin. Dan pemberian terus
menerus zat ini terhadap HL 60 human promyelocytic leuce-
mic cell, akan meningkatkan pematangan sel sampai menyamai
monosit atau granulosit. Jadi sel-sel leukemik jenis ini mungkin
sangat sensitif terhadap sitarabin. Tapi cara kerjanya belum
diketahui dengan tepat.
Keuntungan pemakaian sitarabin dengan dosis yang jauh
lebih rendah daripada rejimen pengobatan anti-leukemia biasa,
telah dipelajari dan diperdebatkan. Sebagai contoh, para ahli dari
Inggris telah melakukan penelitian terhadap pasien dengan
anemia aplastik dan anemia refrakter. Pasien-pasien tersebut
56 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
diobati dengan androgen, sitarabin dosis rendah, dan peng-
obatan suportif. Penelitian meliputi faktor-faktor prognosis dan
efek dari masing-masing pengobatan di atas. Hasilnya ternyata
mengecewakan, karena evolusi dari penyakitnya tidak
terpengaruh. Dalam penelitian lain, digunakan sitarabin dosis
rendah yang diberikan subkutan secara intermittent pada 21
pasien. Lima di antaranya menderita preleukemia, dan sisanya
leukemia nonlimfositik akut. Hasilnya cukup baik, 50% kasus
mencapai remisi sempurna, termasuk 4 dari pasien preleukemia
tadi.
Wisch dengan kolega-koleganya di Amerika telah mempe-
lajari 8 pasien preleukemia dengan berbagai gambaran morfo-
logik; 7 di antaranya dengan peningkatan sel-sel bias dalam
sumsum tulang. Digunakan sitarabin secara infus intravena terus
menerus dengan dosis 20 mg/m2/hari selama 21 hari. Satu
pasien mencapai kesembuhan klinik yang sempurna, dan tetap
baik setelah 14 bulan kemudian. Dua pasien meninggal, dan 5
pasien menunjukkan kemajuan dalam hitung darahnya, yang
bertahan 2 - 4 bulan setelah pemberian obat. Corak
maturasi dalam sumsum tulang mengalami kemajuan, bahkan 1
kasus kembali normal. Dari laporan-laporan lain juga
ditekankan bahwa cara pengobatan demikian dapat menghasil-
kan remisi, atau setidaknya, maturasi hematologik dalam ber-
bagai jenis displasia sumsum tulang preleukemia. Sebelum re-
misi, kadang-kadang ada episode-episode di mana sumsum
tulang menjadi hipoplasia. Hal yang demikian masih dapat
ditolerir, mengingat besarnya potensi untuk maturasi; efek dari
obat terhadap stroma sumsum tulang, dan peranannya dalam
mensekresi substansi-substansi penginduksi juga tak boleh
dilupakan.
Walaupun secara in-vitro efeknya masih belum jelas, tapi
pengalaman dalam klinik meyakinkan kita bahwa zat tersebut
bermanfaat sebagai kemoterapi preleukemia. Bagaimanapun
juga, bahkan dengan dosis yang rendah, risiko terjadinya depresi
sumsum tulang tetap ada. Dosis yang lazim dipakai sebagai
kemoterapi preleukemia telah ditinggalkan, mungkin karena
anggapan bahwa sumsum tulang tidak dapat kembali lagi ke
fungsinya yang normal. Anggapan ini tidak mutlak benar; makin
intensif pengobatan, kesempatan untuk remisi mungkin lebih
besar, dan risiko kematian menurun.
Efek sitarabin (dan mungkin zat-zat penginduksi lain),
dengan dosis yang bervariasi di dalam pengobatan displasia
sumsum tulang pada preleukemia ini, masih perlu dipelajari
secara lebih meluas.
Lancet 1984; i : 943-944
Obat-obat & Insomnia
Insomnia terjadi dalam begitu banyak keadaan, sehingga sulit
diketahui hipnotik mana yang harus dipergunakan dan
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 57
mana yang paling cocok. Dalam 10 tahun belakangan ini banyak
kemajuan yang telah dicapai dalam pemahaman masalah tidur
dan gangguannya; dan banyak obat, diazepin maupun non-
diazepin, telah dibuat untukmemperbaiki tidur. Beberapa waktu
lalu, dalam konperensi tentang "Obat-obatan dan insomnia" di
Inggris telah dicapai suatu konsensus. Pandangan yang lebih
jelas tentang obat-obat tadi mulai tampak, sehingga kini kita
mempunyai pegangan sekadarnya.
Insomnia adalah simtom dari berbagai keadaan. Ini menun-
jukkan perlunya penilaian sistematik terhadap penyebab-
penyebab medis, psikiatrik, ataupun lainnya. Analisis dari
insomnia paling baik dilakukan dalam tiga bagian : transien,
jangka pendek, dan jangka panjang.
Insomnia transien timbul pada mereka yang biasa tidur
nyenyak; biasanya ini karena perubahan keadaan yang me-
nyertai tidur (misalnya, kebisingan), atau pola istirahat yang tak
biasa, misalnya bekerja malam atau setelah perjalanan dengan
pesawat jet ke negeri jauh. Obat hipnotik mungkin diperlukan,
mungkin tidak, tergantung apakah pasien tadi mengeluhkannya
atau tidak. Tapi, bila pengobatan diberikan, hipnotik yang cepat
dieliminasi lebih cocok. Dan ia seharusnya cuma diberikan sekali
dua kali.
Insomnia jangka pendek biasanya berkaitan dengan problema
emosional atau penyakit medis yang serius. Mungkin ia
berlangsung beberapa minggu, dan bisa kumat. Diperlukan
pengelolaan yang baik agar insomnia jangka panjang dapat
dihindari. Yang paling penting ialah perhatian akan higiene tidur.
Hipnotik mungkin sekali berguna, namun jangan lebih dari tiga
minggu pemberiannya; lebih baik kalau cuma sekitar seminggu.
Penggunaan intermiten dianjurkan, setelah beberapa hari tidur
nyenyak. Obat yang cepat dieliminasi biasanya cocok, agar
siangnya tidak mengantuk. Namun pada mereka yang
menunjukkan ansietas cukup banyak, obat yang eliminasinya
lama (diazepam misalnya) boleh dipakai. Tapi harus berhati-hati
agar tidak terlalu mengantuk akibat akumulasi obat.
Banyak kontroversi tentang penggunaan hipnotik pada
insomnia kronik. Diagnosis yang tepat diperlukan sebelum
keputusan diambil. Mungkin sepertiga sampai setengah pende-
rita tadi punya latar belakang penyakit psikiatrik, terutama
depresi, dan pasien-pasien demikian perlu pengobatan khusus.
Kelompok lain termasuk mereka yang menyalahgunakan obat
dan alkohol. Tapi ada juga kelompok yang benar-benar punya
kelainan tidur yang spesifik. Secara praktis, yang terpenting
terutama pada usia lanjut ialah apnea tidur. Pada pasien
demikian, yang biasanya gemuk dan suka tidur mengorok, atau
mengantuk di siang hari sedatif dianggap merupakan
kontraindikasi!
Sekalipun demikian, pada banyak pasien insomnia kronik,
penyebabnya tidak diketahui. Di sini kedua pendekatan :
perbaikan higiene tidur dan hipnotik, akan diperlukan. Yang
penting ialah olahraga, mengurangi stress, pantang kopi dan
alkohol; hipnotik digunakan secara intermiten sekali dalam tiga
malam sampai sebulan. Pada pasien-pasien ini, benzodiazepin
jangka panjang mungkin lebih baik. Bila setelah sebulan belum
berhasil, dapat dicoba antidepresan sedatif, misalnya selama 4
minggu, meskipun tak tampak jelas gejala depresi.
Namun pendekatan ini perlu dipertimbangkan benar-benar.
Diazepin lebih menguntungkan dari barbiturat, bukan saja
karena keamanannya, tetapi juga karena manfaat terapeutiknya.
Masalah yang terutama timbul ialah efek sisanya di siang hari
(yang sedikit bila memakai senyawa yang cepat dieliminasi);
kumatnya insomnia bila obat distop (yang dapat dicegah bila
digunakan jangka pendek dan penghentian pengobatan
bertahap); ketergantungan obat (dapat diminimalkan dengan
dosis kecil intermiten, pemberian jangka pendek, atau
penghentian bertahap); dan potensiasi obat sedatif lainnya.
Untuk menghindarkan semua itu, pasien harus diberi dosis ter-
kecil, dengan jangka waktu sesingkat-singkatnya. Dokter perlu
mendidik pasien untuk menggunakan dosis kecil secara inter-
miten tersebut.
Saran-saran di atas cukup masuk akal. Terapi dengan hip-
notik dengan cara di atas akan banyak mengurangi masalah
penggunaan sedatif yang terlalu lama. Selain itu dosis obat dulu
sering terlalu tinggi. Mungkin dosis yang terlalu tinggi ini karena
salah penilaian; pasien dengan insomnia transien atau jangka
pendek disamakan dosisnya dengan yang untuk pasien insomnia
kronik.
Brit Med J 1984; 288 : 261
Untuk segala surat-surat, pergunakan alamat :
Redaksi Majalah Cermin Dunia Kedokteran
P.O. Box 3105 Jakarta 10002
Pada suatu hari, datang seorang ibu ke dokter dengan mem-
bawa pembantu wanita yang berumur kira-kira 30 tahun.
Ibu rumah tangga tadi mengatakan bahwa pembantunya itu
sedang hamil muda. Hasil pemeriksaan fisik dan tes kehamilan
menunjukkan bahwa pembantu tersebut memang sedang hamil
lebih kurang 10 minggu.
Dokter tersebut mencoba melakukan tanya jawab dengan pem-
bantu tadi, tapi wanita tersebut bungkam seribu bahasa.
Menyadari bahwa mungkin pembantu ini takut sekali ter-
hadap majikannya, maka dokter mempersilahkan sang majikan
menunggu di luar kamar periksa. Ternyata tindakan ini
membawa hasil. Si pembantu sekarang dapat bercerita : bahwa
ia memang hamil akibat hubungan kelamin dengan ayah mertua
majikannya yang sudah berumur lebih kurang 65 tahun. Oom
tua yang sudah pensiun dan tak memiliki kegiatan sehari-hari
yang tetap, ternyata berhasil membujuk/mengancam pembantu
ini untuk melakukan hubungan seksual sampai sebanyak tiga
kali. Kesempatan untuk "pertemuan
"
ini dipilihnya waktu-waktu
dimana rumah sedang kosong oleh karena para anggota keluarga
semua keluar rumah, seperti pada pagi hari.
Dapat dibayangkan bahwa istri rumah tangga tersebut ter-
kejut dan malu sekali setelah mendengar dari dokter tentang
kasus kehamilan yang tak terencana ini. Setelah mengatasi
keributan dalam keluarganya, mereka kembali ke dokter dan
sang majikan mengatakan bahwa telah disepakati oleh para
anggota keluarga besarnya, dimana kehamilan tersebut harus
diakhiri.
Untuk meyakinkan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak
keluarga majikan, maka dokter tersebut mempersilahkan
majikan keluar dari kamar periksa dan mengadakan tanya jawab
dengan pembantu tersebut.
Dijelaskan oleh dokter tersebut : bahwa bila pembantu wanita
itu hendak mempertahankan kehamilannya sampai kemudian
bayinya lahir. maka dokter tersebut akan berusaha agar
majikannya memberikan pengganti materil yang wajar sebagai
uang pesangon si pembantu untuk pulang kedesanya. Bila tidak,
maka akan dicarikan jalan untuk mengakhiri kehamilan ini.
Ternyata memang si pembantu bertekad untuk tidak mene-
ruskan kehamilannya, oleh karena tidak dapat menghadapi beban
batin di kampungnya.
Nah, setelah mendengar itu, dokter tersebut mengatakan kepada
majikannya agar pembantu tersebut dibawa ke sebuah klinik
untuk dihentikannya kehamilannya.
Bagaimana pendapat saudara tentang "penyelesaian" kasus ini?
OLH
58 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Komentar
TANGGAPAN DARI SEGI ETIK KEDOKTERAN.
Inti permasalahan ialah bagaimana sikap etis seorang dokter
terhadap abortus provokatus. Dalam kasus ini, dokter tersebut
memahami keinginan dari sang majikan dan korban untuk
melakukan abortus provokatus dan karena itu dia menyetujui
dengan sekaligus mengirim yang bersangkutan ke sebuah klinik
untuk penghentian kehamilan. Indikasi untuk abortus provokatus
itu adalah indikasi sosial dari kedua pihak, yaitu rasa
"
malu
"
.
Bicara mengenai abortus provokatus, maka secara langsung
dokter berhadapan dengan hati nuraninya sendiri, mengingat
sumpah jabatan dokter yang diantaranya berbunyi : "Saya akan
menghormati hidup insani semenjak saat pembuahan
"
. Namun
kita juga menyaksikan bahwa penyimpangan seakanakan sudah
lumrah terjadi.
Di bawah "permukaan", abortus provokatus dapat dilakukan
secara tersembunyi oleh
"
dukun" yang sulit diharapkan akan
dilakukan dengan memperhatikan kriteria medis, sehingga
sering membawa korban bagi sang calon ibu. Namun yang
dilakukan secara baik menurut kriteria teknis medis juga ada,
untuk mengurangi bahkan menghilangkan risiko dan efek sam-
pingan berupa infeksi, perdarahan, dan lain-lain. Dan yang ter-
akhir ini dilakukan oleh tenaga ahli yaitu dokter !
Secara resmi yang dibenarkan oleh etik kedokteran adalah bila
ada indikasi medis yaitu bila terminasi kehamilan tidak di-
lakukan akan membahayakan si calon ibu. Dengan demikian,
secara tersirat, dunia kedokteran sudah sejak lama menentukan
urutan prioritas dalam menghormati kehidupan insani. Yaitu,
yang pertama dihormati kehidupan insani yang telah
lengkap/telah lahir; baru kemudian insani yang belum lahir ke
dunia !
Secara tidak sadar penampilan sikap "egoisme" dari manusia
sendiri maju ke depan; membela ras manusia yang telah hadir di
dunia, lebih penting ketimbang membela calon manusia yang
belum kelihatan. Beberapa dasawarsa belakangan ini indikasi
lain untuk melakukan abortus provokatus semakin luas, seperti
indikasi sosial dalam arti luas, indikasi sosial dalam skala
keluarga, keenganan mempunyai unwanted child demi
kesejahteraan keluarga dan lain-lain.
Program KB dengan Norma Keluarga Kecil yang Berbahagia
dan Sejahtera (NKKBS) banyak pula dimanfaatkan oleh ang-
gota masyarakat tertentu yang menjurus pada abortus provoka-
tus, biarpun secara resmi cara ini tidak termasuk dalam program
KB. Akan tetapi praktek seperti M.R. masih diperdebatkan
antara yang pro dengan yang kontra, apakah itu suatu
abortus provokatus atau bukan. Bahkan, pemasangan IUD bila
mekanismenya dalam mencegah kehamilan diyakini sebagai
pencegahan nidasi saja, akan berarti telah menciderai sumpah
dokter sebab pembuahan telah terjadi, hanya nidasi yang
terhalang.
Karena berbagai realitas hidup sehari-hari, maka secara di-
am-diam masalah abortus provokatus menjadi semakin ringan.
Dengan perkataan lain secara evolusi telah terjadi pergeseran
nilai dalam kehidupan masyarakat termasuk masyarakat dokter.
Dalam kasus kita ini mungkin sebagai suatu apologi, Sejawat
yang mengirim ke klinik tersebut, merasa tidak bersalah karena
dia tidak menganjurkan dan lagi pula yang melaksanakan
bukan dia sendiri; dia cuma memberikan kemudahan dengan
menunjukkan tempat yang baik dan aman.
Pergeseran nilai yang lain ialah secara tersirat seolah-olah
sudah ada klinik yang berfungsi untuk maksud abortus provo-
katus tanpa indikasi medis, yang diterima oleh masyarakat. Kita
juga menyaksikan bergesernya nilai sakral dari hubungan intim
perkawinan biarpun salah satu sila dalam Pancasila adalah
"
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Makna beradab ini
sering terlanggar, mungkin karena tolak ukurnya kurang jelas.
Pertanyaan kita : "Apakah hubungan seksuil dalam kehi-
dupan perkawinan masih dianggap sakral dan merupakan ra-
hasia pribadi yang termulia, masih dianut ?" Dalam beberapa
hal, misalnya dalam kampanye Safari KB di layar TVRI, sering
kita menyaksikan pertanyaan dan dialog yang tidak lagi
menghormati kesakralan dan kerahasiaan hubungan seksuil
suami istri, seolah-olah perbuatan tersebut merupakan kegiatan
rutin yang tak perlu disembunyikan, karena toh semua orang
tabu juga.
Kembali di sini masalah pergeseran nilai. Bilamana hubung-
an seksuil dua insan yang berlainan jenis, kehilangan nilai sakral
dan keintimannya, maka kehamilan sebagai buah dari hubungan
tersebut juga tidak lagi dinilai sakral, maka dengan sendirinya
penilaian pun menjadi rutin, sehingga pelaksanaan abortus
secara berangsur-angsur akan diterima sebagai hal yang wajar
pula. Seolah-olah kita menerima kesepakatan: "Marilah kita
menikmati dunia ini untuk kita sendiri, tidak perlu memikirkan
hak asasi calon manusia itu". Di sini kita sekarang berada dalam
manifestasi kontroversialitas
"
species" yang namanya manusia.
dr. H. Masri Roestam
Direktorat Transf usi Darah PMI/
Ketua I.D.I. Cabang Jakarta Pusat
TANGGAPAN DARI SEGI HUKUM KEDOKTERAN
Ada 3 persoalan yuridis dalam kasus ini :
Yang pertama menyangkut rahasia pekerjaan dokter.
Seharusnya dokter itu meminta ijin kepada pembantu rumah
tangga untuk memberi tabu tentang kehamilannya kepada si
majikan. Tapi dari cerita selanjutnya ternyata pembukaan rahasia
itu adalah demi kebaikan si pembantu, sehingga tidak ada alasan
untuk menuntut dokternya.
Yang kedua menyangkut ancaman. Jika ini berupa ancaman
kekerasan, misalnya mau dibunuh, maka telah terjadi perkosaan.
Tapi kalau hanya ditakut-takuti akan diberhentikan dari
pekerjaan maka perbuatan ini tidak dapat dituntut.
Yang ketiga menyangkut abortus provokatus. Seperti kita
ketahui, abortus provokatus yang diperbolehkan oleh hukum (
berdasarkan yurisprudensi dan juga sejarah pembuatan
hukumnya) hanya yang berdasarkan indikasi medik.
Jika indikasi untuk dilakukan abortus itu tidak tepat, maka
dokter yang memberi tabu di klinik mana dapat dilakukan
abortus itu dapat dituntut sebagai pembantu melakukan keja-
hatan menurut KUH Pidana pasal 56 :
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana :
ke-1: orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu
dilakukan;
ke-2: orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar
atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Dalam yurisprudensi Belanda (putusan Arrondissements-
rechtbank Amsterdam 5 Februari 1942) dibenarkan suatu abortus
provokatus atas dasar indikasi psikiatrik, di mana psikiater
menerangkan, bahwa si wanita itu berada dalam ketegangan
jiwa yang hebat dengan bahaya bunuh diri (in een zeer ernstige
overspanningstoestand met direct suicide-gevaar). Di Indonesia
belum pernah ada yurisprudensi seperti ini, tapi dalam suatu
perkara (tentang hal lain) dalam sidang pengadilan pernah
terungkap adanya abortus provokatus atas dasar indikasi
psikiatrik dan dokter yang melakukannya tidak dituntut. Jadi
secara diam-diam (stilzwijgend)tampaknya indikasi psikiatrik
juga diterima di sini.
Oleh karena itu sebaiknya dokter mengirim pembantu rumah
tangga tadi ke psikiater untuk meneliti besarnya
"
beban tekanan
batin" yang diderita dan apakah dapat dipertanggungjawabkan,
jika dilakukan abortus provokatus atas dasar
"
be-ban tekanan
batin" itu.
dr. Handoko Tjandroputranto
Lembaga Kriminologi
Universitas Indonesia, Jakarta
60 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
Catatan singkat
Menteri Kesehatan Inggris bulan Mei yang lalu mencabut
izin peredaran tablet anti-rematik yang berisi
oksifenbutason, karena alasan keamanan. Di Inggris ia
beredar dengan nama Tanderil, Tandacote dsb. ( di
Indonesia: Tanderil, Rheumapax, Realin, Reozon). Apotik
- apotik harus mengembalikan stok obat tersebut pada
waktu yang telah ditentukan.
Dulu fenilbutason juga mengalami nasib serupa; Tapi
ia masih boleh dipergunakan oleh dokter di rumah sakit,
pada keadaan tertentu.
Dari Afrika Selatan, dilaporkan adanya 19 kasus per-
lukaan vagina setelah melakukan senggama biasa. Menga-
pa demikian ? Penulis tersebut menduga bahwa perlukaan
vagina tadi terbanyak pada wanita-wanita yang meng-
ulang senggama setelah sekian lama tidak melakukannya.
Tidak disebutkan bagaimana karakteristik dari pasangan
wanita-wanita yang mengalami perlukaan vagina itu.
South African Med J 1983; 64 : 746 - 7
Apakah transplantasi otak dapat dilakukan? Ya, menu-
rut hasil penelitian baru-baru ini. Binatang yang diduga
mengalami kerusakan pada salah satu bagian otaknya, ka-
dang-kadang dapat diperbaiki melalui transplantasi de-
ngan jaringan otak fetus. Dalam waktu mendatang, hal ini
mungkin menjadi kenyataan pada manusia.
Developmental Med and Child Neuro 1983; 25: 654-6
Pil KB ternyata dapat menimbulkan efek samping
berupa otosklerosis. Sebaiknya pada ibu-ibu yang akan
menggunakan pil KB tersebut, sebelumnya dilakukan
pemeriksaan telinga. Juga penting anamnesis ada tidak-
nya riwayat ketulian dalam keluarga.
Br J Fam Planning 1984; 9 : 134
Pada awal tahun 1970, dilakukan screening terhadap
2000 orang laki-laki yang tampaknya sehat, dengan usia
antara 40 - 59 tahun. Hasilnya : 115 orang menderita
penyakit pembuluh koroner jantung yang laten. Pada 109
dari 115 orang ini dilakukan pemeriksaan angiografi.
Didapatkan 36 orang dengan gambaran angiogram yang
normal. Pada f ollow-up 7 tahun kemudian, dari ke 36
orang ini, 3 orang meninggal tiba-tiba, 4 orang menderita
kardiomiopati, dan 1 orang dengan dilatasi/regurgitasi
aorta. Kesimpulan : angiogram normal belum tentu
menunjukkan jantung yang normal.
Circulation 1983; 68 : 490 - 7
Banyak macam ukuran cuf f dari sfigmomanometer
yang dimiliki dan digunakan oleh para dokter. Cuf f yang
terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengubah tekanan
darah seseorang sebesar 8,5 mmHg sistolik dan 4,6 mmHg
diastolik.
Bila cuf f terlalu kecil, tekanan darah akan terukur lebih
tinggi dari yang sebenarnya; sedangkan bila cuf f terlalu
besar, tekanan darah akan terukur lebih rendah. Ini dapat
menyebabkan over treatment atau under treatment.
Circulation 1983; 68 : 763 - 6
Penemuan antibiotika telah diikuti dengan resistensi
kuman. Bagaimana mencegah bencana ini pada obat-obat
antivirus? Pada infeksi bakteri, pemberian antibiotika
profilaksis umumnya dianggap sebagai penyebab resistensi.
Tapi pada obat antivirus, keadaannya berbeda sekali,
terutama virus yang punya fase laten pada siklus hidupnya
- seperti, herpes simplex, sitomegalovirus, dan adenovirus.
Pencegahan pada penyakitpenyakit karena virus tadi dapat
amat bermanfaat. Dan mungkin mencegah timbulnya
resistensi.
Lancet 1984;i:1154
Banyak zat-zat pemanis sintetis. Tapi banyak pula yang tak
dianjurkan karena efek sampingnya. Sakarin, misalnya,
karena menyebabkan kanker kandung kencing, pernah
akan dilarang di Amerika. Tapi ini ditentang oleh para
penderita diabetes yang memerlukan.
Tapi pemanis sintetis aspartam, oleh sebuah komite
kesehatan di Inggris dinyatakan aman. Aspartam ini,
setelah dimakan akan dipecah menjadi fenilalanin dan
asam aspartat; kedua-duanya asam amino alamiah, dan
fenilalanin asam amino yang esensial. Juga setelah makan
aspartam, kadar fenilalanin tubuh tidak meningkat secara
bermakna.
Penyebab vertigo yang sering dan biasa pada orang dewasa
justru jarang menyebabkan vertigo pada anakanak.
Penyelidikan terhadap 50 kasus vertigo yang rekuren pada
anak-anak, ternyata 28% disebabkan epilepsi lobus
temporal, 22% oleh karena epilepsi subkortikal, baru
kemudian penyebab-penyebab lainnya. Anak-anak dengan
vertigo, seharusnya dilakukan pemeriksaan EEG dan
audiometri.
Up Date 1983; 1389 - 1397
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 61
TIUP BALON
Seorang anak laki-laki berumur lebih
kurang 4 tahun sedang berada di kamar
bersama ibunya yang sedang berganti
pakaian.
Sewaktu ibunya menanggalkan kutang-
nya, anak tadi nycletuk :
"
Ibu, balon-
balon ibu kurang keras / besar, perlu
ditiup !"
Ibu :
"
Hush, ini bukan balon !" sambil
menunjuk pada payudaranya.
Anak :
"
Lho, tadi saya lihat bapak di
gudang sedang meniup balon
Minah (si pembantu) sampai
keras sekali !!!"
OLH
K.O.
Sewaktu masih coass, saya berdua
dengan teman saya harus memberikan
ceramah mengenai cara-cara per-
tolongan partus yang benar kepada para
dukun beranak. Sebenarnya kami masih
hijau dalam praktek dibandingkan
mereka. Maklum, belum lagi masuk
kebidanan. Sebelumnya, saya buat
perjanjian dengan teman saya; bila ada
pertanyaan yang tidak dapat saya jawab,
saya akan memberi kode dengan
menyentuh kakinya agar ia yang
menjawab. Beberapa kali hal ini berjalan
mulus. Akhirnya, saya dibuat "knock
out" juga, karena biar sudah saya
tendang-tendang kakinya, ia tetap diam
saja. Sama-sama tidak bisa
Kris
TEKANAN DARAH RENDAH
Seorang sejawat ditugasi oleh Lembaga Transfusi Darah PMI DKI Jaya untuk melaksa-
nakan kegiatan pengambilan darah pada anggota keluarga besar salah satu ludruk terke-
nal di wilayah Jakarta.
Setelah memeriksa seorang pasien, terjadilah percakapan sebagai berikut
Dokter
Pemain ludruk I
Dokter
Pemain ludruk I (dengan agak cemas)
Pemain ludruk II (nyeletuk)
JUDUL BARU
Tiap penerbitan majalah ini selalu dirakit dalam suatu simposium dengan tema
tertentu. Suatu ketika seorang pengumpul naskah bertanya kepada dokter penulis, suatu
judul untuk "Simposium masalah otak
"
: "Dokter, dari judul-judul simposium otak ini,
judul apa lagi yang dipandang masih perlu untuk ditambahkan?"
Dokter membaca sederetan judul-judul, dan sambil manggut-manggut mengatakan : "
Menurut saya sudah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan ini menarik juga.
"
Dengan serta
merta si peminta naskah menulis apa yang dikatakan oleh dokter tsb : 'Resep-resep baru
dalam pengelolaan ......... masakan ......................otak kambing!'
Sang dokter meledak ketawanya dan sang peminta naskah cepat-cepat balik minta diri
sambil berkata : "Dan sop buntut ya dokter."
Sri
:
"Bapak, darahnya tidak bisa diambil. Bapak
sekarang tidak bisa donor"
"Kenapa dokter?"
"Tekanan darah Bapak ini rendah." "
Bagaimana mengobatinya dokter?"
"Gampang mas, makan saja "tangga", kan nanti
tekanan darahnya jadi naik tinggi!!"
dr. Tjandra Yoga Aditama
Jakarta
:
:
:
:
:
POSITIF
Waktu menjalani kepaniteraan klinik
di bagian neurologi, setiap coass harus
membuat presentasi kasus secara
bergilir. Istimewanya, untuk seorang
dosen tertentu presentasi tersebut di-
bawakan di rumah beliau. Jadi setiap kali
kami berbondong- bondong ke ru-
mahnya, dan tentu saja ..., tanpa pasien!
Suatu kali tiba giliran saya. Karena di
rumah sakit tidak ada kasus yang
menarik, terpaksa kasusnya saya karang-
karang sendiri. Status saya salin saja dari
bekas teman saya.
Saatnya pun tiba. Saya bacakan
identifikasi pasien wanita itu, anam-
nesis, dan seterusnya. Beliau manggut-
manggut . . ., tiba-tiba dia tertawa.
Teman-teman yang lain pun ikut ter-
tawa. Saya bingung juga, tapi segera
sadar. Rupanya dalam status palsu
tersebut tertulis : refleks kremaster
positif !
Kris
62 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
MINTA TOLONG
Disuatu ruang praktek seorang dokter, datang seorang pria umur 60 tahun, seorang
wanita umur 25 tahun dan seorang anak kecil umur 2 tahun.
Setelah dipersilahkan duduk, terjadi tanya jawab antara dokter dengan pasien tersebut.
Dokter : "Yang sakit siapa Pak ?"
Si wanita yang menjawab : "Itu Pak Dokter, suami saya senjatanya tidak bisa ber-
gerak
"
. (Maksudnya : impotent).
Dokter (setengah kaget, karena disangkanya sang Bapak tadi adalah orang tua dari
wanita tersebut) : "Sudah berapa lama sakitnya Pak ?"
Bapak :
"
Sudah kurang lebih 5 tahun Pak Dokter
"
.
Dokter :
"
Tapi anak ibu baru 2 tahun, mana mungkin ?"
Si istri mendengar pertanyaan Dokter itu senyum senyum kecil.
Sang Bapak dengan malu-malu kucing menjawab :
"Betul Pak Dokter, anak itu memang anak dari istri saya, tetapi bukan anak saya
"
.
Dokter : "Apakah istri Bapak waktu kawin dengan Bapak sudah
janda ?"
Bapak : "Tidak Pak Dokter, dia waktu itu masih gadis" .
Dokter :
"
Lalu ?"
Bapak : "Waktu itu saya minta tolong kepada tetangga oleh ka-
rena saya ingin punya anak".
Mendengar jawaban yang tidak terduga tadi sang Dokter berkata :
"
Kenapa Bapak dulu
tidak minta tolong kepada saya ?"
Si istri, mendengar perkataan Dokter tadi, terlihat senyum- senyum kecil penuh arti.
Segera Dokter sadar, dan meralatnya.
"Bukan begitu, kenapa tidak berobat, maksud saya !"
dr. Sudaranto
Puskesmas Sail, Pekanbaru, Riau
SALAH PAKAI
Sepasang suami istri datang menghadap seorang dokter dalam rangka KB. Oleh dokter
tersebut diberi 1 doos kondom, sambil bertanya kepada si suami :
"Bapak sudah tahu cara memakainya ?"
"Sudah dok, dulu sebelum kawin saya sudah pernah pakai !"
Pasangan suami istri tersebut kemudian pergi sambil membawa bekal kondom tadi.
Setelah beberapa waktu si istri kembali kepada dokter dan bercerita bahwa haidnya
belum juga datang.
Dokter bertanya : "Apakah bapaknya tiap kali pakai alat tadi, bu ?"
Si istri : "Wah, bapak sering malas, jadi saya yang pakai saja !"
Dokter : "Lho, caranya bagaimana ?"
Si istri : "Saya makan satu biji sebelum campur !"
Dokter : "Wah, salah ! Itu tidak untuk dimakan !"
Si istri : "Pantas sekarang tiap kali saya kentut, keluar plembungannya
(balon) !"
OLH
KEMANA ?
Pengalaman dokter gigi di desa macam- macam.
Ada pasien, seorang kakek tua, yang gigi gerahamnya berlubang. Harus dicabut ! Ke-
mudian dokter memberikan suntikan anestesi lokal, dan menyuruhnya menunggu di luar.
Setelah beberapa saat dokter membuka pintu dan menyilahkan pasien tersebut masuk.
Tapi ........................... ruangan telah kosong, pasien tersebut telah pergi, mungkin diki-
ranya pengobatan telah selesai . . . . atau uangnya yang tidak cukup, sehingga harus
Sri
r
Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984 63
iia~iiillii
RUANG PENYEGAR DAN
PENAMBAH ILMU KEDOKTERAN
Dapatkah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ???
1. Afasia adalah gangguan bahasa, dan biasanya :
(a) disertai gangguan persepsi
(b) disertai gangguan memori
(c) disertai gangguan emosi
(d) disertai gangguan kognitif
(e) tidak disertai gangguan fungsi luhur di atas.
2. Prinsip dari rehabilitasi (speech therapy) penderita afasia:
(a) dimulai seawal mungkin
(b) komunikasi dengan isyarat jangan digunakan
(c) materi pelajaran perlu diulang-ulang
(d) penyertaan keluarga adalah mutlak
(e) semua di atas benar.
3. Mengenai disfungsi otak minor pada anak, pernyataan yang
tidak benar ialah :
(a) diduga diderita oleh 5 - 25% anak-anak usia sekolah.
(b) dapat mengalami kesulitan membaca, menulis, meng-
hitung, atau berbahasa.
(c) anak dengan kesulitan belajar tak perlu pemeriksaan
neurologik.
(d) riwayatnya : tidak dapat diam, sering tersandung dan
jatuh, sulit mengikat tali sepatu, sulit mengancing
baju, dan lain-lain.
(e) terapinya antara lain obat psikostimulan dan cerebral-
metabolic vasodilators.
4. Obat-obat untuk insufisiensi otak, umumnya masih diper-
debatkan efektivitasnya.Tapi, secara umum, tujuannya ialah
sebagai berikut, kecuali :
(a) perbaikan pemakaian 02 dan glukosa oleh otak
(b) penghambatan sintesis protein otak, misalnya dengan
heksobendin
(c) peningkatan resistensi otak terhadap hipoksia.
(d) perbaikan sirkulasi serebral, misalnya dengan nikotinat.
(e) semua jawaban benar.
5. Pada penanggulangan stroke; yang tidak benar ialah :
(a) penderita hipertensi berat cukup bila tekanan ditu-
runkan sampai 160/110 mmHg pada fase akut.
(b) pemberian deksametason masih kontroversial.
(c) bila pasien dapat minum, gliserol dapat diberikan per-
oral, meskipun efeknya masih kontroversial.
(d) pemberian vasodilatansia dan oksigen sangat berguna.
(e) yang terpenting ialah perawatan umum dan mengobati
faktor risiko.
6. Pada cedera otak, manakah pernyataan berikut yang tidak
benar ?
(a) fraktur tengkorak, tanpa kelainan neurologik, secara
klinik tidak begitu berarti.
(b) diantara saraf otot mata, yang sering terkena ialah Saraf
III, sehingga mengalami diplopia.
(c) Saraf ke VII dan VIII sering cuma mengalami ganggu-
an karena edema.
(d) Saraf vagus jarang terkena, karena bila terkena biasanya
penderita mati.
(e) semua jawaban di atas benar.
7. Tumor otak yang paling banyak didapatkan ialah jenis :
(a) glioma
(b) meningioma
(c) adenoma hipofisis
(d) tumor metastasis
(e) tumor pembuluh darah.
8. Pada tumor otak :
(a) Nyeri kepala ditemukan pada sebagian besar pasien.
(b) Pada sebagian besar pasien didapatkan kejang umum.
(c) dapat ditemukan gejala bradikardia dan hipertensi.
(d) Gangguan mental, seperti halusinasi, tak pernah di-
jumpai .
(e) Papil edema jarang ditemukan.
9. Penanggulangan penderita insomnia kronik adalah sebagai
berikut, kecuali :
(a) lebih dipilih benzodiazepin yang kerjanya singkat.
(b) dapat dicoba pemberian antidepresan, meskipun
gejalanya tak jelas.
(c) higiene tidur dan olah raga penting sekali.
(d) bila diberikan hipnotik, dipilih dosis seringan mungkin;
kalau perlu diberikan intermiten.
(e) benzodiazepin lebih dipilih daripada fenobarbital.
10. Mana diantara keadaan ini yang tak dapat menyebabkan
ketulian ?
(a) Keturunan
(b) Influena
(c) Diabetes melitus
(d) Vitamin B-1
(e) Penyakit Meniere.
3 '8 fl 'b
V 'L '
D'01 S ' 9 3 ' Z
V' 6 a ' S 3 ' 1
7I1dd)l uageMa
64 Cermin Dunia Kedokteran No. 34, 1984
ABSTRAK AB5TRAK
PELAYANAN KESEHATAN JIWA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
Pelayanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang, lebih banyak dikenal pada
saat ini daripada 10 tahun yang lalu. Yaitu, sejak WHO membentuk suatu badan khusus
untuk mempelajari strategi supaya pelayanan kesehatan jiwa itu berhasil.
Berikut ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang dicapai oleh Badan tersebut :
(a) Kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa antara masyarakat pedesaan dan
perkotaan adalah sama besar.
(b) Sebagai primary health care, sistem desentralisasi bagi pelayanan kesehatan jiwa
baik di desa dan di kota untuk negara-negara berkembang, dapat dilaksanakan.
(c) Selain oleh dokter umum, pelayanan kesehatan jiwa dapat juga dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang telah mendapat latihan sekedarnya. Cara seperti ini telah digu
.
nakan dibanyak pusat kesehatan, dan pedoman latihan diterbitkan dalam bahasa se-
tempat.
(d) Ketrampilan menolong penderita gangguan jiwa perlu diberikan pada semua staf
medis; bukan hanya untuk menolong penderita gangguan jiwa, tapi untuk meningkatkan
mutu segala bentuk pelayanan kesehatan.
(e) Ketrampilan dalam ilmu mengenai tingkah-laku, pada saat yang bersamaan dapat
menolong dalam formulasi dan implementasi program kesehatan masyarakat, yang
mempromosikan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Kris
WHO Technical Report Series, No 698, 1984; 30 - 31
DUA LANGKAH UNTUK BERUBAH MENJADI KANKER
Oleh 3 team peneliti masing-masing : R. Weinberg dari MIT, USA, E. Rodey dari Cold
Spring Harbour U.S.A dan R.F. Newbold/R.W. Overell dari Institute of Cancer Re-search
dari Inggeris telah ditemukan bahwa untuk perubahan sel-sel normal menjadi sel-sel
kanker (ganas) diperlukan 2 langkah :
Langkah I, disebut immortalization, yaitu berubahnya sel-sel normal sedemikian rupa
sehingga dapat hidup selama-lamanya dalam laboratorium, Sel-sel normal biasanya akan
mati setelah 1k. 50 generasi. Langkah II, diperlukan impuls atau rangsang agar sel-sel
dapat membagi-bagi diri secara cepat.
Urutan kedua langkah ini tidak menjadi soal, akan tetapi kedua-duanya mutlak untuk
mengubah sel-sel normal menjadi sel yang ganas. Perubahan ini dapat disebabkan oleh
gen-gen virus, zat-zat karsinogenik, atau oleh oncogenes, yaitu gen-gen binatang yang
bertalian dengan jenis-jenis kanker tertentu.
OLH
"CHILD ABUSE" Science, Nov. 1983
"Child abuse" merupakan suatu tragedi bagi anak. Ia merupakan contoh rasa saling tidak
mengerti antara orang tua dengan anaknya. Bahkan sering-sering menimbulkan
keterasingan sang ibu dari bayinya.
Perlu dipertimbangkan di sini sensasi yang berlainan antara ibu dan bayi pada saat
dilahirkan. Kelahiran, bagi ibu adalah peristiwa dramatik yang menyakitkan dan
melelahkan. Sang bayi, yang biasanya hidup dalam rahim ibunya, tiba-tiba harus hidup
dalam dunia
"
luar". Pelukan dan buaian dari ibunya itu perlu supaya perubahan tersebut
tidak terlalu besar dirasakan. Tapi, yang sering terjadi, bayi dipisahkan dari ibunya, dan
diletakkan begitu saja dalam box. Tentunya, perubahan ini terasa besar bagi bayi dan
amat tidak menyenangkan.
Mungkin berbicara tentang cinta sudah ketinggalan jaman, tapi bernyanyi lagu cinta
adalah mode. Yang dibutuhkan bagi bayi dan setiap orang, yaitu keinginan untuk dicintai
dan perasaan aman. Bayi yang tidak dicintai akan menangis. Menangis merupakan satu-
satunya cara bagi bayi untuk menuntut sesuatu, Adalah kewajiban seorang ibu untuk
mengetahui apa yang dimaui bayinya bila ia menangis. Misalnya, keinginan untuk
dicintai! Kris
Up date Jan 1984; 29
Anda mungkin juga menyukai
- Asuhan Keperawatan Gerontik Dengan AlzheimerDokumen17 halamanAsuhan Keperawatan Gerontik Dengan AlzheimerAdinda RosdianaBelum ada peringkat
- Wilda Hayati (1914201094)Dokumen4 halamanWilda Hayati (1914201094)Elisabeth SabajoBelum ada peringkat
- Kelompok 1 AfasiaDokumen23 halamanKelompok 1 AfasiaJeklin CrisyaBelum ada peringkat
- Afasia!Dokumen33 halamanAfasia!SANG AYU ARTA SURYANTARIBelum ada peringkat
- Skdi 2Dokumen72 halamanSkdi 2Yaaei channelBelum ada peringkat
- Gangguan Neurobehavior 1Dokumen63 halamanGangguan Neurobehavior 1N Wisnu Sutarja100% (2)
- Gangguan Neurobehavior 1Dokumen63 halamanGangguan Neurobehavior 1Dresti RF100% (1)
- Askep Defisit Neurologi Pada LansiaDokumen20 halamanAskep Defisit Neurologi Pada LansiaGunaBelum ada peringkat
- Assesment Sistem SarafDokumen14 halamanAssesment Sistem SarafSusilo AjaBelum ada peringkat
- AfasiaDokumen22 halamanAfasiaEjil Hastia100% (1)
- NeurobehaviorDokumen87 halamanNeurobehaviorSyarifah Alfi Azzulfa AlathasBelum ada peringkat
- Bab 14 NeurokognitifDokumen44 halamanBab 14 NeurokognitifAtikah ZulfaBelum ada peringkat
- Pemriksaan Fisik Sistem SarafDokumen75 halamanPemriksaan Fisik Sistem SarafCie TieyalegenationBelum ada peringkat
- Blok 19Dokumen6 halamanBlok 19Ihsan HBelum ada peringkat
- NaufalDokumen71 halamanNaufalDede SyarifudinBelum ada peringkat
- GagapDokumen40 halamanGagapMuhammad Khoir Gultom IIBelum ada peringkat
- Kelompok 7 - Ganjil A'18 - PPT Demensia Dan DeliriumDokumen46 halamanKelompok 7 - Ganjil A'18 - PPT Demensia Dan DeliriumAtikah HazimahBelum ada peringkat
- LP Sistem Neurosensori Dan Sistem Digestive 1Dokumen32 halamanLP Sistem Neurosensori Dan Sistem Digestive 1Anonymous O0OhAwtXBelum ada peringkat
- Afasia ICH FixDokumen77 halamanAfasia ICH FixBen Asiel PadangBelum ada peringkat
- Anamnesis Pasca Trauma Dan AfasiaDokumen30 halamanAnamnesis Pasca Trauma Dan AfasiaMuhLutfiBelum ada peringkat
- Fungsi LuhurDokumen9 halamanFungsi LuhurZamzami RamliBelum ada peringkat
- Makalah mp4Dokumen7 halamanMakalah mp4Mentari Erry PutriBelum ada peringkat
- KKPMT 3 Kelompok 1Dokumen20 halamanKKPMT 3 Kelompok 1Jisella RaparBelum ada peringkat
- AfasiaDokumen18 halamanAfasiaDenara Eka SafitriBelum ada peringkat
- MMSEDokumen9 halamanMMSEMatsrial100% (1)
- Speech Terapi MakalahDokumen9 halamanSpeech Terapi MakalahRachmi Tri UtamiBelum ada peringkat
- 11 OKT Neurologi Dan Bahasa-1Dokumen28 halaman11 OKT Neurologi Dan Bahasa-1suriani80Belum ada peringkat
- Muhammad Lanang Damarjati - Tugas Askep Penurunan KesadaranDokumen14 halamanMuhammad Lanang Damarjati - Tugas Askep Penurunan KesadaranMuhammad LanangBelum ada peringkat
- WOC Epilepsi Ruang InfeksiDokumen3 halamanWOC Epilepsi Ruang InfeksifaisalBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Fugsi LuhurDokumen18 halamanPemeriksaan Fugsi LuhurWiduri WulandariBelum ada peringkat
- 720-Article Text-6217-1-10-20211023Dokumen7 halaman720-Article Text-6217-1-10-20211023Ikhwan AbiyyuBelum ada peringkat
- GGGN KomunikasiDokumen11 halamanGGGN KomunikasiRobertus Dwi AtmokoBelum ada peringkat
- AfasiaDokumen27 halamanAfasiaKeisha Salsabila100% (2)
- 4 - Neurosains KognitifDokumen23 halaman4 - Neurosains KognitifFlora Umaya100% (1)
- Bab 1Dokumen26 halamanBab 1Galang Yoga pBelum ada peringkat
- DemensiaDokumen13 halamanDemensiaSyauqi YulsonBelum ada peringkat
- Referat AfasiaDokumen20 halamanReferat AfasiaelsamayoraBelum ada peringkat
- Gangguan MotorikDokumen10 halamanGangguan MotorikhifdznainaiBelum ada peringkat
- Materi 9. Askep Lansia DimensiaDokumen19 halamanMateri 9. Askep Lansia DimensiaDhiya FatiyaBelum ada peringkat
- Referat AfasiaDokumen22 halamanReferat AfasiazainabBelum ada peringkat
- Logbook SolDokumen16 halamanLogbook Solfile skripsiBelum ada peringkat
- Perbedaan Gangguan Bahasa Dengan Gangguan BerfikirDokumen4 halamanPerbedaan Gangguan Bahasa Dengan Gangguan BerfikirshucitezaBelum ada peringkat
- Afasia Referat 2016Dokumen25 halamanAfasia Referat 2016Muliana MuhammadBelum ada peringkat
- SOAL UAS Mata Kuliah NeurologiDokumen6 halamanSOAL UAS Mata Kuliah NeurologiIswandi ErwinBelum ada peringkat
- Askep Koma - Chapter Hepar - SoalDokumen32 halamanAskep Koma - Chapter Hepar - SoalNoka MamolaBelum ada peringkat
- R3 Proses Mental DasarDokumen3 halamanR3 Proses Mental DasarScribdTranslationsBelum ada peringkat
- WowwDokumen18 halamanWowwbernard surbaktiBelum ada peringkat
- Askep DimensiaDokumen19 halamanAskep DimensiaKm TrihadiBelum ada peringkat
- Revisi - MAKALAH TUMOR OTAK N MEDSPINDokumen78 halamanRevisi - MAKALAH TUMOR OTAK N MEDSPINumi nafiatul hasanahBelum ada peringkat
- Kelompok 6 - Komunikasi TX Pada Gangguan Kesadaran Da PendengaranDokumen20 halamanKelompok 6 - Komunikasi TX Pada Gangguan Kesadaran Da PendengaranSindi MaiysarohBelum ada peringkat
- Rangkuman BiopsikologiDokumen7 halamanRangkuman BiopsikologiEby FebriBelum ada peringkat
- Bab VII - Aspek Neurologi BahasaDokumen84 halamanBab VII - Aspek Neurologi Bahasaapi-411140579Belum ada peringkat
- Intelijen: Pengantar psikologi kecerdasan: apa itu kecerdasan, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kecerdasan berkembang, dan bagaimana kecerdasan dapat memengaruhi kehidupan kitaDari EverandIntelijen: Pengantar psikologi kecerdasan: apa itu kecerdasan, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kecerdasan berkembang, dan bagaimana kecerdasan dapat memengaruhi kehidupan kitaBelum ada peringkat
- Bahasa tubuh dan komunikasi non-verbal: Cara memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik berkat psikologi dan ilmu saraf bahasa tubuhDari EverandBahasa tubuh dan komunikasi non-verbal: Cara memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik berkat psikologi dan ilmu saraf bahasa tubuhBelum ada peringkat
- Kesadaran: Menemukan tahapan-tahapan pikiran: dari yang sadar ke yang tidak sadar, dari pengaruh ritme biologis hingga tidur dan mimpiDari EverandKesadaran: Menemukan tahapan-tahapan pikiran: dari yang sadar ke yang tidak sadar, dari pengaruh ritme biologis hingga tidur dan mimpiBelum ada peringkat
- Kepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaDari EverandKepribadian: Pengantar ilmu kepribadian: apa itu kepribadian dan bagaimana menemukan melalui psikologi ilmiah bagaimana kepribadian mempengaruhi kehidupan kitaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (2)
- Pengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Pembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisDari EverandPembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (13)
- PSIKOLOGI KECEMASAN Mengetahui untuk memahami mekanisme fungsinyaDari EverandPSIKOLOGI KECEMASAN Mengetahui untuk memahami mekanisme fungsinyaPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (8)
- 170 / Vol. 36 No. 4 JuliDokumen57 halaman170 / Vol. 36 No. 4 Julirevliee100% (1)
- CDK 168 GiziDokumen69 halamanCDK 168 Gizirevliee100% (2)
- CDK 159 ObesitasDokumen57 halamanCDK 159 ObesitasrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 166 AsmaDokumen36 halamanCDK 166 AsmarevlieeBelum ada peringkat
- CDK 160 ObgynDokumen57 halamanCDK 160 ObgynrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 161 StemcellDokumen57 halamanCDK 161 StemcellrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 169 KardiovaskulerDokumen61 halamanCDK 169 Kardiovaskulerrevliee100% (1)
- CDK 158 KebidananDokumen57 halamanCDK 158 Kebidananrevliee100% (2)
- CDK 165 NeurologiDokumen57 halamanCDK 165 Neurologirevliee100% (2)
- CDK 156 DepresiDokumen57 halamanCDK 156 DepresiBiront Lex NealzBelum ada peringkat
- CDK 163 ThtrevDokumen57 halamanCDK 163 Thtrevrevliee100% (1)
- CDK 152 KesehatanwisatarevDokumen65 halamanCDK 152 KesehatanwisatarevrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 153 StemcellDokumen53 halamanCDK 153 Stemcellrevliee100% (1)
- Fisiologi Dan Patologi LengkapDokumen65 halamanFisiologi Dan Patologi LengkapJihan Azhar KresnawahyuesaBelum ada peringkat
- Cermin Dunia KedokteranDokumen57 halamanCermin Dunia KedokteranAjeng MardhiyahBelum ada peringkat
- CDK 157 NeurologiDokumen57 halamanCDK 157 Neurologishinta_dwijayantiBelum ada peringkat
- CDK 145 ObsginDokumen65 halamanCDK 145 ObsginrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 150 Masalah HatiDokumen69 halamanCDK 150 Masalah HatirevlieeBelum ada peringkat
- Cermin Dunia KedokteranDokumen65 halamanCermin Dunia KedokteranIrwan Taufiqur RachmanBelum ada peringkat
- CDK 139 Kebidanan Dan Penyakit KandunganDokumen57 halamanCDK 139 Kebidanan Dan Penyakit KandunganrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 141 AsmaDokumen61 halamanCDK 141 Asmarevliee100% (1)
- CDK 149 Kesehatan JiwaDokumen68 halamanCDK 149 Kesehatan JiwarevlieeBelum ada peringkat
- CDK 142 AlergiDokumen65 halamanCDK 142 AlergirevlieeBelum ada peringkat
- CDK 147 KardiologiDokumen65 halamanCDK 147 Kardiologirevliee100% (1)
- Kumpulan Jurnal TBCDokumen58 halamanKumpulan Jurnal TBCtiovenra100% (3)
- Kesehatan KerjaDokumen59 halamanKesehatan KerjawahyudhanapermanaBelum ada peringkat
- Masalah KesehatanDokumen57 halamanMasalah KesehatanDian AyuningtyasBelum ada peringkat
- CDK 131 MalariaDokumen65 halamanCDK 131 MalariarevlieeBelum ada peringkat
- NapzaDokumen58 halamanNapzadhany134Belum ada peringkat
- CDK 133 Obstetri Dan GinekologiDokumen64 halamanCDK 133 Obstetri Dan GinekologiErika Kusumawati100% (1)