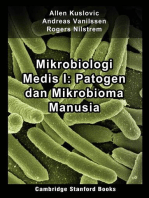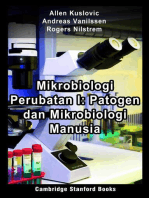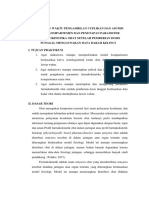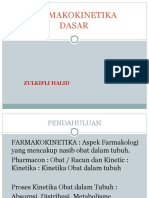CDK 037 Farmakokinetika Klinik
CDK 037 Farmakokinetika Klinik
Diunggah oleh
awadsonJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
CDK 037 Farmakokinetika Klinik
CDK 037 Farmakokinetika Klinik
Diunggah oleh
awadsonHak Cipta:
Format Tersedia
International Standard Serial Number: 0125 -913X
Tulisan dalam majalah ini merupakan pandang-
an/pendapat masing-masing penulis dan tidak
selalu merupakan pandangan atau kebijakan
instansi/lembaga/bagian tempat kerja si penulis.
Karya Sriwidodo
Diterbitkan oleh :
Pusat Penelitian dan Pengembangan PT. Kalbe Farma
Daftar Isi :
Artikel :
3
Pengantar Farmakokinetika
8
Farmakokinetika Klinik
13
Monitoring Kadar Terapeutik Obat
18
Ketersediaan Hayati Obat
21
Pengukuran Klirens Ginjal Obat
26 Teknik Analisis Obat Dalam Cairan Biologis Dengan GLC
dan HPLC
32 Farmakoterapi Rasional
37
Ketersediaan Hayati Sediaan Pelepasan Lambat
41 Strategi Penelitian Farmakokinetika
49
Bioavailabilitas Obat
53 Bagaimana Pengaruh Tubuh Terhadap Obat
55 Konsultasi Farmakologik di Samping Penderita
58 Sekilas Tentang Sub Bagian Farmakokinetika Bagian
Pene-
litian dan Pengembangan PT Kalbe Farma
62
65 Perkembangan
Bunuh Diri Bersama
Mastektomi : Sedikit Mungkin Sa-
ma Dengan Banyak
67 Hukum & Etika : Tepatkah Tindakan Saudara ?
69
Catatan Singkat
70 Humor Ilmu Kedokteran
72
Abstrak abstrak
Cara
Menentukan Kualitas Protein Suatu Bahan Makanan
Artikel
Pengantar Farmakokinetika
Dr Yeyet Cahyati S Apt
PENDAHULUAN
Sejak beberapa tahun yang lalu, pola pengontrolan kualitas
dan pemakaian klinik obat dipengaruhi oleh suatu disiplin
ilmu yang mempelajari nasib obat dalam tubuh. Disiplin ilmu
tersebut kita kenal dengan nama "Fammakokinetika".
Kata " farmakokinetika" berasal dari kata-kata
"
pharma-
con
"
, kata Yunani untuk obat dan racun, dan "kinetic".
Jadi
"
farmakokinetika" adalah
ilmu yang mempelajari kinetika
obat, yang dalam hal ini berarti kinetika obat dalam tubuh.
Proses-
proses yang akan menentukan kinetika obat dalam tu-
buh meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan
ekskresi. Untuk memahami kinetika obat dalam tubuh tidak
cukup hanya dengan menentukan dan mengetahui perkem-
bangan kadar atau jumlah senyawa asalnya saja (unchanged
compound), tetapi juga meliputi metabolitnya.
Bagian
tubuh di man konsentrasi/jumlah obat dan atau
metabolitnya
ditentukan biasanya darah (plasma/serum),
ekskreta (urin, faeses, ludah, dan lain
- lain), atau jaringan tubuh
lain.
PEMODELAN DALAM FARMAKOKINETIKA
Da lam suatu penelitian/studi farmakokinetika, perkembarig-
an kadar/jumlah obat (senyawa asal dan atau metabolitnya)
dalam tubuh dilakukan pada titik-titik waktu yang diskon-
tinyu (misalnya pada waktu-waktu 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3
jam, 6 jam dan 8 jam setelah pemberian obat), karena sampai
Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Institut Teknologi Bandung
Konsultan pada Sub Bidang Farmakokinetika, Bidang Farina-
kologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan PT Kalbe Farina,
Jakarta
dengan saat ini memang tidak mungkin untuk dapat menentu-
kan kinetika obat dalam tubuh secara eksperimental dalam
waktu yang kontinyu. Dengan demikian, data eksperimental
yang akan kita peroleh hanyalah untuk waktu-waktu tersebut
tadi. Sebagai contoh dapat dilihat gambar 1.
Jika data tersebut dibiarkan apa adanya, tidak banyak man-
faat yang bisa ditarik. Oleh karena itu, dalam dunia farina-
kokinetika akan dijumpai apa yang disebut dengan "model
"
.
"Model
"
yang paling sering dipakai adalah model komparte-
mental, di mana keadaan tubuh direjpresentasikan ke dalam
bentuk kompartemen: satu kompartemen atau pluri-komparte-
men. Tiap kompartemen mempunyai besarai volume (isi) yang
disebut "volume distribusi
"
. Model-model tadi hanyalah suatu
representasi
matematika yang tidak bisa dihubungkan dengan
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 3
keadaan fungsi-
fungsi tubuh secara tegas. Oleh karena itu
"
volume
distribusi"tadi disebut
"
volume
distribusi yang
timbul"
(apparent volume of distribution).
Beberapa contoh
model
kompartemental dalam farmakokinetika dapat dilihat
pada gambar 2.
Gambar 2. Representasi model Satu kompartemen dan masing-
masing satu contoh dari model dua kompartemen dan tiga komparte-
men dari model kompartemental tinier terbulca.
Berdasarkan ketepatan regresi kurva
yang diperoleh, kon-
stanta-konstanta
transfer antar kompartemen dan konstanta
kecepatan eliminasi (dan juga konstanta kecepatan absorpsi)
dari model tadi mendekati kinetika
proses tingkat satu, se-
hingga persamaan kinetika obat dapat diselesaikan ke dalam
persamaan umum :
Untuk
model satu kompartemen misalnya, jika obat diberi-
kan secara injeksi intravena (dalam dosis tunggal), perkem-
bangan kadar obat dalam darah dapat direpresentasikan de-
ngan persamaan :
Sedangkan untuk
model 2 kompartemen, dan obat diberi-
kan secara ekstravaskular, persamaan kinetika
yang cocok
adalah :
4 Ccrmin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Waktu
Gambar 3. Bentuk umum kurva perkembangan kadar obat dalam
darah menurut model satu kompartemen setelah pemberian obat secara
injeksi intravena (A), infus dimana infus dihentikan sebelum kesetim-
bangan dicapai (B1), infus dimana infus dihentikan setelah kesetim-
bangan dicapai (B2), dan secara ekstravaskular (oral, rektal, dan lain-
lain) (C).
PROFIL PERKEMBANGAN KADAR OBAT DALAM TU-
BUH (DARAH)
Sebagaimana telah dikatakandi
muka, darah(plasma atau
serum) merupakan cairan tubuh
yang paling sering dipakai
dalam penelitian farmakokinetika. Ini mudah dimengerti
karena: (a)
kebanyakan obat sampai ke reseptornya melalui
darah, dan (b)
tidak mudah mendapatkan jaringan tubuhlain
dari organisme hidup, khususnya manusia.
Profil perkembangan kadar obat dalam darah dapat dibagi
ke dalam tiga kategori :
(a) Profil kinetika, di
mana obat dimasukkan sekaligus ke
dalam sistem peredaran darah (misalnya cara injeksi intra-
vena).
(b) Profil kinetika,di mana obat diberikan secara infus.
(c)
Profil kinetika, di mana obat diberikan secara ekstravasku-
lar (oral,
rektal, dan lain-lain).
Untuk obat yang
diberikan secara injeksi intravena, semua
obat akan masuk sekaligus ke dalam sistem peredaran darah,
kemudian jumlah obat dalam darah akan menurun karena obat
mengalami proses
distribusi dan eliminasi (metabolisme dan
ekskresi).
Untuk obat yang
diberikan secara infus, kadar obat dalam
darah akan naik secara perlahan-lahan sesuai dengan kecepatan
infus, dan akan naik terus sampai infus dihentikan atau sampai
suatu saat di mana kecepatan eliminasi sama dengan kecepatan
infus. Setelah infus dihentikan, kadar obat akan turun kembali
seperti halnya setelah pemberian secara injeksi intravena.
Pada pemberian obat secara ekstravaskular
(oral, rektal,
dan lain-lain), obat akan masuk ke dalam sistem peredaran da-
rah secara perlahan-lahan melalui suatuproses
absorpsi sampai
mencapai puncaknya, kemudian akan turun.
Gambaran umum bentuk kurva kinetika untuk masing-
masing cara pemberian dapat dilihat pada
gambar 3, sedangkan
bentuk kurva kinetika untuk tiapmodel kompartemental
dapat dilihat pada gambar
4.
Adanya suatu kinetika yang
pluri-kompartemental biasanya hanya dapat terlihat dengan
nyata pada pemberian obat secara injeksi intravena.
Waktu
Gambar
4. Bentuk umum kurva perkembangan kadar obat dalam
darah menurut
model satu kompartemen (A),model
dua kompartemen
(B), dan model
tiga kompartemen (C), pada pemberian obat secara
injeksi intravaskular.
KEGUNAAN FARMAKOKINETIKA
Pengetahuan farmakokinetika berguna dalam berbagai bi-
dang farmasi dan kedokteran, seperti untuk bidang farmako-
logi, farmasetika, farmasi klinik, toksikologi dan kimia medi-
sinal.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 5
Bidang farmakologi
Pertama kali, dengan penelitian farmakokinetika dapat di-
bantu diterangkan mekanisme kerja suatu obat dalam tubuh,
khususnya untuk mengetahui senyawa yang mana yang se-
benarnya bekerja dalam tubuh; apakah senyawa asalnya, meta-
bolitnya atau kedua-duanya.
Jika efek obat dapat dinilai secara kuantitatif, data kinetika
obat dalam tubuh sangat penting artinya untuk menentukan
hubungan antara kadar/jumlah obat dalam tubuh dengan in-
tensitas efek yang ditimbulkannya. Dengan demikian daerah
kerja efektif obat (therapeutic window)
dapat ditentukan.
Bidang farmasetica
Dalam bidang farmasetika, farmakokinetika berguna untuk
menilai ketersediaan biologis (bioavailability) suatu senyawa
aktif terapeutik dari sediaannya (sediaan yang diberikan se-
cara ekstravaskular). Seperti sudah banyak dibuktikan, kualitas
zat aktif, jenis dan komposisi bahan pembantu serta teknik
pembuatan sediaan yang dipakai dalam pembuatan suatu se-
diaan dapat mempengaruhi ketersediaan biologis zat aktif dari
sediaan tersebut. Sedangkan ketersediaan biologis zat aktif
akan menentukan efektivitas terapeutik dari sediaan yang ber-
sangkutan.
Selain itu, farmakokinetika dapat membantu menentukan
pilihan bentuk sediaan yang paling cocok/baik untuk dibuat.
Bidang farmasi klinik
Untuk bidang farmasi klinik, farmakokinetika memiliki
beberapa kegunaan yang cukup penting, yaitu :
a) Untuk memilih route
pemberian obat yang paling tepat.
Apakah harus secara injeksi intravena, atau bisa dengan
route
lain seperti secara oral, rektal, dan lain-lain. Ini dapat dilaku-
kan dengan menilai ketersediaan biologis obat setelah pem-
berian dalam berbagai route
pemberian, dan dengan memper-
timbangkan profil kinetika obat yang dihasilkan oleh berbagai
route pemberian tersebut.
b) Dengan cara identifikasi farmakokinetika dapat dihitung
aturan dosis yang tepat untuk setiap individu (dosage regimen
individualization). Sampai dengan saat ini cara identifikasi
farmakokinetika merupakan cara yang paling tepat untuk
pengindividualisasian dosis, khususnya untuk obat-obat dengan
daerah keija terapeutik yang sempit seperti teofilin, dan lain-
lain.
c) Data farmakokiketika suatu obat diperlukan dalam penyu-
sunan aturan dosis yang rasional.
d)
Dapat membantu menerangkan mekanisme interaksi obat,
baik antara obat dengan obat maupun antara obat dengan
makanan atau minuman.
Bidang toksikologi
Dalam bidang ini farmakokinetika dapat membantu mene-
mukan sebab-sebab terjadinya efek toksik dari pemakaian
suatu obat.
Bidang kimia medisinal
Dalam bidang kimia medisinal, pengetahuan farmakokine-
tika dan data farmakokinetika suatu senyawa obat dapat mem-
bantu
memberikan arah terhadap sintesis senyawa-senyawa
obat baru yang lebih unggul: potensi lebih tinggi, stabilitas
6
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
dalam tubuh lebih terjamin, dan profil kinetika yang lebih
menguntungkan untuk pemakaian klinik sesuai dengan indi-
kasinya.
Sebagai contoh, sintesis senyawa-senyawa obat dari golong-
an benzodiazepin. Benzodiazepin mempunyai beberapa indi-
kasi seperti untuk pengimbas tidur, sebagai penenang, anti-
konvulsan, dan lain-lain. Untuk penggunaan sebagai penenang
sekarang telah disintesis beberapa senyawa dengan waktu pa-
ruh eliminasi yang cukup besar (50 jam ke atas) seperti etilo-
flazepat, dan lain-lain.
FARMAKOKINETIKA DI INDUSTRI FARMASI
Secara garis besar, industri-industri farmasi dapat dibagi ke
dalam dua kelompok, yaitu :
I. Industri farmasi yang memproduksi bahan baku (baik se-
nyawa aktif terapeutik maupun bahan pembantu), dan
sekaligus memproduksi sediaan jadi (tablet, kapsul, obat
suntik, dan lain-lain).
II. Industri farmasi yang hanya memproduksi obat jadi.
Untuk industri farmasi yang termasuk ke dalam kelompok
I, khususnya yang mensintesis senyawa-senyawa aktif tera-
peutik baru, penelitian farmakokinetika perlu dilakukan un-
tuk mengetahui/menentukan beberapa hal :
mekanisme kerja obat
arah sintesis senyawa baru selanjutnya
daerah kerja terapeutika obat
aturan dosis standar (standard dosage regimen)
route
pemberian dan bentuk sediaan yang paling cocok
kualitas obat jadi
dan lain-lain.
Untuk industri farmasi yang termasuk kelompok II seperti
lazimnya industri-industri farmasi yang ada di Indonesia dewa-
sa ini, fungsi penelitian farmakokinetika lebih terbatas, ter-
utama untuk menilai kualitas sediaan obat jadi yang dihasil-
kan, yaitu ditinjau dari segi ketersediaan biologisnya
(bio-
availability).
Fungsi lain yang bisa dikembangkan adalah untuk
menilai kembali atau untuk menghaluskan aturan dosis standar
yang sudah ditentukan, dengan memperhitungkan data kine-
tika senyawa aktif dari sediaan obat yang bersangkutan.
Dengan ketersediaan biologis yang tinggi, dosis obat bisa di-
perkecil sehingga penggunaan obat bisa lebih ekonomis. Un-
tuk industri-industri farmasi di Indonesia, fungsi yang kedua
ini
semestinya bisa benar-benar dikembangkan, mengingat
aturan dosis standar yang dipakai yaitu yang sudah ditetapkan
berdasarkan data kinetika obat yang diamati pada orang-orang
Barat. Padahal, obat akan digunakan untuk orang-orang Indo-
nesia yang belum tentu memiliki respon farmakokinetika yang
sama dengan orang Barat terhadap obat-obat yang dipakai.
MASALAH YANG DIHADAPI OLEH INDUSTRI-INDUSTRI
FARMASI DI INDONESIA
Untuk melaksanakan penelitian farmakokiketika terdapat
beberapa masalah yang harus dipecahkan.
Yang pertama adalah masalah tenaga ahli. Untuk penelitian
ini diperlukan tenaga ahli khusus untuk analisis farmakokine-
tika.
Berdasarkan pengalaman penulis, dalam program pen-
didikan tinggi farmasi stratum 1 (Sl) di Indonsia, disiplin
ilmu ini belum diberikan secara mendalam.
Masalah yang kedua adalah masalah peralatan, khususnya
peralatan untuk penentuan kadar obat dalam cairan biologis.
Cara
penentuan kadar untuk keperluan studi farmakokinetika
harus memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang cukup tinggi,
karena: (a) dalam sampel terdapat senyawa lain (baik senyawa
endogen maupun metabolit obat sendiri) yang dapat berinter-
frensi, dan (b) kadar obat yang harus ditentukan kadarnya re-
latif sangat rendah (rata-rata sampai di bawah 1 mcg/ml).
Masalah ini bisa dijawab dengan menggunakan peralatan anali-
sis yang ber-performance
tinggi seperti kromatograf cair penam-
pilan- tinggi ("HPLC
"
),
kromatograf gas, TLC-scanner, dan
lain-lain, di
samping juga diperlukan peralatan ekstraksi dan
derivatisasi untuk skala mikro. Untuk senyawa-senyawa anti-
biotika dengan tujuan studi tertentu (misalnya untuk studi
bioavailabilitas), cara niikrobiologis masih bisa dipakai dan
masih merupakan alternatif pilihan.
Masalah yang ketiga adalah masalah biaya operasional
yang
cukup tinggi; yang diperlukan untuk penyiapan sampel, untuk
analisis kuantitatif dan untuk pemeliharaan alat.
Dengan adanya masalah-masalah itulah maka belum semua
industri farmasi
di Indonesia mampu untuk melakukan pene-
litian farmakokinetika. Pada saat ini memang ketersediaan
biologis suatu sediaan belum ditetapkan sebagai persyaratan
sediaan obat, tetapi kalau nanti persyaratan ini ditetapkan,
mau tidak mau semua industri farmasi harus melaksanakan pe-
nelitian farmakokinetika ini.
PENUTUP
Pengetahuan farmakokinetika bermanfaat dan diperlukan
dalam berbagai bidang pekerjaan farmasi dan kedokteran, se-
perti dalam bidang farmasetika, farmakologi klinik, farmasi
klinik, toksikologi dan kimia medisinal. Karena cukup banyak
masalah yang dihadapi untuk melaksanakannya, sampai de-
ngan saat ini belum semua industri farmasi di Indonsia mam-
pu
melakukan penelitian farmakokinetika ini (khususnya uji
ketersediaan biologis atau bioavailabilitas), padahal pelaksana-
annya cukup penting dalam rangka pelayanan kesehatan yang
lebih rasional, efisien dan efektif.
KEPUSTAKAAN
1. Aiache JM, Devissaguet JPh and Guyot-Herrmann AM (Eds.) Ga-
lenica 2 Biopharmacie, Technique et Documentation, Paris, 1978.
2. Rowland M and Tozer TN. Clinical Pharmacokinetics: Concepts
and Applications, Lea & Febiger, Philadelphia, 1980.
3. Wagner JG. History of pharmacokinetic, Pharmac Ther, 1981; 12 :
537 562.
4. Wagner JG. Do you need a pharmacokinetic model, and, if so, which
one?, J Pharmacokin Biopharm, 1975; 3(6) : 457 477.
5. Wagner JG. Fundamentals of Clinical Pharmacokinetics, 1st ed.,
Illinois; Drug Intelligence Publications, Inc, Hamilton, 1979.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37
1985 7
Farmakokinetika Klinik
dr Budiono Santoso
Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Gajah M
ada,
Yogyakarta
PENDAHULUAN
Semenjak Dost
l
mengajukan istilah farmakokinetika kira-
kira 30 tahun yang lalu, yang
kurang lebih diartikan sebagai
"ilmu
mengenai analisis kuantitatif antara organisma dan
obat", maka kita telah melihat perkembangan
yang begitu
pesat bidang ilmu ini sampai sekarang. Pengertian yang di-
cakup dalam definisi dari Dost tadi sebenarnya kalau ditelaah
lebih dalam meliputi "analisis matematika dari jumlah dan ak-
tifitas obat dalam badan dalam hubungannya dengan waktu".
Namun demikian tulisan ini tidak akan membahas panjang
lebar mengenai "analisis matematka" seperti yang dimaksud
dalam pengertian
di atas, tetapi lebih banyak membicarakan
tempat dan manfaat
dari farmakokinetika dalam klinik, teruta-
ma sehubungan dengan perawatan penderita. Ini didasarkan
pada kenyataan, analisis matematika dalam badan terutama
mengenai jumlah maupun aktifitasnya telah banyak sekali
dibahas dalam berbagai tulisan dan penerbitan. Di lain pihak,
kemanfaatan farmakokinetika dalam kepentingan klinik se-
cara luas sering tidak mendapat perhatian yang layak.
Pengaruh klinik atau terapeutik suatu obat pada seorang
pasien sebenarnya merupakan hasil
dari daya farmakologik
obat tersebut, di man hal yang
terakhir ini akan sangat ter-
gantung pada kadar yang
bisa dicapai pada tempat kerja obat
(reseptor). Sayangnya, pengukuran kadar obat pada reseptor
hampir selalu tidak dimungkinkan. Namun demikian, karena
setiap perubahan kadar obat yang
terukur dalam cairan darah
secara praktis akan mencerminkan perubahan pada reseptor,
dengan pengukuran kadar obat dalam cairan darah akan bisa
diperhitungkan atau diramalkan tingkat aktifitas farmakolo-
gik yang tercapai (lihat Bagan 1). Tinggi rendahnya kadar obat
dalam cairan darah merupakan hasil dari besarnya dosis
yang diberikan, dan pengaruh-pengaruh proses
-proses alami
dalam tubuh mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme sam-
pai ekskresi obat.
Dengan melihat alur peristiwa
yang tergambar pada bagan
satu, sebenarnya farmakokinetika merupakan analisis mate-
matika dari proses-proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan
ekskresi obat. Namun demikian, jika kita kembali kepada defi-
8
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
nisi dari Dost tadi, sebenarnya lingkup farmakokinetika seha-
rusnya juga mencakup analisis matematika
dari aktifitas obat.
Perlu dicatat, walaupun perkembangan teknologi modern saat
ini telah memungkinkan kuantifikasi kadar sebagian besar obat
dalam cairan biologik, misalnya saja dengan teknik kromato-
grafi gas, kromatografi cairan tekanan tinggi (high pressure li-
quid chromatography; HPLC), spektrometri massa (mass spec-
trometry) dan lain-lain, tetapi kuantifikasi aktifitas maupun
pengaruh klinik obat bukan merupakan pekerjaan yang gam-
pang, kalau tidak bisa dikatakan sangat sulit. Sehingga sampai
saat ini farmakokinetika hampir selalu diartikan sebagai studi
kuantitatif dari proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan
ekskresi obat seperti yang
diajukan oleh Greenblatt
dan
Koch-Weser
(1975)
2
Penerapan prinsip-prinsip farmakokine-
tika dalam penanganan penderita secara langsung atau tidak
dikenal sebagai farmakokinetika klinik. Permasalahan yang se-
lalu dihadapi oleh klinikus yang berminat terhadap farmako-
kinetika adalah, bagaimanakah memanfaatkan secara maksimal
pengetahuan tentang kinetika obat untuk kepentingan pena-
nganan penderita?
MANFAATDALAM PENERAPAN KLINIK
Walaupun kepentingan dari penerapan farmakokinetika
kepada masalah-masalah klinik telah banyak sekali diingatkan
dan ditekankan selama bertahun-tahun terakhir ini, tetapi
suatu penelaahan terhadap publikasi -publikasi mengenai far-
makokinetika dalam berkala -berkala terkemuka di dunia
3
telah mengungkapkan, penelitian
-penelitian yang berkaitan
langsung dengan penanganan masalah -
masalah yang dihadapi
dalam klinik kebanyakan hanya menjadi tujuan sekunder.
Misalnya, dalam keadaan klinik
yang sesungguhnya maka
pemberian obat pada pasien lebih sering dengan dosis ganda
(multiple dosing)
dibanding dengan pemberian dosis tunggal
(single dosing),
namun penelitian -penelitian justru lebih ba-
nyak dengan pemberian dosis tunggal baik pada orang sehat
maupun penderita. Bagi para klinikus yang berminat dalam
farmakokinetika, mungkin akan lebih mudah menerima dan
menelaah hasil penelitian dosis berganda dibanding dengan do-
sis tunggal untuk menerapkan hasil tersebut bagi kepentingan
penderita.
Manfaat penerapan farmakokinetika bagi kepentingan pena-
nganan penderita adalah untuk tuntunan penentuan aturan do-
sis (dosage
regimen) yang menyangkut besarnya dosis dan
in-
terval
pemberian dosis, terutama untuk obat-obat dengan
ling-
.
kup terapeutik yang sempit seperti teofilina, digoksin, feni-
toina, fenobarbital, lidokain, prokainamida dan lain-lain.
Contoh kasus 1
Misalnya: jika dalam suatu unit darurat dihadapi seorang
penderita status asmatikus berat, di mana sebagai tindak lanjut
diagnosis
dan evaluasi klinik diputuskan untuk memberi-
kan terapi teofilina
per infus. Dengan melihat beratnya serang-
an asma yang
diderita, klinikus menginginkan kadar teofilina
dalam keadaan tunak
(steady state = C
s
) sebesar 12 ug/ml.
Untuk menentukan berapa kecepatan infus yang perlu diberi-
kan, dan berapa besarnya bolus yang diperlukan bisa diper-
hitungkan dari perhitungan-perhitungan farmakokinetika:
Kecepatan infus = Cl x C
ss
(rumus 1)
Cl adalah klirens tubuh total, yakni menggambarkan ke-
mampuan individu untuk mengeliminasi obat yang
ditunjuk-
kan dengan besarnya
volume darah yang dibersihkan dari
Vd=
volume distribusiyang merupakan volume
hipotetis penyebaran obat dalam cairan tu-
buh.
k
e1
=
tetapan kecepatan eliminasi obat per unit
waktu.
Persamaan (3)
juga bisa ditulis seperti berikut,
t
adalah waktu paroh obat yang
menggambarkan lamanya
jumlah obat (kadar obat) dalam badan turun menjadi separuh-
nya. Karena jika infus diberikan dengan kecepatan
yang sudah
diperhitungkan tadi, kadar obat dalam keadaan tunak
(steady
state) baru akan tercapai 4xt, maka untuk kasus-kasus berat
seperti di atas perlu diberikan suatu dosis pengisi
(loading) agar
tercapai C
ss
dalam waktu cepat.
Besarnya dosis pengisi diperhitungkan,
Contoh kasus 2
Untuk penderita asma yang tidak begitu berat diinginkan
kadar teofilina dalam darah sebesar 5 ug/ml dalam keadaan
tunak. Berapa dosis yang diperlukan dapat diperhitungkan
dari
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
9
Untuk kedua keadaan klinik yang digambarkan pada con-
toh kasus 1 dan 2 di atas, kadar terapeutik bisa dicapai dengan
memperhitungkan kecepatan infus (contoh 1) atau besarnya
dosis oral (contoh
2), jika bisa diketahui nilai volume distribusi
(Vd) maupun waktu paroh (t'%) dan ketersediaan hayati
(F)
untuk dosis oral.
Salah satu manfaat farmakokinetika dalam klinik, seperti
halnya digambarkan pada ke dua contoh di atas adalah untuk
menentukan aturan dosis dan pemberiannya setelah parameter-
parameter kinetika yang diperlukan bisa diketemukan. Persoal-
annya, apakah setiap parameter kinetika harus ditentukan dulu
sebelum menentukan aturan dosis dan pemberiannya pada se-
tiap penderita? Jelas hal ini tidak dimungkinkan karena akan
kehilangan
nilai praktis terapeutiknya. Dalam buku-buku
standar farmakologi klinik atau farmakokinetika, sebenarnya
data mengenai parameter-parameter farmakokinetika dari ber-
bagai obat bisa dicari dan dijadikan pedoman untuk memper-
kirakan nilai parameter kinetika yang
diperlukan (approximate
value).
Namun demikian perlu dicatat hal-hal sebagai berikut:
1). Sebagian besar (hampir semua) data
kinetika obat di-
dapatkan pada orang-orang Barat (ras Kaukasoid), dan makin
banyak diketahui adanya variasi antar etnik yang cukup ber-
makna untuk beberapa obat.
2).
Keaneka-ragaman antar individu dalam satu populasi
dari satu kelompok etnik untuk berbagai obat sering terlalu
besar untuk bisa diambil suatu nilai perkiraan rata-rata yang
dapat diterapkan pada setiap individu.
Manfaat lain dari farmakokinetika adalah mempelajari fak-
tor-faktor yang dapat menipengaruhi proses -proses biologik
yang dialami oleh obat dalam tubuh mulai dari absorpsi, dis-
tribusi, metabolisme maupun ekskresi. Termasuk di sini misal-
nya faktor -faktor genetik maupun lingkungan baik lingkungan
internal maupun eksternal tubuh. Misalnya dengan mengukur
parameter kinetika eliminasi (khusus untuk metabolisme)
suatu obat dalam satu populasi, dapat diidentifikasi kemung-
.
kinan adanya sub populasi yang lain dari umumnya anggota
populasi dalam hal kemampuan metabolisme obat tertentu.
Pengukuran waktu paroh (5%) INH dalam suatu populasi
akan memberikan gambaran distribusi frekuensi yang poli-
modal, di
mana individu
-individu dalam populasi terbagi se-
cara genetik ke dalam kelompok -kelompok asetilator cepat
dan asetilator lambat
4
Contoh
lain, peristiwa-peristiwa saling mempengaruhi
(antar aksi obat) dalam tingkat proses -proses biologik ab-
sorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekskresi dipelajari
dan dievaluasi secara in vivo,
baik pada orang sakit atau-
pun penderita, dengan pendekatan farmakokinetika yakni
dengan pengukuran -pengukuran parameter -parameter kine-
tika peristiwa -peristiwa di atas
5
. Misalnya, hambatan meta-
bolisme primidon oleh karena INH dibuktikan secara klinik
dengan adanya pemanjangan t primidon sesudah pra-perlaku-
an INH dibandingkan tanpa pra-perlakuan INH6.
KEANEKA RAGAMAN ANTAR ETNIK
Seperti telah disinggung di muka, salah satu permasalah-
an yang
sering menjadi bahan pertanyaan dalam berbagai ke-
adaan itu apakah data kinetika suatu obat dari satu kelom-
pok etnik (dalam hal ini umumnya didapat
dari ras Kauka-
soid) bisa dipakai sebagai dasar untuk pembuatan pedoman
aturan dosis dan pemberian pada kelompok etnik lain (ras
Negroid dan Mongoloid)? Jawabannya bisa dua kemungkin-
an, ya dan tidak. Ini mungkin karena tidak ada perbedaan
yang bermakna secara klinik dalam parameter -parameter
farmakokinetika antara masing -masing kelompok etnik. Ke-
mungkinan lain, untuk beberapa obat ternyata perbedaan-
perbedaan antar kelompok etnik ini cukup bermakna klinik
sehingga memerlukan penyesuaian aturan - aturan dosis pada
kelompok etnik lain sesuai dengan parameter-parameter kine-
tik yang didapat pada populasi yang bersangkutan.
Keaneka ragaman antar etnik ini mungkin disebabkan
karena adanya perbedaan dalam frekuensi gen dalam popula-
si yang bersangkutan untuk variasi obat yang di bawah penga-
ruh gen monogenik (polimorfisme genetik) atau oleh karena
perbedaan-perbedaan dalam faktor -faktor lingkungan internal
maupun eksternal yang bisa berpengaruh terhadap proses-
proses kinetika (terutama metabolisme).
Misalnya, keaneka ragaman metabolisme isoniazid
yang
be-
rupa reaksi asetilasi menjadi asetil -isoniazid. Individu-individu
dalam populasi terbagi menjadi asetilator cepat dan asetilator
lambat, di
mana ciri genetik masing-masing di bawah gen do-
minan (R)
dan resesif (r). Frekuensi asetilator pada masing-
masing kelompok etnik sangat berbeda. Pada ras Mongoloid
sebagian besar tergolong ke dalam asetilator cepat dengan ni-
lai
waktu paro (t)
'
kurang dari 2 jam, sedangkan pada ras
Kaukasoid atau Negroidfrekuensi asetilator cepat sedikit lebih
rendah dari pada asetilator lambat
7
.
Pada gambaran histogram, frekuensi distribusi waktu paro
INH dalam kepustakaan nilai antimode yang memisahkan
asetilator cepat dan lambat disebutkan 2 jam, di mana nilai
waktu paro INH kurang dari 2 jam adalah asetilator cepat
4
.
Penelitian terhadap orang-orang Indonesia suku Jawag menun-
jukkan; nilai antimode t - INH yang memisahkan asetilator
cepat dan lambat tidak terletak pada nilai 2 jam, tetapi antara
2 - 3 jam. Mengapa bisa terjadi pergeseran distribusi nilai
t - INH ini sulit diterangkah. Tetapi analisis lebih lanjut
dari data kinetika yang didapat menunjukkan, nilai rata-rata
volume distribusi (Vd) pada subyek -subyek Indonesia
Jawa tadi sebesar 89% SEM 3%berat'badan.
Nilai volume distribusi pada kepustakaan
4,9
rata-rata dilapor-
kan sebesar 61%.
Jika dilihat rumus,
maka kemungkinan pergeseran ke kanan nilai antimode yang
memisahkan asetilator cepat &
lambat pada populasi
Indonesia
- Jawa menjadi antara
2 - 3 jam dibandingkan dengan
nilai 2 jam
pada ras Kaukasoid (Gambar 1),
disebabkan oleh
karena tingginya nilai
volumedistribusi (Vd).
Jika dilihat kecepatan metabolisme rifampisin, pada buku-
buku standar disebutkan, nilai t sesudah pemberian dosis
600
mg
bervariasi antara 1 - 4 jam.
kadar puncak obat aktif
yang dicapai sesudah pemberian
600 mg disebutkan berkisar
antara 7 - 10
ug/ml. Penelitian sementara pada subyek-subyek
Indonesia -
Jawa (Santoso & Suryawati, 1984, belum di-
10
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
N
INH T1/2
Gambar 1. Gambaran histrogram frekuensi distribusi dari waktu
paro INH pada populasi Kaukasoid (atas) dan pada populasi Indonesia
Java (bawah).
Antimode yang memisahkan asetilator cepat (dengan genotipe RR
dan Rr) dan asetilator lambat (dengan genotipe rr) terletak pada nilai
t 2 jam pada orang Kaukasoid dan antara
2- 3jam pada orang-
orang Indonesia Jawa.
publikasi) menunjukkan sesudah pemberian dosis600 mg,
nilai tberagam antara 4 - 12 jam dengan kadar puncak an-
tara 17 29 ug/ml. Perbedaan data
kinetika yang didapat se-
perti ini mungkin mengharuskan untuk mempertimbangkan
kembali aturan dosis pada subyek- subyek
Indonesia - Jawa,
jika diingat kemungkinan pengaruh
-pengaruh toksis dari ri-
fampisin.
Masih banyak lagi contoh
-contoh tentang adanya perbeda-
an antar kelompok etnik dalam parameter
-parameter kinetika
dari obat. Perbedaan ini mungkin relatif kecil, mungkin bisa
juga besar dan mempunyai makna klinik yang mengharuska
n
penyesuaian aturan dosis. Perlu dicatat bahwa perlu tidak-
nya untuk melakukan penyesuaian aturan dosis pada suatu
populasi tidak hanya dengan melihat perbedaan
parameter ki-
netika (misalnya t) tetapi juga mempertimbangkan lebar &
sempitnya lingkup terapeutik
(therapeutic range) kadar obat.
Untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik
yang lebar, ber-
arti jarak antara kadar efektif
minimal dan kadar toksikmini-
mal lebar, perbedaan
parameter kinetik tertentu tidak mem-
bawa konsekuensi apa-apa. Tetapi untuk obat-obat dengan
lingkup terapeutik
yang sempit, adanya variasi kinetika se-
dikit sudah membawa konsekuensiyang sangat penting.
KEANEKA-RAGAMAN ANTAR INDIVIDU
Kalau dikatakandi muka bahwa untuk beberapa obat ter-
nyata didapati perbedaan
yang
cukup bermakna klinik dalam
parameter
-parameter kinetika antara
kelompok-kelompok
etnik,
maka pada individu-
individu dalam satu populasi
pun
akan didapati keaneka-
ragaman kinetikayang mungkin cukup
berarti, terutama untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik
yang
sempit.
Seperti telah dikatakan, keaneka -ragaman
biologik antar in-
dividu dalam proses--proses kinetika (terutama metabolisme)
mungkin berasal dari
faktor- faktor genetik (genetic make-up)
atau faktor-faktor lingkungan (lingkungan internal dan ekster-
nal)
10
. Faktor-
faktor non-genetik meliputi penyakit
-penyakit,
keadaan kurang gizi, umur, pengaruh obat-obat
yang diguna-
kan bersamaan (antar aksi obat) dan lain-lain, termasuk faktor
kebiasaan (merokok), dan kontak dengan cemaran
- cemaran
lingkungan (misalnya pestisida).
Penyakit-penyakit pada
organ eliminasi
misalnya hepar
atau ginjal akan mengurangi kemampuan eliminasi obat dengan
akibat turpnnya nilai klirens (Cl) obat, atau memanjangnya
nilai Ph.
Bagaimanakah aturan dosis obat pada keadaan gang-
guan-gangguan fungsiorgan
seperti ini? Jelas akan diperlukan
suatu penyesuaian dosisyang
tepat dengan kemampuan eli-
minasi tubuh terhadap obat
yang bersangkutan. Pada keada-
an gangguan fungsi ginjal, penyesuaian dosis bisa dikerjakan
dengan memberikan dosis obat yang
sesuai dengan kemam-
puan faal ginjalyang
diukur dengan nilai klirens kreatinin.
Nilai klirens kreatinin memang memberikan gambaran kuan-
titatif faal ginjal. Aturan
-aturan atau rumus-rumus penyesuai-
an dosis pada gangguan faal ginjal banyak dijumpai dalam
buku-buku standar dan dibuat berdasarkan menurunnya nilai
klirens kreatinin.
Jika pada gangguan faal ginjal, ada parameter kuantitatif
yang
bisa dipakai untuk mengukur faal ginjal sehingga penye-
suaian dosis bisa dilakukan berdasarkan baik buruknya faal
saat itu, maka tidak demikian halnya dengan gangguan faal
hati. Tidak ada
parameter kuantitatifyang bisa dipakai untuk
mengukur fungsi hati, sehingga pada keadaan gangguan fungsi
hati jika akan melakukan penyesuaian dosis obat tidak ada
petunjuk yang
tepat. Sayangnya, sampai sekarang orang tidak
bisa menentukan satu obat uji
yang bisa dipakai untuk meng-
ukur kemampuan metabolisme hati untuk segala macam
obat
11
. Walaupun pada mulanya orang banyak menaruh harap-
an bahwa dengan mengukur parameter - parameter eliminasi
antipirin sebagai substratmodel metabolismedi hati, dapat di-
ketahui kemampuan fungsi metabolisme hati untuk obat-obat
lain, ternyata korelasi antara parameter
- parameter eliminasi
antipirin dengan obat
lain terlalu kecil.
Kesulitan yang sama juga dihadapi jika menjumpai kasus-
kasus malnutrisi. Walaupun secara umum sering ada anggap-
an bahwa pada keadaan malnutrisi selalu terjadi penurunan
kemampuan eliminasi obat, tetapi perubahan- perubahan pato-
fisiologik pada malnutrisiyang bisa mempengaruhi kemampu-
an eliminasi obat sangat kompleks
12
. Perubahan- perubahan
juga meliputi proses- proses absorpsi, distribusi, metabolisme
maupun ekskresi obat. Perubahan kinetikayang dialami oleh
satu obat belum tentu sama dengan perubahanyang dialami
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 11
obat lain. Sebab contoh, pada kwashiorkor terjadi penurunan
kemampuan eliminasi isoniazid
13
, tetapi sebaliknya dengan
sulfa-
diazin justru terjadi kenaikan kecepatan eliminasi
14
Klirens (Cl) isoniazid pada 8 orang penderita tbc yang disertai
hipoproteinemia, dengan rehabilitasi nutrisi selama 4 minggu
naik dari 16.0
SEM 2.6 1/jam menjadi 19.9
1/jam
8
(lihat
gambar 2). Ini menunjukkan adanya penurunan kemampuan
metabolisme INH pada keadaan malnutrisi, yang kemudian
kembali membaik sesudah perbaikan gizi.
Gambar 2. Klirens INH pada 8 orang penderita tbc dengan hipo-
albuminemia pada saat masuk (I) sebesar 16.0 SEM 2.6 L/jarn dan se-
sudah rehabilitasi nutrisi dan terapi anti tbc selama 4 minggu (II)
sebesar 19.9
12 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Dari
uraian di atas, maka tidak mungkin untuk membuat
pedoman penyesuaian dosis pada keadaan malnutrisi untuk
semua obat. Setiap obat akan mengalami perubahan-perubah-
an kinetik (kalau ada) sesuai dengan sifat-sifat fisiko kimiawi
dan kinetik masing-masing.
Individualisasi dosis obat pada setiap pasien dengan kondisi
khusus yang potensial bisa merubah parameter -parameter
kinetika . obat, harus dibarengi dengan monitoring terapi.
Besarnya dosis yang diberikan, efek terapeutik yang didapat-
kan, dan efek toksik yang mungkin timbul harus selalu di-
timbang-timbang. Jika memungkinkan, pengukuran kadar obat
dalam plasma akan sangat membantu individualisasi dosis,
terutama untuk obat-obat dengan lingkup terapeutik yang
sempit. Walaupun pendekatan-pendekatan farmakokinetika su-
dah diambil untuk individualisasi dosis, hal ini tidak bisa me-
ngesampingkan pentingnya tindakan monitoring terapi baik
secara klinik terhadap tercapainya terapeutik dan timbulnya
efek toksik, maupun secara laboratorik.
PENELITIAN FARMAKOKINETIK DI INDONESIA
Salah satu hambatan dalam penelitian farmakokinetika
di Indonesia umumnya yaitu kurangnya sarana untuk peng-
ukuran kadar obat dalam cairan biologik. Namun demikian
kalau toh alat-alat yang canggih memang di luar kemampuan
setiap laboratorium untuk mengadakannya, maka alat-alat
yang relatif lebih murah seperti spektrofotometer maupun
spektrofluorometer masih banyak bermanfaat.
Salah satu masalah yang dihadapi saat ini, seperti diuraikan
di depan adalah perlunya data kinetika dari populasi
(popula-
tion kinetics)
orang-orang Indonesia untuk obat-obat ter-
tentu. Sehingga penelitian -penelitian kinetika pada populasi
dari
berbagai kelompok etnik di Indonesia mungkin perlu
mendapatkan perhatian.
Kalau data parameter kinetika obat biasanya didapatkan
dari orang sehat dengan cara pemberian dosis tunggal (single
dose study),
maka untuk penerapan dalam klinik perlu diteliti
kinetika obat-obat pada kondisi
-kondisi klinik khusus dengan
cara pemberian dosis berulang
(multiple dosing). Ini nantinya
akan lebih mudah diterima dan dipakai oleh klinikus dalam
pertimbangan-pertimbangan terapi pada kondisi yang bersang-
kutan. Pengaruh -pengaruh dari cemaran-cemaran lingkungan,
pengaruh penyakit -
penyakit, pengaruh status gizi dan lain-
lain terhadap kinetika obat mungkin menarik untuk diteliti.
KEPUSTAKAAN
1. Dost FH. Der Blutspiegel : kinetik der konsentration Sablaufo in
der kreislauffussigheit. Leipzig : Thieme. 1953.
2. Greenblatt DJ. & Koch Wosser J Clinical Pharmacokinetics. N Eng
J Mod 293 : 702 - 705.
3. Tognoni G Bellantuono C Bonati M D'Incalli M Gerna M Latini
R Mandelli M Porro MG and Riva E. Clinical relevance of Pharma-
cokinetics.
Clinical Pharmacokinetics. 1980; 5 : 105 - 136.
4. Weber WW & Hein DW. Clinical pharmacokinetics of isoniazid.
Clinical Pharmacokinetics, 4 : 401 - 422.
5. Park BK & Brockonridge AM. Clinical implications of enzyme in-
duction and enzyme inhibition. Clinical Pharmacokinetics, 1981;
6 : 1 - 24.
(bersambung ke halaman 66)
Monitoring Kadar Terapeutik Obat
dr Armen Muchtar
Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indo-
nesia, Jakarta
PENDAHULUAN
Yang dimaksud dengan monitoring kadar terapeutik obat
adalah pemeriksaan secara berkala kadar obat dalam darah
guna membantu klinisi dalam menetapkan dosis obat yang da-
pat menyembuhkan atau mengobati penyakit penderita. Per-
lunya monitoring kadar obat dalam tubuh sudah lama dikemu-
kakan, antara lain oleh WilliamWethering, ketika fox
glove
yang mengandung glikosida kuat mulai digunakan, ia meng-
himbau
agar obat yang manjur ini tidak dengan begitu saja di-
tolak penggunaannya, semata-mata karena adanya efek sam-
pingyang berbahaya dan sukar dkendalikan.
Dasar-dasar monitoring kadar terapeutik obat mulai dirin-
tis oleh Brodie dan kawan-kawan ketika mereka berhasil me-
ngukur kadar quinidine dalamplasmamanusia dengan menggu-
nakan fluarometer
1
'
. Arti klinis dari pemeriksaan ini kemudian
diungkapkan oleh Sokolow
2
, ketika ia dapat memperlihatkan
adanya perbedaan interindividuil kadar quinidin
plasma se-
banyak 5 kali pada dosis 3 gram per
hari pada pengobatan arit-
mia. Berdasarkan pengalamannya dalam memonitor kadar qu-
inidin
dalam serum, ia menyimpulkan sebagai berikut
3
*
Efektivitas quinidin dalam pengobatan aritmia atrium kro-
nik dan pencegahan aritmia rekuren, serta timbulnya intoksi-
kasi quinidine terlihat mempunyai korelasi
yang lebih dekat
dengan kadar ketimbang dosis.
* Karena kadar quinidin dalam serum dapat bervariasi lebih
besar dari variasi dalam dosis, maka kadar dalam serummeru-
pakan indilcasiyang lebih terpercaya bila diduga ada toksisitas.
* Walaupun lebih penting dari dosis, sebaiknya kadar dalam
serumtidak dianggap sebagai satu-satunya faktor yang mempe-
ngaruhi toksisitas. Keparahan penyakit, deplesi elektrolit, in-
feksi, ikut pula menentukan toksisitas.
Semenjak itu, sejalan dengan penemuan alat-alat baru yang
sensitif untuk pemeriksaan kadar obat dalam darah, terjadi
perkembangan pesat dalam penelitian dan analisis hubungan
antara dosis -kadar-respon penderita. Secara konsepsionil, de-
wasa ini hubungan tertera dalam Gambar I. Secara matematis,
hubungan itu oleh
Wagner dirumuskan sebagai berikut :
Css = kadar dalam keadaan steady state, fD = fraksi dosis yang
masuk dalam sirkulasi sistemik, t = waktu paruh obat dalam plasma,
Vd = volume distribusi, T = interval pemberian Obat.
INDIVIDUALISASI DOSIS DALAM FARMAKOTERAPI
Dalam praktek, pemberian obat pada umumnya didasarkan
atas dosis rata-rata, yaitu dosis yang diperkirakan memberikan
efek terapeutik dengan efek samping
minimal. Bila dosis rata-
rata itu tidak menimbulkan efek sama sekali atau sudah me-
nimbulkan efek yang
berlebihan, biasanya dokter dengan se-
gera
menghentikan pengobatan karena dianggap 'tidak cocok'
bagi penderita, tanpa perlu mempertimbangkan apakah do-
sis yang
diberilcan itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan
penderita. Pentingnya individualisasi dosis menjadi semakin
beralasan ketika Brodie dkk. memperlihatkan bahwa ada per-
bedaan spesies, strain dan individual dalam kecepatan meta-
bolisme obat
4
. Kemudian, Hammer dan Sjoqvist menemukan
ada perbedaan individual sebesar 30 x lipat
dari kadar "ste-
ady state" desmetil imipramin yang
diresepkan pada suatu do-
sis tertentu
5
. Perbedaan individuil kadar obat dalam keadaan
"steady state" ini barangkali tidak menimbulkan masalah da-
lam penentuan besar dosis bila 'Therapeutic
window" dari
obat
yang bersangkutan cukup besar. Tetapi bila
"therapeutic
window"
suatu obat sempit, individualisasi dosis menjadi pen-
ting,
karena perbedaan dosis yang kecil saja (dalam mg/kg
BB)
sudah dapat menimbulkan perbedaan nyata dalam res-
pons. Individualisasi dosis dengan mudah dapat dilakukan bi-
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 13
Gambar 1.
Faktor-faktor yang menentukan hubungan antara dosis
dan efek obat.
la efek obat mudah diukur, sehingga besar dosis dapat dititra-
si sesuai dengan intensitas respons yang sedang diamati. Bila
respons penderita sukar diamati dengan segera, misalnya kare-
na tujuan pengobatan bersifat profilaksis, atau sukar membe-
dakan efek akibat dosis berlebihan dengan gejala penyakit,
titrasi dosis hanya dapat dilakukan dengan baik berdasarkan
panduan kadar obat dalam darah. Dengan demikian dapat di-
ringkaskan bahwa monitoring kadar terapeutik obat berman-
faat dilakukan guna menentukan dosis dari obat-obat yang :
* kecepatan metabolismenya berbeda nyata secara individual
* mempunyai "therapeutic window"
yang sempit
* efek terapeutiknya sukar atau tidak segera dapat diukur
*
gejala penyakit sukar dibedakan dengan efek samping obat
* kecepatan metabolisme mudah jenuh
OBAT-OBAT YANG KADARNYA PERLU DIMONITOR
Monitoring kadar obat dilakukan atas persyaratan respon
sekelompok penderita mempunyai korelasi yang lebih baik
dengan dosis, dan korelasi itu cukup kuat sehingga dapat diper-
lihatkan pada setiap penderita. Sebelum monitoring itu diker-
jakan secara rutin, terlebih dahulu perlu ada penelitian klinis
yang terkontrol guna memperlihatkan adanya hubungan an-
tara kadar plasma dengan respon klinis. Disain dari
penelitian
seperti ini tergantung pada respon yang dituju, yaitu mungkin
efek terapeutik atau efek toksik atau kedua-duanya
. Obat-obat
yang telah diuji pada percobaan klinik yang terkontrol meme-
nuhi persyaratan tersebut di atas tidak banyak, tetapi merupa-
kan obat-obat penting, sebagian diantaranya masih diperdebat-
14 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
kan manfaat untuk memonitoring kadarnya, karena bila cer-
mat, respon klinis penderita masih dapat diamati. (Tabel 1).
Tabel 1. Obat-obat yang kadarnya sering dimonitor secara rutin.
Obat
Kesaran kadar
terapeutik
Penjelasan
Fenitoin 10-20 mcg/ml Esensial untuk terapi yang ra-
sional karena adanya satu rati-
on kenetik
Teofilin 5-20 mg/ml Esensial untuk terapi rasional
sewaktu serangan akut.Variasi
kenetl individual yang sangat
besar; toksisitas hebat pada ka-
dar 25 mg/ml.
Litium 0,6-1,2 mcg/1 untuk mencegah efek toksik
Fenobarbital 15-20 mg/ml mencegah
therapeutic failure
pada febrile convulsion.
Karbama zepin 5-10 mcg/ml membedakan
"therapeutic fa-
ilure"
dengan efek toksik (pu-
sing, ataksia, diplopia)
Valproate 50-100 mcg/ml Farmakokinetikanya kom-
pleks, masih perlu uji klinik
Quinidin 4-6 mcg/ml Masih perlu diteliti dengan
alat yang lebih sensitif (HPLC)
Prokainamida 4-6 mcg/ml
membedakan therapeutic fai-
lure
dengan efek toksik
Aminoglikosida
-
Gentamisin 5-10 mcg/ml untuk mencegah ototoksisitas
yang irreversibel
Antidepresan
trisiklik
Amitriptilin AT+NT
Hanya untuk depresi
(AT)
Nortriptilin
120-250 mcg/ml endogen
(NT) 50-150 mcg/ml
untuk segera mencapai
kadar terapeutik
Imipraimin (I)
150-300 mcg/ml
Digoksin 0,5-2 mcg/ml
Untuk diagnosis intoksikasi
INTERPRETASI HASIL PEMERIKSAAN KADAR
Haruslah disadari bahwa pemeriksaan kadar obat dalam ca-
iran biologik merupakan bagian yang tak terpisahkandari "phar-
maco therapeutic audit" yang tujuannya untuk memperbaiki
kualitas terapi obat. Tujuan ini hanya dapat dicapai bila ada
'dialog' antara klinisi yang meminta pemeriksaan dengan la-
boratorium pemeriksa. Dalam praktek, tujuan dari monito-
ring akan tercapai dengan baik bila permintaan itu dilengkapi
dengan data klinis yang diperlukan untuk interpretasi (Tabel
2), dan pemeriksaan dilakukan secara berulang selama terapi
pemeliharaan. (Gambar 1). Interpretasi hasil pemeriksaan ka-
dar obat dalam plasma memerlukan berbagai macam data kli-
nis yang lebih banyak
dari data klinis yang diperlukan untuk
menginterpretasikan hasil pemeriksaan kimia klinik untuk di-
agnostik.
Kecuali untuk tolerasi glukosa, pemeriksaan kimia
klinik bila perlu hanya memerlukan puasa malam hari. Waktu
untuk pengambilan sampel darah tidak perlu ketat sekali,
karena zat yang hendak di periksa dalam knnia klinik relatif
kadarnya stabil dari jam ke jam berkat adanya peranan heme-
ostasis tubuh. Dilain pihak interpretasi pemeriksaan kadar
terapeutik obat memerlukan data klinis yang berguna untuk
memperhitungkan secara matematis besarnya dosis dan atu-
ran pemberian, bila resimen dosis harus diubah agar
mencapai
kadar terapeutik (Gambar 2).
Gambar2 . "Flow chart" monitoring kadar terapeutik obat.
UJI KUALITAS DALAMMONITORING
Uji kualitas dalam analisis kadar obat terdiri atas dua
bentuk, yaitu uji kualitas
internal (control) dan uji kualitas
external (inter laboratory quality control).
Uji kualitas internal
bertujuan untuk mengawasi keseksamaan
(precision, relibili-
ty,
reproducibility), sedangkan uji kualitas
external terutama
bertujuan untuk menguji ketepatan
(accuracy) dari metode
pengukuran. Dalam uji kualitas internal
yang dimonitor adalah
penyimpangan hasil pengukuran yang jauh
dari harga rata-
rata, yang
barangkali terjadi karena kekurangcermatan peme-
riksa atau gangguan keandalan
(performance) dari alat-alat
yang digunakan, sedangkan dalam uji kualitas external yang di-
monitor
adalah sensitifitas serta spesifisitas alat, serta kean-
dalan prosedur ekstraksi dari masing-masing laboratorium.
Uji kualitas dalam monitoring kadar terapeutik obat mulai
menarik perhatian ketika Richens
6
melihat adanya perbedaan
besar dari hasil pengukuran kadar fenitoin dari sampel darah
yang sama sumbernya yang dikirim ke enam laboratorium.
Pada tahun 1976, Pippenger dkk
7
mempublikasikan hasil
uji kualitas yang dilakukan secara tersamar dengan menggu-
nakan 3 pooledsera yang masing-masing berisi 4 macam anti-
konvulsan. Sampel dikirim ke laboratorium yang melayani
pemeriksaan kadar obat, dan hasilnya dibandingkan dengan ha-
sil pengukuran oleh 5 laboratorium yang luas pengalaman-
nya dalam pengukuran kadar obat anti konvulsan. Ternyata
ada perbedaan yang sangat besar, di mana pada beberapa ka-
sus ditemui coefficient of variation sebesar 504% (Tabel 3).
Dengan demikian, uji kualitas merupakan hal yang penting
dalam monitoring kadar obat, karena hasil pengukuran yang
2 Data penderita yang diperlukan untuk menjawab permin-
taan monitoring
Nama obat yang akan dianalisis
Nama penderita, umur, kelamin dan berat badan
Nama pengirim dan alamat
Riwayat singkat penyakit
Kehamilan
Alasan untuk memerlsa kadar
Analsis yang terakhir
Tanggal dan jam pengambilan sampel
Tanggal dan jam terakhir minum obat
Kadar kreatininserum
Daftar dari semua obat yang diminum pada waktu yang sa-
ma (dosis, bentuk sediaan, interval pemberian, awal pengoba-
tan/perubahan dosis)
Tanda-tanda perbafican oleh pengobatan atau tanda-tanda
efek samping
Data lain yang dirasa perlu
tidak tepat akan menuntun pengobatan kearah yang salah.
Pengertian yang sesungguhnya dari uji kualitas yaitu pengece-
kan terhadap setiap langkah pemeriksaan, mulai dari pengam-
bilan sampel sampai pada penyerahan hasil pemeriksaan dan
interpretasinya kepada dokter yang meminta. Meskipun demi-
kian, uji kualitas seringkali diartikan secara sempit, yaitu uji
kualitas yang terbatas pada prosedur dan teknik pemeriksaan
laboratorik saja.
SUMBER KEKELIRUAN DALAM MONITORING K ADAR
OBAT
Seringkali tidak disadari bahwa kealpaan atau kekeliruan
dapat terjadi pada tahap-tahap yang
mendahului analisis la-
boratorik. Pemberian obat yang
waktunya tidak sesuai dengan
yang diintruksikan, pengambilan sampel darah yang tidak te-
pat waktunya, sampel darah yang tidak cukup dan terjadi-
nya hemolisis karena hisapan darah ke dalam tabung yang
terlalu cepat adalah kesalahan yang sering terjadi. Karet pe-
nutup tabung reaksi dan kanula dapat menimbulkan persoalan
karena mengandung zat yang dapat menggeser obat
dari ika-
tan protein, dan alat yang terlepas diikat oleh sel darah me-
rah
8
.
Satu titik lemah dalam monitoring ialah perubahan yang
terjadi selama obat disimpan secara invitro dalam tabung plas-
tik. Berapa
lama sampel darah dapat dibiarkan sebelum dipu-
sing? Bagaimana pengaruh kecepatan pusingan terhadap kadar
obat dalam
plasma? Apakah sampel harus disimpan pada su-
hu kamar atau dalam lemari
es? Apakah sampel harus dibeku-
kan dan apa pengaruh pencairan kembali dengan cara pemana-
san?
Perbedaan individual dalam ikatan obat -protein plasma per-
lu diperhitungkan dalam menginterpretasikan hasil pemerik-
saan kadar obat dalam plasma. Seringkali dikemukakan bahwa
yang penting untuk diukur adalah kadar obat bebas, yang
tidak terikat protein plasma, karena jumlahnya lebih mencer-
minkan kadar obat pada reseptor. Kenyataannya, kebanyakan
metoda pengukuran yang ada saat ini adalah mengukur kadar
obat total, balk terikat maupun yang bebas. Perbedaan indi-
vidual dalam jumlah obat yang tak terikat protein plasma se-
Tabel
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 15
ringkali terjadi karena adanya perbedaan sifat
protein, penga-
ruh obat lain yang
diberikan bersama, pengaruh penyakit,
serta sifat fisik dari obat yangdiberikan.
Metabolit aktif dapat mempersulit interpretasi kadar obat
dalam darah, karena sifat-sifat farmakokinetika dan farmakodi-
namika metabolit tidak dkctahui. Kesulitan dengan metabo-
lit adalah belum semuanya dapat diukur serentak dengan me-
ngukur kadar zat asalnya.
Tabel 3.
Hasil uji kualitas external obat antikonvulsan oleh Pip-
penger dkk
7
O b a t
Jumlah labo- Rata2 Coefficient Kisaran
torium yang
of variation (meg/ml)
ikut (%)
Fenitoin
109 13,1 57,3 00 - 70,0
5 12,8 15,7 10,7 - 16,0
Fenobarbital 108 49 50,8 0,0 - 64,0
5 48,1 17,1 34,9 -57,0
Primodon 93
12,3 77,2 0,0 -83
5 12,5 11,5 100-13,5
Etasuksemid 71 14,9 504,7 0,0 - 633,3
5 1,4 156,4 0,0-5.0
PERSONIL D AN PERALATAN DALAM MONITORING.
Sesuai dengan kemampuan personil, kegiatan
monitoring
kadar terapeutik obat dapat dibagi atas dua kelompok; perta-
ma yang
mengeijakan pengukuran dan kemudian melaporkan
hasilnya, dan yang
kedua selain melakukan pengukuran dan
pelaporan hasil, mempunyai kemampuan untuk berdialog de-
ngan dokter pengirim sehubungan dengan
status klinik dan far-
makologik penderita. Sesungguhnya
yang diharapkan adalah
monitoring yang terintegrasi ke dalam therapeutic audit yang
bertujuan memperbaiki kualitas farmakoterapi. Dalam hal ini,
seorang ahli farmakologi klinik mempunyai peranan sentral
dalam kegiatan monitoring kadar terapeutik obat, karena la-
tar belakang pendidlkannya dalam kedokteran dan farmako-
kinetika klinik (Tabel 4).
Tabel 4
Pengukuran kadar obat dalam plasma sebagai bagian dari
therapeutic audit (Sjogvist)
9
Pihak yang
terlibat
Keahlian dalam Farmako-
kologi
Klink.
Analisis obat Terapi
Analisis obat
Ahli farmako-
logi
klinik
Dokter prak-
tek
ya
Mengetahui prin-
sip
tidak
tidak
Prinsip dan
pandangan
global
ya, dalam
bidangnya
tidak
ya
tidak
Peralatan yang digunakan untuk monitoringkadar obat me-
ngalami banyak kemajuan dalam waktu 10 tahun yang ter-
akhir (Tabel 5). Antara tahun 1950-1960, fotometer merupa-
kan alat utama untuk pengukuran kadar obat. Dengan alat ini
diperlukan volume sampel yang besar, teknik estraksi membu-
tuhkan waktu dan majemuk, kurang sensitif dan banyak gang-
guan, sehingga kurang disukai untuk monitoring.
Tabel 5. Metode pengukuran kadar obat dalam darah
Sfektrofotometri dan kalorimetri
Flame fotometry
Bioassay
Fluarometry
Kromatografi: TLC, CLC, HPLC
Ligand assays:
RIA, EIA,
Mass fragmentography (GC-MS)
Pada permulaan tahun 1960 kromatografi gas-cair (GLC)
mulai diperkenalkan. Kelebihan dari fotometri yaitu pemerik-
saan lebih spesifik, karena alat ini mampu memisahkan dan
merlgukur kadar lebih dari satu macam obat. Kekurangannya
alat ini memerlukan penanganan oleh teknisi yang terlatih.
Perkembangan baru dalam GLC adalah pemanfaatan detektor,
terutama detektor nitrogen-fosfor yang bertujuan untuk me-
ningkatkan sensitifitas alat, sehingga hanya sedikit sampel
darah yangdiperlukan.
Kemudian muncul teknk radioimmunoassay
yangmemung-
kinkan pengukuran kadar obat dalam volume kecil. Satu tero-
bosan dalam teknilc radioimmunoassay adalah pengembangan
enzyme immunoaasay (EMIT) dapat memeniksa kadar obat
dari sediaan sebanyak 50 mcl. Setelah kurva harian selesai di-
buat, pengukuran setiap sediaan dapat dilakukan dalam waktu
beberapa menit saja. Kelebihan EMIT adalah sampel darah
yang diperlukah cukup kecil, prosedur sederhana dan hasilnya
cepat diperoleh, serta akurat (Tabel 6).
Tabel 6. Uji kualitas pengukuran kadar fenitoin dengan menggunakan
berbagai metoda (Page dan Richens)
M e t o d a
Jumlah
laboratorium
Jumlah hasil
pemeriksaan
Jumlah percoba-
an yang di luar
95% confidence
limits (%).
GLC
senyawa
asal
34 691 64 (9,3%)
Turunan
51 904 47 (5,2%)
Spektro-
fotometri 10 138 41 (30 %)
Kromato- 3 83 13 (16 %)
grafi lapis
tipis (TLC)
EMIT
8 68
2 (2,9%)
16 Cermin Mania Kedokteran No. 37 1985
Suatu metoda baru yang praktis dan banyak disukai dewasa
ini adalah kromatografi cair bertekanan tinggi (HPLC).
Kelebihannya dari kromatografi gas-cair adalah dalam keteta-
patan, kesederhanaan dan ketepatan analisis, serta pemeriksaan
serentak dari zat asal dan metabolitnya.
Dalam memilih peralatan dan metoda mana yang hendak
digunakan dalam monitoring,
tidak ada patokan yang mudah
untuk diikuti. Biasanya hal itu tergantung pada:
- pengetahuan tentang kebaikan dan kekurangan masing-ma-
sing metoda
- kecakapan personil untuk mengatasi hambatan yang mung-
kin dihadapi
- nilai klinis dari obat yang
hendak diukur kadarnya
- sistem penyediaan, pemeliharaan dari servis dari alat dan
reagensia yang diperlukan.
Berdasarkan kriteria tersebut, dewasa ini dianggap EMITada-
lah alat yang baik untuk pelayanan rutin yang banyak, sedang-
kan HPLC lebih cocok untuk penelitian dan untuk pelayanan
yang permintaanya tidak banyak.
Masalah dana untuk pengadaan alat laboratorium ini seyog-
yanya tidak menjadi persoalan bila kebutuhannya ada, dan
Disajilcan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-
sium Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.
berdasarkan cost-benefit analysis ada manfaatnya buat pende-
rita.
KEPUSTAKAAN
1. Brodie BB and Underfriend S. Estimation of quinine in human
plasma, with note on estimation of quinidine. J. Pharmacol and
Exper. Therap. 1943; 78: 154.
2. Sokolow M and Edgar AL. Blood quinidine concentration as a
guide in the treatment of cardiac arrythmias. Circulation 1950;
1:576-592.
3. Sokolow M. SOme quantitative aspects of treatment with qui-
nidene. Ann Int Med, 1956; 45:482-588.
4. Brodie BB. On mice, microsomes, and man. Pharmacologist
1964;6:12-26.
5. Hammer, W. Sjoqvist F. Plasma levels of monomethy lated tri-
cyclic antidepresants during treatment with imipramine-like
compounds. Life sci 1967; 6: 1895-1903.
6. Richens A. Results of a phenytoin quality control scheme Cli-
nical Pharmacology of Antiepileptic Drugs, Springer, 1975 p
293.
7. Pippenger CE, et al. Interlaboratory variability in determination
of plasma antiepileptic drug concentration.
Arch Neurol. 1976; 33: 351-355.
8. Piafsky KM, Borga O. Inhibitor of drug protein binding in 'Va-
cutainer'. Lancet 1976; 2: 963-964
9. Sjoqvist F. Therapeutic Drug Monitoring Twenty Years Expe-
rience. 2nd World Conference of Clinical Pharmacology and
Therapeutics (Lemberger L and Reidenberg M: eds), 1983; Ju-
ly 31-August 5: 38-63
10. Page J and Richens A. Quality Control of Routine Drug Assays.
Syva Monitor. The Bulletin of Therapeutic Drug Monitoring
1982;11: 1-4..
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 17
Ketersediaan Hayati Obat
Dr M. Masri Apt
Jurusan Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta
PENDAHULUAN
Kegiatan industri farmasi di Indonsia yang telah ada sejak
puluhan tahun yang lalu, telah mendapatkan momentum per-
kembangan yang pesat. Ini karena prioritas yang telah diberi-
kan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Pembangun-
an Nasional mulai tahun 1969. Sebagai hasil nyata selama
15 tahun perkembangannya, yaitu banyaknya produk-
produk obat yang diperdagangkan (specielite)
baik ragam
maupun jenisnya untuk mencukupi kebutuhan kuantitatif
masyarakat.
Arti penting kuantitatif produk obat ini tidak
dapat terlepas dari segi kualitatifnya, yaitu tinjauan dari kuali
-
tas terapeutik produk obat itu sendiri, yang dalam hal ini ke-
tersediaan hayati (bioavailabilitas) obat ikut menjamin keber-
hasilan pengobatan, sebagai salah satu variabel dalam kualitas
terapeutik obat.
Dalam praktek pengobatan, seringkali terjadi bahwa pem
beri obat yang dengan berbagai dasar pertimbangannya telah
mempertukarkan atau menggantilcan pemakaian suatu produk
obat dengan produk lainnya yang ekivalen kimiawi dan ekiva-
len farmasetik. Telah banyak publikasi menyatakan timbulnya
kejadian baik yang bersifat tak efektif maupun timbulnya
toksisitas obat, yang mungkin tidak diketahui kecuali melalui
pengujian klinik mendalam. Masalah biokivalensi obat merupa-
kan masalah serius yang memerlukan penanganan, apabila
dikehendaki suatu situasi yang Iebih balk agar kita tidak men-
jadi korban
dari pemakaian obat, sesuatu yang bertentangan
dengan tujuan pembuatan obat dan pengobatan yaitu untuk
memberiican efek terapi optimal kepada pemakai obat. Uraian
di dalam paper ini bersifat umum, dengan harapan dapat di-
kembangkan
suatu kerja sama multidisipliner dalam pengem-
bangan bioavailabilitas dan bioekivalensi obat, dan bertujuan
meningkatkan kualitas terapeutik produk obat pada umum-
nya.
Disajikan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-
dum Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.
18 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
KETERSEDIAAN HAYATI SEBAGAI KONSEP PENGEM-
BANGAN KUALITAS PRODUK OBAT.
Melihat kembali publikasi penelitian pada tahun 1945 di
mana Oser, Melniek dan Hoehberg mengemukakan cara
mengukur vitamin-vitamin dari
suatu produk obat yang di-
absorpsi oleh tubuh manusia. Hasil ini telah membawa per-
ubahan besar dalam konsep farmasi dari The Art of Compoun-
ding
dalam pembuatan produk obat menjadi saat ini sebagai
drug delivery system yang menurut Wagner
1
, hampir setiap
sesuatu yang dilakukan terhadap sistem ini dapat merubah
kecepatan pelepasan zat aktif dari bentuk dan jumlah yang
diberikan/tersedia pada tempat yang dituju di dalam tubuh.
Keberhasilan pengobatan tidak ditentukan semata-mata oleh
takaran zat aktif di dalam
unit dose akan tetapi bentuk obat
dalam arti keseluruhan. Bentuk obat yang dipandang sebagai
drug delivery system harus dapat menjamin ketersediaan opti-
mal obat di dalam tubuh. Dalam hal ini konsep bioavailabilitas
obat yang menurut Academy of Pharmaceutical Sciences
diartikan sebagai "kecepatan dan besarnya zat aktif utuh
dari
suatu bentuk obat yang masuk ke dalam sirkulasi umum
darah", akan merupakan faktor penentu dan merupakan
parameter keberhasilan pembuatan suatu produk obat.
Definisi yang lebih mendalam
dari F.D.A. yaitu, bioavailabi-
litas suatu (beberapa) zat aktif
dari suatu produk obat di-
definisikan sebagai "kecepatan dan banyaknya yang diabsorpsi
dan menjadi tersedia pada tempat aksi (site of action)
"
.
Defi-
nisi ini
mengarahkan pengertian bioavailabilitas obat kepada
konsep interaksi obat-reseptor, dan membawa arti bioavailabi-
litas menjadi suatu pengertian yang lebih kompleks dan luas.
Bioavailabilitas merupakan karakteristik sesuatu produk obat
terhadap sistem biologis yang menggunakannya, dan men-
cakup juga segi farmakokinetika obat di dalam darah atau
cairan-
cairan biologis,yaitu sebagai respons atau reaksi tubuh
terhadap zat kimia yang masuh ke dalam sistemnya.
Farmakokinetika
obat mengandung banyak parameter
yang dapat dipakai untuk menginterpretasi respons biologis
atau reaksi organ terhadap obat, sehingga cara-cara pengobatan
terhadap pasien akan menjadi lebih rasional, mengandung segi
kuantitatif dan kualitatif.
Dengan pengembangan konsep ini secara keseluruhan, se-
suatu produk obat akan mencapai tingkat yang sebaik-baik-
nya untuk aplikasi klinik.
KETERSEDIAAN HAYATI OBAT SEBAGAI SALAH SATU
VARIABEL PENJAMIN KUALITAS TERAPEUTIK.
Tujuan bioavailabilitas obat sesungguhnya antara lain agar
suatu produk obat mampu memberikan suatu efek terapi
optimal kepada pemakai obat, dalam arti suatu produk obat
akan cepat dan mempunyai kemampuan dalam mengobati
sesuatu penyakit yang diderita seseorang. Dengan ini effektivi-
tas pengobatan akan dicapai dengan baik. Selain itu, bio-
availabilitas juga
menekankan tentang pembatasan atau peng-
aturan pemakaian obat agar keamanan (safety) pemakaian
obat dapat dijamin, dan terhindar dari pengaruh toksik atau
efek-efek yang tidak dikehendaki. Untuk itu perlu diketahui
sejauh mana dan bagaimana obat telah tersedia di dalam darah
untuk mampu memberikan respons klinik yang sesuai, baik
sebagai zat aktif tunggal ataupun kombinasi beberapa zat aktif
dari suatu bentuk obat.
Seringkali penyimpangan dari tujuan-tujuan ini tidak di-
ketahui dengan baik, kecuali melalui analisis klinik yang men-
dalam terhadap pemakai obat, hingga dapat diketahui sebab-
sebab fenomena toksik karena pemberian obat. Terutama un-
tuk obat-obat yang
potensinya tergolong keras, sedangkan
bioavailabilitasnya dan profil farmakokinetika bentuk obat
tersebut terhadap populasi pemakai obat belum diketahui.
Seyogyanya bagi obat-obat tertentu tersebut didapatkan data
tentang bioavailabilitas beserta profil farmakokinetikanya.
Selanjutnya, apabila hal ini telah terpenuhi, perlu ditekan-
kan tentang cara-cara pemberian atau pemakaian obat yang
didasarkan atas penggunaan prinsip farmakokinetika obat,
agar dicapai suatu kualitas terapeutik yang optimal setelah
memperhatikan keadaan atau kondisi penerima obat.
ESTIMASI KETERSEDIAAN HAYATI OBAT.
Pada dasarnya, estimasi bioavailabilitas obat dapat dilaku-
kan menurut metode- metode farmakokinetika dan klinik
'
.
Metode farmakokinetika mencoba memperkirakan availabilitas
fisiologis obat melalui pengukuran obat unchanged di dalam
darah/urin atau metabolit-metabolit yang terbentuk, sedang-
kan
metode klinik didasarkan atas percobaan-percobaan
klinik. Dalam hal ini diperlukan variabel klinik untuk meng-
ukur efikasitas obat atau mengukur besarnya efek obat, se-
perti penurunan kadar gula darah, aktifitas komplek protrom-
bin, dan sebagainya.
Selain kedua metode tersebut di atas, bioavailabilitas obat
dapat juga diperkirakan dari segi farmakologis seperti yang di-
lakukan oleh beberapa peneliti2,
3
.
Data farmakologis yang diperlukan untuk mengevaluasi dan
mengoptimasi bioavailabilitas produk obat adalah pengukuran
intensitas respons farmakologis
yang berupa signal-signal,
dipersyaratkan suatu respons bertingkat dalam fungsinya ter-
hadap dosis. Respons ini tidak
lain hasil interaksi antara zat
aktif dan reseptor di tempat aksi, sehingga akan diperoleh
availabilitas biofasik obat. Dalam hal ini, kemungkinan me-
lakukan sampling untuk menentukan kadar obat di tempat
aksi, dari mana dapat di1corelasikan antara dosis dan respons
farmakologisnya.
Dengan uraian sederhana
di atas, bioavailabilitas obat pada
hakekatnya mempunyai arti luas dan terutama mempelajari
efek-efek obat yang berasal
dari suatu produk obat. Estimasi
dan penilaian bioavailabilitas obat
dari segi klinik meminta
biaya yang tinggi dan membutuhkan banyak waktu, sedang-
kan secara farmakologis relatif juga mahal.
Estimasi availabilitas fisiologis dengan mengukur plasma-
level obat atau ekskresi uriner zat aktif
unchanged, atau ke-
mungkinan lain yaitu saliva level
obat merupakan cara yang
cukup ekonomis dan relatif singkat. Asalkan cara ini dapat
didisain, dikelola dan dievaluasi dengan baik, diharapkan
hasil-hasilnya akan relatif dekat dengan potensi obat yang se-
benarnya.
Penilaian availabilitas fisiologis obat dapat ditarik dari
beberapa variabel farmakokinetika, seperti luas area di bawah
kurva, konsentrasi puncak, waktu mencapai konsentrasi pun-
cak, jumlah ekskresi uriner, jumlah zat yang diserap, dan
sebagainya.
Sasaran studi bioavailabilitas obat
Di samping memperkirakan bioavailabilitas suatu produk
obat, selanjutnya perlu dipelajari faktor yang
mempengaruhi-
nya, faktor yang menjaga atau mempertahankan bioavailabili-
tas, dan faktor kondisi yang diperlukan obat agar bioavailabili-
tasnya dapat berfungsi se-efektif mungkin. Ini merupakan
jangkauan studi bioavailabilitas obat.
Cakupan sasaran- sasaran studi bioavailabilitas suatu produk
obat, seperti tertera pada tabel berikut
4
:
Tabel : Sasaran-sasaran studi bioavailabilitas obat
I. Ekivalensi
A. Bentuk obat.
B. Syarat-syarat pengaturan
C. Pemasaran (lawan produk saingan)
II. Penentuan "waktu pemakaian".
A. Tentang dosis : jumlah dan bentuk
B. Route pemakaian
C.
Pertimbangan-pertimbangan temporal.
III. Interaksi-interaksi.
A. Kompatibilitas (absorpsi)
1. Eksipien-eksipien, bahan pemanis, dan sebagainya
2. Makanan
3. Obat-obat yang dikombinasikan atau dipakai bersamaan
B. Perlakuan terhadap over dosis
C. Interferensi/Potensiasi
1.
Inhibisi metabolisme
2. Induksi Enzim
IV. Korelasi -korelasi in vivo - in vitro.
V. Korelasi-korelasi in vivo - binatang.
VI. Korelasi-korelasi bioavailabilitas - aktivitas (farmakologis).
Kesemua studi ini adalah
bagian dari studi bioavailabilitas
suatu produk obat. Ini memerukan juga studi tentang bio-
availabilitas produk obat
lain yang sama untuk menentukan
bioekivalensinya.
BIOEKIVALENSI BEBERAPA PRODUK OBAT.
Sejumlah penelitian mengungkapkan, beberapa produk obat
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 19
yang
mempunyai ekivalensi kimiawi dan ekivalensi farmase-
tika, namun
di antara beberapa produk-produk itu tidak mem-
berikan bioekivalensi. Hal
ini telah diselidiki misalnya ter-
hadap zat-zat aktif digoksin
5
, oksitetrasiklin
6
, dan lain-lain.
Ketidak-bioekivalensi ini
menimbulkan problem serius da-
lam bidang pengobatan, yaitu apabila masing -masing produ
k
obat belum diketahui bioavailabilitasnya, sehingga pengganti-
an suatu specialite dengan
specialite lain dapat membawa
risiko kepada pemakai obat. Selain itu, telah diketahui juga
adanya ketidak -bioekivalensi obat dari batch-ke-batch suatu
specialite obat dari pabrik yang sana
5
.
Ketidak-bioekivalensi yang dapat terjadi baik antar produk
obat atau antar batch dari suatu specialite obat ini seharusnya
menjadi pemikiran dan tindakan berhati-hati produsen obat
dalam memproduksi obat, yang harus menjaga stabilitas fisis-
khemis dan bioavailabilitas secara bersamaan.
Studi bioekivalensi
Studi bioekivalensi produk obat pada umumnya dengan
maksud membandingkan bioavailabilitas antara
7
: suatu for-
mulasi baru obat standar dibandingkan terhadap formulasi
asli/lama, atau suatu bentuk pemakaian baru obat dibanding-
kan terhadap formulasi yangdiperdagangkan.
Karena sifatnya merupakan pembandingan bioavailabilitas
antar produk obat yang berasal dari beberapa pabrik, diperlu-
kan :
1. Peralatan analitik yang mempunyai kemampuan tinggi.
Alat harus mampu menentukan kadar obat bahkan sampai
beberapa mg/ml cairan biologis. Diperlukan alat-alat dengan
presisi, ketelitian, kepekaan dan selektifitas yang
tinggi. Alat-
alat seperti HPLC, G
LC,
Radioimmune assays, teknik-teknik
fluoresensi, Mass Spectrometry dan sebagainya akan sangat
membantu untuk tugas-tugas tersebut.
2. Prosedur yang seragam (standar) tentang syarat atau cara
bagaimana suatu percobaan bioekivalensi dikerjakan terhadap
zat aktif, mencakup :
disain eksperimental; dipilih model yang paling tepat untuk
keperluan percobaan dengan mengingat jumlah produk obat
yang diuji. Model yang dipilih nantinya harus mampu mem-
perkirakan adanya variabilitas-variabilitas inter/antar subyek,
batch-ke-batch, interval waktu percobaan atau perlakuan.
subyek yang dikenala percobaan dan syarat-syaratnya.
3. Metode Statistik.
Dalam hal ini perlu dipilih metode yang
tepat setelah memper-
timbangkan efek-efek yang ditimbulkan oleh adanya variasi-
variasi, baik dari masing-masing individu di dalam kelompok,
maupun variasi batch dari suatu produk.
ukuran sampel merupakan persoalan sangat penting
yang
harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dengan tepat,
sebagai faktor penentu untuk dapat membedakan bila d
i an-
tara produk obat terdapat perbedaan yang berarti.
Prosedur sampling perlu digariskan atau ditentukan agar
hasil-hasilnya berguna dalam pengolahan data
secara statistik.
Cara analisis statistik dipilih yang paling
sesuai, apakah
studi
membandingkan 2, 3 atau lebih produk obat. Selain
itu, apakah yang diukur variabel karakteristik atau beberapa
variabel. Semua ini merupakan kriteria yang perlu ditentukan
atau digariskan bersama untuk percobaan bioekivalensi obat.
Sasaran studi bioekivalensi produk obat
Dari sekian banyak specialite yang
beredar, tentu saja tidak
semua obat harus mengalami uji kesetaraan bioavailabilitasnya.
Dikenal adanya obat-obat poten dengan risiko yang cukup
besar bagi kehidupan manusia, obat-obat yang mudah me-
nimbulkan efek kematian karena over dosis, atau lainnya, akan
merupakan prioritas penelitian bioavailabilitas dan bioekiva-
lensi obat.
Studi bioavailabilitas obat di Indonesia
Di lingkungan Industri farmasi
Riset bioavailabilitas obat atau produk obat di beberapa
industri
memberikan arti sangat penting bagi perkembangan
industri farmasi tersebut di
masa yang akan datang, dan ke-
pentingan masyarakat pemakai obat
di fihak lainnya. Peneliti-
an ini perlu digalakkan terhadap semua industri farmasi baik
yang menghasilkan produk obat jadi, bahan baku obat dan
juga kosmetika.
Hal ini akan semakin perlu, baik untuk kepen-
tingan masyarakat di dalam negeri, maupun untuk kemungkin-
an pemasaran ke luar negeri, di mana tuntutan bioavailabilitas
obat akan merupakan persyaratan utama.
Pengembangan dan pengaturan bioavailabilitas obat
Masalah bioavailabilitas obat bukan mempakan masalah se-
suatu fihak, namun merupakan persoalan semua fihak y
ang
berkepentingan terhadap obat.
Di dalam hal ini perlu dikelola,
dikembangkan dan diatur segala informasi tentang bioavailabi-
litas dan biekivalensi obat dalam satu sistem terpadu. Untuk
itu diperlukan satu wadah resmi dengan tujuan semata-mata
untuk
membantu
meningkatkan kualitas bioavailabilitas /
terapeutik produk -produk obat Organ yang mampu menam-
pung, mengolah dan mendistribusi informasi bioavailabilitas
dan bioekivalensi obat, di samping Drug Monitoring yang
telah ada.
KESIMPULAN DAN SARAN.
Bioavailabilitas produk obat diakui merupakan salah satu
faktor
yang
sangat penting untuk menjamin efektifitas peng-
obatan dan kualitas terapeutik produk obat itu sendiri.
Bioavailabilitas obat mempunyai pengertian luas, namun
dapat ditentukan beberapa kriteria yang diperlukan untuk
kepentingan evaluasi dan hal ini tergantung dari kesepakatan
ilmiah. Riset bioavailabilitas obat perlu lebih digalakkan ke
segenap industri farmasi, pengembangan produk obat dari segi
in vitro dan in vivo. Di samping itu, diperlukan suatu petun-
juk atau pedoman tentang studi bioavailabilitas dan bioekiva-
lensi obat pada manusia.
Dibutuhkan suatu sistem atau organ resmi yangmelaksana-
kan sistem informasi dari hasil riset bioavailabilitas obat, ber-
ada di bawah pengawasan POM, organ resmi yang anggota-
anggotanya terdiri dari ilmuwan-ilmuwan berkompeten untuk
keperluan tersebut, seperti ahli-ahli farmakologi, biostatistika,
klinis, kimia. Diperlukan bantuan dari segenap industri far-
masi.
Sebelum itu, diperlukan serangkaian diskusi panel tentang
bioavailabilitas dan bioekivalensi obat, membahas tentang
pedoman, prosedur dan hal-hal yang
bersifat penilaian bio-
availabilitas dan bioekivalensi obat.
KEPUSTAKAAN
1. JG Wagner. Biopharmaceutics and Relevant Pharmacokinetics,
ed. I, Illinois : Drug Intelligence Publications, 1971.
(Bersambung ke halaman 61)
20 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Pengukuran Klirens Ginjal Obat
Dra Sri Suryawati Apt
Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
PENDAHULUAN
Dalam menentukan dosis obat suatu individu, seringkali
perhatian khusus perlu diberikan, sehubungan dengan kemam-
puan tubuh individu untuk mengeliminasi obat yang diberikan.
Ini dapat dijumpai misalnya pada individu dengan usia lanjut,
bayi, kelainan fungsi alat- alat eliminasi, atau karena terjadi
interaksi dengan obat lain sehingga eliminasinya terhambat
l-2
Untuk mengetahui kemampuan tubuh mengeliminasi obat
tertentu, pengukuran parameter-parameter kinetika eliminasi
merupakan metoda yang telah banyak dikenal dan diperguna-
kan. Pengukuran parameter - parameter ini meliputi kecepatan
eliminasi (k
el
), waktu paro biologik (t
0,5
) dan klirens tubuh
total (Cl) yang memerlukan pengambilan sampel darah secara
serial selama waktu tertentu. Tentu saja ini merupakan metode
yang rumit dan kurang menyenangkan bagi pasien.
Untuk obat- obat tertentu, terutama yang mengalami
eliminasi dengan cara ekskresi melalui ginjal, dengan meng-
ukur nilai klirens ginjal kita telah mendapatkan gambaran
kemampuan tubuh untuk mengeliminasi obat tersebut. Ini
berdasarkan asumsi bahwa :
Cl
total
=
Cl
renal
+ Cl
nonrenal
Apabila ekskresi ginjal merupakan cara eliminasi utama untuk
suatu obat, maka :
Cl
total =
Cl
renal
Klirens ginjal suatu obat didefinisikan sebagai volume
darah yang dapat dibersihkan dari obat tersebut oleh ginjal
per satuan waktu, sehingga sebenarnya nilai klirens ginjal ini
merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kemampuan
ginjal untuk membersihkan obat dari tubuh. Secara lebih se-
derhana klirens ginjal dapat didefinisikan, dalam hubungan-
nya dengan pembuangan obat melalui ginjal, sebagai hasil
dari kecepatan aliran darah ginjal (Qr ) dan extraction ratio
ginjal (Er );
Disajikan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-
sium Farmakokinetla Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.
Cl
r
=
Q
r
x E
r
(volume/unit waktu), sedangkan E
r
adalah
selisih kadar obat dalam plasma arteri dan vena per kadar
obat dalam plasma arteri, atau
Dapat dikatakan pula, sebenarnya nilai klirens ginjal tersebut
merupakan tetapan yang menggambarkan hubungan antara
kecepatan ekskresi obat pada waktu t (= dAe/dt) dengan
konsentrasi obat dalam plasma Dada waktu t (= C). atau
Perlu diperhatikan bahwa sebenarnya klirens ginjal merupakan
hasil dari proses-proses filtrasi glomeruler dan sekresi maupun
reabsorpsi di sepanjang tubuli renis.
Banyak manfaat yang dapat diambil
dari pengukuran kadar
obat dalam urin. Keterbatasan kemampuan ekskresi ginjal
suatu obat misalnya, dapat diketahui
dari nilai klirens ginjal
yang terukur setelah pemberian dosis bertingkat. Manfaat
yang sangat besar dalam hubungannya dengan terapi obat itu
untuk mengetahui kemampuan tubuh mengeliminasi obat
yang diberikan, bila obat tersebut dieliminasi terutama dengan
ekskresi ginjal. Untuk obat- obat ini, perubahan kemampuan
ekskresi ginjal akan memberikan akibat yang nyata pada efek
farmakologiknya. Selain itu, pengukuran klirens ginjal juga
bermanfaat untuk kepentingan monitoring terapi obat, ter-
utama pada keadaan- keadaan dimana overdosis
perlu dicurigai,
mengingat :
dimana t
0,5
adalah waktu paro obat, kel adalah tetapan ke-
cepatan eliminasi, dan k
r
adalah tetapan kecepatan ekskresi
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 21
ginjal.
Selain hal di atas, untuk obat- obat yang eliminasi utama-
nya adalah ekskresi ginjal ini, pengukuran jumlah obat dalam
urin dapat memberikan gambaran kemampuan absorpsinya
tanpa harus memberikan obat secara intravenosa.
MEKANISME EKSKRESI
Ekskresi obat melalui ginjal dipengaruhi oleh sifat- sifat
fisiko- kimia obat, ikatan dengan protein plasma dan faal
ginjal. Nefron merupakan unit utama fungsi ginjal, terdiri atas
glomerulus, tubulus proksimalis, ansa Henle, tubulus distalis
dan duktus kolektikus. Glomerulus menyaring darah dan
filtrat mengalir ke tubulus. Hampir semua air dari filtrat
direabsorpsi, dan hanya 12 ml/menit saja yang menjadi
urin. Sementara itu terjadi pula sekresi dan reabsorpsi di se-
panjang tubuli proksimalis dan distalis.
Jumlah obat yang diekskresi ke dalam urin merupakan
hasil filtrasi, sekresi dan reabsorpsi. Filtrasi dan sekresi mem-
perbesar jumlah obat, sedangkan reabsorpsi mengurangi.
Dengan kata lain :
Filtrasi giomeruler
Kira- kira 25% volume semenit jantung, yaitu 1,2 1,5 liter
darah permenit, mengalir ke ginjal. Sepuluh persen dari jumlah
tersebut difiltrasi di glomerulus. Hanya obat dalam bentuk
bebas yang terfiltrasi. Molekul obat yang terikat pada makro-
molekul atau sel- sel darah tak dapat melalui membran glo-
meruler.
Dengan demikian filtrat mengandung obat dengan
kadar yang identik dengan kadarnya di cairan plasma, yaitu
fraksi obat yang bebas
(= Cb).
Kecepatan filtrasi pada orang dewasa normal adalah sebesar
kira- kira 125 ml/menit, dan disebut sebagai kecepatan filtrasi
glomeruler atau GFR (glomenilar filtration rate), sehingga :
Mengingat hanya obat dalam bentuk bebas yang dapat ter-
filtrasi, dan fraksi obat yang bebas sebesar f
b
, maka :
kecepatan filtrasi = f
b
x GFR x C
C adalah kadar obat di dalam darah.
Bila ekskresi obat ke dalam urin terutama dengan meng-
gunakan cara filtrasi glomeruler, dan mengingat bahwa
dianggap bahwa kecepatan ekskresi ginjal sama dengan k.e-
cenatan filtrasi. sehingga :
Kreatinin, suatu senyawa endogen dan inulin, suatu poli-
sakarida eksogen, tidak terikat pada protein plasma dan
tidak mengalami sekresi maupun reabsorpsi. Dikatakan bahwa
jumlah yang terfiltrasi, seluruhnya berada dalam urin sehingga
nilai klirens ginjal kedua obat ini dapat digunakan untuk meng-
ukur besarnya kecepatan filtrasi glomeruler.
22 Cumin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Sekresi aktif
Filtrasi berlangsung terus. Sekresi dapat diketahui bila
ternyata kecepatan ekskresi melebihi kecepatan filtrasi obat.
Mengingat persamaan :
sehingga
maka terlihat, apabila nilai klirens ginjal ternyata melebihi
klirens yang disebabkan filtrasi, tentu terjadi pula sekresi.
Mungkin pula terjadi reabsorpsi, namun lebih kecil daripada
sekresinya.
Reabsorpsi
Reabsorpsi diduga pasti terjadi, apabila klirens ginjal yang
terukur ternyata nilainya lebih kecil daripada klirens yang
disebabkan filtrasi glomeruler (yang ditunjukkan dengan nilai
klirens kreatinin). Mungkin pula berlangsung sekresi aktif,
namun besarnya tidak melebihi reabsorpsi. Reabsorpsi dapat
bervariasi dari nol sampai sempurna. Reabsorpsi aktif terjadi
pada beberapa senyawa endogen misalnya vitamin -vitamin,
elektrolit, glukosa dan asam- asam amino, namun untuk ke-
banyakan obat reabsorpsi berlangsung secara pasif. Derajat
reabsorpsi tergantung pada sifat- sifat obat, misalnya polaritas,
derajat ionisasi dan berat molekulnya. Obat- obat yang sangat
lipofilik akan mengalami reabsorpsi sempurna. Reabsorpsi di-
pengaruhi pula oleh faktor- faktor fisiologik seperti misalnya
pH dan kecepatan pembentukan urin.
PENGUKURAN KLIRENS GINJAL
Untuk mengukur klirens ginjal suatu obat, dikenal dua
metode dengan kelebihan dan kelemahan masing- masing.
Dasar ke dua metode ini adalah pengertian yang telah dijelas-
kan di muka, hahwa :
Metode I
Karena tidak mungkin untuk mengukur kecepatan ekskresi
obat ke dalam urin pada waktu sesaat, persamaan di atas
dijabarkan menjadi :
yaitu berdasarkan pengukuran yang dilakukan dalam interval
waktu tertentu.
A Ae/ A t adalah kecepatan ekskresi ginjal obat yang diukur
selama A t, dan C
mid
adalah konsentrasi obat dalam plasma path
pertengahan interval waktu tersebut.
A Ae/ A t dapat dihitung dari :
A Ae/ A t = Q
u
x C
u
sehingga :
Q
u
adalah kecepatan pembentukan win dalam interval waktu
tertentu dan C
u
adalah kadar obat (dalam bentuk babas) dalam
sampel win tersebut.
Nampaknya metode ini sangat sederhana dan praktis untuk
dilaksanakan, namun sebenarnya banyak hal-hal yang perlu
dipertimbangkan pada pelaksanaannya. Penyimpangan hasil
pengukuran klirens ginjal dapat terjadi misalnya pada peng-
ambilan sampel. Pada pengambilan sampel darah misalnya,
idealnya diambil dari arteri
4
. Penggunaan darah venosa perifer
akan
memberikan kadar obat yang lebih rendah daripada
arteri, sehingga nilai klirens yang terukur lebih besar. Namun
tentunya sangat sulit untuk mengambil sampel darah arteri
sehingga umumnya digunakan darah venosa perifer. Kesulitan
lain yaitu dalam mengumpulkan urin, terutama bila tidak
menggunakan kateter. Untuk melancarkan produksi urin,
dapat diberikan minum air putih 400 ml 12 jam sebelum mi-
num obat, 200 ml pada waktu minum obat dan diteruskan
dengan 200 ml tiap 1 jam.
Perhatian khusus perlu diberikan pada penentuan interval
pengambilan sampel urin, karena tergantung pada sifat-sifat
farmakokinetika
masing-masing obat. Pengambilan sampel
urin dilakukan pada fase eliminasi (pada model satu komparte-
men), atau fase terminal (pada model dua kompartemen).
Pengukuran klirens yang dilakukan pada fase absorpsi maupun
distribusi akan memberikan hasil yang menyesatkan. Selain
hal di atas, lama interval pengumpulan urin juga perlu diper-
timbangkan. Bila kecepatan ekskresi obat mengikuti orde 1,
interval sepanjang waktu paro obat pun tidak akan memberi-
kan kesalahan yang berarti. Untuk obat-obat yang ekskresi
ginjalnya tidak mengikuti orde 1, kesalahan pengukuran dapat
diperkecil dengan cara memperpendek interval pengumpulan
urin.
Namun perlu diperhatikan bahwa interval di bawah 0,5
jam akan memberikan hasil yang kurang tepat.
Metode II
Telah diterangkan di muka, metode ini berdasarkan penger
tian bahwa Cl
r
=
dA
__
dt, maka pada waktu 0 sampai t
C
Ae
t
adalah jumlah obat yang telah diekskresi dalam bentuk
tetap ke urin sampai waktu t, dan AUC
t
adalah luas daerah
di bawah kurva kadar obat dalam plasma versus waktu dari
0 sampai t. Pada waktu 0 sampai tak terhingga, maka
Ae
~
adalah jumlah total obat dalam bentuk tetap yang di-
temukan kembali di urin, dan AUC
t
adalah luas daerah di
bawah kurva kadar obat dalam plasma versus waktu dari 0
sampai tak terhingga. Ae
~
dapat dihitung berdasarkan volume
urin yang ditampung dari waktu 0 sampai kira-kira 10 kali
waktu paro obat, dikalikan kadar obat dalam sampel urin
tersebut. Bila semua dosis obat yang diberikan masuk sirkulasi
sistemik dan ekskresi ginjal merupakan cara eliminasi utama,
maka :
Metode pengukuran ini jelas memerlukan waktu yang lebih
panjang daripada metode I, dan sedikitpun tidak boleh ada
urin yang terlewatkan, tetapi mudah dikerjakan karena tidak
direpotkan dengan kesalahan-kesalahan misalnya karena pe-
ngosongan kandung kencing yang tidak sempurna, kurang
tepatnya interval dan lain-lain yang kadang-kadang sulit untuk
diatasi.
Analisis kadar obat dalam urin
Ketepatan pengukuran klirens ginjal obat sangat dipenga-
ruhi metode yang digunakan untuk penetapan kadar obat
dalam sampel. Perlu diperhatikan pula stabilitas obat tersebut
dalam sampel urin maupun plasma, karena seperti telah di-
katakan di muka, klirens dihitung berdasarkan kadar obat tak
berubah. Metabolit-metabolit yang tidak stabil, misalnya
konjugat glukuronida
3
memberikan hasil pengukuran yang
kurang tepat. Selain itu diperlukan pula metode analisis yang
cukup sensitif untuk membedakan obat dengan metabolit-
metabolitnya.
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA
EKSKRESI GINJAL
Hemodinamika ginjal
Perubahan kecepatan aliran darah ginjal umumnya akan
mempengaruhi proses-proses filtrasi glomeruler, sekresi mau-
pun reabsorpsi tubuler, meskipun perubahan di bawah 10
20% mungkin tidak akan memperlihatkan akibat yang nyata
Pengurangan konsumsi natrium mungkin dapat menurunkan
aliran darah ginjal dan kecepatan filtrasi glomeruler, sedang
pemberian infus larutan salin dan diuretik osmotik dapat
memperbesar aliran darah ginjal dan ekskresi air
5
. Tentu saja
hal ini akan berpengaruh pada proses reabsorpsi obat. Bebe-
rapa obat diketahui dapat menurunkan ke-
cepatan aliran darah ginjal, misalnya propranolol
6
. Dalam gam-
bar 1 terlihat bahwa pemberian propranolol 1 jam sebelumnya,
menyebabkan turunnya nilai klirens kreatinin dari 70,9
( SEM 5.3) ml/menit menjadi 58,6 ( SEM 3.4) ml/menit.
Untuk obat-obat yang ekskresinya tergantung pada ke-
cepatan aliran darah ginjal, seperti misalnya salisilat dosis
tinggi, penurunan kecepatan aliran darah ginjal menyebabkan
turunnya nilai klirens ginjal obat tersebut. Pada gambar 2
dapat dilihat, pra pemberian propranolol mengakibatkan
menurunnya klirens ginjal salisilat (setelah pemberian aspirin
1000 mg) dari 4,6 ( SEM 0.56) ml/menit menjadi 3,26 (
SEM 0.35) ml/menit
6
.
Usia
Kemampuan ekskresi ginjal pada umumnya lebih rendah
pada bayi dan anak-anak
7
, dan pada usia lanjut
8
bila diban-
dingkan dengan orang dewasa normal. Ini disebabkan karena
lebih rendahnya kemampuan filtrasi glomeruler pada anak-
anak dan usia lanjut, ditambah dengan belum sempurnanya
sistem sekresi pada bayi baru lahir, meskipun hal ini diim-
bangi dengan ikatan protein yang lebih rendah dan juga
rendahnya kemampuan reabsorpsi
5
.
pH urin
Untuk obat-obat yang bersifat elektrolit lemah, klirens
ginjal sangat dipengaruhi oleh pH urin. Untuk asam lemah
misalnya, lingkungan urin yang asam akan mengakibatkan
berkurangnya jumlah obat yang diekskresi, karena reabsorpsi
tubuli meningkat. Sebaliknya, suatu basa lemah akan meng-
alami kenaikan ekskresi dalam lingkungan urin yang sama.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 23
Dalam gambar 3 dapat dilihat bahwa ekskresi ginjal metamfe-
tamin ternyata lebih banyak pada lingkungan urin asam bila
dibandingkar dengan lingkungan alkalis
9
Ikatan dengan protein plasma
Seperti telah diterangkan di muka, jumlah obat yang meng-
alami filtrasi ditentukan oleh besarnya fraksi obat bebas dalam
plasma. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa apabila
filtrasi glomeruler merupakan mekanisme ekskresi utama,
makin besar fraksi obat yang terikat dengan protein plasma,
makin kecil nilai klirens ginjalnya.
Sebagai contoh dapat dikemukakan perbedaan nilai klirens
ginjal antara sulfadiazin (ikatan protein 40
60%) dan sul-
fametazin (ikatan protein 8090%)
10
. Pada gambar 4 terlihat
bahwa nilai klirens ginjal sulfametazin jauh lebih rendah
daripada sulfadiazin. Perlu diperhatikan, selain ikatan protein
yang besar pada sulfametazin, obat ini eliminasi utamanya
adalah dengan asetilasi.
Ketergantungan dosis
Pada umumnya, kecepatan ekskresi ginjal suatu obat
proporsional dengan kadarnya di dalam plasma, sehingga pe-
ningkatan dosis akan menaikkan nilai klirens ginjal. Namun
pada beberapa obat, pada dosis tertentu akan mengalami
kejenuhan dalam mekanisme ekskresinya, sehingga kenaikan
dosis justru akan mengakibatkan menurunnya nilai klirens
ginjal. Sebagai contoh adalah salisilat dan sulfadiazin
10
Dalam gambar 5 dapat dilihat bahwa klirens ginjal salisilat
lebih rendah pada dosis aspirin 1000 mg dibandingkan dengan
dosis aspirin 500 mg. Dalam gambar 6 dapat dilihat pula pe-
nurunan klirens ginjal sulfadiazin pada pemberian dosis 1000
Gambar 4. Nilai klirens ginjal sulfametazin dan sulfadiazin setelah
pemberian dosis tunggal 500 mg per oral (dari : Suryawati & Santoso,
1985 a).
24 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Gambar 5. Nilai klirens ginjal
salisilat setelah pemberian aspirin
dosis 500 mg dan 1000 mg per oral. (dari : Suryawati &
Santoso,
1985 a).
mg dibandingkan dengan dosis 500 mg.
Sedangkan pada sulfa-
metazin, kenaikan dosis tidak menyebabkan penurunan nilai
klirens ginjal (gambar 7)
10
Kelainan fungsi ginjal
Umumnya nilai klirens kreatinin dianggap sebagai ukuran
untuk mengetahui fungsi ginjal, meskipun sebenarnya nilai
ini hanya menggambarkan kemampuan ultrafiltrasi glomeruler
saja.
Mengingat bahwa klirens tubuh total
merupakan jumlah
klirens ginjal dan klirens non ginjal, maka apabila fungsi
ginjal menurun :
a) Obat-obat yang eliminasi utamanya adalah ekskresi ginjal,
kecepatan eliminasi akan berkurang sehingga mengakibatkan
memanjangnya waktu paro obat, dan mungkin sekali terjadi
akumulasi pada pemberian berulang.
b) Obat-obat
yang eliminasi utamanya tidak melalui ginjal,
penurunan fungsi ginjal tidak akan berpengaruh nyata pada
eliminasinya.
c) Untuk obat-obat yang dieliminasi dengan kedua cara ter-
sebut, penurunan fungsi ginjal akan mengakibatkan menurun-
nya kecepatan eliminasi, tergantung seberapa besar ekskresi
ginjal berperan.
KEPUSTAKAAN
1. Breimer DD & Danhof M. Interindividual differences in pharma-
cokinetics and drug metabolism. Dalam: Breimer DD (ed.). Towards
Gambar 6. Nilai klirens ginjal sulfadiazin
setelah pemberian dosis
500 mg dan 1000 mg per oral. (dari :
Suryawati & Santoso, 1985 a).
Gambar 7. Nilai
klirens ginjal sulfametazin setelah pemberian
per oral dosis 500 mg dan 1000 mg. (dari : Suryawati & Santoso,
1985 a).
(Bersambung ke halaman 61)
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 25
Teknik Analisis Obat Dalam Cairan
Biologis Dengan GLC dan HPLC
Drs Mohammad Makin Ibnu Hadjar PhD
Jurusan Kimia Farmasi Fakultas Farmasi
Universitas Gadfah Mada, Yogyakarta
Bagi beberapa kelompok peneliti, metode analisis obat da-
lam cairan biologis mempunyai arti yang sangat penting.
Masalah- masalah yang berhubungan dengan studi ketersediaan
hayati obat, pengembangan obat baru, penyalahgunaan obat,
farmakokinetika klinik dan riset obat - obatan, semuanya me-
nuntut adanya metode analisis obat dalam sampel biologis
dengan kepekaan, kespesifikan, kecepatan, ketepatan dan ke-
telitian yang
tinggi, tetapi dengan biaya yang tidak terlalu
mahal.
Kesulitan utama yang
dihadapi ialah, selain kadar yang
biasanya sangat kecil, dalam cairan biologis obat ada bersama-
sama dengan metabolit -metabolitnya dengan struktur kimia
yang hampir mirip. Tercampurnya obat dengan zat-zat endoge-
nous dalam sampel biologis (dalam jumlah yang jauh lebih
besar dari obatnya) menambah kesulitan tersebut. Metode
analisis yang
digunakan dengan sendirinya harus mampu men-
deteksi dan menetapkan kadar obat dan metabolit-metabolit-
nya, serta mempunyai prosedur clean-up yang singkat dan
sederhana, agar kehilangan obat dan metabolitnya dapat di-
hindarkan.
Kromatografi cairan-gas (GLC) dan kromatografi cairan
tekanan tinggi (HPLC) telah membuktikan keunggulannya
terhadap metode-metode yang lain dalam analisis obat dalam
cairan biologis.
PERANAN ANALISIS OBAT DALAM CAIRAN BIOLOGIS
DALAM BERBAGAI STUDI
Tidak sedikit obat yang mempunyai indeks terapeutik yang
rendah, di mama
rasio dosis toksis/dosis terapeutik < 10. Obat-
obat tertentu, seperti teofilina, akan memberikan efek samping
yang
toksis apabila konsentrasinya dalam darah mencapai
dua kali konsentrasi terapeutiknya. Sering timbul kesulitan-
kesulitan yang serius bagi penderita yang diberi obat jenis ini,
karena adanya perbedaan konsentrasi terapeutik antar
-individu
yang besar. Untuk terapi yang optimal
dan pengaturan dosis
secara individu diperlukan adanya data
kinetika obat-obat
tersebut. Kegiatan studi farmakokinetika klinik seperti ini ti-
dak akan pernah dapat dilakukan tanpa melaksanakan analisis
obat dalam cairan biologis.
Dalam pengembangan obat baru, pertanyaan tentang keter-
sediaan hayatinya merupakan sesuatu yang sangat penting.
Bisa saja suatu obat baru pada uji farmakologik menunjukkan
adanya potensi, yang kemudian pada uji farmakokinetika
memberikan absorpsi
yang kurang baik dan memberikan harga
waktu paruh yang rendah dalam tubuh. Tentunya
agar tidak
diderita kerugian yang lebih lanjut, arah dari pengembangan
obat baru tersebut harus ditinjau kembali. Keputusan yang
cepat dan tepat itu mutlak memerlukan informasi atau data
yang diperoleh dari percobaan analisis obat dalam cairan bio-
logis.
Studi metabolisme suatu senyawa, yang juga melakukan
analisisnya dalam cairan biologis, seringkali menjurus pada pe-
nemuan obat baru. Oksifenbutazone dan desipramine merupa-
kan contoh obat-obat baru yang ditemukan setelah studi
metabolisme. Mereka masing-masing sebagai metabolit dari
fenilbutazone dan imipramine.
Selain
dalam studi biofarmasetika dan farmakokinetika
tersebut di
atas, analisis obat dalam cairan biologis mem-
punyai peranan yang
penting pula dalam toksikologi, pusat-
pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan obat, deteksi bebe-
rapa penyakit (meningkatnya kadar metilguanidina dalam
serum
penderita uremia),
memperoleh informasi tentang se-
berapa jauh penyebaran suatu tumor
(meningkatnya kadar
5-S-sisteinildopa, suatu asam amino
baru, dalam cairan bio-
logis), dan lain
sebagainya.
PROBLEM
ANALISIS OBAT DALAM CAIRAN BIOLOGIS
Kadar obat dalam cairan biologis yang
umumnya sangat
kecil (10-
6
- 10-
12
g
mr
-1
) membatasi metoda-metoda yang
dapat digunakan untuk menetapkan kadarnya; hanya metode-
metode yang
sangat sensitif saja yang dapat dipakai. Dalam
cairan biologis, obat selalu ada bersama-sama dengan meta-
26 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
bolit - metabolitnya. Struktur kimia dari metabolit - metabolit
tersebut pada umumnya hampir mirip dengan struktur kimia
obat induknya, sehingga sukar mendeteksi mana yang obat
mana yang
metabolit. Mutlak perlu digunakannya metode
analisis yang sangat selektif. Zat- zat
endogenous (dalam jum-
lah yangjauh lebih besar
dari jumlah obatnya) dalam matriks
sampel biologis sangat
mengganggu pelaksanaan analisis,
khususnya metode spektroskopi, karena zat- zat endogenous
tersebut juga
menyerap sinar ultraviolet/visibel. Prosedur
clean- up sampel yang berbelit- belit akan memberikan risiko
hilang atau berkurangnya obat dan metabolit - metabolitnya.
GLC dan HPLC
yang selain mampu mendeteksi dan mene-
tapkan kadar, juga sekaligus mampu melakukan pemisahan,
sehingga dapat mengatasi
problem yang didiskusikan di atas.
Berikut akan didiskusikan masalah kromatografi.
KROMATOGRAFI
Kromatografi dalam berbagai bentuknya telah digunakan
secara luas sebagai teknik pemisahan dan analisis. Pada tahun
1941, Martin dan Synge, yangkemudian mendapat hadiah
Nobel, dalam makalahnya mengemukakan pengertian- pengerti-
an dasar tentang kromatografi gas (GC) dan HPLC. Tidak ku-
rang dari 10 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1952, James
dan Martin untuk pertama kali mengintrodusir penggunaan
GC. Sejak saat itu GC telah menjadi bentuk kromatografi
yang palingbaik dan berkembang dengan sangat cepat. Ben-
tuk- bentuk kromatografi yang lainseperti kromatografi ker-
tas, kromatografi lapis tipis (TLC), kromatografi penukar ion
dan kromatografi eksklusi (semuanya termasuk kromatografi
cairan), belum memperoleh sukses yang sama seperti yang
telah dicapai oleh GC. Hal ini disebabkan karena efisiensinya
yang rendah serta waktu analisisnya yang panjang: Pada awal
tahun 1960- an, Giddings menunjukkan bahwa kerangka kerja
teoritis yang dikembangkan untuk GC berlaku sama baiknya
untuk kromatografi cairan, dan antara tahun 1967 - 1969
Kirkland, Huber, dan kelompok Horvath, Preiss dan Lipsky
mengemukakan penggunaan HPLC yang pertama kali. Dengan
menggunakan tekanan yang tinggi (sampai dengan 5000 psi),
HPLC dapat mengatasi kelemahan- kelemahan dari kromato-
grafi cairan pada umumnya, misalnya viskositas cairan yang
relatif lebih besar dibanding dengan viskositas gas, sehingga
HPLC mampu memberikan waktu analisis (5 - 30 menit)
yangkurang lebih sama dengan waktu analisisnya GC.
Dalam beberapa hal, memang, baik teknik GC maupun
HPLC dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang
sama. Keduanya mempunyai keunggulan yangberupa sensitivi-
tas, selektivitas dan kecepatan analisis yang tinggi. Dengan
menggunakan detektor ultraviolet mereka dapat memberikan
pola spektrum ultraviolet dari masing- masing komponen sam-
pel yang diperiksa. Keduanya dapat dihubungkan langsung
dengan spektrometer massa, sehingga dapat diperoleh pola
spektrum massa dari masing- masing komponen campuran
yang sangat penting untuk elusidasi struktur kimianya. Kedua
teknik ini juga dapat digunakan untuk kromatografi prepara-
tif, yaitu masing- masing komponen campuran dapat dikum-
pulkan dalam keadaan yang sangat murni, sehingga dapat di-
gunakan untuk percobaan- percobaan penelitian lebih lanjut.
Kedua- duanya juga dapat dilengkapi dengan sistem micro-
processor, sehingga analisis dapat dilaksanakan tanpa kehadir-
an sang operator.
Akan tetapi, sejumlah besar obat - obatan tidak dapat di-
analisis dengan teknik GC, karena sifatnya yang sangat polar
(konjugat sulfat dan glukuronat dari obat dan metabolit-
metabolitnya), tidak mudah menguap dan tidak stabil terha-
dap panas, kalau tanpa modifikasi struktur kimianya terlebih
dahulu. Teknik HPLC merupakan pilihan utama untuk ana-
lisis
golongan obat- obat tersebut. Kemampuan HPLC untuk
menangani secara langsung obat- obat dan metabolit
- metabolit
yang sangat polar serta konjugat - konjugatnya dalam cairan
biologis sungguh merupakan suatu keunggulan. Pelaksanaan
analisisnya yang
pada suhu kamar akan mencegah peruraian
obat selama proses analisis. Selain detektor, jumlah variabel
yang dapat diatur dalam HPLC jauh lebih banyak dari pada
dalam GC. Kalau hanya fase diam saja yang dapat divariasi
pada analisis dengan GC, maka baik fase diam maupun fase
gerak kedua- duanya dapat divariasi dalam teknik HPLC.
Bukan itu saja, berbagai ragamnya
mode
kromatografi (mode-
mode adsorpsi, partisi, penukar ion dan eksklusi) pada proses
pemisahan dengan HPLC memungkinkan teknik ini dapat di-
gunakan untuk analisis hampir semua jenis obat. Keunggulan
lain yang
disumbangkan oleh HPLC dalam analisis obat dalam
cairan biologis ialah prosedur ekstraksi, dan clean-up yang
mendahului analisis relatif sangat berkurang dibandingkan
dengan teknik GC. Bahkan telah dilaporkan keberhasilan
analisis obat dalam urin dengan menginjeksikan langsung
sampel ke dalam kolom dan menggunakan sistem reversed
phase, dimana fase gerak digunakan air yangdapat mengelusi
zat- zat endogenous yang menyerap ultraviolet itu bersama
solvent front. Jumlah jenis detektor yang dapat dipilih pada
teknik
HPLC juga lebih banyak dibandingkan dengan GC.
Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut akan didiskusikan
dasar- dasar GC dan HPLC.
KROMATOGRAFI GAS
Pada GC, fase geraknya berupa gas yang inert, sedang fase
diamnya dapat berupa cairan (disebut kromatografi cairan- gas
atau "gas- liquid chromatography", yangdisingkat GLC) atau
berupa padatan (kromatografi padatan- gas, "gas- solid chroma-
tography", GSC). Proses pemisahan pada GLC terjadi dengan
mekanisme partisi, sedang pada GSC nielalui mode adsorpsi.
Untuk sampel yang berupa obat, GLC lebih populer daripada
GSC. Ini disebabkan karena hampir semua obat akan meng-
alami peruraian dengan kondisi yang diperlukan agar terjadi
elusi pada GSC Oleh karena itu, istilah GC dalam literatur-
literatur dimaksudkan untuk GLC.
Fase diam yang palingsering digunakan pada analisis obat
dalam cairan biologis dengan teknik GLC ialah siloksan yang
tersubstitusi (OV- 1 dan OV- 17) dan polietilen glikol yang di-
salurkan (1 - 5%) pada solid support.
Bagian- bagianpokok suatu GLC ialah : silinder tempat gas
pembawa, pengatur aliran dan tekanan gas, tempat injeksi
sampel, kolom, detektor, rekorder, dan thermostat untuk
tempat injeksi sampel, kolom dan detektor.
Setelah sampel diinjeksikan, komponen- komponen sampel
yang ada dalam keadaan uap dibawa oleh gas pembawa ke da-
lam kolom. Dalam kolom, komponen - komponen tersebut ber-
partisipasi antara gas pembawa dan fase diam (cairan). Fase
diam ini secara selektif menahan komponen - komponen sampel
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 27
sesuai dengan koefisien distribusinya, sehingga terbentuk pita-
pita komponen yang terpisah dalam gas pembawa. Bersama
aliran gas pembawa, pita-pita komponen ini meninggalkan ko-
lom dan dideteksi oleh detektor yang kemudian oleh rekorder
dibuat kromatogramnya.
Macam detektor yang dikenal pada GC ialah detektor han-
taran panas ("thermal conductivity detector", TCD), detektor
ionisasi
nyala ("flame ionization detector
"
, FID), detektor
penangkap elektron (
"
electron capture detector' , ECD) dan
detektor yang hanya khusus mendeteksi senyawa yang me-
ngandung unsur nitrogen dan fosfor.
TCD berdasar atas prinsip, suatu benda yang panas akan
kehilangan panasnya pada suatu kecepatan yang tergantung
kepada komposisi gas di sekitarnya. Jadi, kecepatan hilangnya
panas itu dapat digunakan sebagai ukuran tentang komposisi
gas. Detektor ini kurang sensitif untuk analisis obat dalam cair-
an biologis.
FID merupakan detektor yang paling luas penggunaannya,
bahkan dianggap sebagai detektor yang universal untuk analisis
obat dalam cairan biologis menggunakan GLC. Pada detektor
ini, komponen-komponen sampel yang keluar dari kolom di-
bakar dalam nyala (campuran gas hidrogen dan udara atau
oksigen). Sejurnlah besar ion yang terbentuk dalam nyala
masuk ke dalam celah elektrode dan menurunkan tegangan
listrik dari celah elektrode mula-mula. Penurunan tegangan ini
yang kemudian dicatat sebagai sinyal oleh rekorder. Intensitas
sinyal ini berbanding lurus dengan konsentrasi solute dalam gas
pembawa.
Aliran elektron sebagai hasil ionisasi gas pembawa (nitrogen
atau argon/methan) dalam ECD memberikan sinyal yang be-
rupa baseline suatu kromatogram. Bila kemudian suatu se-
nyawa masuk ke dalam detektor, sebagian dari elektron ter-
sebut akan ditangkap oleh senyawa sebelum mereka mencapai
plat detektor. Ini mengakibatkan aliran arus listrik dalam de-
tektor berkurang, yang oleh rekorder akan dicatat sebagai
suatu peak. Detektor ini hanya dapat digunakan untuk se-
'wawa obat-obatan yang dapat mengabsorpsi elektron dengan
mudah, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung gugus kar-
bonil dan nitro yang terkonjugasi sertasenyawa-senyawa yang
mengandung halogen-organik. Sensitivitas detektor ini pada
tingkat pikogram. Suatu psikotropik baru (1,2-benzisoxazole-
3-acetamidoxime hydrochloride), analisisnya dalam plasma
berhasil dilakukan dengan GLC menggunakan detektor ini.
Spektrometer massa dapat juga digunakan sebagai detektor
pada GLC. Kombinasi GLC dengan spektrometer massa (GC-
MS) saat ini merupakan suatu alat yang ampuh dalam identifi-
kasi obat dan metabolit-metabolitnya dalam cairan biologis.
Untuk obat-obat yang sukar menguap dan tidak stabil
terhadap panas, agar dapat dianalisis secara GLC harus dideri-
vatisasi secara kimia. Obat-obat dengan gugus fungsional yang
sangat polar seperti hidroksil (OH), karboksil (COOH) dan
amino (NH
2
) diubah menjadi eter (OR), ester (COOR) dan
amida (NHCOR) yang merupakan gugus-gugus yang kurang
polar.
KROMATOGRAFI CAIRAN TEKANAN TINGGI
Seperti tampak dari namanya, fase gerak yang digunakan
pada HPLC berupa cairan yang dialirkan dengan tekanan
sangat tinggi. Fase diamnya dapat berbagai macam, tergantung
mode kromatografi yang dipilih dalam proses pemisahan.
Proses pemisahan dalam HPLC dapat dilakukan dengan
berbagai mode kromatografi sebagai berikut :
Mode kromatografi cairan-cairan (partisi) :
fase diam
berupa cairan yang disalutkan atau diikatkan secara kimia
pada
solid support.
Komponen sampel yang dipisahkan ber-
partisi di antara fase diam dan fase gerak. Pada mode ini di-
kenal sistem normal phase (fase diam berupa senyawa yang
polar, sedang fase geraknya non-polar) dan sistem reversed
phase
(fase diam berupa senyawa yang non-polar, sedang fase
geraknya polar). Dengan sistem normal phase dapat dipisahkan
pestisida, steroid, anilina, alkaloida, glikol, alkohol, fenol,
aromatik dan komplek logam.
Sistem reversed phase dapat
memisahkan alkohol, aromatik, antrakuinon, alkaloid, oligo-
mer, antibiotika, barbiturat, steroid, pestisida-klor dan vita-
min-vitamin.
Mode kromatografi pasangan ion ('ion pair chromato-
graphy'; IPC) : merupakan bentuk khusus dari kromatografi
cairan-cairan yang digunakan untuk pemisahan senyawa obat-
obat yang ionik atau yang dapat terionisasi seperti amino
biogenik, sulfonamida, karboksilat dan sulfonat. Ada dua me-
kanisme proses pemisahan pada IPC, yaitu mode partisi, di
mana molekul sampel yang ionik atau yang mudah terionisasi,
tetapi tidak bersifat lipofilik, membentuk suatu pasangan ion
dengan suatu counter-ion yang cocok yang ditambahkan pada
fase geraknya. Dengan terbentuknya pasangan ion ini akan
menambah sifat lipofilik sampel, sehingga memperbesar afini-
tasnya terhadap fase diam. Mekanisme yang kedua ialah mode
penukar ion, di mana counter-ion yang polar dianggap sebagai
diabsorpsi oleh fase diam hidrokarbon sehingga seperti mem-
bentuk suatu titik penukar ion, pada mana molekul sampel
yang polar akan dapat diabsorpsi seperti pada kromatografi
penukar ion.
Mode kromatografi padatan-cairan (adsorpsi) :
fase
diamnya berupa padatan yang dapat mengadsorpsi molekul
sampel yang dipisahkan secara reversibel. Dalam sistem normal
phase digunakan fase diam yang polar (silica gel, alumina)
dan fase gerak non-polar (heksan, kloroform). Sebaliknya,
pada sistem reversed phase
digunakan fase diam yang non-
polar (butiran polimer) dengan fase gerak yang polar (air,
etanol). Dengan mode adsorpsi ini dapat dipisahkan anti-
oksidan, vitamin, steroid, barbiturat, zat-zat warna, amina,
hidrokarbon, fenol, alkaloida, amida, lipida, asam-asam amino
dan alkohol-alkohol.
Mode kromatografi penukar ion ("ion-exchange chroma-
tography'; IEC) : fase diam terdiri dari suatu matriks yang
tegar, yang permukaannya menyangga suatu muatan positif
sehingga menyajikan suatu titik penukar ion (R
+
). Bila diguna-
kan suatu fase gerak yang mengandung anion, titik penukar
ion tersebut akan menarik dan memegang suatu counter-
ion
negatif (Y
-
). Sampel yang berupa anion (X
-
) kemudian
dapat bertukaran dengan
counter-ion (Y
-
) :
R
+
Y
-
+ X
-
'7
=
R
+
X
-
+ Y
-
.
Karen prosesnya menyangkut penukaran anion, disebut kro-
matografi penukar anion. Proses kromatografi penukar kation
dapat digambarkan :
28 Cermin Dunia
Kedokteran No. 37 1985
Fase diam penukar kation mengandung gugusan asam, dibeda-
kan menjadi penukar kation kuat (SO
3
-
) dan penukar kation
lemah (COO ). Fase diam penukar anion mengandung gugus-
an basa; dibedakan menjadi penukar anion kuat (NR
+
) dan
penukar anion lemah (NH2). Mode kromatografi ini berhasil
digunakan untuk memisahkan dan analisis asam amino, asam
nukleat, protein, asam karboksilat, sulfonat aromatik, gula-
gula, obat-obat analgetik, vitamin, purin dan glikosida.
Mode kromatografi eksklusi ("exclusion chromatogra-
phy"; EC, juga disebut "gel filtration chromatography", gel
permeation chromatography" atau "gel chromatography") :
memisahkan campuran sesuai dengan ukuran dan bentuk mo-
lekulnya. Molekul-molekul kecil yang dapat masuk secara
bebas ke dalam pori-pori fase padat dikatakan sebagai mem-
punyai koefisien distribusi K = 1, sedang molekul-molekul
besar dieksklusi secara sempurna dari seluruh pori-pori mem-
punyai K = 0. Molekul-molekul ukuran sedang mempunyai
K antara 0 dan 1. Jadi, molekul-molekul besar akan bergerak
jauh lebih cepat melalui kolom dibanding dengan molekul-
molekul kecil. Molekul-molekul akan dielusi berturut-turut
sesuai dengan penurunan ukurannya. Contoh fase diam pada
mode ialah suatu gel dekstran dalam bentuk butiran yang di-
pasarkan dengan nama Sephadex. Mode kromatografi ini ber-
hasil
digunakan pada pemisahan senyawa-senyawa dengan
bobot molekul > 2000, termasuk polimer organik (poliole-
fine, polistirene,
polivinyl, poliamida), bipolimer (protein,
asam nukleat, oligosakrida, peptida, gula-gula, glikol).
Selain beragamnya mode kromatografi, keunggulan HPLC
juga karena luasnya pilihan detektor yang dapat digunakan.
Secara garis besar, detektor dalam HPLC dapat dibedakan :
1 ). berdasar pengukuran diferensial suatu sifat yang dimiliki
baik oleh molekul sampel maupun fase gerak (disebut
bulk
property detector,
yang termasuk ini misalnya : detektor
indeks bias, detektor konduktivitas dan detektor tetapan
dielektrika).
2). berdasar pengukuran suatu sifat yang spesifik dari mole
-
kul sampel (disebut solute property detector). Jenis yang ke-
dua ini dibedakan lagi menjadi : yang tidak perlu adanya
pemisahan fase gerak, termasuk ini ialah detektor-detektor
fotometer (uv-vis dan fluoresen), polarografi dan radioaktif;
dan yang fase feraknya harus dipisahkan dahulu, termasuk ini
ialah FID dan ECD.
Pada detektor ultraviolet/visibel, deteksi komponen sampel
didasarkan pada absorpsi sinar ultraviolet (untuk detektor
ultraviolet) dan sinar tampak (untuk detektor visibel). Detek-
tor ultraviolet merupakan detektor yang paling luas digunakan
karena sensitivitas dan reprodusibelitasnya yang tinggi serta
mudah operasinya.
Obat-obat yang fluoresen dapat dipisahkan dan dianalisis
dengan indikator fluorimeter, seperti aflatoksin, beberapa
asam amino aromatik, fenol, kuinolin dan estrogen. Untuk
obat-obat yang tidak berfluoresensi dapat dibuat menjadi
turunannya
yang berfluoresensi dengan pereaksi seperti
dansyl klorida (5-dimetilaminonaftalene-l-sulfonil klorida).
Detektor ini lebih peka dari pada detektor ultraviolet.
Detektor fotometer inframerah juga dapat digunakan pada
HPLC. Dengan detektor ini dapat dibuat pola spektrum infra-
merah dari komponen sampel sehingga gugus-gugus fungsional-
nya dapat diketahui.
Detektor indeks bias merupakan detektor yang juga luas
penggunaannya setelah detektor ultraviolet. Dasarnya ialah
pengukuran perbedaan indeks bias fase gerak murni dengan
indeks bias fase gerak yang berisi komponen sampel, sehingga
dapat dianggap sebagai detektor yang universal pada HPLC.
Detektor ini kurang sensitif dibanding dengan detektor ultra-
violet dan sangat peka terhadap perubahan suhu.
Sekarang juga telah ada HPLC yang dikombinasi dengan
spektrometer massa. Dengan HPLC-MS, prospek studi yang
berkaitan dengan analisis obat dalam cairan biologis menjadi
lebih cerah lagi.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa bagian-bagian pokok dari
suatu HPLC meliputi wadah penyuplai pelarut (fase gerak),
pompa penakan, tempat injeksi sampel, kolom, detektor dan
rekorder.
Untuk memperoleh kondisi terbaik pada analisis obat da-
lam cairan biologis menggunakan HPLC, perlu pendekatan
yang akan diuraikan sebagai berikut.
PENDEKATAN DALAM ANALISIS DENGAN HPLC
Sifat Permasalahan
Macam dan sifat obat yang akan diperiksa harus diketahui
dahulu,
misalnya kelarutan, pola spektrum ultraviolet, pola
spektrum inframerah (untuk gugus fungsional), struktur mo-
lekul dan lain sebagainya. Perlu juga diketahui apakah yang
perlu dianalisis itu,
misalnya hanya obatnya saja atau obat
dan
metabolit-metabolitnya. Apakah sebagai hasil analisis
cukup suatu kromatogram atau masing-masing komponen
sampel harus dipisahkan/dikompulkan untuk percobaan lebih
lanjut? Juga apakah analisis yang akan dilakukan itu hanya
dimaksudkan untuk memecahkan suatu masalah saja atau akan
dijadikan metode kontrol kualitas yang rutin ?
Jawaban dari semua pertanyaan di atas akan mempengaruhi
dan menentukan pendekatan analisisnya.
Pemilihan Mode Kromatografi
Setelah
menentukan sampai seberapa jauh analisis itu di-
perlukan dan sifat-sifat sampel, sang analis kemudian memilih
mode kromatografi yang paling cocok untuk memberikan
hasil yang dikehendaki. Pemilihan mode kromatografi (partisi,
adsorpsi, penukar ion, pasangan ion atau eksklusi) yang di-
dasarkan atas kriteria bobot molekul, kelarutan dan sifat
gugus fungsional dapat dilihat pada transparansi.
Seleksi Fase Diam dan Fase Gerak
Suatu pemisahan akan berhasil apabila tercapai suatu kese-
timbangan yang tepat antara kekuatan-kekuatan intermoleku-
lar yang melibatkan molekul sampel, fase gerak dan fase diam.
Sebagai ukuran kekuatan-kekuatan intermolekular tersebut
ialah polaritas molekul. Hampir semua pemisahan-pemisahan
yang baik diperoleh karena cocoknya polaritas molekul sampel
dengan polaritas fase diam dan digunakannya fase gerak yang
berbeda polaritasnya.
Pada kromatografi dengan sistem normal phase, komponen
sampel yang paling kurang polar akan dielusi terlebih dahulu;
penambahan polaritas dari fase geraknya akan menurunkan
waktu elusinya.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 29
-
3
Pada kromatografi dengan sistem
reversed phase, komponen
sampel yang paling polar akan terelusi terlebih dahulu; penam-
bahan
polaritas dari gase gerak akan menaikkan waktu
elusi-
nya. Diagram pada transparansi akan menggambarkan hal ini.
Pemilian Detektor
Detektor index bias merupakan satu-satunya detektor pada
HPLC yang universal, tetapi kurang sensitif dan sangat peka
terhadap perubahan suhu. Detektor ultraviolet dengan panjang
gelombang yang variabel merupakan pilihan yang paling baik
bagi sekelompok besar obat-obatan. Dalam hal-hal yang sangat
spesifik dapat digunakan detektor-detektor fluorometer dan
elektrokimia.
Pemisahan Kromatografi
Untuk mempertimbangkan kondisi analisis yang optimal
perlu difahami pengertian-pengertian pokok dalam kroma-
tografi yang secara umum berlaku bagi semua mode. Dua para-
meter kromatografi yang penting dalam optimasi hingga di-
peroleh suatu pemisahan yang maksimum dan dalam waktu
yang minimum:
1). Persamaan yang menghubungkan waktu retensi (t
R
) dan
faktor kapasitas (k'),
2). Persamaan
yang menghubungkan resolusi (Rs) dengan
faktor kapasitas (k
'
),
retensi relatif ( a) dan jumlah theore-
tical plates
(N) :
Harga optimum untuk k
'
adalah antara 1 10. Harga k'
yang lebih besar cenderung akan memperpanjang waktu re-
tensi dan pita-pita kromatografi terelusi sebagai peaks yang
lebar dan datar sehingga sukar untuk mendeteksinya. Apabila
harga k
'
sudah terletak pada rentangan yang optimum, maka
harga k
'
tidak sepantasnya diubah. Perubahan resolusi hanya
akan diperoleh dengan menaikkan N, atau a .
Faktor kapasitas (k
'
) merupakan parameter yang paling
mudah dioptimasi, karena biasanya hanya menyangkut per-
ubahan kekuatan fase gerak. Tetapi k
'
sebetulnyajuga dapat
diatur dengan merubah fase diamnya, walaupun hal ini jelas
tidak menyenangkan.
Harga optimum untuk a terletak antara 1,05 10. Per-
ubahan harga dapat diperoleh dengan merubah sifat fase diam
dan/atau fase gerak. Perubahan fase gerak di sini lebih ber-
makna kalau yang diubah komposisi fase gerak; bukan per-
ubahan kekuatannya. Pengaruh perubahan a lebih sukar di-
ramalkan dari pada perubahan k
'
dan N, dan dalam suatu
sampel yang terdiri dari banyak komponen, perubahan a ha-
nya akan merubah urut-urutan peaknya saja. Tetapi dalam hal
waktu analisis, memang perubahan a merupakan cara yang ter-
baik untuk memperbaiki Rs. Karena untuk memperbaiki Rs
lebih mudah dicapai dengan menaikkan N, cara ini nampak-
nya lebih baik. Tetapi perbaikan Rs dengan cara ini umumnya
akan mengakibatkan bertambahnya waktu retensi, karena pe-
nambahan N biasanya diperoleh dengan penambahan panjang
kolom atau pengurangan kecepatan alir fase gerak. Secara
umum dapat dikatakan bahwa optimasi pemisahan dapat di-
lakukan, dengan menentukan fast diam yang sesuai dengan
mode kromatogtafi yang akan digunakan, kemudian meng-
ubah-ubah fase gerak
hingga dicapai pemisahan yang sebaik-
baiknya.
Setelah diperoleh suatu kromatogram
yang baik, tentunya
yang terakhir ialah bagaimana mengevaluasi
data kromato-
gram itu.
Analisis Kualitatif
Identifikasi suatu komponen sampel dapat dilakukan de-
ngan membandingkan harga t
R
dari peak yang muncul dalam
kromatogram dengan harga t
R
suatu reference standard.
Apa-
bila harga t
R tersebut sama dalam dua atau lebih sistem yang
dicoba,
maka dikatakan bahwa kedua senyawa tersebut
identik.
Untuk lebih menegaskan kesimpulan tersebut, dapat
dilakukan percobaan
spiking, yaitu kepada sampel ditambah-
kan obat standard reference
kemudian dibuat kromatogram-
nya. Apabila kedua senyawa tersebut identik maka
standard
reference akan menaikkan tinggi peak
dari obat yang dianalisis.
Untuk HPLC yang dilengkapi dengan spektrometer massa,
identifikasi obat yang dianalisis dapat dilakukan dengan
mencocokkan pola spektrum massa yang diperoleh dengan
yang ada dalam literatur-literatur. Untuk obat yang baru,
identifikasinya dilakukan dengan mencoba mengelusidasi
strukturnya tidak saja dengan spektrum massanya tetapi
juga dengan spektra NMR, IR dan UV dari obat yang dipisah-
kan dan dikumpulkan dari eluat yang keluar dari HPLC.
Analisis Kuantitatif
Detektor yang ideal pada HPLC ialah yang mampu meng-
hasilkan sinyal yang mempunyai korelasi linier dengan konsen-
trasi komponen sampel. Dengan asumsi seperti tersebut,
konsentrasi komponen sampel dapat diturunkan dari intensitas
sinyal yang ditunjukkan dalam kromatogram.
Dikenal dua cara pengukuran secara kuantitatif, yaitu
dengan mengukur peak height dan peak area.
Dikenal beberapa metode untuk merubah data peak height
atau peak area
dari suatu kromatogram menjadi konsentrasi
dari komponen sampel yang sesuai, yaitu dengan membuat
kurva baku dengan cara-cara external standard, internal stan-
dard dan standard addition.
Sebelum sampai kepada bagian aplikasi GLC dan HPLC
dalam analisis obat dalam cairan biologis, berikut akan disaji-
kan preparasi sampel dalam GLC dan HPLC.
PREPARASI SAMPEL
Seperti telah dikemukakan di muka, prosedur ekstraksi
dan clean-up dalam HPLC lebih sederhana dari teknik-teknik
yang lain. Telah banyak dilaporkan bahwa beberapa sampel
biologis dapat dianalisis dengan HPLC dengan langsung meng-
injeksikan ke dalam kolom (pra-kolom). Namun adanya pro-
tein, lipid, garam-garam dalam jumlah yang relatif banyak
dalam sampel biologis, perlu diperhatikan untuk menghindari
adanya gangguan pada efisiensi kolom. Protein dapat dihilang-
kan dengan cara pengendapan, ultrafiltrasi dan penggunaan
pra-kolom. Pereaksi-pereaksi asam seperti asam trikloroasetat,
asam perklorat dan asam tungstat dapat digunakan untuk
mengendapkan protein dalam cairan biologis untuk analisis
30 Cennin Dunia Kedokteran No. 37 1985
obat-obat yang tahan asam. Untuk yang tidak tahan asam,
pengendapan dilakukan dengan etanol atau metanol. Peng-
gunaan pra-kolom untuk
menghilangkan protein telah dila-
porkan pada analisis frusemide, dengan langsung menginjeksi-
kan plasma ke dalam pra-kolom yang mempunyai susunan
sama dengan kolom analisis. Dengan
menggunakan buffer
fosfat (pH 2,5) sebagai fase gerak, protein tertimbun pada pra-
kolom ini.
Fase gerak metilenklorida atau dietil eter dapat mengelusi
lipid netral dengan menggunakan mode kromatografi adsorpsi.
Dengan mode yang sama fase gerak campuran metilenklorida/
metanol atau metanol dapat mengelusi fosfolipid. Lipid yang
terelusi ini tidak akan mengganggu bila digunakan detektor
ultraviolet
karena absorpsi molar senyawa-senyawa tersebut
rendah.
Pada sistem
reversed phase, lipid dapat tertahan pada fase
diam hingga dapat menyebabkan terganggunya efisiensi ko-
lom. Ini dapat diatasi dengan mengaliri kloroform setiap se-
telah 100 kali injeksi plasma yang sari dengan eter.
Kalau problem utama pada sampel plasma adalah penghilang-
an protein dan lipid, maka pada sampel urin masalah yang
dihadapi adalah,
bagaimana menghilangkan garam-garam
anorganik atau komponen-komponen dengan bobot molekul
rendah yang memiliki sifat-sifat kromatografik yang mirip
dengan obat yang dianalisis. Konsentrasi obat dalam sampel
urin juga perlu mendapat perhatian. Garam-garam anorganik
dapat dipisahkan dari sampel urin dengan melewatkan sampel
melalui suatu kolom yang berisi resin Amberlite XAD-2 yang
dapat
menahan senyawa-senyawa organik dan meneruskan
garam-garam anorganik dan dengan mengelusinya dengan
metanol, dapat diperoleh senyawa organik yang dikehendaki.
Akhirnya akan diberikan beberapa aplikasi GLC dan HPLC
dalam analisis obat dalam cairan biologis.
APLIKASI GLC DAN HPLC DALAM ANALISIS OBAT
DALAM CAIRAN BIOLOGIS
Teknik GLC dan HPLC telah membuktikan kemampuan-
nya untuk menganalisis sejumlah besar golongan
obat-obatan
dalam cairan biologis.
Analisis dibenzepine dan metabolit-metabolitnya serta pe-
netapan fenobarbital, primidone dan fenitoin, semuanya dalam
cairan biologis, secara GLC, akan dibahas sebagai contoh.
Contoh analisis menggunakan teknik HPLC yang akan di-
diskusikan meliputi penetapan propranolol dan 4-dehidroksi-
propranolol dalam plasma secara simultan dan penetapan para-
setamol dan metabolit-metabilitnya.
KEPUSTAKAAN
1. Pryde A, and Gilbert MT.
"Aplications of high performance
liquid
chromatography."
New York: Chapman and Hall Ltd., 1979.
2.
Hamilton RJ, and Sewell PA. "Introduction to high performance
liquid
chromatography".
New York: Chapman and
Hall Ltd., 1977.
3.
Smith RV,
and Stewart IT. "Textbook of
biopharmaceutic analy-
sis". Philadelphia: Lea & Febiger, 1981.
4.
McNair HM, and Bonelli EJ. "Basic gas
chromatography", 5
th
ed.,
California: Varian Aerograph, 1969.
5. Dell D. in "Assay of
drugs and
other trace compounds in biological
fluids" (E.
Reid, ed.), Amsterdam:
North-Holland Publishing
Company, 1976; p. 131 134.
6.
Done JN, Knox JH, and Loheac J.
"Applications of highspeed
liquid chromatography". London:
John Wiley & Sons, 1974.
7.
Nation RL, Peng GW, and Chiou WL. Journal of
Chromatography,
1978; 145 : 429.
8. Rutherford DM, and Flanagan
RJ. Journal of
Chromatography,
1978; 157 : 311.
9. Schlicht
HJ, and Gelbke HP. Journal
of Chromatography,
1978;
166: 599.
Disajilcan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-
sium Farmakokinetllca Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 31
Farmakoterapi
rasional
dr. R.H. Yudono
Jurusan Farmakologi Fakultas Kedokteran
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Menurut saya, kalau penanggulangan penyakit secara medis
itu rasional, maka sudah semestinya
farmakoterapinya juga
rasional. Sayang sekali banyak pengobatan oleh dokter tidak
dilakukan secara rasional; apalagi orang awam yang meng-
obati diri sendiri (self medication)
dengan obat bebas atau
obat bebas terbatas.
Untuk dapat melakukan pengobatan secara rasional, per-
tama-tama kali harus ditegakkan diagnosanya, atau bila hal ini
tidak mungkin dilakukan, setidak
- tidaknya harus ditentukan
diagnosa kemungkinan. Jika seorang dokter tak dapat menen-
tukan diagnosa kemungkinan, maka dengan sendirinya ia tak
dapat
memberi pengobatan secara kausal rasional. Karena
kewajiban dokter harus mengurangi penderitaan dan memper-
panjang umur, maka kalau ia tak dapat memberi pengobatan
kausal rasional, setidak
- tidaknya ia dapat mengurangi pen-
deritaan secara simtomatik rasional, asal ini tidak menopengi
(masking)
penyakitnya atau bahkan membuat penyakitnya
bertambah parah.
Yang paling disayangkan tentunya ialah, bila diagnosa su-
dah dapat ditegakkan secara rasional, akan tetapi farmakotera-
pinya tidak rasional.
Hal ini dapat disebabkan karena dokter kurang menguasai
patofisiologi dari
badan yang sakit, kurang menguasai farmako-
logi klinik
dengan farmakokinetikanya dan kurang dapat
menghubungkan secara logis patofisiologi dengan farmakologi.
Dari
pihak penderita, seringkali terapi rasional tak memberi-
kan hasil yang diinginkan karena kurang menuruti nasihat
dokter (penderita dengan pengobatan jangka panjang, harga
obat mahal, orang berumur lanjut yang suka lupa dsb.) (Black-
well, 1973).
Evaluasi dari terapi tentunya diperlukan untuk membukti-
kan bahwa terapi itu tepat, artinya dapat menyembuhkan
dan tidak menyebabkan efek-efek yang merugikan.
Beberapa hal tidak rasional dapat terjadi, seperti misalnya,
dalam : (a)
Penentuan obat dengan rejimen terapinya, atau
(b) Cara pemberian obat.
PENENTUAN OBAT DAN REJIMEN TERAPI
Suatu hat yang masih belum kita ketahui dengan pasti
adalah apakah
suatu obat yang dibuat oleh
industri farmasi
yang terkenal itu tentu lebih bail( dari
pada suatu obat yang
sama yang dihasilkan oleh industri farmasi yang kecil yang
kurang terkenal (therapeutic equivalence).
Penentuan obat secara rasional dapat lebih mudah dilaku-
kan bila kita selalu membiasakan diri untuk mempertimbang-
kan lebl dulu masak-masak hubungan antara indikasi, hukum-
hukum farmakologi klinik dan sifat-sifat obat. Kalau kita su-
dah terbiasa berpikir secara logis
- metodis sistematis, maka
pengalaman menjadi berharga untuk di kemudian hari diguna-
kan untuk menentukan penggunaan obat dengan cepat. Se-
lain itu, kebiasaan mengevaluasi hasil terapi menyebabkan
kita lebih menguasai ilmu
pengobatan tersebut, termasuk me-
ngetahui obat mana yang balk stabilitasnya, tidak mudah di-
rusak oleh isi lambung-usus, keterdapatan hayati
(bioavailabi-
lity),
sedikit efek sampingnya, dan kurang mengganggu organ-
organ badan yang penting.
Patofisiologi dari
penyakit perlu diketahui supaya dapat
disesuaikan dengan macam obatnya, formulasinya, dosisnya,
frekuensi pemberian seharinya, dan cara pemberiannya.
Formulasi obat harus sesuai dengan keadaan tertentu dari
traktus digestivus.
Misalnya jangan memberikan obat yang
mudah dirusak oleh asam bila ada gangguan hiperasiditas
dan sebagainya. Pengurangan dosis obat perlu dilakukan pada
adanya gangguan ekskresi renal atau; frekuensi pemberian obat
sehari
mungkin perlu dikurangi ataupun obat diganti dengan
yang diekskresi melalui hepar/empedu. Pada keadaan hipo-
proteinemia, dosis perlu dikecilkan karena albumin yang
mengikat obat berkurang, sehingga obat bebas (unbound)
bertambah konsentrasinya. Penderita dengan gangguan hepar,
perlu dikurangi dosisnya atau frekuensi pemberian sehari.
Pada adanya dekompensasi kordis, karena distribusi obatnya
lambat, maka dosisnya perlu dikurangi, karena pada permula-
an terjadi kumulasi dari obat di dalam darah; jika konsentrasi
32 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
obat itu mencapai otak dan jantung, maka obat itu dapat me-
racuni.
Jika penderita memerlukan lebih dari satu
macam obat,
maka perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya interaksi-
interaksi antara obat itu sendiri, fungsional atau kimiawi
maupun fisikokimiawi atau secara tidak langsung melalui
pendesakan dari ikatannya pada albumin atau melalui pe-
macuan atau penghambatan enzim-enzim metabolisme obat.
Interaksi antara obat yang satu dan yang lain dapat juga terjadi
pada tempat absorpsinya, tempat aksinya dan pada ekskresi
renalnya. Di samping itu masih juga adanya variabilitas karena
perbedaan genetik (poor and efficient metabolizer, rapid and
slow acetylator dll.). Sehubungan dengan ini perlu dipertim-
bangkan tentang kemungkinan perubahan - perubahan dosis
atau frekuensi pemberian obat sehari, karena dosis yang ter-
tera di buku-buku farmakologi atau farmakope (dosis stan-
dar ) kebanyakan ditentukan pada orang ras Kaukasoid.
Karena kemungkinan adanya interaksi - interaksi antara obat
yang satu dan yang lain yang kadang- kadang sukar diperkira-
kan terlebih dulu itu maka dokter perlu mengendalikan diri
untuk tidak terlalu banyak memberikan obat sekaligus (poly-
pharmacy) pada seorang penderita.
Farmakoterapi hams dilakukan secara individual mengingat
keadaan penderita :
umur yang muda sekali atau yang tua sekali
sifat-sifat genetik
lingkungan hidup (kebiasaan merokok, minum alkohol,
business dan sebagainya).
riwayat sakit dan riwayat pengobatan sebelumnya : derajat
sakitnya setelah diobati, berhasil atau tidak berhasil me-
nyembuhkan, efek samping yang merugikan, allergi, inter-
aksi-interaksi, kebiasaan tak dihabiskan atau dimakan tak
menurut aturan, kebiasaan mengobati sendiri dan sebagai-
nya.
Umur muda sekali
l
Makin muda anak, relatif makin besar dosisnya, karena
metabolismenya lebih kuat (per kg BB).
Makin tinggi temperatur badan, makin kuat metabolisme-
nya : tiap derajat Celcius kenaikan temperatur badan sesuai
dengan 10% kenaikan metabolisme.
Anak terlalu gemuk (obesitas) relatif memerlukan lebih se-
dikit obat, karena jaringan lemak relatif kurang berpenga-
ruh dalam metabolisme.
Karena enzim-enzim detoksifikasi, fungsi renal, pengikatan
pada protein serum dan barier darah otak belum sepurna,
maka jangan mudah memberi obat pada bayi. Untuk bayi
yang baru lahir (neonatus) penetapan dosis belum ditetapkan
secara tepat (akurat).
Oliguria pada tiap umur memerlukan pengurangan dosis atau
pengurangan frekuensi pemberian obat sehari.
Penentuan konsentrasi obat di dalam plasma darah penting
untuk memonitor terapi; jadi bukan dosis obatnya waktu di-
berikan pada penderita. Therapeutic range adalah jarak antara
konsentrasi efektif minimal dan konsentrasi efektif maksimal
dari obat di dalam plasma darah pada sebagian besar dari
populasi.
Intoksikasi karena obat dapat diharapkan terjadi, jika konsen-
trasi obat itu di dalam plasma darah melebihi therapeutic
range.
atau
Dosis obat = Volume distribusi X konsentrasi obat dalam plasma
darah.
Volume distribusi dari obat yang satu berbeda dengan obat yang lain,
karena kelarutannya di dalam cairan-cairan badan dan ikatannya pada
jaringan jaringan badan berbeda.
misalnya :
Digoksin (Lanoksin) :
konsentrasi plasma darah terapeutik : 0,9 ng/cc
0,0009 ug/cc
0,0009 mg/L
= 7,5 X 0,0009 = 0,00675 mg/kg
Walaupun Vd itu ditentukan dari data yang didapat pada pem-
berian i.v., juga dapat digunakan untuk pemberian per os dan
i.m.
Obat-obat yang absorpsi i.m. nya kurang baik, lebih balk di-
berikan secara i.v. lambat, terutama bila diperlukan onset of
action yang cepat (misalnya digoksin, fenitoin, diazepam dan
sebagainya).
Eliminasi renal
Mempertahankan konsentrasi plasma darah terapeutik suatu
obat dilakukan dengan memberikan obat dalam dosis yang
ekuivalen dengan eliminasinya.
Obat-obat poler seperti : penisillin, aminoglykosides dan se-
bagainya dapat langsung diekskresi oleh ginjal. Kumulasi dapat
terjadi jika frekuensi pemberian obat itu lebih cepat dari wak-
tu paruh. Jadi interval pemberian obat harus dilakukan sesuai
dengan 1 2 waktu paruh. Suatu steady state (plateau)
dapat
tercapai.
Eliminasi hepatik
Untuk menentukan dosis dari obat-obat yang dimetabolisir
di dalam hepar haruslah berhati-hati, karena hepar mempunyai
kapasitas metabolistik yang terbatas. Sehingga ada kemungkin-
an suatu ketika pemberian dosis multipel tidak dimetabolisir
dan konsentrasi obat dalam plasma darah akan naik dengan
cepat (lihat gambar). Jika hal ini tidak dikontrol dengan pe-
nentuan konsentrasi obat di dalam plasma darah, maka akan
terjadi akumulasi.
Contoh :
Seorang anak mempunyai BB : 20 kg
Anak itu mendapat fenitoin tiap 24 jam sekali per os.
4 jam sesudah mendapat obat, konsentrasi plasma darahnya :
18 ug/cc = 18 mg/L.
Dekat sebelum diberikan dosis per os yang kedua, pada kon-
trol ternyata konsentrasi obat di dalam plasma darah menjadi
10 ug/cc = 10 mg/L. Ini berarti bahwa dalam 20 jam (24 4)
terjadi penurunan konsentrasi obat, karena metabolisme, se-
banyak 8 mg/L.
Vd fenitoin = 0,75 L/kg, jadi anak
dengan BB = 20 kg, Vd
nya : 20 x 0,75 = 15 L
Dosis = Vd x konsentrasi obat dalam plasma darah
Do sis = 15 L x 8 mg/ L = 120 mg
Vd : 7,5 L/kg
dosis obat
(initial)
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 33
Jika dosis obat dalam 20 jam adalah 120 mg, maka dalam
24 jam adalah
24
20
X 120 mg = 144 mg.
Jadi dosis maintenance
untuk anak dari 20 kg = 144 mg atau
___ 144
20
=
7,2 mg/kg BB diberikan tiap 24 jam sekali per os.
Gambar :
Perbedaan kurve eliminasi langsung oleh ginjal dan eliminasi yang di-
dahului metabolisme oleh hepar.
ROUTE DARI ELIMINASI OBAT
Renal
Hepatik
Digoksin (25%) 75%
Fenobarbital (25%) 75%
Aminoglikosid
Salisilat
Furosemid
Teofilin
Penisilin
Fenitoin
Asetaminofen
Alkohol
Kafein
Konsentrasi terapeutik obat dalam plasma darah.
Digoksin 0,9 2,4
ng/cc
Fenobarbital 15 30 ug/cc
Salisilat < 350 ug/cc
Teofilin 7 20 ug/cc
Fenitoin 10 20 ug/cc
Asetaminofen 10 20 ug/cc
Alkohol (etanol)
(bergejala) 1000 ug/cc
Prokainamida 4 6 ug/cc
Quinidin 3 5 ug/cc
Sulfisoksazol 100 ug/cc
34
Cermin, Dunia Kedokteran No. 37 1985
Volume distribusi (Vd) (dalam L/kg BB).
Fenotiazin > 30
Asetaminofen 10 1,0
Fenobarbital 0,75
Fenitoin 0,75
Salisilat
0,2 (terapeutik)
0,6 (toksik)
Furosemid
0,2
Teofilin 0,46
Digoksin 7,5
Penisilin 0,2 0,3
Benzodiazepin > 10
Infus yang kontinyu
Dewasa ini beberapa macam obat diberikan secara infus
yang kontinyu untuk mendapatkan konsentrasi obat di dalam
plasma darah yang konstan (obat - obatnya : teofilin, insulin,
tolazoline (alpha-blocker), nitroprusid, lidokain, dopamin).
Jika tidak dilakukan kalkulasi dari konsentrasi teofilin di
dalam plasma darah, ada kemungkinan konsentrasi ini menjadi
rendah, seperti pada infus aminofilin : dosis yang diberikan
biasanya 0,9 mg/kg/jam. Pada dosis ini konsentrasi steady
state di dalam plasma darah adalah 10 ug/cc
Dari daftar konsentrasi terapeutik, dapat kita lihat
therapeutic
range nya : 7 20 ug/cc. Ini berarti bahwa 10 ug/cc itu ter-
masuk therapeutic range yang rendah, dan ini mungkin oleh
penderita asma bronkial dirasakan kurang menolong, terutama
pada status asmatikus.
Jika kita menghendaki konsentrasi steady state dari teofilin
itu 15 ug/cc (15 mg/liter), maka :
Dosis infus
= 15 (mg/liter X 0,1 (L/kg/jam)
(mg/kg/jam) (konsentrasi (plasma clearance)
plasma darah)
Dosis infus = 1,5 mg/kg/jam
Infus yang kontinyu harus diawali dengan pemberian
loading initial
dose,
sehingga konsentrasi teofilin dalam plasma darah menjadi 15 ug/
cc.
Umur tua sekali :
Dari segi biologis, yang dimaksudkan di sini ialah orang ber
-
umur 75 tahun atau lebih, walaupun ada juga yang meng-
anggap orang tua sekali itu berumur lebih dari
50 tahun
2
.
Pengobatan pada umur yang lanjut ini sering tidak rasional,
karena penderita mungkin kurang mengerti maksud pengobat-
an itu, sehingga sering menggunakan obatnya menurut pikiran-
nya sendiri yang tidak benar dan juga mereka sering lupa
minum/makan obatnya pada waktu-waktu yang ditentukan.
Dalam hal ini dokter harus menerangkan dengan jelas cara
menggunakan obat itu, atau ditulis pada kertas khusus dengan
jelas, atau diberitahukan pada pengantar penderita tua itu.
Juga, kalau dapat, dokter menentukan rejimen terapi yang se-
derhana. Sehubungan dengan ini perlu dikemukakan, 20
25% dari
penderita tua itu mengalami reaksi - reaksi obat yang
merugikan dan ini sering juga disebabkan karena interaksi-
interaksi polifarmasi
2
.
Respon penderita dari
golongan ini terhadap banyak obat
berbeda dengan penderita dewasa muda, karena absorpsi,
distribusi,
metabolisme dan ekskresinya berbeda. Perbedaan
pada orang tua sekali dalam absorpsi melalui dinding usus
__
dapat disebabkan karena berkurangnya aliran darah splanknik,
naiknya pH lambung dan berkurangnya transfer aktif maupun
pasif. Sebaliknya, ada perlambatan dari motilitas usus teoritis
menambah absorpsi obat.
Pada orang tua, kemungkinan terdapat penambahan jaring-
an lemak, sedangkan cairan badan total, volume plasma,
caftan intersisial dan massa badan tanpa lemak berkurang.
Ini dapat mengurangi volume distribusi dari obat yang larut
dalam air, dan menambah volume distribusi dari obat yang la-
rut dalam lemak. Dosis standar dari obat yang larut dalam air
pada keadaan penderita itu akan mudah menimbulkan intoksi-
kasi.
Pada berkurangnya albumin (protein pengikat obat) yang
mungkin terdapat pada orang tua, obat bebas (free drug)
tentunya lebih banyak dan ini dapat menyebabkan intoksikasi.
Pengurangan cardiac output dan penambahan tahanan
vaskuler perifer dapat juga mengurangi aliran darah renal dan
hepatik. Ini juga dapat menyebabkan intoksikasi dari obat
dengan dosis standar, karena eliminasinya (metabolisme dan
ekskresi) berkurang, lebih-lebih karena kemampuan untuk
transformasi enzimatik obat berkurang.
Glomerular filtration rate dari orang berumur antara 20
90 tahun rata-rata berkurang 355. Karena itu, dan karena masa
badan tanpa lemak juga berkurang, sehingga produksi kreatinin
endogen berkurang. Maka berkurangnya creatinin clearance
karena gangguan fungsi renal dapat tersembunyi, sebab di-
sangka normal. Pemberian obat-obat anti hipertensi mudah
menimbulkan hipotensi ortostatik, karena tahanan dalam
pembuluh-pembuluh darah perifer pada orang tua bertambah
dan kekuatan otot jantung berkurang. Pada semua umur juga
berlaku :
Pada edema, relatif diperlukan sedikit obat.
Penyakit hati dan ginjal relatif memerlukan obat dengan
dosis yang dilcurangi, karena berkurangnya eliminasi (meta-
bolisme dan ekskresi) obat.
Obat jangan diberikan pada idiosinkrasi.
Rejimen terapi harus ditentukan berdasarkan observasi
klinik dan dengan pertolongan pemeriksaan laboratorik.
Obat lama yang sudah diketahui baik jangan diganti dengan
obat baru yang belum dikenal baik sifat-sifatnya.
Sifat-sifat Genetik
Farmakoterapi terhadap penderita yang mempunyai dasar
genetik tertentu harus disesuaikan. Contoh-contoh dalam hal
ini di antaranya adalah :
Rejimen terapi Isoniazid dan Hydralazine perlu disesuaikan
dengan adanya asetilator cepat atau lambat, sekalipun per-
bedaannya tidak banyak.
Jangan memberi terapi dengan kinin, kinidin, sulfonamida,
kloramfenikol, acetosal dan sebagainya pada penderita
dengan defisiensi glukosa-6-fosfat dehidrogenase, karena
dapat menyebabkan hemolisis.
lingkungan hidup
Kebiasaan-kebiasaan dalam hidup seorang penderita sering-
kali menyebabkan respon yang berubah terhadap obat.
Seorang perokok berat misalnya, memerlukan lebih banyak
mikronutriensia dan nutriensia dari pada bukan perokok,
karena absorpsi melalui dinding usus terganggu (iritasi mukosa
usus oleh asap rokok yang tertelan). Di samping itu, zat-zat
yang terdapat di dalam asap rokok merupakan inducer dari
microsomal drug metabolizing enzymes.
Berdasarkan ini, dosis obat per os perlu ditinggikan untuk
mendapat efek yang diinginkan. Berapa besar dosis obat yang
harus diberikan tergantung dari konsentrasi obat dalam plasma
darah dan tergantung dari sensitivitas tempat aksi obat.
Pengobatan terhadap peminum alkohol perlu didasari
pengetahuan tentang kemungkinan adanya sinergisme dengan
depresansia umum (alkoholisme akut), atau adanya toleransi
farmakodinamika dan farmakokinetika (alkoholisme kronik).
Juga perlu disadari bahwa karena adanya gangguan absorpsi
di traktus digestivus, pemberian obat per os harus ditinggikan
dosisnya.
Penderita yang aktif sekali dalam kehidupan sehari-hari jika
mungkin jangan diberi obat yang menekan aktivitas mental,
dan jangan diberi rejimen terapi yang mengharuskan penderita
itu seringkali memakan atau meminum obat, karena kemung-
kinan lupa itu besar.
Selanjutnya yang juga penting untuk diperhatikan ialah
riwayat sakit serta pengobatannya yang lalu, karena mungkin
dapat berpengaruh baik ataupun buruk terhadap pengobatan
yang akan diberikan sekarang.
Riwayat sakit yang lalu perlu diketahui, karena kemungkin-
an berhubungan dengan penyakit sekarang. Apalagi jika pe-
nyakit yang lalu dapat diperkirakan belum sembuh benar atau
meninggalkan bekas kelainan yang memudahkan terjadinya
penyakit sekarang.
Riwayat pengobatan yang lalupun penting untuk diketahui,
sehingga memudahkan dokter memberi pengobatan yang
tepat.
CARA PEMBERIAN OBAT
Tentang cara pemberian obat selanjutnya perlu juga diten-
tukan sesuai dengan situasi dan kondisi medis penderita. Jika
tidak ada keperluan khusus dan tidak ada halangan, maka pem-
berian obat secara oral paling banyak dilakukan (lebih dari
80%)
3
. Juga pada pemberian obat secara oral ini terdapat ba-
nyak variabel-variabel antara penderita yang satu dan yang
lain, bahkan juga pada satu penderita dalam situasi dan kondisi
yang berbeda, karena perbedaan dalam produksi, sifat dan
komposisi dari getah-getah lambung dan usus, kecepatan pe-
ngosongan lambung, ada atau tidak adanya zat makanan, ke-
adaan patologis dari saluran pencernaan dan sebagainya.
4
Adanya gangguan-gangguan emosional, terutama di negara
maju yang separuh sampai dua pertiga dari penderita merupa-
kan penyebab dari gangguan gastrointestinal. dapat meng-
ganggu absorpsi obat.
Dengan tidak memperhatikan kebiasaan dan cara hidup
(merokok, makan, minum dan sebagainya) penderita, maka
terapi rasionalpun kadang-kadang tidak memberi hasil yang
diharapkan.
Pemberian kemoterapeutika pada diare tanpa usaha mengu-
rangi frekuensi peristaltik, tentunya tak rasional.
PENUTUP
Dari apa yang telah dikemukakan di atas dapat drtarik ke-
simpulan :
1). Setelah berusaha menegakkan diagnosis penyakit secara
medis rasional melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 35
laboratorik,
maka dokter perlu mengetahui dengan baik pa-
tologi dan patofisiologi penyakitnya, dan secara logis-metodis-
sistematis menentukan penanggulangannya untuk secara medis
rasional mengembalikan homeostasis badan, tidak kurang dan
tidak berlebihan.
2).
Jika farmakoterapi diperlukan, maka dengan melalui pe-
nyesuaian secara rasional patologi dan patofisiologinya dengan
obat, menurut prinsip-prinsip farmakologi klinik dengan mem-
perbesar rasio keuntungan : kerugian, dan memperkecil rasio
ongkos : keuntungan, diharapkan penyakitnya dapat disem-
buhkan atau setidak-tidaknya penderitaan dapat dikurangi
secara tidak berlebihan.
Karena farmakoterapi demikian itu hanya mengobati hal-
hal yang esensial saja, maka tak
lain terapi itu harus juga di-
lakukan dengan menggunakan obat-obat
yang esensial.
KEPUSTAKAAN
1.
Silves HK, Obrien D. (ed) Current Pedriatric Diagnosis & Treatment,
6th ed, Los Altos, California: Lange Medical Publications, 1980;
1029-1047.
2.
Birket DJ, Wing LMH. Drug Treatment in Old Age, Medical Pro-
gress, 1984; 11 (6): 41-48.
3.
Melmon KL, Morrelli HF. Clinical Pharmacology, Basic Principles
in Therapeutics, New York: The Macmillan Company, 1972; 3 - 58,
534-544.
4.
Levine RR. Factors Affecting Gastrointestinal Absorption of Drugs,
American Journal of Digestive Disorders, 1970; 15: 171-188.
5.
Anderson RJ et al : Therapeutic considerations for Elderly Hyper-
tensives, Clinical Therapeutics, 1982; 5: 25-35.
6.
Birket
DJ et al. Fundamentals of Clinicals Pharmacology. Drug
Absorption and Bioavailability, Medical Progress
1979; 6 (8):
51-56.
7.
Blackwell B : Drug Therapy, The New England, 1973; 289 (5):
249-252.
8.
Isselbacher KJ, Adams RD, Brauwald E, Petersdorf RG, Wilson JD.
Harrison's Principles of Internal Medioine, 9th ed., Tokyo: Mc-
Graw-Hill
Kogakusha,
Ltd., International Student Edition, 1980;
372-383.
Disajikan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-
sium Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.
36 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Ketersediaan Hayati
Sediaan Pelepasan Lambat
Drs Victor S Ringoringo, Apt
Pengembangan teknologi formulasi baru pada dua dekade
terakhir banyak ditekankan pada pengembangan bentuk sedia-
an obat yang dapat melepaskan obat secara terkontrol. Salah
satu di antaranya adalah pengembangan bentuk sediaan obat
yang
,
didisain untuk meningkatkan durasi aksi obat yang ter-
kandung di dalamnya. Beberapa jenis bentuk sediaan obat
yang dikembangkan untuk maksud ini adalah
l ,2
Sediaan pelepasan lambat
Sediaan aksi diperpanjang
Sediaan aksi berulang
Ketiga jenis sediaan di atas dapat dibedakan sebagai ber-
ikut :
Sediaan pelepasan lambat
Obat dalam sediaan pelepasan lambat mempunyai sistem
pelepasan obat yang unik, yaitu mula-mula dilepaskan kira-
kira separuh dari dosis total yang merupakan
dosis inisial, kemudian diikuti dengan pelepasan sisa obat se-
cara bertahap dan seragam selama periode waktu tertentu.
Tujuan sediaan ini adalah untuk memperoleh kadar tera-
peutik obat dalam darah dengan cepat, dan mempertahankan
kadar tersebut selama periode waktu tertentu.
Sediaan aksi diperpanjang
Sediaan ini melepaskan obat dengan laju pelepasan tertentu,
yang dapat menghasilkan durasi aksi obat yang lebih panjang
dibandingkan dengan pemberian dosis tunggal yang normal.
Sediaan ini berbeda dengan sediaan pelepasan lambat yaitu
tidak adanya dosis inisial.
Sediaan aksi berulang
Sediaan aksi berulang didesain untuk melepaskan dengan
segera satu dosis tunggal, kemudian diikuti dengan pelepasan
dosis tunggal kedua, ketiga dan selanjutnya setelah interval
waktu tertentu. Keuntungan utama
dari sediaan ini adalah ber-
kurangnya frekuensi pemberian obat. Tetapi kadar obat dalam
Disajikan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi dan Simpo-
slum Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta, 3 - 4 Desember 1984.
darah sama dengan pemberian obat secara intermiten dengan
dosis tunggal.
Sediaan pelepasan lambat didesain untuk memberikan
kadar obat dalam darah yang adekuat selama periode waktu
tertentu untuk mendapatkan keuntungan -
keuntungan klinik,
yaitu :
1. meningkatkan hasil terapi obat, berupa peningkatan efekti-
vitas dan penurunan efek samping serta efek toksik obat
2.
meningkatkan kepatuhan penderita dengan aturan dosis
yang lebih menyenangkan
3. untuk obat tertentu, dari segi ekonomi dapat diperoleh
penghematan biaya pengobatan
Tetapi di samping keuntungan-
keuntungan di atas, ada pula
kerugian-kerugian dalam pemakaian sediaan pelepasan lambat
yaitu
1. tidak adanya fleksibilitas aturan dosis
2. untuk beberapa obat harganya semakin mahal oleh karena
penerapan teknologi yang tinggi
3. adanya risiko over dosis
1,2
FARMAKOKINETIKA SEDIAAN PELEPASAN LAMBAT
Dengan menggunakan konsep sederhana model farmakoki-
netika satu kompartemen terbuka, efek laju pelepasan lambat
terhadap kadar obat dalam darah dapat digambarkan sebagai
berikut
4
:
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 37
Keterangan
1. (f
i
)
dan (f
s
) adalah fraksi dosis obat formulasi sediaan pelepasan
lambat yang
memberikan pelepasan cepat dan pelepasan lambat
2. k
i
dan k
r
adalah tetapan laju pelepasan obat fraksi pelepasan
cepat
dan fraksi pelepasan
lambat
3. k
a
dan k
e
adalah tetapan laju absorpsi dan eliminasi
4. Ci dan C~ adalah
kadar obat yang dilepaskan pada tempat pemberian
obat dan fraksi
pelepasan cepat dan fraksi pelepasan lambat
5. C
b
dan ce adalah kadar
obat
yang
diabsorpsi dan yang dieliminasi
Fraksi pelepasan cepat didesain untuk mencapai kadar
terapeutik dengan cepat, dan fraksi pelepasan lambat didesain
untuk mempertahankan kadar terapeutik tersebut
1
EVALUASI SEDIAAN PELEPASAN LAMBAT
Pengembangan sediaan pelepasan lambat bertujuan :
1.
absorpsi obat dari sediaan pelepasan lambat yang maksimal
2. meminimalisir variabilitas antar pasien.
Pada pengembangan sediaan pelepasan lambat, pendekatan
yang dilakukan adalah dengan memodifikasi laju pelepasan
obat dengan manipulasi farmasetika, yang dapat merubah laju
absorpsi obat dan kadar obat dalam darah. Oleh karena itu
harus ada jaminan dan bukti ilmiah bahwa efektivitas ab-
sorpsi obat tidak terganggu, dan variabilitas tidak meningkat
4
.
Menurut FDA
4
, obat-obat dalam sediaan pelepasan lambat
dianggap sebagai obat baru, sehingga harus memenuhi per-
syaratan keamanan dan khasiat obat secara klinik. Sama
seperti obat baru dalam bentuk sediaan konvensional, per-
setujuan terhadap sediaan pelepasan lambat berdasarkan
pada evaluasi khasiat dan keamanan secara klinik dan bukti
karakteristik pelepasan lambatnya.
Persyaratan keamanan dan khasiat
Untuk obat yang dalam sediaan konvensional telah di-
ketahui aman dan efektif :
1. diperlukan suatu studi klinik terkontrol untuk membukti-
kan keamanan dan keefektifan obat tersebut dalam sediaan
pelepasan lambat
2.
data ketersediaan hayati obat dalam sediaan pelepasan lam-
bat.
Sedangkan untuk obat yang dalam sediaan pelepasan lam-
bat telah terbukti aman dan efektif, diperlukan adanya :
1. data ketersediaan hayati yang komparabel dengan standar
sediaan pelepasan lambat obat sejenis.
2. data ketersediaan hayati yang pada keadaan mantap
(steady-
state)
komparabel dengan obat sejenis dalam sediaan pe-
lepasan cepat yang konvensional.
Data ketersediaan hayati dapat berupa profil kadar obat
dalam darah dan profil kecepatan ekskresi melalui urin pada
keadaan mantap
4
.
Uji ketersediaan
hayati sediaan pelepasan lambat ber-
tujuan untuk menentukan apakah kondisi berikut ini dipe-
nuhi atau tidak
s
1. produk sediaan pelepasan lambat tersebut memenuhi
persyaratan pelepasan lambat atau tidak. Dengan perkataan
lain, apakah memang benar produk tersebut merupakan se-
diaan pelepasan lambat ?
2.
keadaan mantap yang ditunjukkan ekivalen dengan produk
biasa yang mengandung zat aktif yang sama
3.
formulasi produk tersebut menunjukkan profil farmakoki-.
netika yang konsisten
38 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Dengan demikian uji ketersediaan hayati hendaknya me-
muat data in vivo tentang profil farmakokinetika, data keter-
sediaan hayati yang komparabel dengan standar, dan reprodu-
sibilitas prilaku in vivo.
Standar pembanding
Produk standar pembanding untuk uji ketersediaan hayati
sediaan pelepasan lambat dapat berupa
5
1. sediaan larutan atau suspensi dari obat yang sama
2. sediaan konvensional dengan aturan dosis biasa yang me-
ngandung zat aktif yang sama
3. sediaan pelepasan lambat standar
4. sediaan lain.
Metoda uji ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat
Dosis tunggal
a)
Dosis tunggal sediaan pelepasan lambat dibandingkan
dengan dosis tunggal sediaan pelepasan cepat yang konven-
sional. Profil farmakokinetika obat dengan t 1,7 jam dalam
sediaan pelepasan cepat dan sediaan pelepasan lambat dapat
dilihat pada Gambar 1 berikut
4
:
2
6 10 14 16 20
26
Waktu (jam)
Gambar 1. Simulasi kurva kadar obat dalam plasma vs waktu dari
obat dengan t 1,7 jam
berdasarkan model farmakokinetika satu
kompartemen.
Tampak bahwa pada sediaan pelepasan lambat, kurva berben-
tuk flat sedang sediaan pelepasan cepat berupa lembah dengan
puncak yang tinggi.
Keefektifan dan keamanan obat dalam sediaan pelepasan lam-
bat ini harus dibuktikan secara klinik, dan dibandingkan de-
ngan sediaan pelepasan cepatnya.
b) Dosis tunggal sediaan pelepasan lambat dibandingkan de-
ngan dosis berganda sediaan pelepasan cepat yang konven-
sional. Profil kadar obat dalam darah sediaan pelepasan lambat
dengan t 1 jam, yang dibandingkan dengan 3 dosis berturut-
an dari obat yang sama dengan sediaan pelepasan cepat dapat
dilihat pada Gambar 2
4
.
Terjadi penurunan kadar puncak sampai 30% pada. sediaan
pelepasan lambat, tetapi luas area di bawah kurvanya relatif
sama bila dibandingkan dengan sediaan pelepasan cepat. Profil
kadar obat dalam darah sediaan pelepasan lambat harus ber-
ada dalam batas-batas kadar terapi obat tersebut. Hal ini
harus dikaitkan dengan efektivitas dan keamanan secara klinik.
Dosis berganda
Seringkali tidak mungkin untuk mengevaluasi dengan baik
ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat berdasarkan
dosis tunggal, sehingga penelitian ketersediaan hayati dosis
Gambar 2. Simulasi kurva kadar vs waktu dari sediaan pelepasan
cepat (1) dan sediaan pelepasan lambat (2) dari obat dengan t 1
jam.
berganda sediaan pelepasan lambat perlu dibandingkan dengan
dosis berganda sediaan pelepasan cepat yang konvensional.
Dalam hal ini parameter - parameter yang dipakai sebagai kri-
teria adalah
4
:
1) kadar obat plasma dalam keadaan mantap harus diperoleh
pada obat sediaan pelepasan lambat dan obat sediaan pe-
lepasan cepat pada sejumlah sukarelawan yang cukup.
2) penentuan kadar pada keadaan mantap harus ditentukan
dengan membandingkan nilai-nilai Cmin (trough) pada 3
hari atau lebih.
3) kegagalan dalam memperoleh kadar keadaan mantap pada
sebagian besar sukarelawan menunjukkan kurang patuhnya
pasien atau kegagalan dalam formulasi.
4)
perbandingan parameter - parameter farmakokinetika seperti
C
min
, AUC dan lain-lain hanya terbatas pada subyek
yang mencapai keadaan mantap.
5) perbandingan AUC selama interval pemberian dosis hanya
dibenarkan bila kedua obat yang diuji dan obat standar
berada pada keadaan mantap. Kalau tidak, perbandingan
secara teoritis tidak valid.
Evaluasi in vitro
Walaupun belum ada metoda evaluasi in vitro yang dapat
meniru dengan sempurna keadaan in vivo yang sebenarnya,
'uji in vitro dapat dikembangkan untuk mensimulasi pelepasan
obat secara lambat dari sediaannya.
Metoda in vitro yang dapat
dikembangkan untuk meng-
evaluasi sediaan pelepasan lambat yaitu dengan uji laju di-
solusi
4,6
.
Persyaratan uji disolusi in vitro yaitu :
1. metoda yang reprodusibel
2. pemilihan medium yang tepat
3. hidrodinamika larutan yang terkontrol baik
4. pemilihan sink condition yang tepat.
Walaupun belum ada metoda yang resmi secara kompendial,
ada beberapa metoda yang sekarang terus dikembangkan,
yaitu : metoda flow trough system dan metoda rotating-
bottle.
Pada metoda
rotating bottle,
sediaan pelepasan lambat
dapat diuji pelepasannya pada berbagai variasi pH yaitu mulai
dari pH 1,2 (1 jam), pH 2,5 (1 jam), pH 4,5 (1,5 jam), pH 7
(1,5 jam), dan pH 7,5 (2 jam). Urutan pH ini menggambarkan
perubahan pH mulai dari lambung sampai ke usus.
Dianjurkan untuk melakukan uji disolusi in vivo dan uji
ketersediaan hayati in vivo secara bersamaan. Uji in vitro
yang berkorelasi baik dengan uji in vivo dapat dipakai untuk
memperkirakan ketersediaan hayati sediaan pelepasan lambat
in vivo.
KESIMPULAN
Di dalam mengevaluasi suatu obat dalam sediaan pelepasan
lambat, faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan ada-
lah :
1. Sifat-sifat farmakokinetika, farmakodinamika, dan toksi-
kologi obat.
2. Ketersediaan hayati
3.
Karakteristik pelepasan lambat
4. Reprodusibilitas in vivo
5. Profil farmakokinetika yang menunjukkan pelepasan
lambat
6. Bukti klinik yang mendukung keamanan dan keefektifan
sediaan pelepasan lambat.
LAMPIRAN I
UJI KETERSEDIAAN HAYATI SEDIAAN PELEPASAN
LAMBAT PAPAVERIN HC1
Karakteristik papaverin HCI
pKa
=
6,4
C
maks
pada dosis 300 mg sediaan pelepasan cepat = 1 mcg/
ml
t = 90 120 menit.
Sediaan pelepasan lambat berupa encapsulated pellets atau
granules dengan dosis 150 dan 300 mg, interval pemberian
obat, T = 8 12 jam.
Kriteria uji ketersediaan hayati
1. Uji ketersediaan hayati hendaknya dilakukan dengan disain
menyilang (complete cross-over design) dengan mengguna-
kan larutan papaverin HC1 sebagai standar pembanding.
2. Jumlah sukarelawan 20 orang.
3. Sukarelawan diperiksa kesehatannya, meliputi pemeriksaan
fisik dan laboratoris. Hanya sukarelawan. sehat yang boleh
diikutsertakan dalam penelitian.
4. Sukarelawan berumur 18 50 tahun dengan berat badan
10%dari berat badan idealnya.
5. Sukarelawan tidak diperkenankan meminum obat apapun
selama 1 minggu sebelum penelitian berlangsung.
6. Sukarelawan harus berpuasa 8 jam sebelum uji dilaksana-
kan. Obat diminum dengan 240 ml air. Minuman dan ma-
kanan lain tidak boleh diberikan selama 4 jam sesudah
pemberian obat. Komposisi makanan harus diseragamkan.
7. Sampel darah harus dikumpulkan selama 12 jam atau lebih
setelah pemberian obat.
8. Sampel serum atau plasma hendaknya dianalisis dengan
metoda spesifik terhadap papaverin HC1 dengan sensitivitas
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 39
0,01 mcg/ml.
9. Wash-out selama interval 1 minggu.
10. Data yang dianalisis mencakup kadar papaverin HC1 pada
setiap periode sampling,
C
maks,
t
maks, dan AUC.
11. Data kadar papaverin HC1 dalam darah pada setiap sam-
pling hendaknya dianalisis dengan analisis varian untuk
menguji perbedaan antara obat yang diperbandingkan.
12. Bila sediaan pelepasan lambat tersebut dinyatakan ekiva-
len terhadap regimen dosis-berganda suatu produk dengan
pelepasan cepat yang normal, maka data harus diberikan
untuk membuktikan pernyataan tersebut
.
Rujukan : Dittert LW, Disanto AR. The Bioavailability of Drug
Products. Cumulative Edition. Washington : American Pharmaceutical
Association, 1978 : 71-74.
Gambar 3. Simulasi kadar teofilin dalam serum tyh = 3,7 jam) rata-
rata pada anak dari beberapa formulasi teofilin yang berbeda.
Keterangan :
__________
= absorpsi konstan
- - - - - - - - - = tablet biasa
..................... =
formulasi sediaan pelepasan lambat yang diabsorpsi
sempurna dan reliabel
. . . = formulasi sediaan pelepasan lambat yang diabsorpsi
tidak sempurna dan eratik
Dikutip dari : Weinberger M, Hendeles L, and Johnson G. Rationale
and Procedures for Measuring Serum levels of Theophylline. Dalam :
Baer DM, Dito WR. Interpretations in Therapeutic Drug Monitoring.
Chicago : American Society of Clinical Pathologists, 1981 : 125.
KEPUSTAKAAN
1. Notari RE. Biopharmaceutics
and Clinical Pharmacokinetics.
Third Edition. New York : Marcel Dekker, Inc, 1980 : 152-72.
2. Ballard BE. Prolonged Action Pharmaceuticals.
Dalam : Osol A, ed.
Remington's
Pharmaceutical Sciences. 16
th
Edition.
Pensylvania :
Mack Publishing Company, 1980: 15941602.
3. McGinty,
Stavchansky, and Martin. Bioavailability
in Tablet Tech-
nology. Dalam : Lieberman HA, Lachman L.
Pharmaceutical Dosage
Forms. Volume II (Tablets). New York : Marcel Dekker, Inc., 1980:
43439.
4. Cabana. BE, Chien
YH. Regulatory Considerations in Controlled
Release Medications. PJB Publications Limited.
5. The National Archives of the United
States. Code of Federal Re-
gulations. 21 Parts 300 to 499. Washington :
US. Government
Printing Office, 1982: 123.
6. Hanson WA. Handbook
of Dissolution Testing. Oregon : Pharma-
ceutical Technology Publications, 1982: 45 -61.
40 Cermin Dunia
Kedokteran No. 37 1985
Strategi Penelitian Farmakokinetika
Drs Imono Argo Donatus SU
Jurusan Bio Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada
PENDAHULUAN
Seperti telak diketahui, mutu suatu produk obat ditentu-
kan oleh persyaratan keamanan, kemanjuran, dan akseptabi-
litas yang dipenuhinya, ketika obat tersebut dipergunakan.
Manjur, bararti obat dapat sampai sel sasaran dengan kadar
yang tepat guna. Namun
untuk mengukur kadar obat di sel
sasaran ini, merupakan pekerjaan yang tidak mudah, bahkan
tak
berlebihan jika dikatakan sebagai suatu hal yang sangat
sulit dan riskan untuk dilakukan pada manusia. Karenanya
timbullah permasalahan di sini, yakni: bagaimana cara me-
naksir dan mengkaji ketepatgunaan obat di sel sasaran serta
nasibnya di dalam badan? Penelitian farmakokinetika me-
rupakan salah satu alternatif jawaban terhadap permasalah-
an tersebut.
Seperti penelitian pada umumnya,
agar tujuan peneliti-
an dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin, perlu di-
susun suatu strategi pencapaiannya. Demikian pula halnya da-
lam penelitian farmakokinetika. Karenanya, dalam makalah
ini akan dipaparkan dan dikaji tentang strategi penelitian far-
makokinetika yang meliputi: pengertian dan arti penting serta
penerapan atau operasional strategi penelitian farmakokine-
tika.
PENGERTIAN DAN ARTI PENTING
Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari kinetika
absorpsi, distribusi dan eliminasi (biotransfonnasi dan ekskre-
si) suatu obat di dalam badan
1
. Takrif (definisi) tersebut me-
ngandung pengertian: dalam farmakokinetika akan dipelajari
proses perpindahan atau nasib obat di dalam badan.
Nasib obat
di dalam badan dapat dikaji melalui pentahap-
an aksi hayati atau biologisnya, seperti terlihat pada gambar
1.
Di situ jelas terlihat, untuk dapat menimbulkan efek seper-
ti
yang diharapkan terdapat tiga tahapan penting yang akan
* Dipresentasikan pada Seminar Berkala I Ikatan Ahli Farmakologi
Indonesia dan Simposium Farmakokinetika Klinik - Yogyakarta,
3 - 4 Desember 1984.
dilalui oleh obat. Yaitu meliputi tahap farmasetika, tahap
farmakokinetika, dan tahap farmakodinamika. Tahapan far-
makokinetika (absorpsi, distribusi, biotransfonnasi, ekskresi)
merupakan tahapan
yang berfungsi untuk menyediakan obat
agar berada di dalam sirkulasi sistemik, sehingga obat dapat
menjalankan aksinya seperti yang diharapkan. Karenanya,
fraksi dosis yang
mencapai sirkulasi sistemik dinyatakan se-
bagai ketersediaan hayati atau ketersediaan biologis obat.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 41
Pada dasarnya strategi adalah suatu rencana yang disusun
sebelumnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan
demikian, berdasarkan atas fungsi tahapan farmakokinetika
obat, dalam makalah ini strategi penelitian farmakokinetika
ditakrifkan sebagai: suatu rencana yang disusun sebelum me-
neliti tahapan farmakokinetika obat, guna memperoleh infor-
masi tentang ketersediaan hayati atau ketersediaan biologis-
nya. Takrif atau definisi tersebut mengandung pengertian:
1).
obyek penelitian farmakokinetika adalah tahap farma-
kokinetika obat yakni proses absorpsi, distribusi, dan elimina-
si;
2). hasil
penelitian farmakokinetika merupakan informasi
tentang nilai ketersediaan hayatinya;
3).
nilai ketersediaan hayati obat akan berguna untuk men-
jelaskan, meramalkan, dan mengendalikan efek farmakologik
obat yang diwujudkan sebagai onset, durasi, dan intensitas
efek;
4). agar kesahihan (validitas) penjelasan, peramalan, dan
pengendaliannya dapat diandalkan, perlu disusun suatu ren-
cana yang canggih sebelum menjalankan penelitian farmako-
kinetika.
Telah dijelaskan di atas bahwa obyek penelitian farma-
kokinetika adalah tahap farmakokinetika obat. Sebagai tolok
ukurnya adalah parameter farmakokinetika. Banyak takrif
(definisi) tentang parameter farmakokinetika, namun dalam
makalah ini hanya akan dipaparkan satu takrif yang paling
sederhana, yakni yang diajukan oleh Reilley (1974).
3
Oleh
Reilley, parameter farmakokinetika ditakrifkan sebagai besar-
an yang diturunkan secara matematik dari hasil pengukuran
kadar obat atau metabolitnya di dalam darah atau urin.
Dari takrif yang sederhana ini, tersirat beberapa pengertian
dasar yang memiliki arti penting dalam menyusun strategi pe-
nelitian farmakokinetika. Pertama, dari kata matematik, ter-
sirat pengertian bahwa harga parameter yang diukur merupa-
kan harga pendekatan. Selain itu juga tersirat, dalam meng-
hitung parameter farmakokinetika, diperlukan asumsi-asumsi
tertentu seperti ordo kinetika dan model kompartemen ba-
dan.
Kedua, dari perkataan kadar obat atau metabolitnya,
terkandung pengertian bahwa pemilihan metode penetapan
kadar terutama harus didasarkan pada spesifitas metode yang
akan dipergunakan. Ketiga, dari perkataan darah atau urin,
terkandung pengertian bahwa pemilihan cuplikan hayati atau
biologis harus didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan
yang rasional dan mendasar.
Berdasarkan atas pengertian parameter farmakokinetika
dan urutan pelaksanaan penelitian farmakokinetika, yang ter-
masuk dalam strategi penelitian farmakokinetika adalah:
(1) pemilihan rancangan uji coba,
(2)
.
pemilihan subyek uji
dan jumlahnya, (3) pemilihan cuplikan hayati (biologis),
(4) pemilihan metode analisis, (5) pemilihan takaran dosis,
(6) pemilihan lama dan banyaknya waktu pengambilan cuplik-
an hayati, (7) analisis dan evaluasi hasil.
Strategi tersebut perlu dipertimbangkan sebelum melaksa-
nakan penelitian farmakokinetika. Mengapa demikian? Karena
kesahihan hasil penelitian tergantung pada kecanggihan pene-
rapan strategi tersebut. Dengan perkataan lain, penerapan
strategi
penelitian farmakokinetika memiliki arti penting
dalam menjamin keterandalan dan kesahihan hasil penelitian.
Artinya, ketetapan pengukuran parameter farmakokinetika
suatu obat dapat terjamin, sehingga penerapannya dalam sis-
tern pengobatan dapat memiliki nilai yang tepat guna dan ber-
hasil guna.
PENERAPAN STRATEGI
Pada dasarnya penelitian farmakokinetika dikerjakan pada
tahap praklinis maupun tahap uji klinis suatu obat. Oleh
karena itu, penerapan strategi penelitiannya juga harus dise-
suaikan dengan kondisi yang ada pada kedua tahap tersebut,
di samping tujuan yang akan dicapainya.
Pemilihan rancangan uji coba
Keberhasilan suatu penelitian takkan lepas dari metodologi
penelitian dan rancangan uji coba yang diterapkan, sesuai de-
ngan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. De-
mikian pula halnya dengan penelitian farmakokinetika. Ter-
gantung pada tujuan yang akan dicapai, maka ketepatan pe-
milihan rancangan uji coba akan menentukan keterandalan
dan kesahihan hasil ujinya. Misalnya jika kita ingin mengetahui
harga parameter farmakokinetika suatu obat pada subyek
sehat, rancangan uji coba yang kita tetapkan kemungkinan
akan berbeda jika kita ingin mengetahuinya pada subyek sakit.
Mengapa demikian? Karena pada subyek sakit mungkin ter-
dapat keterbatasan- keterbatasan tertentu seperti jarak antara
mulai sakit dan sembuh, sehingga terkadang tidak memungkin-
kan diterapkannya rancangan pola silang yang dapat diterap-
kan pada subyek sehat.
Dalam memilih rancangan uji coba, perlu pula dipertim-
bangkan adanya berbagai variabel yang melekat pada subyek
uji rnaupun pada sistem penelitiannya sendiri. Variabel-varia-
bel tersebut dinyatakan sebagai variabilitas antar subyek
4
(mi-
sal umur, berat badan, daya tahan, kemampuan metabolisme),
variabilitas karena perlakuan (misal dosis yang berbeda, for-
mulasi yang berbeda), waktu (efek waktu dapat disebabkan
oleh pembahan lingkungan, kelelahan, efek sisa suatu perlaku-
an atas perlakuan lainnya), variabilitas dalam subyek, dan resi-
dual yakni variabditias yang tidak dapat diidentifikasi seperti
kesalahan penetapan kadar dan lain sebagainya.
Variabel-variabel tersebut dapat diperkecil efeknya de-
ngan suatu rancangan uji-coba yang tepat. Rancangan yang
sering dipergunakan dalam penelitian farmakokinetika meli-
puti rancangan acak lengkap (completely randomized design)
dan rancangan pola silang (cross over design).
Rancangan acak lengkap dipergunakan jika variabel luar
tidak diketahui, atau bila pengaruh variabel ini yang sengaja
tidak dikontrol terhadap variasi subyek, adalah sangat kecil.
Rancangan ini juga dipakai jika diketahui bahwa subyek ke-
adaannya seragam dan inferensi yang dibuat berdasarkan hasil
percobaan tidak dimaksudkan sebagai inferensi yang bersifat
percobaan tidak dimaksudkan sebagai inferensi yang bersifat
luas serta berlaku untuk populasi yang lebl beragam5. Se-
bagai contoh, jika kita akan menilai ketersediaan hayati kom-
paratif antara produk A dan B, maka sejumlah subyek dibagi
ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama mendapat produk
A dan kelompok kedua produk B, seperti terlihat pada tabel
1. Sedang jika tiga produk obat yang diperbandingkan rancang-
an uji-coba terlihat pada tabel 2. Perlu diingat bahwa rancang-
42 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
an ini memiliki satu kelemahan. Yakni, walaupun randomi-
sasi dan matching telah dilakukan sejauh mungkin, namun
kemampuan metabolisme di antara subyek itu mungkin masih
tetap ada. Karenanya, dapat dimengerti jika rancangan ini
tidak disarankan jika hasil ujinya dipergunakan untuk inferen-
si populasi yang lebih beragam.
Tabel 1
Tabel 2
Catoh rancanBan acak lengkap
lengkap dengan 2 perkkuan A
dan B.
Contoh rancangan acak
lengkap dengan 3 perlaku-
an A, B, dan C.
Kelompok Kelompok
I II I 11 III
A B A B C
Memperhatikan keterbatasan rancangan acak lengkap ter-
sebut, maka dlkembangkan suatu rancangan yang lebih repre-
sentatif untuk inferensi populasi, yakni rancangan pola silang.
Rancangan ini terutama ditujukan untuk memperkecil penga-
ruh variabilitas dalam subyek di samping variabilitas waktu dan
sebagainya. Misalnya dalam contoh teradahulu, dua produk A
dan B dibandingkan harga ketersediaan hayatinya, maka ma-
sing-masing subyek akan menerima kedua produk tersebut
pada waktu yang berbeda. Dengan demikian masing- masing
subyek akan berlaku sebagai kontrol terhadap ia sendiri. Da-
lam rancangan ini dikenal dua macam rancangan pola silang,
yakni blok lengkap dan blok tak lengkap. Blok lengkap artinya
setiap subyek mendapat perlakuan yang lengkap, misal A dan
B atau A, B, dan C, seperti terlihat pada tabel 3 dan 4.
Tabe1 3. Contoh rancangan pola silang blok lengkap, 2 perlakuan A
dan B, 12 subyek.
Kelompok subyek Periode waktu
I
II
1............ 6
7.............12
I II
A B
B A
Tabel 4. Contoh rancangan pola silang blok lengkap, 3 perlakuan A,
B, dan C, 12 subyek.
Kelompok subyek Periode waktu
I II III
I 1 2 A B C
II 3 44 B C A
III
5
6 C A B
IV 7 8 A C B
V 9 10 B A C
VI 11 12 C B A
Berbeda dengan blok lengkap, pada rancangan pola silang
tak lengkap setiap subyek tidak mendapatkan seluruh macam
perlakuan. Rancangan ini biasanya dipergunakan jika perlaku-
an yang akan diperbandingkan sama dengan, atau lebih besar
dari pada empat perlakuan, seperti terlihat pada tabel 5. Ran-
cangan ini disarankan untuk dipilih berdasarkan atas berbagai
pertimbangan, di antaranya: (1) periode atau waktu penelitian
akan sangat panjang, (2) pengambilan darah yang berlebihan
pada subyek uji, berdasarkan pertimbangan medis tak diper-
kenankan, (3) karena terlalu sering seorang subyek kembali
untuk menjalankan uji berikutnya, terdapat kecenderungan
sukarelawan gagal menyelesailcan penelitian
4
Tabel 5. Contoh rancangan pola silang blok tak lengkap, 4 perlaku-
an A, B, C, dan D, 12 subyek.
Subyek Periode waktu
I II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
D
C
B
D
D
B
B
C
A
A
C
B
C
A
C
A
B
A
D
D
D
C
B
Dari uraian- uraian di atas, jelaslah bahwa dalam memilih
rancangan uji-coba disarankan untuk mempertimbangkan
variabilitas penelitian, keterbatasan rancangan, serta tujuan
yang akan dicapai.
Pemilihan dan jumlah subyek uji
Subyek uji yang dipergunakan dalam penelitian farma-
kokinetika meliputi hewan atau manusia. Hewan uji diper-
gunakan pada tahap uji praklinis pengembangan obat atau-
pun jika terjadi kasus (terutama kasus keamanan) setelah suatu
sediaan obat beredar di pasaran. Sedang manusia uji diperguna-
kan pada tahap uji klinis.
Pemilihan hewan uji tergantung pada tujuan yang akan
dicapai, pengalaman sebelumnya dengan senyawa
- senyawa
yang serupa atau berhubungan, dan sifat rancangan uji-coba-
nya
6
. Namun, pemilihan hewan uji ini bukan pekerjaan
mudah. Banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang masih
diperlukan, yakni bentuk sediaan dan cara pemberian, kemu-
dahan penanganan hewan uji, kemudahan pengosongan lam-
bung, kemudahan mendapatkan cuplikan hayati, besar contoh
hayati, dan volume maksimum yang dapat diterima oleh he-
wan uji
7
.
Pada umumnya hasil penelitian farmakokinetika diperguna-
kan untuk menentukan aturan dosis pada manusia. Karena-
nya, pemilihan hewan uji hendaknya diutamakan pada adanya
kemiripan mekanisme absorpsi, distribusi, dan eliminasinya
terhadap suatu obat dengan manusia. Misalnya untuk keperlu-
an uji ketersediaan hayati suatu obat atau sediaan obat, dapat
dipergunakan hewan uji anjing, kera, babi, kelinci, mencit,
tikus.
Anjing merupakan hewan uji pilihan, karena anjing mampu
diberi berbagai bentuk sediaan obat secara oral. Keuntungan
Cermin Dania Kedokteran No. 37 1985 43
lainnya, anjing
mampu diberi dosis obat secara berulang,
yang mana hal ini sangat panting bagi penelitian komparatif
dengan rancangan pola silang. Selain itu, hewan ini dapat
memberikan sejumlah cuplikan hayati yang cukup memadai
untuk kepentingan analisis farmakokinetika. Dan yang lebih
penting, anjing dan manusia memiliki kemiripan fisiologis sa-
luran cerna mereka, terutama dalam hal keduanya tidak secara
berkesinambungan mensekresi asam klorida ke dalam lumen
gastrik
maupun empedu ke dalam usus halus. Kera tentunya
juga merupakan hewan uji pilihan. Namun, karena penangan-
annya lebih sulit, biasanya hanya dipergunakan jika diketa-
hui anjing tidak menunjukkan kemiripan dengan manusia
dalam hal sifat penerimaan terhadap golongan obat tertentu.
Bagi juga merupakan hewan uji pilihan karena makanannya.
morfologi dan fisiologi saluran cerna, fisiologi jantung serta
ginjalnya, sangat mirip dengan manusia. Namun besar badan-
nya merupakan faktor pembatas. Hewan kecil seperti mencit,
tikus dan hamster bukan hewan uji pilihan karena mereka
tidak dapat diberi kebanyakan bentuk sediaan obat secara
utuh melalui mulut. Selain itu hewan-hewan ini cuplikan bio-
logisnya lama dan sulit diperoleh. Karenanya, hewan uji ini
biasanya hanya dipergunakan dalam penelitian pendahuluan.
Kelinci juga bukan hewan uji pilihan terutama untuk peneliti-
an absorpsi, karena terdapat perbedaan yang besar fisiologis
saluran cernanya dengan manusia, yakni kecepatan pengosong-
an lambungnya lambat serta sulit diperoleh dengan metode
puasa konvensional
8
.
Jika subyek ujinya manusia, sebelum uji coba dilaksanakan,
terlebih dahulu dipenuhi persyaratan
-persyaratan uji klinik
seperti pernah dipaparkan oleh Lesne (1976)
9
atau mengikuti
buku petunjuk "Guidelines for biopharmaceutical studies in
man" (1972)
10
. Selain kriteria
"
sehat" atau sakit" dari subyek
uji, perlu mendapat perhatian pula latar belakang pendidikan
serta hubungan kerja antara peneliti dan subyek uji'.
Berapakah jumlah subyek uji yang dipergunakan dalam pe-
nelitian farmakokinetika? Suatu pertanyaan yang terkadang
sulit
untuk dijawab, dan seringkali menimbulkan masalah
dalam menilai kesahihan hasil penelitian.
Jumlah subyek yang diperlukan dalam penelitian farma-
kokinetika, terutama tergantung pada variabilitas antar subyek
bagi obat. Jika variabilitas antar subyek, misalnya untuk harga
luas daerah di bawah kurva (AUC) relatif kecil, subyek uji
yang diperlukan juga relatif sedikit. Sebaliknya jika variabilitas
AUC antar subyek relatif besar, maka jumlah subyek uji yang
diperlukan juga relatif besar. Dengan perkataan lain, jumlah
subyek uji ditentukan oleh koefisien variasi antar subyek.
11
Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat suatu cara yang
dapat menentukan jumlah subyek uji yang sesuai untuk pene-
litian farmakokinetika, yakni menggunakan teori hipotesis
8
.
Untuk keperluan tersebut, diperlukan empat parameter,
yakni:
1).
A, beda terkecil suatu parameter farmakokinetika (misal
AUC) antara perlakuan (misal formulasi, perbedaan dosis)
yang dikehendaki dapat mendeteksi.
2). a, tingkat signifikansi di man uji-t akan dikerjakan.
3).
1
Q, probabilitas bahwa perbedaan akan terdeteksi.
4). T
2
, variansi error flap observasi
6
.
Harga a dan Q kita tentukan, sedang A dipilih atas dasar
pengetahuan klinis tentang besar perbedaan yang secara tera-
peutik akan bermakna. Dan T
2
biasanya dinilai dari hasil
orientasi atau publikasi. Bila keempat parameter tersebut telah
ditentukan, jumlah subyek (n) yang akan dipergunakan dapat
diperoleh. Sebagai contoh, jika kita ingin membandingkan
harga ketersediaan hayati dua produk obat menggunakan
suatu rancangan uji-coba tertentu. Hipotesis nol menyatakan
tidak adanya perbedaan harga AUC antara dua formulasi. De-
ngan menggunakan rancangan uji coba dengan n subyek uji,
rata-rata AUC _ dari
dua formulasi memiliki suatu distribusi
dengan rata-rata nol dan variansi 2 T
2
/n. Hipotesis nol akan di-
tolak jika perbedaan antar rata-rata melebihi ta/ 6,/ 2 T
2
/n.
Selanjutnya ingat bahwa bagi suatu probabilitas (1
/) me-
nemukan perbedaan A jika betul-betul ada,
A harus lebih
besar dari pada nilai t a/ 9\/ 2 T2 /n dengan sekurang-kurang-
nya t( N,/2 T
2
/n. Keadaan ini dinyatakan sebagai:
Persamaan tersebut dapat disusun ulang sebagai berikut:
Dengan demikian jumlah subyek uji yang diperlukan untuk
harga ketersediaan hayati dua formulasi tersebut akan dike-
tahui.
6
Pemilihan cuplikan hayati
Cuplikan hayati yang paling sering dipergunakan di dalam
penelitian farmakokinetika
adalah darah atau urin.
Masalahnya kapan dipergunakan darah dan kapan urin? Jika
mungkin, penetapan kadar obat tak berubah pada cuplikan
darahlah yang menjadi pilihan pertama. Mengapa demikian?
Pertama, karena darah merupakan tempat yang paling cepat
dicapai obat dan paling logis bagi penetapan kadar obat di
dalam badan. Paling logis karena darahlah yang mengambil
obat dari tempat absorpsi, mendistribusikan ke jaringan sa-
saran, serta menghantarkan ke organ eliminasi
12
.
Kedua, bagi
kebanyakan obat, bentuk obat tak berubah merupakan se-
nyawa yang memiliki aktivitas farmakologik. Karenanya, pe-
netapan kadar pada cuplikan darah akan memberikan suatu
indikasi langsung berapa kadarnya yang mencapai sirkulasi.
Jika tidak ada metode penetapan kadar obat dalam darah yang
tersedia, atau jika level darah pada pemberian dosis normal,
sangat rendah untuk dapat ditetapkan dengan tepat, maka
penetapan kadar obat pada cuplikan urin merupakan alterna-
tifnya
12
.
Sebenarnya penggunaan cuplikan urin dapat lebih
baik dari
pada darah, terutama jika obat diekskresikan ke
dalam urin secara sempurna dalam bentuk tak berubah. Kare-
na selain data urin mengukur langsung jumlah obat yang
berada di dalam badan, juga karena variabilitas clearance
renal dapat diabaikan. Keterbatasan penggunaan cuplikan urin
di antaranya karena sulitnya pengosongan kandung kencing,
kemungkinan terjadinya dekomposisi obat selama penyimpan-
an, dan kemungkinan terhidrolisnya konyugat metabolit yang
tidak stabil di dalam urin, sehingga dapat mempengaruhi
jumlah total obat dalam bentuk tak berubah yang dieksresikan
pada waktu tak terhingga. Akibatnya dapat terjadi kesalahan
penafsiran terhadap harga ketersediaan hayati obat yang di-
44 Cermin Dunia Kedokteran
No. 37 1985
teliti.
Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa ketetapan pemilih-
an cuplikan hayati akan mempengaruhi kesahihan
hasil uji.
Pemilihan metode analisis penetapan kadar
Telah dibraikan bahwa parameter farmakokinetika suatu
obat diperoleh dari hasil pengukuran kadar obat atau meta-
bolitnya di dalam darah atau urin. Dengan demikian, jelas
bahwa metode analisis penetapan kadar obat yang diperguna-
kan dalam penelitian farmakokinetika harus memenuhi ber-
bagai persyaratan, yakni: (1) selektif atau spesifik, (2) sensi-
tif, (3) teliti dan tepat, (4) dan cepat
13
Selektivitas metode menempati prioritas pertama, karena
bentuk obat yang akan ditetapkan dalam cuplikan hayati ada-
lah bentuk tak berubah atau metabolitnya. Artinya, metode
analisis yang dipergunakan hams memiliki spesifitas yang ting-
gi terhadap salah satu bentuk obat yang akan ditetapkan ter-
sebut. Smith dan Stewart (1981)
14
bahkan lebih memperluas
lagi pengertian selektivitas metode ini, yakni kemampuan sua-
tu
metode penetapan kadar untuk membedakan suatu obat
dari
metabolitnya, obat lain (dalam kasus tertentu yang ber-
kaitan),
dan kandungan endogen cairan hayati. Pemilihan
metode yang memiliki slektivitas tinggi ini perlu mendapat
perhatian khusus. Mengapa demikian? Karena hal ini erat se-
kali kaitannya dengan rumus-rumus matematik yang akan di-
terapkan dalam menghitung parameter farmakokinetika. Ru-
mus matematik yang diturunkan berdasarkan data pengukur-
an kadar obat tak berubah dalam cuplikan hayati berlainan
dengan yang diturunkan dari data kadar metabolitnya.
Sensitivitas
metode berkaitan dengan kadar terendah yang
dapat diukur oleh metode yang dipergunakan. Dalam peneliti-
an fanmakokinetika, pilihan metode analisis juga tergantung
pada tingkat sensitivitas yang dimiliki oleh metode. Ini dapat
dimengerti mengingat dalam menghitung parameter farmakoki-
netika suatu obat, diperlukan sederetan data kadar obat dari
waktu ke waktu atau
dari kadar tertinggi sampai ke kadar
terendah dalam cuplikan hayati yang dipergunakan. Misal kita
akan menghitung AUC, maka perlu data kadar obat dari wak-
tu nol sampai tak terhingga. Karenanya, metode analisis yang
dipilih hams dapat meliput kadar obat tertinggi sampai teren-
dah yang ada di dalam badan.
Ketelitian (accuracy) dan ketepatan
(precision) perlu pula
dipertimbangkan dalam memilih metode analisis, karena akan
menentukan kesahihan (validitas) hasil penetapan kadar. Ke-
ketelitian ditunjukkan oleh kemampuan metode dalam mem-
berikan hasil pengukurannya sedekat mungkin dengan nilai
sesungguhnya. Ini dapat diketahui dari
harga perolehan kern-
balinya (recovery), yang dinyatakan sebagai % error (harga
sesungguhnya dikurangi harga uji, dibagi harga sesungguhnya,
kali 100%). Ketepatan menunjukkan kedekatan hasil penguku-
ran berulang pada cuplikan hayati yang sama. Ini dapat dike-
tahui dari
harga replikasinya, yang dinyatakan sebagai koefisi-
en variasi (deviasi baku dibagi harga rata-rata, kali 100%
15
Cepat, juga merupakan persyaratan yang perlu dipertim-
bangkan dalam pemilihan metode analisis penetapan kadar.
Ini berkaitan dengan banyaknya cuplikan hayati yang hams
dianalisis dalam satu macam penelitian farmakokinetika (ku-
rang lebih 180 600 penetapan).
Persyaratan-persyaratan tersebut di atas, sebaiknya benar-
benar dipertimbangkan dalam pemilihan metode penetapan
kadar, karena kesahihan harga parameter farmakokinetika
yang diukur sangat tergantung pada kesahihan hasil penetap-
an kadarnya dalam cuplikan hayati yang ditentukan.
Pemilihan takaran dosis dan bentuk sediaan obat
Berapakah takaran dosis yang akan diberikan? Pertanyaan
ini selalu timbul sebelum mengerjakan penelitian farmakokine-
tika.
Walaupun demikian hal ini seringkali menimbulkan masa-
lah yang sulit diatasi, terutama jika akan mengembangkan
sediaan obat baru pada tahap uji praklinik dengan hewan uji
tertentu.
Pemilihan takaran dosis yang akan diberikan pada hewan
uji pada tahap uji praklinik, dapat didasarkan pada data harga
LD
5o
senyawa yang akan diuji. Namun perlu diingat dan di-
sadari dalam mempergunakan data harga LD
5o
tersebut, yakni
cara pemberian senyawa selama penelitian toksisitas akutnya.
Jika dalam penelitian toksisitas akut, senyawa diberikan dalam
bentuk larutan, maka takaran dosis dipilih yang betul-betul
memiliki batas keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sedang jika senyawa atau obat diberikan dalam bentuk sedia-
an padat atau suspensi, serta telah diketahui memiliki harga
LDso yang sangat tinggi, maka batas keamanan yang besar ti-
dak diperlukan
6
Perbandingan harga LD
5o
oral lawan intravena dapat diker-
jakan untuk memperoleh wawawan terhadap masalah absor-
pbabilitas sebagai fungsi cara pemberian oral. Hal ini tentunya
akan berguna dalam meramalkan efek toksik sebagai fungsi
kenaikan takaran dosis. Jika informasi ini tidak tersedia, maka
dapat dipergunakan harga LD
50
intravena sebagai dosis awal
penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni sebesar
5 10% LD
5o
intravena
6
.
Selain parameter-
parameter famakologik dan toksikologik
tersebut di atas, pemilihan takaran dosis juga hams dikaitkan
dengan sensitivitas metode penetapan kadar obat tak berubah
atau metabolitnya. Maksudnya takaran dosis yang diberikan
hams menjamin dapat diukurnya kadar obat atau metabolit
pada jarak waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cu-
kup untuk evaluasi farmakokinetika.
Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan takaran
dosis ini adalah adanya fenomena "kinetika tergantung dosis".
Yakni suatu fenomena yang menunjukkan adanya perubahan
parameter farmakokinetika obat bila takaran dosisnya diubah.
Keadaan ini berkaitan dengan asumsi ordo kinetika obat ter-
sebut. Kinetika obat diasumsikan mengikuti ordo nol bila
menunjukkan fenomena kinetika tergantung dosis. Hal ini
perlu diperhatikan, karena akan menentukan rumus mate-
matik yang dipergunakan untuk menghitung parameter farma-
kokinetikaanya. Jika mengikuti ordo nol, perhitungannya
mengikuti rumus pada farmakokinetika
non-liniair. Hal ini
berbeda jika asumsinya mengikuti ordo pertama, yakni para-
meter farmakokinetika obat tidak dipengaruhi oleh perubahan
dosis (farmakokinetika liniair).
Fenomena kinetika tergantung dosis dapat disebabkan oleh
beberapa hal, misalnya: (1) obat diberikan dalam dosis besar,
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 45
sehingga kapasitas proses metaboliknya dilampaui, (2) bila
terjadi kompetisi antara dua obat yang berbeda atas satu ma-
cam proses metabolisme,
(3) jika zat pembawa bagi transport
aktif suatu obat mengalami kejenuhan
16
. Keadaan ini dapat
diketahui dengan menghitung waktu paruh (t
) eliminasi obat,
setelah pemberian beberapa takaran dosis yang berbeda. Jika
harga tlh obat berbeda-beda, berarti kinetika obat mengikuti
ordo nol atau tergantung dosis
17
.
Bentuk sediaan obat yang akan diberikan juga harus dipilih
dengan hati-hati, terutama pada penelitian pendahuluan pada
tahap praklinis. Pertama kali, obat diberikan dalam bentuk
larutan baik secara oral maupun intravena. Baru kemudian
dikembangkan ke bentuk sediaan lain.
Baik takaran dosis maupun bentuk sediaan obat biasanya
sudah tidak begitu menjadi masalah bagi uji klinis.
Pemilihan lama dan banyaknya waktu pengambilan cuplikan
hayati
Sesuai dengan takrif parameter farmakokinetika yang di-
pergunakan dalam makalah ini, dimaksud cuplikan hayati
meliputi darah dan urin. Sebenarnya dalam penelitian farma-
kokinetika dapat pula dikerjakan dengan cuplikan hayati
lainnya seperti saliva. Namun, karena darah dan urin yang
paling banyak dipergunakan, dalam kesempatan ini hanya
akan dijelaskan strategi pemilihan lama dan banyaknya waktu
pengambilan cuplikan darah dan urin, sesuai dengan takrif
parameter farmakokinetika yang dipergunakan dalam makalah
ini.
Jika cuplikan
darah yang dipergunakan, pengambilan
cuplikan dianjurkan berlangsung selama 3 5 kali harga waktu
paruh eliminasi (tlh) obat yang diuji. Dan 7 10 kali th obat.
Jika cuplikan urin yang dipergunakan, yakni praktis 99,2
99,9% obat telah diekskresikan
16
Frekuensi atau banyaknya pengambilan cuplikan, erat
kaitannya dengan asumsi model kompartemen badan. Jika
kinetika obat mengikuti model dua kompartemen terbuka,
dianjurkan banyak pengambilan cuplikannya paling tidak 3
kali pada tahap absorpsi, 3 kali pada sekitar puncak, 3 kali
pada tahap distribusi, dan 3 kali pada tahap eliminasi. Keadaan
ini
diperlukan untuk mendapatkan data kadar obat dalam
darah lawan waktu yang cukup untuk evaluasi parameter
farmakokinetika obat. Pengambilan cuplikan pada tahap distri-
busi tidak diperlukan, jika kinetika obat mengikuti model satu
kompartemen terbuka
16
. Waktu pengambilan cuplikan yang
optimal ini perlu diperhatikan, karena akan menentukan ke-
sahihan penetapan asumsi model kompartemennya. Hal ini
dapat dikerjakan dengan penelitian pendahuluan atau orien-
tasi
18
.
Orientasi dalam penelitian farmakokinetika setelah pem-
berian obat intravena memiliki banyak keuntungan. Di antara-
nya, sensitivitas dan selektivitas
metode penetapan kadar
sebagai fungsi cara pemberian dapat segera ditentukan. Me-
ngapa demikian? Karena obat langsung ditempatkan dalam
aliran darah, sehingga kadar tertinggi dan terendah obat yang
ada di dalam badan segera dapat diketahui. Keadaan ini akan
menggambarkan pula kadar tertinggi obat setelah pemberian
oral, jika obat diabsorpsi dengan sempurna. Dengan menge-
tahui kadar tertinggi ini, sensitivitas metode penetapan kadar
segera dapat ditetapkan, yakni sampai kurang lebih 10 20%
kadar tertinggi obat (80 90% obat telah diekskresikan).
Dalam orientasi intravena tersebut, beberapa cuplikan
harus diperoleh pada jam pertama setelah pemberian obat,
diikuti setiap jam untuk periode jam ke 8 12 berikutnya,
dan beberapa cuplikan lagi sampai jam ke 48. Ini diperlukan
untuk mengevaluasi kemungkinan asumsi model komparte-
mennya. Setelah orientasi intravena, sebaiknya juga dilakukan
orientasi cara pemberian lain ekstravaskular, agar adanya pe-
ngaruh fisiologis pada proses absorpsi obat dapat diketahui
sejak dini.
Analisis dan evaluasi hasil
Analisis data uji coba dan evaluasi hasil penelitian merupa-
kan tahap terakhir penelitian farmakokinetika. Karenanya,
tidaklah berlebihan jika dalam serangkaian pengkajian tahap
terakhir penelitian ini diperlukan kecermatan dan ketelitian
dalam menganalisis data, serta pengetahuan klinis maupun
formulasi farmasetik.
Data uji coba yang pertama kali perlu dianalisis adalah
sederetan kadar obat tak berubah atau metabolitnya di dalam
darah atau urin, pada sederetan waktu tertentu. Sebelum data
tersebut dipergunakan untuk menghitung parameter farma-
kokinetika, langkah pertama yang dikerjakan adalah menetap-
kan model kompartemen badan yang diikutinya. Langkah ini
penting, karena akan menentukan penerapan rumus matematik
yang akan dipergunakan untuk menghitung parameter farma-
kokinetika. Analisis kompartemen ini dapat dikerjakan dengan
memplotkan data kadar obat tak berubah dalam darah lawan
waktu pada kertas grafik semilogaritmik, atau plot log kece-
patan ekskresi (dAe/dt) lawan waktu pada kertas grafik
numerik. Jika data urin yang dipergunakan. Dengan melihat
adanya fase distribusi (yakni grafik bifasik untuk pemberian
intravena dan grafik trifasik untuk pemberian oral), kinetika
obat dapat dikatakan mengikuti model dua kompartemen
terbuka. Jika fase distribusi ini tidak terlihat pada grafik, maka
kinetika obat pada umumnya dikatakan mengikuti model satu
kompartemen terbuka. Namun, perlu dicatat bahwa keadaan
ini hanya berlaku jika tetapan kecepatan distribusi (alfa)
diasumsikan harganya lebih besar
dari pada tetapan kecepatan
absorpsinya (ka),
i
pada pemberian obat secara oral.
Notari (1980)
19
menyatakan, kinetika obat akan meng-
ikuti model satu kompartemen terbuka, jika harga tetapan ke-
cepatan distribusi antar kompartemen (k
12
+
k
21
) sama atau
lebih besar
dari pada 20 kali harga tetapan kecepatan eliminasi-
nya (K
el
). Dengan perkataan lain, kinetika obat mengikuti
model dua kompartemen terbuka, jika harga tetapan kecepat-
an distribusi antar kompartemen yang diperoleh itu lebih kecil
daripada 20 kali harga tetapan kecepatan eliminasinya (k
12
+
k
21
=<K
el
).
Kecermatan mengasumsikan model kompartemen ini pen-
ting sekali dalam memperoleh ketepatan perhitungan para-
meter farmakokinetika obat. Misalnya kita menghitung waktu
paruh eliminasi obat dengan asumsi kinetikanya mengikuti
model satu kompartemen terbuka, padahal sebenarnya meng-
ikuti model dua kompartemen terbuka, maka harga yang di-
peroleh akan lebih besar dari pada harga sesungguhnya (t =
0,693/K
el
untuk model satu kompartemen, t =
0,693/Q
46 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
untuk model dua kompartemen, dan harga B selalu lebih besar
dari pada harga
K
el).
Kesalahan penafsiran model
kompartemen ini biasanya
disebabkan oleh ketidakcermatan dalam menetapkan waktu
pengambilan cuplikan hayati, yakni tidak mengambil cuplikan
hayati pada fase distribusi obat, seperti dicontohkan pada
gambar 2. Jelas terlihat pada gambar 2 tersebut, harga t,
AUC, dan C
0
p
p
(kadar obat dalam darah pada waktu nol)
yang
dihitung dengan asumsi model satu kompartemen, berbeda
dengan yang dihitung berdasarkan asumsi model
dua kom-
partemen terbuka.
Gb. 2. Grafik kadar obat dalam darah lawan waktu setelah pemberian
intravena. (a) model satu kompartemen, (b) model dua kompartemen.
Setelah analisis data
uji coba dilaksanakan dan perhitungan
parameter
farmakokinetika obat dikerjakan, langkah berikut-
nya adalah analisis statistik. Analisis statistik ini tidak begitu
sulit untuk dikerjakan, karena tinggal mengikuti rancangan
uji coba
yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, perlu
ditekankan di sini bahwa hasil uji statistik bukan merupakan
kesimpulan akhir hasil
penelitian. Statistik hanya merupakan
salah satu alat pendukung pengambilan keputusan. Misalnya
kita membandingkan harga AUC dari produk obat A lawan
produk baku B. Jika kemudian dari
hasil uji-t ditemukan
bahwa beda harga AUC antara Produk A dan B (AUC produk
A 10%lebih tinggi dari pada AUCB) menunjukkan perbedaan
yang bermakna, pada taraf kepercayaan 95%. Hasil ini ternyata
tidak dapat dipergunakan untuk menarik kesimpulan bahwa
produk A lebih baik absirpsinya dari pada produk B. Mengapa
demikian? Karena sebelumnya telah diketahui bahwa produk
obat tersebut hanya akan memberikan perbedaan terapeutik
yang nyata, jika harga AUC nya 30% lebih tinggi dari pada
harga AUC produk baku. Ini dapat dimengerti, mengingat per-
bedaan yang bermakna dari hasil uji-t tersebut sangat ditentu-
kan oleh harga deviasi baku masing -masing kelompok ujinya.
Sedang perbedaan efek terapeutik ditentukan oleh baik bu-
ruknya formulasi, bukan oleh besar-kecilnya deviasi baku.
Contoh lain, pada uji coba
di atas harga AUC produk
A 40%
lebih tinggi dari pada harga AUC produk B, dan hasil uji-t
nya menunjukkan perbedaan
yang bermakna, menggunakan
10 subyek uji. Namun karena dalam percobaan pendahuluan
(orientasi) telah diketahui bahwa untuk mendeteksi adanya
perbedaan harga AUC sebesar 30%
antara dua produk tersebut
(A ), paling optimal diperlukan 40
subyek uji (diperhitungkan
dengan teori hipotesis), maka hasil penelitian ini tidak dapat
dipergunakan untuk menarik kesimpulan secara umum, karena
jumlah subyek uji yang
dipergunakan kurang representatif un-
tuk
menggambarkan keadaan populasi
yang sebenarnya.
Tahap terakhir dari penelitian garmakikinetika adalah
evaluasi hasil penelitian. Telah diuraikan terdahulu, dalam
tahap evaluasi ini diperlukan pengetahuan klinik ataupun
farmasetik. Pengetahuan klinik diperlukan untuk menjamin
kesahihan kesimpulan hasil penelitian, seperti dicontohkan
di
atas. Pengetahuan farmasetik juga diperlukan, karena peneliti-
an farmakokinetika terbanyak dipergunakan dalam pengem-
bangan obat atau produk obat. Misalnya, kita menguji waktu
paruh eliminasi tablet
asetosal pada sekelompok orangIndone-
sia. Ternyata hasil perhitungan t nya jauh berbeda dengan
penelitian sejenis yang ditemukan pada sekelompok orang
Eropa. Dalam hal ini kita tidak dapat langsung menyatakan
bahwa profil tlh asetosal orang Indonesia berbeda dengan
profil t orang Eropa. Mengapa demikian? Karena kita tidak
tahu sistem formulasi dan teknik pabrikasi tablet asetosal
yang dikerjakan oleh peneliti Eropa tersebut. Mungkin saja
peneliti Eropa menggunakan bahan baku asetosal yang bentuk
kristalnya berbeda dengan yang kita pakai. Padahal bentuk
kristal setosal menentukan tetapan kecepatan absorpsinya.
Juga mungkin peneliti Eropa menggunakan teknik pabrikasi
yang lain dalam pembuatan tablet asetosal, dengan yang kita
buat. Selain itu, mungkin juga metode analisis penetapan kadar
obat dalam cuplikan hayati yang dipergunakan oleh peneliti
Eropa lain dengan yang kita pergunakan. Hal ini kiranya dapat
menggambarkan, sebelum kita menyimpulkan hasil penelitian
farmakikinetika, sebaiknya dilakukan evaluasi yang cermat ter-
lebih dahulu terhadap berbagai variabel yang mungkin dapat
mempengaruhi kesahihan kesimpulan penelitian.
Telah dikaji tentang strategi penelitian farmakokinetika
dari pemilihan rancangan uji coba sampai ke analisis dan
evaluasi hasil. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk memberi
gambaran betapa sulit dan rumitnya pelaksanaan penelitian
farmakokinetika, melainkan justru sebaliknya.
KEPUSTAKAAN:
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 47
1. Curry SH. Drug disposition and pharmacokinetics. Oxford:
10. ............. Guidelines for biopharmaceutical studies in man. APHA
Blackwell Scientific Publication, 1977.
Academy of Pharmaceutical Sciences. 1972; 1-33.
2. Arieens & Simonis AM. Optimalization of pharmacokinetics -
11. Wagner JG. Biophazmaceutics and relevant pharmacokinetics.
an essential aspect of drug development by metabolic stabili-
l
rt
ed. Hamilton: Drug Intelligence Publications, Inc. 1971;
tation. In: Keverling Buisman JA (Ed). Strategy in drug research.
245-246.
Amsterdam: Scientific Publishing Company, 1982;4:165-178.
12. Tozer TN. Pharmacokinetic principles relevant to bioavailability
3.
Reilly WJO. Drug dosage regimes and iboavailability part I -
studies. In: Blanchard J, Sawchuk RJ & Brodie BB (eds). Prin-
elementary pharmacokinetics. Aust J Pharm. 1974; 54:648.
ciples and perpective in drug bioavailability. Basel: S Karger AG.
4. Wagner JG Fundamental of clinical pharmacokinetics 1
st
ed.
1979; 121-154.
Hamilton: Drug Intelligence Publications Inc. 1975; 290-297.
13.
Hirtz J Analytical problems in bioavailability testing. In: Deasy
5.
Maria Astuti. Rancangan percobaan dan analisa statistik bagian
& Timoney )eds). The quality control of medicines. Amsterdam:
I.
Yogyakarta: Fakultas Peternakan UGM 1980; 5-7.
Elseivier Scientific Publishing Company. 1976; 245-252.
6.
Kaplan SA. Biopharmaceutics in the preformulation stages of
14.
Smith RV & Stewart JT Textbook of biopharmaceutical analy-
drug development. In: James Swarbrick (ed) Current concepts
sis. Philadelphia: Lea & Febiger. 1981; 7-9.
in the pharmaceutical sciences-dosage form design and bioavai-
15.
Schwartz MA & De Silva JAF. Quantitative drug analysis in bio-
lability. Philadelphia: Lea & Febiger. 1973; 8-9, 152-158.
availability studies. In: Blanchard J, Sawchuk J & Brodie BB
7. Imono AD. Uji ketersediaan hayati (bioavailability) in vivo ber-
(eds). Principles and perspectives in drug bioavailability. Basel:
bagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Dalam: Pro-
S Karger AG. 1979; 90-99.
ceedings Kongres Nasional XI dan Kongres Ihniah ISFI. Jakarta:
16. Ritschel WA Handbook of basic pharmacokinetics 2
nd
ed. Ha-
ISFI. 1983; 463-467.
milton: Drus Intelligence Publication, Inc, 1980; 230-232, 280.
8.
Kaplan SA, Jack ML. In vitro, in situ, and in vivo models in bio-
17. Shargel L & Yu ABC. Applied biopharmaceutics and pharmaco-
availability assesment. In: Blancard J, Sawchuk RJ & Brodie
kinetics. New York: Appleton Century Crofts. 1980; 15-16.
BB (eds) Principles and perspective in drug bioavailability.
Basel: S Karger AG. 1979; 181-199.
18. D. Argenio DZ. Optimal sampling times for pharmacokinetics
9. Lesne M Bioavailability testing in man-pharmacokinetics consi
experiments. J Pharmacokin Bipharm. 1981;9 (6) : 39-355.
derations. In: Deasy & Timoney (eds) The quality control of
19. Notari RE Biopharmaceutics and clinical pharmacokinetics -
medicines. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company.
an introduction, 3
rd
ed. New York: Marcel Dekker, Inc. 1980;
1976; 215-223.
18-29.
48 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Bioavailabilitas Obat
Drs. Victor S. Ringoringo Apt
Perkembangan terakhir dalam proses pengembangan dan pe-
masaran obat banyak disesuaikan dengan perubahan sikap dari
dokter, pejabat pemerintah, dan masyarakat terhadap obat.
Pada 10 20 tahun yang lalu industri-industri farmasi banyak
menekankan pada penemuan obat-obat baru, dan peta ke-
farmasian pada saat itu ditandai dengan cepatnya suatu mo-
lekul obat baru ditemukan. Dewasa ini, kecepatan penemuan
obat baru mulai menurun, sebagian disebabkan karena sudah
cukup banyak tersedia obat yang efektif untuk berbagai pe-
nyakit. Masa paten yang sudah daluwarsa dari berbagai macam
obat seringkali menyebabkan munculnya bermacam-macam
produk obat yang mengandung zat aktif yang ekivalen.
Sementara itu masyarakat mengharapkan obat bermutu
dengan harga yang terjangkau, dan banyak industri obat mem-
promosikan penulisan resep obat dalam nama generik sebagai
salah satu usaha untuk meningkatkan kompetisi harga obat
di antara industri obat.
Situasi ini menempatkan apoteker di tengah-tengah dua sisi
yang ekstrim. Di sisi pertama apoteker dituntut untuk menu-
runkan biaya pemeliharaan kesehatan melalui penurunan harga
obat, tetapi di sisi lain apoteker bertanggung jawab terhadap
kualitas obat yang baik. Apoteker bertanggung jawab dalam
seleksi obat, dan dalam banyak hal peranannya semakin besar
dalam pemilihan produk obat yang bermutu tinggi.
Dalam pemikiran para dokter seringkali timbul beberapa
pertanyaan :
1) Apakah ada perbedaan klinik yang bermakna di antara
produk obat komersial yang mengandung jenis dan jumlah
zat aktif yang sama ?
2) Bagaimanakah sifat perbedaan-perbedaan tersebut ?
3) Faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan terse-
but ?
4) Bagaimanakah perbedaan tersebut dapat diukur dan di-
evaluasi ?
5) Kriteria apa yang digunakan apoteker untuk memilih obat
yang ditulisnya dalam resep ?
UJI BIOAVAILABILITAS DAN UJI IN-VITRO
Untuk menjamin ekivalensi terapeutik dan klinik dari suatu
produk obat dalam berbagai
batch
produksi, secara ideal pen-
ting untuk mengukur secara tepat efek klinik dan potensi dari
sampel yang representatif dari masing-masing batch produk
obat tersebut. Walaupun demikian, pada prakteknya hal ter-
sebut tidak mungkin dilakukan karena adanya pertimbangan
praktis dan aspek etis seperti :
1) Uji klinik memerlukan populasi penderita yang ekstensif
dengan jenis dan keparahanpenyakit yang seragam
2) Uji klinik pelaksanaannya kompleks dan mahal
3) Teknik pengukuran yang obyektif sulit ditemukan dan
seringkali tidak sensitif terhadap berbagai kondisi penyakit
Cara pendekatan yang terbaik untuk memperkirakan efek
klinik suatu obat adalah dengan pengukuran kadar obat dalam
darah, karena ada hubungan yang erat antara kadar obat dalam
darah dengan efek klinik obat tersebut. Tetapi dalam hal ini
juga ditemukan beberapa kelemahan seperti :
1)
Uji kadar obat dalam darah biayanya mahal, memerlukan
peralatan analitis yang canggih, tenaga ahli yang terampil,
dan sejumlah sukarelawan sehat. Dengan demikian kelayakan
untuk melakukan uji bioavailabilitas dari setiap
batch produk
obat patut dipertanyakan.
2) Konsep bioavailabilitas berpijak pada asumsi bahwa para-
meter biologis suatu obat (kadar obat dalam darah dan jaring-
an, ekskresi obat dalam urin atau pengukuran produk meta-
bolit) secara langsung berkaitan dengan efek klinik obat. Se-
mentara asumsi ini mungkin saja absah, tetapi sulit untuk
memperkirakan ketepatan korelasinya. Misalnya, jika dua
produk menunjukkan perbedaan bioavailabilitas sebesar 20%,
apakah perbedaan ini secara klinik bermakna ?
Sementara saat ini tidak mungkin untuk melakukan uji ka-
dar obat dalam darah untuk setiap
batch produk obat, industri
obat dapat menggunakan uji bioavailabilitas untuk menentu-
kan bahwa produk obatnya dengan formulasi dan proses pro-
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 49
duksi yang spesifik akan memberikan efek klinik yang se-
banding dengan produk obat sejenis yang diproduksi industri
obat lain (produk originator atau produk inovator),
yang
pada uji kliniknya memberikan hasil yang baik.
Sebagai salah satu alternatif untuk melakukan uji bioavaila-
bilitas pada setiap batch produk obat, uji in vitro telah dikem-
bangkan sebagai indikator bioavailabilitas, atau untuk mene-
tapkan bahwa batch produk obat selanjutnya akan menunjuk-
kan bioavailabilitas dan efek klinik yang sebanding dengan
batch sebelumnya yang telah ditetapkan uji kadar obat dalam
darah dan uji kliniknya.
Uji laju disolusi dan uji difraksi sinar X merupakan 2 con-
toh prosedur laboratoris yang dapat merefleksikan perilaku
obat in-vivo. Uji ini telah dimasukkan dalam USP dan NF dan
telah diterapkan pada sejumlah obat. Uji laju disolusi meng-
ukur laju disolusi sejumlah obat dalam medium tertentu dan
pada kondisi tertentu. Uji difraksi sinar X melengkapi bebe-
rapa indikasi dari laju dan jumlah obat yang melarut, dengan
demikian akan bermanfaat dalam memperkirakan absorpsi
obat. Sementara kedua uji ini bukan merupakan uji bioavaila-
bilitas yang sebenarnya, maka kedua uji ini hanya merupa-
kan indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan
bioavailabilitas obat. Suatu industri obat yang mempunyai
data klinik atau informasi yang menunjukkan bahwa produk
obatnya secara klinik efektif, dan bila data ini dikorelasikan
dengan uji in vitro dengan tepat, dan bila formulasi serta pro-
sedur produksi tidak berubah, maka konsistensi dari batch
ke batch dapat dijamin dengan melakukan uji laju disolusi,
uji difraksi sinar X atau uji in vitro lainnya yang relevan.
PENGERTIAN BIOAVALABILITAS
Konsep bioavailabilitas pertama kali diperkenalkan oleh
Osser pada tahun 1945, yaitu pada waktu Osser mempelajari
absorpsi relatif sediaan vitamin. Istilah yang dipakai pertama-
kali adalah availabilitas fisiologik, yang kemudian diperluas
pengertiannya dengan istilah bioavailabilitas.
Dimulai di negara Amerika Serikat, barulah pada tahun
1960 istilah bioavailabilitas
masuk ke dalam arena promosi
obat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya produk
obat yang sama yang diproduksi oleh berbagai industri obat,
adanya keluhan dari pasien dan dokter di man obat yang
sama memberikan efek terapeutik yang berbeda, kemudian
dengan adanya ketentuan tidak diperbolehkannya Apotek
mengganti obat yang tertulis dalam resep dengan obat merek
lainnya.
Sebagai cabang ilmu yang relatif baru, ditemukan berbagai
definisi tentang bioavailabilitas dalam berbagai literatur.
Bagian yang esensial dalam konsep bioavailabilitas adalah
absorpsi obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ada 2 unsur penting
dalam absorpsi obat yang perlu dipertimbangkan, yaitu :
1) kecepatan absorpsi obat
2) jumlah obat yang diabsorpsi
Ke dua faktor ini sangat kritis dalam memperoleh efek
terapeutik yang diinginkan dengan toksisitas yang minimal.
Atas dasar kedua faktor ini dapat diperkirakan bagaimana
seharusnya definisi tentang bioavailabilitas.
Dua definisi berikut ini merupakan definisi yang relatif
lebih sesuai dengan kedua faktor di atas adalah :
Definisi 1 : Bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan
ukuran kecepatan absorpsi obat dan jumlah
50 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
obat tersebut yang diabsorpsi secara utuh oleh
tubuh, dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik.
Definisi 2 : Bioavailabilitas suatu sediaan obat merupakan
ukuran kecepatan absorpsi obat dan jumlah
obat tersebut yang diabsorpsi.
TUJUAN PENETAPAN BIOAVAILABILITAS
Dengan mengetahui jumlah relatif obat yang diabsorpsi
dan kecepatan obat berada dalam sirkulasi sistemik, dapat di-
perkirakan tercapai tidaknya efek terapi yang dikehendaki
menurut formulasinya. Dengan demikian, bioavailabilitas da-
pat digunakan untuk mengetahui faktor formulasi yang dapat
mempengaruhi efektivitas obat.
Beberapa manfaat studi
bioavailabilitas yang berkaitan dengan mutu produk obat
yaitu :
1) bagi apoteker dalam bidang penelitian kefarmasian, bio-
availabilitas
merupakan uji yang penting dalam penelitian
peningkatan mutu obat
2)
bagi dokter dan apoteker di apotek, bioavailabilitas merupa-
kan pertimbangan kritis yang digunakan untuk pemilihan
obat yang bermutu baik.
PENGUKURAN BIOAVAILABILITAS
Jumlah obat yang diabsorpsi biasanya ditentukan dengan
mengukur luas area di bawah kurva (AUC) dari kurva kadar
obat dalam darah versus waktu, atau dari jumlah obat kumula-
tif yang diekskresikan melalui urin. Jika suatu obat diberikan
per oral dan beberapa jam sesudahnya diambil satu seri dari
sampel darah dan dianalisis kadar obat dalarn darah, kemudian
hasilnya di plot pada kertas grafik, akan diperoleh kurva kadar
darah-waktu seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Kurva kadar serum waktu setelah pemberian dosis tung-
gal suatu obat per oral.
Obat diberikan per oral pada waktu nol; pada saat ini kadar
obat dalam darah adalah nol. Setelah obat melalui lambung
dan/atau usus, akan berdisintegrasi dan segera melarut dan
absorpsi pun berlangsung. Peningkatan kadar obat dalam darah
akan terlihat pada sampel darah berikutnya sampai tercapai
kadar puncak. Titik ini disebut
puncak kurva kadar serum
waktu. Pada titik ini kecepatan absorpsi sebanding dengan
kecepatan eliminasi. Di sebelah kiri titik puncak kurva merupa-
kan fase absorpsi, di mana kecepatan absorpsi lebih besar
daripada kecepatan-eliminasi. Di sebelah kanan titik puncak
kurva disebut fase eliminasi, di man kecepatan absorpsi
lebih kecil daripada kecepatan eliminasi.
Hubungan antara bioavailabilitas dan efektivitas klinik
obat didasarkan pada asumsi bahwa intensitas dan durasi
respon farmakologik obat berkaitan erat dengan kadar dan
durasi obat aktif dalam darah atau sirkulasi sistemik. Profil
kadar obat dalam darah memungkinkan perhitungan kece-
patan dan jumlah obat yang diabsorpsi dari suatu produk obat,
dengan demikian data ini sangat membantu dalam mengevalua-
si besarnya pengaruh formulasi pada perilaku obat dalam tu-
buh.
Bila suatu industri obat telah memiliki data efektifitas obat
melalui uji klinik dari suatu formulasi obat, maka industri
obat lainnya yang ingin memasarkan obat yang sejenis haruslah
melakukan suatu penetapan bioavailabilitas yang dapat menun-
jukkan bahwa formulasinya memberikan kadar puncak yang
sama, kecepatan absorpsi yang sama, dan jumlah obat yang
diabsorpsi yang sama dengan formulasi dari industri obat yang
pertama. Jika ke tiga kriteria di atas dipenuhi, adalah beralasan
untuk
mengharapkan bahwa formulasi yang dikembangkan
industri obat ke dua akan memberikan efek terapeutik yang
sama dengan produk obat pertama. Aplikasi konsep bio-
availabilitas yang semacam ini disebut bioekivalensi.
Kriteria Bioekivalensi
Bioekivalensi berdasarkan data kadar obat dalam darah.
Ada tiga parameter penting dalam mengevaluasi bioekivalensi
antara dua formulasi dari obat yang sama, yaitu :
1)
Kadar maksimal/kadar puncak,
C
maks
(mcg/ml)
Pada Gambar 1,
C
maks = 4,0 mcg/ml.
Kadar maksimal dari kurva kadar darah waktu merupakan
kadar dalam darah tertinggi yang dicapai setelah pemberian
obat per oral.
2) Waktu mencapai kadar maksimal,
t
maks
(jam)
Pada Gambar 1,
t
maks
= 2,0 jam.
Waktu mencapai kadar maksimal merupakan waktu yang di-
perlukan untuk mencapai kadar maksimal setelah pemberian
obat. Parameter
t
maks
berkaitan erat dengan kecepatan
absorpsi obat dan dapat digunakan sebagai ukuran yang se-
derhana untuk mengukur kecepatan absorpsi.
3) Luas area di bawah kurva, AUC (mcg/ml x jam)
Pada Gambar 1, AUC
0-12
= 21,5 mcg/ml x jam.
Luas area di bawah kurva merupakan parameter yang terpen-
ting dan merupakan ukuran banyaknya obat yang diabsorpsi
setelah pemberian dosis tunggal suatu obat per oral.
Bioekivalensi berdasarkan data ekskresi obat dalam urin.
Bila yang diukur adalah ekskresi obat dalam urin kumulatif,
parameter-parameter yang penting adalah :
1) Jumlah kumulatif obat yang diekskresikan dalam urin
2) Kecepatan ekskresi obat dalam urin
Jika kecepatan dan jumlah obat yang diekskresikan melalui
urin setelah pemberian 2 macam produk obat yang mengan-
dung obat aktif yang sama itu identik, dapat disimpulkan bah-
wa ke dua produk obat tersebut adalah bioekivalen. Ini dida-
sarkan pada konsep bahwa obat yang diekskresikan ke dalam
urin berasal dari darah.
Jika kedua profil kadar obat dalam darah dan pengukuran
ekskresi obat dalam urin diperoleh dari satu subyek yang sama,
maka ke dua data tersebut merupakan komplemen satu sama
lain.
JENIS PENELITIAN BIOAVAILABILITAS OBAT
Penelitian bioavailabilitas obat dapat merupakan :
1)
Penelitian bioavailabilitas absolut, yaitu
membandingkan
bioavailabilitas suatu bentuk sediaan obat per oral dengan
pemberian secara intravena.
2) Penelitian bioavailabilitas relatif, yaitu membandingkan
secara relatif bioavailabilitas suatu bentuk sediaan obat per
oral dengan bentuk sediaan obat sejenis lainnya.
Sebagai produk standar dapat digunakan :
1) produk larutan oral
2) produk inovator/originator, yaitu produk yang dibuat oleh
pabrik penemunya, yang dianggap mempunyai bioavailabilitas
terbaik yang sudah teruji secara klinik dengan hasil terapi
yang baik (biasanya ditentukan oleh lembaga resmi, misalnya
FDA).
Penelitian bioavailabilitas relatif dapat diterapkan untuk :
1)
memilih satu dari alternatif dua atau lebih bentuk sediaan
yang sama dengan formulasi yang berbeda yang akan dipro-
duksi oleh suatu pabrik, sehingga diketahui pengaruh kompo-
nen formulasi terhadap bioavailabilitas.
2)
memilih bentuk sediaan yang mempunyai bioavailabilitas
terbaik dari beberapa alternatif bentuk sediaan yang akan di-
kembangkan.
3)
mengontrol variabilitas yang mungkin terjadi antar batch
dari bentuk sediaan yang sama dari batch yang berlainan.
4)
membandingkan secara komparatif produk pabrik mana
yang mempunyai bioavailabilitas terbaik.
PELAKSANAAN PENELITIAN BIOAVAILABILITAS
OBAT :
Penelitian bioavailabilitas obat memerukan fasilitas labora-
torium analisis/bioanalitik yang canggih dengan tenaga ahli
yang profesional dan harus memenuhi persyaratan tertentu.
Untuk beberapa macam obat, persyaratan pelaksanaannya
telah dikeluarkan oleh American Pharmaceutical Association
dalam bukunya 'The Bioavailability of Drug Products.'
Protokol penelitian bioavailabilitas obat hendaknya me-
muat tujuan percobaan, latar belakang obat yang hendak di-
teliti,
bahan obat, pemilihan sukarelawan, disain penelitian,
penanganan sampel, metoda analisis kadar obat dalam darah,
dan hal-hal lain.
Secara garis besar pelaksanaan suatu penelitian bioavailabi-
litas obat dilakukan sebagai berikut :
1) Pemilihan sukarelawan yang mencakup pemeriksaan kese-
hatan, penandatanganan informed consent.
2) Periode puasa dari minum obat apapun (1 minggu)
3) Puasa 1 malam sebelum pemberian obat
4)
Pemberian obat
5) Pengambilan sampel material hayati (darah dan/atau urin)
pada interval waktu tertentu.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 51
5) Penyimpanan dan preparasi sampel
6)
Analisis kadar obat dalam material hayati
Langkah 2) s/d 6) dapat berulang sesudah periode wash-out
sesuai dengan protokol.
7) Tabulasi
data, perhitungan parameter-parameter farma-
kokinetika, analisis statistik.
8)
Penyusunan laporan.
OBAT-OBAT YANG PERLU DITELITI BIOAVAILABILI-
TASNYA :
Perlukah penelitian bioavailabilitas dilakukan untuk setiap
obat? Memang masih belum ada suatu ketentuan yang berlaku
umum untuk bioavailabilitas produk obat. Walaupun demiki-
an, penelitian bioavailabilitas perlu dilakukan dalam hal ber-
ikut :
1) Obat-obat yang batas keamanannya sempit
2) Obat-obat yang absorpsinya berfluktuasi
3) Obat-obat yang variasi individunya besar dalam kadar
plasma pada dosis biasa
4) Diperlukan untuk mempertahankan MEC/MIC obat dalam
cairan hayati selama terapi
5) Obat-obat baru
KEPUSTAKAAN
1. Birkett DJ et al. Drug Absorption
and Bioavailability, Medical
Progress, August 1979, vol. 6 No. 8, pp. 51-61.
2.
Dittert LW et al. The Bioavailability of Drug Products, Cumulative
Edition, 1978, American Pharmaceutical Association, pp. 9-20.
3.
Weser JK. Bioavailability of Drugs, New England J. Med., Vol. 291
No. 5, pp. 233-237.
52 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Bagaimana Pengaruh Tubuh
Terhadap Obat
Dr. Mathilda B. Widianto
Unit Bidang
Farmakologi Jurusan Farmasi
Institut Teknologi Bandung, Bandung
Untuk dapat menjawab pertanyaan yang kelihatannya se-
derhana ini, ada sejumlah parameter yang harus diperhatikan.
Pada prinsipnya setiap orang harus menyadari bahwa tidak ada
"tubuh standar", tiap organisme akan memberikan pengaruh
yang tidak sama terhadap suatu obat. Di samping perbedaan
genetik, juga harus disadari bahwa individu yang sakit tidak
sama reaksinya terhadap obat dibandingkan individu yang
sehat dan normal. Belum lagi pengaruh lain,misalnya interaksi
dengan obat lain, makanan, lingkungan hidup sehari-hari yang
kesemuanya ini dapat mempengaruhi absorpsi, distribusi,
biotransformasi
maupun ekskresi obat. Jika kita perhatikan
hal-hal tersebut, kebiasaan
memberikan obat sehari 3 kali
akan berkurang, apalagi kalau kronofarmakologi ikut diper-
timbangkan.
FARMAKOGENETIKA:
apa itu ?
Kalimat yang sangat trivial : "tiap individu berbeda" ber-
laku pada penggunaan obat-obatan. Dosis yang sama dari
suatu obat dapat memberikan efek utama maupun efek sam-
pingan yang berbeda pada individu yang berbeda. Dengan
demikian, pengaturan dosis sesuai kebutuhan perorangan
merupakan dasar yang baik pada setiap terapi.
Pada umumnya faktor seperti pengaruh usia, kelamin,
makanan dan sebagainya sudah banyak dipertimbangkan,
sedangkan faktor genetik sebagai determinan kerja obat ku-
rang mendapat perhatian.
Adanya perbedaan kerja obat di sini disebabkan karena :
Adanya perbedaan individual bail( jumlah reseptor maupun
affinitas obat untuk dapat terikat pada reseptor tersebut.
Adanya perbedaan pola absorpsi, distribusi, biotransformasi
maupun ekskresi obat, hingga dosis yang sama dapat me-
nyebabkan berbedanya kadar obat dalam plasma pasien
bersangkutan.
Perbedaan genetik ini biasanya disebabkan polimorfismus
enzim-enzim tertentu, di man terbentuk isoenzim dengan
aktivitas enzim yang berbeda. Tentu saja hal ini dapat menye-
babkan adanya efek obat yang jauh menyimpang dari yang
diharapkan. Setelah pemberian beberapa obat seperti sulfa-
sulfa, nitrofurantoin, primaquin, maka pada sekitar 10% orang
negro dan sebagian penduduk sekitar Laut Tengah (Iran,
Junani, Sardinia) timbul anemia hemolitik yang parah. Ter-
nyata ini disebabkan kurangnya enzim glukose-6-fosfat de-
hidrogenase yang berperan pada biotransformasi senyawa-
senyawa tersebut. Gangguan pada enzim glukuronil transferase
misalnya menyebabkan hiperbilirubinemia di samping tentu-
nya juga akan menghambat ekskresi senyawa seperti paraseta-
mol yang juga membutuhkan enzim ini. Polimorfisme genetik
ini juga terjadi untuk senyawa lain misalnya INH (asetilasi),
suksametonium (hidrolisis) dan lain-lain.
FARMAKOKINETIKA : seringkali terjadi tidak sesuai
dengan dugaan
Besaran farmakokinetika yang tertera pada pustaka dan
brosur obat adalah keadaan kinetika obat pada individu
normal. Di sinilah letak problem utamanya : obat justru di-
gunakan pada orang sakit, hingga misalnya konstanta eliminasi
yang dinyatakan untuk obat bersangkutan akan dapat sangat
berbeda. Terutama pada penderita penyakit ginjal, hati dan
gangguan kardiovaskular, perubahan besaran ini sudah harus
diduga pasti terjadi. Dalam hal ini tentu sudah seharusnyalah
baik dosis maupun interval pemberiannya diubah untuk men-
dapatkan efek terapi yang diinginkan, atau menghindari
efek sampmg yang mungkin terjadi. Khusus untuk obat-obat
yang mempunyal indeks terapi kecil, sudah banyak dilakukan
penelitian farmakokinetika pada keadaan insufisiensi organ
eliminasinya.
Untuk mendapatkan gambaran kinetik obat bersangkutan,
dapat dilakukan dengan melihat kurva waktu vs kadar obat
dalam plasma. Untuk beberapa senyawa sudah ada petunjuk
pengaturan dosis pada keadaan patofisiologis tertentu. Jelas-
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 53
lah, hanya dokter yang mengetahui sifat kinetika obat pada
keadaan khusus inilah yang dapat melakukan terapi dengan
tepat.
Hal lain yaitu terjadinya induksi enzim hingga obat
yang digunakan akan diuraikanlebih cepat. Dari sekian banyak-
nya sistem enzim dalam tubuh kita, yang paling berperan pada
metabolisme senyawa asing adalah sitokrom P450 yang ter-
sebar di paru-paru, ginjal, dinding usus halus, kulit, hati,
Jumlah enzim ini akan dapat meningkat pada pemakaian
suatu senyawa untuk waktu yang cukup lama. Karena peng-
uraian obat dipercepat tentu saja kerja obat menjadi lebih
singkat dan lebih lemah. Sulitnya lagi karena enzim bekerja
pada banyak jenis obat, tentu pengaruhnya juga akan dialami
obat-obat ini, bahkan oleh substrat tubuh sendiri.
Barbiturat, terutama feniletilbarbiturat merupakan induk-
tor enzim yang kuat. Pemakaian senyawa ini untuk waktu
yang lama akan jelas mempengaruhi terapi dengan obat lain,
karena waktu paruh senyawa tersebut akan berkurang. Sebagai
contoh, terapi dengan difenilhidantoin. Di sini diamati bahwa
kadar difenilhidantoin akan turun dengan drastis dalam
waktu satu minggu pemberian feniletilbarbiturat. Dengan
demikian, untuk mendapatkan kadar obat dalam plasma yang
cukup untuk mencegah serangan epilepsi, mau tidak mau
dosis difenilhidantoin harus ditinggikan. Akan tetapi harus
pula diingat, untuk menurunkan dosis jika pemakaian obat
lain yang bertindak sebagai induktor enzim tersebut dihenti-
kan. Contoh lain yaitu percepatan eliminasi kontraseptiva
oral setelah pemakaian barbiturat.
Beberapa obat lain justru melakukan inhibisi sistem enzim
(nortriptilin, simetidin, alopurinol, kloramfenikol, steroida
kontraseptif), sehingga obat-obat yang dimetabolisir oleh
sistem enzim yang sama akan diuraikan lebih lambat, dan
dengan demikian kadar obat dalam plasma akan lebih tinggi.
MAKANAN/MINUMAN
Pola makanan seseorang serta komposisi dietnya mem-
pengaruhi metabolisme banyak senyawa. Orang-orang vege-
tarier akan memetabolisir obat tertentu dengan kecepatan
yang jauh lebih lambat daripada "pemakan segala".
Makanan dengan jumlah karbohidrat tinggi akan memper-
lambat kecepatan metabolisme obat-obat seperti antipirin dan
teofilin, sedangkan protein sebaliknya. Beberapa penelitian
lain menunjukkan, intake kronik minuman yang mengandung
teobromin, misalnya kopi, teh, kakao akan dapat menghambat
metabolisme beberapa obat. Pengaruh alkohol pada metabolis-
me obat tidak selalu sama. Alkohol yang diminum dalam jum-
lah banyak akan menginduksi enzim, hingga lamanya obat da-
lam organisme akan lebih singkat. Akan tetapi pada peminum
kronis dan berat, justru sebaliknya karena hatinya sudah ter-
kena sirosis.
Pengaruh merokok pada metabolisme obat juga sudah
banyak diteliti. Perokok berat pada umumnya mempunyai
sistem sitokrom P448 yang terinduksi, hingga obat-obat se-
perti teofilin, genasetin akan diurai lebih cepat. Pada orang-
orang ini, klirens ("Clearance") teofilin dua kali lebih tinggi
daripada tidak perokok, hingga pada pengobatan asma tentu
perlu pengaturan dosis.
KEADAAN PENYAKIT
Faktor patologis yang mempengaruhi metabolisme obat,
paling banyak diteliti pada penderita penyakit hati dan tiroid.
Perubahan yang dapat terjadi pada berbagai jenis penyakit
hati
antara lain perubahan aktivitas enzim, ketersediaan
kofaktor, aliran darah ke hati, susunan hepar sendiri dan lain-
lain yang masing-
masing dapat mempengaruhi disposisi obat.
Sangatlah sulit untuk meramalkan sampai seberapa jauh
metabolisme suatu senyawa dipengaruhi oleh keadaan penya-
kit pasien tertentu, karena dari
data biokimia tidak dapat
dicari korelasi yang tepat. Karena itu, terapi obat secara
individual
harus didasarkan pada respons klinis atau kon-
sentrasi obat dalam plasma pasien bersangkutan.
Pada penyakit tiroid, hasil penelitian menunjukkan bahwa
hipertiroidea akan menstimulasi metabolisme obat dan ke-
adaan sebaliknya terjadi pada penderita hipotiroidea.
KONTAK DENGAN SENYAWA KIMIA TERTENTU
Kontak kronis dengan senyawa kimia tertentu seperti DDT,
hidrokarbon polisiklik dan lain-lain dapat mengubah aktivitas
enzim pemetabolisir obat.
Walaupun penelitian untuk ini
belum banyak, dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar
senyawa yang larut lemak akan menyebabkan terjadinya
induksi sedangkan logam-logam berat seperti Pb akan ber-
tindak sebagai inhibitor enzim. Tentu saja faktor penentu
lainnya seperti waktu kontak, dosis harian dan sebagainya
akan sangat berpengaruh.
Konsekuensi dari pembicaraan di atas tentulah perlunya
pengaturan dosis obat pada terapi, terutama pada obat - obatan
yang jarak dosis terapeutik dan dosis letalisnya cukup dekat.
Untuk pengembangan obat baru perlu diperhatikan faktor-
faktor tersebut di atas, apakah biotransformasi obat dalam
tubuh dipengaruhi oleh faktor genetika, makanan tertentu
atau faktor lain. Jawaban tentu sudah harus didapat sebelum
melangkah ke percobaan klinik double blind, pada saat mana
pasien biasanya mendapat dosis obat dan bentuk sediaan yang
sama. Ini tentu merupakan penentu reputasi obat tersebut
hingga pengaturan dosis sudah dapat diatur pada tahap awal
obat disebarluaskan..
Dengan mempertimbangkan faktor -
faktor tadi, di samping
faktor lain seperti first pass effect yang belum dibahas di sini,
maka untuk mendapatkan terapi yang rasional dan sesuai
dengan tujuan pengobatan, dosis obat dan interval pemberian
harus disesuaikan hingga indikasi "sehari 3 kali" harus diubah
sesuai kebutuhan.
KEPUSTAKAAN
1.
La Du BN, Mandel HG, Way EL. Fundamentals of Drug Metabolism
and Drug Disposition, New York: Krieger Publ Co., 1979.
2.
Dtsch Ap Z, 1984; 124: 233-235.
3. Clin Pharmacol Ther, 1976; 20: 643
.
653.
4. Eur J Clin Pharmacol, 1984; 27: 595-602.
5. Mutschler E. Arzneimittelwirkungen, 4 Auflage,
Stuttgart: Wissen-
schaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 1981.
54 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Konsultasi Farmakologik
di Samping Penderita
dr. Budiono Santoso
Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Yogjakarta
Universitas Gadjah Mada.
PENDAHULUAN
Salah satu peran farmakologi yang bisa dikembangkan da-
lam penanganan penderita adalah mekanisme konsultasi lang-
sung mengenai kasus-kasus, di mana dijumpai adanya permasa-
lahan obat dan pengobatan. Judul makalah "konsultasi farma-
kologi di samping penderita" mungkin tidak begitu jelas dan
terlalu agresif, tetapi yang dimaksudkan di sini yaitu adanya
mekanisme konsultasi antara klinikus sebagai penanggung ja-
wab penanganan penderita dengan salah satu sistem pendu-
kungnya (back up system) untuk meningkatkan secara maksi-
mal kemanfaatan terapi, dan mengurangi sekecil mungkin ri -
siko efek samping pengobatan. Halkin (1984
1
) dalam kuliah
tamu pada "The Second World Conference of Clinical Phar-
macology
& Therapeutics" mengajukannya dengan istilah
"Beside clinical pharmacology and concultation".
Dalam tulisan ini akan dibicarakan secara ringkas menge-
nai tujuan,
manfaat, lingkup kegiatan dan pelaksanaannya.
Khusus dengan melihat permasalahan farmakoterapi di Indone-
sia, nampaknya kegiatan semacam ini perlu dikembangkan.
TUJUAN & MANFAAT
Essensi utama dari penerapan farmakologi klinik dalam pe-
nanganan penderita sehari-hari adalah memastikan kualitas
farmakoterapi. Telah disadari bahwa setiap pemberian obat
pada penderita selalu disertai dengan kemungkinan timbulnya
risllco,
walau paling ringan sekali pun. Kualitas farmakoterapi
yang di tuju dalam penerapan farmakologi klinik untuk pe-
nanganan
penderita adalah tercapainya "keseimbangan"
antara manfaat dan risiko tersebut. Dengan kata lain, bagaima-
na manfaat farmakoterapi bisa dicapai secara maksimal demi
perawatan atau penyembuhan penderita dengan risko sekecil
mungkin. Sehingga manfaat dari mekanisme konsultasi lang-
sung adalah dalam upaya peningkatan kualitas penanganan pe-
nyakit penderita, bila ditinjau dari segi pelayanan.
Manfaat lain dari segi proses pendidlkan bagi calon-calon
dokter, yaitu memberikan pengalaman langsung dalam penera-
pan farmakologi klinik dalam penanganan masalah-masalah
penyakit pada masing-masing tipe penderita. Jelas bahwa hal
ini hanya berlaku di pusat-pusat pendidikan kedokteran atau
di rumah-rumah sakit pendidikan. Jika hal ini disimak lebih
lanjut, sebenarnya merupakan perwujudkan dari konsep pe-
ngajaran farmakologi yang tidak sekedar bersifat didaktik
melalui kuliah-kuliah konvensional, tetapi dengan memberikan
pengalaman nyata bagi calon-calon dokter dalam penanganan
penderita. Secara kritilc seorang calon dokter mendapatkan
pengalaman dalam berbagai hal, menyangkut :
1).
Pemilihan obat berdasarkan diagnosis yang ditegakkan.
Di sini analisis manfaat-risiko (benefit-risk)
dan manfaat-ong-
kos (benefit-cost) mau tidak mau juga pasti harus terpikirkan.
2).
Penentuan dosis, dan individualisasi dosis pada keadaan-
keadaan tertentu yang berhubungan dengan kondisi pasien.
Misalnya, penyesuaian dosis obat pada keadaan gangguan faal
ginjal.
3). Penilaian respons penderita terhadap terapi. Apakah ke-
adaan penderita membaik dengan terapi yang diberikan ?
Apa yang dinilai? Kapan harus dipertimbangkan ganti alterna-
tif terapi (switch of therapy)
bila tidak ada respons ? Menga-
pa tidak ada respons? Apakah tidak adanya respons terhadap
pengobatan disebabkan karena faktor-faktor dalam tingkat ki-
netik, yang mungkin masih bisa dikoreksi dengan peningkatan
dosis, misalnya jika dikarenakan kadar yang tercapai tidak
mencapai kadar terapeutik minimal. Ataukah dalam tingkat
dinamik, misalnya karena adanya resistensi pada keadaan infek
si?
4). Mencari kemungkinan timbulnya efek yang tidak dike-
hendaki (adverse reaction) dari terapi, baik berupa efek sam-
ping ataupun efek toksik, dalam berbagai tingkat.
Fenomena-fenomena dalam farmakologi dan terapeutika
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 55
yang secara konvensional didapatkan dari kuliah-kuliah di ke-
las mungkin bisa didapatkan dalam kenyataan klinik yang di-
hadapi, misalnya tentang antar aksi obat pada pengobatan-
pengobatan kombinasi. Satu hal yang perlu disadari dan di-
tandaskan pada calon-calon dokter, setiap pemberian obat,
apapun jenisnya, harus dipertimbangkan dan dipikirkan ke-
mungkinan (prediction) timbulnya berbagai pengaruh, baik
pengaruh klinik atau pengaruh buruk.
Apa yang dikemukakan di atas mungkin merupakan be-
ban dari klinikus, tetapi bukankah hal-hal yang disebutkan tadi
sebenarnya juga merupakan konsekuensi logis dari terapeuti-
ka? Suatu hal yang biasa dan logis, hanya mungkin sering ter-
kesampingkan.
Mekanisme konsultasi langsung juga bermanfaat dalam men-
dukung ke arah terapi rational (rational drug therapy). Hal-
hal yang berkaitan dengan ketidaktepatan dan ketidaksesuaian
tempi pada suatu keadaan klinik, tidak perlu terjadi atau bisa
ditekan se minimal mungkin dengan mekanisme konsultasi.
Kerangka dalam rasionalisasi terapi mulai dari keputusan
dan pertimbangan-pertirnbangan yang perlu diperhatikan, se-
cara sistematik meliputi
l
Keputusan
1. Diagnosis
a. Tepat (akurat) atau
b. Paling tidak diagnosis yang paling mungkin
(probable)
2. Pengertian penyakit
a. Patofisiologi
b. Riwayat alamiah
3.
Mengobati atau tidak
a. Obat mungkin tidak diperlukan :
Sama sekali tidak perlu obat
Terapi lain lebih bermanfaat
b. Jika diperlukan obat :
Keuntungan (manfaat) yang diharapkan ?
Kemungkinan efek buruk ?
Kerugianbila obat tidak diberikan?
4. Obat dan aturan dosis
a. Pemilihan obat, dosis, sediaan, dan cara pemberian
b. Pemilihan dosis dan aturan dosis yang tepat pada pende-
rita dengan melihat kondisi si penderita.
c. Lama pengobatan berdasarkan perjalanan alamiah penya-
kit.
obat dan pasien (ke-
56 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
LINGKUP KEGIATAN & PERAN FARMAKOLOGIK
Walaupun mungkin farmakologi klinik merupakan ilmu
yang bersifat "eksperimental
3
, jika dilihat dari definisi "the
scientific study of drugs in man"
4
, namun langsung atau ti-
dak bidang ini berkaitan erat dengan pelayanan perawatan
penderita.
Seperti telah dikatakan di awal tulisan ini, sesuai penera-
pan farmakologi klinik dalam penanganan penderita adalah
mendorong tercapainya keseimbangan dalam manfaat terapi
yang bisa dicapai, dan risiko pengobatan yang mungkin timbul
pada kasus-kasus individual. Untuk memenuhi tugas terapeu-
tik ini diperlukan kemampuan dan pengetahuan dalam :
a). Penanganan (manajemen) dalam berbagai bidang klinik
secara luas (misalnya ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan
anak)
b). Penerapan prinsip-prinsip pemilihan obat, farmakoki-
netika dan farmakodinamika klinik
c).
Rancangan (disain), pelaksanaan dan analisis data pene-
lit ian klinik.
Dengan kemampuan dan pengetahuan seperti yang disebutkan
di atas, konsultasi farmakologi dapat mempengaruhi/mening-
katkan penanganan kasus-kasus individual (individual patient
care), melalui antara lain
1
:
1. Detoksi kuantitatif adanya ketidak-tepatan terapi atau ke-
tidak-sesuaian terapi, pada keadaan-keadaan di mana pengama-
tan-pengamatan klink tidak jelas. Untuk ini di perlukan pe-
ngukuran kadar obat dalam cairan biologik.
2. Memeriksa mekanisme ketidak-sesuaian respons terhadap
pengobatan, untuk memastikan apakah perlu mengganti pi-
lihan obat (dinamika atau mengganti aturan dosis (kinoti-
ka).
3. Penilaian kembali (reappraisal) strategi terapeutik yang
telah efinisi "the scientific study of drugs in man"
4. Merancang dan menganalisis data penelitian-penelitan kli-
nik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul da-
lam prektek klinik sehari-hari.
5. Monitoring pemilihan obat, kebiasaan resep
(prescribing
habit) dan penggunaan informasi obat.
Konsultasi farmakologik tidak perlu untuk setiap kasus.
Mungkin prioritas utama adalah kasus-kasus serius, atau me-
ngancam kehidupan (life threatening) yang perlu penanganan
secara intensif. Pertanggungan jawab penanganan penderita
tetap berada di tangan klinikus. Konsultasi farmakologik
hanya sebagai salah satu sistem pendukung (back up system),
sehingga klinikus harus benar-benar mempertimbangkan semua
kemungkinan dari saran-saran yang diterima dalam konsultasi.
Kapan, di man dan bagaimana mekanisme konsultasi di
organisir dan dikerjakan akan sangat tergantung pada keada-
an masing-masing tempat dan juga kegiatan-kegiatan akademik
lain yang dijalankan. Tetapi yang mungkin paling bermanfaat
untuk dikembangkan adalah unit-unit ilmu penyakit dalam,
il mu kesehatan anak, kemudian ilmu bedah, kebidanan dan ne-
urologi. Hal ini membatasi kemungkinan unit-unit lain.
Karena kegiatan mekanisme konsultasi sebenarnya me-
nyangkut hubungan antar orang, diperlukan kesiapan-kesiapan
Pertimbangan-pertimbangan
1. Kecocokkan (kompatibilitas) antara
mungkinan terjadinya efek buruk)
2.
Kompatibilitas antar obat (intereksi)
3. Pertimbangan masak-masak keputusan 4.a di atas.
Tindakan
1. Menulis resep/instruksi pengobatan
2. Instruksi-instruksi khususjika perlu :
a. Efek samping yang mungkin timbul
b.
Cara pemberian obat
3. Evaluasi (follow-up)
a. Dari gejala yang ada. Titrasi-dosis
b. Ketaatanminum obat perlu dikontrol.
dari pihak yang terlihat. Seperti dikatakan
di depan, dari
farmakologi diperlukan kesiapan-kesiapan dalam alternatif-
alternatif pemilihan obat, individualisasi dosis monitoring man-
faat klinik, efek buruk, penilaian strategi terapeutk, dan lain-
lain. Selain kesiapan-kesiapan dalam bidang terapeutika, pe-
ningkatan sarana laboratorium farmakologi klinik untuk anali-
sis kadar obat-obat tertentu dalam cairan biologik perlu diper-
hatkan.
PEMBAKUAN STRATEGI TERAPI
Di pusat-pusat pelayanan atau pusat-pusat pendidiikan dok-
tor, biasanya berdasarkan masalah-masalah penyakit
yang di-
hadapi, telah dibuat suatu strategi terapi standar untuk masing-
masing jenis penyakit. Strategi terapeutik dibuat berdasarkan
tulisan-tulisan atau laporan-laporan penelitian yang
dimuat
dalam berkla-berkala kedokteran, atau berdasarkan tambahan
pengalaman setempat yang telah di telaah secara tuntas. Evalu-
asi pengalaman setempat akan banyak bermanfaat dalam me
ngembangkan standar terapeutik di masing-masing rumah-
sakit. Misalnya, dalam menghadapi satu kasus meningitis pada
anak, sebelum hasil pemerlksaan mikrobiologk untuk me-
mastkan kuman
penyebabnya dan pola sensitifitas kuman ter-
hadap antibiotika di terima, di mana ini akan makan waktu be-
berapa hari, dokter harus secepat mungkin memberikan tera-
pi. Bagaknana dokter harus memilih antibiotika yang
tepat?
Pemilihan alternatif sebelum ada kepastian hasil laboratorium,
dibuat berdasarkan pustaka dan perkiraan-perkiraan ilmiah
(scfentfic guess) berdasarkan data epedemiologik maupun
pola sensitifitas se tempat yang dikumpulkan dari data sebe-
lumnya di
Rumah-Sakit yang bersangkutan. Ketidak-cocokan
dengan hasil
laboratorium, bisa dlkoreksi kemudian dengan
melihat evaluasi terapeutik dari penderita yang bersangkutan.
Strategi-strategi terapeutik untuk tiap-tiap keadaan klinik
yang dominan perlu dikembangkan, dan dinilai kembali dari
waktu ke waktu. Pertimbangan-pertimbangan farmakologi kli-
ntk bisa dtberkan dalam pengembangan strategi terapeutik
seperti ini dan dalam penelaahannya kembali. Hal ini langsung
atau tidak akan mendorong upaya peningkatan kualitas pera-
watan penderita. Mekanisme konsultasi langsung akan berman-
faat untuk setiap kali menilai strategi terapi yang sudah di-
terima tersebut, berdasarkan pengalaman dari pasien ke pa-
sien.
KESIMPULAN
Sebagai penutup, bisa disimpulkan bahwa mekanisme kon-
sultasi famakologik langsung akan sedikit banyak membantu
dalam peningkatan kualitas terapi, dan
di samping itu meru-
pakan media yang sangat bermanfaat untuk pengajaran farina-
kologi klinik melalui pengalaman.
Lingkup konsultasi diharapkan beranjak dari pemilihan
obat, penentuan dan penyesuaian dosis,
monitoring terapi,
identifikasi efek samping dan evaluasi strategi terapi. Kerjasa-
ma dari klinikus dan pihak farmakologi akan sangat menentu-
kan bermanfaat atau tidaknya mekanisme ini.
KEPUSTAKAAN
1.
Halkin H. Principles of Clinical Pharmacology.
IV. Bedside Clinical
Pharmacology & Consultation.
In : Lemberger, L. &
Reidenberg, M.M.
(eds). Procoodings of the Second World Conference of
Clinical Pharma-
cology & Therapeutics. Published by the American
Society for Phar-
macology and Experimental Therapeutics, Bethesda,
Maryland 1984
pp: 31-36.
2.
Sjoqvist F. Borga 0 & Orme ME.
Fundamentals of Clinical Pharmacology. In : Avery. G.S (ed) Drug Tre-
atment - Principle and Practice of Clinical Pharmacology & Therapeu-
tics. 2
nd
ed. Sydney : Adis Press,
pp : 1 - 61
3.
Gross F. Clinical Pharmacology is an exporimental science. M.M.
(eds).. Principles of Clinical Pharmacology & Therapeutics.
Published
by the American Society for Pharmacology and Expreimental Therape-
utics. Bethesda, Maryland. 1984 pp :
316 - 330.
4. World Health Organization. Clinical Pharmacology : Scope, Orga-
nization, Training. WHO Technical Report Series, No. 446, 1970.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 57
Sekilas Tentang
Sub Bidang Farmakokinetika
Bagian Penelitian dan Pengembangan
PT Kalbe Farma
LATAR BELAKANG PENDIRIANNYA
Dengan dicapainya kemajuan- kemajuan yang pesat dalam
bidang farmakologi klinik, biofarmasi dan farmakokinetika,
sekarang bisa diketahui bahwa :
a).
terdapat hubungan yang erat antara jumlah/konsentrasi
obat dalam tubuh (pada "site of action") dengan intensitas
efek yang ditimbulkannya.
b). persyaratan beberapa sifat fisik dan kandungan zat aktif
sediaan tidak cukup untuk bisa menjamin tercapainya efekti-
fitas
obat yang diharapkan. Dengan kata lain, dua sediaan
(dengan komposisi zat aktif dan bentuk sediaan yang sama)
yang ekivalen dalam hal persyaratan tersebut belum tentu
dapat menghasilkan ketersediaan zat aktif dalam tubuh (bio-
availabilitas) yang ekivalen.
Sesuai dengan motto PT. Kalbe Farma : "Mengabdikan ilmu
untuk kesehatan dan kesejahteraan", maka adanya perkem-
bangan ilmu-ilmu tadi telah dengan sendirinya menyebabkan
perubahan pandangan dalam menilai kualitas sediaan yang
dihasilkan.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh obat-obat
yang diproduksi tidak lagi cukup hanya dengan memenuhi
persyaratan- persyaratan resmi yang ada saja (kandungan zat
-
aktif, sifat fisik sediaan, dll.) tetapi harus benar-benar memiliki
potensi terapeutik yang tinggi : bioavailabilitas yang baik.
Dengan demikian, pada awal tahun 1982 pada saat Sub
Bidang Farmakologi dinaikkan posisinya menjadi Bidang
Farmakologi, lahirlah beberapa Sub Bidang yang berada di ba-
wah Bidang Farmakologi, salah satu diantaranya adalah Sub
Bidang Farmakokinetika yang tugas utamanya melaksanakan
uji bioavailabilitas.
Pada tahap selanjutnya, fungsi
- fungsi yang dijalankan Sub
Bidang ini ternyata mengalami perkembangan, di antaranya
adalah : pemeriksaan kecepatan disolusi zat aktif dari sediaan
(dissolution rate),
sehingga kalau melihat fungsinya yang ada
sekarang ini, Sub Bidang ini mungkin akan lebih tepat kalau
disebut Sub Bidang Biofarmasi & Farmakokinetika.
Gambar 1. Staf peneliti pada sub bidang Biofarmasi & Farmako-
kinetika bergambar bersama Kepala Bidang Farmakologi dan Manager
Puslitbang. Berdiri dari kiri ke kanan : Dr. A. Hadyana P. (Manager
Puslitbang), dr. Bambang Suharto (Ka. Bid. Farmakologi), Dr. Yeyet
Cahyati S., Apt. (Konsultan, Staf. Pengajar pada Jurusan Farmasi
FMIPA ITB), Drs. Victor S. Ringoringo (Ka. Sub. Bid. perioda 1982
1984); duduk dari kiri ke kanan : Yuniwati A. Chandra, Erni Suwaro,
dan Tuti Resmiati (analis), Dra. Umi BS Apt. (Ka. Sub. Bid. Bio-
farmasi & Farmakokinetika sejak 1984 s/d sekarang).
FUNGSI - FUNGSI YANG SUDAH DIJALANKAN
Sesuai dengan kedudukan PT. KALBE FARMA sebagai se-
buah industri farmasi yang memproduksi sediaan obat jadi,
fungsi - fungsi yang sudah dilaksanakan oleh Sub Bidang ini
meliputi :
1). Pemilihan bahan baku zat aktif (sumbernya) yang paling
baik dengan melihat kecepatan disolusinya.
Sebagaimana kita
tahu, suatu senyawa aktif yang dihasilkan/diproduksi oleh
industri - industri yang berbeda belum tentu berkualitas sama,
sedangkan kualitas bahan baku yang dipergunakan akan dapat
mempengaruhi kualitas sediaan yang dihasilkan. Kecepatan
58 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Gambar 2. "HANSON Dissolution Tester", alat uji laju disolusi
type USP dengan kapasitas 6 labu yang dilengkapi dengan peralatan
sampling dan penggantian cairan dissolusi otomatis, yang sudah di-
miliki oleh Sub bidang Biofarmasi & Farmakokinetika Puslitbang
PT. Kalbe Farma.
Gambar 3. Kamar dan peralatan khusus untuk pengambilan sampel
cairan biologis dari sukarelawan.
disolusi zat aktif dari sediaan dalam saluran pencernaan ma-
kanan cukup erat kaitannya dengan kecepatan absorbsi obat
tersebut dalam tubuh.
2). Evaluasi sifat/kualitas sediaan dalam tahap pengembangan.
Sub Bidang Biofarmasi. & Farmakokinetika ini ikut membantu
bidang formulasi dalam pengembangan dan perbaikan formula
sediaan, khususnya sediaan padat (tablet, kapsul, kaplet)
dengan efek sistemik yang digunakan secara oral, yaitu dengan
menentukan profil disolusi zat aktif dari
masing-masing
formula yang dicoba. Data ini kemudian akan menjadi suatu
bahan pertimbangan untuk bidang formulasi dalam menentu-
kan langkah-langkah selanjutnya mengenai formula -formula
yang sudah dikembangkan tadi. Apakah harus ada perbaikan
lagi, atau langsung ke penentuan bioavailabilitas dengan me-
milih satu atau beberapa formula yang terbaik.
3).
Penilaian tahap akhir mutu sediaan. Sediaan- sediaan yang
formulasinya sudah selesai dan siap untuk diproduksi dalam
skala besar untuk mulai dipasarkan, khususnya sediaan-sedia-
an dalam bentuk padat yang digunakan secara oral, diperiksa
mutunya dengan menilai bioavailabilitasnya. Penilaian bio-
availabilitas dilakukan secara komparatif dengan membanding-
kannya terhadap bioavailabilitas sediaan lain (dalam bentuk
sediaan dan komposisi zat aktif yang sama), yang diproduksi
oleh pabrik farmasi lain yang patut dijadikan sebagai patokan
yang baik. Penelitian ini dilakukan terhadap sukarelawan
sehat, di mana terhadap mereka ini terlebih dahulu dijelaskan
beberapa hal yang meliputi : tujuan penelitian, obat yang
dicoba, efek samping yang mungkin terjadi, tanggung jawab
perusahaan, dan lain-lain. Sebelum penelitian dimulai.
4). Penilaian ketepatan aturan dosis (dosage regimen). Dengan
mengetahui therapeutic window dan data farmakokinetika-
nya, aturan dosis obat dinilai kembali, apakah dosis tidak ter-
lalu besar sehingga pemakaian obat tidak efisien atau malah
mungkin akan timbul efek-efek yang tidak diharapkan, atau
mungkin terlalu kecil sehingga obat tidak akan bekerja secara
efektif.
Data farmakokinetika yang dipakai di sini adalah data far-
makokinetika yang telah dihasilkan dan diamati pada orang-
orang Indonesia sendiri, yang penelitiannya dilakukan oleh
PT. Kalbe Farma. Sebugaimana kita ketahui, data farma-
kokinetika suatu obat yang dihasilkan oleh orang-orang Barat
belum tentu sama dengan yang dihasilkan oleh orang-orang
Indonesia. Oleh karena itu, aturan dosis yang sudah disusun
untuk orang-orang Barat belum tentu sama dengan yang di-
perlukan oleh orang-orang Indonesia. Dengan demikian, se-
benarnya aturan pemakaian obat di Indonsia harus didasar-
kan kepada kondisi- kondisi yang ada di Indonesia sendiri.
Hal inilah yang sedang dirintis oleh PT. Kalbe Farina dalam
rangka pemakaian obat yang lebih rasional di negara kita.
SARANA YANG TERSEDIA
Untuk melaksanakan fungsi -fungsi di atas tadi, Sub Bidang
Biofarmasi & Farmakokinetika telah melengkapi diri dengan
sarana- sarana yang diperlukan, baik ruang dan peralatan mau-
pun sumber daya manusia.
Ruangan
Sampai dengan saat ini, Sub Bidang Biofarmasi & Farma-
Gambar 4. "DESAGA Tri-dimensional Shaker ", pengocok tiga
dimensi yang khusus digunakan untuk ekstraksi senyawa aktif dari
cairan biologis.
Cermin Dunia
Kedokteran No. 37 1985 59
Gambar 5.. Satu set alat penguapan pelarut organik yang dirancang
sendiri, yang memakai sistem hampa udara dan aliran gas nitrogen di
samping thermostat sendiri.
kokinetika telah memiliki beberapa ruangan sendiri untuk
pelaksanaan aktivitasnya, di antaranya adalah ruang labora-
torium untuk penyiapan sampel (sample preparation) dan
analisis, dan "ruang sukarelawan" yang digunakan untuk pem-
berian sampel obat dan pengambilan sampel cairan biologis.
Peralatan
Sub Bidang ini sudah memiliki seju mlah peralatan yang
cukup lengkap untuk mclaksanakan tugas
-tugasnya. Peralat-
an yang tersedia dapat diperinci sebagai berikut :
Peralatan sampling dan penyimpanan sampel meliputi
sejumlah
meubelair untuk sukarelawan, lemari pendingin
(freezer), dan lain-lain.
Peralatan untuk pengolahan dan penyiapan sampel :
alat sentrifus, alat pengocok tiga dimensi (tridimensional
shaker), tabung ekstrasksi khusus (dapat dipakai sekaligus
untuk pengocokan, sentrifugasi, penguapan pelarut, dan untuk
rekonstitusi ekstrak), satu set alat penguapan pelarut (terdiri
dari pemanas, sistem hampa dan sistem aliran gas nitrogen),
thermostat, oven, whirlimixer, dan lain-lain.
Peralatan untuk analisis : seperangkat peralatan untuk
analisis mikrobiologik (cawan petri, inkubator, dan lain -lain),
dan peralatan analisis lain yang ditunjang oleh Sub Bidang
Standardisasi seperti : kromatograf cair penampilan tinggi
(HPLC), kromatograf gas (GC), TLC-Scanner, spektrofoto-
meter UV-Visible, spektrofotometer serapan atom (AAS),
Alat disolusi (dissolution tester) type
USP, model
Hanson, kapasitas 6 labu dengan alat pengambil dan peng-
ganti cairan disolusi yang otomatis.
Alat simulasi
(absorption simulator) SARTORIUS.
Peralatan untuk pengolahan data. Untuk pengolahan
data Sub Bidang Farmakokinetika memiliki kalkulator yang
dapat diprogram
(programmable calculator) dan mendapat
bantuan dari bagian pengolahan data elektronik (Electronical
Data Processing)
untuk penggunaan komputer, khususnya
untuk keperluan penentuan parameter
farmakokinetika
dengan cara regresi non-linier dan untuk simulasi perkembang-
an kadar obat dalam tubuh.
Personalia
Sejak mulai berdiri sampai dengan sekarang, Sub Bidang
ini dipnnpin oleh seorang tenaga Apoteker yang dibantu be-
berapa orang tenaga analis.
Karena fungsinya yang semakin meningkat sehingga masa-
lah-masalah yang dihadapi menjadi lebih banyak, pada saat
ini Sub Bidang Biofarmasi & Farmakokinetika
mendapat
tambahan bantuan tenaga, yaitu seorang tenaga Apoteker
yang telah mendapatkan pendidikan khusus dalam bidang
farmakokinetika. Bantuan lainnya adalah bantuan pelayanan
dariSub Bidang Bio-analitik, dalam hal pengembangan metoda
analisis dan pelaksanaan analisis yang sebenarnya yang dilaku-
kan secara fisikokimia (HPLC, CC, TLC-spektrofotodensito-
metri, dan lain-lain).
HASIL-HASIL YANG SUDAH DICAPAI
Telah cukup banyak penelitian- penelitian yang dilakukan
oleh Sub Bidang Farmakokinetika, khususnya penelitian da-
lam hal bioavailabilitas.
Penelitian bioavailabilitas yang sudah diselesaikan di antara-
nya adalah penelitian bioavailabilitas untuk sediaan : ampisilin
kapsul dan kaplet (Kalpicilin
), amoksisilin kapsul dan kaplet
(Kalmoxilin
), eritromisin stearat kapsul dan kaplet (Kalthro-
cun
), furosemid tablet (Salurix
), Josamisin tablet (Josa-
Gambar 6. Kromatograf cair penampilan tinggi (HPLC) Merek
Hewlett-Packard type 1084 B, satu di antara beberapa alat analisis
modern yang sudah dimiliki oleh Puslitbang PT. Kalbe Farma, yang
juga digunakan untuk penentuan kadar zat aktif terapeutik dalam cair-
an biologis.
60 Cermin Dunia
Kedokteran
No. 37 1985
Gambar 7. Salah satu =sin komputer milik PT. Kalbe Farina yang
digunakan untuk identifikasi parameter farmakokinetik dcngan cara
rcgresi
non-linier.
xin
1, parasetamol tablet (Procold
, rifampisin kapsul
(Kalrifam), dan lain- lain.
Hasil- hasil tersebut di atas sudah dipublikasikan baik pada
seminar- seminar maupun pada majalah- majalah yang sifatnya
il
miah. Di antaranya adalah :
1. Victor SR, Bioavailabilitas komparatif dua preparat kapsul Amoksi-
silin 250 mg, Pekan Ilmiah & Simposium Fakultas Farmasi UGM,
Yogyakarta. September 1981.
2. Victor SR, Bioavailabilitas komparatif dua preparat kapsul Rifam-
pisin 300 mg, Kongres Nasional Mikrobiologi ke 3, Jakarta, 26
28 Nopcmber 1981.
3. Victor SR, Ern Suwaro dan Yuniwati ACh, Bioavailabilitas kom-
paratif tiga preparat tablet ampisilin 500 mg, Kongres Ilmiah Far-
masi Nasional ke IV, Jakarta, 20 22 Januari 1983.
4. Victor SR, Erni Suwaro dan Yuniwati ACh, Bioavailabilitas kom-
paratif tiga preparat kapsul ampisilin 250 mg, Kongres Nasional
ke V Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia, Semarang, 27 Nopember
1 Desember 1983.
5.
Victor SR, John Tilly dan Erni Suwaro, Penetapan bioavailabilitas
komparatif dua preparat tablet ampisilin 500 mg dengan metoda
ekskresi urin kumulatif, Kongres Ilmiah Farmasi Nasional ke V,
Bandung, 26 28 Agustus 1984.
6. Victor SR, Bioavailabilitas komparatif tiga preparat Amoksisilin
500 mg, Majalah Farmakologi Indonesia & Terapi, Th. II (1), 1985,
17.21.
(Yeyet CahyatiS.)
(Sambungan dari halaman 25)
Better Savety of Drugs and Pharmaceutical Products. Elsevier
Biomedical Press, 1980: 11742.
2.Ritschel
WA. Handbook of Basic Pharmacokinetics, first edition,
Hamilton: Drug Intelligence Publication Inc, 1976 : 14359.
3.Rowland M & Tozer TN. Clinical Pharmacokinetics: concepts and
applications, Philadelphia: Lea & Febiger, 1980 : 4864.
4.Brun C, Hilden T & Raaschou F. The significance of the difference
in systemic arterial and venous blood concentrations in renal
clearance methods. J Clin Invest, 1949 : 14452.
5.Tucker GT. Measurement of the renal clearance of drugs. Br J Clin
Pharmac, 1981; 12 : 76170.
6.Suryawati S & Santoso B. Penurunan kecepatan eliminasi renal
salisilat karena pra perlakuan propranolol. In press: Majalah Farma-
kologi & Terapi Indonesia, 1985b.
7.Rane A & Wilson JT. Clinical pharmacokinetics in infants and
children. Clin Pharmacokin, 1976; 1 : 224.
8.Crooke J, O'Malley K & Stevenson IH. Pharmacokinetics in the
elderly. Clin Pharmacokin, 1976; 1 : 28096.
9.Beckett AH & Rowland M. Urinal)) excretion kinetics of methyl-
amphetamine in man. Nature, 1965; 206 : 12601.
10.Suryawati S & Santoso B. Pengaruh dosis terhadap eliminasi renal
salisilat, sulfadiazin dan sulfametazin. Akan dipublikasi, 1985a.
(Sambungan dari halaman 20)
2.
VF Smolen. Quantitative determinations of drug bioavailability
and biokinetic behavior from pharmacological - data for ophthalmic
and oral administrations of a mydriatic drug, J Pharm Sci 1971;
60;354 365.
3.
VF Smolen, WA Weigand . Drug bioavailability and pharmacokinetic
analysis from pharmacological data, J. Pharmacokin Biopharm
1973;1: 329 -- 335.
4.
RL Wolen, A Rubin BE Rodda, AS Ridolfo, CM Gruber Jr. Pro-
blems associated with bioavailability and dosage regimen studies in
man, J Pharmacokin Biopharm. 1974; 2 : 365 377.
5. J Lindenbaum, MH Mellow, MO Blackstone, VP Butler Jr. Variation
in biologic availability of digoxin from four preparations, New Engl
J Med 1971; 285 1344 47.
6. Blair DC, Barnes RW, Wildner EL, Murray WJ. Biological availability
of oxytetracycline hydrochloride capsules. A comparison of all
manufacturing sources supplying the United States market, JAMA
1971; 215 : 251 254.
7. WH Hauck, S Anderson. A New Statistical procedure for testing
equivalence in two - group comparative bioavailability trials. J
Pharmacokin Biopharm. 1984;12 : 83 117.
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 61
Cara Menentukan Kualitas
Protein Suatu Bahan Makanan
Dra. Oey Kam Nio
Unit Penelitian Gizi Diponegoro
dari
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Departemen Kesehatan
Kualitas suatu
protein bahan makanan ditentukan oleh pola
asam aminonya, serta jumlah masing - masing asam amino
esensialnya. Asam
amino esensial, yaitu asamamino yang tidak
dapat disintesis oleh tubuh kita sendiri, dan dengan demikian
harus diperoleh dari makanan sehari-hari adalah : valin, leusin,
iso-leusin, lisin, triptofan, metionin, fenilalanin, threonin.
Asam amino non-esensial juga diperlukan oleh tubuh, te-
tapi karma dapat disintesis oleh tubuh sendiri, jadi tak mutlak
harus ada dalam makanan sehari-hari. Kualitas suatu protein
nrakanan akan semakin tinggi, bola pola asam aminonya se-
makin menyamai pola asamamino protein tubulr kita. Kualitas
suatu protein dapat ditentukan dengan beberapa cara, misal-
nya cara Knnia dan cara Biologik.
CARA KIMIA
Penentuan Chemical Score atau Amino Acid Score dengan
menggunakan kadar asam amino (esensial) dapat memberikan
perkiraan tentang kualitas protein, tapi tidak tentang bio-
availability asam-aminonya.
Dengan cara ini, sesudah kadar masing-masing asam-amino
esensial-nya ditentukan, kadar ini dibandingkan dengan yang
tertera pada suatu reference protein. Sebagai Reference pro-
tein sekarang dipakai whole hen's egg protein atau Cow's
milk protein
1
. Sebelumnya digunakan Provisional Amino Acid
Pattern (PAAP) dari FAO/WHO. PAAP adalah suatu "pro-
tein" hepotetis yang mempunyai nilai biologik yang tinggi
dan pola asam amino yang spesifik
2
. First limiting amino
acid adalah asam amino esensial yang juinlahnya terkecil
dibanding dengan jumlah asam amino yang sama yang ada
pada suatu reference protein. First limiting amino acid ini
dapat dipakai untuk menghitung chemical score
3
atau amino
acid score
4
yang merupakan suatu ramalan ilmiah mengenai
kualitas suatu protein. Asam amino dengan kadar yang kedua
terkecil dibandingkan dengan yang ada pada reference protein
dinamakan second limiting amino acid, dan seterusnya.
Dengan cara kimia ini tidak diperhitungkan besarnya daya
cerna (digestibility)
protein, dan pula apakah asam amino
ber-
ada dalam bentuk
yang dapat dipakai tubulr (bio-availability).
Juga perlu perhatian bahwa pola asam amino suatu protein
akan berubah
dari keadaan semula, sesudah mengalami pe-
nyerapan dan pemecahan (absorpsi dan pencernaan).
CARA BIOLOGIK
Binatang percobaan untuk keperluan ini, yang umum di-
pakai adalah tikus putih (albino rats), tetapi dapat dipakai
juga binatang lain,
misalnya ayam. Tikus putih dipakai karena
tikus putih seperti juga manusia, adalah omnivor, dan telah
terbukti bahwa kebutuhan akan asarn amino esensialnya me-
nyamai kebutuhan manusia, khususnya anak-anak.
Di samping
itu pemeliharaannya relatif murah, misalnya makanan dan
kandang, pula dapat berkembang biak dengan pesat. Tikus
laboratorium dalam keadaan sehat dapat hidup 2 - 3 tahun.
Satu
minggu umur tikus putih ekivalen dengan 30 minggu
umur manusia, sehingga pengaruh zat gizi terhadap pertum-
buhan dapat dipelajari dengan cepat pada tikus putih.
Untuk penelitian ilmiah harus dipakai tikus putih dari
inbred strain,
dengan syarat tertentu mengenai usia, kelamin
dan berat badan. Juga harus memenuhi syarat defined labo-
ratory animal.
Artinya apabila genotype, phenotype dan
dramatype-nya telah konstan.
Syarat-
syarat ini perlu diperhatikan, karena hasil yang
diperoleh harus dapat dibandingkan dengan hasil lain dari
penentuan sendiri (reproducibility).
Juga untuk dapat di-
bandingkan dengan hasil peneliti lain
yang menggunakan
tikus-tikus putih yang sama. Tikus putih
yang memcnuhi
syarat ini (defined) tcrsedia di Unit
Penelitian Gizi Dipone-
goro dari Badan Penclitian dan Pengembangan
Kesehatan,
Dep Ke, Jakarta.
Tikus putih ini sejak tahun 1954 khusus dibiakkan di Unit
Penelitian Gizi Diponegoro, dan dinamakan Lembaga Makanan
62 Ccrmin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Rakyat (LMR)-strain, asal Wistar (Wistar derived).
Ada beberapa cara biologik untuk menentukan kualitas
suatu protein makanan, misalnya BV atau Biological Value,
PER atau Protein Efficiency Ratio, dan NPU atau Net Protein
Utilization.
Syarat untuk penentuan PER
5
dan NPU
6,7
dengan tikus
putih adalah sebagai berikut :
Protein Efficiency
Ratio (P.E.R.)
Kenaikan berat
badan (g)
Jumlah protein yang
dimakan (g)
Net Protein
Utilization (N.P.U.)
N yang ditahan
tubuh (g)
N yang dimakan (g)
Standard | Operative
Lamanya penelitian
Binatang percobaan
Umur
Kelamin
Induk
Tempat
Makanan eksperimen :
(experimental diet)
a) Tanpa protein
(Protein free diet)
b)
Reference diet
Susu bubuk skim
Kadar protein
c) Makanan percobaan
(Test diet)
Kadar protein
Pada akhir percobaan
hasil penunjukan :
4 minggu
Tikus putih muda
(inbred)
28 hari
Biasanya semua jantan
Anak tikus putih
beberapa induk
Tikus dalam satu
kandang
Tidak dipakai untuk
PER tetapi dipakai
untuk NPR
10%
10%
Tikus tetap hidup
Efek protein terhadap
pertumbuhan
10 hari
30 1 hari
Dapat dipakai jantan
atau betina
diperoleh dari :
4 induk
4 tikus dari tiap induk
ditempatkan dalam satu
kandang dan dianggap
sebagai satu kesatuan.
Diperlukan
untuk se-
tiap penentuan (untuk
perhitungan)
10%
10%
> 10%
Tikus dimatikan untuk
penentuan kadar N-
tubuh (dikeringkan da-
lam
oven pada temp.
105
o
C) selama 3 hari.
Kualitas Efisiensi
protein penggunaan
protein da-
lam tubuh.
PROTEIN EFFICIENCYRATIO.
5
Pengertian PER telah diperkenalkan oleh Osborne, pada
tahun 1919,
dan hingga sekarang masih tetap dipakai secara
resmi di USA dan Canada untuk evaluasi kualitas suatu pro-
tein,
walaupun memerlukan waktu yang lama,
yaitu 4 minggu.
Kecepatan pertumbuhan suatu binatang percobaan dalam
kondisi tertentu dapat dipakai sebagai ukuran untuk kualitas
suatu protein
makanan. Bila makanan kekurangan akan satu
atau lebih dari satu asam amino esensial, maka pertumbuhan
akan lambat atau berhenti sama sekali.
Definisi Protein "Efisiensi
Rasio" adalah sebagai berikut :
Untuk tikus :
Salah satu kelemahan PER
adalah, dianggapnya seluruh pro-
tein yang dimakan dipakai untuk pertumbuhan, dan tidak ada
yang untuk mempertahankan jaringan-jaringan yang sudah ada
(maintenance). Untuk mengatasi kelemahan ini, diperkenalkan
suatu pengertian baru yaitu
Net Protein Ratio
8
dengan
definisi :
Kenaikan berat badan (gram) + Penurunan berat badan kelom-
pok tikus dengan
makanan tanpa protein (gram)
NPR=
Jumlah protein yang dimakan (gram)
Penentuan NPR sama seperti penentuan PER, akan tetapi di-
tambah dengan kelompok tikus yang diberi makanan tanpa
protein (protein free diet).
Hasil PER selalu dikemukakan dengan menunjukkan kadar
protein yang ada pada tes diet (umumnya 10%), dan dibanding
(dikonversi) dengan hasil reference
protein yang umumnya
terdiri dari reference casein. Karena reference casein
yang baik
sulit diperoleh di Jakarta, maka digunakan sebagai reference
protein itu susu bubuk skim, dengan pengertian bahwa susu
bubuk skim yang digunakan adalah susu bubuk skim yang
masih baru dan ditranspor /disimpan dalam kondisi yang
sesuai.
NILAI
BIOLOGIK (BIOLOGICAL VALUE), DAN NET PRO-
TEIN UTILIZATION (NPU).
Pengertian Nilai Biologik atau
Biological Value BV)
9
sudah
diperkenalkan oleh Thomas sejak tahun 1909. Angka nilai
biologik menunjukkan persentase nitrogen yang dapat di-
tahan oleh tubuh dari yang di absorpsi.
atau : menurut Mitchell (1923
1924) sebagai berikut
Penentuan angka Nilai Biologik merupakan suatu balance
study, dengan harus pula ditentukan kadar nitrogen dalam tin-
ja dan air seni. lni suatu prosedur yang
sangat memakan wak-
tu. Dalam rumus Nilai Biologik tidak diperhitungkan Daya
Cerna (Digestibility) protein, sedangkan daya cerna merupa-
kan faktor penting, apakah suatu protein
besar manfaatnya
untuk tubuh atau tidak.
Definisi untuk Digestibility (D)
10
atau Daya Cerna adalah
sebagai berikut
I = Jumlah N
F = Nitrogen tinja tikus (dengan makanan percobaan)
Fk = N
itrogen tinja metabolik (dari tinja tikus dengan makanan tanpa
protein)
U = Nitrogen air seni tikus (dengan makanan percobaan)
Uk = Nitrogen air seni endogen (air seni tikus dengan makanan tanpa
protein).
Khusus untuk menyederhanakan seluruh prosedur tersebut,
Miller dan Bender telah memperkenalkan pengertian Net
Protein Utilization.
6,7
yang mempunyai rumus sebagai ber-
ikut :
- NPU
=
B.V. x D
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 63
|
|
|
|
|
|
|
|
Metoda ini dibanding dengan balance-study asli dari Mitchell
jauh lebih sederhana dengan memberi hasil yang cukup ber-
guna untuk screening
nilai berbagai jenis protein.
dengan pengertian :
B = Nitrogen tubuh tikus dengan makanan percobaan (tes diet)
I
= Jumlah Nitrogen yang dimakan tikus dengan makanan percobaan
(tes diet)
Bk = Nitrogen tubuh tikus dengan makanan tanpa protein (protein
free diet)
Ik = Jumlah Nitrogen yang dimakan tikus
.
dengan makanan tanpa
protein (protein free diet).
Menurut Miller dan Bender
7
, penentuan nitrogen tubuh
tikus tak perlu ditentukan secara langsung, karena untuk
suatu tikus putih inbredperbandingan N/H
2
0 adalah konstan,
sehingga cukup dengan menentukan kadar H
2
O dalam tubuh
tikus pada akhir percobaan.
Y dapat dihitung dengan formula
log (4.8 Y) = 0.437 1.0123 X
X : umur tikus dalam hari pada akhir percobaan.
Berlakunya perbandingan N
____
H
2
0
konstan harus dibuktikan
dahulu untuk tiap strain tikus yang dipakai.
Beberapa contoh hasil NPU- standar dan NPU-operative yang
diperoleh di Unit Penelitian Gizi Diponegoro, Badan Peneliti-
an dan Pengembangan Kesehatan, Dep Kes, Jakarta.
NPU.standard
Whole Hen's Egg 95
Whole Milk Powder, Cow's 80 90
Skim Milk Powder, good quality 80 90
bad quality
(Yellow colour)
60
Viobin fish protein concentrate 82
Ikan kecil kering (lokal market) 61
Kacang kedela, rebus dan
dikeringkan
50 60
Tempe 50 60
Kacang tanah, goreng 50
Oncom kacang tanah
Bahan makanan campuran
kaya akan protein :
50
NPU-operative NPU-standard
Corn Soy Milk (CSM) 69 53
Wheat Soy Beverage (WSB) 53 46
64
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
PENGGUNAAN PRAKTIS NPU ADALAH :
Evaluasi kualitas protein
1. Bahan makanan kaya akan protein : asal nabati
asal hewani
2. Limba industri, yang murah dan lokal dapat diperoleh
seperti : ampas kelapa
ampas kacang kedela (ampas pembuatan tahu)
ampas kacang tanah
cottonseed meal
kapokseed meal
biji karet
bekatul beras (defatted)
3. Campuran (1) dan (2).
4. Bila campuran bahan-bahan makanan ditambah dengan
asam-asam amino sintetis.
Meramalkan secara ilmiah
Ketetapan penggunaan (suitability) dari campuran bahan
makanan untuk :
infant's milk formulas.
weaning foods
Nilai gizi (protein) makanan sehari-hari penduduk di bawah
garis kemiskinan (dinyatakan sebagai NDpCals
%).
Menentukan naik atau turunnya nilai gizi (protein) suatu
makanan selama pengolahan, penyimpanan dan lain-lain.
KEPUSTAKAAN
1. Ross Hackler L. In Vitro Indices: Relationships to Estimating Pro-
tein Value for teh Human. In: Evaluation of Protein for Humans,
Bodwell CE (ed). Westport-Connecticut-USA: The AVI Publishing
Company Inc. 1976; 55-67.
2.
FAO, Nutrition Studies No. 16, 1957.
3. Block RJ and Mitchell HH. The Correlation of the Amino Acid
Composition of Protein with Their Nutritive Value. Nutr Abst
Rev. 19461947; 1,6: 249-78.
4. FAO/WHO. Energy and Protein Requirements. WHO Tech Rept
Ser, Geneva, Switzerland: World Health Organization, 1973; 522.
5. AOAC. Official Methods of Analysis, 12
th
ed. Washington DC:
Official Agricultural Chemists. 1975.
6. Bender AE and Doell BH. Note on the Determination of Net
Protein Utilization by Carcass Analysis. Brit J Nutr. 1957; 11:
138-43.
7. Miller DS and Bender AE. The Determination of The Net Utili-
zation of Proteins by a Shirtened Method. Brit J Nutr, 1955; 9:
382-88.
8. Bender AE and Doell BH. Biological Evaluation of Proteins: A
New Aspect. Brit J Nutr, 1957; 11: 140.
9. Mitchell HH. A Method for Determining The Biological Value of
Protein. J Biol Chem, 19231924; 58: 873.
10. Bressani R. Human Assays and Application. In: Evaluation of Pro-
teins for Humans, Bodwell CE (ed) Westport-Connecticut-USA:
The AVI Publishing Company Inc. 1976; 86-89.
11. Nomura T and Tajima Y Defined Laboratory Animals. In: Ad-
vanced in Pharmacology and Therapeutics II. Yoshida H, Hagihara
Y and Ebashi S (ed). Oxford and New York: Pergamon Press.
1982;5: 325-33.
PERKEMBANGAN
Bunuh Diri Bersama
BANYAK kisah rakyat tentang percintaan yang diakhiri
dengan mati bersama. Ada Sam Pek Eng Tai, ada Pranacitra
Rara Mendut , kita kenal juga tragedi Romeo & Yuliet-nya
William Shakespeare. Namun, dari segi kedokteran, bagaimana
ini dapat diterangkan?
Bunuh diri bersama keputusan dua orang untuk mati
bersama jarang terjadi. Cohen, dengan penelitiannya yang
diterbitkan tahun 1961, masih tetap merupakan nara-sumber
yang paling baik. Ia hanya menemukan 58 kejadian demiki-
an di Inggris selama tahun 1955 8. Kematian ini hanya me-
rupakan 0,6% dari seluruh angka bunuh diri dalam masa itu.
Sainsbury, yang lebih dulu meneliti masalah ini, menemukan
8 kematian dari 4 kejadian bunuh diri bersama di tahun 1936-
8, dari seluruh angka bunuh diri, yaitu 390.
Kebanyakan orang yang melakukan bunuh-diri-bersama
mati, sehingga penelitian menjadi sulit. Data-data demografik
dapat dicatat, dan catatan/pesan-pesan pelakunya kalau ada
dapat memberikan informasi yang berharga; namun terlalu
tergesa-gesa
mengasumsi bahwa pernyataan dari mereka yang
berhasil diselamatkan ini kadang sulit atau tak mungkin
dibedakan dari pembunuhan disertai dengan bunuh diri, atau
bahkan dari kecelakaan.
Suatu artikel baru-baru ini mencoba merangkum tulisan
West dan penelitian dari orang-orang yang selamat.Dinyatakan
bahwa penganjur perbuatan itu biasanya pria, secara psikiatrik
sakit jiwa dengan depresi psikotik, dan biasanya mati. Ia punya
riwayat sakit jiwa. Orang yang selamat umumnya wanita,
yang tak punya riwayat perilaku suisidal, dan secara psikiatrik
tidak sakit jiwa. Si penganjur itu sering memberi paksaan dan
tekanan yang besar sekali pada pasangannya. Di sini tampak
persamaan antara si penganjur dengan pembunuh yang
kemudian bunuh diri, suatu peristiwa yang jauh lebih sering
terjadi. Pada kasus ini pun pelakunya umumnya pria, dengan
riwayat penyakit psikiatrik, serta riwayat perilaku suisidal. Te-
lah lama West mencatat hubungan erat antara bunuh diri dan
pembunuhan ipi: "satu dari tiga pembunuhan diikuti dengan
bunuh diri."
Dokter, apalagi ahli psikiatri, sering prihatin akan risiko
bunuh diri pada mereka yang menderita penyakit-penyakit
depresif. Adanya riwayat keluarga, usia setengah baya atau
usia tua, adanya penyakit fisik, usaha bunuh diri sebelumnya
dan hilangnya salah satu orang tua pada masa kanak-kanak,
merupakan pertanda yang tak baik. Apakah pertanda dari bu-
nuh-diri bersama misalnya hubungan yang terlalu erat
perlu dicari? Seharusnya demikian. Terutama karena kita se-
ring mengecilkan kemungkinan pembunuhan terhadap anggota
keluarga dekat.
Namun, selain agresi, ada juga motif lain dari bunuh diri
bersama itu. Lima dari contoh Cohen tak punya unsur agresi,
melainkan pakta percintaan (meskipun salah satu pria tidak
ingin mati). Ia mencatat: "keputusan itu umumnya keputusan
bersama." Catatan-catatan yang ditinggalkan hampir selalu
menyatakan bahwa keputusan itu keputusan bersama. Tapi,
perlu diperhatikan bahwa inisiatif umumnya dimulai oleh satu
orang, dan kadang kala perlu banyak paksaan. Kematian buda-
yawan besar Arthur Koestler setahun yang lalu bersama istri-
nya, yang tampaknya seperti bunuh diri bersama, sebenarnya
merupakan dua keputusan yang berbeda. Seperti halnya de-
ngan Romeo dan Yuliet, yang bunuh diri berturut-turut, atas
prakarsa sendiri-sendiri.
Mengingat hal-hal di atas, dokter perlu benaribenar
memperhatikan pasien yang menderita depresi berat. Potensi
agresivitas dan potensi bunuh dirinya perlu diikuti dengan sek-
sama.
Lancet 1984; 288:i,346 - 7
Mastektomi:
sedikit mungkin
sama dengan banyak
Secara historis, mastektomi radikal, yang diperkenalkan sekitar
tahun 1900, ditujukan buat wanita dengan tumor yang besar.
Belakangan, pemeriksaan menunjukkan adanya penyebaran
lewat saluran getah bening dari tumor primer ke kelenjar-
kelenjar aksila. Sehingga operasi besar tadi dibenarkan.
Ada konsensus umum bahwa kanker mulai sebagai penyakit
lokal, menyebar secara langsung maupun lewat getah bening,
dan secara bedah "dapat disembuhkan" sampai terjadi meta-
statis jauh yang saatnya tak diketahui. Konsep ini menye-
babkan operasi makin lama makin besar, dengan asumsi bahwa
bila tumor primer dapat diangkat cukup cepat dan cukup luas,
dengan kelenjar regional sekaligus, maka harapan hidup akan
meningkat.
Namun, setelah Perang Dunia II, sementara pencatatan
penderita tumor di negara-maju lebih cermat, analisa tabel-
kehidupan (life-table analysis) menjadi alat pengukurnya, dan
data yang lebih baik tentang harapan hidup dapat diperoleh.
Data ini mulai menunjukkan bahwa survival tidak diperbaiki
dengan operasi yang lebih luas itu. Maka dilakukan berbagai
penelitian
klinik terkontrol, secara acak dan multicenter,
untuk menelitinya lebih jauh.
Salah satu penelitian itu dilakukan oleh Fischer B dkk. Ia
menunjukkan, bahwa pada wanita dengan kelenjar aksila yang
negatif, pengangkatan buah dada secara sederhana (mastek-
tomi total), dengan atau tanpa terapi sinar X, memberikan
harapan hidup yang sama dengan mastektomi radikal yang
merusak badah itu. Pada wanita dengan kelenjar aksila positif,
mastektomi radikal tidak memberikan survival yang lebih baik
daripada mastektomi sederhana plus iradiasi. Data ini me-
nunjukkan bahwa pasien yang akan mati karena kanker payu-
dara itu meski telah dioperasi dan diiradiasi telah mem-
punyai mikrometastasis, yang membuat kedua jenis terapi itu
sama hasilnya. Kalau benar begini, maka keberhasilan mas-
tektomi tadi pada pasien tadi harus diukur dengan ada tidak-
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 65
nya rekurensi di dinding dada, di flap operasi, graft kulit,
atau aksila. Penelitian tadi juga menunjukkan bahwa rekurensi
lokal meningkat dengan pasti dalam 5 tahun pertama setelah
operasi; setelah itu, peningkatannya minimal. Penelitian lain
juga menunjukkan bahwa rekurensi lokal lebih berhubungan
dengan status kelenjar aksila dibandingkan dengan prosedur
operasi.
Lebih jauh lagi, angka kematian wanita dengan penyakit
Stadium I (kelenjar negatif) berbeda dengan yang Stadium II
(kelenjar positif), pengamatan yang didukung oleh banyak pe-
nelitian lain. Semua ini membawa kita kepada kemungkinan
yang menarik: yaitu bahwa wanita dengan Stadium II bukan-
lah mereka yang terlambat berobat ke dokter, melainkan me-
reka yang tumornya lebih agresif, yang metastasis kelenjar
aksilanya lebih nyata, yang metastasis jauhnya lebih cepat
muncul, yang rekurensi lokalnya lebih sering, dan yang kemati-
annya lebih cepat datang.
Penelitian lebih lanjut oleh Fischer B dkk. meneliti apakah
operasi yang lebih kecil lagi, yaitu mastektomi segmental,
dengan pinggir yang bebas tumor, dapat menggantikan mas-
tektomi sederhana (simple mastectomy). Kelompok yang
menjalani mastektomi segmental ini dibagi lagi menjadi mereka
yang mendapat iradiasi pada sisa payudaranya dan mereka
yang tidak. Tidak begitu mengherankan bahwa ternyata
survival 5 tahun bagi semua kelompok itu sama saja.
Masalah utama buat mastektomi segmental, setidaknya
buat 5 tahun pertama pasca bedah, bukanlah angka survival-
nya, melainkan jumlah rekurensi lokal dan timbulnya kanker
primer kedua pada payudara yang sama. Di antara mereka
yang dapat hidup setelah 5 tahun, 28 persen dari yang tidak
diiradiasi dan 8 persen dari mereka yang menerima radiasi
mempunyai tumor payudara rekurens. Sayang, dari data yang
ada, lebih sulit menentukan angka rekurensi lokal atau regional
lainnya pada ketiga kelompok terapi itu. Tapi, tampaknya,
angka itu hampir sama pada kelompok mastektomi dan
mastektomi segmental, dan lebih rendah pada kelompok mas-
tektomi segmental plus iradiasi. Rekurensi lokal pada dua
kelompok pertama itu tak berbeda dengan data pada peneliti-
an pertama. Telah menjadi pendapat umum bahwa rekurensi
lokal berasal dari eksisi yang tidak adekuat, meskipun bebe-
rapa penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan kelenjar
positif lebih sering mengalami rekurensi lokal daripada mereka
yang kelenjarnya negatif; fakta yang menunjukkan bahwa
rekurensi itu lebih merupakan sifat tumor tersebut dan bukan
karena ketidakmampuan ahli bedah.
Kegunaan terapi sinar X dalam penelitian ini muncul pada
saat beberapa ahli menganjurkan penghentian pemakaiannya.
Terapi sinar X, seperti halnya pembedahan, adalah upaya lokal
yang keefektifannya tidak dinilai dari survival pasien, namun
dari rekurensi regional atau lokal-nya. Dalam penelitian operasi
mastektomi radikal di atas tadi, rekurensi aksila lebih sedikit
terjadi bila diberikan radiasi profilaktik pada aksila yang tak
didiseksi. Pada penelitian mastektomi segmental di atas, re-
kurensi lokal dan kanker ipsilateral lebih jarang pada wanita
yang payudaranya diiradiasi. Observasi yang belakangan ini
agak tersamar oleh pemberian kemoterapi pada wanita yang
kelenjarnya positif.
Bagaimana kegunaan radiasi sinar X dibandingkan dengan
kemoterapi? Tidak cukup jelas untuk dapat memilih salah
satunya. Iradiasi adalah senjata yang "sekali buang". Maka
keuntungan pemberian profilaktiknya harus dibandingkan
dengan keuntungan menyimpan senjata itu untuk 15 25
persen survivor yang nanti akan mengalami rekurensi yang
dapat ditangani dengan radiasi.
Manfaat diseksi aksila pada penerita yang aksilanya negatif
juga diteliti pada penelitian ini. Meskipun banyak penelitian
menunjukkan bahwa pemeriksaan negatif-palsu dan positif-
palsu itu cukup sering, data dari penelitian 10 tahun ini me-
nunjukkan bahwa meski tidak didiseksi, survival pasien tak
berbeda. Diseksi aksila pada penderita yang kelenjarnya tak
teraba dapat dibenarkan bila interpretasi diagnostik diinginkan
atau diperlukan, namun ia bukanlah tindakan terapeutik.
Menunggu sampai kelenjar menjadi besar dan baru direseksi
tampaknya tidak mempengaruhi survival.
Kesimpulan yang menarik dari mastektomi segmental da-
lam penelitian ini mesti ditaruh pada konteksnya. Operasi ini
dilakukan pada pasien dengan Stadium I dan II, dengan tumor
yang diameternya sama atau kurang dari 4 cm, yang dapat
direseksi dengan bersih (pinggirnya bebas tumor). Pada 10%
pasien yang pinggir reseksinya tak bebas tumor, dan pada
semua yang tumornya muncul lagi pada payudara ipsilateral,
dilakukan mastektomi total sebagai prosedur kedua. Pasien
dengan kelenjar positif diberi kemoterapi tambahan.
Dari pembicaraan ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan
pembedahan pada kanker payudara dapat dicapai dengan
operasi yang lebih konservatif daripada yang biasa dilakukan.
Namun masih diperlukan waktu lagi untuk memastikannya.
N Engl J Med 1985; 312: 713-4
(Sambungan dari halaman 12)
6. Sutton G & Kupferberg HJ. Isoniazid as an inhibitor of primidone
metabolism. Neurology, 1975; 25 : 1179 1181.
7. Ellard GA. Variations between individuals and populations in the
acetylation of isoniazid and its significance ofr the treatment of
pulmonary tuberculosis. Clin Pharmacol Ther, 1976; 19 : 610
624.
8.
Santoso B. Genetic and covironmental influences on polymorphic
drug acetylation. Ph-D thesis, Univ Nowcastle Upon Tyne UK,
1983.
9. Jenne JW Mc Donald FM & Mondoza E. A study of the fonal cle-
arances, metabolic inactivation rates, and serum fall-off interac-
tion of isoniazid and para-amino salicylic acid in man. Amer Rev
Resp Dis, 1961; 84 : 371 378.
10. Vessel E. Geno-environment interactions in drug metabolism.
In : Turner P (ed), Clinical Pharmacology & Therapeutics. Procoo-
dings of the first world conference. MacMillan Publisher;1980;
pp : 63 79.
11. Park BK. Assessment of the drug metabolism capacity of the li-
ver. Br J Clin Pharmac,1982;14 : 631 651.
12. Krishnaswamy K. Drug metabolism and pharmacokinetics in mal-
nutrition. Clinical Pharmacokinetics, 1979; 3 : 216 240.
13. Buchanan M Eyeberg C & Davies, M. Isoniazid pharmacokinetics
in kwashiorkor. S Afr Med J, 1979; 56 : 299 300.
14. Shastri RA & Krishnaswamy. Metabolism of sulphadiazine in mal-
nutrition. Br J Clin Pharmac, 1979; 7 : 69 73
66 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Hukum &
Etika
Tepatkah Tindakan Saudara ?
Sebagai dokter praktek, anda tentunya pernah menghadapi
pengalaman seperti ini. Tapi, tindakan apa yang
seharusnya
dan sebarknya anda lakukan, inilah pokok yang
kami persoal-
kan kali ini.
Problemnya begini : Suatu kali, teman sejawat kita keda-
tangan pasien dengan keluhan sesak nafas, dan memang ada
riwayat asma. Pemerrksaan fisik pun menyokong kearah itu.
Setelah disuntik, dan dan teman sejawat kita baru akan menu-
lis resep ketika tiba-tiba saja pasien mengedorkan sehelai co-
py resep. Katanya : "Dok, tolong obatnya yang seperti ini sa-
ja, karena biasanya saya minum obat itu dan selalu sembuh."
Di atas
copy resep itu memang tertulis nama seorang dok-
ter specialis.
Teman sejawat kita-rupanya karena takut pasiennya nanti
lad ke dokter lain- menurut saja, dan menulis resepnya sesuai
dengan copy resep.
Dalam menghadapi persoalan demikian, dokter dapat ber-
tindak sebagai berikut :
a.
Setuju dengan obat-obat yang tertulis dalamcopy resep ter-
sebut dan menulis resep yang sama.
b.
Tidak setuju, tapi tetap menyalin nama seperti
yang tertulis
dalamcopy resep.
c.
Tidak setuju, dan menolak dengan tegas untuk menyalin-
kan
copy resep tersebut dalam resepnya.
Secara etika kedokteran dan hukum, bagaimana perjabaran
dari ke tiga tindakan di atas??
Atau, mungkin saudara dapat mengusulkan cara lain yang
lebih baik ???
Komentar
TANGGAPAN DARI SEGI ETIK KEDOKTERAN
Dalam menilai suatu tindakan dokter dari
segi etik itu tidak
selalu mudah. Lebih-lebih pada kasus "marginal".
ditambah si-
tuasi dan kondisi yang sudah tidak ideal. Artinya, bila dalam
kejadian sehari-hari, hal-hal yang
kurang etis sudah terlanjur
dianggap biasa atau wajar saja. Misalnya, seorang dokter umum
mengirim pasiennya ke dokter spesialis untuk konsultasi. Bia-
sanya terjadi :
*
Sejawat spesialis langsung mengambil alih pengobatan pa-
sien, tanpa memberitahu si dokter umum; ini sudah hampir-
hampir dianggap lumrah.
* Kadang- kadang pasien dikembalikan ke dokter umum de-
ngan anjuranyang tertulis dalam amplop tertutup. Sering jus-
tru si sakit yang protes, karena merasa dirinya di "pingpong"
dan harus membayar dua kali.
Kedua kejadian tersebut sebenarnya tidak/kurang etis, tapi
justru sudah dianggap lumrah.
Begitu pula dalam kasus yang drkemukakan di atas. Untuk
gampangnya, sejawat kita langsung saja memenuhi perminta-
an pasien dan menjalin resep yang disodorkan. Sepintas lalu
ini dianggap wajar saja. Buat apa repot-repot mempersoalkan
hal demikian, hanya buang-buang waktu dan sebagainya.
Dari segi etis, perlu dipertimbangkan apakah isi resep itu
sesuai dengan ksakitan sejawat tadi. Bila sesuai, ya tidak ada
masalah. Jadi, pertimbangannya itu atas dasar ilmiah, yaitu
medik-farmakologik kita setuju dengan isi resep yang akan di-
salin, dan bukan karma pertimbangan non medis, seperti
takut pasien lari/pindah ke dokter lain, dan sebagainya.
Bila isi resep yang disuruh salin tidak sesuai dengan penda-
pat sejawat tersebut, ia harus berani menolak dan memberikan
penjelasan yang meyakinkan terhadap pasien, misalnya sakit-
nya saat ini tidak persis sama seperti saat pasien menerima re-
sep dari dokter spesialis duku, dan sebagainya.
Bila pasien tidak dapat diyakinkan, saya kira yang terbaik
dari segi etik yaitu mengajurkan agar pasien kembali ke dok-
ter spesialisnya. Kita tidak perlu memaksakan pasien untuk
menerima resep dari kita. Karena kepercayaan pasien atau
suatu obat itu kadang - kadang memberikan efek sugestif bagi
penyembuhannya.
Jadi, dalam tiap kasus harus ada pertimbangan sendiri, dan
tidak bisa meniru kasus yang pernah ada saja. Untuk itu, tang-
gapan atas tiga alternatif yang dikemukakan adalah sebagai
berikut :
ad (a). Bisa benar, asal pertimbangannya sesuai secara medik-
farmakologi, bukan karena ingin menjaga pasien agar tidak lari
kedokter lain, dan lain-lain alasan non medik.
ad (b). Saya kira secara etik kurang baik, yaitu memberi re-
sep tidak atas keyakinan sendiri. Bagaimana bila ternyata ada
reaksi yang tidak dingini, tentu tidak dapat dijawab. "Saya
sudah bilang tidak setuju, tapi pasien yang mendesak." Setiap
dokter harus berbuat sesuai dengan keyakinanya.
ad (c). Tidak setuju, juga tidak menyalinkan resep, adalah
kurang bijaksana. Sebaiknya pasien disarankan kembali saja
pada dokter spesialis yang bersangkutan. Bila perlu dengan su-
rat pengantar yang jelas! Tapi sebelumnya jelaskan dahulu
pertimbangan sendiri yang bukan karena gengsi, tapi ilmiah.
Demikianlah pendapat saya dapat permasalahan yang diaju-
kan di atas.
dr. H. Masri Rustam
Direktorat Transfusi Darah
PMI/Ketua IDI Cabang
J akarta Pusat
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 67
TANGGAPAN DARI SEGI HUKUM KEDOKTERAN
Selama tidak terjadi apa-apa pada diri si pasien, maka tidak
akan ada masalah hukum. Jika sampai terjadi sesuatu pada diri
si
pasien, barulah timbul masalah hukum,
balk pidana maupun
perdata.
Menurut hukum pidana
Apapun yang
menjadi pilihan dokter itu, jika dapat dibukti-
kan adanya kesalahan/kealpaan dari
fihak dokter, maka dapat
dilakukan tuntutan berdasarkan K.U.H.Pidana pasal 360 yang
berbunyi :
1).
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebab-
kan orang lain
mendapat luka berat, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima
tahun atau pidana kurungan paling
lama satu tahun.
2).
Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebab-
kan orang lain
luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul pe-
nyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pen-
carian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara
paling lama
sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama
enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima
ratus rupiah.
Misalnya dokter itu menyalin begitu saja copy resep dokter
spesialis tadi dan terjadi overdoses,
karena penyakitnya se-
karang sudah jauh lebih ringan daripada waktu diperiksa oleh
dokter spesialis dulu, dokter itu tidak dapat menggeser ke-
salahan/kealpaan itu kepada si pasien. Dokter harus bertang-
gung jawab sepenuhnya atas apa yang
ia tulis dalam resepnya
(kecuali yang
merupakan tanggung jawab apoteker atau asis-
tennya, yaitu tentang obat-obat dengan dosis maksimal),
karena dokterlah yang memiliki pengetahuan kedokteran dan
bukan si pasien.
Menurut hukum perdata
Seperti telah kita ketahui, hubungan dokter -pasien merupa-
kan suatu persetujuan/kontrak terapeutik.
Dalam K.U.H.Perdata pasal 1338 antara lain dikatakan,
suatu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Selanjutnya menurut K.U.H.Perdata. pasal 1339,
suatu per-
setujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal
yang dengan
tegas dinyatakan
di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu
yang
menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan atau undang
-undang.
Jika dokter itu tidak setuju dengan copy resep dokter
spesialis tadi, tapi ia tetap menyalinnya, jelas tidak ada itikad
baik dari
fihak dokter itu, maupun tidak sesuai dengan ke-
patutan, kebiasaan atau undang-undang. Kalau sampai terjadi
sesuatu pada si pasien, maka dokter itu tidak dapat meng-
geser
kesalahan/kealpaan kepada si pasien. Ia tidak dapat
mengatakan: "Salahnya sendiri. Mengapa minta obat itu."
Dalam hal pilihan dokter itu adalah sub a). atau sub c).,
dengan sendirinya kesalahan/kealpaan menjadi tanggung
jawab dokter itu sepenuhnya.
Jadi apapun pilihan dokter itu, jika karena kesalahan/
kealpaannya si pasien sampai menderita kerugian, misalnya
harus dirawat di rumah sakit dan tidak dapat bekerja, dokter
itu dapat dituntut berdasarkan K.U.H.Perdata pasal
1365
yang berbunyi: Tiap perbuatan melanggar hukum
yang mem-
bawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang
karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti
kerugian tersebut.
dr. Handoko Tjondroputranto
Lernbaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
68 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
Catatan Singkat
Mengapa manusia berciuman? Diduga waktu berciuman
itu terjadi pertukaran "semio
- chemical" dan "phero-
mone", yaitu sejenis hormon yang dapat meningkatkan
rangsang seksual.
Berciuman itu biasanya dilakukan dengan saling
menghisap, atau saling merasakan sekresi-sekresi
kulit
pasangannya. Sebum yang diproduksi kulit itu kaya
akan substansi- substansi "semio-chemical", karena pada
kulit
wajah banyak terdapat kelenjar-kelenjar sebaseus
yang mencapai puncaknya pada usia dewasa.
Brit J Dermatol 1984; 111: 623-7
Alat masak listrik (oven) itu memanaskan makanan ter-
utama di
bagian tengahnya. Oleh sebab itu, bila kita
terburu-buru menggigit kue dari oven yang tampaknya
sudah dingin, dapat membuat lidah terbakar karena
ba-
gian
tengahnya inasih panas.
Hal yang sania bila para ibu
memanaskan susu botol.
Botol yang diraba sudah dingin jangan langsung dimi-
numkan pada bayi, karena susunya sendiri masih panas!
J. Paed 1984; 105: 864-7
Pembedahan tidak selalu dianjurkan pada
anak-anak
dengan ventrikular septal defek (VSD) yang kecil dan
tidak menimbulkan gejala; karena defek tersebut dapat
menutup secara spontan. Kegiatan fisik
anak juga tidak
perlu dibatasi secara ketat. Ini terbukti
dari hasil per-
cobaan terhadap 35 anak
dengan VSD yang dilakukan
kateterisasi jantung sambil melakukan latihan. Ternyata
latihan fisik tersebut tidak mernberikan perubahan efek
hemodinamik yang berarti.
Circulation; 1984; 70: 729-34
Adakah kepribadian pramorbid yang karaktcristik pada
penderita-penderita Parkinson? Kebanyakan penderita
itu
mcnunjukkan emosi dan sikap yang kaku, dengan
afek
yang dangkal, dan adanya kecenderungan pula
untuk menderita dcpresi.
J Neurol, Neurosurg and Psychiatry 1985; 48: 97-100
Kebakaran yang terjadi di Tokyo akhir tahun lalu te-
lah
merusak seluruh jaringan telekomunikasi dari satu
bagian
kota tersebut. Apa akibatnya? 217 cabang dari
bank Mitsubishi harus menghentikan kegiatannya, sistem
medical record dari
satu rumah sakit terganggu, demi-
kian juga sistem telex, credit card, dan telepon-telepon
putus. Diperlukan waktu beberapa minggu sebelum se-
luruh jaringan tersebut diperbaiki.
Beberapa jenis burung peliharaan mahal sulit dibedakan
mana yang jantan atau betina (bahkan burung
-
burung itu
sendiri bingung memilih lawan jenisnya, hingga kopulasi
biasanya dilakukan dengan coba-coba dahulu).
Untuk membantu mereka, ahli-ahli bedah hewan
memeriksa rongga abdomen burung itu dengan teknik
endoskopi fibreoptik. Teknik ini juga dilakukan oleh
para staf dari
Institute Zoology di London, dalam mem-
bedakan jenis kelamin dari
1056 burung-burung yang
terdiri dari 144 spesies yang berlainan.
Veterinary Record, 8 Des. p596-8
Pada pria muda yang pekerjaannya sehari-hari memegang
daging mentah, risiko timbul kutil (warts)
pada tangan-
nya dua kali lipat daripada pekerja lainnya.
Diduga virus kutil itu lebih cepat menyebar pada
kulit yang lembab, seperti pada kulit tangan pemegang
daging!
Archives Dermatol 1984; 120: 1314-7
Infeksi ulangan dengan gonore itu seung terjadi, walau-
pun pasien telah berulang-ulang mendapat suntikan an-
tibiotika. "Vaksin untuk mencegah penyebarannya per-
lu dikembangkan." Demikianlah argumentasi yang di-
muat dalam buletin WHO dan dengan problem resis-
tensi yang makin meningkat terhadap antibiotika, vak-
sin tersebut merupakan kunci untuk mengontrol penya-
kit gonore itu.
Bull WHO 1984; 62 : 671-80
Anda tidak merokok? Risiko anda sama seperti perokok
bila senantiasa berdekatan dengaa seorang perokok.
Ada istilah "honeymoon distance", yaitu suatu jarak
sejauh 1,5 meter. Di luar jarak tersebut, asap rokok akan
terdilusi sehingga dapat dikatakan aman.
Brit Med J 1984;
289 : 1385
Skizofrenia dapat disebabkan oleh virus! Demikian hi-
potesis
Timothy Crow yang dimuat dalam British
Journal of Psychiatry. Virus dapat berintegrasi dengan
gen dan diturunkan pada anak mereka.
Virus yang sama diduga sebagai penyebab penyakit
manik depresif, karena ada bukti di mana banyaknya
penderita manik depresif pada satu generasi akan diikuti
dengan
meningkatnya penderita skizofrenia pada ge-
nerasi selanjutnya.
Brit J Psy 1984; 145:24353
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 69
BEDA SEKALI
Disebuah kantor rumah sakit terde-
ngar percakapan dua orang mantri
juru rawat, yang
satu sudah agak
tua dan satunya lagi masih muda.
Muda: "Mas, saya ini belum mahir
memasang kateter. Tadi pagi
pasiennya teriak-teriak kesa-
kitan sewaktu kateter saya
masukkan".
Tua: "Pasiennya laki-laki atau pe-
rempuan?"
Muda: "Laki- laki."
Tua :
"Ya jelas kesakitan kalau di-
masuki. Coba kalau dimasuk-
kan, pasti enak sekali."
Muda : ???
Umi
70 Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985
SAYA SUDAH SIAP DOK
Seorang pasien pria menghadap seorang dokter untuk keluhannya yaitu nafsu sex yang
terlalu besar.
Dokter : "Baik sebelum saya periksa, saudara perlu disiapkan dulu oleh suster: yaitu
telanjang sampai pinggang !"
Dan dengan itu dokter menyuruh perawatnya,
yang cukup cantik wajahnya untuk
orang sakit tersebut.
Beberapa saat kemudian terdengar teriakan
dari suster tadi dari
ruang periksa, dan
suster berlarian keluar. Dengan keget dokter lari masuk ruang periksa dan menanya-
kan apa yang terjadi.
Pasien :
"Saya sudah siap dok.
"
Dokter : "Astaga, saya memang mengatakan supaya saudara telanjang sampai
pinggang, tapi yang saya maksud dari
kepala sampai pinggang, bukan
dari kaki sampai pinggang.
"
Tentunya saudara pembaca dapat menebak, apa kiranya
yang membuat suster tersebut
lari terbirit-birit keluar dari ruang praktek.
OLH
GANGGUAN KESEIMBANGAN
Seorang pasien datang ke tempat praktek Dokter Ahli saraf
Pasien:
"Dok, akhir-akhir ini saya selalu pusing. Kenapa kiranya Dok?"
Dokter: "Apakah anda bekerja?"
Pasien:
"Ya, saya bekerja di kota pada sebuah perusahaan swasta, tapi masih harian
Dok!"
Dokter: "Berapa orang yang anda tanggung?"
Pasien:
"Tujuh orang Dok, satu istri dan enam orang anak".
Sambil mengerutkan da-
hi Dokter mangguk-mangguk.
"Oooooo............begitu, jadi pusing anda ini akibat gangguan keseimbangan".
Pasien terheran-heran : "Tidak Dok, kalau jalan saya tidak pernah sempoyongan".
Dokter: "Ya, memang, yang terganggu keseimbangan pemasukan dan pengeluaran
Anda".
Pasien: ??????????
dr. IGN Mayun
Lab. Histologi FK
UNUD Denpasar-Bali
PASIEN LUGU
Seorang gadis 16 tahun ingin berkon-
sultasi dengan seorang Dokter.
Gadis : ..Dokter, apakah ada obat un-
tuk menumbuhkan buah da-
da? Katanya kalau diremas-
remas bisa tumbuh sempur-
na, apakah betul Dok?"
Dokter : "Siapa yang memberi tahu
anda?"
Gadis: "Teman sekolah saya, Dok!
(Maksudnya teman pria)
Dokter : "Anda percaya?"
Gadis : "Ya, Dok sudah saya laku-
kan".
Dokter: "Bagaimana hasilnya ?"
Pasien : "Masih tetap kecil Dok, apa-
kah salah, Dok? cara me-
remasnya ?"
Dokter; (kebingungan) ???
dr. I G N Mayun
Lab. Histologi FK UNUD
DenpasarBali
PASIEN YANG SATU INI
Seorang dara wanita datang pada dok-
ter
ahli
penyakit kulit. Diketuknya
pintu tempat dokter itu praktek. Baru
saja dipersilahkan masuk oleh dokter
tersebut dan menongolkan kepalanya,
si pasien tersebut kelihatan terkejut
dan....... klepat ... keluar lagi. Dokter
penasaran lari keluar memanggilnya :
"He neng mau apa sih sebenarnya ?"
Dengan malu-malu si pasien muda ter-
sebut mengatakan
"
Dok, sebenarnya
saya mau berobat jerawat saya ini
pada dokter. Tapi setelah saya lihat
dokter juga jerawatan ..........
???????
BERMAIN UHU UHU
Serombongan dokter dari suatu negara Arab berkunjung ke sebuah kota besar di
Jerman Barat untuk mengikuti sebuah konferensi ilmu kedokteran dan tinggal di se-
buah hotel M. Setelah acara ilmiah selesai, dapat difahami bahwa para dokter tersebut
mencari hiburan malam yang tak terdapat di negerinya sendiri. Salah seorang di
antaranya berjumpa dengan seorang wanita Jerman dan mereka berdua bersepakat
untuk berkencan malam itu. Dibawanya dokter negara Arab tadi ke dalam kamar
sebuah hotel besar.
Wanita Jerman mengusulkan agar mereka berdua bermain Uhu, yaitu tiap kali
si wanita berseru "uhu", dokter tadi haru smenanggalkan sepotong pakaiannya. Bila
semua potong pakaian dokter tersebut sudah dilepas, tiba giliran sang dokter untuk
berseru "uhu" dan sang wanita yang akan melepaskan pakaiannya. Gagasan ini di-
terima dengan gembira oleh dokter tersebut. Untuk membuat suasana lebih menarik
maka semua lampu dipadamkan. Nah, permainan Uhu ini berlangsung baik sampai
dokter tersebut telah telanjang bulat dan ia telah berkali-kali berseru uhu-uhu dengan
genitnya. Setelah selesai sekian kali berseru uhu, oleh dokter tersebut diperkirakan
tentunya semua pakaian wanita sudah terlepas dan dinyalakannya kembali lampu-
lampu kamar.
Dengan rasa terkejut sekali diketahui wanita Jerman telah pergi beserta semua pa-
kaian dokter (beserta uangnya tentunya). Dokter tersebut dihadapkan pada persoalan,
cara bagaimana dapat kembali ke hotel di man rombongannya menginap. Sewaktu
melihat keluar jendela, dilihatnya serombongan orang berjubah putih (seperti orang-
orang "safari" padang pasir) sedang berjalan. Timbul gagasannya yang cemerlang
dalam benaknya dan dengan cepat disambarnya sprei putih dari atas tempat tidur, dan
sambil berkerudung meninggalkan hotel untuk bergabung dengan rombongan berjubah
putih di jalanan.
Dalam bahasa Arab ditanyakan kepada seseorang di sebelahnya hendak kemana
rombongan ini. "Ke hotel M, dan anda tentunya juga habis bermain Uhu, bukan ?"
OLH
TAKTIK.
Seorang pengemis tua minta sedekah pada seorang nyonya dokter yang kaya tetapi pe-
lit.
Nyonya : "Pergi! Tak ada uang!"
Pengemis :
"
Memang benar kata Udin, nyonya itu tidak pernah pegang uang. Se-
mua gaji suaminya diserahkan kepada pelayannya yang cantik
"
Sambil menggerutu pengemis itu berlalu.
Nyonya kaya itu marah dan melemparkan uang Rp. 1000, sambil berkata :
"
Apa kamu bilang! Saya tidak pernah pegang uang? Huhh !".
Pengemis itu mengambil uang sambil menggerutu kembali, kali ini dengan lirih
"Memang benar kata Udin, bahwa cara ini lebih berhasil ..........".
dr Adhi P.
Semarang
SRI
SALAH PENGERTIAN .
Dalam tempat praktek terjadi dialog antara seorang psikiater dengan pasien nenek tua.
+ :
"
Mengapa tidak dapat tidur dan gelisah, nek ?"
: "Memang dokter, sebab saya dikatakan terlibat kasus sex, kata polisi.
"
(dengan
suara gugup dan gemetar).
+
:
"
Hmm, sudah tua begini masih kuat juga di bidang sex ! Apa nenek tidak punya
suami ?"
"
Apa hubungannya dengan suami saya dok ? Ini cuma urusan pemalsuan.
"
+ :
"
Pemalsuan apa, nek ?"
"Itu kertas sek, yang untuk ambil uang itu."
+ : "Oooooooo itu............
rupanya masalah cek kosong . . . . hahaha ...."
dr. A. Hannie AC
Dumai
BAYAR BERAPA
Ketika mengobati seorang penderita
wanita setengah umur di Puskesmas di
daerah Riau, terjadilah percakapan se-
bagai berikut :
Dokter (setelah selesai memeriksa) :
Nah Ibu. Ibu ini perlu disuntik, mau
kan ?
Pasien (dengan spontan) : Satu jarum
bayar berapa, dok ?
Dokter : ???
dr. Tjandra Yoga Aditama
Cermin Dunia Kedokteran No. 37 1985 71
ABSTRAK -ABSTRAK
LEDAKAN PENDUDUK
Demikian gawatkah keadaannya? Memang demikian! Bahkan jauh lebih buruk dari-
pada yang dapat kita bayangkan. Ambil kota Meksiko sebagai contoh; mungkin kota
terbesar di dunia, dalamperjalanannya menuju kota megalopolis pertama. Dengan 17
juta penduduk (seperempat dari total penduduk negara tersebut) yang hanya menem-
pati luas permukaan bumi sebesar 2395 km
2
(densitasnya 7000 orang/km
2
). Lebih
dari 5 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dari 3 juta lebih unit perumahan,
dua dari setiap tiga rumah tidak memenuhi syarat-syarat sanitasi dan konstruksi: 19%
tidak ada sarana pembuangan, 21% tidak ada saran air bersih. Kenyataannya, sistem
suplai air memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebanyak 6
milyar liter air per hari.
Setiap hari, diperlukan 20 juta liter bensin, listrik sebanyak 11,1 juta kilo watt/
jam, 3750 ekor hewan potong, dan 5,35 juta kilogram tortillas (sejenis makanan khas
Meksiko). Setiap 24 jam, penduduknya membuat 20 juta perjalanan dalam 1728
kereta bawah tanah, lebih dari 10.000 bis, 86.700 taksi, dan 2,7 juta mobil pribadi.
Pada jam jam sibuk, rata-rata kecepatan mobil di jalan hanya 20 km/jam. Asap dari
kendaraan bermotor setiap hari menghasilkan 14.000 ton karbon monoksid. Bila ini
ditambah dengan 3850 ton yang dihasilkan dari 130.000 pabrik, dan 11.000 ton dari
asap dapur, hasilnya merupakan problem polusi yang luar biasa . Pada daerah tertentu,
diperkirakan polusi udara itu 200% di atas level yang diperbolehkan. Petugas kesehat-
an kota mengingatkan: bernafas dalam daerah tersebut sama seperti merokok 40 ba-
tang per hari!
Kris
International dateline, June 1984
KOMPLIKASI LUKA STERNUM DAPAT TERJ ADI KARENA IKAT PINGGANG
PENGAMAN MOBIL.
Para dokter dari bagian Gawat Darurat RS. Royal Victoria, Belfast, memperi-
ngatkan bahwa penggunaan ikat pinggang pengaman di mobil memungkinkan terjadi-
nya akibat yang serius. Telah dialami oleh 3 orang penderita bahwa ikat pinggang pe-
ngaman dapat menginduksi terjadinya fraktur sternum.
Dalam hal ini penderita hanya mengalami memar pada jaringan lunak sepanjang
ikat pinggang pengaman tersebut. Hasil EKG ternyata normal, tapi dengan foto sinar X
menunjukkan fraktur sternum yang abnormal. Selang waktu 2 4 hari, terbukti bah-
wa memar miokardium berkembang dengan meningkatnya DK MB (Creati-
ne Kinase -
Myocardium Band), suatu isoensim yang hanya ditemukan pada sel sel
miokardium. Peningkatan kadar isoensim ini menunjukkan derajat kerusakan mio-
kardium. Salah seorang penderita kemudian mengalami kegagalan ventrikel sehingga
diperlukan pengobatan dengan digoksin dan diuretika.
Hampir 1/3 bagian penderita dengan memar miokardium kemungkinan dapat
mengalami komplikasi kardiak yang membahayakan. Tetapi hal ini sering kali tidak di-
perhatikan karena penderita tampak sehat setelah mengalami trauma kecil.
DYT
Injury, 1984; NOV. 16 : 3 p. 155
72
Cermin Dunia Kedokteran No.
37 1985
Anda mungkin juga menyukai
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Laporan Resmi Penetapan Waktu Pengambilan Cuplikan Dan Asumsi Model KompartemenDokumen21 halamanLaporan Resmi Penetapan Waktu Pengambilan Cuplikan Dan Asumsi Model KompartemenRiski WahyuniBelum ada peringkat
- Laporan Penetapan Parameter Farmakokinetika Obat Setelah Pemberian Dosis Tungg FixDokumen18 halamanLaporan Penetapan Parameter Farmakokinetika Obat Setelah Pemberian Dosis Tungg FixMAUDYBelum ada peringkat
- Fisiologi Dan Patologi LengkapDokumen65 halamanFisiologi Dan Patologi LengkapJihan Azhar KresnawahyuesaBelum ada peringkat
- CDK 165 NeurologiDokumen57 halamanCDK 165 Neurologirevliee100% (2)
- Penetapan Waktu Pengambilan Cuplikan Dan Asumsi Model Kompartemen Dan Penetapan Parameter Farmakokinetika Obat Setelah Pemberian Dosis Tunggal Menggunakan Data Darah KelinciDokumen26 halamanPenetapan Waktu Pengambilan Cuplikan Dan Asumsi Model Kompartemen Dan Penetapan Parameter Farmakokinetika Obat Setelah Pemberian Dosis Tunggal Menggunakan Data Darah KelinciMAUDY100% (1)
- Profil Dan Model FarmakokinetikDokumen32 halamanProfil Dan Model Farmakokinetikrizqia nafisaBelum ada peringkat
- Tugas FarmakokinetikDokumen8 halamanTugas FarmakokinetikArmydha Iga100% (1)
- Laprak Kel.3B IV 2 Kompartemen TerbukaDokumen23 halamanLaprak Kel.3B IV 2 Kompartemen Terbukasaila salsabilaBelum ada peringkat
- Laporan Biofar IVDokumen26 halamanLaporan Biofar IVsangayu100% (1)
- Farmakokinetik Bab 1Dokumen17 halamanFarmakokinetik Bab 1RiskiahNurfathin100% (2)
- p2&3 Penetapan Waktu Pengambilan Cuplikan Biofar Kel 1Dokumen50 halamanp2&3 Penetapan Waktu Pengambilan Cuplikan Biofar Kel 1Rosamaria Yuni Utami88% (8)
- Pengantar FarmakokinetikaDokumen28 halamanPengantar FarmakokinetikapintataBelum ada peringkat
- MAKALAH Tugas Bu SulinaDokumen14 halamanMAKALAH Tugas Bu SulinaSeptyana KumalasariBelum ada peringkat
- Makalah Praktikum Biofarmasetika P.2Dokumen51 halamanMakalah Praktikum Biofarmasetika P.2Lina LinuxBelum ada peringkat
- Latar Belakang Laporan Farkindas1Dokumen4 halamanLatar Belakang Laporan Farkindas1FirohBelum ada peringkat
- Laprak FARKINDAS PDokumen21 halamanLaprak FARKINDAS PAl MaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Vii Simulasi 2 Kompartemen Kel.5bDokumen24 halamanLaporan Praktikum Vii Simulasi 2 Kompartemen Kel.5bnana29100% (1)
- E0018080 - Nur Wulan Septiyani - Laporan Resmi P2P3Dokumen36 halamanE0018080 - Nur Wulan Septiyani - Laporan Resmi P2P3Nur Wulan SeptiyaniBelum ada peringkat
- 3a - Fiji Indah Gunawan - E0018016Dokumen36 halaman3a - Fiji Indah Gunawan - E0018016Fiji IndahBelum ada peringkat
- Farmakokinetika Sed IntravenaDokumen32 halamanFarmakokinetika Sed IntravenaVitananda Tiara MaharaniBelum ada peringkat
- Laprak BFFK Rute IV Model Kompartemen 2 TerbukaDokumen25 halamanLaprak BFFK Rute IV Model Kompartemen 2 TerbukaGHINA KHALIDAH MHS 2017Belum ada peringkat
- Laporan Akhir Biofar p1Dokumen18 halamanLaporan Akhir Biofar p1Ayue adnyaniBelum ada peringkat
- C Fadliah Ramadhan O1a1 18172Dokumen34 halamanC Fadliah Ramadhan O1a1 18172Fadliah RamadhanBelum ada peringkat
- Farmakokinetik UTADokumen30 halamanFarmakokinetik UTAFatimah AsrianiBelum ada peringkat
- Laprak 1 Biofar I.V TerbukaDokumen25 halamanLaprak 1 Biofar I.V TerbukaYudha PramestichaBelum ada peringkat
- A4B - Maria Nindyahni GagoDokumen27 halamanA4B - Maria Nindyahni GagoNur WahyuniBelum ada peringkat
- Model FarmakokinetikaDokumen39 halamanModel FarmakokinetikaMahmud YumassikBelum ada peringkat
- Farmakokinetik 3 2Dokumen38 halamanFarmakokinetik 3 2Reffany Dyah SeptatiwiBelum ada peringkat
- Laporan Resmi Praktikum P1Dokumen43 halamanLaporan Resmi Praktikum P1vanda rinaBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Prak. Biofarmasi FIXS NGKDokumen27 halamanLaporan Akhir Prak. Biofarmasi FIXS NGKNgakanBelum ada peringkat
- Finnis Laporan Urine Kel 2Dokumen22 halamanFinnis Laporan Urine Kel 2Maila KhaririBelum ada peringkat
- Laporan Farkin Kompartemen 1Dokumen13 halamanLaporan Farkin Kompartemen 1Vevy AjaaBelum ada peringkat
- Jurnal Awal IV Dan EV K1 TerbukaDokumen16 halamanJurnal Awal IV Dan EV K1 TerbukaNurul FebrianiBelum ada peringkat
- 2.model KompartemenDokumen33 halaman2.model KompartemenRhevi RhianBelum ada peringkat
- Farmakokinetika DasarDokumen19 halamanFarmakokinetika Dasarwinda angraeniBelum ada peringkat
- Tugas Farmakokinetika 1Dokumen6 halamanTugas Farmakokinetika 1Afner OtnielBelum ada peringkat
- Pertemuan 2FKDokumen24 halamanPertemuan 2FKIndah UiBelum ada peringkat
- KinetikDokumen3 halamanKinetikSuna septiani AndiniBelum ada peringkat
- FARKIN Sebelum Uts IikDokumen125 halamanFARKIN Sebelum Uts IikelindanungkyBelum ada peringkat
- F.kin 1Dokumen15 halamanF.kin 1AvrianisTambunanBelum ada peringkat
- 55 Farmakokinetik FINALDokumen12 halaman55 Farmakokinetik FINALsalsabilakeyssa342Belum ada peringkat
- Laprak BFFK Kel.2ADokumen41 halamanLaprak BFFK Kel.2ASelvianaBelum ada peringkat
- Makalah - Farmakokinetik Kelompok Ii Kelas D 2018Dokumen17 halamanMakalah - Farmakokinetik Kelompok Ii Kelas D 2018DewiBelum ada peringkat
- Praktikum BiofarmasetikaDokumen4 halamanPraktikum BiofarmasetikasantiparamitaBelum ada peringkat
- Laprak BiofarmasetikaDokumen16 halamanLaprak BiofarmasetikaWanda AprilliaBelum ada peringkat
- Makalah Praktikum FarmakokinetikDokumen28 halamanMakalah Praktikum FarmakokinetikZahra MarseliBelum ada peringkat
- Elfrida Hazna P.M - 10117048 - Laporan Resmi Data UrinDokumen28 halamanElfrida Hazna P.M - 10117048 - Laporan Resmi Data Urinmohamad azisBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum BFFK KelinciDokumen17 halamanLaporan Praktikum BFFK KelinciAuliyani Rosdiana KhoirunisaBelum ada peringkat
- 1 PETUNJUK PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA DAN FARMAKOKINETIK 2019-2020-Bikin 60 PDFDokumen38 halaman1 PETUNJUK PRAKTIKUM BIOFARMASETIKA DAN FARMAKOKINETIK 2019-2020-Bikin 60 PDFagus sudarwantoBelum ada peringkat
- Model FarmakokinetikaDokumen14 halamanModel FarmakokinetikaRika RositaBelum ada peringkat
- Farkin DikitDokumen9 halamanFarkin DikitLee ViaBelum ada peringkat
- Dasar TeoriDokumen6 halamanDasar Teorisoft winteryBelum ada peringkat
- Tugas FarmakokinetikaDokumen13 halamanTugas FarmakokinetikaDesak MothyBelum ada peringkat
- CDK 166 AsmaDokumen36 halamanCDK 166 AsmarevlieeBelum ada peringkat
- CDK 168 GiziDokumen69 halamanCDK 168 Gizirevliee100% (2)
- CDK 169 KardiovaskulerDokumen61 halamanCDK 169 Kardiovaskulerrevliee100% (1)
- CDK 160 ObgynDokumen57 halamanCDK 160 ObgynrevlieeBelum ada peringkat
- 170 / Vol. 36 No. 4 JuliDokumen57 halaman170 / Vol. 36 No. 4 Julirevliee100% (1)
- CDK 163 ThtrevDokumen57 halamanCDK 163 Thtrevrevliee100% (1)
- CDK 152 KesehatanwisatarevDokumen65 halamanCDK 152 KesehatanwisatarevrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 158 KebidananDokumen57 halamanCDK 158 Kebidananrevliee100% (2)
- CDK 161 StemcellDokumen57 halamanCDK 161 StemcellrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 159 ObesitasDokumen57 halamanCDK 159 ObesitasrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 157 NeurologiDokumen57 halamanCDK 157 Neurologishinta_dwijayantiBelum ada peringkat
- CDK 145 ObsginDokumen65 halamanCDK 145 ObsginrevlieeBelum ada peringkat
- Cermin Dunia KedokteranDokumen65 halamanCermin Dunia KedokteranIrwan Taufiqur RachmanBelum ada peringkat
- CDK 156 DepresiDokumen57 halamanCDK 156 DepresiBiront Lex NealzBelum ada peringkat
- Cermin Dunia KedokteranDokumen57 halamanCermin Dunia KedokteranAjeng MardhiyahBelum ada peringkat
- CDK 153 StemcellDokumen53 halamanCDK 153 Stemcellrevliee100% (1)
- CDK 149 Kesehatan JiwaDokumen68 halamanCDK 149 Kesehatan JiwarevlieeBelum ada peringkat
- CDK 147 KardiologiDokumen65 halamanCDK 147 Kardiologirevliee100% (1)
- CDK 150 Masalah HatiDokumen69 halamanCDK 150 Masalah HatirevlieeBelum ada peringkat
- CDK 142 AlergiDokumen65 halamanCDK 142 AlergirevlieeBelum ada peringkat
- Kumpulan Jurnal TBCDokumen58 halamanKumpulan Jurnal TBCtiovenra100% (3)
- CDK 141 AsmaDokumen61 halamanCDK 141 Asmarevliee100% (1)
- Masalah KesehatanDokumen57 halamanMasalah KesehatanDian AyuningtyasBelum ada peringkat
- NapzaDokumen58 halamanNapzadhany134Belum ada peringkat
- CDK 139 Kebidanan Dan Penyakit KandunganDokumen57 halamanCDK 139 Kebidanan Dan Penyakit KandunganrevlieeBelum ada peringkat
- CDK 131 MalariaDokumen65 halamanCDK 131 MalariarevlieeBelum ada peringkat
- Kesehatan KerjaDokumen59 halamanKesehatan KerjawahyudhanapermanaBelum ada peringkat
- CDK 133 Obstetri Dan GinekologiDokumen64 halamanCDK 133 Obstetri Dan GinekologiErika Kusumawati100% (1)