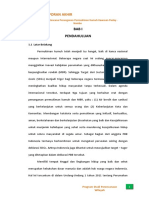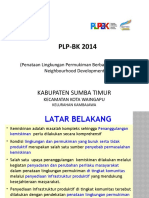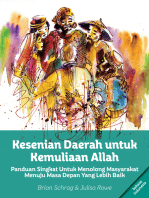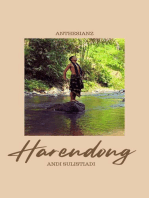Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh RTPKPK
Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh RTPKPK
Diunggah oleh
Mohammad YanuarJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh RTPKPK
Rencana Tindak Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh RTPKPK
Diunggah oleh
Mohammad YanuarHak Cipta:
Format Tersedia
KERANGKA ACUAN KERJA
A.
LATAR BELAKANG
Permukiman kumuh, baik kumuh perkotaan maupun kumuh kumuh merupakan permasalahan
krusial bagi fungsi kota atau wilayah karena menjadi hambatan bagi efektivitas perekonomian dan
aktivitas habitatnya. Pada dasarnya upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh telah
berlangsung sejak lama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Beberapa upya peningkatan
kualitas lingkungan melalui peningkatan infrastruktur permukiman adalah Program Kampung
Improvement Program (KIP), KIP Komprehensif, Program Penanganan Lingkungan Permukiman
Kumuh (P2LPK), Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), Program Peningkatan
Kualitas Lingkungan (PKL), Program Penanganan Kawasan Kumuh melalui Urban Renuawal.
Pemberdayaan yang melibatkan masyarakat mulai dari tahap identifikasi hingga implementasi
dimaksudkan memberikan peluang untuk mandiri dan bermitra dengan pelaku pembangunan lainnya.
Pergeseran pendekatan untuk masyarakat kepada membangun bersama masyarakat secara
perlahan mulai diterapkan dalam berbagai program penanganan permukiman kumuh yang ada.
Keterlibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam program-program diatas adalah
upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara terintegrasi. Strategi dan skenario pengembangan
kawasan kumuh perlu diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan kota/wilayah. Dibidang
prasarana dan sarana perumahan dan permukiman ditekankan pada kawasan kumuh perkotaan dan
kawasan permukiman kumuh dan atau kawasan permukiman baru (wilayah pengembangan).
Permukiman kumuh ini pada umumnya memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat berat
baik dari aspek fisik maupun aspek non fisik, sehingga telah menimbulkan suatu image bahwa
kawasan permukiman kumuh identik dengan sebuah kawasan permukiman kumuh dan kotor. Hal ini
dapat dilihat dari permasalahan yang dihadapi di kawasan tersebut yiatu sebagai berikut :
1. Permasalahan fisik : rendahnya aksesibilitas terhadap kepemilikan lahan dan hunian. 40% dari
kumuh menempati lahan illegal atau mengadakan penimbunan dengan sengaja pada daerah
perairan tertentu di pesisir atau daerah badan sungai. Rendahnya kualitas lingkungan terlihat dari
kekumuhan bangunan dan lingkungan. Kekumuhan lingkungan fisik kawasan permukiman kumuh
dapat dihubungkan dengan jenis pekerjaan. Kawasan yang buruk menyebabkan kualitas
lingkungan tidak menunjukkan lingkungan yang sehat dan kering. Sifat air yang mengalir
menyebabkan pada penghuni memanfaatkannya sebagai saran pembuangan air kotor dan
sampah.
2. Permasalahan Non Fisik : Kawasan hunian kumuh seringkali diidentikkan dengan kemiskinan dan
kekumuhan. Status tinggal kumuh sifatnya mobile atau mereka selalu berpindah dari satu tempat
ke tempat lain dengan tanpa memiliki identitas yang formal. Sebagian besar dari penghuni
kawasan permukiman kumuh adalah pendatang. Komunitas kumuh home industri membutuhkan
tempat pembuangan limbah yang dapat dijangkau dengan mudah. Sebagai konsekuensi tempat
pembukaan sampah menjadi relatif dekat dengan hunian dan menimbulkan pencemaran sampah
dan bau. Beberapa peraturan penataan ruang yang sudah disusun terkait dengan permukiman
yang layak huni dan sehat belum sepenuhnya diterapkan sehingga kebiasaan dan budaya
masyarakat kumuh lambat untuk berubah menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya.
Jika di lihat dari permasalahan tersebut diatas, kawasan permukiman kumuh kumuh perlu segera
mendapat perhatian utama untuk segera ditangani, namun pada umumnya terbentur oleh rendahnya
KERANGKA ACUAN KERJA
daya kemampuan masyarakat untuk memperbaiki kondisi lingkungan mereka yang disebabkan oleh
tingkat pendapatan masih di bawah standart kehidupan. Disisi lain permasalahan permukiman kumuh
kumuh juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu perlu
dilakukannya penyusunan Rencana Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Kumuh di
Perkotaan dengan maksud agar terjadi peningkatan berbagai macam aspek kehidupan baik itu fisik,
ekonomi maupun lingkungan di kawasan permukiman kumuh.
Meningkatnya kualitas lingkungan pada umumnya terjadi seiring dengan peningkatan
kemampuan ekonomi penghuninya. Untuk itu diperlukan kondisi lingkungan permukiman yang
responsif, yang mampu mendukung pengembangan jatidiri, produktifitas dan kemandirian masyarakat
penghuninya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas
kelembagaan pengelolaan penanganan permukiman kumuh, baik unsur pemerintahan lokal
masyarakat maupun lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga yang bergerak di bidang ini.
Untuk mendukung itu, perlu pula dilakukan kegiatan peningkatan pembangunan/rehabilitasi prasarana
dan sarana dasar lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan sosial-ekonomi di lingkungan
permukiman kumuh tersebut.
Agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu memperhatikan;
1. Ketersediaan kebijakan di daerah : Pemerintah Kota/Kabupaten diharapkan mempunyai dan
menunjukkan komitmen politis untuk memberikan perhatian terhadap keberadaan dan penanganan
masalah kumuh, antara lain dengan cara : menyusun kebijakan penanganan lingkungan kumuh
sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan kota/kabupaten. Ikut memfasilitasi
upayaupaya peningkatan kualitas lingkungan. Bila perlu melakukan evaluasi dan review terhadap
rencana tata ruang.
2. Ketersediaan pembiayaan sektor prasarana dan sarana : Ketersediaan dan komitmen pemerintah
kota/kabupaten untuk dapat mengalokasikan sharing dana dari APBD untuk mengisi program
penanganan lingkungan kumuh yang antara lain : Kegiatan-kegiatan yang tertera dalam Rencana
Tindak Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Kumuh, yang tercantum dalam rencana
pengembangan sektor perumahan dalam kerangka pembangunan daerah, yang tertera dalam
alokasi penanggulangan kemiskinan. Alokasi yang dapat digunakan untuk membantu perbaikan
sarana dan prasarana lingkungan permukiman, penyediaan lahan yang terjangkau untuk
masyarakat miskin, bahkan untuk menstimulasi pembangunan perumahan yang dilakukan secara
swadaya oleh masyarakat.
B.
LANDASAN HUKUM
Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan dalam kegiatan ini adalah :
1. UU No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman;
2. UU No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. UU No. 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana;
7. UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
8. UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah;
9. UU No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. PP No. 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah;
12. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaI No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun Dan
Lingkungan Siap Bangun;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
KERANGKA ACUAN KERJA
15. Inpres Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh yang Berada di atas Tanah
Negara;
16. Keppres No. 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional;
17. Keppres No. 32/1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
18. Keppres No. 75/1993, tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
19. Keppres No. 37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N);
20. Keppres No. 63/2000, tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan
Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N);
21. KepMen KIMPRASWIL No.217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional
Perumahan dan Permukiman;
22. Permendagri No. 1/1987, tentang Penyerahan prasarana lingkungan utilitas umum, dan fasilitas
sosial kepada Pemda;
23. Rencana operasi Peningkatan Kualitas Lingkungan, Perumahan Swadaya, Kasiba/Lisiba BS,
Penyediaan RS bersubsidi, Rusunawa dalam mendukung pengembangan satu juta rumah;
24. Rencana strategis (renstra) pengembangan perumahan dan permukiman;
25. Petunjuk operasional proyek pengembangan perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Tengah.
26. Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perkotaan.
C.
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
1. MAKSUD
Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh Kumuh
adalah :
a. Masukan rencana dan program pembangunan fisik bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam penanganan Permukiman Kumuh Kumuh.
b. Masukan teknis bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk rincian
penyelenggaraan, pengelolaan dan pemeliharaan dalam upaya penataan dan peningkatan
kualitas lingkungan permukiman kumuh kumuh dan pemberdayaan komunitas perumahan
terutama dalam penanganan kawasan kumuh.
c. Masukan teknis bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengarahkan
peran serta seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, swasta, masyarakat lokal, investor) dalam
mewujudkan lingkungan yang dikehendaki.
2. TUJUAN
Tujuan disusunya
Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh Kumuh adalah
memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh
serta sebagai acuan dalam pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan kawasan
Permukiman (fisik dan non fisik) di daerah perencanaan.
3. SASARAN
Sasaran kegiatan Rencana Tindak Penanganan Permukiman Kumuh Kumuh adalah:
a. Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kawasan dann wilayah sekitarnya.
b. Tersusunnya rencana program pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh kumuh.
c. Tersedianya arahan/ acuan untuk pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan
permukiman kumuh kumuh di Perkotaan.
d. Tersusunnya rencana teknis dalam bentuk rincian kegiatan, sumber dana, pengelolaan/
pengendalian penanganan permukiman kumuh kumuh.
3
KERANGKA ACUAN KERJA
e. Tersusunnya Rencana Tindak Penanganan Kawasan Kumuh kumuh, terutama pada wilayah/
kawasan yang benar-benar segera perlu di tangani.
f.
Tersusunnya master plan penanganan permukiman kumuh kumuh.
g. Terwujudnya Rencana Program Menengah Pembangunan (RPJM) dan atau Rencana Program
Investasi Jangka Menengah Pembangunan (RPIJM) Infrastruktur ke-Cipta Karya-an pada
kawasan permukiman kumuh.
h. Tersusunnya Detail Engineering Desain (DED) untuk tahun pertama pada lokasi/kawasan
prioritas.
D.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
1. RUANG LINGKUP WILAYAH
Ruang lingkup lokasi pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Tindak Penanganan
Lingkungan Permukiman Kumuh Kumuh ini berada di Perkotaan. Lokasi akan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari stakeholder terkait, lokasi perencanaan bisa
lebih dari 1 (satu) kawasan permukiman dan atau dengan luas area 50 Ha.
2. RUANG LINGKUP KEGIATAN
a. Mengidentifikasi lokasi kawasan permukiman kumuh kumuh di Perkotaan sesuai lokasi yang
disepakati/ ditetapkan.
b. Mengidentifikasi potensi, permasalahan
permukiman kumuh di Perkotaan.
c.
dan
kendala
pengembangan
kawasan
kumuh
Mengkaji kebijakan-kebijakan dalam hal penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh baik di
tingkat Kabupaten/kota maupun Provinsi.
d. Menganalisis penanganan
komprehensif.
kawasan
permukiman
kumuh
kumuh
di
Perkotaan
secara
e. Melakukan penjaringan aspirasi masyarakat setempat melalui forum rembug warga masyarakat
setempat atau FGD (Forum Group Discussion).
f.
Menyusun serta merumuskan konsep rencana penanganan kawasan permukiman kumuh kumuh
berdasarkan hasil FGD maupun analisis.
g. Menyusun serta mendesain lokasi prioritas penanganan baik dalam bentuk site plan maupun
gambar perencanaannya serta masterplannya.
h. Menyusun perencanaan teknis (DED) lokasi prioritas pertama yang akan di tangani pada tahun
pertama atas dasar kesepakatan bersama antara tim teknis, masyarakat dan Pemda setempat.
i.
Menyiapkan serta menyusun dokumen lelang (RKS, Gambar Kerja, RAB) lokasi prioritas I yang
akan di tangani pada tahun pertama.
j.
Menyelenggarakan konsultasi teknis, sosialisasi kegiatan, pembahasan konsep penanganan, dan
workshop.
E.
SUBTANSI MATERI
Ruang lingkup substansi pada pekerjaan ini, secara materi masih mengacu kepada konsepkonsep peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, serta peningkatan prasarana
dan sarana dasar perumahan dan permukiman, yaitu :
1. PENERAPAN KONSEP TRIDAYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERMUKIMAN
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang (UU) nomor 22/99 dan Undang-Undang (UU)
nomor 25/99 yang disertai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 25/2000, penyelenggaraan
pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan selaras dengan semangat tersebut (seperti
tertuang dalam KSNPP Keputusan Menkimpraswil Nomor 217/KPTS/M/2002 tanggal 13 Mei 2002).
KERANGKA ACUAN KERJA
Bagian terpenting dalam strategi nasional tersebut adalah mengembangkan infrastruktur
pembangunan perumahan dan permukiman, yang dalam hal ini diarahkan pada pembentukan
kelembagaan pembiayaan pembangunan perumahan dan permukiman.
Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran
dan partisipasi penuh dari para pihak, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat
sebagai sumber daya pembangunan, agar :
1. Mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong diri dan
keluarganya menuju keadaan yang lebih baik (mampu menumbuhkan kesadaran kritis
masyarakat).
2. Mampu mengenali menggali dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk kepentingan
diri dan kelompoknya.
3. Mampu mengeksistensikan diri dan kehendaknya secara jelas dan mendapatkan memanfaat dari
padanya.
Sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat mensyaratkan prakondisi untuk dapat
dijalankan dengan baik, antara lain :
1. Proses pertama adalah meningkatnya kesejahteraan, walaupun secara semu masyarakat merasa
nyaman dengan kondisi kesehariannya. Upaya untuk mensejahterakan ini dapat ditempuh
antara lain melalui:
a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar.
b. Kesempatan untuk mengeksistensikan diri dan aspirasi atau harapannya secara nyata,
c. Diberikan dukungan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi.
Pada proses ini masyarakat perlu dibuat merasa sejahtera walaupun ketergantungannya kepada
pemberi bantuan/dukungan masih sangat besar. Proses awal dalam masa transisi ini
menumbuhkan trust (kepercayaan) dan ikatan yang lebih kuat.
2. Proses kedua adalah membukakan akses kepada sumber daya yang berada di luar
komunitasnya, sebagai jalan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Pemerintah atau
berbagai pihak dapat membantu membukakan akses ini melalui:
a. Bantuan untuk menyusun dan menuangkan aspirasi masing-masing ke dalam suatu bentuk
tertentu (Community Action Plan/CAP atau apapun namanya).
b. Pengenalan sumber daya kunci yang berada di luar komunitasnya dan bagaimana tata cara
untuk menjangkaunya.
c. Memperkuat kelembagaan pada tingkat komunitas yang merupakan
merepresentasikan keberadaan kelompok ini keluar komunitasnya.
atau
dapat
d. Memperkuat peran dan fungsi kelembagaan pada tingkatan komunitas yang dapat
menjembatani kepentingan warga dengan sumber daya kunci luar. Bentuknya dapat berupa
pelatihan, pemberian modal awal yang bersifat guliran sehingga bankable.
3. Proses ketiga adalah mengupayakan agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui
informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dilakukan
dengan upaya pendampingan, dengan indikasi keberhasilan :
a. Mulai mempertanyakan posisi tawar diri dan kelompoknya dalam setiap kesempatan yang
dibukakan (tawaran terlibat dalam program pembangunan, tawaran untuk mendapatkan
intervensi dari luar dll)
b. Mempertanyakan dasar hukum serta status intervensi dari luar (ingin berperan bukan sekedar
berperan serta).
c. Menggeser kontribusi kelompok menjadi modal kelompok dengan menempatkan intervensi
dari luar sebagai modal tambahan yang diperlukan dan akan dimanfaatkan sesuai dengan
persepsi dan aspirasi.
4. Proses keempat dan merupakan bagian akhir dari proses pemberdayaan ini adalah upaya untuk
menumbuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan, yang ditempuh antara lain melalui:
KERANGKA ACUAN KERJA
a. Pemberian dan pengalih peran lebih besar secara bertahap sesuai dengan peningkatan
kapasitas dan kapabilitasnya.
b. Lebih banyak didengar dan diakomodasikan aspirasinya.
c. Diajak menilai/melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.
Konsep Tridaya merupakan konsep pengembangan kawasan yang memadukan unsur
manusia sebagai pelaku, unsur usaha sebagai bentuk dari aktivitas pelaku, dan lingkungan sebagai
ruang aktivitas. Konsep ini merupakan salah satu konsep pembangunan berwawasan lingkungan
yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep TRIDAYA
(pemberdayaan manusia, usaha, dan lingkungan) terstruktur dalam 3 (tiga) upaya pengembangan
yang meliputi perencanaan sosial, ekonomi, dan fisik sebagai berikut:
1. Perencanaan Sosial
Berorientasi dan bermotivasi kepada segi-segi kehidupan masyarakat. Produk perencanaan
sosial ini merupakan arahan dan pedoman pengembangan kependudukan, dan kelembagaan.
Misalnya dengan peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan
maupun lembaga sosial yang ada. Kualitas SDM dapat ditingkatkan dengan berbagai penyuluhan
dan pelatihan ketrampilan kerja.
2. Perencanaan Ekonomi
Berorientasi dan bermotivasi kepada pengembangan perekonomian, dimana produk perencanaan
ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan, lapangan
kerja, distribusi konsumsi, dan pengembangan perangkutan dan perhubungan. Perencanaan
ekonomi ini diwujudkan dengan peningkatan aktivitas produksi dan pengembangan aktivitas
industri pengolahan. Pelaksanaan peningkatan aktivitas produksi dan industri ini dilakukan oleh
masyarakat sendiri sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Peningkatan tersebut diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Perencanaan Fisik
Merupakan segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik.
Perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka
menjabarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.. Perencanaan fisik diiwujudkan dengan
perbaikan kondisi sarana dan prasarana persampahan di lingkungan permukiman sesuai standar
kelayakan huni, pengadaan sarana prasarana persampahan. Perencanaan fisik juga diharapkan
dapat meningkatkan standar kualitas hidup masyarakat.
Konsep Tridaya yang terdiri dari Bina Manusia, Bina Ekonomi atau Usaha dan Bina Lingkungan
dipandang saat ini mampu menjadi komponen yang efektif untuk menggerakan proses
pemberdayaan.
a. Aspek Bina Manusia
1) Memberikan dorongan percaya diri untuk dapat berkembang dan masyarakat mempunyai
arti penting dalam pembangunan yang akan dan sedang dilakukan.
2) Pembangunan sumber daya manusia melalui jenis kegiatan yang dapat dikembangkan
secara sosial ekonomi.
3) Masyarakat akan menyadari bahwa untuk dapat membangun bukan hanya menunggu
bantuan akan tetapi bagaimana menciptakan bantuan dan sekaligus berpartisipasi
didalamnya.
b. Aspek Bina Lingkungan
1) Pengembangan sumber daya yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi
lingkungan baik keluarga maupun masyarakat.
2) Hasil yang dicapai dapat memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan.
3) Kegiatan yang dilakukan dapat menciptakan suatu bentuk lingkungan sosial dan ekonomi
yang lebih baik.
c. Aspek Bina Usaha
1) Kegiatan dapat memberikan dampak secara ekonomi bagi individu masyarakat, keluarga
maupun masyarakat secara luas.
6
KERANGKA ACUAN KERJA
2) Kegiatan yang dilakukan dapat berfungsi sebagai income generating.
3) Kegiatan yang dilakukan dapat menjadi embrio bagi penciptaan lapangan kerja baru.
Aplikasi Tridaya telah distrukturkan dalam indikasi program pengembangan dalam 3 (tiga)
dimensi pengembangan yaitu dimensi manusia (sosial dan budaya), ekonomi dan fisik lingkungan.
Sesuai dengan harapan dari kerangka acuan kerja dalam hal pengelolaan atau pengkoordinasian
stakeholders yang terlibat maka perlu disusun suatu bentuk kelembagaan yang mampu
mengakomodasi pengembangan ketiga dimensi tersebut. Kelembagaan ini yang juga akan menjadi
wadah partsipasi dan kemitraan, yang secara khusus akan menyatukannya melalui institusi
pengembangan bertumpu pada kelompok masyarakat/komunitas.
Dimensi parsial
yang menjadi
dasar dari
pembentukan
kinerja TRIDAYA
(sosial, ekonomi
dan fisik
lingkungan)
Pengembangan
Fisik / Lingk.
Pengembangan
Kelembagaan
Pengembangan
Ekonomi
Integrasi antar
dimensi melalui
kerangka
kelembagaan :
communitybasedinstitutional
development
Pengembangan
Sosial
Kerangka TRIDAYA
Gambar
Kerangka Tridaya
2. KRITERIA TEKNIS KOMPONEN PROGRAM
Kriteria Teknis Komponen Program ini disusun berdasarkan acuan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan
Sederhana Tidak Bersusun, dimana kriteria prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang ada
ditentukan sebagai berikut :
a. Jalan lingkungan, merupakan jalan yang melayani semua rumah di dalam jarak maksimum 100 m
dari salah satu arah, 300 m dari jarak jalan dua arah.
b. Jalan setapak, adalah jalan untuk orang berjalan, yang melayani semua rumah dalam jarak 20 m
dari jalan setapak.
c.
Saluran: (0,3 m 0,5 m), di dalam merancang saluran air hujan dan air limbah kotor rumah
tangga hendaknya memperhatikan daya tampung saluran untuk menempatkan ukuran saluran.
d. Air bersih : hidran umum/kran umum 3 10 unit setiap kampung.
e. Tempat Penampungan Sampah (TPS): fasilitas penampungan 6 m3/2 ha jarak dari tempat tinggal
terdekat 50 s/d 100 m diangkat 2 kali/minggu.
f.
Tempat kegiatan usaha, misal toko, kios dll
g. Mandi, cuci dan kakus (MCK) umum, lokasi MCK hendaknya dipilih lokasi mudah dijangkau,
terdapat sumber air, 3 s/d 4 unit MCK setiap kampung.
h. Fasilitas Ruang Terbuka (Open Space) sebagai ruang publik dan ruang sosial, dimana sebagai
wadah untuk aktifitas sehari-hari masyarakat setempat, juga memiliki makna sosial maupun
kultural. Kondisi inilah yang dibahas secara lebih detail, berkaitan dengan keberadaan ruang luar
sebagai salah satu fasilitas yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat kumuh.
Anda mungkin juga menyukai
- RP2KPKPDokumen64 halamanRP2KPKPFathurrahman Burhanuddin100% (1)
- Bab 1Dokumen6 halamanBab 1Ashari S.Pd.IBelum ada peringkat
- RPKPKPDokumen12 halamanRPKPKPjuniusBelum ada peringkat
- Materi 2 KLPP IkmDokumen30 halamanMateri 2 KLPP IkmChloe LiliesBelum ada peringkat
- KAK RP2KPKPK Labusel RevisiDokumen14 halamanKAK RP2KPKPK Labusel RevisiallfizapBelum ada peringkat
- RPLP Cimuncang BAB IDokumen5 halamanRPLP Cimuncang BAB IUrban Planner Serang-CilegonBelum ada peringkat
- Panduan Plp2kbk - Kumuh KotaDokumen36 halamanPanduan Plp2kbk - Kumuh Kotabeta paramitaBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen11 halamanBab I PendahuluanIkal M YasinBelum ada peringkat
- Bab IDokumen11 halamanBab ILa IbalBelum ada peringkat
- KAK RKP Kumuh FinalDokumen17 halamanKAK RKP Kumuh FinalTorpin KibaidBelum ada peringkat
- Proposal Renovasi TPS Desa KalirejoDokumen8 halamanProposal Renovasi TPS Desa KalirejoPratama AdityaBelum ada peringkat
- Laporan Community Action Plan Desa Bagendit Kec Banyuresmi Kab Garut PDFDokumen57 halamanLaporan Community Action Plan Desa Bagendit Kec Banyuresmi Kab Garut PDFA Hendy Sopyandi100% (4)
- UAS Pengolahan Limbah Oleh Yosua Manaek P. S 13114704Dokumen5 halamanUAS Pengolahan Limbah Oleh Yosua Manaek P. S 13114704JossuaSiagian100% (1)
- RPLPDokumen9 halamanRPLPFachmi RamadhaniBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Meranti PandakDokumen30 halamanLaporan Pendahuluan Meranti PandakidzulBelum ada peringkat
- Kak Identifikasi Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh Bone, Soppeng, Wajo, SinjaiDokumen11 halamanKak Identifikasi Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh Bone, Soppeng, Wajo, SinjaiIlham YahyaBelum ada peringkat
- Laporan RP2KPKPK BAB 1Dokumen11 halamanLaporan RP2KPKPK BAB 1ayu asariBelum ada peringkat
- Jawaban KumuhDokumen2 halamanJawaban KumuhSyahrul LatiefBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa IndonesiaDokumen7 halamanMakalah Bahasa IndonesiaGAPEKNAS LAMPUNGBelum ada peringkat
- Rp2kpkp Kab. BantaengDokumen113 halamanRp2kpkp Kab. Bantaengrahmat salehBelum ada peringkat
- Kak Master Plan Kawasan KumuhDokumen20 halamanKak Master Plan Kawasan KumuhMuhammad Salmy75% (4)
- E. Pendekatan Dan MetodologiDokumen41 halamanE. Pendekatan Dan Metodologidadan daramansyahBelum ada peringkat
- Pendahuluan - RPLP RevDokumen3 halamanPendahuluan - RPLP RevFachmi RamadhaniBelum ada peringkat
- Bab 1 PendahuluanDokumen4 halamanBab 1 PendahuluanDiana EvelinaBelum ada peringkat
- Identifikasi Pemukiman Kumuh Dan Strategi Penangananya Pada Pemukiman Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota PalopoDokumen34 halamanIdentifikasi Pemukiman Kumuh Dan Strategi Penangananya Pada Pemukiman Di Kelurahan Pontap Kecamatan Wara Timur Kota Paloporio simanjuntakBelum ada peringkat
- rp2kp-kp Kabupaten Bantaeng PDFDokumen115 halamanrp2kp-kp Kabupaten Bantaeng PDFHerdy Pratama PutraBelum ada peringkat
- Bab 1 Kel Alam JayaDokumen14 halamanBab 1 Kel Alam JayaEkky MuammarBelum ada peringkat
- Substansi Penyusunan RP2KPKPKDokumen61 halamanSubstansi Penyusunan RP2KPKPKNuraeni Dg KanangBelum ada peringkat
- Pedoman Teknis Program Kota Tanpa KumuhDokumen70 halamanPedoman Teknis Program Kota Tanpa KumuhSaiful AminBelum ada peringkat
- Bab 1 Pendahuluan - RPLPDokumen3 halamanBab 1 Pendahuluan - RPLPFachmi RamadhaniBelum ada peringkat
- Masalah Tata Guna LahanDokumen2 halamanMasalah Tata Guna LahanFatma Rana WallaBelum ada peringkat
- KAK Dan BOQ RKP PolmanDokumen20 halamanKAK Dan BOQ RKP PolmanHidayat M NurBelum ada peringkat
- Kotaku PDFDokumen10 halamanKotaku PDFeman sulaemanBelum ada peringkat
- Kak-Rp2kpkpk Kab Morowali - 2Dokumen19 halamanKak-Rp2kpkpk Kab Morowali - 2Nahruddin MaiBelum ada peringkat
- 08 JuknisDokumen259 halaman08 JuknisriswandiBelum ada peringkat
- Asis 1 Kelompok Slum Area KalibuntuDokumen24 halamanAsis 1 Kelompok Slum Area KalibuntuLazirizalBelum ada peringkat
- Dokumen PentingDokumen135 halamanDokumen Pentingakbari tumadaBelum ada peringkat
- 1 Bahan 3Dokumen6 halaman1 Bahan 3NardiiBelum ada peringkat
- Minggu 2 Permukiman KumuhDokumen40 halamanMinggu 2 Permukiman Kumuhmarselly dwiputriBelum ada peringkat
- 4.KAK Kota Tuo PDFDokumen7 halaman4.KAK Kota Tuo PDFAndrew Halim RamadanBelum ada peringkat
- 04-Juknis SanimasDokumen164 halaman04-Juknis SanimasGayus Purba100% (1)
- Pedoman 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis Masyarakat Di Kawasan PermukimanDokumen163 halamanPedoman 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Berbasis Masyarakat Di Kawasan PermukimanOswar Mungkasa100% (5)
- Buku Panduan PLP2K-BKDokumen45 halamanBuku Panduan PLP2K-BKbabi bauBelum ada peringkat
- Proposal 21 Usulan Program Kali Asri LestariDokumen14 halamanProposal 21 Usulan Program Kali Asri LestariElisa SutanudjajaBelum ada peringkat
- Identifikasi Dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota GorontaloDokumen22 halamanIdentifikasi Dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota GorontaloWahyu YudhoBelum ada peringkat
- Kebijakan Dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan Permukiman KumuhDokumen11 halamanKebijakan Dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan Permukiman KumuhMahfud AfandiBelum ada peringkat
- Bab 1 PendahuluanDokumen12 halamanBab 1 PendahuluanwiwiedplanBelum ada peringkat
- Tugas 3 - Pengantar Perencana Wilayah Dan Kota - 048582705Dokumen3 halamanTugas 3 - Pengantar Perencana Wilayah Dan Kota - 048582705aulina sairaBelum ada peringkat
- Paparan PLPBK WaingapuDokumen20 halamanPaparan PLPBK WaingapuYanMeS SeboBelum ada peringkat
- Gambaran Umum Program KotakuDokumen18 halamanGambaran Umum Program KotakuAdhi PratamaBelum ada peringkat
- Laporan Permukiman Kumuh Di Kota PalopoDokumen19 halamanLaporan Permukiman Kumuh Di Kota PalopoGregorius NisanBelum ada peringkat
- BAB 1 PENDAHULUAN - OkDokumen29 halamanBAB 1 PENDAHULUAN - OkmelisaBelum ada peringkat
- Dokumen AjarDokumen46 halamanDokumen AjarUki KadirBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen14 halamanBab I PendahuluanIkalmyBelum ada peringkat
- Proposal Desa GetasanDokumen14 halamanProposal Desa GetasanTia NoorsBelum ada peringkat
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat
- BAB II Profil Kab MagelangDokumen17 halamanBAB II Profil Kab MagelangWahyu YudhoBelum ada peringkat
- Brosur Baja RinganDokumen6 halamanBrosur Baja RinganWahyu Yudho100% (1)
- Sni 2836Dokumen26 halamanSni 2836Wahyu YudhoBelum ada peringkat
- Peta Jalan Kab PatiDokumen11 halamanPeta Jalan Kab PatiWahyu YudhoBelum ada peringkat
- Klu 2012Dokumen222 halamanKlu 2012Tjahjo Boedi Santoso100% (1)
- BAB II Profil Kab MagelangDokumen17 halamanBAB II Profil Kab MagelangWahyu YudhoBelum ada peringkat
- Permendagri 61-2007 TTG Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUDDokumen39 halamanPermendagri 61-2007 TTG Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUDridwante100% (5)
- Identifikasi Dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota GorontaloDokumen22 halamanIdentifikasi Dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota GorontaloWahyu YudhoBelum ada peringkat