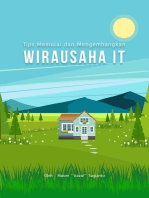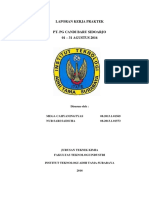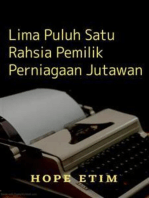LAPORAN PKL
LAPORAN PKL
Diunggah oleh
Siti HawaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
LAPORAN PKL
LAPORAN PKL
Diunggah oleh
Siti HawaHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PKL
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang
meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Peningkatan kualitas
SDM suatu negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya
adalah dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan di
perguruan tinggi masih berbentuk teori dan latihan kerja dalam skala kecil
dan frekuensi yang relatif sedikit. Untuk dapat terjun langsung di masyarakat
tidak hanya dibutuhkan pendidikan formal yang tinggi dengan nilai
memuaskan, namun diperlukan juga keterampilan (skill) dan pengalaman
sebagai pendukung untuk lebih mengenali bidang pekerjaan yang sesuai
dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tuntutan dunia kerja atau pasar
kerja.
Bagi mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan, PKL dilakukan untuk
mendapatkan keterampilan, pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan praktek secara langsung pada perusahaan-perusahaan industri yang
mengolah bahan pangan baik skala kecil, menengah, maupun besar, sehingga
sistem ini sangat penting untuk membekali para mahasiswa dengan suatu
proses pendidikan keahlian profesional yang terpadu secara sistematik antara
program pendidikan di bangku kuliah dengan program penguasaan keahlian
yang diperoleh melalui bekerja langsung secara terarah untuk mencapai
tingkat keahlian profesional tertentu. PKL sangat bermanfaat bagi mahasiswa
Ilmu dan Teknologi Pangan untuk mengetahui teknologi yang diterapkan
pada perusahaan yang mengolah bahan pangan secara umum. Perusahaanperusahaan yang menerapkan teknologi tersebut salah satunya adalah PT. PG.
Candi Baru Sidoarjo. PT. PG. Candi Baru memproduksi Gula Kristal Putih
(GKP).
Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi
dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak diperdagangkan dalam
bentuk kristal sukrosa padat. Gula sebagai sukrosa diperoleh dari nira tebu,
bit gula atau aren. Proses untuk menghasilkan gula mencakup tahap ekstraksi
(pemerasan) diikuti dengan pemurnian melalui distilasi (penyulingan)
(Sihombing, 2013). Dalam hal ini diharapkan selama kegiatan PKL
berlangsung, akan terjalin hubungan yang baik antara lembaga akademis
dengan perusahaan yang terkait.
B. Maksud dan Tujuan PKL
Adapun maksud dari pelaksanaan PKL ini antara lain:
1. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan pada pabrik tempat
mahasiswa melakukan kegiatan PKL.
2. Terbinanya mahasiswa PKL untuk merasakan dunia kerja secara langsung
dalam kurun waktu yang ditentukan.
3. Mencari informasi mengenai bagaimana mendapatkan data dilapangan
untuk diolah dan dikaji kemudian oleh mahasiswa peserta PKL.
4. Terciptanya keharmonisan dan kerja sama antara perusahaan dengan
pihak Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri melalui mahasiswa
peserta PKL.
Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini antara lain:
Tujuan Umum:
1. Mempelajari dan menyesuaikan materi yang didapatkan selama proses
perkuliahan dengan kondisi real yang ada di lapangan tempat mahasiswa
PKL.
2. Mengetahui bagaimanan proses pengolahan gula kristal putih mulai dari
persiapan bahan baku sampai pada proses pengemasan.
3. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta
keterampilan mahasiswa pada perusahaan tempat PKL.
Tujuan Khusus:
Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan PKL ini yaitu untuk
mengetahui bagaimana penerapan Good Agricultural Practice (GAP), Good
Manufacturing Practice (GMP) dan Good Handling Product (GHP) pada
produk Gula Kristal Putih (GKP) dari penanaman bahan baku sampai produk
siap kemas di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo.
C. Kegunaan PKL
1. Bagi Mahasiswa
a. Melatih keterampilan mahasiswa program sarjana sesuai dengan
pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas
Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram.
b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unitunit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan.
c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba
menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan
formal.
2. Bagi Fakultas
Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan
tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, Fakultas
Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram dapat
mewujudkan konsep tautan dan sepadan (link and match) dalam
meningkatkan
kualitas
layanan
pada
pemangku
kepentingan
(stakeholders)
3. Bagi Perusahaan
a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial
kelembagaan.
b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis
antara instansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat
bagi pihak-pihak yang terlibat.
D. Tempat PKL
PKL ini dilaksanakan di PT. PG. Candi Baru, yang terletak di Desa
Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, tepatnya
di Jalan Raya Candi Baru Nomor 10 Sidoarjo. Pemilihan perusahaan ini
berdasarkan inisiatif mahasiswa pelaksana PKL untuk mencoba melakukan
praktek kerja lapangan di perusahaan yang memproduksi gula kristal putih.
E. Jadwal PKL
PKL ini dilaksanakan selam 32 hari, terhitung sejak tanggal 10
Agustus 2015 - 10 September 2015. Praktek kerja dilaksanakan setiap hari
Senin sampai Sabtu, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
A. Sejarah Perusahaan
PT. PG. Candi Baru merupakan salah satu perusahaan agroindustri
yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, perusahaan ini bergerak dibidang
industri gula. Pabrik Gula Candi Baru berdiri pada tahun 1832 yang terletak
di Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Pabrik ini didirikan
oleh keluarga The Goen Tjing dengan nama N.V. Suiker Fabriek Tjandi.
Pada tanggal 21 Oktober 1911, pabrik tersebut dibeli oleh Kapten Tjoa.
Pengesahannya terdaftar pada Badan Hukum Panitia Pengadilan Negeri di
Surabaya No.12 tanggal 31 Oktober 1911 dengan nama NV. Suiker Fabrik
Tjandi. Ketika itu, pabrik beroperasi dengan kapasitas 750 ton tebu perhari
dan gula yang dihasilkan adalah gula SHS. Gula SHS ini berasal dari bahasa
belanda yaitu Superior Hooft Suiker.
Pada tahun 1941-1950 pabrik tidak beroperasi dan baru beroperasi
kembali pada tahun 1950. Berdasarkan RUPS tanggal 8 Februari 1962 nama
perusahaan diubah menjadi PT. Pabrik Gula Tjandi dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No.Y.A.5/112/1 tanggal 14 Oktober 1962. Pada tahun 1972,
seorang bernama H. Wirontono Bakrie membeli pabrik ini dan setiap tahun
kapasitas gilingnya ditingkatkan. Pada tahun 1975, kapasitas gilingnya
ditingkatkan menjadi 1.250 ton tebu perhari dan pada tahun 1981 kapasitas
gilingnya ditingkatkan kembali menjadi 1.500 ton tebu perhari.
Manajemen PT. PG. Tjandi dipegang oleh PT. Rajawali Nusantara
Indonesia (PT. RNI). Tahun 1992, PT. RNI memutuskan untuk mengambil
alih saham PT. PG. Tjandi Baru sebesar 55% dari Wirontono Bakrie dan
memulai masa giling pada tahun 1993 dengan perubahan nama menjadi PT.
PG. Candi Baru, dengan kapasitas giling ditingkatkan menjadi 1.750 ton
perhari. Tahun 2004, saham PT. RNI menjadi 98% dan pada tahun 2006
kapasitas giling ditingkatkan menjadi 2.100 ton perhari dengan gula yang
dihasilkan sebanyak 155 ton perhari dengan investasi difokuskan pada
peningkatan rendemen seperti High Grade Centrifugal, Evaporator dan
Crystalizer.
Tahun
2013,
terjadi
investasi
Cooling
Tower
untuk
mengefisiensikan penggunaan air pada kondensor dan terjadi perubahan
kapasitas giling menjadi 2.700 ton perhari. PT. PG. Candi Baru mulai
menerapkan sistem manajemen mutu seperti ISO 9001:2008 dan SNI
3140.3:2010 pada tahun 2014. Sasaran operasional giling tahun 2015 adalah
460.000 ton tebu giling, dengan kapasitas giling 2.600 ton perhari, dengan
rendemen 8,2%, kulitas gula 120 ICUMSA dan produksi gula 37.720 Ton
selama 180 hari giling.
Visi dari PT. PG. Candi Baru adalah sebagai perusahaan terbaik dalam
bidang agroindustri, siap menghadapi tantangan dan unggul dalam kompetisi
global serta bertumpu pada kemampuan sendiri (own capabilities). Misi PT.
PG. Candi Baru menjadi perusahaan dengan kinerja terbaik dalam bidang
agroindustri, yang dikelola secara profesional dan inovatif dengan orientasi
kualitas produk pelayanan pelanggan yang prima sebagai karya sumber daya
manusia yang handal, mampu tumbuh dan berkembang memenuhi harapan
pihak-pihak yang berkepentingan terkait (stake holders). PT. PG. Candi Baru
telah banyak menerima penghargaan baik di bidang lingkungan maupun di
bidang industri, antara lain penghargaan RNI Awards 2012 dengan kategori
Best Operating Company, juara 2 kategori Inovasi Teknologi BUMN Terbaik,
penghargaan menteri BUMN dengan kategori Pabrik Gula Bebas Suplemasi
Energi pada tahun 2012 dan penghargaan lingkungan hidup peringkat BIRU.
B. Struktur Organisasi
PT. PG Candi Baru adalah suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT).
Perusahaan dipegang oleh seorang direktur, yang membawahi beberapa
kepala bagian. Masing-masing kepala bagian ini dibantu oleh beberapa orang
staff.. Tanggung jawab masing-masing kepala bagian yang terdapat di PT.
PG. Candi Baru Sidoarjo adalah sebagai berikut :
a) Direktur
Tugas Direktur :
1. Mengadakan rapat kerja dengan kepala bagian dan menetapkan
rencana serta pelaksanaan kerja.
2. Mengontrol semua bidang dan menjelaskan masalah internal dan
eksternal.
3. Memberi instruksi
baik
berupa
teknis
dan
nonteknis
dan
mengkoordinir seluruh karyawan melalui kepala bagian masingmasing.
4. Bertanggung jawab kepada direksi atas kelancaran kerja pabrik.
b) Kabag Akutansi & Keuangan
Tugas Kabag. Akutansi & Keuangan melaksanakan kebijaksanaan
direksi dan ketentuan Direktur dibidang anggaran akutansi, umum dan
sumber daya manusia dalam :
1. Menyelenggarakan pembukaan perusahaan.
2. Membuat laporan pertanggung jawaban perusahaan.
3. Membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan.
4. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
5. Menyelenggarakan administrasi pergudangan, investasi dan hasilhasil perusahaan.
6. Mengadakan pembinaan harta kekayaan perusahaan.
7. Membina kerjasama antar bagian dan pihak lain untuk kelancaran
usaha perusahaan.
c) Kabag SDM & Umum
Tugas Kabag. SDM & Umum melaksanakan kebijaksanaan
direksi dan ketentuan Direktur dibidang rekrutment, umum dan sumber
daya manusia dalam :
1. Mengkoordinasikan perumusan dan pemberdayaan pegawai (Man
Power Planning), sesuai kebutuhan perusahaan.
2. Mengkoordinasikan perumusan sistem pengadaan, penempatan dan
pengembangan pegawai.
3. Mengkoordinasikan perumusan sistem dan kebijakan imbal jasa
pegawai dengan mempertimbangkan internal / external equity.
4. Bersama manajemen merumuskan pola pengembangan organisasi
perusahaan.
5. Menyelenggarakan Sistem Informasi SDM dalam suatu data base
Kepegawaian.
6. Menyelenggarakan kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja / perjalanan
dinas dan penerimaan tamu perusahaan.
7. Menyiapkan laporan kegiatan Divisi secara benar dan tepat waktu.
d) Kabag Tanaman
Tugas Kabag Tanaman adalah melaksanakan kebijakan direksi dan
ketentuan Direktur dalam bidang pembudidayaan tebu dan penyediaan
bibit tebu, rencana tebang dan angkut serta kegiatan lain yang
menyangkut penyediaan bahan baku tebu yaitu :
1. Bertanggung jawab kepada Direktur dalam hal tanaman.
2. Menyusun rencana kebutuhan awal tanaman untuk masa yang akan
datang.
3. Menyusun komposisi tanaman mengenai letak, luas, masa tanam dan
jenis tebu, guna mengusahakan peningkatan produksi dan menaikkan
rendemen.
4. Menyusun rencana anggaran belanja dalam bidang tanaman, tebang
dan pengangkutan
5. Membuat laporan berkala maupun insidental mengenai pelaksanaan
pekerjaan tanaman.
e) Kabag Instalasi
Tugas Kabag Instalasi adalah membantu general manager dalam
melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan, serta reparasi mesin dan
instalasi pabrik, lori, loko, kendaraan, traktor, pompa, bangunan serta
penyediaan tenaga listrik yaitu :
1. Merencanakan, mengkoordinir
dan
mengawasi
pelaksanaan
maintenance terhadap instalasi pabrik.
2. Mengadakan pergantian dan perbaikan alat-alat produksi gula
termasuk sarana dan transportasi.
3. Bertanggung jawab atas kelancaran pemakaian mesin selama masa
giling.
f) Kabag Pabrikasi
Tugas Kabag Pabrikasi adalah membantu kepala pabrik atau
general manager dalam melaksanakan pengolahan gula dalam :
1. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pengolahan proses
pabrikasi pabrik gula
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran belanja dalam bidang pabrikasi.
3. Melaksanakan kebijaksanaan perusahaan dalam bidang pabrikasi.
C. Kegiatan Umum Perusahaan
Kegiatan umum di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo adalah memproduksi
gula kristal putih (GKP) dan Analisa Laboratorium. Kegiatan yang terjadwal
di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo ini secara umum, masuk kerja untuk office
yaitu pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 07.00 sampai
dengan pukul 15.30 WIB, hari Sabtu dari pukul 07.00 sampai pukul
15.30WIB dan hari Minggu libur. Namun untuk karyawan pada bagian
10
produksi diterapkan 3 waktu kerja yang dinamakan dengan pembagian shift.
Jadwal kerja untuk pembagian waktu kerja ini terdiri dari shift pagi, shift
siang dan shift malam. Shift pagi masuk mulai pukul 06.00 sampai dengan
14.00 WIB, shift siang mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB
dan shift malam masuk mulai pukul 22.00 sampai dengan 06.00 WIB.
Karyawan pada bagian produksi akan bekerja saat musim giling tiba
dan tidak terdapat hari libur, hari minggu dan hari libur nasional dihitung
sebagai lembur. Karyawan bagian produksi diperbolehkan lembur maksimal 3
jam perhari dan 14 jam perminggunya. Setiap 6 bulan sekali atau sebelum
musim giling tiba PT. PG. Candi Baru melakukan pengecekan kesehatan
karyawan, baik karyawan office maupun karyawan bagian produksi. Diluar
musim giling akan diadakan senam pada hari jumat.
11
BAB III
PELAKSANAAN PKL
A. Bidang Kerja
A.1. Proses Pengolahan
a. Bahan Baku
PT. PG Candi Baru memperoleh bahan baku tebu dari kelompok tani
di bawah naungan perusahaan. Kelompok tani ini tersebar di beberapa
daerah meliputi Sidoarjo, Pasuruan, Gresik, Malang, Lumajang dan
Mojokerto. PT. PG. Candi Baru Sidoarjo menggunakan dua bahan baku
untuk proses produksi Gula Kristal Putih (GKP), yaitu bahan baku utama
dan bahan baku penunjang.
1) Bahan baku utama
PT. PG Candi Baru menggunakan tebu sebagai bahan baku
utama, dengan kapasitas giling sebanyak 2.700 Ton Cane per Day
(TCD). Tebu yang diterima PT. PG. Candi Baru diklasifikasikan menjadi
:
a. Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)
TRI adalah tebu yang modal kerjanya dibiayai oleh bank dan
mendapatkan bimbingan teknis budidaya dari PT. PG. Candi Baru.
Cara ini menggunakan sistem bagi hasil (66% untuk Petani dan
34% untuk Pabrik).
b. Tebu Sendiri (TS)
TS adalah tebu milik pabrik dengan sistem menyewa tanah rakyat
dan penggarapannya dibiayai oleh PT. PG. Candi Baru.
c. Tebu Rakyat Mandiri (TRM) atau Tebu Bebas (TRB)
TRM adalah tebu rakyat milik petani disekitar pabrik atau diluar
daerah yang tidak mendapatkan kredit dari pihak bank maupun
pabrik.
12
Karakteristik tebu yang digunakan sebagai bahan baku harus
memenuhi kriteria standar Bersih, Segar dan Manis (BSM), yaitu :
a. Bersih, kadar trash (tetes dan blotong) tidak lebih dari 5%.
b. Segar, tebu yang di giling merupakan tebu yang memiliki waktu
tebang dan waktu pengiriman kurang dari 48 jam. Hal ini ditujukan
untuk menjaga kadar gula pada tebu tidak mengalami penurunan
yang terlalu besar dan pH tebu harus < 4,8.
c. Manis, tebu yang digunakan harus memiliki potensi rendemen yang
tinggi (Brix > 17) dengan kriteria : Kadar nira tinggi (85%) dan
Nilai nira perahan pertama (n.p.p) tinggi (lebih dari 12%)
2) Bahan baku penunjang
Bahan baku penunjang ditambahkan untuk menghasilkan mutu
gula yang lebih baik. Bahan baku penunjang yang digunakan dalam
proses pembuatan gula tebu antara lain:
a. Asam Fosfat (H3PO4)
Fosfat adalah senyawa fosfor yang anionnya mempunyai
atom fosfor yang dilengkapi oleh empat atom oksigen yang terletak
pada sudut tetrahedron (Saragih, 2009). Konsentrasi asam fosfat
adalah 25% (b/b).
b. Air Imbibisi
Air imbibisi merupakan air yang didapatkan dari penyerapan
air (absorpsi) oleh benda-benda yang padat (solid) atau agak padat
(semi solid). Fungsi penambahan air imbibisi adalah untuk
mendapatkan presentase pemerahan yang tinggi dan menekan kadar
sukrosa yang tertinggal pada ampas. Suhu air imbibisi yang
digunakan adalah 60-70oC.
c. Kapur Tohor (CaO)
Kapur tohor (CaO) merupakan oksida basa yang didapat dari
batuan gamping di mana terkandung kalsium oksida sedikitnya 90%
13
dan magnesia 0-5%, kalsium karbonat, silika, alumina, feri oksida
terdapat sedikit sebagai ketidakmurnian (Sembiring, 2009). Takaran
susu kapur yang digunakan adalah 120-150 kg/100 ton tebu
Penambahan susu kapur ini bertujuan untuk : meningkatkan pH nira
menjadi alkalis (basa), mencegah terjadinya inversi saccharosa
menjadi D-glukosa dan D-fruktosa, menjernihkan nira, ketika kapur
beraksi dengan fosfat dan belerang, akan terbentuk garam yang
dapat menyerap kotoran dalam nira dan mengendapkannya.
d. Belerang (gas SO2)
Belerang adalah kristal padat berwarna kuning, namun
keberadaannya di alam dapat berupa elemen murni atau sebagai
sulfida dan mineral sulfat. Belerang ditambahkan dalam bentuk gas
SO2 pada proses sulfitasi. Gas SO2 berfungsi sebagai bleacher atau
pemucat warna. Gas SO2 berperan sebagai reduktor ion ferri
sehingga warna nira menjadi lebih pucat dan viskositas akan
berkurang.
e. Flokulan
Flokulan yang ditambahkan pada tahap pemurnian ditujukan
untuk mengikat partikel-partikel pengotor/ impurities pada nira agar
membentuk flok-flok yang berukuran lebih besar sehingga lebih
mudah mengendap. Flokulan merupakan senyawa polimer rantai
panjang yang bermuatan negatif (Pandreou,dkk., 2014). Konsentrasi
flokulan yang ditambahkan adalah 0,2%.
f. Fondan
Fondan adalah bahan baku penunjang proses produksi yang
berguna untuk membentuk kristal pada proses pemasakan. Fondan
14
didapat dari gula yang tidak masuk standar perusahan pada stasiun
penyelesaian kemudian dileburkan kemudian ditambahkan gelatin,
gliserin, glukosa dan shortening.
g. Soda flake (NaOH)
Penggunaan soda flake bertujuan untuk melunakkan kerakkerak yang ada pada evaporator. Kebutuhan untuk tiap pembersihan
evaporator adalah 150 kg, jumlah tersebut juga tergantung pada
kondisi kerak yang terbentuk.
h. Kaporit (Ca(ClO)2)
Penambahan kaporit bertujuan untuk membunuh bakteri
yang ada pada nira. Nira yang bebas bakteri memiliki kemungkinan
yang lebih kecil untuk mengalami terjadinya inversi Saccharosa
menjadi glukosa dan fruktosa. Kaporit juga digunakan untuk
membunuh bakteri pada pemakaian cane cutter.
i. Tawas (KAl(SO4)212H2O)
Tawas berfungsi untuk mengendapkan kotoran air sungai
yang digunakan sebagai feed water boiler di bak pengendapan air.
j. Bakterisida dan Fungisida
Bakterisida dan fungisida ditambahkan dengan tujuan
mengontrol pertumbuhan bakteri dan jamur dalam nira, serta
menurunkan kehilangan sukrosa yang terjadi karena inversi pada
stasiun gilingan.
b. Uraian Proses Produksi
Proses produksi yang digunakan untuk memproduksi gula SHS- IA di
PT. PG. Candi Baru adalah Sulfitasi Katalis Kontinyu, proses ini melalui
beberapa tahapan yang dilakukan di tujuh stasiun yang berbeda, yaitu:
Air Kondensat
15
Batang Tebu
Air Imbibisi 60-70oC
Kapur Tohor
Penggilingan
(Ekstraksi)
Ampas
Nira Mentah
Penyaringan
(Penjernihan)
Kotoran
Nira
Asam Fosfat
Kapur Tohor
Gas SO2
Accofloc
Pemurnian
(Klarifikasi)
Uap Panas 117C
Penguapan
(Evaporasi)
Blotong
Gas SO2
Nira Encer
Air Kondensat
Nira Kental
Pemasakan
(Kristalisasi)
Air Kondensat
Puteran
(Pemisahan)
Tetes / Molasse
Kristal
Udara Panas
Pengeringan
Pengayakan
Gula
Gula Produk
Pengemasan
Gula dalam Kemasan
Gambar III. 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Gula Tebu
(Sumber: Pandreou, dkk., 2014 yang dimodifikasi)
16
1) Tahap Persiapan
Tahap persiapan bertujuan untuk mempersiapkan tebu sampai
tebu siap giling. Pada Tahap persiapan terdapat tiga pos, yaitu :
a. Pos Penerimaan atau Pos Pantau
Pada pos penerimaan dilakukan pemeriksaan kadar gula
(brix) tebu menggunakan refraktometer dan pemeriksaan pH tebu
menggunakan pH meter.
b. Pos Penimbangan
Pada pos penimbangan, truk yang bermuatan tebu di
timbang terlebih dahulu, setelah muatan truk diturunkan, truk
kemudian ditimbang kembali. Berat muatan yang diperoleh
merupakan selisih dari berat truk bermuatan dan berat truk kosong.
c. Pos Pembongkaran
Pada pos pembongkaran, tebu dari truk dipindahkan ke lori
(kereta pengangkut tebu) tebu menggunakan cane crane kemudian
dipindahkan ke meja tebu sebelum masuk ke dalam stasiun
gilingan. Tempat antrian tebu yang akan digiling disebut dengan
Emplacement
tebu.
Pengambilan
pada
emplacement
ini
menggunakan sistem FIFO (First In First Out).
2) Tahap Penggilingan
Tahap penggilingan bertujuan untuk memperoleh nira sebanyakbanyaknya dan meminimalkan kandungan nira pada ampas tebu. Tebu
pada emplacement dipindahkan ke meja tebu. Pada meja tebu, tebu
diatur ketinggiannya agar memudahkan proses penggilingan. Dari meja
tebu, tebu dibawa oleh cane carrier I menuju cane cutter untuk
dipotong-potong, sehingga memudahkan unigrator untuk proses
pencacahan tebu menjadi serabut-serabut tebu. Sebelum serabut tebu
17
masuk ke dalam penggilingan dilakukan proses preliming, yaitu
penambahan kapur tohor pada tebu.
Serabut yang telah bercampur dengan kapur tohor masuk ke
gilingan I. Nira perahan pertama langsung menuju saringan Dutch
States Mines Screen (DSM screen) untuk dipisahkan antara nira dan
ampas yang masih terbawa dan ditampung dalam bak nira tertimbang.
Ampas dari gilingan I dibawa oleh intermediate carrier menuju gilingan
II, pada gilingan dua terjadi penambahan air imbibisi. Nira hasil gilingan
II menuju penampung II yang berhubungan dengan DSM screen,
sedangkan ampas gilingan II dibawa menuju gilingan III. Pada gilingan
III juga terjadi penambahan air imbibisi.
Nira dari gilingan III, dibawa kembali menuju gilingan II sebagai
nira imbibisi. Ampas gilingan III dibawa ke gilingan IV. Nira gilingan
IV menuju gilingan II sebagai nira imbibisi, sedangkan ampas dari
gilingan IV dibawa ke stasiun ketel oleh baggase carrier. Dibawah
baggase carrier terdapat saringan yang berfungsi untuk memisahkan
ampas kasar dan ampas halus. Ampas kasar dikirim menuju ketel, yang
akan digunakan sebagai bahan bakar dapur ketel. Ampas halus di blower
menuju mixer untuk dicampur dengan nira kotor untuk dijadikan
blotong.
3) Tahap Pemurnian
Tahap pemurnian bertujuan untuk memisahkan gula dari kotoran
yang ikut terlarut dalam nira. Proses pemurnian pada produksi gula
sangat penting, karena dapat mempengaruhi gula yang dihasilkan. Nira
yang telah disaring oleh DSM screen dan ditampung pada bak nira
18
tertimbang, ditambahkan asam fosfat dan ditarik menuju juice heater I
atau pemanas pendahuluan I. Nira dipanaskan hingga suhu 70-80C
dengan uap bekas dari proses stasiun gilingan. Pemanasan pendahuluan
ini bertujuan untuk mempercepat reaksi pengendapan kalsium fosfat dan
membunuh bakteri dalam nira, sehingga tidak mengganggu proses
pembentukan kristal gula.
Nira dari juice heater I masuk ke dalam tabung Ca-sakarat untuk
dicampur dengan susu kapur dan nira kental guna menyempurnakan
pembentukan flok, sehingga pH sakarat naik menjadi naik menjadi 8,6.
Nira dari tabung sakarat dialirkan menuju sulfur tower untuk
dicampurkan dengan gas SO2 atau biasa disebut sebagai proses sulfitasi.
Gas SO2 dari sulfur burner masuk melewati bawah sulfur tower,
sedangkan nira masuk melalui atas sulfur tower. Proses sulfitasi
menghasilkan kisaran pH nira dari 7-7,2. Kemudian nira dipompa
menuju juice heater II, nira dipanaskan hingga mencapai suhu 105110C. Pemanasan ini bertujuan untuk menyempurnakan reaksi
pengendapan, membunuh mikroba yang resisten pada suhu 75-85C dan
menguapkan gas-gas yang terlarut yang dapat menguap, sehingga tidak
mengganggu proses pengendapan.
Nira dialirkan ke flash tank untuk melepaskan uap gas (gas yang
mengganggu/gas amonia). Nira dari flash tank masuk ke dalam Single
Tray Clarifier. Penambahan flokulan dilakukan agar molekul-molekul
yang terbentuk saling berikatan satu sama lain membentuk partikel yang
19
lebih besar (flok-flok), sehingga kotoran yang membentuk flok lebih
mudah mengendap.
Flok-flok atau nira kotor yang mengendap akan dialirkan menuju
Rotary Vacuum Filter (RVF), yang ditambahkan ampas halus dan susu
kapur. Proses pencampuran tersebut bertujuan untuk mendapatkan nira
tapis yang masih terkandung pada nira kotor. Nira tapis dialirkan menuju
bak penampung nira mentah, sedangkan blotong ditampung oleh truktruk dan dibawa pada pihak ketiga. Nira jernih dari Single Tray Clarifier
secara overflow menuju bak penampungan nira jernih, yang sebelumnya
disaring menggunakan DSM screen.
4) Tahap Penguapan
Tujuan dari proses penguapan adalah menguapkan sebanyak
mungkin air yang terkandung pada nira jernih, sehingga mencapai
kondisi larutan mendekati jenuh. Nira jernih hasil pemurnian dialirkan
menuju evaporator untuk mendapatkan nira kental dengan % Brix
minimal 60% dengan sistem lima kali penguapan. Penguapan dilakukan
pada kondisi vakum karena nira tidak tahan terhadap suhu tinggi,
sehingga tekanan dalam evaporator dinaikkan agar mencapai kondisi
vakum dan titik didih nira dapat diturunkan sampai 60C, begitu juga
sebaliknya. Jika tekanan evaporator rendah maka titik didih nira akan
meningkat. Suhu larutan setiap evaporator akan mengalami penurunan
karena adanya proses kondensasi. Besar tekanan vakum setiap
evaporator sebesar 64 cmHg (0,84 atm).
Nira jernih dipompa menuju evaporator I, diuapkan dengan uap
bekas yang memiliki suhu 117C. Uap bekas ini masuk lewat pipa dan
20
memanaskan nira yang mengalir pada pipa calandria. Dengan adanya
perbedaan suhu antara steam dan nira, maka steam akan terkondensasi
menjadi air kondensat dan larutan nira akan menguap. Ketinggian nira
pada evaporator harus diperhatikan, karena jika ketinggian nira dibawah
standar (1/3 dari tinggi pipa calandria) maka uap nira yang terbentuk
tidak akan tertarik, sedangkan jika melebihi standar maka nira akan ikut
tertarik. Jadi disetiap evaporator dilengkapi dengan penangkap nira
(lovre) yang dipasang pada lubang pengeluaran uap untuk menahan gula
yang menguap agar jatuh kembali ke dalam evaporator.
Nira yang keluar dari evaporator terakhir biasanya lebih keruh
dan lebih kental karena adanya kenaikan konsentrasi dan penggumpalan
nira, sehingga dilakukan proses pemucatan (bleaching) dalam sulfur
tower dengan cara dikontakkan dengan gas SO2. Nira dari sulfur tower
mengalir menuju bak penampung nira tersulfitasi.
5) Tahap Pemasakan
Tahap pemasakan bertujuan untuk memasak nira kental dengan
proses pembentukan dan pembesaran kristal gula menjadi gula produk.
a. Masakan D
Bahan untuk membuat masakan D adalah nira kental
tersulfitir, fondan, leburan gula D2 dan stroop A. Leburan gula D2
dan stroop A berfungsi untuk menaikkan harga kemurnian (HK) dari
nira. Mula-mula nira kental dari bak penampungan nira tersulfitasi
dialirkan menuju pan masakan D untuk dipanaskan dengan suhu
100C, sampai terbentuk benangan dan diusahakan tidak terjadi
21
pengkristalan terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan fondan
sebagai bibit gula dan dipanaskan kembali. Selama pemanasan
terjadi pembentukan inti kristal yang harus dikontrol, agar terbentuk
inti kristal yang diinginkan.
Untuk mengurangi kristal palsu yang terbentuk, dilakukan
penambahan air agar kristal palsu larut dan kembali menjadi cuite.
Waktu masak normal pada masakan D sekitar 5-7 jam, hingga
masakan mencapai harga kemurnian yang dikehendaki yaitu antara
59-60.
b. Masakan C
Bahan untuk membuat masakan C adalah gula D2 (babonan
D), nira kental dan stroop A yang berfungsi untuk menaikkan HK.
Ketiga bahan tersebut dipanaskan dengan suhu 70C sampai kristal
cukup besar, proses pemasakan memakan waktu sekitar 4-5 jam
tergantung suplai uap dari stasiun ketel. Untuk mengurangi kristal
palsu yang terbentuk, dilakukan penambahan air agar kristal palsu
larut dan kembali menjadi cuite. Dilakukan pengontrolan ukuran
kristal dengan sesekali mengambil sampel masakan dan melihatnya
melalui kaca bening yang disinari lampu. Setelah ukuran kristal
menjadi lebih besar yaitu 0,6 mm dengan harga kemurnian 70-71,
masakan diturunkan menuju palung pendingin.
c. Masakan A
Bahan untuk membuat masakan A adalah gula C, nira kental
dan klare SHS. Mula-mula nira kental dimasukkan pada pan
masakan dan dipanaskan dengan suhu 58C sampai timbul
benangan, kemudian gula babonan C ditambahkan sebagai bibit.
22
Proses pemasakan dikontrol agar tidak terbentuk inti kristal palsu,
jika terdapat inti kristal palsu maka dilakukan penambahan air.
Proses pemasakan berlangsung antara 3-4 jam dengan harga
kemurnian yang dikehendaki sebesar 78-80. Setelah proses
pembesaran kristal dengan ukuran 0,9-1,0 mm, masakan diturunkan
menuju palung pendingin.
6) Tahap Pemutaran
Tahap pemutaran bertujuan untuk memisahkan kristal gula dari
larutannya dengan cara sentrifugal.
a. Putaran gula D
Masakan D yang berada pada talang U dialirkan menuju
puteran D1. Pada saat proses pemutaran, ditambahkan air agar
pemisahan menjadi lebih sempurna. Cairan yang terpisah dari gula
D1 disebut tetes. Tetes selanjutnya dialirkan menuju talang
penampung tetes, sedangkan gula D1 kembali diputar pada putaran
gula D2. Pada proses pemutaran ditambahkan air, proses ini
menghasilkan gula D2 dan klare D. kemudian klare D dialirkan
menuju peti tunggu klare D dan gula D2 (babonan D) dialirkan ke
peti babonan D .
b. Putaran gula C
Masakan C dari palung pendingin dialirkan menuju putaran
C. Dari putaran C dihasilkan gula C dan hasil samping stroop C.
Pada saat proses pemutaran, dilakukan penambahan air agar
pemisahan terjadi lebih sempurna.
c. Putaran gula A
Masakan A dari palung pendingin dialirkan menuju putaran
A dan ditambahkan air, sehingga dihasilkan stroop A dan gula A.
23
Stroop A dipompa menuju peti tunggu, sedangkan gula A diproses
lebih lanjut pada putaran SHS.
d. Putaran gula SHS
Gula A yang merupakan hasil dari putaran A, diputar
kembali pada putaran SHS. Pada putaran terjadi penambahan air,
yang bertujuan untuk menyempurnakan penghilangan kotoran.
Hasil dari putaran SHS adalah gula SHS dan klare SHS. Klare SHS
dialirkan menuju peti tunggu dan gula SHS akan diproses lebih
lanjut pada stasiun penyelesaian.
7) Tahap Penyelesaian
Tahap penyelesaian bertujuan untuk mengeringkan gula SHS dan
menyeleksi ukuran gula serta menghasilkan gula produk. Gula SHS
hasil dari putaran SHS dikeringkan dengan sugar dryer, yang merupakan
pengering yang menggunakan udara panas bersuhu 50C selama 2,5
jam. Setelah gula mengalami pengeringan pada sugar dryer, gula
tersebut melalui proses pendinginan (cooler) yang mempunyai suhu
30C, sehingga diperoleh gula kering. Gula kering yang dihasilkan
memiliki kadar air 0,03-0,05%, kemudian melalui talang getar. Pada
talang getar terdapat 2 jenis ayakan yaitu ayakan 8 mesh dan ayakan 23
mesh. Gula halus dan gula kasar dimasukkan kembali pada proses
pemasakan sedangkan gula produk dari ayakan 23 mesh ditarik oleh
bucket elevator atau tangga jacob menuju sugar bin untuk dilakukan
pengemasan.
Gula produk yang dihasilkan merupakan gula kristal putih
dengan kualitas IA dengan kriteria besar butiran 0,9-1,0 mm dan %
24
remisi kurang dari 70. Kriteria gula yang diterapkan telah sesuai dengan
syarat mutu gula kristal putih SNI 3140.3 tahun 2010. Kualitas gula
dapat dilihat pada tabel 1 dan Syarat mutu gula pada tabel 2.
Tabel 1. Syarat Mutu Gula Kristal Putih
Parameter Uji
Satuan
Warna Kristal
Warna Larutan (ICUMSA)
Besar Jenis Butir
Susut Pengeringan (b/b)
Polarisasi
Abu (b/b)
SO2
CT
IU
Mm
%
Z
%
mg/kg
Persyaratan
GKP 1
GKP 2
4,0-7,5
7,6-10,0
81-200
201-300
0,8-1,2
0,8-1,2
Maks 0,1
Maks 0,1
Min 99,6
Min 99,5
Maks 0,10
Maks 0,15
Maks 30
Maks 30
(Sumber: Nugraheni, 2010)
Tabel 2. Kualitas Gula
Kualitas
SHS 1A
SHS 1B
SHS 1
Nilai Remisi
>70
>65
>60
Besar Butir (mm)
0,9-1,0
0,9-1,0
0,8-1,0
(Sumber: Prawaningrum, 2011)
c. Pengemasan
Jenis kemasan di PT. PG. Candi Baru terdapat dua macam, yaitu
kemasan karung dan kemasan plastik. Gula dari sugar bin ditimbang
sebanyak 50 Kg, setelah itu karung dijahit dan menuju tempat pengangkutan.
Kemasan plastik yang berisi 1 Kg dikemas dengan menggunakan sealer dan
dikemas dengan kardus.
d. Penyimpanan
Karung-karung gula dari tempat pengangkutan diangkut ke gudang,
pengangkutan gula di PT. PG. Candi Baru masih menggunakan tenaga
manusia. PT. PG. Candi Baru memiliki dua gudang, yaitu gudang barat dan
gudang timur. Gudang barat dan gudang timur dengan kapasitas masing-
25
masing 6.400 ton dan 5.100 ton. Maksimal tumpukan yang digunakan untuk
kemasan kardus adalah 5 tumpukan dan tumpukan karung (stapelan) adalah
40-45 tumpukan.
e. Pemasaran
PT. PG. Candi Baru memasarkan gula yang dihasilkan kepada
konsumen melalui dua jalur. Pertama, melalui Panitia lelang gula, yang
terdiri dari kelompok tani di bawah naungan PT. PG. Candi Baru. Jumlah
produk gula yang dilelang adalah 66% dari gula hasil produksi, gula lelang
ini dikemas dengan karung. Kedua, gula hasil produksi 34% yang dikemas
dengan plastik ditangani langsung oleh anak perusahaan PT. RNI yang
bergerak di bidang perdagangan yaitu PT. Rajawali Nusindo dengan merek
Raja Gula. Gula yang ditangani oleh PT. Rajawali Nusindo, biasanya
dijual secara retail. Gula-gula ini didistribusikan di seluruh Indonesia.
A.2. Mesin dan Peralatan Pengolahan
A.2.1. Pos Pantau
1. Mesin Perah
Gambar III. 2. Mesin Perah
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk mendapatkan sampel nira dari tebu yang akan diperiksa
26
2. Hand Refraktometer
Gambar III. 3. Hand Refraktometer
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk mengukur kadar gula (brix) pada sampel nira dari tebu
yang baru diterima.
Brix
: 58-90%
Be
: 38-43
Water
: 12-27%
Akurasi : 0,5%
Min. Div : 0,5% Brix, Be, Water
Suhu
: 10C-30C
Ukuran : 27x40x150 mm
3. pH Meter
27
Gambar III. 4. pH Meter
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk mengukur pH nira
A.2.2. Tahap Persiapan
1. Timbangan Truk
Gambar III. 5. Timbangan Truk
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk mengetahui berat truk kosong dan truk isi tebu
Merk
: AND
Jenis
: Timbangan elektronik (sistem komputer)
Buatan
: PT. Libra Mas
Tahun
: 2003
Tipe
: Load cell
Jumlah
: 2 buah
Kapasitas: 30 ton dan 60 ton
28
2. Timbangan Lori
Fungsi
: Untuk mengetahui berat lori
Merk
: Berkel
Jenis
: CW-211/1000 RE-2
Buatan
: Rotherdam
Tahun
: 1965
Tipe
: RE.2.10000
Jumlah
: 1 buah
Kapasitas: 10 ton
3. Timbangan Digital Gantung
Gambar III. 6. Timbangan Digital Gantung
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk menimbang tebu langsung dari truk
Merk
: EHP
Buatan
: Germany
Tipe
: Load cell
Jumlah
: 1 buah
Kapasitas: 10 ton
4. Lori
29
Gambar III. 7. Lori
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Sebagai tempat tebu penyimpanan tebu sebelum diolah
Kapasitas: 3-5 ton
5. Meja Tebu (Cane Table)
Gambar III. 8. Meja Tebu
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Sebagai tempat menampung tebu dari truk atau lori
sebelum digiling
Panjang
: 9,4 m
Lebar
: 5,7 m
Power motor
: 15 kW
Ketinggian
: 2,8 m
Kemiringan
: 30
Kecepatan
: 0,28 m/detik
6. Krepyak Tebu (Cane Carrier)
30
Gambar III. 9. Cane Carrier
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk membawa potongan tebu menuju unigrator atau Stasiun
Penggilingan
Tabel 3. Spesifikasi Cane Carrier
Spesifikasi
Cane Carrier I
Model
Slat Carrier
Lebar
1524 m
Panjang Bagian Datar
17,3 m
Panjang Bagian Miring
13 m
Motor
50 HP
Kecepatan
850 rpm
Cane Carrier II
Slat Carrier
1524 m
4m
7m
30 HP
1200 rpm
7. Cane Leveller
Gambar III. 10. Cane Laveller
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk meratakan ketinggian tebu ( 1m)
Diameter
: 850 mm
Panjang
: 1520 mm
Jumlah pisau
: 562
31
Penggerak
Kecepatan
:
: 730 rpm
Gear reducer : 1:30
Slipring motor : 125 HP
Kecepatan
: 600 rpm
A.2.3. Tahap Penggilingan
1. Gilingan
Gambar III. 11. Gilingan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Memerah tebu hingga menghasilkan nira.
Tipe
: Roll crusher
Spesifikasi
Produksi
Tahun
Diameter Rol
Panjang Rol
Jumlah Rol
Kecepatan
Daya
Ratio
Tekanan Hidrolik
Tabel 4. Spesifikasi Gilingan
Gilingan I
Gilingan II
Gilingan III
PT. Bima
Ex. PG.
PT. Bima
Bisma Indra
Krebet Baru
Bisma Indra
1993
1993
1993
914 mm
914 mm
900 mm
1524 mm
1524 mm
1524 mm
4 buah
3 buah
3 buah
4200 rpm
4300 rpm
3700 rpm
240 HP
180 HP
120 HP
1:19,4
1:20,62
1:24,5
2
2
200
Kg/cm
200
Kg/cm2
200 Kg/cm
2. Intermediate Cane Carier
Gilingan IV
PT. Bima
Bisma Indra
1993
900 mm
1524 mm
4 buah
3500 rpm
250 HP
1:17,21
200 Kg/cm2
32
Gambar III. 12. Intermediate Cane Carrier
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk membawa ampas dari gilingan satu menuju
gilingan yang lain
Kecepatan cakar : 3 x peripheral speed roll atas
3. Pompa Nira Mentah Gilingan
Fungsi
Spesifikasi
Kapasitas
Head
Kecepatan
Power
Diameter Inlet
Diameter Outlet
: Untuk memompa nira menuju DSM Screen
Tabel 5. Spesifikasi Pompa Nira
Pompa Barat
120 m3/jam
25 mka
1455 rpm
15 kW
5 inch
5 inch
Pompa Timur
120 m3/jam
25 mka
1455 rpm
20 kW
5 inch
5 inch
4. Saringan Nira Mentah (DSM Screen)
Gambar III. 13. Saringan Nira Mentah (DSM Screen)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Menyaring nira gilingan I dan II
33
Panjang
:2m
Lebar
:1m
Diameter lubang : 0,5 mm
5. Bak Penampung Nira Mentah
Gambar III. 14. Bak Penampung Nira Mentah
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Menampung nira hasil pemerahan dari gilingan I dan II
Jumlah
: 1 buah
Panjang : 2 m
Lebar
: 1,5 m
Tinggi
:2m
A.2.4. Tahap Pemurnian
1. Peti Tarik Nira Mentah/Bak Penampung
Fungsi
: Menampung nira hasil pemerahan dari gilingan I dan II
Volume : 6,2 m3
Operasi : Kontinyu
Panjang : 2 m
34
Lebar
: 1,5 m
Tinggi
:2m
Tipe
: Bak penampung horizontal berbentuk balok
2. Pompa Nira Mentah Tertimbang
Fungsi
: Untuk memompa nira mentah tertimbang ke pemanas I
Kapasitas
: 163 m3 /jam
Head
: 30 mka
Kecepatan
: 1455 rpm
Power
: 22 kW
Diameter in/out : 5 in
3.
Juice Heater
Gambar III. 15. Juice Heater
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Sebagai pemanasan pendahuluan nira.
Tipe
: Shell and Tue Heat Exchanger
JH I
: Memanaskan nira mentah sebelum masuk flock flow sampai suhu
70-80oC
JH II
: Memanaskan nira dari sulfitator I sampai suhu 100-105oC
Tabel 6. Spesifikasi Pemanas Nira I/ II/ III
35
No.
LP (m2)
Tahun Pembuatan
Dipakai
n/pp
Keterangan
1
2
120
120
1978
1988
I
I
Bomastork
Srikayamas
3
4
120
120
1979
1979
I
II
Gruno-Sby
Gruno-Sby
5
6
120
120
1978
1979
II
II
Bomastork
BBI Pas
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
Tabel 7. Spesifikasi Juice Heater
No
.
Panjang
Pipa
(mm)
Diameter
pipa in/out
(mm)
3590
33/36
I
3590
33/36
II
3590
33/36
III
3590
33/36
IV
3590
33/36
V
3590
33/36
VI
3590
33/36
VII
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
Jumlah
Pipa
Luas
pemanas
(m2)
504
180
504
504
180
180
432
504
648
648
120
180
200
200
Jumlah
passes
Tahun
12
12
12
12
12
12
12
2007
2008
2010
1990
1993
2013
2013
4. Reaktor Ca-Sakarat
Gambar III. 16. Reaktor Ca-Sakarat
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Mencampur susu kapur dengan nira mentah.
Diameter
: 500 mm
Volume
: 0,46 m3
Waktu tinggal
: 1-3 detik
36
5. Sulfur tower I
Gambar III. 17. Sulfur Tower
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Menetralkan nira encer tersulfitasi dari Ca-sakarat
Dimensi
: 1,8 m x 2,5 m
Volume
: 6,98 m3
Waktu tinggal
: 5 menit
6. Flash Tank
Gambar III. 18. Flash Tank
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Mengeluarkan gas yang tersisa dalam nira.
Diameter
: 3,5 m
Tinggi
: 2,5 m
Volume
: 24,04 m3
Waktu tinggal
: 15 menit
Diameter cerobong
: 0,15 m
37
7. Single Tray Clarifier
Gambar III. 19. Single Tray Clarifier
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Mengendapkan kotoran/flok
Diameter
:5m
Tinggi
:3m
Volume
: 58,88 m3
Lama tinggal
: 30-40 menit
Luas bidang pengendapan
: 75 m2
Kecepatan putar scrapper
: 1 putaran/14 menit
8. Tangki Penampung Nira Jernih
Fungsi
: Menampung nira jernih dari DSM screen
Operasi
: Semi kontinyu
Diameter
: 3,2 m
Tinggi
:3m
Volume
: 24,12 m3
Waktu tinggal
: 15 menit
9. Saringan nira jernih (DSM Screen)
38
Gambar III. 20. DSM Screen
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk memisahkan nira dengan kotoran
Bahan
: Stainless steel
Operasi
: Kontinyu
Perforasi
: 200 mesh
Luas penyaring : 2,0 m2
Bahan penyaring : Kain nilon
10. Rotary Vacuum Filter
Gambar III. 21. Rotary Vacuum Filter
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk memisahkan blotong dengan nira tapis
Diameter : 10 ft
Panjang : 18 ft
Luas
: 40,2 m2
39
11. Peti Pengaduk Susu Kapur
Gambar III. 22. Peti Pengaduk Susu Kapur
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk pencampuran kapur dan air
Diameter : 1310 mm
Tinggi
: 880 mm
Volume : 1,2 m3
A.2.5. Tahap Penguapan
1. Evaporator
Gambar III. 23. Evaporator
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Menguapkan nira encer menjadi nira kental.
Operasi : Semi kontinyu
Tabel 8. Spesifikasi Evaporator
40
Evaporator
Panjang
pipa
(mm)
Diameter
pipa
in/out
(mm)
44/45
I
2300
2300
44/45
II
2300
44/45
III
2300
44/45
IV
2300
44/45
V
2300
44/45
VI
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
LP
(m2)
Tahun
Tipe
1200
1190
1000
1000
870
870
2010
1992
1977
1998
1984
1985
Robert
Robert
Smith
Smith
Robert
Robert
Jumlah
Pipa
3728
4821
2295
2714
2714
2. Sulfur Tower II
Fungsi
: Mereaksikan nira dari evaporator dengan gas SO2
Tinggi
: 5170 mm
Diameter
: 1200 mm
Dimensi
: 1,8 m x 2,5 m
Volume
: 6,98 m3
Waktu tinggal
: 5 menit
A.2.6. Tahap pemasakan
1. Pan Masakan
Gambar III. 24. Pan Masakan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Membentuk kondisi lewat jenuh larutan gula dan mempercepat
kristalisasi gula.
41
Operasi : Semi kontinyu
Tipe
: Vakum pan dilengkapi steam sebagai pemanas.
Tabel 9. Spesifikasi Pan Masakan
Spesifikasi
Jumlah Pipa
Lebar Pipa
Tahun
Masakan
Volume
Panjang Pipa
Suhu
Kapasitas
Tekanan
Pan I
820 buah
270 m2
2014
D
45 m3
1110 m
100oC
200 HL
65 cmHg
Pan II
854 buah
235 m2
1986
D
40 m3
1110 m
68 oC
400 HL
66 cmHg
Pan III
820 buah
270 m2
2013
D/C
45 m3
1110 m
70 oC
200 HL
58 cmHg
Pan IV
746 buah
240 m2
1994
A
40 m3
1110 m
58 oC
400 HL
65 cmHg
Pan V
860 buah
235 m2
1986
A
40 m3
1110 m
64 oC
400 HL
67 cmHg
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
2. Peti Tunggu
Gambar III. 25. Peti Tunggu
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Tabel 10. Spesifikasi Peti Tunggu
Peti Tunggu
Jumlah
Volume Total (m3)
Nira Kental I
1
20
Stroop A
3
100
Stroop C
1
30
Klare D
1
30
Leburan Gula D-II
3
12
Klare SHS
1
20
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
Pan VI
746 buah
240 m2
2007
A
40 m3
1110 m
58 oC
400 HL
68 cmHg
Pan VII
660 buah
220 m2
1983
A
38 m3
1110 m
122 oC
380 HL
66 cmHg
42
3. Koeltrog (palung pendingin)
Gambar III. 26. Koeltrog
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Menampung masakan dan tempat kristalisasi lanjutan
Jumlah
: 14 buah
Operasi : Semi kontinyu
Tabel 11. Spesifikasi Koeltrog
No
Volume (m3)
Masakan
I
400
D
II
380
D
III
300
D
IV
300
D
V
400
D
VI
380
C
VII
250
C
VIII
300
A
IX
200
A
X
400
A
XI
200
A
XII
200
A
XIII
200
A
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
A.2.7. Tahap Pemutaran
1. Putaran Gula A
Jenis/Bentuk
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
43
Gambar III. 27. Putaran Gula A
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi : Untuk memisahkan stroop A dengan gula yang terbentuk
Tabel 12. Spesifikasi Putaran Gula A
Spesifikasi
Semi Automatic
Manual
Merk
Broad Bent
Broad Bent
Kapasitas
0,8 ton
0,3 ton
950 rpm
Kecepatan
950 rpm
15
kW/400-440
V
Daya
15 kW/400-440 V
Dimensi
1200x1400 mm
914x356 mm
(Sumber : Pandreau, dkk., 2014)
Semi Automatic
WS
0,8 ton
950 rpm
15 kW/400-440 V
1200x1400 mm
2. Putaran Gula SHS
Gambar III. 28. Putaran Gula SHS
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk memisahkan klare SHS dengan gula
Kapasitas
: 1,3 ton
Tebal
: 18 inch
Diameter
: 36 inch
44
Jumlah putaran
: 20 putaran/jam
Volume keranjang
: 1300x1067 mm
Kecepatan maksimal
: 1200 rpm
3. Putaran Gula D
Gambar III. 29. Putaran Gula D
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi : Untuk memisahkan tetes dengan gula yang terbentuk
Spesifikasi
Merk
Tipe
Kapasitas
Kecepatan
Tabel 13. Spesifikasi Putaran Gula D
D1
I
II
Broad Bent
BMA
SPV 1220
K2200
15 ton
15 ton
2050 rpm
1030 rpm
D2
BMA
K850
3 ton
2275 rpm
4. Putaran Gula C
Gambar III. 30. Putaran Gula C
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk memisahkan stroop C dan gula C
45
Kapasitas
: 5 ton
Tebal
: 1190 inch
Diameter
: 1200 inch
Jumlah putaran
: 20 putaran/jam
A.2.8. Tahap Penyelesaian
1. Talang goyang
Gambar III. 31. Talang Goyang
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Meningkatkan produk gula secara alami, sebagai alat transportasi
dari stasiun putaran ke sugar bin dan sebagai penyaring gula yang
keluar dari putaran SHS sehingga diperoleh Kristal gula yang
ukurannya standar.
Operasi : Kontinyu
Kapasitas: 1,94112 ton/jam
Tipe
: Engkel (Single Stang)
Sudut
: 60
Bahan
: Plat siku, kayu waru tua (sebagai per pegas)
2. Sugar Dryer
46
Gambar III. 32. Sugar Dryer
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk mengeringkan gula menggunakan udara panas.
Panjang
: 16 meter
Kapasitas
: 20 ton/jam
Produksi
: PT. Multinas Indonesia
Tinggi
: 5 meter
Waktu tinggal
: 2,5 menit
3. Bucket Elevator
Gambar III. 33. Bucket Elevator
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Membawa gula ke sugar bin.
Kecepatan
: 37 rpm
Diameter gear
: 0,38 m
47
Jumlah
: 2 buah
Operasi
: kontinyu
Tinggi elevator : 23 meter
Kapasitas
: 260 ku/jam
Jumlah bucket
: 29 buah
Tahun
: 1921
Jenis rantai
: Jefri
4. Sugar bin
Gambar III. 34. Sugar Bin
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Menampung gula produk
Kapasitas: 40 ton
Tinggi
: 8 meter
Operasi : Semi kontinyu
Tipe
: Tangki penampung berbentuk silinder dengan dasar berbentuk.
Diameter : 4 meter
Material : Plat stainless steel SUS 304 2 mm
5. Ayakan
48
(a)
(b)
Gambar III. 35. Ayakan 8 mesh, panjang 13 M (a), Ayakan 23 mesh,
panjang 8 M (b)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Fungsi
: Untuk menyaring kristal gula
A.3. Sanitasi dan Higiene
PT. PG. Candi Baru menerapkan Sanitation Standard Operating
Procedure (SSOP) yang merupakan prosedur tertulis di mana proses pembuatan
pangan harus diproduksi dalam kondisi yang bersih. Metode pemantauan yang
umum digunakan yaitu metode cek list yang umumnya digunakan untuk
memonitor pra-operasi, pelaksanaan infeksi, tindakan koreksi dan verifikasi.
Sanitasi di PT. PG. Candi Baru meliputi sanitasi lingkungan kerja, sanitasi
peralatan dan sanitasi pekerja.
a. Sanitasi Lingkungan
Di PT. PG. Candi Baru yang dimaksud sanitasi lingkungan kerja yaitu
sanitasi yang meliputi kebersihan kantor, ruang produksi, laboratorium, taman,
musholla dan toilet. Hal yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan
yaitu melakukan pembersihan pada lantai, dinding, langit-langit, jendela,
ventilasi udara. Ruang perkantoran dilakukan pembersihan sebanyak 3 kali
dalam sehari. Taman dan halaman pabrik dilakukan pembersihan sebanyak 2
49
kali dalam sehari, sedangkan pada ruang produksi lantai dibersihkan setiap
hari, dalam sehari dilakukan sebanyak 2 kali dari pihak pekerja khusus dan per
shift dari pekerja dalam shift tersebut.
b. Sanitasi Peralatan
Pembersihan alat produksi di PT. PG. Candi Baru menggunakan
metode wet cleaning. Wet cleaning (pembersihan basah), yaitu pembersihan
secara keseluruhan kotoran pada alat dengan menggunakan air atau larutan
tertentu untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada alat. Wet cleaning
dibedakan menjadi dua yaitu : pertama, Cleaning In Place (CIP) Merupakan
pembersihan secara keseluruhan kotoran tanpa pembongkaran alat dan mesin.
Kedua, Cleaning Out Place (COP) Adalah pembersihan secara keseluruhan
kotoran pada alat dengan pembongkaran alat dan mesin.
c. Sanitasi Pekerja
Pencemaran yang ditimbulkan oleh karyawan dapat berupa debu atau
kotoran yang dapat menempel pada karyawan, baik pada pakaian, rambut,
kulit dan kemungkinan cemaran lain yang dapat ditimbulkan oleh karyawan.
Usaha yang dilakukan agar produk tidak tercemar maka setiap karyawan
menggunakan pakain khusus. Di PT. PG. Candi Baru para pekerjanya tidak
menggunakan seragam dan perlindungan terhadap cemaran. Pabrik hanya
menyediakan seragam untuk pekerja yang melakukan pengemasan, akan tetapi
seragam tersebut jarang sekali dipakai. Hal ini disebabkan karena suhu di
50
dalam ruang pengolahan sangat panas, jadi jika para pekerja diwajibkan
menggunakan seragam dikhawatirkan dapat mengganggu kenyamanan
pekerja. Kebersihan dan kesehatan karyawan serta pekerja mempengaruhi
kualitas mutu produk, sehingga kesehatan dan kebersihan pekerja sangat perlu
diperhatikan.
d. Penanganan Limbah
Limbah yang terdapat pada PT. PG. Candi Baru dibagi menjadi 4 yaitu
limbah B3, limbah gas, limbah cair dan limbah padat. Setiap limbah yang
dihasilkan, memiliki cara penanganan yang berbeda-beda, sehingga terdapat
penanganan limbah B3, padat, cair dan gas.
a) Penanganan limbah B3
Sesuai
dengan
Keputusan
Bupati
Sidoarjo
Nomor
188/580/404.1.3.2/2013. Di mana PT. PG. Candi Baru hanya diizinkan
untuk melakukan penyimpanan sementara limbah B3 selama 180 hari.
Untuk pengelolaan lebih lanjut, PT. PG. Candi Baru bekerjasama dengan
pihak ketiga, yaitu PT. Prasada Pamunah Limbah Industri (PPLI) Bogor
dengan MOU No.023/PPLI-OA/11-2014 yang berlaku selama 3 bulan dan
setelahnya dilakukan perpanjangan kembali.
b) Penanganan limbah padat
1. Blotong
Pemanfaatan blotong di PT. PG. Candi Baru dijual pada pihak ketiga
sesuai dengan perjanjian kontrak.
2. Abu kering
51
Abu kering ini merupakan sisa pembakaran dapur ketel tekanan
rendah dan menengah. Limbah ini dapat memicu kebakaran maupun
panas. Oleh karena itu, abu yang dihasilkan harus disingkirkan dari
dapur ketel, lalu abu ditampung untuk kemudian disemprot dengan
air agar sisa api padam dan dialirkan ke bak pengendapan.
3. Abu basah
Abu basah merupakan limbah padat sisa pembakaran dapur ketel
tekanan menengah yang telah ditangkap oleh Wet Dust Collector
(WDC). Fraksi kasar ditangkap oleh saringan talang getar dan fraksi
halus diendapkan di pengendapan kontinyu.
4. Ampas
Ampas merupakan limbah hasil pemerahan nira pada stasiun
gilingan. Sebagian ampas ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar
ketel, sedangkan sisanya disimpan sebagai persediaan bahan bakar.
Jika terdapat kelebihan, ampas dijual ke pihak lain, misalnya industri
yang menggunakan ampas yang menggunakan bahan bakar.
c) Penanganan limbah gas
Untuk menanggulangi pencemaran udara dan menjaga program
langit biru, PT. PG. Candi Baru telah memasang Dust Collector (DC)
sistem basah karena sistem ini dianggap paling efektif untuk menangkap
debu. Pada cerobong asap juga dilengkapi sampling point untuk
menganalisa gas yang keluar dari cerobong. Disamping hal-hal tersebut
PT. PG. Candi Baru masih terus berusaha untuk mengadakan beberapa
52
penelitian dengan tujuan agar pembakaran dapur ketel sesempurna
mungkin untuk menekan sisa pembakaran sekecil-kecilnya.
d) Penanganan limbah cair
Limbah cair PT. PG. Candi Baru diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu :
1) Limbah cair non polutan
Limbah cair yang tidak menimbulkan polusi ini berasal dari
air kondensat kondensor, air pendingin tobong belerang, air
pendingin pompa vacuum, air pendingin sublimator, air jatuhan dan
air injeksi. Limbah ini dapat langsung dialirkan ke sungai karena
tidak berbahaya, namun sebelumnya limbah harus ditampung dalam
bak penampungan agar suhunya turun dan tidak mempengaruhi suhu
air sungai
2) Limbah cair polutan
Merupakan limbah cair yang menimbulkan polusi bagi
lingkungan. Limbah cair ini dihasilkan dari stasiun gilingan, berupa
air pendingin dan air pembersih stasiun gilingan yang telah tercampur
dengan oli. Stasiun pemurnian, penguapan, masakan dan putaran,
berupa air bekas pembersihan pipa-pipa pemanas, air bekas cucian
evaporator, ceceran stroop, nira dan minyak putaran dan masakan
serta air buangan laboratorium. Penanganan limbah cair di PT. PG.
Candi Baru terdiri dari 3 bagian, yaitu:
53
a. Inhouse Keeping
Inhouse Keeping merupakan tindakan preventif yang bertujuan
untuk mengurangi debit dan konsentrasi limbah yang dihasilkan.
Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan efektifitas
produksi dan mengurangi beban sistem pengolahan limbah. Halhal yang dilakukan dalam tahap inhouse keeping, antara lain:
1. Membuat tanggul disekitar pompa dan peti nira untuk
menampung bocoran / tumpahan nira.
2. Membuat
tempat
penampungan
larutan
soda
bekas
pembersihan evaporator dan pan masakan, kemudian diatur
pengeluarannya secara kontinyu dengan maksud untuk
meningkatkan pH air buangan.
3. Air pendingin mesin-mesin yang menampung minyak
sebaiknya, sebelum dibuang dipisahkan antara air dan
minyaknya.
4. Nira sisa analisa laboratorium ditampung, kemudian
dikembalikan pada peti nira di stasiun pemurnian, sedangkan
kertas saring bekas yang berisi endapan dikumpulkan dan
dimasukkan ke dapur ketel untuk dibakar.
5. Air buangan dilakukan pengolahan secara anaerob dengan
pelarutan zat-zat organik, dimana zat-zat organik yang tidak
larut dalam limbah akan diolah oleh enzim hidrolisiase atau
asam menjadi zat-zat yang larut dalam limbah.
54
b. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Penanganan limbah cair di PT. PG. Candi Baru dilakukan dengan
sistem Aerasi Bio-Oksidasi dengan penambahan Ca(OH)2 dan
mikroba (aerobic mikroba). Kapasitas pengolahan limbah adalah
864 m3/hari.
A.4. Tugas Khusus
Tugas khusus mahasiswa yang diberikan oleh dosen pembimbing PKL
yaitu Mengetahui bagaimana penerapan Good Agriculture Practice (GAP), Good
Manufacturing Practice (GMP) dan Good Handling Product (GHP) pada produk
Gula Kristal Putih (GKP) dari penanaman bahan baku sampai produk siap kemas
di PT. PG. Candi Baru Sidoarjo.
a. Good Agriculture Practice (GAP)
Good Agriculture Practices (GAP) atau cara budidaya yang baik
merupakan standar pekerjaan dalam setiap usaha pertanian agar produksi
yang dihasilkan memenuhi standar internasional. Kontrol kualitas dapat
dilakukan dengan mengecek proses produksi. Sasaran yang akan dicapai
dalam GAP adalah terwujudnya keamanan pangan, jaminan mutu, usaha
agribisnis hortikultura berkelanjutan dan peningkatan daya saing (Prasetyo,
2015). Penerapan GAP di PT. PG. Candi Baru dapat dilihat pada beberapa
aspek, yaitu :
1. Penyediaan bibit
Bibit tebu yang akan ditanam merupakan hasil budidaya secara
Bud Chips. Bud Chips merupakan metode penggandaan bibit dengan
cara mengisolasi mata tunas, pemberian desinfektan, perlakuan Heat
55
Water Treatment (HWT) dan zat pengatur tumbuh. Bibit ditumbuhkan
dalam media tanah yang steril, sehingga diharapkan mampu
menghasilkan produktivitas tinggi.
Gambar III. 36. Pembibitan dengan metode Bud Chips
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
2. Persiapan lahan
Persiapan lahan untuk budidaya tebu dimulai dengan pembuatan
got dan pembuatan juringan. Ukuran got standar, yaitu got keliling
dengan lebar 60 cm dan kedalaman 70 cm, sedangkan got malang
dengan lebar 50 cm dan kedalaman 60 cm. Ukuran standar juringan,
yaitu lebar 50 cm dan kedalaman 30 cm untuk tanah basah, 25 cm untuk
tanah kering. Pada lahan tebu juga dibuat jalan tikus sebagai jalan untuk
mengontrol tebu (Suwarto, dkk., 2014).
Gambar III. 37. Persiapan Lahan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
56
3. Penanaman
Bibit dipindahkan ke lahan setelah bibit berumur 3 bulan. Bibit
diletakkan pada juringan yang telah dibuat saat persiapan lahan.
Gambar III. 38. Bibit Tebu Siap Tanam
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
4. Pemupukan
Pemupukan menggunakan pupuk urea selama 2 minggu pertama,
dengan perbandingan pupuk dan air 1:1 dan pupuk tonsca untuk
minggu-minggu selanjutnya. Pemupukan dilakukan setiap dua minggu
sekali.
5. Panen
Tebu dapat dipanen setelah berumur 5-6 bulan. Tebu yang akan dipanen
melalui proses penebangan dan pengelentekkan (pemisahan daun
dengan batang tebu). Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi cemaran
fisik pada saat pengolahan.
Gambar III. 39. Proses Pemanenan
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
b. Good Manufacturing Practice (GMP)
57
Good Manufacturing Practices (GMP) atau Cara Produksi Makanan
yang Baik (CPMB) merupakan suatu pedoman cara memproduksi makanan
dengan tujuan agar produsen memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah
ditentukan untuk menghasilkan produk makanan tertentu sesuai dengan
tuntutan konsumen (Zainuri, 2013). Penerapan GMP di PT. PG. Candi Baru
dapat dilihat pada aspek-aspek berikut:
1. Lingkungan sarana pengolahan
Di lingkungan sarana pengolahan PT. PG. Candi Baru bebas dari
tumbuhnya tanaman liar dan kebersihan lingkungan terawat dengan
baik. Lokasi PT. PG. Candi Baru jauh dari Industri yang telah
mengalami polusi.
2. Bangunan dan fasilitas pabrik
Bangunan, peralatan dan fasilitas PG. Candi Baru telah dirancang agar
dapat menjamin bahwa selama proses pengolahan bahan pangan tidak
tercemar baik oleh cemaran biologis, kimia dan kotoran lainnya.
3. Peralatan pengolahan
Peralatan pengolahan di PT. PG. Candi Baru dilakukan pembersihan
setiap hari dengan sistem Cleaning In Place (CIP).
4. Fasilitas dan kegiatan sanitasi
Ruang dan peralatan pengolahan di PT. PG. Candi Baru kurang terjaga
kebersihannya, sehingga kurang menjamin produk bebas dari cemaran.
Suplai air berasal dari air sungai yang telah mengalami pemurnian
terlebih dahulu dan air PDAM. PT. PG. Candi Baru telah dilengkapi
sistem pembuangan air dan limbah yang baik.
5. Sistem pengendalian hama
Bangunan pabrik Candi Baru telah terhindar dari hama berupa binatang
pengerat, hal ini disebabkan karena udara sekitar tempat pengolahan
sangat panas, sehingga binatang pengerat tidak dapat bertahan hidup.
58
6. Higiene karyawan
Fasilitas higiene karyawan, seperti toilet di PT. PG. Candi Baru telah
banyak tersedia dan memadai. Setiap 6 bulan sekali di PT. PG. Candi
Baru diadakan pemeriksaan untuk semua karyawan, sehingga tidak ada
karyawan sakit yang bekerja. Karyawan PT. PG. Candi Baru kurang
memerhatikan higienitas diri sendiri, sehingga hampir semua karyawan
yang melakukan proses produksi tidak menggunakan masker, baju kerja
dan penutup kepala.
7. Pengendalian proses
Setiap bahan baku yang akan diolah telah melalui pos pemeriksaan
Quality Control (QC), sehingga bahan baku yang akan diolah
merupakan bahan baku terbaik. Namun, PT. PG. Candi Baru kurang
memperhatikan QC untuk produk jadi. PT. PG. Candi Baru telah
menetapkan kemasan dan pelabelan. Disetiap kemasan gula yang
diproduksi
telah
dicantumkan
informasi
yang
diperlukan
oleh
konsumen.
8. Manajemen dan pengawasan
PT. PG. Candi Baru telah melakukan pengendalian produksi yang efektif
dan menerapkan manajemen pengendalian mutu sejak tahun 2014 yaitu
ISO 9001 : 2008 dan SNI 3140.3 : 2010
9. Pencatatan dan dokumentasi
PT. PG. Candi Baru telah melakukan pencatatan setiap tahapan
produksi, setiap satu jam sekali dilakukan pengontrolan dan pencatatan
oleh mandor keliling, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dapat
ditelusuri sebabnya.
c. Good Handling Product (GHP)
Produk pangan jika tidak ditangani
dengan benar akan mudah
mengalami kerusakan. Untuk meminimalkan kerusakan-kerusakan tersebut,
59
maka perlu dilakukan penanganan produk jadi yang sesuai dengan pedoman
yang memenuhi syarat SNI. Prosedur GHP yang diterapkan di PT. PG. Candi
Baru adalah :
1. Pengemasan yang baik
Pengemasan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan produk, akan
menyebabkan produk mudah rusak dan mengurangi umur simpan
produk tersebut. Untuk mengurangi terjadinya penyerapan air berlebih
pada gula, maka untuk kemasan karung terlebih dahulu dilapisi plastik.
Tampak belakang
Tampak depan
Gambar III. 40. Kemasan Gula 1 Kg
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
2. Jumlah tumpukan
Tumpukan setiap
kemasan
produk
harus
diperhatikan,
untuk
menghindari kerusakan kemasan, seperti : penyok, bocor dan lain-lain.
Kemasan 1 kg yang dibungkus dengan kardus memiliki jumlah
tumpukan maksimal 5 kardus. Cara penumpukan kemasan karung dan
kardus mengikuti cara penyusunan batu bata dalam pembuatan
bangunan.
60
Gambar III. 41. Penyusunan Karung Gula (50 Kg)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
Gambar III. 42. Penyusunan Kardus Gula (1 Kg)
(Sumber : Dokumentasi Pribadi)
B. Fokus dan Pelaksanaan Kegiatan
Praktek kerja lapangan ini dilakukan dengan metode observasi,
wawancara, pustaka dan mengamati langsung proses produksi Gula Kristal
Putih (GKP) di PT. PG. Candi Baru. Mulai dari pembibitan tebu, pengecekan
bahan baku, persiapan bahan baku (Raw Material) sampai pada pengemasan
produk. Hal-hal yang difokuskan mahasiswa dalam Praktek Kerja Lapangan,
antara lain:
1) Pemahaman mahasiswa terhadap pekerjaan terutama pada proses produksi
GKP melalui beberapa tahap pengolahan yaitu penerimaan bahan baku,
penggilingan tebu, pemurnian, penguapan, pemasakan dan penambahan
bibit gula, putaran, penyelesaian, pengemasan dan penyimpanan.
61
2) Sikap mahasiswa dalam mencapai tujuan PKL diperlukan beberapa sikap
dari mahasiswa yaitu, aktif dalam mencari data dan informasi, disiplin,
teliti dan kesungguhan dalam melakukan PKL.
C. Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi oleh mahasiswa selama PKL yaitu, waktu PKL
yang singkat sehingga pengumpulan data dan informasi tidak bisa didapatkan
secara rinci sehingga pelaporan hasil PKL kurang maksimal. Kurangnya
pemahaman mahasiswa tentang teori teknologi gula, sehingga membutuhkan
waktu lama untuk memahami setiap proses dan istilah-istilah yang digunakan
dalam proses produksi gula. Pekerja yang ada di bagian pabrikasi cukup sibuk
sehingga mahasiswa PKL harus benar-benar jeli untuk bisa membagi waktu
dan melihat waktu luang pekerja maupun pembimbing saat dilapangan.
D. Cara Mengatasi Kendala
Mahasiswa PKL berusaha melakukan diskusi kelompok untuk
membagi tugas dalam hal pengumpulan data sehingga informasi bisa
didapatkan. Selain itu mahasiswa melakukan diskusi dengan karyawan yang
berada di panel produksi untuk mendapatkan data dan informasi. Belajar
mandiri melalui internet dan bertanya secara langsung kepada para pekerja
pabrikasi.
62
BAB IV
KESIMPULAN
A. Kesimpulan
1. PT. PG. Candi Baru merupakan pabrik pangan yang mengolah tebu
menjadi gula kristal putih 1A sebagai produk utama dan produk samping
berupa tetes, blotong serta ampas tebu.
2. Pengolahan gula di PT. PG. Candi Baru menggunakan proses sulfitasi
alkalis kontinyu, dengan kriteria besar butir, warna (ICUMSA), kadar abu,
kadar air, nilai remisi dan kadar SO2 yang sesuai dengan SNI 3140.3:2010.
3. Penanganan limbah di PT. PG. Candi Baru telah dilakukan dengan baik.
Limbah B3 dan limbah padat diolah oleh pihak ketiga, sedangkan limbah
cair diolah sendiri oleh pihak pabrik.
4. Penerapan sanitasi di PT. PG. Candi Baru telah dilakukan dengan baik,
terutama sanitasi lingkungan dan peralatan. Untuk sanitasi pekerja belum
dilaksanakan dengan baik, karena suhu di ruan pengolahan sangat panas.
5. PT. PG. Candi Baru telah menerapkan Good Agriculture Practice (GAP),
Good Handling Product (GHP) dengan baik dan penerapan Good
Manufacturing Practice (GMP) belum memenuhi syarat pada aspek
higiene karyawan.
B. Saran-Saran
Perlunya peningkatan kedisiplinan untuk menggunakan alat pelindung
diri (APD) saat bekerja guna meminimalkan resiko kecelakaan kerja. Perlunya
peningkatan sistem Quality Control (QC) pada produk jadi. Perlunya
pengurangan antrian tebu pada stasiun emplacement.
DAFTAR PUSTAKA
Nugraheni, M., 2010. SNI Gula Pasir. http://staff.uny.ac.id [Diakses tanggal 5
Desember 2015].
63
Pandreou, D.R., Alviany, R. dan Pranoto, K.N., 2014. Laporan Kerja Praktek Di
PT. PG. Candi Baru. Universitas Surabaya. Surabaya.
Prasetyo, A., 2015. Good Agricultural. https://www.scribd.com/doc [Diakses
tanggal 1 September 2015].
Prawaningrum, H., 2011. Proses Produksi Gula SHS Di PT. Kebon Agung PG.
Trangkil. IPB. Bogor.
Saragih, R. T. P., 2009. Penentuan Kadar Fosfat pada Air Umpan Recovery
Boiler dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis Di PT. Toba Pulp Lestari,
Tbk-PORSEA.
Sembiring, S.R., 2009. Transesterifikasi Heterogen Minyak Sawit Mentah dan
Metanol Menggunakan Katalis Padat Kalsium Oksida. Universitas
Sumatera Utara. Medan.
Sihombing, E. S. Y., 2013. Analisa Kandungan Rhodamin B dan Formalin pada
Gula Merah serta Pengetahuan dan Sikap Pedagang Di Pasar Tradisional
Kecamatan Medan Baru. Universitas Sumatera Utara. Medan.
Suwarto, Octavianty, Y. dan Hermawati, S., 2014. Top 15 Tanaman Perkebunan.
Penebar Swadaya. Jakarta.
Zainuri, 2013. Good Manufacturing Practice, Materi Kuliah Pengendalian Mutu.
Universitas Mataram. Mataram.
64
Lampiran 1. Surat Permohonan PKL
65
Lampiran 2. Surat Penerimaan PKL dari PT. PG. Candi Baru
Lampiran 3. Surat Tugas PKL
66
67
Lampiran 4. Jurnal Harian PKL
68
69
Lampiran 5. Format Penilaian PKL
70
Lampiran 6. Surat Keterangan selasai PKL
71
Lampiran 7. Struktur Organisasi PT. PG. Candi Baru
72
73
Lampiran 8. Flow Sheet PT. PG. Candi Baru
74
Lampiran 9. Sertifikat ISO 9001 : 2008
75
Lampiran 10. Sertifikat SNI 3140. 3 : 2010
76
Lampiran 11. Lokasi PT. PG. Candi Baru
Anda mungkin juga menyukai
- Sartono - Pengantar Metode Pengawasan Pabrik GulaDokumen179 halamanSartono - Pengantar Metode Pengawasan Pabrik GulaKharis Munandar Tanjung100% (2)
- Analisa Performa Pre-Evaporator Pabrik GulaDokumen28 halamanAnalisa Performa Pre-Evaporator Pabrik Gulayoh_rico100% (1)
- Neraca PanasDokumen298 halamanNeraca PanasTiansel100% (1)
- Lampiran C5 Expansion Valve (EV-01)Dokumen3 halamanLampiran C5 Expansion Valve (EV-01)Viona WidyaBelum ada peringkat
- LAPORAN PKL Petrokimia Departemen Produksi IIBDokumen110 halamanLAPORAN PKL Petrokimia Departemen Produksi IIBNadia Ulfa100% (2)
- Tips memulai dan Mengembangkan Wirausaha ITDari EverandTips memulai dan Mengembangkan Wirausaha ITPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (74)
- Laporan PKL PG MadukismoDokumen9 halamanLaporan PKL PG MadukismoRustam AdjiBelum ada peringkat
- Efisiensi EvaporatorDokumen4 halamanEfisiensi EvaporatordwiriskityaniBelum ada peringkat
- Laporan Tugas KhususDokumen21 halamanLaporan Tugas KhususTommy Indra KBelum ada peringkat
- Preliminary Design of Carboxymethyl Cellulose Production by Russel and Sucrose Fermentation Process With Annual 25000 Tons Capacity (Exlude Appendix)Dokumen94 halamanPreliminary Design of Carboxymethyl Cellulose Production by Russel and Sucrose Fermentation Process With Annual 25000 Tons Capacity (Exlude Appendix)prasBelum ada peringkat
- PG Candi FixDokumen71 halamanPG Candi Fixfauzi0% (1)
- Neraca Energi Pada Juice HeaterDokumen5 halamanNeraca Energi Pada Juice HeaterPra TiwiBelum ada peringkat
- Laporan PKL Pabrik Gula Kanigoro MadiunDokumen47 halamanLaporan PKL Pabrik Gula Kanigoro MadiunSeptian Nugraha100% (4)
- Flash TankDokumen7 halamanFlash TankRantau SilalahiBelum ada peringkat
- Perhitungan Neraca Massa & PanasDokumen7 halamanPerhitungan Neraca Massa & PanasNaufal DimasyqiBelum ada peringkat
- Bab IV Dan Appendiks B (Neraca Panas)Dokumen107 halamanBab IV Dan Appendiks B (Neraca Panas)Dita Pramitha Sari0% (1)
- Stasiun Puteran Dan IanDokumen12 halamanStasiun Puteran Dan IanMitsoe Donie100% (4)
- Neraca Massa Dan Panas Asam SulfatDokumen24 halamanNeraca Massa Dan Panas Asam Sulfatdininovilasari0% (2)
- Laporan PKL Pabrik II B Departemen PPEDokumen143 halamanLaporan PKL Pabrik II B Departemen PPEUlfia Al Rahma100% (2)
- Lampiran Neraca Massa PDFDokumen144 halamanLampiran Neraca Massa PDFharrison_s100% (1)
- Spesifikasi Alat FurnaceDokumen4 halamanSpesifikasi Alat FurnaceMaya ElvisaBelum ada peringkat
- Laporan PT GMM BoilerDokumen60 halamanLaporan PT GMM BoilerarifBelum ada peringkat
- Pabrik Gula Candi SidoarjoDokumen6 halamanPabrik Gula Candi SidoarjoDhiyaul IhsantiBelum ada peringkat
- Laporan Tugas Khusus KPDokumen39 halamanLaporan Tugas Khusus KPeniBelum ada peringkat
- Power Point Kerja Praktek PG - Candi BaruDokumen20 halamanPower Point Kerja Praktek PG - Candi BaruZain SaputraBelum ada peringkat
- Bahan Bakar UtilitasDokumen36 halamanBahan Bakar UtilitasPratama BerdinantoBelum ada peringkat
- lAMPIRAN PERHITUNGAN NERACA MASSADokumen21 halamanlAMPIRAN PERHITUNGAN NERACA MASSASania Carolina18Belum ada peringkat
- Laporan PKL 3 PG - Tersana Baru 2017 Mareta Safitriyana TKM 14.01.009Dokumen166 halamanLaporan PKL 3 PG - Tersana Baru 2017 Mareta Safitriyana TKM 14.01.009mareta safitriyanaBelum ada peringkat
- BAB I - Pendahuluan - Prarancangan Pabrik Pati Singkong Termodifikasi (Tepung Mocaf) Kapasitas Produksi 150.000 Ton Per TahunDokumen18 halamanBAB I - Pendahuluan - Prarancangan Pabrik Pati Singkong Termodifikasi (Tepung Mocaf) Kapasitas Produksi 150.000 Ton Per TahunnayBelum ada peringkat
- Biodiesel Generasi Ke 3Dokumen9 halamanBiodiesel Generasi Ke 3Viesta ListuyEriBelum ada peringkat
- BAB III Stasiun PemurnianDokumen24 halamanBAB III Stasiun PemurnianIlham MuhammadBelum ada peringkat
- Pra Rencana Pabrik Etanol Dari Ubi Kayu Dengan Proses Fermentasi Kapasitas 20000 TontahunDokumen360 halamanPra Rencana Pabrik Etanol Dari Ubi Kayu Dengan Proses Fermentasi Kapasitas 20000 TontahunCristiano Hamdiansyah Sempadian100% (13)
- Laporan KP (Devi Amalia)Dokumen43 halamanLaporan KP (Devi Amalia)devi amaliaBelum ada peringkat
- Lampiran Neraca MassaDokumen21 halamanLampiran Neraca MassaAnggraeniLarasatiSuradi100% (1)
- CLARIANTDokumen22 halamanCLARIANTPipit Aditia ListiyaniBelum ada peringkat
- Perhitungan Neraca Massa Di Cement MillDokumen3 halamanPerhitungan Neraca Massa Di Cement MillWahyuddin Shabir Wa DzakirBelum ada peringkat
- Pabrik Pembuatan EtilbenzenaDokumen75 halamanPabrik Pembuatan EtilbenzenaExel Dua CincinBelum ada peringkat
- ITS Sirup GlukosaDokumen14 halamanITS Sirup GlukosasafrizalibrahimBelum ada peringkat
- Furnace Tipe BoxDokumen9 halamanFurnace Tipe BoxNima LufiaBelum ada peringkat
- Apa Itu Chemical Engineering ToolsDokumen6 halamanApa Itu Chemical Engineering Toolsyos pakarnusaBelum ada peringkat
- Laporan PKL - Ppu Technical SupportDokumen119 halamanLaporan PKL - Ppu Technical SupportpaulusBelum ada peringkat
- Teknologi EvaporatorDokumen21 halamanTeknologi EvaporatorAlifa PritianBelum ada peringkat
- Reaktor Fixed Bed XDokumen38 halamanReaktor Fixed Bed XRetno Elakadesci50% (2)
- Pra Perancangan Pabrik Propylene Glycol Dengan Bahan Baku Gliserol PDFDokumen64 halamanPra Perancangan Pabrik Propylene Glycol Dengan Bahan Baku Gliserol PDFrizal yahdyBelum ada peringkat
- Lampiran C Spesifikasi Perancangan Alat Heat ExchangerDokumen8 halamanLampiran C Spesifikasi Perancangan Alat Heat Exchangeraulia haniefBelum ada peringkat
- Perhitungan Neraca PanasDokumen86 halamanPerhitungan Neraca Panasshekure50% (2)
- Beda Evaporasi PengeringanDokumen5 halamanBeda Evaporasi PengeringanAyhiess AryaniBelum ada peringkat
- Contoh Laporan Pabrik GulaDokumen47 halamanContoh Laporan Pabrik GulaAvebFrederiksen80% (10)
- BAB III Neraca MassaDokumen4 halamanBAB III Neraca MassaDeni Eka SobirinBelum ada peringkat
- Reaktor Gelembung PDFDokumen81 halamanReaktor Gelembung PDFtaufik akfa100% (1)
- Proses Operasi PG. Kebon Agung MalangDokumen13 halamanProses Operasi PG. Kebon Agung MalangKinzhuy MotageBelum ada peringkat
- Packed Bed Catalytic ReaktorDokumen22 halamanPacked Bed Catalytic ReaktorDita Aulia AzizahBelum ada peringkat
- Lampiran B Neraca Panas NewDokumen24 halamanLampiran B Neraca Panas NewMuhammad AswanBelum ada peringkat
- Isi LaporanDokumen85 halamanIsi LaporancessareBelum ada peringkat
- Laporan MagangDokumen10 halamanLaporan Magangdeigo samuelBelum ada peringkat
- KLP 3 - BINTER A - Hasil Studi Lapang PTPN PG TakalarDokumen23 halamanKLP 3 - BINTER A - Hasil Studi Lapang PTPN PG Takalaralmunawwara armanBelum ada peringkat
- IsiDokumen29 halamanIsiYoga Pranata SuharyaBelum ada peringkat
- Laporan Praktek Kerja LapanganDokumen35 halamanLaporan Praktek Kerja LapanganC'nunk Apriyani RaBelum ada peringkat
- MATRIK Evaluasi Renja DISPORA 2023Dokumen5 halamanMATRIK Evaluasi Renja DISPORA 2023Siti HawaBelum ada peringkat
- Cascading - Pokin DisporaDokumen13 halamanCascading - Pokin DisporaSiti HawaBelum ada peringkat
- Muslim, S.SosDokumen11 halamanMuslim, S.SosSiti HawaBelum ada peringkat
- Laporan OjtDokumen13 halamanLaporan OjtSiti HawaBelum ada peringkat
- Laporan PKLDokumen77 halamanLaporan PKLSiti Hawa100% (2)
- Laporan Thermo Acara IIIDokumen16 halamanLaporan Thermo Acara IIISiti Hawa0% (2)
- Laporan Tetap FermentasiDokumen90 halamanLaporan Tetap FermentasiSiti HawaBelum ada peringkat
- Laporan Kimia Pangan IIDokumen6 halamanLaporan Kimia Pangan IISiti HawaBelum ada peringkat