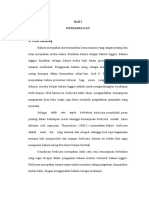Makalah Erin Moderasi
Diunggah oleh
RifaldiHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Makalah Erin Moderasi
Diunggah oleh
RifaldiHak Cipta:
Format Tersedia
Moderasi, Integrasi, dan Kearifan Lokal dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam.
A. Diskursus Pendidikan Agama Islam
Diskursus berasal dari bahasa latin discursus, yang secara harfiah berarti “berlari
bolak – balik” adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam
ilmu filsafat, diskursus merupakan suatu konsep sistem berfikir, pemikiran dan gambaran
yang kemudian membangun konsep suatu kultur dan budaya. Diskursus dibangun oleh
asumsi – asumsi yang umum yang kemudian menjadi cirri khas dalam pembicaraan baik
oleh suatu kelompok tertentu maupun oleh suatu periode sejarah tertentu. Salah satuh
contohnya ialah, dengan mempelajari arsip dan dokumen sejarah pada abad pertengahan,
bisa disimpulkan bahwa pada masa itu orang gila tidak dianggap berbahaya namun
dianggap memiliki kebijaksanaan batiniah, sedangkan pada abad ke – 20 orang gila
diperlakukan sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan untuk pulih.
Dalam hal ini, penulis membahas tentang diskursus yg ada di dalam pendidikan
agama Islam. Abu Hamid Al-Ghazali (w. 1111 M) membagi ilmu menjadi empat sistem
klasifikasi yang berbeda: pertama, pembagian ilmu menjadi teoretis dan praktis.
Pembagian ini didasarkan atas pembedaan antara intelek teoretis dan intelek praktis, yang
umumnya diterapkan pada ilmu-ilmu agama, bukan filosofis. Kedua, pembagian
pengetahuan menjadi pengetahuan huduri dan pengetahuan husuli, yang didasarkan atas
perbedaan tentang cara-cara mengetahui. Pengetahuan huduri lebih unggul ketimbang
husuli, karena terbebas dari kesalahan dan keraguan, yang memberikan kepastian
tertinggi mengenai kebenaran-kebenaran spiritual. Ketiga, pembagian atas ilmu-ilmu
agama (syari‘ah) dan intelektual (‘aqli,yah, gayr al-syari‘ah), yang didasarkan atas
pembedaan sumber wahyu dan sumber akal. Keempat, pembagian ilmu--ilmu menjadi
fardlu ain dan fardlu kifayah, yang didasarkan atas perbedaan antara dua macam
kewajiban yang berhubungan dengan pencarian pengetahuan.
Hadis “Mencari ilmu itu wajib bagi setiap Muslim” telah melahirkan berbagai
pembahasan, seperti: ilmu apa yang —dikategorikan— wajib dicari oleh seorang muslim.
Sebagian ulama memang hanya memasukkan cabang-cabang ilmu yang secara langsung
ber-hubungan dengan agama ke dalam “kategori” wajib, sementara tipe-tipe ilmu yang
lain, mereka menyerahkan kepada umat untuk menentukan ilmu mana yang paling
bermanfaat bagi mereka. “Kalian lebih tahu soal urusan kalian sendiri” demikian sabda
Rasul.
Al-Ghazali sendiri menemukan banyak jawaban yang berbeda terhadap
permasalahan tersebut. Para mutakallimun (ahli ilmu kalam) me-mandang bahwa belajar
teologi merupakan sebuah kewajiban, sementara para fuqaha (ahli-ahli fiqih) berpikir
bahwa fiqih Islamlah yang dicantumkan di dalam hadis Rasulullah itu. Al-Ghazali sendiri
lebih memandang bahwa ilmu yang wajib dicari menurut agama adalah yang terkait pada
pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam, karenanya harus di-ketahui dengan
pasti. Misalnya, seseorang yang kerjanya beternak binatang, haruslah mengetahui aturan
zakat. Atau bila seseorang menjadi pedagang yang melakukan usahanya di dalam sistem
riba, maka orang itu harus menyadari doktrin agama mengenainya, sehingga dapat
menjauhinya.
Selanjutnya soal ilmu yang termasuk wajib kifayah (sesuatu yang wajib atas
keseluruhan masyarakat selama kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sosial tersebut
masih ada, tapi setelah kewajiban itu dilaksanakan oleh sejumlah individu, maka oto-
matis yang lainnya terbebas dari kewajiban itu), Al-Ghazali mengklasifikasi-kan ilmu
kepada “ilmu agama” dan “ilmu nonagama”. Dengan “ilmu agama (‘ulum syar’i), beliau
maksudkan kelompok ilmu yang diajarkan lewat ajaran-ajaran Nabi dan wahyu.
Sedangkan yang lainnya dimasukkan dalam kelompok “ilmu nonagama”.
“Ilmu non-agama” masih diklasifikasikan kepada ilmu yang terpuji (mahmud),
dibolehkan (mubah) dan tercela (madzmum). Menurut al-Ghazali, ilmu sejarah termasuk
kategori ilmu mubah; sihir termasuk kategori “ilmu” tercela. Ilmu-ilmu terpuji, yang
penting di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk wajib kifayah; lebih dari itu, hanya
memberi manfaat tambahan kepada mereka yang mempelajarinya. Ilmu tentang obat,
matematika, dan kerajinan-kerajin-an yang diperlukan oleh masyarakat dimasukkan
dalam kategori wajib kifayah. Penyelidikan yang lebih terinci dan mendalam terhadap
masalah--masalah ilmu kedokteran atau matematika diletakkan pada kategori kedua;
yaitu bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya tanpa ada keharusan untuk
melakukannya.
Al-Ghazali juga mengklasifikasikan “ilmu agama” dalam dua kelompok: terpuji
(mahmud) dan tercela (madzmum). Yang dimaksud dengan “ilmu agama tercela” adalah
ilmu yang tampaknya diarahkan kepada syariah, tapi nyatanya menyimpang dari ajaran-
ajarannya. Sedangkan “ilmu agama terpuji” dibagi dalam empat kelompok:
1. Ushul (dasar-dasar; yaitu: Al-Quran, Al-Sunnah, ijma’ atau consensus dan tradisi
[kebiasaan] para sahabat Nabi).
2. Furu‘(masalah-masalah sekunder atau cabang; yaitu: masalah-masalah fiqih, etika,
dan pengalaman mistik.
3. Studi-studi pengantar (qaidah, sharaf, bahasa Arab, dan lain--lain).
4. Studi-studi pelengkap (membaca dan menerjemahkan Al--Quran, mempelajari
prinsip-prinsip fiqih, ‘ilm al—rijal atau penyelidikan biografi para perawi hadis-
hadis, dan lain--lain).
Al-Ghazali memandang ilmu yang tercakup di dalam empat kelompok di atas
sebagai wajib kifayah. Sampai di sini kita bisa membuat kesimpulan sementara bahwa
ilmu itu merupakan tangkapan manusia sebagai subjek atas realitas sebagai objek terkait
pokok permasalahan tertentu. Perbedaan pokok permasalahan membuat ilmu menjelma
menjadi beberapa bidang, sebagaimana klasifikasi di atas.
Sebenarnya berkaitan peserta didik sebagai subjek dan realitas sebagai objek juga
melahirkan klasifikasi yang lain lagi. Sebagai subjek tahu, peserta didik itu memiliki
potensi indera, perasaan, pikiran, intuisi, dan spiritual, sementara realitas itu juga terdiri
dari objek indrawi, objek pikir, objek rasa, objek iman. Tentang beberapa hal ini
tampaknya juga diisyarakat oleh al-Quran dan al-Hadits, seperti (a) perintah untuk
memperhatikan unta, langit, dll (misalnya QS al-Ghasiyah: 17-20) yang terkait dengan
objek inderawi; (b) perintah untuk berkata yang lembut, atau larangan untuk saling
berolok-olok, yang terkait dengan objek rasa; (c) perintah untuk memikirkan hakikat
manusia, hakikat ciptaan Allah, ini pertanda ada objek pikir; (d) terkait hakikat Tuhan,
malaikat, dan hal-hal yang ghaib, berarti objek iman.
Dari perbedaan inilah kemudian kita mengenal pembagian ilmu menjadi beberapa
“spisies”, yaitu pengalaman (pre-ilmiah), sains (ilmu pengetahuan), filsafat, dan ilmu
agama. Dengan demikian “ilmu” merupakan istilah generik yang tercakup di dalamnya
segala jenis ilmu. Beberapa spisies ilmu ini bisa dibedakan pada beberapa aspeknya, yaitu
objeknya, metodenya, validitasnya, termasuk subjeknya. Terkait dengan hubungan diatas,
diskursus dalam pendidikan Islam dapat ditinjau melalui 3 dimensi analisa yaitu
moderasi, integrasi dan kearifan lokal.
B. Moderasi dalam Diskursus Pendidikan Islam
Kata moderasi dalam bahsa Arab diartiakan al-wasathiyah. Seacara bahasa al-
wasathiyah berasal dari kata wasath. Al-Asfahaniy mendefenisikan wasath dengan
sawa‟un yaitu tengahtengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengahtengan
atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. Wasathan juga bermakna menjaga dari
bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.27 Sedangkan
makna yang sama juga terdapat dalam Mu‟jam al-Wasit yaitu adulan dan khiyaran
sederhana dan terpilih Ibnu.
Asyur mendefinisikan kata wasath dengan dua makna. Pertama, definisi menurut
etimologi, kata wasath berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki
dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi, makna
wasath adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan
pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa moderasi/ wasathiyah adalah sebuah
kondisi terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan menuju dua sikap; sikap
berlebihlebihan (ifrath) dan sikap muqashshir yang mengurang-ngurangi sesuatu yang
dibatasi Allah swt. Sifat wasathiyah umat Islam adalah anugerah yang diberikan Allah
swt secara khusus. Saat mereka konsisten menjalankan ajaran-ajaran Allah swt, maka
saat itulah mereka menjadi umat terbaik dan terpilih. Sifat ini telah menjadikan umat
Islam sebagai umat moderat; moderat dalam segala urusan, baik urusan agama atau
urusan sosial di dunia.
Moderasi dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat wilayah pembahasan,
yaitu: 1. Moderat dalam persoalan „aqidah; 2. Moderat dalam persoalan ibadah; 3.
Moderat dalam persoalan perangai dan budi pekerti; 4. Moderat dalam persoalan tasyri‟
(pembentukan syariat).
Wasathiyah (moderasi) ajaran Islam tercermin, antara lain dalam hal-hal berikut:
1. Aqidah
Aqidah Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada di tengah antara mereka
yang tunduk pada khurafat dan mempercayai segala sesuatu walau tanpa dasar, dan
mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Selain mengajak
beriman kepada yang ghaib, Islam mengajak akal manusia untuk membuktikan
ajakannya secara rasional.
Demikian prinsip yang selalu diajarkannya. Dalam keimanan Islam tidak sampai
mempertuhankan para pembawa risalah dari Tuhan, karena mereka adalah manusia
biasa yang diberi wahyu, dan tidak menyepelekannya, bahkan sampai membunuhnya,
seperti yang dilakukan umat Yahudi.
2. Ibadah
Islam mewajibkan penganutnya untuk melakukan ibadah dalam bentuk dan
jumlah yang sangat terbatas, misalnya shalat limat kali dalam sehari, puasa sebulan
dalam setahun, haji sekali dalam seumur hidup, agar selalu ada komunikasi antara
manusia dengan Tuhannya. Selebihnya Allah mempersilahkan manusia untuk
berkarya dan bekerja mencari rezeki Allah di muka bumi.
Moderasi dalam peribadatan sangat jelas dalam firman Allah:
9. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk melaksanakan shalat
pada hari Jum‟at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-
beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 10. Apabila shalat
telah dikumandangkan, maka bertebaranlah di bumi; carilah karunia Allah, dan
ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (QS. al-Jumu‟ah/62: 9-10).37
Allah SWT menerangkan apabila muadzin mengumandangkan adzan pada hari
jum‟at, maka hendaklah kita meinggalkan perniagaan dan segala usaha dunia serta
bersegera ke masjid mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat jum‟at, dengan
cara yang wajar, tidak berlari-lari, tetapi berjalan dengan tenang sampai ke masjid.
Pada ayat selanjutnya, Allah menerangkan bahwa setelah selesai melaksanakan shalat
jum‟at, umat Islam boleh berteburan di muka bumi untuk melaksanakan urusan
duniawi, dan berusaha mencari rezeki yang halal, sesudah menunaikan yang
bermanfaat untuk akhirat. Hendaklah mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam
mengerjakan usahanya dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan,
dan lainnya.
3. Akhlak
Dalam pandangan al-Qur‟an manusia terdiri dari dua unsur, yaitu ruh dan jasad.
Dalam proses penciptaan manusia awal (Adam) dijelaskan bahwa Allah telah
menciptakannya dari tanah kemudian meniupkan ke dalam tubuhnya ruh. Kedua
unsur itu mempunyai hak yang harus dipenuhi. Karena itu, Rasulullah saw mengecam
keras sahabatnya yang dianggapnya berlebihan dalam beribadah dengan mengabaikan
hak tubuhnya, keluarga, dan masyarakat
4. Pembentukan Syariat
Apa yang dapat ditangkap sebagai keseimbangan tasry‟ dalam Islam adalah
penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada asas manfaat-madharat, suci-
najis, serta bersihkotor. Dengan kata lain, satu-satunya tolak ukur yang digunakan
Islam dalam penentuan halal dan haram adalah maslahah umat atau dalam bahasa
kaidah fiqhiyyahnya: jalbu al-mashalih wa dar‟u al-mafasid (upaya mendatangkan
kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Kenyataan ini tidak sama, misalnya, dengan
syariat agama Yahudi yang cenderung berlebihan dalam pengharaman sesuatu.
Bahkan, sebagai azab Tuhan dari sikap berlebihan ini, sebagimana diisyaratkan al-
Qur‟an, Allah mengharamkan pula atas mereka hal-hal yang semestinya halal.
Lembaga pendidikan Islam secara ideologis dapat menginstalkan konsep baik dan
konsep nilai yang ada dalam paham Islam moderat ke dalam tujuan pendidikannya,
sehingga menghasilkan pendidikan Islam moderat. Menurut Abudin Nata, pendidikan
moderasi Islam atau disebutnya sebagai pendidikan Islam rahmah li al-alamin, memiliki
sepuluh nilai dasar yang menjadi indikatornya, yaitu: (1) pendidikan damai, yang
menghormati hak asasi manusia dan persahabatan antara bangsa, ras, atau kelompok
agama; (2) pendidikan yang mengembangkan kewirausahaan dan kemitraan dengan
dunia industri; (3) pendidikan yang memperhatikan isi profetik Islam, yaitu humanisasi,
liberasi dan transendensi untuk perubahan sosial; (4) pendidikan yang memuat ajaran
toleransi beragama dan pluralisme; (5) pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang
menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat; (6) pendidikan yang
menyeimbangkan antara wawasan intelektual (head), wawasan spiritual dan akhlak mulai
(heart) dan keterampilan okasional (hand); (7) pendidikan yang menghasilkan ulama
yang intelek dan intelek yang ulama; (8) pendidikan yang menjadi solusi bagi problem-
problem pendidikan saat ini seperti masalah dualisme dan metodologi pembelajaran; (9)
pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif; dan (10)
pendidikan yang mampu meningkatkan penguasaan atas bahasa asing.
C. Integrasi dalam Diskursus Pendidikan Islam
Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi satu
kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari kata bahasa Inggris “integration” yang berarti
kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi demaknai sebagai proses penyesuaian di antara
unsure – unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan pola yang memiliki
keserasian fungsi.
Selama ini ada pandangan atau persepsi yang salah (misperception) tapi
berkembang di masyarakat tentang apa yang mereka sebut dengan agama, pendidikan
agama, pelajaran agama, dan belajar agama. Agama menurut pandangan mereka tidak
lebih dari kegiatan ritual, seperti zikir, berdo’a, shalat, puasa, zakat, haji, mengurus
jenazah, pernikahan, dan sejenisnya. 1 Pekerjaan-pekerjaan ritual di atas, kalau di tingkat
pemerintahan desa, berkaitan dengan tugas-tugas modin atau kesra (kesejahteraan
rakyat), bukan tugas lurah, apalagi kepala daerah atau kepala negara. Jadi, agama itu
tingkatannya adalah modin, bukan kepala pemerintahan, dalam pandangan mereka.
Pandangan di atas ternyata membawa dampak pada pandangan mereka yang salah
juga tentang pendidikan agama dan pelajaran agama. Madrasah, pondok pesantren,
perguruan tinggi Islam, mereka sebut sebagai lembaga pendidikan agama (Islam). 2
Dengan demikian, lain daripada itu mereka sebut lembaga pendidikan umum, seperti SD,
SMP, SMU/ SMK, AKBID, AKPER, AKPOL, Universitas, dsb. Demikian pula
pandangan di atas berdampak dikotomi ilmu. Pelajaran fikih, tauhid, akhlak, tasawwuf,
tarikh dan bahasa Arab mereka sebut sebagai pelajaran agama (Islam). 3 Maka, pelajaran
IPA, IPS, Kewarganegaraan, dst biasa mereka namakan sebagai pelajaran umum. Itulah
pandangan yang salah kaprah, salah tapi terus hidup di masyarakat.
Tatkala seseorang ingin belajar agama, maka mereka dating ke lembaga
pendidikan agama seperti madrasah, perguruan tinggi Islam, atau pesantren. Begitu pula
ketika mereka hendak belajar agama, maka mereka belajar fikih, tauhid, akhlak,
tasawwuf, tarikh dan bahasa Arab itu. 4 Karena, itulah yang mereka sebut dengan agama
(Islam). Hal ini juga terlihat pada pembagian fakultas pada perguruan tinggi agama, yang
hanya meliputi fakultas tarbiyah, ushuluddin, syari’ah, dan dakwah. Fakultas ekonomi,
sosial-politik, sains, dsb tidak mereka sebut sebagai fakultas agama tapi mereka sebut
fakultas umum.
Pada hakekatnya Islam bukan hanya sekedar agama. Islam tidak hanya urusan
ritual. Selain menyangkut kegiatan ritual, Islam juga berbicara tentang ilmu pengetahuan,
kualitas kehidupan manusia, keadilan, dan juga berbicara tentang beramal shaleh atau
bekerja secara profesional. 5 Rasulullah SAW diutus ke dunia bukan hanya ngurusi ritual
tapi li utammima makarima al-akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Dengan kata lain,
Islam tidak saja menyangkut agama tetapi juga peradaban. Namun sayangnya, ketika
berbicara tentang Islam, imajinasi orang (masyarakat) hanya tertuju kepada persoalan
ritual.
Mestinya, semua aspek terkait dengan Islam harus dilihat secara utuh. 6
Seseorang berhasil menjalankan ritual secara khusyuk oleh karena yang bersangkutan
telah mengenal dirinya sendiri, orang lain, alam, dan Tuhannya. Untuk mengenal semua
itu, seseorang harus belajar sains secara mendalam sebagaimana yang diperintahkan oleh
Allah SWT melalui al-Qur’an dan hadits Nabi. Kalau pemahaman seperti itu yang
dikembangkan, maka semua mata kuliah yang diberikan di kampus-kampus perguruan
tinggi Islam seharusnya dimaknai sebagai bagian untuk meningkatkan keberislaman
untuk menuju ridha Allah.
Di balik fenomena di atas ada pandangan atau paradigm dikotomis. Di dalam
paradigma ini, aspek kehidupan dipandang dengan dua sisi yang berlawanan. 7 Seperti:
laki-laki dan perempuan, pendidikan keagamaan dan non-keagamaan atau pendidikan
umum, dst. Paradigma dikotomis tersebut pada gilirannya berkembang dalam
memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani; sehingga
pendidikan agama Islam hanya diletakkan pada aspek kehidupan akhirat atau kehidupan
rohani saja.
Menurut Muhaimin, ada 3 (tiga) peta paradigma pengembangan pendidikan
Islam, yaitu paradigma dikotomis, paradigm mekanis, dan paradigma organis atau
sistemik. 8 Paradigma dikotomis adalah seperti disebut di atas. Implikasinya adalah
adanya penyempitan makna, seperti pengertian ulama menjadi fuqaha, sehingga mereka
tidak dimasukkan ke dalam barisan kaum intelektual. Implikasi lainnya, pengembangan
pendidikan agama Islam lebih berorientasi pada keakheratan, sedangkan masalah dunia
dianggap tidak penting, serta menekankan pada pendalaman al-‘ulum al-diniyah (ilmu-
ilmu keagamaan) yang merupakan jalan pintas untuk menuju kebahagiaan akhirat,
sementara sains (ilmu pengetahuan umum) terpisah dari agama. Demikian pula
pendekatan yang digunakan lebih bersifat keagamaan yang normatif, doktriner, dan
absolutis.
Sedangkan paradigma mekanis memiliki pandangan bahwa kehidupan terdiri dari
berbagai aspek. Seperti mesin, semua aspek bekerja dan bergerak sesuai fungsinya.
Paradigma mekanis memandang pendidikan sebagai penanaman dan pengembangan
seperangkat nilai kehidupan, yang bergerak dan berjalan menurut fungsinya masing-
masing. 9 Dalam hal ini agama adalah adalah salah satu aspek atau nilai dan sains adalah
aspek yang lain. Antara aspek satu dengan lainya bisa saling berkonsultasi atau tidak.
Adapun paradigma organis atau sistemik berpandangan bahwa hidup adalah
susunn yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan. Dalam
konteks pendidikan Islam, paradigm organisme memandang bahwa aktivitas
kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang hidup
bersama dan bekerjasama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup
yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama.
Paradigma organis atau sistemik saat ini diusahakan melalui pendidikan tinggi,
melalui kajian-kajian ilmiah, menggantikan paradigm lama yang dikotomis sehingga
dapat memberi solusi bagi masalah penyempitan makna Islam menjadi hanya agama.
Diskursus tentang kaitan agama dan sains dapat dilihat dari paradigma-paradigma
di atas. Paradigma dikotomis sudah mulai ditinggalkan oleh, terutama, para akademisi
kalangan perguruan tinggi Islam. Sedangkan kedua paradigma lainnya, mekanis dan
organis, tampaknya harus diuji dalam ujikan sejarah perjalanan pendidikan tinggi di
negeri ini. Itulah isu aktual yang kita hadapi dan perlu kita cermati.
D. Kearifan Lokal dalam Diskursus Pendidikan Islam.
Kearifan lokal menurut UU No. 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolahan
lingkungan hidup Bab: I Pasal I Butir 30 adalah: nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelolah lingkungan hidup secara
lestari. Menurut Ridwan kearifan lokal sering disebut local wisdom dapat dipahami
sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan
bersikap terhadap sesuatu objek, peristiwa, yang terjadi dalam ruangan tertentu. Di mana
wisdom dipahami sebagai kemampuan seorang dalam menggunakan akal pikirannya
dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu objek, atau
peristiwa yang terjadi. Menurut Direktur Afri-Afya, Caroline Nyamai-Kisia pengertian
kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai, pandangan-pandangan
setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam
dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.24 Selanjutnya, menurut Ridwan berpendapat
bahwa: Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha
manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap
terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.
Pengertian tersebut yang disusun secara etimologi, wisdom dipahami sebagai
kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau
bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang tejadi.
Istilah wisdom sering diartikan sebagai “kearifan/kebijaksanaan”. Lokal secara spesifik
menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Sebagai
ruang interaksi yang sudah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya melibatkan suatu
pola hubungan antara manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungan
fisiknya. Pola interaksi yang sudah terdeasain tersebut disebut setting. Setting adalah
sebuah ruang interaksi tempat seseorang dapat menyusun hubungan-hubungan face to
face dalam lingkungannya. Sebuah setting kehidupan yang sudah terbentuk secara
langsung akan memproduksi nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut yang akan menjadi
landasan hubungan mereka atau menjadi acuan tingkah laku mereka.
Pendidikan agama di Indonesia hanya menekankan aspek pengajaran. Tentu
dalam hal ini, pengajaran ritual keagamaan yang kering pemaknaannya secara spritual.
Model pengajarannya lebih pada transfer ilmu-ilmu agama, bukan penanaman nilai-nilai
suci keagamaan yang mampu dijadikan fondasi dalam kehidupan di masyarakat.
Kurangnya pengayaan terhadap pentingnya berakhlak mulia bagi peserta didik,
menambah daftar panjang problem pendidikan agama dewasa ini. Selalu ditemukan pada
lembaga pendidikan adalah “pengajar agama” bukan “guru agama”. apa yang telah
disampaikan oleh “pengajar agama’ hanya bisa dipikirkan dan dipahami. Sedangkan,
“guru agama” harus dihayati, didenga dan dan diamalkan.
Pendidikan agama seharusnya mampu mentransformasikan nilai-nilai agama dan
nilainilai kearifan lokal ke dalam diri peserta didik. Sehingga apa yang diterimanya dari
belajar agama tersebut dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik harus
mampu menjadi penggerak dan sumber inspirasi bagi peserta didik dan masyarakat.
Meski sebagian besar masyarakat modern menganggap implementasi budaya tersebut
merupakan suatu hal yang ketinggalan zaman, namun bagi masyarakat yang melestarikan
budaya tersebut menganggapnya sebagai salah satu aturan yang paling efektif dalam
mencegah peserta didik untuk berbuat penyimpangan dan membentuk karakter kejujuran.
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Pendidikan Tematik Kel. 6 (RPP Pembelajaran Tematik)Dokumen18 halamanMakalah Pendidikan Tematik Kel. 6 (RPP Pembelajaran Tematik)Puspa hati BanyaBelum ada peringkat
- MAKALAH DimasDokumen12 halamanMAKALAH Dimasdale kusumaBelum ada peringkat
- Resensi Ilmu Kalam Pak Nurkilimmmm Buku Pemikiran Kalam Karya HM Laily MansyurDokumen30 halamanResensi Ilmu Kalam Pak Nurkilimmmm Buku Pemikiran Kalam Karya HM Laily MansyurTirta Wahyudi100% (1)
- Makalah Hadits Tarbawi - SUBYEK PENDIDIKAN - UnsikaDokumen11 halamanMakalah Hadits Tarbawi - SUBYEK PENDIDIKAN - UnsikaCecep Abdullah100% (1)
- Perbandingan Agama Kel 2-2Dokumen18 halamanPerbandingan Agama Kel 2-2Sia BulanBelum ada peringkat
- Sejarah TepDokumen20 halamanSejarah TepdekaonscribdBelum ada peringkat
- Bab 1 Reading Text in IslamDokumen8 halamanBab 1 Reading Text in IslamNor RestinaBelum ada peringkat
- Makalah Hakekat Ilmu Dalam Al-QuranDokumen13 halamanMakalah Hakekat Ilmu Dalam Al-QuranAgitsni Alfa TasyaBelum ada peringkat
- Makalah Pengertian TasawufDokumen15 halamanMakalah Pengertian TasawuffitriidaniBelum ada peringkat
- Teknik Dalam Pembelajaran BerbicaraDokumen14 halamanTeknik Dalam Pembelajaran BerbicaraAgus Zaqi FirmansyahBelum ada peringkat
- Makalah Maharah KitabahDokumen13 halamanMakalah Maharah KitabahHenik Al HusnawatiBelum ada peringkat
- Pengembangan Pendekatan Dan Metode PembelajaranDokumen16 halamanPengembangan Pendekatan Dan Metode PembelajaranDiah SarithiBelum ada peringkat
- Makalah Konsep Tafsir Dan Hadis Tarbawi Dan Urgensinya Bagi Pendidikan IslamDokumen12 halamanMakalah Konsep Tafsir Dan Hadis Tarbawi Dan Urgensinya Bagi Pendidikan IslamAnjas Pramono100% (1)
- MAKALAH Strategi PembelajaranDokumen14 halamanMAKALAH Strategi PembelajaranAnnazwa Ratnika Al-FadlBelum ada peringkat
- Pembaharuan Pendidikan Islam Di IndiaDokumen27 halamanPembaharuan Pendidikan Islam Di IndiaNrannisa01 FajrianiBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 2 Materi Bagan Dan Peta KonsepDokumen18 halamanMakalah Kelompok 2 Materi Bagan Dan Peta KonsepSafitri FitriBelum ada peringkat
- Deskripsi Lingkungan PAKEMIDokumen6 halamanDeskripsi Lingkungan PAKEMIFarichatul ilmiahBelum ada peringkat
- Strategi Pembelajaran PAIDokumen20 halamanStrategi Pembelajaran PAI0105 Resa Sofia FikriBelum ada peringkat
- Lima Pilar Syariat Islam Di AcehDokumen7 halamanLima Pilar Syariat Islam Di AcehHTN-18MUHAJIR100% (1)
- Makalah Pembelajaran Bahasa Arab MIDokumen14 halamanMakalah Pembelajaran Bahasa Arab MINisa Nurul AwaliyahBelum ada peringkat
- Makalah Administrasi Pendidikan Tentang Ruang Lingkup Administrasi PendidikanDokumen11 halamanMakalah Administrasi Pendidikan Tentang Ruang Lingkup Administrasi PendidikanARahman ShiddiqBelum ada peringkat
- Makalah Psikologi PendidikanDokumen11 halamanMakalah Psikologi PendidikanULvhe ManiZheBelum ada peringkat
- Makalah Kel 3 Hakikat IpaDokumen13 halamanMakalah Kel 3 Hakikat IpaMai DilaBelum ada peringkat
- Makalah Pengembangan Sumber BelajarDokumen18 halamanMakalah Pengembangan Sumber BelajarFahrhulBelum ada peringkat
- Kelompok 2 Kewajiban Belajar MengajarDokumen13 halamanKelompok 2 Kewajiban Belajar MengajarFaradiba NurkamilaBelum ada peringkat
- Resume Buku Asas Kurikulum Ah NasutionDokumen16 halamanResume Buku Asas Kurikulum Ah NasutionWahyu PratamaBelum ada peringkat
- Media PembelajaranDokumen9 halamanMedia PembelajaranDjihanBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 9 Kepribadian Guru Pai 5fDokumen19 halamanMakalah Kelompok 9 Kepribadian Guru Pai 5fAnisa DwiBelum ada peringkat
- Makalah Lingkungan Pembelajaran EfektifDokumen15 halamanMakalah Lingkungan Pembelajaran EfektifArie IhzaBelum ada peringkat
- Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Serta Pengaruhnya Dalam Pendidikan Dan PerkembanganDokumen15 halamanPertumbuhan Dan Perkembangan Anak Serta Pengaruhnya Dalam Pendidikan Dan PerkembanganZukét PrintingBelum ada peringkat
- DALIL-DALIL KEHUJJAHAN HADIS Dan FUNGSI PDFDokumen13 halamanDALIL-DALIL KEHUJJAHAN HADIS Dan FUNGSI PDFBayu SandyBelum ada peringkat
- Makalah Tafsir Tarbawi - Mpib - Kelompok 1Dokumen9 halamanMakalah Tafsir Tarbawi - Mpib - Kelompok 10035 silvijelliantiBelum ada peringkat
- Makalah Akidah Akhlak Kel 1Dokumen10 halamanMakalah Akidah Akhlak Kel 1Miftahul Hidayat100% (1)
- Makalah Bahasa Arab MI Kelompok 3Dokumen10 halamanMakalah Bahasa Arab MI Kelompok 3ilham photocopyBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 4 Telaah Kurikulum PaiDokumen21 halamanMakalah Kelompok 4 Telaah Kurikulum PaiAnak PoerbaBelum ada peringkat
- UTS Perencanaan PendidikanDokumen5 halamanUTS Perencanaan PendidikanAsrul BinIsmailBelum ada peringkat
- Pendidikan MultikulturalDokumen7 halamanPendidikan MultikulturalMardiyatul MunaBelum ada peringkat
- Hadist Dan Tafsir Media Pembelajaran-1Dokumen17 halamanHadist Dan Tafsir Media Pembelajaran-1Indra pebriandiBelum ada peringkat
- Makalah Pengembangan Kurikulum Materi Ke - 9 Naufal VeinaDokumen23 halamanMakalah Pengembangan Kurikulum Materi Ke - 9 Naufal VeinaIffah MaulanaBelum ada peringkat
- Makalah Ilmu Dakwah Kel.1Dokumen12 halamanMakalah Ilmu Dakwah Kel.1Hafidz Ramadhanz100% (1)
- HAKIKAT Pendidikan IslamDokumen82 halamanHAKIKAT Pendidikan IslamRindang KurniawanBelum ada peringkat
- Makalah Beauty TreatmentDokumen17 halamanMakalah Beauty TreatmentYuni DwitriBelum ada peringkat
- Perencanaan Pembelajaran FiqhDokumen13 halamanPerencanaan Pembelajaran FiqhDeden MHBelum ada peringkat
- Fiqih PendidikanDokumen12 halamanFiqih PendidikanAjied SaifarBelum ada peringkat
- Kelompok 3 Akidah AkhlakDokumen8 halamanKelompok 3 Akidah Akhlakilan suwatiBelum ada peringkat
- Prinsip Pendidikan IslamDokumen8 halamanPrinsip Pendidikan IslamAnisBelum ada peringkat
- CP, TP, ATP AKHLAK FASE F Sem 1Dokumen5 halamanCP, TP, ATP AKHLAK FASE F Sem 1renyBelum ada peringkat
- Makalah Literasi Kel 1Dokumen16 halamanMakalah Literasi Kel 1Dinar KarimahBelum ada peringkat
- M A K A L A H Metode Pengembangan Kurikulum PembelajaranDokumen12 halamanM A K A L A H Metode Pengembangan Kurikulum PembelajaranMuhammad Rowi Bagus WicaksonoBelum ada peringkat
- Lang KahDokumen13 halamanLang KahZizah100% (1)
- Makalah MSI Kel 9Dokumen13 halamanMakalah MSI Kel 9Delia putriBelum ada peringkat
- Konsep Umum Tentang Psikologi Belajar Pai 5aDokumen25 halamanKonsep Umum Tentang Psikologi Belajar Pai 5aLulukBelum ada peringkat
- Pembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap MadrasahDokumen8 halamanPembaharuan Pendidikan Islam Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap MadrasahNazma Tazkiyatul KhumairaBelum ada peringkat
- Makalah Hadits Tarbawi Kelompok 04Dokumen18 halamanMakalah Hadits Tarbawi Kelompok 04Faizul AkbarBelum ada peringkat
- Makalah Kel 4 Telaah Kurikurum PaiDokumen27 halamanMakalah Kel 4 Telaah Kurikurum PaiAsril Azhar100% (1)
- Makalah Sejarah Kebudayaan Islam TipologiDokumen10 halamanMakalah Sejarah Kebudayaan Islam TipologiSerba GunaBelum ada peringkat
- Metode Pendidikan Dalam Perspektif Alquran Surat Al Maidah Ayat 67 Dan Al ARof Ayat 176-177Dokumen13 halamanMetode Pendidikan Dalam Perspektif Alquran Surat Al Maidah Ayat 67 Dan Al ARof Ayat 176-177Zukét PrintingBelum ada peringkat
- ANALISIS FILSAFAT TENTANG PENDIDIKAN ISLAM FixDokumen25 halamanANALISIS FILSAFAT TENTANG PENDIDIKAN ISLAM Fixkhofiyul arifBelum ada peringkat
- Aliran Utama Dalam Filsafat Pendidikan IslamDokumen12 halamanAliran Utama Dalam Filsafat Pendidikan IslamPascasarjana UndarBelum ada peringkat
- Hubungan Antara Sains Dan IslamDokumen8 halamanHubungan Antara Sains Dan IslamMyraBelum ada peringkat